Esok pagi.
Pagi kesekian setelah strobilus pertama tumbuh di belahan dunia sana yang entah di mana letaknya.
Sebuah kehidupan harus tetap berjalan tidak melihat apakah bersama atau sendirian.
Tidak kusangka kepergiannya benar-benar membawa dampak yang sebesar ini bagi kehidupanku.
Tak hanya perihal Zahwa, aku juga kehilangan pekerjaanku. Aku meminta izin cuti satu hari, ternyata bosku memberiku lebih banyak.
Ia bilang aku boleh beristirahat di rumah sampai nanti aku dipanggil kembali, itu artinya cutiku sampai waktu yang tidak ditentukan.
Pun aku ragu apakah aku akan dipanggil kembali.
Ceritanya sederhana saja, sehari setelah acara mengantar Zahwa. Esoknya aku kembali melakukan rutinitasku seperti biasa, membuka gerbang dan etalase toko.
Tak ada perasaan atau kecurigaan apa pun yang terbayang dalam benak ini.
Hingga sore harinya aku mencari ke mana kunci yang biasa kugantung di dekat sling bag hitam andalanku.
Yayuk bilang, seseorang telah mengambilnya. Ia juga menambahkan, ada orang lain yang akan menggantikan tugasku tiap pagi.
Terlalu positive thinking diriku ini, aku manggut-manggut saja. Terus terang aku sedang jenuh harus setiap hari berangkat lebih pagi dari siapa pun.
Aku menyambut kabar yang kukira bahagia itu dengan penuh penerimaan.
Barulah ketika selangkah lagi aku turun dari undakan toko bermaksud pulang ke rumah, Jupri memintaku bertemu bos pemilik toko dan bertemulah kami bertiga di ruangan dekat percetakan undangan.
Di sana aku dikritik habis-habisan oleh bosku dan tak ada satu pun pembelaan yang bisa aku berikan.
Sebab mau bagaimanapun alasan yang aku katakan pada mereka, jika lawan bicara memang tidak membutuhkan tentu tidak guna alasan itu.
Malah hanya jadi ajang pembenaran dan menandakan keegoisan seseorang yang tak mau disalahkan, merasa dirinya sudah benar. Jupri juga hanya diam saja.
Tak membelaku sama sekali.
Rupanya penerimaanku yang penuh tidak bersambut pada keberuntungan yang utuh.
Ibu sudah tahu tentang hal ini, ia tidak menyalahkanku atau bertanya macam-macam.
Ia hanya sudah tidak membangunkanku saat subuh buta. Dan tidak menanyakan, “Bagaimana tadi di toko?” di hari setelahnya.
Belum pernah sekali pun aku mendengar orang yang memiliki pemahaman penuh berkata bahwa bangkit dari kehilangan dan patah hati adalah hal yang mudah.
Dua hari pertama, aku tidak beranjak dari tempat tidur.
Sampai akhirnya Ibu mengetuk pelan pintu kamarku. “Nang, jangan murung terus begitu, keluarlah barang sebentar, bertemu orang-orang bisa jadi obat buatmu yang sedang kesepian.”
Hanya itu, dan aku tidak menengok atau menjawab apa pun. Aku pura-pura tidur, tapi Ibu tahu aku berpura-pura.
Lima menit setelahnya, entah impuls mana yang membuatku bangkit, mengambil handuk dan membersihkan diri.
Tengkuk leherku terasa segar seolah berteriak kegirangan setelah dua hari tidak bertemu air.
Aku berpamitan pada Ibu yang tengah memasak untuk mengirim bekal untuk orang-orang yang bekerja di ladang.
Aku bilang ingin berkunjung ke rumah seseorang, di kecamatan sebelah.
Ibu mengiyakan dan tak banyak bertanya. Sudah mau bangun saja Ibu bersyukur bukan main.
Di dalam bus, tak terlalu banyak orang, aku juga memilih sudut yang sepi. Dari sini aku bisa melihat semua penumpang bus yang duduk, naik atau turun.
Beberapa mengangguk kepada penumpang yang masih tinggal di dalam bus. Kami yang berada di dalam, balas mengangguk.
Sesederhana itu menghargai orang lain.
Sepertinya aku mulai menyukai sebuah perjalanan.
Perjalanan ini memberiku jeda untuk tidak melakukan apa-apa tapi tetap memiliki tujuan.
Kali ini perasaanku lebih baik dibanding dengan sebelumnya yang hanya berdiam diri dalam ruangan 3x4 meter yang berdinding semi kayu.
Entah apa rahasianya, tapi benar kata Ibu, bertemu orang dapat mengobati rasa sepi.
Di kursi seberang, duduklah seorang perempuan bertopi baret. Ia turun bersamaan dengan aku, meninggalkan tiga keping uang koin kepada pak sopir.
Kuperhatikan wajahnya Jawa, namun segala yang ia kenakan mirip sekali dengan artis-artis di film bernuansa oriental.
Rambutnya juga sudah tidak asli, agaknya dicat coklat, namun nampak enak saja untuk dipandang.
Di sini stereotype terhadap orang yang mengenakan pewarna rambut sedikit buruk, terlebih lagi perempuan. Ia pasti bukan berasal dari Nara atau desa dekat sini.
Sepuluh meter di belakangnya, aku melihat ia berbelok ke arah di mana seharusnya aku juga berbelok. Aku curiga jangan-jangan ia menuju ke tempat yang sama denganku.
Tak salah lagi, ketika aku sampai mengetuk gerbang hitam rumah milik Pak Bah, gadis itu juga di sana.
“Anak muda ini lagi,” sambutnya ramah. Lebih ramah dari biasanya. Wajahnya juga memancarkan seri yang berbeda.
Aku sungkem mendekap tangan Pak Bah. Sejenak aku melirik sekitar dan kutangkap sosok gadis bertopi baret tadi tengah mengeluarkan isi kopernya di ruangan dalam.
Aku tidak masuk, hanya duduk di depan meja reparasi yang biasa digunakan Pak Bah. Seperti yang kulakukan hari-hari lalu.
Setelah diamati, sepertinya aku pernah bertemu dengan gadis ini, kalau ingatanku tidak salah.
Ingin kutanya siapa gadis itu, tapi belum genap niatku untuk menjalankan. Pak Bah sudah menjelaskan terlebih dahulu.
“Kau satu bus dengan putriku?”
Telingaku berdiri. Dugaan awalku ia hanya sekadar pelanggan Pak Bah, tak kusangka ia adalah putrinya.
Gadis ini benar-benar sudah jauh sekali untuk dikatakan sebagai orang Jawa.
Bagi orang yang menilai sesuatu hanya dari kelihatannya, pasti tidak akan percaya ini.
Pak Bah adalah orang yang dihormati dan cukup dikenal karena eksistensinya dalam dunia dakwah dan seminar.
Meskipun ia bukan seseorang jebolan pondok pesanten atau sejenisnya, yang kudengar ia sering diminta berbicara tentang pengalamannya menelusuri tempat yang tidak banyak orang Nara bisa lakukan, ke negeri kincir angin misalnya.
“Atau kau kemari diantar seseorang?”
“Tidak, Pak Bah. Tadi naik bus.” Jawabku seadanya.
“Oh, kalau begitu kau pasti sudah melihat putriku. Ia jenuh dengan kehidupannya di kota yang selalu bertemu banyak orang, katanya sesak, riuh, ia tengah kemari mencari sesuatu yang lebih sepi.”
Aku mengangguk.
“Ada apa kau kemari, Nak?”


 littlemagic
littlemagic




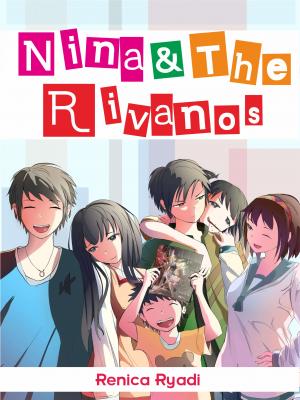







I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog