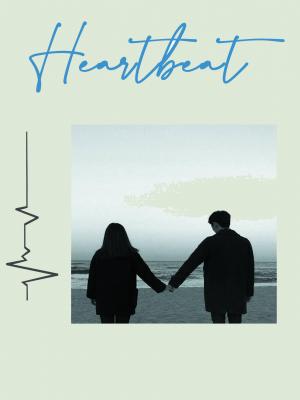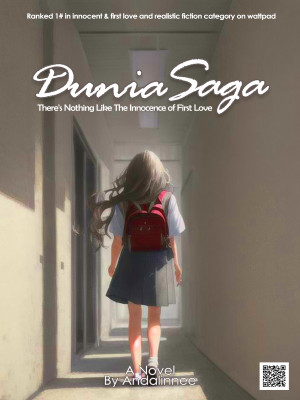Kalakian, dengan angkuh dan dada dibusungkan—karena merasa jadi pahlawan, kendati kesiangan—Edo membuka pintu rumah dengan kunci cadangan yang dibawanya.
“Kangmas Edo sengklekk!”
Mendengar jeritan nyaring itu, Varen tergelak lirih. Masih mengikuti langkah Edo untuk memasuki rumah sederhana yang tak seharum dan semengkilap biasanya.
“Kamu udah pacaran sama Varen?” Olena mendelik dramatis. “Hiliih, dasar. Gengsi bilang bosss!” maki wanita itu sebelum akhirnya beranjak pergi.
Gusar tetapi tak mungkin mengungkapkan, Lana hanya membuang napas kasar-kasar. Napasnya jadi memburu, kekesalannya mendarah daging. Barang kali pingsan sesaat akan jadi lebih baik daripada menerima tekanan banting segenting ini.
“Lanaa!”
“Hm?!”
Tanpa mengucapkan salam apa pun sebelumnya, Varen malah menyalangkan netra. Menempatkan diri di muka Lana dan memeriksa keadaan gadis tersebut.
“Lo sakit, ya? Kok bisa? Sakit apa? Panas? Demam? Flu? Ambeien? Diare? Peemes? Tumor? Kanker?” berondong Varen teramat khawatir.
Edo yang berdiri di tengah ruangan sampai menganga paripurna. Tercengang oleh kelakuan manusia tampan di sana—yang tengah melayangkan puluhan pertanyaan pada Lana.
“GGS! Ganteng, Ganteng Sinting! Kayak gue, ahaha,” gumamnya antusias.
Mengingat keberadaannya yang mungkin mengusik pasangan muda itu, Edo memutuskan berjalan pergi. Mungkin lebih baik ia akan menanyakan siapa Varen sebenarnya nanti.
“Kok lo nggak buka-buka block chat gue? Udah makan, ‘kan? Udah enakan? Udah tidur? Cukup, ‘kan tidurnya? Tidur delapan jam, ‘kan?”
Meski gadis itu membisu, Varen masih meneruskan celotehnya.
“Lo kebanyakan bersih-bersih, ya? Atau kebanyakan belajar? Jadi orang jangan terlalu rajin, tapi jangan terlalu males! Sesekali lo tidur, nggak akan buat dunia hancur Atau ... lo gini karna lo kangen sama gue? Ehem, bener, ‘kan! Maaf, jangan salahkan gue, tapi salahkan Sang Mahakuasa yang membuatku terlalu sempurna.”
Lana menghela napas lenyai. Irasnya kentara datar eksesif malasnya menghadapi satu spesies ini. Delapan menit berselang, tetapi sang lelaki masih meneruskan ocehannya tanpa henti. Kalaupun memberi jeda, mungkin hanya setengah sekon sebagai durasi.
Gila, tuh mulut atau kaset rusak?
“—Beb?”
Plakkkk
Nggak apa-apa bicara dan mengusiknya berulang kali, tetapi tak ada lagi toleransi bila nekat menyebutnya dengan sembarangan.
Tertegun, lelaki itu mematung selama lima belas detik. Tak bergerak ataupun berkutik. Parah! Kegarangan Lana meningkat tiga kali lipat kini. Juga, jangan lupakan tamparan tiada taranya yang pedas nan nyeri.
“Maaf ...,” lirih Varen. Membelai pipinya yang sukses memerah. Boleh jadi, tamparan tadi menyisakan bekas telempap Lana pada pipi mulusnya.
“Pulang atau gue usir,” ancam Lana penuh penekanan.
Mencebikkan bibir, Varen segera menciptakan raut menggemaskan tetapi memuakkan—bagi seorang Lana.
“Pulang ... atau gue usir,” ulangnya. Kali ini dengan lengan kanan yang menggenggam erat sebuah penggaris besi. Tebalnya enam senti.
Menyengir singkat, Varen menggaruk punggungnya kilat.
“Tapi gue masih mau di sini. Gimana, dong?” ujarnya bersama netra yang berkilauan, meminta belas kasihan.
“Selama lo di sini, lo mesti jadi kacung. Gue belum bersih-bersih soalnya,” jawab Lana serampangan. Lantaran kehabisan akal untuk menghadapi lelaki tersebut, apa pun yang menghampiri benaknya segera saja ia lontarkan.
Sungguh—sebenarnya apa, sih, yang menarik dari Lana?
“Oke!”
“HAH?!”
“Gue harus gimana? Lap semua medali, piala, dan piagam? Sikat kamar mandi? Bersihin kamar? Atau ngilangin debu di sofa?” berondong Varen dalam satu tarikan napas. “Apa aja gue rela asal gue boleh di sini.”
Lana mengerutkan glabelanya dalam-dalam. Dibuat bimbang oleh kesungguhan Varen yang hampir seperti suatu bualan.
“Terserah—lo bebas milih! Lo bikin gue gila!”
Wanodya itu membalikkan badannya. Bermaksud meninggalkan Varen yang lagi-lagi berhasil menghentikan langkahnya.
“Gue janji buat rumah lo mengkilap! Tapi sebagai gantinya, gue minta lo tetep di sini,” pintanya. Kali ini dengan nada netral yang meyakinkan.
“Apa?”
“Pokoknya lo di sini aja, ya?”
Selepas keheningan melingkupi keduanya cukup lama, akhirnya gadis itu bergumam lirih. Mengiyakan. Pun sebenarnya, tidak ada bedanya ketika Lana menyenta. Pasti sang lelaki memiliki seribu satu cara guna membuatnya mengatakan ‘iya’.
🌻
Dienka memicingkan netranya, berusaha memastikan jika sosok yang berdiri di pekarangan rumahnya itu merupakan Candra. Gemas untuk lekas memastikan, segera saja ia membuka pintu utama. Mengendap-endap sekejap untuk mengikis jarak dengan sosok yang masih memandangi ponselnya. Membiarkan guyuran air dari cakrawala menghujani raga.
“Candra?”
Sosok yang mengenakan kaos oblong itu menoleh. Memandangnya cukup lama. Sosoknya tak mengenakan jaket atau apa pun itu untuk melindungi selira, sedangkan cuaca jelas hujan deras disertai tagar.
“Candra!”
Buru-buru Dienka menyambar payungnya. Berhamburan menghampiri sosok yang sama. Lantas ia lekas memayungi sang lelaki yang tengah menggigil ringan dan mengirim ratusan pesan—teruntuknya.
“Elo ngapain, sih?!” hardik Dienka. Mengutuk kebodohan juga gilanya keputusan Candra untuk menemuinya—dalam hardikan yang tersirat.
Bukannya beranjak dan menggandeng Dienka agar segera menepi, justru lelaki itu tersenyum penuh misteri.
“Syukurlah. Ternyata lo beneran nggak pindah rumah,” seru Candra, berupaya mengalahkan bahana rinai hujan.
Tersenyum tipis, gadis itu bersilih mendengkus samar.
Akhirnya Dienka mengalami apa yang Lana rasakan selama ini: bila kini, ia tak lagi sanggup menyangkak hati apalagi menaruh benci pada si lelaki.
“Minum dulu.” Dienka mengulurkan secangkir teh hangat—yang dibuatnya secepat kilat—pada Candra yang tengah terselubung selimut.
“Nggak usah, Ka,” tolak Candra. Medorong pelan cangkir tadi kembali pada Dienka. “Gue nggak apa-apa.”
Berkeras hati, Dienka menggeleng tegas.
“Habisin itu ... atau gue bakal kacangin lo,” tekan Dienka.
Baik niatnya; Dienka hanya ingin Candra sungguh baik-baik saja.
Menghela napas, Candra gegas menyeruput isi dari cangkir antik pada cekalannya. Lumayan tergesa-gesa sampai melupakan suatu fakta bahwa itu ... panas.
“Ah!” ringis Candra. Menjulurkan lidah setelah memaksakan diri untuk meneguk teh yang sempat diisapnya. Belingsatan, tanpa sengaja lengannya menyampuk cangkir tadi; yang segera tumpah pada meja kayu atas teras kediaman Dienka.
“G-gue minta lo minum, tapi nggak maksa lo buat habisin dalam satu tegukan!” cicit Dienka panik.
Dara itu melangkah masuk ke rumahnya, menyambar kain serbet lalu kembali untuk mengeringkan lantai yang basah karena kecelakaan kecil barusan.
“Gu—”
“Sorry ... gue cuma khawatir sama lo,” sela Dienka selagi mengusap lantainya. Tak mengerti kalau-kalau pemuda itu ingin minta maaf atas tingkah sembrononya yang jelas merepotkan.
“Nggak. Gue yang minta maaf.”
Dienka tak meresponsnya. Masih menyeka teh manis yang tercurah ke meja juga lantai keramik jingganya.
“Udah gue aja!” Beringsut mendekati Dienka, Candra lekas bercangkung di sandingnya.
“Udah lo duduk aja. Ini kewajiban gue,” titah Dienka. Bertepatan dengan tersunggingnya satu senyuman simpul.
Menghela napas panjang, Candra kembali mendaratkan pantatnya pada kursi kayu hitam. Tak ingin memperpanjang perdebatan.
“Ada apa? To the point aja,” lirih Dienka dengan senyuman kaku.
“Gue emang maunya nggak ada basa-basi.” Candra menghela napas sekilat. “Lo tahu kenapa Lana nggak masuk?”
Kontan, alis Dienka bertaut temu. Serius? Dengan cuaca segenting ini, pun jarak kediamannya yang jelas jauh—Candra hanya menanyakan perihal Lana?!
Aaah ... Dienka lupa. Candra mana peduli dengan gadis lain? Lelaki itu hanya akan memprioritaskan Lana; tak peduli selama apa sangkala berantara.
“Gue yakin dia hubungin lo, jadi: dia sakit apa? Apa ada hubungannya sama penolakan kemarin lusa? Atau ... orang yang dia maksud?” tanya Candra beruntun. Seolah tak mau peduli pada Dienka yang masih membisu.
“Kemarin Lana sempat beritahu gue; kalau ada orang yang suka sama gue melebihi dia. Dan kayaknya, Lana sayang sama orang itu ....” Lelaki itu memberi jeda atas ucapannya. “Menurut lo ... orang itu siapa, Ka?”
Dienka masih menyengap. Mengendap.
Tanpa bisa mengontrol diri, dua netra tersebut sudah berkaca-kaca. Air yang bersumber dari kelenjar lakrimal itu pun sudah memenuhi bola mata—siap untuk menetes kapan saja. Mungkin, selamanya dia hanya dimanfaatkan sebagai pengantara oleh mereka.
“Can ... apa di otak lo isinya Lana semua?” cicit Dienka dengan suara parau.
Tanpa sempat mencegah, benteng penahannya lebih dulu pecah. Netranya sembap dalam sekejap. “Apa yang lo peduliin cuma Lana? Cuma selamanya Lana yang lo prioritaskan?” Telempapnya mengepal kencang. Sungguh tak sanggup lagi menghadapi lara yang menerjang. “Apa cuma Lana yang boleh nerima cinta lo?”
Dienka menjeda tangisan yang kemudian berubah menjadi sedu-sedan. Menjelma kembali jadi satu pekikan.
“Kurang besar apa cinta yang gue kasih ke lo?!” jerit Dienka, menaikkan nada bicaranya. Mengubah ekspresi Candra seketika. “Apa ... apa boleh gue berharap walau gue tau itu mustahil?”
Candra membisu. Setia menatap Dienka sedalam-dalamnya.
“Gue, Can! Gue! Gue yang suka sama lo!” tekan Dienka tersedan-sedan.
Kalakian, dengan masih berurai air mata, gadis itu melesat masuk dengan segera. Menyisakan Candra nan tetap pada posisi semula—digauli oleh rintik-rintik hujan.
Insan apatis itu tak terlalu terkejut akan pengakuan Dienka. Dia hanya gulana, serta kecewa. Lantaran kadang kala, ketampanan dan pesona yang ia miliki malah membuatnya membenci diri sendiri. Bukan tanpa alasan, tetapi telah banyak yang terluka karenanya. Entah secara langsung, ataupun sebaliknya.
Termasuk Dienka, juga Lana.


 aneylarevaa_
aneylarevaa_