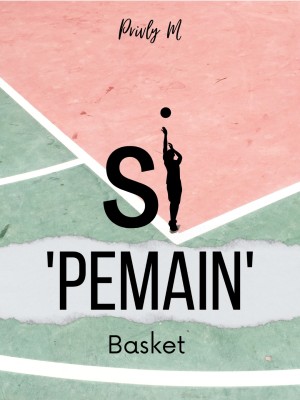Selasa, 15 Desember. 18.14 WITA
Separuh tubuhku, dari bahu hingga bagian bawah rok panjang yang kukenakan basah ketika aku tiba di rumah sakit, menenteng sekotak Donat Do’Nut yang tidak serapi saat aku membelinya, meski aku telah melindunginya sepenuh hati seperti orang bodoh.
“Kamu kemana aja?” adalah sapaan pertama dari Mama. Ia mengomel, seperti biasa, Hal yang hampir membuatku lega, seandainya tidak dapat kudengar nada khawatir alih-alih marah dalam suaranya.
Aku tidak menjawabnya, juga tidak menatapnya. Kedua mata Mama yang selalu menuai pujian dari orang-orang, mata yang diwariskannya pada saudari kembarku, sekarang begitu kuyu setelah berhari-hari kehilangan semangatnya. Aku... tidak sanggup menyaksikan. Yang kulakukan justru berjalan melewatinya, mendekati ruang ICU tempat Laura dirawat.
“Dia belum bangun,” kata Mama. Dan meski aku sudah menduganya, aku tidak bisa menghentikan diri dari rasa kecewa.
Laura, kapan... kamu akan bangun?
“Ganti baju dulu sana. Kamu basah,” kata Mama lagi. “Nanti sakit.”
Sesungguhnya, aku sangat ingin menjawab dengan “You should tell yourself that,” mengingat betapa kurus ia terlihat, betapa rapuhnya. Kapan terakhir kali dia makan? Apakah ia tidur dengan cukup?
Tetapi urung, aku menelan kembali kata-kataku dan justru menatapnya, dengan ragu bertanya. “Boleh ... aku masuk?”
***
Tanganku sedikit gemetar dan melemah tatkala aku memegangi pegangan pintu. Ada banyak ketidaksiapan yang menahanku di tempat. Ketidaksiapanku melihat Laura, satu-satunya yang kubagi tempat, bersesakan bersama di rahim ibu sekarang terbaring koma. Ketidaksiapanku menemukan Laura, satu-satunya yang tumbuh bersamaku dari awal hingga detik ini, belum pernah terpisahkan sekarang berada di gerbang yang sewaktu-waktu dapat memisahkan kami kapan saja.
Did I took her for granted?
Aku selalu beranggapan dia akan selalu ada. Di snaa. Mengganguku. Menjadi sosok saudari yang menyebalkan. Menjadi penghalang. Seseorang yang kubenci tapi selalu ada. Selamanya. Tidak pernah terpikir olehku bagaimana jika kebersamaan kami berhenti suatu hari. Bagaimana jika dia pergi secara mendadak? Seperti ... apa yang telah terjadi.
Laura itu kuat. Laura selalu kuat. Laura selalu cantik. Melihatnya ... lemah tak berdaya dengan perban di sana sini dan alat-alat medis yang melekat di tubuh membuatku ... tidak henti menyalahkan diri.
Hari ini, aku tidak bisa menghindarinya. Aku harus bertemu Laura, bicara dengannnya. Memintanya, kalau bisa, untuk berjuang, untuk kembali. Aku pun menarik napas panjang, menguatkan diriku. Dan begitu saja, kenangan mendatangiku satu persatu.
“Na! Nanaaaa! Ayo main!”
Kami masih kecil waktu itu, enam atau tujuh tahun. Dan di umur itu, tugas rumah pertamaku adalah menyapu halaman setiap hari Minggu. Karena halamannya cukup luas, tugas itu dibagi berdua, dua-duanya mendapat bagian sama rata. Harus, kalau tidak, Mama akan berteriak-teriak lagi karena anak kembarnya yang bertengkar soal ketidakadilan.
Pagi itu, kulihat Launa meninggalkan sapunya entah dimana dan berlari menghampiriku. Jemarinya menunjuk tempat bermain kami, satu tempat di sudut halaman yang mempunyai jungkat-jungkit dan sepasang ayunan buatan Papa. Aku, yang masih sibuk menyapu daun-daun kering, menggeleng. “Kan kita belum selesai. Nanti dimarahin Mama!”
“Bentar aja! Nggak bakal dimarahin!” jawab Laura enteng.
“Enggak, ah!”
“Mama lagi nggak ada, kok!”
Aku yang masih enam tahun, tentu saja tidak sanggup menahan godaan bermain. Setelah ragu sejenak dan Laura meyakinkanku sekali lagi, aku segera melempar sapu ke tanah, lantas berlari untuk bermain jungkat jungkit yang dicat biru muda dan pink bersama Laura. Kami bersenang-senang untuk waktu yang tidak terlalu lama, tertawa sampai lupa bahaya. Hingga, Mama segera datang dengan tampang mengerikan.
“Siapa yang nyuruh main?!” bentak Mama, sapu di tangannya. Aku dan Laura tergopoh-gopoh turun dari mainan, lalu berdua menunduk menatap sepatu. “Kenapa nggak nyapu?!”
Aku melirik Laura. Mempertimbangkan apakah sebaiknya aku memberitahu yang sebenarnya dan membiarkan Laura mendapat hukuman. Atau tidak. Atau aku bisa diam saja agar tidak jadi anak pengadu. Namun bahkan sebelum aku berhasil membuat keputusan, Laura telah bicara lebih dulu.
“Nana yang ajak, Ma! Kata Nana, kita main aja, nggak usah ngerjain tugas!”
Seketika leherku menoleh pada Laura, menatapnya tajam. Dia, sebaliknya, tidak melihat ke mataku. Ia melihat ke manapun selain padaku, dengan sengaja menghindari tatapanku yang penuh pertanyaan.
“Nana!” Tanpa bertanya, Mama membentakku. “Bagus, ya! Main aja kerjaannya! Pakai ajak-ajak lagi. Kamu harus mendapat hukuman.”
Tatapanku tidak berpindah dari Laura. Tanganku mengepal. Saat itu, aku amat membencinya. Sejak dulu, aku tahu aku membencinya.
Aku memutar pergelangan tanganku, mendorongnya, mengayunkan pintu terbuka.
“Ra, ini yang terakhir dan gue akan, nggak akan pernah mau-maunya dimanfaatin lo lagi!”
Aku bergumam lalu membuang napas lewat mulut. Kembali menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Saat ini, aku sedang menempatkan diri dalam bahaya. Karena jika ketahuan, habislah riwayatku. Bukan hanya nilaiku yang bisa jeblok, tetapi bagaimana kalau sampai dipanggil BK dan orangtuaku harus dihadirkan? Membayangkannya saja, aku tidak sanggup. Tetapi di sinilah aku, menantang bahaya. Dan semua, terima kasih pada Laura.
Kudorong pintu terbuka, lalu tersenyum pada Mr. Ryan, guru Bahasa Inggris kami waktu SMP yang super ramah. Sedikit rasa bersalah menyelinap di dadaku mengingat beliau adalah salah satu guru yang paling kukagumi, tetapi mengiyakan permintaan konyol Laura membuatku harus membohonginya.
Ya, permintaan konyol.
Mr. Ryan menyuruhku duduk dan aku menurut. Selama satu menit pertama, aku bahkan tidak sanggup menatapnya, hanya memandangi kedua tanganku yang berkeringan dan kebanyakan diremas, gugup setengah mati karena yang akan kulakukan saat ini adalah ... menjalani tes lisan. Jadi dalam dua hari, aku harus melewati dua tes Bahasa Inggris berbeda, yang salah satunya bukan tanggung jawabku. Salah satunya seharusnya menjadi tanggung jawab Laura, kalau bukan ia yang mengeluh sakit perut karena menstruasi dan memohon padaku untuk menggantikan. Bodohnya, aku bersedia setelah dibujuk sedemikian rupa.
Aku dan Laura beda kelas di SMP kelas dua. Dengan mempertimbangkan Mr. Ryan termasuk sebagai guru baru yang tidak akan dapat membedakan wajah kami, dan bahwa siapapun tidak akan dapat membedakannya jika aku mulai berpenampilan seperti Laura, aku pun menyanggupi. Pagi-pagi, aku telah mengikat rambutku seperti yang Laura biasa lakukan, memakai seragam serta jaket dan tasnya, lalu menunggu giliran tes dengan menggunakan namanya.
“Laura Andriana?” Mr. Ryan tersenyum lebar.
Kupaksa, agar senyumku tidak tampak seperti orang bersalah. “Yes, Sir.”
Selama detik-detik pertama, aku mulai menghitung kapan kedokku akan terbongkar, kapan Mr. Ryan akan menyadarinya? Tapi seiring senyum guru Bahasa Inggris berusia awal tiga puluhan ini yang melebar, debar keras di dadaku perlahan mereda.
“Good morning, Laura. How are you?”
Aku ikut tersenyum lebar, percaya diri. Seperti Laura.
“I feel great!”
Ajaibnya, semuanya berjalan lancar. Aku keluar dari ruang tes dengan semua orang yang mengerubungiku, menyapaku, bertanya berbagai hal, yang kucoba jawab sebisanya. Semuanya memanggilku Laura. Tidak ada yang mencurigaiku sama sekali. Dan sebenarnya ... selain tes yang membuat kupingku dipenuhi dengung detak jantungku sendiri, sisa hari itu cukup menyenangkan.
Merasakan sedikit perhatian-perhatian itu ... cukup menyenangkan.
“Bagus, ya. Gue capek-capek menguras otak lo enak main!”
Laura yang ketika aku pulang justru sibuk bermain di ponsel mendongak menatapku. Aku meletakkan tas di atas kasur, di samping Laura, lalu mengabaikannya untuk mengganti seragam.
“Gimana tesnya?” tanya cewek itu penasaran. “Lancar?”
Aku hanya mengendikkan bahu sebagai balasan, mencopot seragam dari tubuhku yang sedikit berkeringat dan menyangkutkannya pada gantungan baju. Selanjutnya, aku membelakangi Laura, membuka lemari untuk mencari-cari kaus yang nyaman dipakai.
Tidak begitu kuperhatikan ketika Laura merangkak di atas kasur, mendekatiku. Dan yang lebih di luar dugaan, ia tahu-tahu memelukku yang baru setengah memasukkan kepala ke dalam kerah kaus lusuh milikku.
“Makasih Nana! You’re the best!”
Kami tidak biasa berpelukan begini. Terlebih, aku bukan jenis orang yang menyenangi kontak fisik. Jadi aku tidak begitu tahu apa yang harus kulakukan.
“Iya, iya. Lepasin, nggak!” ketusku, masih setengah jengkel, setengah kikuk.
Tetapi, Laura tidak terpengaruh, ia mengecup pipiku sebelum bangkit dari berdiri. “Ayo! Gue udah beliin mi ayam khusus buat lo!”
Yang kuingat, aku mengeluh saat itu. Pipiku jadi basah yang harus kusapu dengan kaus baju. Lalu, aku menyumpah pada Laura sebelum kami benar-benar pergi membeli mi ayam.
Aku melangkah maju memasuki ruangan. Satu persatu. Perlahan. Di atas ranjang rumah sakit, aku melihatnya. Laura terbaring kaku di ujung sana, terbalut perban.
“Cewek!”
Salah satu hal yang kubenci dari tumbuh menjadi remaja adalah bahwa makhluk berjenis kelamin laki-laki mulai menatap dengan cara berbeda. Aku tahu mereka hanya iseng, tetapi keisengan itu membuat benar-benar risih sehingga jika tidak terlalu penting, aku tidak akan mau menjebloskan diri ke hadapan orang-orang ini. Tetapi Bunda menyuruh mengantarkan makanan ke rumah Nenek dan mau tidak mau, hanya ini jalan satu-satunya ke sana. Dengan beberapa remaja putus sekolah yang bersikap seperti preman bergerombol di depan gang.
“Misi,” jawabku sehalus mungkin, sembari mencari celah, berharap mereka bisa mengabaikanku dan memberi jalan.
Nyatanya tidak.
“Mampir dulu dong bentar sama Aa!” jawab salah satu, yang segera mendapat sorakan dari yang lain.
Sementara yang kulakukan hanya mampu diam-diam membuang napas muak.
Sepertinya, dorongan dari teman-temannya membuat cowok yang berdiri di hadapanku semakin berani. Ia melangkah mendekat, lalu dengan kurang ajar mencolekku di dagu. Aku segera mundur, tetapi terlalu terlambat untuk itu. Dan yang kulakukan, justru semakin membuat mereka bersorak senang.
Seandainya dulu aku tidak menolak ajakan untuk bergabung dengan kelompok bela diri di sekolah dasar ...
Aku ingin sekali menendang mereka, memukul, memaki, apapun yang membuat mereka tidak berani mendekatiku lagi. Atau setidaknya yang menjauhkan mereka dariku saat ini saja. Tetapi aku berhadapan dengan lima cowok, yang kelima-limanya lebih tinggi dariku. Seandainya aku berteriak pun, akan terasa terlalu berlebihan. Dan aku tidak bisa berteriak.
Kesempatan yang kupunya hanya lari, pulang kembali ke rumah. Aku sedang mempertimbangkannya ketika satu buah tas selempang melayang mengenai si cowok kurang ajar yang mencolekku.
“Apa lo? Beraninya sama cewek! Cemen!”
Beberapa suara tampak terkejut. Bukan hanya karena serangan dadakan itu, tetapi juga kemunculan Laura. Aku, termasuk salah seorang yang terkejut itu.
“Bentar! Mereka ada dua?!” Beberapa tampak kebingungan.
“Iya! Mau apa kalian? Mau ganggu?! Aku laporin Bapakku, mau?!”
Laura juga tidak menguasai bela diri apapun. Tetapi ia membulatkan matanya galak, berteriak lantang, dan mengayunkan tasnya dengan keras, membuat mau tidak mau, cowok-cowok itu mundur, berlarian kabur.
Laura menggandeng tanganku.
“Kok lo nggak bilang mau ke rumah Nenek?”
“Mama yang nyuruh.”
“Lain kali, ajak gue. Biar nanti kalau mereka ganggu lagi, gue lempar pakai sepatu.”
Aku tersenyum. Meski banyak percekcokan yang sering terjadi di antara kami, Laura tetap saudariku, keluargaku... sahabatku. Dan dia ... tidak selalu menyebalkan.
Kini, aku berdiri di sisinya. Cewek itu diam seperti onggokan daging. Hanya detak jantung yang dicatat kardiograf yang terpasang di sisi tempat tidur yang memberitahu bahwa Laura masih hidup. Saudari kembarku masih hidup.
Aku meraih tangannya, merasakan sisa-sisa hangat. Hal yang membuatku ingin percaya bahwa... Laura masih punya harapan. Bahwa ... keajaiban itu ada. Dan aku berharap, keajaiban itu datang sekarang.
“Ra... Kamu tahu bahwa kita selalu punya ikatan, kan? Kita selalu punya cara untuk bicara satu sama lain. Kita selalu tahu perasaan satu sama lain. Dan hari ini ..., ada yang mau kukasih tahu. Aku tahu, kamu ... di sana dengerin, kan?”
Dan aku menumpahkannya. Rahasia itu.


 rainaya
rainaya