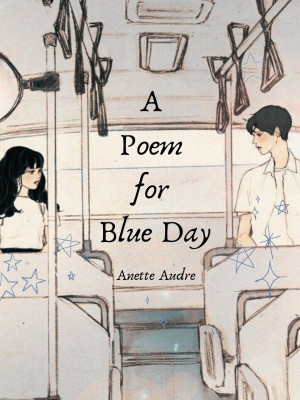Sial! Harusnya aku dengar perkataan
Ethan waktu itu. Perempuan sama saja! Kalau sudah jadi pacar bakal berubah
egois, sensitif, dan cemburuan.
Setelah meninggalkan aku begitu saja,
ia tidak sama sekali mengubungiku. Karena bujukan Aksa, akhirnya aku yang mengalah
untuk menghubunginya lebih dulu. Bukannya diangkat, Mara malah memblok nomor
dan seluruh sosial mediaku.
"Bener kata Ethan, Sa! Gausah lo
punya cewek. Ribet!" kataku memperingati. Sementara Aksa terlihat acuh
sebab sedang menghitung untung dagangan hari ini.
Aku marah dan merasa tidak dihargai.
Sejak tadi yang aku lakukan hanyalah menatap ponselku yang tak bernyawa. Mau
pulang ke kosan saja malas rasanya. Sehingga setelah mengisi acara di kafe, aku
lebih memilih untuk bermalam di rumah Aksa.
Tak lama, Mentari datang. Ia turun
dari gojek, lalu masuk rumah dengan wajah kelelahan.
Bagaimana tidak? Setelah membantu
Aksa melayani pembeli, ia masih harus lanjut bekerja ke kafe.
"Baliknya malem banget. Kafe
lagi rame, ya?" tanya Aksa basa-basi, memecah keheningan yang sempat
tercipta. Mentari hanya mengangguk, lalu melepas sepatu, dan memasukannya ke
dalam rak samping pintu masuk.
"Gue nggak lewat O'Eight sih
jadi nggak tahu lo belum balik. Kalau tahu begitu, tadi gue nunggu aja biar
balik bareng," kataku menimpali ucapan Aksa.
"Nggak apa-apa kok, Kak. Santai
aja," balas Mentari yang langsung berlalu begitu saja. Meninggalkan aku
dan Aksa yang masih duduk di teras depan rumah.
Masalah di hidupku datang silih
berganti. Sejak kecil, aku selalu merasa dunia yang aku tempati begitu tak
adil. Ketika semua orang punya keluarga yang lengkap, keluargaku harus terpisah
belah. Ketika semua teman-temanku mampu membeli mainan--yang harganya tak
melulu mahal--aku harus berhemat bahkan puasa untuk menyisihkan uang saku untuk
membelinya.
Ibu selalu bilang keuangan keluarga
sedang tak baik. Aku harus paham. Usaha ayah dulu lumayan maju. Ia memiliki
toko ikan di pasar. Namun, setelah ia ditipu oleh sahabatnya sendiri, usahanya
makin tak karuan.
Ayah dan sahabatnya berencana membuka
toko ikan yang lebih besar. Sahabatnya menjanjikan bahwa ia akan menjualnya
juga sampai keluar negeri. Katanya, sahabat ayahku ini pernah kerja di Taiwan
dan kenal beberapa pengusaha di sana. Ayah sampai menjual rumah pusaka dari
orang tuanya, juga mobil, serta perhiasan Ibu.
Namun ternyata, sahabat ayah penipu.
Ia membawa kabur uang puluhan juta yang pada zaman itu jumlahnya besar sekali.
Rumah tangga Ibu dan Ayah kena imbasnya. Hampir setiap hari mereka bertengkar.
Kekurangan ekonomi sering kali salimg melempar umpatan bahasa hewan. Dulu, ayah
dan ibu tak pernah begitu, tetapi sekarang semuanya sudah berubah.
Ayah tidak tahu keberadaannya di mana
setelah keluar dari penjara karena kasus KDRT. Sementara Ibu sudah bahagia
dengan keluarga barunya di Amerika.
Aku tak pernah ingin tahu adikku atau
suami baru ibuku. Karena rasanya, hatiku belum menerima.
Sampai pada saat sosok yang tak ingin
aku temui itu datang di depan universitas. Ibu dan dua anaknya datang
menemuiku.
Sama sepertiku, Ethan dan Aksa juga kaget
melihat kedatangan ibuku dan dua anaknya yang tiba-tiba. Mereka sempat terdiam
sesaat, tapi setelahnya berlaku ramah dan sopan. Ini pertama kalinya mereka
bertemu. Biasanya hanya lihat melalui video call ketika ibu meneleponku. Antara
Ethan, Aksa, dan ibu terlibat obrolan basa-basi seperti bertanya kabar, kapan
datang, dan bagaimana progress kuliah.
Mengerti jika ibu ingin ngobrol empat
mata denganku, Ethan dan Aksa pun pamit pergi. Mereka enggan mengganggu momen
yang dulu selalu aku semogakan. Setidaknya sampai Oma meninggal dunia.
Ibu masih terlihat cantik untuk
ukuran wanita sebayanya. Tubuhnya terlihat sehat dan terawat. Kulitnya putih
bersih, serta penampilannya yang modis. Ibu sangat berbeda sekali dengan ibu
yang aku lihat terakhir kali.
Sambil menggendong kedua putrinya, ia
melangkah mendekat ke arahku yang masih mematung di tempat. Selangkah demi
selangkah, ia mendekatiku dengan air mata yang sudah tak terbendung lagi.
Tangannya beralih mengelus pipiku lembut. "Daniel. Anak Ibu," ujarnya
dengan suara bergetar. "Ibu nggak nyangka kamu udah sebesar ini."
**
Pot tanaman kesayangan milik Oma yang
sengaja di taruh di sudut ruang makan layu. Entah mengapa begitu. Setiap pagi
biasanya Oma rajin menyiramnya. Awalnya aku bingung kenapa Oma lebih memilih menaruhnya
di situ. Oma bilang agar tanaman itu tak kekurangan sinar matahari. Lalu, aku
makin bingung, kenapa tidak menaruhnya di depan halaman saja. Kemudian senyum
Oma—yang lebih terlihat tersenyum getir itu—memandang ke arahku.
Itu tanaman bambu hias jepang yang
diberikan oleh Ibu. Beberapa tahun lalu, sebelum keberangkatannya ke Amerika.
Ibu bilang tanaman ini bisa mendatangkan rezeki. Aku juga masih ingat betul,
harapan dan do'a yang Ibu tuturkan untuk Oma. Membuat Oma menangis haru dan
memeluk putrinya itu penuh kehangatan.
Kini, setelah Ibu kembali dan Oma
sudah pergi ke pangkuan sang kuasa, tanaman itu layu. tanaman itu mati.
"Aku nggak setuju kalau Daniel
harus ikut Mbak ke Amerika," kata Om Hari dengan suara lantang dan tegas.
"Daniel masih kuliah. Biarkan dia selesaikan dulu kuliahnya!"
Suasana ini begitu emosional. Ruang
makan yang biasanya kami gunakan untuk makan, berubah menjadi kursi panas
penghakiman. Aku merasa tak berhak berkata apa-apa, meskipun aku berhak membela
diriku sendiri. Untuk apa aku ke Amerika? Sekarang aku sudah terbiasa hidup
tanpa ibu. Aku bisa mengurus diriku sendiri.
"Di sana hidup Daniel bisa
terjamin, Ri. Kalau memang nggak bisa ikut sekarang karena sayang kuliahnya ...
setelah lulus nanti Daneil bisa ikut sama Mbak."
“Tapi apa lebih baik kita tanya
Daniel-nya saja Mbak?” sambung Tante Asih yang sependapat dengan suaminya itu. “Itu
bukan keputusan yang bisa diambil buru-buru.”
“Daniel pasti mau. Itu yang selalu
dia inginkan … tinggal bersamaku.” Nada ibu sangat tegas. Seolah-olah tahu betul
apa yang diinginkan oleh anaknya.
Aku menggeleng pelan. Rasanya meski
ingin bicara kasar dan berteriak, sulit untuk mulutku berucap. Hatiku terluka.
Terluka sudah lama sekali sampai-sampai aku tak tahu pasti tepatnya kapan. Entah
saat perceraian, entah saat melihat ayahku ditangkap depan mataku sendiri, atau
ketika mendengar ibu menikah lagi. Bu Lela pernah bilang bahwa waktu akan
membuatku paham dan mengerti. Bahwa pemikiran anak-anak sepertiku tak akan bisa
sejalan dengan keputusan orang dewasa. Namun sampai sekarang, aku dibuat makin
tak mengerti.
“Daniel nggak mau ikut ibu,” kataku
berusaha bicara.
“Kok begitu? Kemarin-kemarin Daniel
bilang mau tinggal sama Ibu?”
Aku menghela napas dalam, masih berusaha
menahan luapan emosi yang sudah bergejolak di dalam dada. Membuat dadaku sesak
hampir mati. “Kemarin itu kapan?” tanyaku masih berusaha bicara dengan tenang. “Kemarin
yang kemarin? Kemarin satu tahun yang lalu? Atau kemarin 10 tahun yang lalu?”
Kami semua terdiam. Suasana mendadak hening
ketika aku bicara. Jujur saja, hal ini membuat aku muak. Kenapa tidak ada orang
yang bicara? Aku butuh penjelasan. Bukan tatapan sedih yang makin membuatku
sia-sia.
“Apakah salah ketika anak 11 tahun
memohon pada ibunya untuk tinggal bersama? Ayahku di penjara … lalu aku
bagaimana?” kataku dengan air mata yang tak bisa ditahan. “Apakah salah ketika
semua orang datang bersama orang tuanya untuk mengambil rapor di sekolah, aku
memohon pada ibu untuk datang … sekali saja seumur hidup untuk datang ke
perayaan kelulusanku?”
Kudengar suara isakan tangis Tante
Asih yang tak bisa dibendung. Tante memang lebih melankolis dibanding siapa
pun. Meskipun bukan ibu kandangku, aku tahu bahwa ia menyayangiku.
“Ibu tahu … ibu salah,” ujarnya dengan
suara begetar, tak kuasa menahan tangis. “Biarkan ibu memperbaiki keadaan ini.
Apalagi setelah kepergian Oma … hidup ibu sangat hampa. Rasa bersalah terus menghantui
ibu. Ibu tak bisa makan dan tidur dengan nyenyak. Seolah-olah Tuhan sedang
mengukum Ibu, Niel.”
“Simpan saja penyesalan Ibu,” kataku
dengan nada dingin. “Aku juga tidak mau tinggal bersama ibu. Tinggal saja Bahagia
bersama keluarga kecil Ibu di Amerika. Aku sudah tak mengharapkan apa-apa lagi.
Mulai sekarang … nggak usah kirim uang lagi ke Daneil kalau itu yang membuat ibu
nantinya berpikir berhak memaksa aku tinggal di sana. Aku nggak mau berhutang
budi.”
“Bukan begitu, Niel. Sudah seharusnya
Ibu mengirimkan kamu uang. Kamu itu anak ibu—”
Aku bangkit dari kursi. Suara derit
kursi membuat pandangan mereka semua tertuju padaku. Biar saja mereka berpikir
aku kurang ajar atau orang yang lari dari masalah. Kuakui, aku memang pengecut.
Akan tetapi, hal yang aku lakukan demi kebaikanku sendiri. Rasa sedih bisa menggerogoti
pikiranku. Aku tak ingin berlarut bahkan terjebak lagi dalam perasaan ini.
Biar saja perasaan bersalah ibu
menghantui dirinya. Dan biar saja, kesepian ini menemaniku selamanya.
“Aku pergi.”


 irennatiff
irennatiff