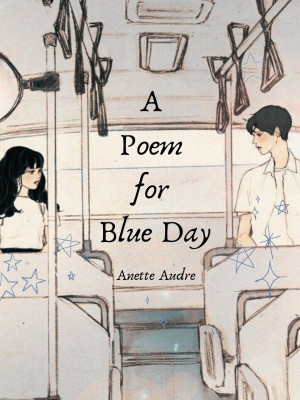Suasana pagi menjelang Subuh makin dingin. Udara yang kuhirup begitu sejuk memenuhi paru-paruku. Agar tidak ketahuan orang rumah, aku membuka pagar rumah pelan-pelan. Kemudian memasukan motor ke dalam bagasi.
Hendak melepas sepatu, suara berisik gemerincing kunci terdengar dari arah dalam rumah. Tak lama keluarlah Om Hari. Ia berdiri di hadapanku dengan wajah tak bersahabat.
"Mau jadi berandalan kamu pulang hampir pagi begini?"
Pergerakanku melemah. Om Hari memang sering berkata seenaknya, ini bukan kali pertama. Namun entah mengapa, rasanya hatiku seperti tertusuk paku tajam, sakit sekali.
"Daniel punya alasan, Om."
"Alasan apa lagi?!" ujar Om Hari penuh penekanan. Rupanya ia tidak begitu gila untuk teriak dan marah-marah di pagi buta begini. "Kamu itu sering banget bikin Oma khawatir!"
"Tapi ... Daniel udah izin sama Oma dan Tante Asih kok!"
"Apa? Izin kerja? Kerja apa kamu pulang jam segini? Muka kamu pun cemongan begitu? Bikin ulah apa lagi kamu, hah!"
Mati-matian aku menahan napasku agar tak memburu. Mataku sudah panas, sudah aku kepal kedua tangan erat-erat. Aku tahan agar jangan sampai melakukan hal kelewat batas.
Selama ini aku sadar telah banyak merepotkan. Masih untung ada Oma dan Om Hari yang mau menampungku agar tidak jadi gelandangan.
Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil. Kejadian itu membuatku kehilangan banyak hal. Dan menimbulkan rasa takut luar biasa akibat pertikaian mereka. Ayah pergi entah kemana setelah di penjara, sementara Ibu pergi kerja ke luar negeri, lalu menikah dengan majikannya sendiri. Sampai saat ini, Ibu tak pernah kembali.
Memang ibu bertanggung jawab. Ibu masih mengirim nafkah untukku, tetapi jumlahnya tak mencukupi kebutuhanku. Dulu saat Oma masih berjualan catering, beliaulah yang membantu kekurangannya. Namun setelah keadaan Oma memburuk, beliau tidak lagi berjualan catering.
Usia Oma juga sudah tak muda lagi, beliau sudah sering sakit-sakitan. Ibuku yang hanya seorang IRT setelah menikah pun tak bisa mengirim uang lebih ke Indonesia. Dan Om Hari berbaik hati membiayai kekurangan yang ada. Aku tahu ... aku berhutang budi padanya. Oleh sebab itu, apa pun ucapan atau umpatan yang dilontarkan Om Hari, akan aku terima.
“Maaf—“
"Kalau sudah bilang maaf, jangan diulangi!" potongnya cepat. "Belajar yang benar. Lulus dan cepet dapat kerjaan. Sebagai seorang laki-laki, kamu harus berdiri pakai kakimu sendiri!"
I try, kataku dalam hati. Bahkan aku sampai manggung nge-band begini biar dapat uang tambahan. Biar bisa nabung dan gak ngerepotin orang rumah. Akan tetapi, apa yang aku lakukan selalu salah.
Tanpa berkata apa-apa lagi, Om Hari masuk ke dalam rumah. Sementara aku mengurungkan niatku melepas sepatu dan memilih untuk bangkit dari kursi, lalu bergegas kembali menyalakan motor, kemudian pergi.
***
Setelah Mas Aksa menjelaskan kejadian di kafe tadi, raut wajah Ibu dan Babeh berubah. Antara perasaan khawatir atau lega karena aku masih diberi selamat.
Aku menghubungi Tente Diandra, owner O'Eight. Ia pun segera datang ke kafe untuk melihat kondisinya langsung.
Hubunganku dengan Tante Diandra cukup baik. Mengingat aku adalah sahabat baik ponakannya, Iren. Setelah menjelaskan kejadian kebakaran itu, syukurlah Tante Diandra mengerti. Dan Adrian yang sangat butuh pekerjaan sambilan itu tak jadi di pecat.
Pagi-pagi sekali setelah membantu ibu menyuci perlatan masak, aku mendengar suara Daniel. Aku mengintip dari horden yang memisahkan antara dapur dan ruang makan. Dia masih mengenakan pakaian yang sama seperti semalam. Itu artinya dia tidak pulang ke rumah.
"Makasih banyak ya, Niel. Aduh ... Ibu nggak bisa bayangin gimana kalau kamu nggak cepet-cepet ke dalam kafe buat padamin api. Begitu kata ibu dengan nada yang penuh syukur, sampai-sampai ia mengelus dadaknya berkali-kali.
"Kebetulan aja kok, Buk. Syukurlah Tari dan temennya nggak kenapa-kenapa."
Percakapan mereka kembali terjalin. Bisa dibilang antara ibu dan Daniel memang dekat. Mereka sering ngobrol banyak hal. Saking dekatnya, ibu dan babeh sudah menganggap Daniel sebagai anak kandungnya sendiri.
Aku membali ke membilas piring yang sudah kucuci. Samar-samar kudengar percakapan mereka lagi.
"Aksa sama Babeh udah ke warung, Buk?"
"Udah. Ini di rumah cuma ada Ibu sama Tari," jawab ibu. "Eh, kamu udah makan belum, Niel?"
"Belum...."
"Owalah. Laukannya udah abis lagi. Bentar, ya!" kata Ibu. "Mantari ... gorengin ayam di freezer kulkas sama ceplok telor ya buat Mas Daniel."
Napasku tercekat karena kaget. "Ya-ya, Buk," balasku dengan terbata-bata.
"Nggak usah ah, Buk. Nanti beli aja nasi kuning di sebelah warung Babeh."
"Jangan! Makanan rumah lebih sehat tahu," ujar Ibu sambil terkekeh. "Ya udah ... Niel di sini ya sambil nunggu makanan jadi. Ibu mau ke warung bantu-bantu Babeh, sekalian bilang ke Aksa kamu dateng ke rumah."
"Mau dianter nggak, Bu?"
"Nggak usah. Ibu sengaja mau jalan pagi." Ibu membuka gorden dapur, lalu berkata lagi padaku, "Tolong ya, Nduk. Itu nanti siapin makanannya buat Mas Daniel."
"Ya, Buk." Aku mengangguk paham.
Sejujurnya, aku bukan tak nyaman. Hanya saja, berinteraksi dengan orang lain menguras energiku. Apalagi ini laki-laki. Aku bingung memulai suatu percakapan. Makanya selama ini kalau ada Daniel atau pun Ethan, aku lebih memilih di kamar atau ke Warung.
"Mau gue bantuin nggak?"
Punggungku mendadak membeku. Suara bariton itu menganggetkanku. "E-eh nggak usah. Gue selesein bilas piring, baru goreng ayam-nya ya."
Cowok itu pun mengangguk. Tanpa bilang apa-apa lagi, ia meletakan piring bersih yang kuletakan di jaring baskom ke lemari piring bersih. "Kalau bantu masukin piring bersih ... nggak apa-apa, kan?"


 irennatiff
irennatiff