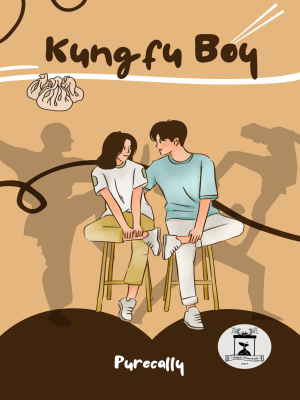Jam
yang melingkar di pergelangan tangan Hayley sudah menunjukan pukul dua belas
malam. Namun, keinginannya untuk pulang sama sekali tidak ada. Ia ingin terus
di sini tertawa bebas bersama Will, membicarakan hal-hal yang tak penting, yang
tak ada hubungannya dengan kehidupan aslinya dan masalahnya di New York.
“Bukankah ini jam dimana seluruh
wanita baik-baik sudah harus berada di kamarnya?” tanya Will.
Hayley menguap. Ia memang mengantuk,
tetapi belum mau beranjak dari sisi Will. “Siapa bilang aku wanita baik-baik?”
“Begitu?” goda Will.
“Tidak ada wanita baik-baik yang mau
berteman dengan pencuri sepeda,” balas Hayley menggigit bibir menahan senyuman.
Will terkekeh. Ia lalu turun dari
sisi jembatan dan mengulurkan tangannya untuk membantu Hayley turun. Namun,
Hayley menggeleng.
“Aku belum mau pulang,” tolak Hayley
sedikit merengek.
Will merapatkan jaket Hayley. “Sudah
larut. Hawa akan semakin dingin, kau bisa masuk angin.”
Hayley tetap menggeleng dan tidak
mau menerima uluran tangan Will. “Aku tidak bekerja besok, aku bisa tidur
larut.”
Sebenarnya Hayley tidak khawatir
akan masuk angin atau tidur larut. Ia hanya tidak mau sendiri—untuk pertama
kalinya ia tidak menemukan kenyamanan dalam kesendirian. Ini benar-benar gawat,
ia tahu itu. Ia juga tidak mau ketergantungan pada kehadiran Jane, Matthew, dan
Will. Tapi tanpa mereka, hidup Hayley terasa hampa dan sunyi.
Will menatapnya dengan lembut di
bawah kegelapan langit malam. Tidak ada bintang di langit, keindahan malam ini
digantikan oleh pancaran sinar bola mata indah milik Will ketika menatapnya.
“Ikutlah denganku,” ajak Will.
“Kemana?” tanya Hayley.
“Suatu tempat.” Will tidak
menjelaskan tempat apa yang ia maksud. Namun, Hayley tetap ingin ikut.
Kemanapun itu, asalkan Will tetap berada di sisinya.
Setelah sebelumnya mengembalikan
sepeda itu secara diam-diam, mereka berjalan membelah gelapnya malam. Rasa
kantuk Hayley hilang begitu saja di detik Will menuntunnya ke sebuah tempat.
Rumah.
Tempat yang Will maksud adalah
sebuah rumah.
Dan rumah itu—
“Ini tempat tinggalku, Hayley. Bukan
rumah, aku sudah lama tak berumah,” jelas Will ketika mereka berdiri di depan
pintu coklat tua.
“Ini jelas-jelas sebuah rumah,
Willy. Apa maksudmu?” Mata Hayley menyusuri detail rumah itu, model rumahnya
hampir sama seperti milik Jane. Hanya saja, milik Will lebih kecil.
“Definisi rumah menurutku adalah
seseorang, bukan tempat dimana aku tidur atau melakukan aktivitas.”
Hayley tertegun dibuatnya. Lelaki
dihadapannya ini tak henti-hentinya memberi kejutan. Will memang berbeda dengan
laki-laki yang sebelumnya pernah hadir di hidup Hayley. Lelaki tampan itu
selalu punya caranya sendiri untuk membuat Hayley merasa lebih hidup.
Ia memerhatikan tangan Will ketika pria
itu memasukkan kunci ke dalam lubang pintu lalu memutarnya. Dengan masih tidak
percaya jika Will mengajaknya ke tempat ia tinggal, Hayley berjalan masuk.
Rumah Will sangat sederhana, di lantai pertama hanya diisi dengan beberapa
furnitur; lemari tua kecil, dua sofa berwarna merah ati, meja kayu, dan
perapian.
Tidak ada televisi ataupun radio.
“Wow,” ucap Hayley tanpa sadar.
Sedangkan Will sibuk membuatkan mereka teh hangat. “Di mana kau biasa menulis?”
lanjut Hayley setelah berdeham.
Will membawa dua gelas teh hangat itu
pada masing-masing tangannya. “Lantai atas. Ayo.”
Mereka menaiki tangga kayu dengan
hati-hati menuju lantai atas. Jika tadi Hayley sudah cukup terkesan pada lantai
bawah, kini ia benar-benar terpukau dengan apa yang Will tempatkan di lantai
atas. Karena ketika ia menginjakkan kaki di lantai tersebut, ia disambut dengan
jejeran rak-rak yang dipenuhi oleh buku-buku yang tertata rapi. Tidak hanya
itu, pada bagian dinding pun dipenuhi oleh buku-buku dengan rak yang seakan
terbang.
Di bagian pojok dekat jendela besar,
terdapat meja tua yang diatasnya tergeletak sebuah laptop dan tumpukan
buku-buku catatan serta adapula kursi kayu yang diatasnya dilengkapi oleh
bantalan yang empuk.
“Itu tempatku menulis,” jelas Will
menujuk pada meja dekat jendela besar itu. Hayley mengangguk sembari mengamati
meja itu dengan saksama.
“Di mana kau tidur?” tanya Hayley
setelah beberapa saat.
Will menunjuk pada ruangan yang pintunya
tertutup rapat, yang hampir tidak terlihat karena terhalang oleh rak buku.
“Disitu, tapi aku jarang menempatinya. Kamar itu hampir tak pernah terpakai.
Karena aku lebih sering ketiduran di meja tempatku menulis atau di sofa lantai
bawah ketika sedang mencari ide.”
Hayley berjalan menyusuri rak-rak itu
sembari menyentuh buku-buku Will satu-persatu secara singkat. Ia mengamati,
berusaha mencari-cari siapa Will Morrison sebenarnya, selain penulis novel yang
nama pena-nya sudah terkenal di mana-mana.
“Teh-mu disini, silakan melihat-lihat.
Aku harus menulis sebentar, tidak akan lama.” Will menaruh teh Hayley di rak
buku lalu duduk di kursi empuk itu dan membuka laptopnya. Meninggalkan Hayley
yang masih asyik melihat koleksi buku milik Will.
Beberapa jam kemudian, suara Hayley
sudah tak terdengar. Wanita itu tidak lagi berada di lantai atas, membuat Will
khawatir. Setelah menutup laptopnya, ia menuruni tangga dengan tergesa-gesa.
Perasaan lega menghampirinya tatkala melihat wajah damai Hayley yang tertidur di
sofa tempat ia biasa tidur.
Hayley tertidur dengan novel The Secret
History yang terbuka di dekapannya. Rupanya ia tertidur ketika sedang membaca.
Will menengadah, melihat jam di
dinding yang menunjukkan pukul dua pagi. Inilah kelemahannya ketika menulis, ia
menjadi lupa waktu dan lupa sekitarnya. Hayley pasti bosan menunggunya. Will
menunduk, menatap Hayley dengan perasaan bersalah.
“Maafkan aku, Hayley. Maaf,” lirih
Will.
Dengan hati-hati, Will membopong
tubuh Hayley ke lantai atas. Ia meletakkan tubuh itu di atas ranjang miliknya
lalu menarik selimut untuk menutupi setengah tubuh Hayley. Will selama ini sadar
akan keindahan wajah Hayley. Bulu matanya yang lentik, bibirnya yang ranum, dan
hidungnya yang mungil.
Tetapi, yang paling membuat Will
terpesona adalah bola mata hijau Hayley. Bahkan ketika Will terpejam pun,
bayangan mata itu muncul di kegelapan.
“Good
night, Love,” bisik Will. Ia mengurungkan niatnya untuk mengecup kening
Hayley karena mengingat bila saat ini bukan saat yang tepat untuk melakukan hal
bodoh.
Ketika Will hendak berjalan keluar
kamar, Hayley tiba-tiba berucap lirih dengan kedua mata yang masih terpejam,
“Will? Will, kaukah itu?”
“Ya, ini aku,” jawab Will lembut.
“Jangan pergi,” lanjut Hayley.
Keningnya berkeringat dan mengerut. Matanya masih menutup.
“Aku disini, selama yang kau mau.”
Setelah itu, hening. Hayley kembali
ke alam mimpinya dengan kening yang sudah tidak mengerut. Will mengusap kening
itu perlahan sebelum akhirnya keluar kamar tanpa menimbulkan suara. Bagaimanapun, ia belum bisa menuruti permintaan Hayley yang itu.
***
“Pagi.” Senyum manis Will menjadi
hal pertama yang Hayley lihat ketika ia keluar dari kamar Will dengan perasaan
bersalah pagi itu.
Hayley terlihat kacau. Rambutnya
acak-acakan dan wajahnya kusam karena kemarin malam sebelum tidur tidak sempat
melakukan ritual cuci mukanya. Hayley menuruni tangga dengan perasaan tak enak.
“Pertama-tama, aku minta maaf karena aku ketiduran. Kedua, aku minta maaf
karena ulahku, kau jadi tidur di sofa. Ketiga, aku benar-benar minta—“
“Hayley, Love, it’s okay,” potong Will. Ia beranjak dari sofa untuk menghampiri
Hayley yang berdiri di ujung tangga. “Aku kan sudah bilang, tempat tidurku itu
di sofa atau di meja,” lanjutnya sambil terkekeh.
“Tapi tetap saja, aku minta maaf.
Seharusnya kau bangunkan saja aku tadi malam. Tidak masalah.” Hayley menggaruk
kepalanya yang tak gatal.
Will menggeleng. Ia membuka lemari
dan mengambil sisir lalu mulai menyisir rambut Hayley dengan perlahan. “Tidak
mungkin. Bahkan jika kau benar-benar ingin pulang, aku akan menggendongmu dalam
keadaan tidur sampai rumah.”
Hayley tak bisa menahan senyumnya mendengar
itu. Apalagi perlakuan Will yang menyisir rambutnya tanpa disuruh. Lelaki
dihadapannya benar-benar sangat act of
service. “Aku harus kembali, ada pekerjaan rumah yang harus kukerjakan,”
ucap Hayley sembari mengikat rambut pirangnya yang sudah rapi menjadi kucir
kuda.
Will mengangguk meskipun tak rela.
“Biarkan aku mengantarmu.”
“Tidak perlu,” tolak Hayley. “Aku
sudah cukup merepotkanmu.”
Karena tidak mau memaksa dan
berdebat, Will mengalah. Akhirnya ia hanya mengantar Hayley sampai depan. Ia
bersandar pada kusen pintu dengan senyum tipisnya. Otot-otot tangan Will terlihat
menonjol dari balik kaus yang dikenakannya. Tak ada pemandangan yang lebih
indah daripada itu bagi Hayley.
“Terima kasih, Willy. Sampai jumpa
nanti,” pamit Hayley lalu berjinjit untuk mencium pipi Will secara singkat tapi
mampu membuat statistik jantung Will meningkat.
Hayley sudah melewati pagar ketika
Will berkata, “Hayley. Maukah kau ikut denganku nanti siang? Aku akan
mewawancarai seseorang untuk novel yang sedang kutulis.”
Hayley menoleh ke belakang lalu mengangguk antusias. “Tentu. Tunggu aku di jembatan ya!"
Will tersenyum sembari mengangguk. “See you, love.”
Sepeninggal
Hayley dari rumahnya, Will menyibukkan diri dengan meneruskan menulis draft Chapter 10 untuk novel yang sedang
ditulisnya. Ia sudah menulis cukup banyak kata sejak tadi malam. Entah kenapa,
akhir-akhir ini writer’s block yang
dialaminya tidak begitu parah dan mudah hilang.
Will tidak berbohong ketika ia
menemui Hayley di rumah Jane secara diam-diam malam itu karena tidak bisa
menulis. Ide yang biasanya mengalir dengan lancar tiba-tiba buntu, dan hal
pertama yang ada di pikirannya adalah Hayley. Tanpa berpikir panjang, ia
langsung menemui Hayley dan mengajaknya mengobrol, meskipun dengan cara agak
sedikit memaksa.
Setelahnya, secara ajaib ia bisa
menulis lagi.
Ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Ia selalu kesulitan ketika cobaan menulis itu datang. Misalnya, beberapa bulan
yang lalu, ia bahkan sudah masuk ke beberapa bar yang ramai untuk mencari suasana baru dan orang-orang baru
tetapi hasilnya tetap nihil. Ia tetap pulang ke rumah dengan ide kosong
dan lebih parahnya lagi dalam keadaan mabuk berat.
Tapi dengan Hayley, semuanya terasa
mudah. Dengan hanya melihat senyum manisnya saja, Will sudah ingin buru-buru
menulis beribu-ribu kata.
Ia sedang asyik menulis tatkala
suara ketukan pintu dari luar menghentikannya. Will buru-buru turun untuk
membuka pintu, karena pasti itu Hayley.
“Hayley, kukira kita akan bertemu di
jem—Paman Mark?” Ekspresinya berubah dalam sepersekian detik ketika menyadari
bahwa yang dihadapannya bukan orang yang ia nanti.
“Kau sedang sibuk?” tanya seseorang
yang disebut Paman Mark itu. Wajahnya terlihat gusar, seperti ada sesuatu yang
cepat-cepat ingin dibicarakan.
“Tidak terlalu,” jawab Will lalu
mempersilakan Paman Mark untuk masuk.
Hanya ada keheningan selama beberapa
saat ketika keduanya sudah sama-sama duduk di sofa. Will tidak tahu harus
mengatakan apa karena ia sendiri juga tak tahu tujuan dari kedatangan Paman
Mark.
“William,” ucap Paman Mark menatap
Will dalam-dalam. “Lily terpuruk akhir-akhir ini, aku tidak tahu harus
bagaimana lagi. Dia juga kecewa karena kau ada di sini tetapi jarang
menemuinya.”
Will menunduk, menatap lantai kayu
di bawahnya. Tidak ada kontak mata yang intens, tetapi rasanya seperti
terbakar. Seluruh tubuh Will panas, ia ingin cepat-cepat masuk ke dalam
genangan air dingin untuk menetralkan diri.
“Kau tahu sendiri, Paman. Dari awal
ini semua sebuah kesalahan. Aku memang bersedia untuk bertanggung jawab, itu
tujuan utamaku datang kesini—ketempat yang sudah kusumpah serapahi tidak akan
kuinjak lagi. Tapi, bukan berarti aku akan melakukan itu dengan cara yang
kalian inginkan. Aku punya caraku sendiri.” Will memutar-mutar cincin perak di
jemari kirinya. Ia tanpa sadar sering melakukan itu ketika sedang cemas atau
takut.
“Hanya satu yang dia butukan,
William. Kehadiranmu disisinya dalam masa sulit seperti ini.” Paman Mark
menggeser tubuhnya agar lebih dekat dengan Will. “Kumohon, temuilah Lily dan
katakanlah bahwa semua akan baik-baik saja. Dia pasti akan mendengarkanmu.”
Will menghela nafas kasar. Ia
menutup wajahnya dengan kedua tangan. “Aku akan menemuinya. Secepatnya.”
“Maksudku, temui dia sekarang. Sebagai
seorang Ayah, aku tidak tega melihatnya seperti itu. Kumohon bantu aku. Bantu
aku memperbaiki putriku Lily.” Paman Mark sudah siap akan berlutut dihadapan
Will, namun Will cepat-cepat menahan bahu pria tua itu.
Mark Hughes adalah pemilik restoran
terkenal bernama The Platinum di The Cotswolds. Ia dikenal dengan
keangkuhannya, tapi sekarang keangkuhan itu hilang entah kemana di hadapan
Will.
“Beri aku waktu.” Hanya itu yang
diucapkan Will. Ia lalu berjalan untuk membuka pintu; memberi kode pada Paman
Mark untuk keluar.
Paman Mark berjalan lunglai keluar
dari rumah Will. Ia berharap Will akan memenuhi permintaannya. Ia rela
melakukan apa saja untuk kebahagiaan putri satu-satunya itu.
Putrinya yang sekarang sedang
mengandung.
***
“Kau yakin Madison baik-baik saja?”
tanya Hayley pada Jane di sebrang telepon. Ia sedang menelepon Jane di London
menggunakan telepon rumah.
“Baik, Sayang. Nanti akan
kuceritakan semuanya di rumah.” Jane terdengar kelelahan. Entah apa yang
dikerjakannya disana, Hayley tidak tahu. Semua orang akhir-akhir ini serasa
menyembunyikan sesuatu. Dan hanya dirinya seorang yang tidak tahu apa-apa.
“Hati-hati, Jane. Aku harus pergi
sekarang, sampaikan salamku pada semuanya!” pamit Hayley lalu menutup telepon
dengan helaan nafas lelah.
Hayley sebenarnya ingin memaksa Jane
untuk menjelaskan semuanya, tapi di sisi lain, ia belum siap dengan masalah
baru yang akan datang di hidupnya. Satu-persatu, ya satu-persatu, ia akan
menyelesaikannya.
Yang terpenting sekarang ia tak
sabar untuk bertemu Will di jembatan sungai Eye. Berada di dekat Will selalu
membuatnya lupa akan semua masalah-masalah di hidupnya. Yang ada hanya tawa,
senyuman, dan momen menyenangkan selama bersama pria itu.
Hayley mengunci pintu rumah setelah
sebelumnya memasang topi di kepalanya. Siang ini matahari cukup terik. Sinarnya
terasa menusuk kulit, tidak menghangatkan seperti biasanya. Ia bersenandung ria
selama perjalanan. Perasaan bahagia begitu menyelimutinya, padahal ia hanya
akan menemani Will mewawancarai seseorang, bukan yang lain.
Sesampainya di jembatan sungai Eye,
ada beberapa remaja yang sedang bermain air di tepi sungai. Adapula yang asyik
berenang sambil tertawa lepas—menciprati temannya dengan air. Melihat itu,
Hayley tersenyum simpul. Senang rasanya ketika melihat orang lain tertawa
lepas. Mereka semua seperti tidak memiliki beban.
Hayley duduk di sisi jembatan
seperti tadi malam. Bedanya, kali ini Will belum terlihat batang hidungnya.
Hayley menatap ke sekelilingnya mencari-cari sosok Will.
Tidak ada.
Mungkin pria itu masih menulis.
Hayley meyakinkan diri lalu membuka
novel The Secret History yang dipinjamnya dari rumah Will tadi pagi. Ia akan
membaca selama beberapa menit sembari menunggu kedatangan Will.
Sayangnya, menit berganti menjadi
jam, namun Will tak kunjung datang. Hayley mulai resah, kalimat-kalimat dalam
novel yang dibacanya sudah tidak dapat dipahami. Fokusnya sudah buyar, ia hanya
ingin Will datang.
Ia melirik jam di pergelangan
tangannya—pukul dua siang. Dua jam sudah dirinya menunggu disini dan sama
sekali tak ada tanda-tanda bahwa Will akan datang. Dirinya dan Will sama-sama
sedang tidak menggunakan ponsel. Jadi, solusinya adalah mendatangi kediaman
Will secara langsung.
Mungkin pria itu lupa waktu karena
terlalu tenggelam pada aktivitas menulisnya sehingga lupa jika mempunyai janji
dengan Hayley.
Hayley turun dari sisi jembatan dan
berjalan menuju kediaman Will sambil mengucapkan mantra tersebut berkali-kali
‘Mungkin Will lupa’, ‘Mungkin Will ketiduran’, ‘Mungkin Will merasa tanggung
sehingga harus menulis lagi selama beberapa saat’, dan masih banyak Mungkin
Will-Mungkin Will yang lain.
Ketika sudah berhadap-hadapan dengan
pintu tempat tinggal Will, Hayley seketika menjadi ragu. Ia takut jika mantra
itu tidak berhasil dan Will mengecewakannya. Tetapi kemudian ia berpikir,
seharusnya yang dirugikan disini adalah Will, bukan dirinya. Karena Will-lah
yang seharusnya melakukan wawancara untuk kepentingan novelnya. Ia hanya
menemani. Jadi, ia tidak harus kecewa.
Namun sayangnya, rasa kecewa tidak
bisa dihindari tatkala pintu itu tidak terbuka sama sekali meskipun sudah
diketuk puluhan kali.
“Will! Kau di dalam? Ini aku
Hayley.” Hayley menggedor pintu, tidak lagi mengetuk. “Will? Kau baik-baik
saja?” lanjut Hayley.
“Dia pergi beberapa jam yang lalu.
Jangan berisik, kau menganggu sekali,” ucap seorang wanita tua yang keluar dari
rumah sebelah Will. Wanita itu terlihat marah, ekspresinya persis seperti Ibu
tiri Cinderella.
“Maaf.” Hayley memaksakan senyuman.
“Tahukah kau kemana dia pergi?” tanya Hayley seramah mungkin.
“Mana kutahu.” Wanita itu mendelik
sembari mengangkat bahu. “Tidak peduli. Bukan urusanku.” Tanpa mengucapkan
apapun lagi, ia masuk ke dalam rumah dengan membanting pintu.
Hayley merutuk. “Nenek sihir.”
Ia menatap rumah Will sambil
berpikir kemana lelaki itu pergi. Jika Will pergi beberapa jam yang lalu,
kemungkinan Will pergi untuk menemuinya di jembatan. Tapi, sejak tadi Will
tidak muncul di jembatan.
Will,
kau di mana?
Hayley menjadi khawatir. Takut
sesuatu terjadi pada pria itu. Tapi yang membuatnya lebih takut adalah; Will
melupakan janjinya dan pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Seolah janjinya
dengan Hayley bukan apa-apa. Hayley memang belum lama mengenal Will, ia masih
tidak tahu apa-apa tentang pria itu selain pekerjaannya sebagai penulis. Namun,
bukan berarti ia tidak percaya.
Apapun alasannya, Hayley harap semua
itu setara dengan rasa kecewa yang dialaminya sekarang.


 sabrinewrites
sabrinewrites