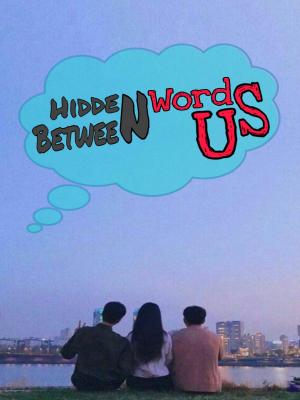Dalam diam, tanpa diketahui Lengkara atau siapapun, Aksa selalu merasa takut akan hari dimana ia tak lagi bersama Lengkara. Akan pagi kala matanya terpejam, ia harus dihadapkan dengan kenyataan jika Lengkara telah tiada. Setiap malam, Aksa selalu menangis sambil memandangi foto Lengkara disertai untaian doa yang tak lekang ia panjatkan kepada Sang Kuasa. Berharap ada satu saja kesempatan untuk Lengkara dengan kesembuhan yang juga diharapkan oleh kekasihnya itu. Namun semakin hari ia melihat kondisi Lengkara yang kian memburuk. Tubuh Lengkara semakin kurus dan seringkali merasakan sakit. Jika bisa, ia ingin bernegosiasi dengan Sang Pencipta, untuk memindahkan penyakit yang membebani Lengkara kepadanya saja.
Bersamaan dengan itu, ia mengingat kenangan bersama kakaknya—Vidya. Ia merindukan Vidya melebihi siapapun. Kakak yang sangat dekat dengannya dan tahu segalanya tentang Aksa melebihi bapak dan mama. Vidya selalu menyempatkan waktu untuk bersama Aksa ditengah kesibukannya. Hingga sebuah penyakit harus membuat Vidya meninggalkan semuanya. Entah itu hobi, pekerjaan, kebiasaan dan menjaga jarak dengan keluarganya—seperti yang dilakukan Lengkara sebelumnya. Namun hanya satu orang yang masih setia membujuk dan memaksa untuk berada di dekat Vidya, yaitu Aksa. Pemuda itu selalu mempunyai 1000 cara agar kakaknya tidak menjauhinya.
Kemudian suatu hari, di kala penyakitnya sudah mencapai stadium akhir, Aksa dengan bodohnya menuruti keinginan Vidya untuk membawanya jauh dari jangkauan bapak dan mama. Yang saat itu seharusnya Vidya menjalani operasi dan segala pengobatan yang disarankan oleh dokter. Namun Vidya keras kepala, dan memaksa Aksa untuk membawanya pergi dengan alasan ingin liburan. Aksa menurut, ia membawa Vidya ke tempat yang benar-benar memberikan ketenangan untuk Vidya. Hingga beberapa hari kemudian, Vidya menghembuskan nafas terakhirnya tanpa diketahui Aksa.
Aksa menyesal, seandainya ia tahu bahwa itu hanyalah alasan Vidya untuk menghindari pengobatan dan operasi, ia mungkin akan melakukan berbagai cara lagi agar Vidya tidak melarikan diri. Seandainya ia dapat memutar-balikan waktu, mungkin saja Vidya saat ini ada di sisinya dalam keadaan sehat.
Dan ia tak ingin itu terjadi kepada Lengkara. Aksa berupaya untuk membujuk Lengkara menjalani pengobatan sampai Lengkara mau. Meski hal itu hanya mencegah, bukan mengobati sepenuhnya, Aksa yakin bahwa keajaiban itu ada. Dirinya yakin bahwa Lengkara akan sembuh walaupun sebenarnya kesembuhan Lengkara hanya mencapai 20% saja.
Apalagi saat ia memberanikan diri untuk menanyakan kepada dokter ketika menemani Lengkara menjalani kemoterapi, dokter mengatakan bahwa—
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin, dan kita percayakan semuanya kepada Allah SWT.”
Aksa mengusap air matanya yang sedari tadi jatuh dan mengalir. Menghela nafas dalam dan menghembuskannya pelan untuk menetralisir rasa sakit yang bersemayam dalam dada selama ini. Tanpa diketahuinya, sedari tadi bapak mengintip di balik tirai. Merasa kasihan dengan anak laki-lakinya yang memang akhir-akhir ini sering melamun di balkon sambil menangis menatap dua foto gadis di tangannya. Foto Vidya dan Lengkara.
“Jangan bersedih terlalu dalam, Aksa.” Bapak bergabung dan duduk di salah satu kursi kosong.
Aksa terperanjat dan segera mengusap sisa air matanya. Ia gelagapan karena terpergok oleh bapak dan merasa malu karena menangis. “Eh bapak.”
“Akhir-akhir ini kamu sering menangis, ada apa? Kamu kangen kakakmu?” tanya bapak.
“Iya, pak.” Suara Aksa terdengar parau.
“Dan kekasihmu?”
Aksa semakin menundukkan kepalanya tak sanggup menjawab. Sebab bukan hanya rindu tetapi rasa takut juga ikut andil.
“Kamu gak mau cerita sama bapak soal Lengkara?” bapak mencoba memancing agar Aksa menceritakan penyebab anak bujangnya itu menangis.
Bukannya menjawab, Aksa malah melanjutkan tangisnya, kini diiringi isakan yang terdengar memilukan. Sementara bapak membiarkan Aksa menangis sepuasnya dan menumpahkan segala lara sampai Aksa memulai ceritanya. Bapak sekilas teringat masa lalu, dimana ia pernah melihat putranya menangis memilukan seperti ini ketika Vidya meninggal dunia.
Sedari dulu, selain pada Vidya, Aksa selalu bercerita tentang hal apapun kepada bapak. Entah itu tentang sekolah, tentang keluhan-keluhannya akan tugas yang diberikan guru, tentang latihan taekwondonya, dan masih banyak lagi. Selain menjadi orangtua yang selalu memberikan contoh dan didikan yang baik untuk Aksa, bapak juga berperan sebagai teman Aksa. Membuat Aksa nyaman berada di rumah bersama keluarganya. Namun tentang Lengkara, Aksa belum menceritakannya. Ia terlalu lemah untuk menceritakan Lengkara dan hanya bisa menangis tanpa diketahui siapapun.
“Lengkara, pak..” suaranya beradu dengan isak tangis yang masih ada, terdengar begitu serak.
Tangan keriput bapak mulai mengelus puncak kelapa anak bujangnya itu. Meski Aksa sudah berusia 22 tahun, tapi di mata bapak Aksa masih anak-anak.
“Lengkara punya kanker otak dan udah mencapai stadium akhir.”
Bapak terkejut mendengar itu, namun ia tak menampakkan kepada Aksa. Dadanya langsung terasa sakit, teringat Vidya—anak gadisnya yang meninggal dunia karena kanker.
“Aksa belum siap kehilangan Lengkara, pak. Aksa takut gak bisa tanpa Lengkara. Padahal Aksa belum sepenuhnya ikhlas untuk kepergian kakak, kenapa Allah kembali menghadapkan Aksa untuk merasakan kehilangan itu lagi?” Aksa masih menangis, seperti ada sesuatu yang memukul dadanya berulang kali sampai rasanya sakit sekali. “Aksa harus gimana, pak? Aksa bingung..”
Bapak menarik kepala Aksa untuk bersandar di pundaknya. Membiarkan kembali tangis itu tumpah sepuasnya. Bapak bisa merasakan rasa sakit yang dipendam oleh anak bujangnya ini, pun dengan ketulusan yang begitu besar dalam diri Aksa. Tangan itu kembali mengelus lengan bahu anaknya, memberikan kehangatan dan kekuatan untuk Aksa lebih kuat dan tegar menghadapi semuanya.
“Aksa, setiap manusia pasti punya waktu-waktu tertentu yang diatur oleh Allah untuk kembali padaNya. Bisa saja besok bapak atau mama yang dipanggil oleh Allah.”
Mendengar itu Aksa menengadah, melayangkan tatapan tak terima kepada bapak. Lantas bapak tertawa. ”Bapak cuman menganalogikan, Aksa, kok kamu sewot? Kanker macam apapun itu, stadiumnya sudah sampai akhir pun, kalau Allah berkehendak untuk menyembuhkan pasti sembuh, Aksa. Tinggal dari Lengkara-nya saja untuk bersemangat menjalani kesembuhan. Dan kamu sebagai orang terdekatnya setelah keluarganya, harus mendukung Lengkara. Jangan malah bersedih bahkan sampai ninggalin dia sekarang cuman karena kamu merasa gak sanggup jika suatu saat nanti kehilangan dia. Itu justru akan membuat Lengkara semakin sakit, Aksa.”
Bapak melanjutkan, “Takdir gak ada yang tahu, Aksa. Dan Allah itu Maha Besar, apa yang dianggap tidak mungkin akan menjadi mungkin jika Allah berkehendak. Percayakan saja semua padaNya, kita sebagai manusia tinggal berusaha.”
“Dan jangan terlalu larut dalam kesedihan karena kepergian kakakmu, Aksa. Bapak tahu, mungkin kamu masih merasa bersalah dengan kejadian beberapa tahun lalu. Tapi yang harus kamu tahu gak ada yang menyalahkan kamu. Bapak dan mama ikhlas dengan kepergian kakakmu. Karena bapak dan mama pun percaya bahwa kakakmu telah damai di sana, gak ngerasain sakit lagi kayak waktu masih ada sama kita. Belajarlah mengikhlaskan kakak dan memaafkan dirimu sendiri, supaya kakakmu tenang di sana, ya?”
Aksa mengangguk, memeluk bapak dan merasakan ketenangan meski tak sepenuhnya. Bersamaan dengan itu bayangan tentang Lengkara melintas di benaknya. Tentang hari-hari yang telah mereka lewati bersama dan kenangan yang dengan sukarela mereka cipta. Mungkin saat ini kondisi Lengkara makin parah, namun ajaibnya gadis itu tak pernah menunjukkan lemah di hadapan Aksa. Terkadang Aksa iba dan sesak di dadanya, akan tetapi Aksa merasa bangga memiliki kekasih seperti Lengkara. Telah berubah menjadi Lengkara yang lebih baik daripada sebelumnya.
Mungkin memang benar kata bapak, Aksa harus terus mendampingi Lengkara dan menyemangati gadis itu.
.........
Hari ini Lengkara akan menjalani operasi untuk mengangkat sel-sel jaringan di dalam otaknya walaupun tindakan ini terlambat dilakukan. Karena sebelumnya Lengkara selalu menolak menjalani pengobatan apapun untuk menyembuhkan kanker di otaknya itu. Seluruh keluarga termasuk Lengkara sendiri berharap dengan operasi ini dapat menyembuhkannya, namun apa dikata bila operasi ini hanya lah bentuk pencegahan agar kanker tidak menyebar ke mana-mana lagi. Lengkara dipaksa tabah oleh keadaan, dengan seurai senyumnya ia meyakinkan kepada ayah, bunda dan kakaknya bahwa semua akan berjalan dengan lancar dan baik-baik saja.
Sebelum operasi dilakukan, Aksa datang membawa makanan kesukaan Lengkara. Namun sayang, makanan itu tidak dapat dikonsumsi Lengkara sebab gadis itu harus menjalani puasa sebelum operasi. Aksa tak bersedih, justru ia terus menyemangati Lengkara. Keluarga Lengkara pun memberikan ruang untuk Aksa dan anak gadisnya dengan pergi meninggalkan mereka di dalam ruangan.
“Katanya pasien yang menjalani operasi ini akan sadar dalam waktu yang lama.” Lengkara menundukkan kepalanya. Yang ia takutkan justru ia tak akan bangun kembali dan melihat wajah-wajah yang ia sayangi. “Nanti kalau aku—“
“Hei?” Aksa mengangkat kepala Lengkara, kemudian mereka bersitatap. “Mau selama apapun itu, aku akan tetap nunggu kamu, sayang. Kamu harus semangat menjalani proses ini untuk diri kamu sendiri, keluarga dan aku. Kami semua akan selalu ada di samping kamu, Kar. Jangan takut, percayakan semua kepada Allah, ya?”
Air matanya menetes kala mendengar penuturan Aksa. Lantas dilapnya air mata itu oleh jemari Aksa, kemudian dikecupnya kening Lengkara dengan penuh kasih sayang. “Kamu cantik banget kalau pake kacamata. Apalagi kalau bulat,” Aksa terkekeh. Semenjak kemoterapi minggu lalu, Lengkara merasa pandangannya mengabur. Alhasil tatkala diperiksa, sepasang mata itu minus. Ini disebabkan efek dari penyakit kanker otaknya yang semakin parah.
“Kamu mah ngeledek!”
“Ih jangan marah dong, aku kan muji kamu, bukan ngeledek.” Aksa makin semena-mena untuk mencubit kedua pipi Lengkara sampai gadis itu meringis dan melayangkan pukulan.
“Tapi, Sa, kenapa kamu..” untuk sesaat Lengkara memejamkan matanya. Ternyata sulit mengungkapkan daripada memikirkannya. Berat jika dirinya harus melepaskan Aksa—pemuda yang selalu ada untuknya dan menjadi penyemangatnya. Namun Lengkara tak ingin Aksa nanti melahap rasa sakit lebih dalam karena kehilangannya. Ia ingin Aksa bahagia dan menemukan tambatan hati untuk menggantikan posisinya. Setidaknya Lengkara akan pergi dengan damai jika mengetahui ada yang mencintai Aksa dengan tulus.
“Kenapa, Kara?” suara lembut itu makin membuat Lengkara tak rela. Haruskah ia melepaskan Aksa ketika pemuda itu membuatnya jatuh dalam rasa yang begitu indah?
“Kondisi aku makin memburuk, kenapa kamu.. kenapa kamu gak nyari yang—“
“Aku tahu apa yang mau kamu katakan.” Sela Aksa. Raut pemuda itu cepat berubah kala mengerti maksud perkataan Lengkara ke mana. “Aku gak suka kamu bilang gitu, Kar. Mencintai dan bertahan sama kamu sampai saat ini adalah keputusan dan keinginan aku sendiri. Gak ada maksud lain yang terselubung. Jadi untuk sekarang kamu fokus menjalani pengobatan, jangan pikirin yang lain. Oke?”
Beberapa detik kemudian orangtua Lengkara masuk bersama dokter dan beberapa perawat untuk membawa Lengkara ke ruang operasi. Dengan senyumnya, Lengkara perlahan meninggalkan ruangan dengan membawa doa dan harapan dari orang-orang terkasih. Tanpa diketahui Lengkara, Aksa menangis. Layaknya sebuah perpisahan, Aksa merasa tak rela dengan hal ini. Namun ia tak bisa bertindak seenaknya, jadi Aksa segera pergi ke mushola untuk memohon doa agar seluruh rangkaian operasi dilancarkan.
2 minggu berlalu setelah operasi dilakukan Lengkara belum juga sadar. Gadis itu terkapar lemas di atas ranjang dengan berbagai alat medis yang menempel di tubuhnya. Setiap hari Aksa berkunjung ke sana dengan membawa makanan kesukaan Lengkara. Berharap gadis itu cepat sadar dan memakan semuanya sepuasnya. Kala ia menatap wajah Lengkara yang begitu tenang, Aksa kembali menitikkan air mata. Seandainya ia ada di posisi Lengkara pasti akan sulit untuknya. Menjalani hari-hari tanpa impian kembali, dihadapkan dengan berbagai rasa takut yang hinggap sebab penyakit itu, dan pengobatan serta kemoterapi yang cukup menguras tenaga.
Sebenarnya Aksa telah bersikap lancang. Meski hanya mengintip melalui pintu, saat keluarga Lengkara berdiskusi dengan dokter di dalam ruangan. Aksa dapat melihat dengan jelas keputusasaan di wajah-wajah mereka ketika dokter menjelaskan dan memberikan hasil radiografi pada otak Lengkara. Nampaknya tak ada harapan lagi untuk gadis itu sembuh. Kini Aksa hanya berharap bisa lebih lama dengan Lengkara meski itu mustahil terjadi.
Kemudian digenggamnya tangan Lengkara yang kini terlihat kurus. Aksa terenyuh dan merasa sesak melihat kondisi tubuh gadis itu akhir-akhir ini. Akan tetapi Aksa tak pernah berkomentar, justru pemuda itu selalu mengatakan bahwa Lengkara begitu cantik setiap harinya. Seperti hari ini meski dengan mata yang terpejam. Ingin rasanya Aksa melihat wajah itu disertai senyum manisnya. Ingin rasanya Aksa kembali mendekap tubuh Lengkara yang begitu hangat. Ingin rasanya Aksa mendengar ocehan Lengkara. Aksa begitu merindukannya.
”Kapan kamu bangun, Kar? Aku kangen.” Diusapnya pipi sang kekasih penuh rindu. “Nanti kalau kamu bangun, janji ya habisin semua makanan ini? Ada coklat, kue, astor, sosis kemasan, dan kayaknya kalau kamu gak bangun-bangun aku takut nanti ruangan ini jadi supermarket.” Aksa terkekeh sendiri membayangkan itu meski disertai dengan air mata yang mengalir. “Kamu tahu gak, Kar? Kemarin aku dapat kabar dari pelatih kalau aku bakal turun kejuaraan taekwondo. Udah lama banget rasanya gak tanding dan kayaknya akan seru deh. Apalagi nanti ada kamu yang nonton untuk dukung aku. Mau ya hadir? Aku ngarep banget tahu!”
Untuk sesaat Aksa mengusap air matanya yang tersisa di pipi. “Kamu hebat, Kar, kamu bisa bertahan sampai titik ini. Aku bangga dan bersyukur punya pacar kayak kamu. Aku janji akan mewujudkan mimpi-mimpi kamu yang kamu tulis dalam buku. Maaf kalau aku lancang moto bagian itu. Cepet sadar, ya? Supaya kita bisa kembali wujudkan mimpi-mimpi yang belum kita lakukan.” Terakhir sebelum Aksa ke luar ruangan bergantian dengan Kinara untuk menjaga Lengkara, Aksa mengecup kening gadis itu.
“Aku sayang kamu, Kar.”
........
Fera berlari dengan perasaan khawatir yang begitu menggebu dalam dadanya. Dari kampus sampai ke rumah sakit, Fera menjalankan mobilnya dengan kecepatan penuh. Ia pun berlari setelah mengetahui di mana letak ruangan yang Lengkara tempati. Gemetar, resah, takut dan rasa tidak percaya menjadi satu kesatuan yang utuh dalam dadanya. Membuat Fera tak karuan dan segera ingin sampai untuk melihat langsung sahabatnya itu. Setelah mendengar kabar jika Lengkara mengidap kanker otak dari orang-orang yang mulai membicarakannya di kampus, Fera langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikan. Menghubungi terlebih dahulu Aksa, Fera akhirnya tahu di mana Lengkara dirawat.
“Aksa..”
Aksa mengangkat kepalanya, mendapati Fera yang mulai mendekatinya. Sudah sejak 20 menit yang lalu Aksa duduk di kursi tunggu di luar ruangan ICU yang Lengkara tempati.
Masih dengan nafas memburu, ia langsung menanyakan kepada Aksa. “Sa, bener kalau..”
Aksa mengangguk, saat Fera hendak membuka pintu, Aksa mencegah. “Duduk dulu, ada banyak yang mau gue ceritain ke lo.” Ujarnya.
“Soal apa, Sa?”
“Soal Lengkara.”
Fera memilih diam dan mendengarkan apa yang akan dikatakan Aksa.
“Sebenernya masalah ini antara lo dan Kara, bukan gue. Tapi mewakili Lengkara yang sampai saat ini belum sadar juga, gue pengen lo tahu semua hal yang gak pernah Lengkara sampaikan setelah membuat lo benci sama dia.”
Fera mengerutkan keningnya, merasa tak paham dengan apa yang disampaikan oleh Aksa. Namun ia memilih diam dan membiarkan Aksa sampai selesai berbicara.
“Alasan Lengkara dulu bersikap buruk, karena dia gak mau melihat orang-orang yang dia sayang sedih karena penyakitnya. Lengkara cuman gak mau bikin lo dan keluarganya merasakan kehilangan kalau dia nantinya udah gak ada lagi di dunia. Itu sebabnya dia berupaya menjauhi dan membuat lo dan keluarganya benci ke dia walaupun dengan cara yang salah. Semua beban dan rasa sakit itu Lengkara makan sendirian, dia gak mau membebani orang-orang yang dia sayang. Mungkin gue baru beberapa bulan ini mengenal Lengkara, tapi sebelum gue bener-bener melihat Lengkara seperti sekarang, dia selalu terlihat sedih dan nangis sendirian di tempat sepi. Pandangannya selalu menyiratkan duka yang bahkan membuat gue sakit hati saat lihat wajah itu.”
Kini Fera mengerti kenapa dulu Lengkara bersikap seenaknya dan menghinanya tanpa sebab. Menjauhinya dan tak pernah lagi mau bersamanya. Awalnya Fera berusaha memperbaiki keadaan, namun Lengkara terus menjauh dan akhirnya Fera balik membencinya dan tak ingin bertemu lagi dengan Lengkara. Akan tetapi, ternyata dibalik semua ini ada rasa sakit yang berusaha Lengkara sembunyikan. Ada duka yang diam-diam Lengkara tutupi seorang diri. Dalam hati Fera merasa bodoh dan gagal menjadi sahabat terbaik Lengkara. Dia tak peka dengan apa yang Lengkara rasakan. Jika ia tahu, pasti ia tak akan bersikap demikian kepada Lengkara dan malah makin menyakiti sahabatnya itu.
Aksa melanjutkan, “Kara selalu nyerita ke gue kalau dia kangen bareng sama lo ke mana pun dan ngelakuin apapun. Dia selalu pengen bicara sama lo, tapi lo selalu menghindar. Dia ngerasa sedih dan bersalah karena udah ngelakuin hal yang salah ke lo terutama keluarganya. Dia selalu bilang, seharusnya dia gak pernah ngelakuin hal bodoh itu.” Aksa menoleh pada Fera yang ternyata sedari tadi telah menjatuhkan air matanya. “Ini permintaan dari gue buat Lengkara, maafin dia dan sahabatan lagi sama dia, Fer. Lengkara udah terlalu lemah, jangan bikin makin terbebani.”
Bukannya menjawab, Fera malah makin tenggelam dalam tangisnya. Tak percaya bahwa sahabat yang dulu selalu ada untuknya, selalu bersamanya dan merangkai mimpi yang sama, kini tengah berjuang melawan kematian yang telah berada di depan mata. Ia tak menyangka bahwa kematian lah sesungguhnya yang akan memisahkan mereka.
..........
“Deretan artis yang berhasil sembuh dari kanker stadium akhir.” Sagara sengaja membaca artikel itu keras supaya Aksa yang tengah berada di samping kasur tempat Lengkara berbaring mendengar. Niatnya hanya ingin menghapus kekhawatiran Aksa yang membuat temannya itu tidak semangat melakukan apapun. “Pertama.. eh main ambil aja! Gue lagi baca!”
“Ngapain sih lo baca artikel gitu di saat kondisinya lagi gini? Kasihan Aksa!” tegur Agam. Mereka berempat menemani Aksa untuk menunggu Lengkara dengan membawa makan siang untuk Aksa. Ruangan yang sebelumnya sepi kini diramaikan oleh mereka. Aksa tak ingin ambil pusing. Justru kehadiran mereka sedikit menghalau kesedihannya karena Lengkara tak juga bangun. Bahkan keluarga Lengkara mempersilahkan dan memberikan ruang untuk mereka menemani Lengkara.
“Gue kan cuman mau ngasih motivasi ke Aksa, kalau Lengkara bisa sembuh.” Belanya pada diri sendiri.
“Tapi gak sekarang juga!”
“Tapi kata Sagara bener juga, siapa tahu Lengkara bisa sembuh?” ujar Novan. Sagara mendelik pada Agam ketika Novan secara tak langsung mendukungnya.
Galen menggeleng tak paham dengan tingkah laku teman-temannya. Seharusnya mereka di sini menghibur Aksa, bukan malah bertingkah seperti itu. Lantas Galen menghampiri Aksa yang sedari tadi hanya diam sembari memandang wajah Lengkara yang tengah tertidur lelap. Ditepuknya punggung Aksa dengan pelan berulang kali, mencoba menguatkan pemuda yang kini terlihat sedih karena penantiannya tak juga membuahkan hasil.
“Sa, makan dulu, keburu dingin.” Ucapnya.
“Gue gak laper, Len.”
Galen duduk di ujung kasur. “Nanti lo sakit, Sa.”
Aksa tak menjawab lagi, pemuda itu memilih diam dan menyandarkan kepalanya di samping tangan Lengkara. Dalam hati ia tak berhenti berdoa, berharap hari ini Lengkara sadar setelah lebih dari 2 minggu gadis itu masih asik terlelap. Sementara Galen tak bisa berbuat apapun selain diam dan mencoba memahami Aksa. Apa yang Aksa alami dan rasakan tentu berat untuknya. Ini kali pertama ia melihat Aksa seterpuruk ini dan begitu dalam mencintai Lengkara. Ia yakin cinta yang dimiliki Aksa sangat tulus untuk Lengkara—gadis yang beruntung dimiliki Aksa.
Hal yang mengejutkan pun membuat Aksa dan Galen terkesiap kala jemari Lengkara bergerak-gerak. Selayaknya mendapatkan hadiah undian yang begitu besar, Aksa sampai menangis haru dan segera memijit tombol darurat untuk memanggil dokter. Novan, Sagara, dan Agam berlari mendekati kasur dan merasakan syukur yang sama. Akhirnya setelah penantian yang cukup berat, Lengkara bisa tersadar dari tidurnya yang lumayan panjang.
“Sayang.. akhirnya kamu bangun.” Aksa tak bisa lagi mendefinisikan kebahagiaan yang terpatri dalam hatinya. Ia tak henti mengucap syukur karena Allah telah mengabulkan doanya.
Lengkara perlahan membuka matanya. Apa yang dilihatnya pertama adalah beberapa lelaki yang berada di tiap sisi kasurnya meski terlihat kabur. Ia merasakan kepalanya begitu pening, apalagi di bagian bekas operasi. Kemudian tak lama dokter dan beberapa suster datang, membuat para lelaki beringsut mundur dan membiarkan dokter yang menanganinya. Aksa yang begitu bahagia lantas menghubungi ayah Lengkara, mengabarkan jika Lengkara telah sadar.
Mereka keluar ruangan untuk membiarkan dokter menyelesaikan tugasnya.
“Nah gini dong, kan enak lihatnya senyumnya lebar, selebar samudra.” Canda Sagara. Kini Aksa menanggapinya dengan senyum yang menampilkan geligi putihnya.
“Hai Lengkara! Aku Saga! Selamat datang kembali di dunia Aksa! Al—emmh!” ucap Saga yang langsung dibekap oleh tangan Agam, kemudian pemuda itu menarik Sagara diikuti Galen dan Novan.
“Jangan banyak tingkah, biarin Aksa sama Lengkara ngobrol dulu. Lo, ikut gue!” kata Agam.
“Kita pergi dulu ya? Kalau kalian butuh kita, hubungi aja.” Ucap Novan yang diangguki Aksa. Sementara Lengkara mengutas senyum tipisnya. Kini hanya ada Aksa dan Lengkara dalam ruangan itu. Sedari tadi setelah memeriksa keadaan Lengkara, dokter dan suster telah pergi keluar ruangan.
“Berapa lama aku koma?” tanya Lengkara dengan suara yang masih terdengar lemah.
“2 minggu lebih.” Jawab Aksa. Mendengar itu Lengkara terbelalak, namun segera Aksa berkata, “Gimana udah agak mendingan?”
“Belum kayaknya, aku masih ngerasa sakit kepala banget, apalagi di bagian sini.” Tunjuk Lengkara pada bagian kepalanya yang diperban. “Terus kata dokter aku harus dirawat dulu beberapa hari.”
“Gapapa, nanti juga gak kerasa lagi.”
Lengkara mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, ia menemukan tumpukan makanan di sofa, “Itu dari siapa?”
“Aku, buat kamu.”
“Sebanyak itu?!”
Aksa terkekeh, “Aku tiap hari selalu bawa makanan, tadinya mau dibawa bunda kamu ke rumah, tapi kata aku siapa tahu Lengkara cepet sadar dan makan semuanya sampai habis. 2 minggu lebih pasti laper banget kan?”
Selayaknya magnet, kata-kata Aksa memancing air matanya untuk keluar. Haru terasa dalam dada, syukur terpanjat dalam hati. Ia tak mengira bahwa Aksa akan sebaik ini dan masih membersamainya meski dirinya menyusahkan Aksa. Lengkara tidak tahu bagaimana keadaannya jika tidak ada Aksa. Pemuda itulah yang membuatnya sadar, pemuda itulah yang membuatnya berdamai dengan keluarga dan dirinya sendiri. Ia merasa beruntung bertemu dengan lelaki seperti Aksa.
“Kok nangis sih? Perkataan aku nyakitin kamu? Atau kamu gak suka semua makanan yang aku bawa?” tanya Aksa, cemas.
“Makasih banyak, Sa, makasih. Aku suka banget.” Hanya itu yang keluar dari mulut Lengkara dilanjutkan dengan tangis penuh haru bercampur sesak dalam dada. Dengan sigap Aksa berdiri dan memeluk Lengkara yang tengah berbaring. Mengelus rambut gadis itu dengan penuh kasih sayang.
“Kamu gak perlu berterima kasih, sudah jadi tugas aku untuk bikin kamu bahagia, Kar.”


 sastradanpena#
sastradanpena#