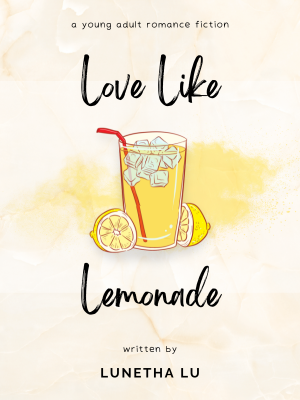Abi mempercepat langkah setelah tiba di UGD rumah sakit dekat bengkel. Ia segera mencari Aco, senior sekaligus mentor putranya yang tadi menghubungi untuk kemari. Raut lelaki paruh baya itu memucat. Keringatnya juga panas-dingin. Ia bahkan lupa cara mengatur napas saat sosok yang dicari masih sendirian, duduk berjongkok di dekat pintu.
"Di mana?" tanya Abi tanpa basa-basi. Dahinya makin berkerut ketika melihat lengan baju Aco dipenuhi bekas darah.
"Om."
Aco segera berdiri. Ia membungkuk kecil, lalu mencium tangan Abi sebagai bentuk sopan santun. Seketika lidahnya kelu dan bingung mau berkata apa, padahal ia tadi sudah menyiapkan mental setelah Abi sempat mengamuk di telepon. Berbagai kosa kata di kepalanya seakan bersembunyi sampai-sampai ia gagap menjawab. Hanya 'ah, eh, anu,' yang keluar dari mulutnya.
"Bang, lo dicari--Papa? Kok bisa di sini?"
Dua lelaki dewasa pun serempak menoleh. Abi sontak terbelalak dengan mulut yang masih menganga ketika Geboy keluar ruangan dengan santai. Ia lekas mengecek tubuh putranya itu, menyentuhnya dari ujung kepala sampai kaki. Selain perban di pelipis kanan dan bekas infus di pergelangan kiri, sepertinya enggak ada hal yang perlu dikhawatirkan.
"Kamu nggak apa-apa?"
Geboy menelan ludah. Baru kali ini ia melihat papanya ngos-ngosan seperti itu. Matanya juga merah dan berair, bahkan kedua tangan yang memegangi pundak terasa bergetar. Ia segera mengangguk, lalu menyerahkan resep obat yang diberikan dokter untuk ditebus ke apotek.
"Dijahit dikit," terang Geboy kurang jelas.
Abi mengembuskan napas panjang. Ia lantas berjalan ke arah Aco dan berterima kasih. Setelah itu, ia menyuruhnya untuk pulang lebih dulu. Masalah motor Geboy yang masih di bengkel, biar Kang Mus yang mengurusnya. Enggak lupa Abi meminta maaf karena sudah merepotkan.
"Kamu tunggu di mobil."
Geboy berkedip konstan saat menerima kunci mobil papanya. Ia pun menurut tanpa bertanya dan segera menuju parkiran, sedangkan Aco langsung pamit mencari angkot buat irit ongkos.
Usai menemukan mobil papanya dan duduk dengan nyaman di kursi belakang, Geboy mulai memejamkan mata. Ia ingin mencari tahu apa yang terjadi. Memori siang tadi masih berupa kepingan puzzle baginya. Hal yang ia ingat, ia tiba-tiba merasa pusing ketika berdiri sampai akhirnya oleng dan membentur motor, entah di bagian mana. Lalu saat sadar, ia sudah dikelilingi bau obat-obatan dan petugas medis.
"Boy?"
Sang pemilik nama itu refleks membuka mata saat papanya memanggil. "Iya, Pa."
Abi sudah berada di dalam, tapi belum menyalakan mesin. "Pusing?"
"Aku nggak apa-apa."
"Apa kata dokter?"
"Darah rendah."
"Terus lukanya?"
"Nggak ada kemungkinan gegar otak, tapi kalau ada keluhan bisa langsung periksa."
Sontak Abi mendengkus. Tanpa ada pertanyaan lagi, ia mulai menjalankan mobilnya. Geboy bisa melihat melalui kaca bahwa papanya itu seperti tengah menyesali sesuatu. Memang apa yang ia harapkan? Suatu hal parah terjadi padanya, begitu? Kini ia yang menghela napas.
"Berhenti aja di halte. Aku bisa pulang sendiri. Papa perlu buru-buru ke kantor, kan? Maaf udah bikin khawatir."
"Kalau emang kamu merasa bersalah, seharusnya dari awal hati-hati, Boy. Kamu tahu betapa paniknya Papa tadi? Ternyata kamu nggak kenapa-kenapa."
Papa pasti sedang merugi, batin Geboy pahit. Ia memalingkan muka ke jendela mobil, memandangi gedung berjalan yang mulai tertutupi langit sore. Matanya makin berkaca-kaca saat mendengar, "Kamu terlalu lemah. Papa jadi pesimis lagi."
Permintaan untuk diturunkan di halte sengaja diabaikan. Abi terus melaju sampai berhenti di lampu merah. Geboy yang membenci keheningan ini sontak menekan tombol yang mengunci pintu belakang lalu keluar tanpa pamit.
"Boy!"
Abi berteriak berulang kali. Ia hendak menyusul dan menyeret anak itu kembali, tapi lampu keburu hijau dan ia terus-menerus diklakson untuk segera jalan. Saat berhasil putar balik ke tempat semula, sosok yang dicari sudah lenyap. Ia pun memutuskan kembali ke kantor, seperti yang putranya sebutkan. Melihat keadaannya yang baik-baik saja--sampai bisa pundung dan kabur begitu--ia enggak perlu ketar-ketir.
Sementara itu, Geboy yang berlari kecil lalu ganti berjalan cepat kini duduk di Indomaret Point. Untunglah ponselnya masih ada di kantong celana, entah Aco yang memasukkan atau dari awal sudah ada di situ--lupa. Ia segera menghubungi Komal untuk menjemputnya.
Hanya butuh sepuluh menit, lelaki yang memakai celana kuning pendek itu tergopoh-gopoh menerobos hujan dan mendekati Geboy. Alisnya spontan terangkat saat ngeuh ada yang berbeda di kepala sahabatnya itu.
"Anjir, ditambal lagi lo?"
Sungguh pertanyaan yang sangat perhatian.
"Entar aja cerita di rumah. Ayo balik."
"Masih hujan ini."
Geboy mengangkat jas hujan plastik yang baru saja ia beli. "Gampang."
"Tapi luka lo--"
"Aman. Udah, ayo. Gue pusing pengen rebahan."
"I-iya, deh."
Komal segera menyalakan vespanya lalu menerjang hujan kesekian kali. Jalan pintas yang enggak begitu macet cukup menyelamatkan mereka, jadi enggak basah kuyup amat. Setelah sampai di rumah Komal, dua lelaki itu segera masuk kamar dan mengeringkan tubuh menggunakan handuk. Ini bukan kali pertama Geboy ke sini, jadi ibu Komal pun sudah terbiasa saat anaknya menyelonong masuk. Ia cuma geleng-geleng saat mendapati jejak kaki dan tetesan air di sepanjang ruang tamu.
"Ibu bikinin teh hangat. Cepat diminum biar enggak masuk angin," ucap wanita itu usai mengetuk pintu lalu menaruh nampan di atas nakas.
"Makasih, Tante." Geboy tersenyum manis.
"Kamu udah makan, Boy? Mau dibawakan ke sini aja?"
"Nggak usah, Tante. Aku nggak mau ngerepotin."
"Ya udah, entar kalau lapar cari sendiri di dapur, ya. Komal juga."
"Iya, Bu."
Geboy membungkuk kecil lalu mengunci kamar setelah ibu Komal hilang dari pandangan. Ia lalu selonjoran di bawah dan bersandar pada kasur. Tapi, tiba-tiba Komal dengan enteng menarik kerahnya, membawa agar duduk di atas.
"Biasa aja dong, Mal. Lo pikir gue anak kucing?"
"Lagian udah tau dingin malah di situ."
"Gue kepanasan, kok."
Komal mengerutkan kening. Ia refleks mengecek suhu Geboy dengan menyentuh lengannya. Seketika raut muka lelaki berubah datar dan ia pun melirik sinis.
"Panas pala lo! Dingin begini."
"Kepala gue emang panas."
"Gue nggak bakal nanya kalau lo nggak cerita sendiri. Jadi, mending sekarang tiduran aja. Gue ambil makan dulu."
Belum sampai melangkah, Geboy menahan tangan Komal dan mencengkeramnya. Mencoba peka, lelaki itu berhenti dan berbalik. Ia lalu berjongkok dan menatap sang sahabat dari bawah lekat-lekat.
Geboy enggak menangis. Ekspresinya kosong, seperti dikuras habis dan cuma tersisa energi untuk hidup. Komal menepuk kaki Geboy berkali-kali agar ia bisa sadar dan berusaha kembali waras. Meski mengaku enggak mau berurusan tanpa dilibatkan, Komal tetap ingin tahu.
"Mal," ucap Geboy setelah hening beberapa saat.
"Iya."
"Gue jadi anak kurang apa, ya?"
Komal menelan ludah. "Kenapa lo tiba-tiba nanya gitu?"
Geboy bergeming. Ia ingin menjelaskan, tapi malas mengutarakan. Kawannya itu tahu sesuatu, tapi memancingnya berkata lebih dulu. Ia mau meluapkan emosi yang beradu dengan pening di kepala, tapi tenaganya masih di bawah rata-rata. Alhasil, lelaki itu tiba-tiba terpejam dan hampir tersungkur kalau saja Komal enggak menahan di depan.
"Gue tahu lo capek."
Komal segera membantu Geboy berbaring di kasur dan menyelimutinya hingga batas dada. Ia kemudian mengambil ponsel dan mengirim pesan pada Tyas, mama Geboy, bahwa anak mereka itu akan menginap di sini dan enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah mendapat balasan berupa 'iya' dan 'terima kasih', ia bisa bernapas lega dan ikut beristirahat.
Kalaupun nanti terjadi sesuatu, Geboy merasa lebih aman dan nyaman di sini dibanding di rumah.
***


 hwarien
hwarien