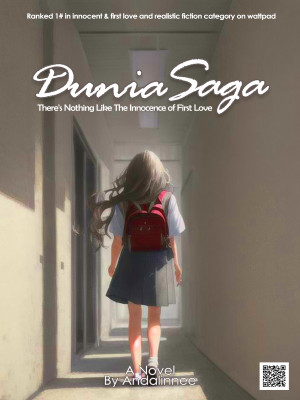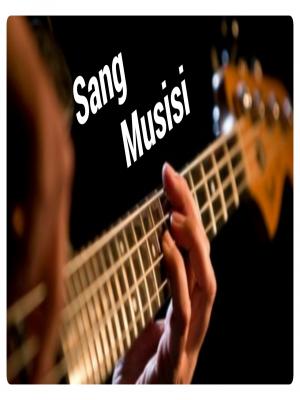Kalian pasti pernah merasakan yang namanya cinta pertama, bukan?
Bagiku, sensasi cinta pertama adalah perasaan yang sangat amat sulit dilupakan. Tentang hati kita yang pertama kalinya begitu mendambakan sosok seseorang yang tidak pernah dipikirkan oleh kita.
Ketika hati dan pikiran melangkah sejalan ingin bersamanya dalam sebuh ikatan yang anak milenial sebut pacaran.
Intinya, cinta pertama tidak akan bisa dilup akan seumur hidup bagi setiap individu.
Bahkan ada beberapa orang yang masih mencintai sosok cinta pertamanya dalam jangka waktu tahunan meski statusnya belum jelas. Memendam perasaan menyakitkan yang terhalang oleh pertanyaan, ‘apa dia juga suka aku?’
Jangan jauh-jauh mengambil contoh dari banyak novel yang menceritakan tentang kisah cinta pertama tak kesampaian. Sementara aku sendiri sudah merasakannya.
Mari kita mulai membahas sosok dirinya, si cinta pertamaku.
Namanya Adrian Herdiansyah. Lelaki kelahiran 22 agustus, seumuran denganku. Kami teman sekelas sejak tahun terakhir menggunakan seragam putih biru. Yang paling menonjol pada dirinya adalah otak cemerlangnya, yang membuat dia sering dipanggil kepala sekolah saat upacara hari senin setelah dia memenangkan perlombaan bidang akademik. Ketenarannya menjadikan dia punya banyak teman, tapi jarang punya teman perempuan.
Bicara tentang fisiknya, postur tubuhnya cukup tinggi seperti ukuran remaja lelaki kebanyakan, punya rambut hitam sedikit ikal, nampak terlihat manis dengan kulit putihnya, tatapan iris hitamnya selalu tajam ketika memperhatikan orang, dan jangan lupakan juga kedua lesung pipi ketika dia tersenyum. Tahu Nicolas Saputra? Nah, mirip-mirip sedikit lha.
Pintar dan tampan, well itu adalah tipe relative itu membuat perempuan jatuh cinta.
Tapi aku punya alasan lain mengapa aku bisa jatuh cinta padanya. Bukan, ini bukan musuh jadi cinta, bukan juga tabrakan di koridor dulu kemudian jadi dekat.
Ini lebih sederhana dari yang dibayangkan. Berawal dari, ajakan dia pulang bersama sejak awal satu kelas.
“Rumah kamu ke arah sana? Sama dong kayak aku, pulang bareng yuk?”
Saat itu umurku masih 15 tahun, aku pikir terlalu dini untuk merasakan cinta kepada lawan jelas.
Semuanya karena keterbiasan bersama, sekitar 30 menit duduk di sepeda yang sama setiap senin sampai jumat, membuat kami sama-sama nyaman dengan obrolan masing-masing, apa pun itu.
Karena itu pula, aku jadi tahu banyak hal spesifik mengenai Adrian. Bahkan hal kecil seperti; dia penyuka makanan pedas, suku asli jawa, punya phobia ketinggian, anak tunggal, dan masih banyak lagi.
Begitu juga, dia tahu banyak mengenai diriku.
Yang paling aku suka selama 30 menit bersama itu, saat dia berbicara mengenai dirinya. Sejak cukup lama bersama, entah mengapa aku sangat ingin tahu semuanya mengenai dia. Semua tentang dia, adalah yang paling aku suka.
Status kami yang hanya teman, membuat otakku berpikir lama kalau aku menyukai dia. Menjadikan di sosok cinta pertamaku.
Dan karena status kami pula yang membuat aku tak berani berkata tentang perasaanku untuk dia. Masih terekam jelas dalam kepala, saat kelulusan sekolah, aku sudah menyiapkan semalaman lebih kalimat pengungkapan cinta kepadanya. Namun ketika hari H,
“Selamat ya, kamu dapat nilai tertinggi dan masuk SMA favorite yang kamu mau. Sebagai teman, aku bangga. Semoga kamu sukses selalu.”
Hanya Sederet kalimat itu yang mampu aku ucapkan.
Setelah kami berbeda sekolah, dia masih suka menghubungiku atau barangkali mengajak jalan-jalan. Tapi dalam intensitas jarang.
Begitu juga dalam bertukar kabar.
Ketika kamu menjadikan dia rutinitas dalam kepalamu. Dia malah menjadikan kamu tempat singgahan. Itu yang aku rasakan saat masih menyimpan perasaan untuknya.
Perasaan teramat dalam hingga aku selalu menceritakan sosoknya pada siapa pun, terutama teman dekat.
“Ra, lo ‘kan punya pacar, tapi kenapa bareng sama gue mulu? Yang lain aja pulang di antar pacarnya terus.”
Saat masih kelas 11, aku punya teman sebangku yang kupanggil Indy, dia adalah salah satu orang yang tahu tentang Adrian.
“Pacar aja nggak punya,” balasku tanpa minat. Percaya deh, hal yang paling malas dibahas jomblo adalah masalah tentang pacaran.
“Cowok yang sering lo ceritain dulu tuh, yang lo bilang dekat sama lo, Adrian ‘kan namanya? Dia bukan pacar lo?”
“Cuma teman.” Sungguh, saat masih menyimpan perasaan padanya, aku sering merasa tertohok sendiri menyebut status kami.
“Biasanya dari teman jadi demen, sabar aja,” Indy menepuk punggungku cukup keras, sehingga aku yang sedang minum es teh manis langsung terbatuk pelan, “terus sekarang gimana hubungan lo sama Adrian? Berjalan semulus kulit bayi nggak?”
“Semakin hari, semakin jarang kontakan. Semakin gue sadar, kalau kayaknya cuma gue aja yang sayang sama dia. Sementara dia anggap gue teman biasa atau bahan singgahan? Sebab gue gampang terima dia setelah dia hilang lama dan entah ke mana.”
“Kayak tarik ulur gitu ya?”
“Iya!” Ku habiskan minuman dalam sekali teguk, lalu menaruh gelas di meja makan dengan cukup keras. “Mending ganteng, jelek aja sok mainin perasaan cewek. Kesal sendiri gue jadinya.”
“Jadi dia jelek?’
“Ya… nggak jelek juga, sih. Biasa aja gitu.”
“Jadi penasaran gue. Lihat fotonya, dong.”
“Oke.”
Seumur-umur, meski dulu sering bersama, aku hanya punya 1 foto bersama Adrian. Itu pun dipaksa Andre ketika kelulusan sekolah. Aku ingat jelas, aku dan dia memakai batik biru saat foto bersama pertama dan terakhir kalinya.
“Ini cakep juga euy. Gini nih cewek jaman sekarang, kalau ngambek sama doi suka ngejelek-jelekin.”
“Udah jelek kali.”
“By the way, Adrian mirip sama cowok yang di gerbang sekolah kita ya?”
Aku dan Indy yang sedang makan di warung bakso dekat sekolah pun, menoleh ke arah yang diberitahu Indy.
Aku segera memakai kacamata yang tersimpan di seragam, memang ada Adrian yang sedang mengendarai motor lengkap dengan pakaian sekolahnya, mataku langsung terbelalak kaget. Dan spontan berkata, “itu… Adrian.”
“Eh gila, aslinya lebih ganteng.”
“Iya ganteng banget,” balasku, spontan juga.
“Belum ada satu jam lo bilang Adrian jelek. Cewek labil.”
“Khilaf,” jawabku asal, “udah ah gue ke Adrian dulu.”
“Ngapain lo bawa tas juga?”
“Mau pulang sama Adrian lha.” Percaya diriku memang tinggi, meski saat itu aku belum tahu kenapa Adrian datang setelah lama kami tidak bertemu. “Duluan, Ndy. Assalamu’alaikum.”
“Wa’alalaikum salam.”
Aku berlari kecil ke arah Adrian. Saat jarak kami mulai dekat, aku menyapanya, seolah lupa jika beberapa hari belakang aku berpikiran jelek tentang dia yang selalu menghilang.
“Adrian.”
Dia menoleh, dan tersenyum memamerkan kedua lesung pipinya. Manis sekali, “Cyra,” dia memanggil namaku, dengan suara bass yang sangat nyaman didengar, “untung kamu belum pulang. Baru aku mau balik waktu satpam bilang kelas 11 udah pulang semua.”
“Kamu ada perlu sama aku?”
“Kalau nggak ada perlu, aku nggak mungkin ke sini, Ra.”
“He he.”
“Aku mau ajak kamu jalan, sekalian ada yang mau aku omongin, bisa?”
“Duh gimana ya.” Jual mahal bagi seorang perempuan adalah hal wajar, supaya tidak dianggap hatinya mudah diambil…
“Kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa kok.”
…tapi sayangnya, aku selalu gagal bersikap sok jual mahal di depan Adrian. “Bisa kok, aku baru ingat hari ini nggak ada tugas dan nggak ada kumpul sama teman.”
“Oke.” Adrian memakaikan aku helm hitam yang lebih kecil dari helm yang dia pakai. “Ayo naik, Ra.”
Segera aku duduk di jok belakang motor bebeknya.
“Pegangan ya.”
Jangankan hanya pegangan, aku malah ingin peluk dia dari belakang ala-ala sinetron yang sering dilihat nenekku. Tapi karena terhalang tas besarnya, mana bisa?!
“Kenapa diam aja?”
“Tas kamu gede banget. Gimana aku mau pegangan?”
“Sebentar ya.” Adrian memindahkan tasnya ke depan.
Aku pikir, dengan begitu aku jadi bisa memeluk Adrian.
Duk!
“Eh?! Maaf ya.”
Namun tetap tidak bisa karena helm yang kami pakai waktu itu membentur ketika aku ingin memeluk Adrian. Terpaksa aku harus puas hanya memegang pundak Adrian saja.
“Kita mau ke mana?” tanyaku, saat dia menjalankan motornya.
“Kedai yang ada di ujung jalan dekat sini. Mau beli es krim yang banyak.”
“Kamu ‘kan nggak suka es krim.”
“Tapi kamu suka.”
Nah ini yang buat aku mudah bawa perasaan. Sifatnya yang perhatian. “A-ah. Makasih.”
Aku mengulum senyum seraya menunduk, menyembunyikan wajah yang bersemu merah. Sebenarnya sih, dulu es krim bukan hal yang paling aku suka lagi kalau ada dia disampingku.
Karena hal yang paling aku suka melebihi es krim itu… adalah dia.
Duk!
Dua kali aku terbentur helm. Yang kedua kalinya adalah ketika Adrian menghentikan motornya. Dalam hati, aku bertekad tidak mau menggunakan helmnya lagi.
“Udah sampai nih, Ra.”
Aku lebih dulu turun dari motor, lalu menunggu Adrian selesai memarkirkan motornya sebelum ikut lelaki itu duduk dibangku dekat kasir.
“Es krim vanilla ukuran besar satu ya,” ucap Adrian pada pelayan.
“Kenapa satu aja?” tanyaku.
“Aku nggak suka manis. Jadi buat kamu aja.”
“Makasih.” Tuh ‘kan dibikin baper lagi! “Oh iya, kamu mau ngomong apa?”
Demi apa pun, ketika mengajukan pertanyaan itu jantung berdebar cepat karena melambungkan ekspetasi tentang jawabannya.
“Cuma mau kasih undangan reuni SMP buat kamu, Andre, Putri, sama Sarah. Tadi aku udah chat mereka buat datang ke sini, tapi pada nggak bisa makanya aku ke sekolah kamu, sekalian kasih surat undangan mereka.”
Ternyata ekspetasiku malah menjatuhkanku sendiri, terpukul oleh realita yang lebih tajam.
“Aku baru ingat, besok ulangan komputer akuntansi. Aku pulang dulu.”
“Tapi kamu belum makan es krim.”
“Gigi aku lagi sakit jadi nggak bisa, maaf lupa bilang lagi.”
Kemudian aku bangkit dari kursi dan berjalan cepat keluar dari kedai. Samar-samar aku dengar Adrian panggil namaku. Aku pikir, mungkin dia mau mengejar aku karena masih ada yang mau dibicarakan. Jadi sebisa mungkin aku berlari supaya dia tidak bisa mengejar.
Ekspetasi masa remaja, konyolnya bikin sakit hati.


 arisalfaita
arisalfaita