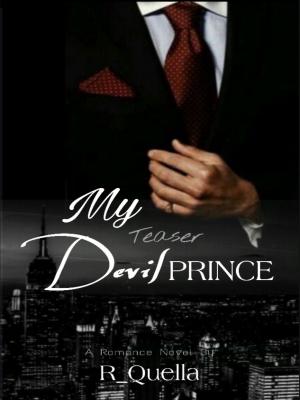Aku memeluk diriku sendiri saat break setelah pembukaan kegiatan penting BKKT, organisasi kuliah di bidang kesenian. Aku bungkam, memainkan ujung kemeja merah muda, sedangkan orang lain sibuk berkelompok, berbicara, dan saling menyenggol lengan karena respons sang komunikator.
“Tadi kamu ketemu lagi sama dia?”
“Wow, terus-terus?”
“Dia itu tiba-tiba masukin saos super banyak pas aku lagi makan di kantin! Sebel gak sih?”
“Ada proses nih! Besok kita makan bakso, ya, lo wajib traktir!”
“Seneng banget lihat temennya bangkrut.”
Dalam suatu organisasi, aku merasakan bahwa kebersamaan adalah omong kosong. Mereka bahkan tidak peduli jika ada seseorang yang merasa sangat-sangat kecil, duduk di dalam gedung yang sama.
“Kakimu kenapa, Lan?” tanyaku mencoba bersuara pada lelaki di sebelahku yang menarik perhatian karena lututnya dililit perban.
“Jatuh.” Dia sama sekali tidak melihat wajahku, kembali berbicara pada orang lain.
Telak, dadaku sesak. Orang melakukan hal sama padaku, tidak menganggap bahwa aku juga manusia yang punya perasaan.
Aku kemudian menghabiskan banyak waktu untuk melihat jendela besar, menikmati langit biru cerah, awan cirrus yang bergerak, hingga air mata membuat pandanganku memburam. Suatu hari aku ingin melihat bintang dengan langit seluas ini bersama orang yang mencintaiku.
“Ini pengumuman orang-orang yang bakal ikut di event kesenian bulan depan, ya.” Suara pembina bernama Pak Bara menegangkan satu angkatan organisasi yang kuikuti. Memang, tiga hari lalu ada acara khusus sebagai perayaan sekaligus tantangan atas diterimanya sebagai anggota.
“Sudahlah aku pasrah." Ucapan mengandung tawakal seseorang membuat semua tertawa, termasuk aku dengan tawa yang dipalsukan.
Aku hanya tidak ingin terlihat berbeda.
“Habis itu Bella, Lili, Tiara ….”
Aku sempat menahan napas, takut jika tidak lolos. Dua teman sejurusan yang diterima di organisasi ini sudah disebutkan namanya, sedangkan namaku belum.
“Selamat, Li,” ucapku kepada orang yang paling akrab di sampingku--meski ia irit bicara juga. Ruangan itu ricuh, sibuk menyelamatinya.
“Aku enggak nyangka, Thania,” desisnya yang mengetahui hasil kerja kerasnya terbayar, tersenyum sekilas kepadaku.
Setelah menjelang belasan, hatiku sempat mencelos. Badanku tegang. Keringat dan degupan jantung yang sempat mereda sekarang muncul secara luar biasa.
“Thania? Thania ada orangnya?”
Tepat, ketika aku hendak melambaikan tangan--menyerah, menyiapkan diri menjadi kaum gagal, aku tersenyum, mengangkat tangan secara mendadak, menerima kesempatan untuk memulai hal hebat, berpikir dengan ini orang tahu bahwa aku ada. Urutan 17 dari 20.
“Oke, semuanya diam. Nama-nama tadi sudah disebutkan, waktunya penutupan, sebelum kemalaman.” Pak Bara mengecek jam tangannya.
Semua orang yang sempat menselonjorkan kaki, menghadap acak, tidak sesuai tempatnya di atas karpet, sontak merapikan posisi.
Sebelum aku benar-benar pergi meninggalkan ruangan, tepat di ambang pintu bercat kuno, aku tak sengaja melihat ke belakang, semacam sisi tembok bertirai merah yang kosong dan mengucapkan suatu harapan.
“Aku harap bisa ketemu hantu, biar seengaknya aku enggak sendiri lagi.”
Setelah air mata yang kubendung tadi jatuh dari kedua mataku, aku segera berjalan cepat menuju mobil dan mengusapnya.
Semua akan segera berakhir, Thania. Tetap kuat.
Ya, seharusnya aku sadar, bahwa hantu itu bukan mainan, dia benar ada karena aku mungkin saja akan menyesalinya.
***
Setelah melempar tas ke kursi apartemen, aku terkejut akan suara kaki seseorang.
“Halo? Ada orang?” telusurku ketika berusaha membuka pintu kamar mandi.
Aku sungguh acuh pada hal seperti ini. Namun, ketika aku berbalik, mataku menangkap dua bayangan hitam yang ada di ujung ruangan, di atas lampu tidur.
Aku diam, menahan takut, mundur satu langkah, tetapi seseorang menepuk pundak kananku, membuatku tanpa aba-aba berteriak.
Dia, seorang pria dengan kemeja cokelat-kuning dan dalaman putih polos, lengkap senyum yang membuatku masih tetap berteriak.
“Ka-kamu siapa? Kenapa bisa masuk sini? Enggak ada yang bisa masuk apartemen ini kecuali aku.”
“Namaku Nando Ardian, hantu yang kamu panggil tadi sore.”
“Ha-hantu? Enggak-enggak, jangan ngaco.”
Aku memegang kepalaku setelah bayangan hitam itu menghilang dan terduduk di atas kasur.
“Bebanku sudah terlalu berat untuk hal beginian, cukup!”
Aku memejamkan mata, berusaha melempar semua masalah, rasa kesepian, dan kehaluan ini ke luar. Namun, ketika aku membuka mata, semua mustahil.
Dia nyata.
“Bayangan hitam tadi bilang, kalo kamu bakal mati 40 hari lagi. Ada banyak hantu di sekitar apartemen, tapi kayaknya kamu cuma bisa lihat aku, padahal banyak yang hadir saat kamu menginginkan hantu di sana, termasuk aku.”
Dan dalam hitungan detik ketiga, aku pingsan setelah rasa takut dan khayalan ini tak kunjung hilang.
***
Pertama kali aku membuka mata, sosok Nando muncul di sampingku, sedang menumpukan kepalanya di sisi kasur, membuatku terperangah.
“Kok-kok aku enggak bangun-bangun? Enggak mungkin,” ucapku sembari menepuk pipi, kemudian mengucek mata, berharap sosok yang ada di depanku ini benar-benar tidak nyata.
“Kamu sudah bangun, Thania.”
“Aku percaya kamu hantu karena kemarin kamu bisa masuk begitu saja ke apartemenku. Namun, aku cuma enggak nyangka aku bisa lihat hantu, sedangkan fisikmu saja terlihat jelas!”
Aku membalikkan badan, entah kenapa rasanya malu jika begini. Kubuka gorden dan Nando juga bukan hantu yang binasa karena cahaya matahari, ia masih saja tersenyum hangat.
“Kenapa harus kamu, Do?”
Nando berdiri dari tekukan lututnya, kemudian menghampiriku dan duduk di salah satu kursi.
“Aku juga enggak ngerti, Than. Mungkin, tanda-tanda orang mati pasti akan dihantui oleh sesuatu dan itu aku.”
Kakiku lemas, jatuh ke atas alas dan rambut yang sedikit bergelombangku menjuntai ke bawah.
“Bagaimana jika aku besok mati?”
Nando dengan tubuh utuh berjalan ke arahku, lalu membentuk posisi jongkok, dan aku tak bisa merasakan napasnya di depan wajahku.
“Bukankah kamu ingin mati, Than? Kenapa sekarang harus sedih? Hantu-hantu sangat menginginkanmu melakukannya, mereka kesepian.”
Dengan jin dan kemeja yang sama, tepat tanggal 22 April hari kesatu menjelang kematian, aku mampu melihat mata hitamnya pertama kali.
Ia mampu mendengar semua desisanku selama ini, yang orang sekalipun mendengar saja tidak mau.
Aku tertawa gila. “Ah, ini pasti khayalan. Dibanding mengurus hantu yang tidak benar adanya, lebih baik aku segera ke perpustakaan, mengisi waktuku dengan hal logis.”
Selanjutnya, aku mengambil beberapa baju, bersiap untuk mengabaikan pikiran yang kacau.
“Kamu tahu enggak sih, Than, ada dua planet yang menyerupai bumi kita. Di sana ada kandungan air yang dinilai cukup, letaknya 21 juta cahaya dari sini. Ya, fisiknya pun persis kayak bintang, hampir tepatnya matahari.”
Nando tiba-tiba berbicara di sampingku di ujung meja berkursi empat, tetapi hanya aku yang duduk di sini.
Sebelumnya, aku yakin jika aku ke sini mengendarai mobil seorang. Jika boleh kuakui, dia membahas bagian buku di depanku secara ilmiah. Dia cerdas.
“Nando, kenapa kamu enggak berniat buat ngejauh, atau ngilangin diri? Aku tambah gila jadinya! Kamu itu siapa, sih?” Aku mencakar pipiku gemas, menutup buku astronomi itu dan memelototinya.
“Aku cuma enggak mau kamu merasa kesepian. Lain kali, kalo kamu berharap, mikir dulu bagus apa enggak buat kamu. Semisal buruk, jangan salahin aku kalo hidupmu juga bakalan buruk.”
Bisik-bisik seseorang di belakangku membuatku menoleh, banyak orang yang satu meja dekat denganku tengah melihatiku takut. Aku baru sadar, mereka tidak bisa melihat Nando.
“Jangan dilihatin, dia udah enggak waras!”
“Oh, Thania yang ansos itu, ya?”
Enam kata itu entah kenapa menusuk hatiku yang masih belum pulih. Kuambil tiga paket buku yang sudah kupilah dan berlari meninggalkan Nando beserta orang-orang itu. Aku tidak tahan, sungguh.
***
“Sakit, ya?” tanya Nando lagi. “Kenapa kamu enggak pernah lawan mereka? Terus kenapa kamu ke toko kue? Siapa yang ulang tahun?”
Aku tak menjawabnya. Sibuk memilih kue tar untuk mama yang akan datang mengunjungi apartemenku. Katanya, kebetulan tugas luar kotanya bertempat sama dengan letakku saat ini.
“Mau yang mana, Kak?” Seorang pegawai toko kue bertopi putih-hitam itu menanyaiku.
Aku melipat tangan, merasa terganggu dengan Nando yang mengucapkan pertanyaan berikutnya, sedangkan aku perlu mengambil keputusan.
“Gimana kalo yang cokelat, terus cerinya dua?”
Bagaimanapun, aku juga menjadikan kue itu ke dalam daftar pilihan yang akan kubeli.
“Kenapa enggak yang pink aja? Aku suka warna itu, cocok buat mama.”
Lagi-lagi, aku tak menyadari berbicara dengan hantu.
“Kamu meragukan kecerdasanku?”
Baiklah, jika dipikir sampai ujung dunia, aku akan menurutinya kali ini. Kue dengan cokelat batang dan krim tak terlalu banyak, berbentuk hati cocok untuk mama yang sulit sekali ditemui.
Setelah sampai ke apartemen, aku tiba sembari membawa properti ulang tahun.
“Kamu nyiapin ini sendiri?”
“Kalo kamu jenius, kamu pasti tahu jawabanku apa,” jedaku setelah meniup balon ke-empat.
“Aku bantuin?”
“Kamu itu han--”
Iya mengambi lembaran kertas yang disambung menjadi “happy birthday” dan menarik kursi sepanjang 2 meter dan melilitkannya pada suatu paku. Dia ternyata juga bisa menyentuh barang.
“Do, kalo orang lain lihat, bisa bahaya, itu melayang sendiri,” desisku sembari memasukkan tiga bunga mawar ke dalam vas.
Sesinis apa pun sikapku padanya, dia justru hanya tertawa. Dia adalah sosok yang berbeda.
Jam berganti jam, aku memandang kue dengan tatapan kosong. Sudah ada 20 missing calls dariku dan berakhir dengan pesan bahwa mama masih terlalu disibukkan dengan jadwal diklat.
Pertahananku sudah roboh. Awalnya, aku menahan air mata dari pagi untuk ulang tahun mama, hingga make-up juga gaun khusus, tetapi aku salah, yang diperjuangkan justru mengecewakan.
“Mama kapan datang? Berapa tahun lagi semuanya harus terulang kayak tahun lalu?” Setetes, dua tetes air mata, jatuh membasahi kue. “Kenapa di dunia ini enggak ada yang pernah abadi? Kenapa aku sendiri, Ma? Ayah pergi ninggalin kita dan mungkin Mama bakalan ninggalin Thania. Kita perlahan-lahan menjauh, memendam semua luka, mengurusnya masing-masing, dan esok, bisa saja aku tiba-tiba enggak ada lagi.”
Aku melamun ke suatu titik, membiarkan suaraku makin lama makin berat dan aku punya alasan untuk menangis sekarang. Menunjukkan bahwa air mata adalah bukti ketidakadilan bagiku.
“Lepasin, Than, aku tahu kamu enggak sekuat yang kamu tunjukkin. Ketika aku ngelihat matamu secara dekat, entah kenapa aku pengen nangis, banyak banget lebam di hatimu yang kamu tutupin.”
Nando mengusap air mataku, dan untuk pertama kalinya, aku berteriak sekeras mungkin dan menangis di pelukan seorang lelaki.
“Kenapa semua ngejauhin aku, Do. Kenapa aku sekasat mata itu?”
Aku mampu merasakan dinginnya pelukan Nando malam itu. Dingin sekali. Tak ada embus napas di perutnya, seperti semua yang aku pikirkan, bahwa duniaku mati.
“Aku yakin, aku sudah siap mati, Do.” Kubiarkan baju Nando basah. Kuremas pakaiannya, membiarkan seseorang mengetahui sebetapa terlukanya aku, meskipun itu hantu sekalipun.
Nando berusaha mengelus rambutku yang acak-acakan karena terlalu lama menunggu. Percayalah, kasih sayang Nando mampu mengalahkan rasa kesepianku.
“Biarin aku mati…,” ucapku sembari mengambil pisau besi pemotong kue dan diam-diam mengiris pergelangan tanganku tanpa Nando lihat saat keheningan kamarku hanya menyisakan suara pendingin ruangan.
Semakin dalam pisau itu mengiris, entah kenapa aku juga tertawa senang, melihat darahku sendiri jatuh ke atas lantai, membentuk garis tebal kemerahan yang parah.
Sayang, Nando justru mengetahuinya.
“Jangan senekat ini, Than!” Ia mengambil pisau yang berlumur darah dan membantingnya.
“Mati itu enggak sebahagia yang kamu kira! Bukan pula aku hantu, kamu juga perlu jadi sosok yang sama sepertiku!”
Tawaku miris, aku mengigit bibir bawahku, semuanya makin menjadi-jadi.
“Aku enggak sanggup lagi, Do! Di dunia nyata sama akhirat nanti, semuanya sama saja. Aku sama-sama tersiksa, ‘kan?” Ya, aku tertawa gila sekarang, hingga akhirnya menangis lagi.
Malam ini, menjadi malam paling termenyakitkan yang pernah ada dan aku meluapkannya tanpa lagi menyembunyikan.
Nando memegang pundakku, menyisihkan helai rambut yang menempel di pipi. Nando marah, aku tahu itu. Tangannya terasa kuat sekali sekarang.
“Kamu bisa bahagia, Than. Aku mencintaimu.”
***
“Mama,” igauku saat membuka mata di hari kedua aku akan mati, mengharapkan sosok tersebut ada di depanku sekarang, tetapi nihil.
Lagu Don’t Watch Me Cry - Jorja Smith cover Alexander Porat terdengar sebagai pembuka yang indah pagi ini. Nando. Dia yang menyetelnya.
“Lagumu sedih-sedih semua, ya?” Nando tersenyum, seperti tidak terjadi apa-apa semalam. Bagaimana aku tertidur di pelukannya lalu pindah ke kasur secara nyaman. “Kamu sempat nulis puisi juga kemarin. Kali ini, majasnya ngebuat orang susah nebak.”
Nando sudah tahu segalanya. Tentang laguku, hobiku, kebiasaanku, semuanya.
“Do, siapa sih sebenarnya kamu itu?” tanyaku dengan suara serak.
“Kalo kamu kacau, bangunnya memang kesiangan begini, ya? Enggak ada acara?”
“Jangan ngalihin pembicaraan, Do.”
Aku memelototkan mataku ketika teringat sesuatu. Ada penanyangan privat penampilan teater tahun lalu, yang wajib dikunjungi. Adapula informasi untuk yang menjadi pemain utama, tetapi masih tidak ada clue-nya sama sekali.
“Astaga, Nando!” Setelahnya, aku terbatuk-batuk karena aku kesulitan bicara, tetapi justru berteriak hingga ternggorokanku terasa perih.
“Aku tahu. Kamu sudah terlambat, Thania. Lebih baik kamu lanjutkan tidur saja, nanti sore aku ingin mengajakmu ke suatu tempat.”
Nando mengambilkan air putih dan menyodorkannya ke arahku. Aku mengernyitkan dahi ketika dia tahu bahwa aku benar-benar ada acara.
Buku catatanku, di sana ada jadwal kegiatanku.
“Do, kenapa kamu tidak pernah menjauh dariku?”
Nando mengamati wajahku saksama, alis, mata, hidung, bibir, semuanya.
“Bisa berbicara dengan manusia, adalah hal terbahagiaku, seolah aku adalah hal normal. Jika aku tidak muncul lagi, itu hal yang mudah. Namun, aku sudah menawarkan diriku untuk menemani hari beratmu. Harapanmu.”
Setelah berbincang dengannya beberapa topik, akhirnya aku memutuskan untuk tidur kembali. Membiarkan semua dari diriku benar-benar pulih.
“Di gedung kesenian?” tanyaku ketika Nando mengarahkanku ke arah tempat bercat kuning-gelap dari jauh.
“Iya, tepatnya tempat bertirai merah,” bilang Nando.
Aku penasaran, mengapa sore menjelang malam seperti ini ia ingin aku ke sini.
“Dulu aku jatuh ketika berusaha memasang semacam spanduk di sini. Sebenarnya, bukan karena aku jatuhnya, tetapi karena aku punya glioblastoma, kanker otak yang mempengaruhi keseimbanganku, tetapi aku enggak mengerti kenapa aku masih di gentayangan, padahal enggak ada yang perlu diperjuangin.”
Nando memegang kepalanya yang terasa sakit. Aku melihat jahitan di sekitar kepalanya saat ia berusaha menyibak rambut tebal lurusnya.
“Pak Kerta pernah bilang di sini saat hendak tampil , bahwa dia punya anak yang mungkin sekira 20 tahun sekarang, suka kesenian, cocok sama aku, tapi aku sudah mati duluan. Dia bercerita banyak, dia bahagia banget, katanya aku bakalan sukses dengan kemampuanku. Nyatanya, hidup saja aku enggak mampu.”
Nando murung, sorot matanya gelap, rasanya aku tahu siapa dia.
“Tunggu. Pak Kerta? Dia ayahku, Do!”
Nando menaikkan kedua alisnya dan kembali melihatku, menyambungkan semua kronologi.
“Namanya Tata, bukan Thania.”
“Itu panggilan sayang ayahku ke aku.”
Tak ada raut kebahagiaan setelah itu. Nando memilih mengajakku keluar, kemungkinan besar ia ingin pulang. Aku sendiri tidak tahu mengapa. Sesuatu menggores perasaannya.
“Kenapa, Nando?”
“Kamu masa depanku, Than. Semisal aku enggak mati, kita udah pacaran sekarang. Ayahmu pernah bilang, kalo kamu kuliah, kita bakal tunangan. Namun, Tuhan lebih sayang aku ketimbang perasaanku.”
Aku menggenggam tangan Nando yang suhunya kurang dari minus delapan derajat. Kami duduk di kursi, di mana bintang sungguh nyata di sini.
Beberapa orang ada yang berlalu lalang, sepenuhnya lampu dihidupkan, aku merasakan kebahagiaan di keramaian untuk pertama kalinya, beserta bau petrikor menenangkan.
“Kayak bintang, dia enggak punya alasan untuk ditutup kabut, hilang, tapi dia tetap ada. Semua yang terjadi itu ketetapan, Do. Nanti, kalau sudah masuk surga, kamu bisa dapat bidadari lebih cantik daripada aku.”
“Aku mencintaimu, Than.”
“Aku belum bisa mencintaimu, Do. Semua basa-basi, menghabiskan waktu.”
Nando terlihat sabar. Orang di sini sibuk mengurus pekerjaannya yang berupa skripsi atau UKM tambahan. Aku menumpukan telapak tanganku di atas lutut, memejam mata, menikmati saat seperti ini. Ditemani orang yang mencintaiku, walau aku tidak mencintainya.
“Suatu saat nanti, kamu akan merasakan, rasanya bertemu seseorang, mendengar namanya, dan melihat wajahnya pertama kali, hatimu terasa berdebar. Lalu, ketika kamu menunggu, kamu akan disatukan dengan rindu yang kejam, dan kamu harus siap tersakiti jika orang itu tidak bisa bersamamu.”
“Maaf, Do.” Suaraku terdengar kembali serak. Sebulir air mata terjun ke pipi saat semua liku hidup ini mengharukan sekaligus sesak dalam satu waktu.
“Jangan nangis lagi. Aku enggak mau orang yang kucintai melakukan hal yang ngebuat hatiku makin sakit.”
Nando mencontohkan senyum tegar yang bersemangat, meski kali ini, rasanya sulit untuknya berlaku demikian. Malam itu, aku menikmati malam bersama Nando dengan sangat bahagia, membahas masa lalu, dan harapan hidupku benar-benar kembali berkatnya.
***
Setelah penyesalan tidak berangkat pada penayangan ulang teater, aku mendapatkan hasil kesimpulan dari Lili, bahwa aku menjadi tokoh utama di sana, dan semua benar adanya saat ada kumpul setelah jam kuliah.
“Thania, ini naskahnya, jangan lupa pelajarin. Terus ini ada buku yang isinya sudut pandang, semoga kamu suka.” Adit datang ke arahku membawakan beberapa lembar kertas yang sudah dijadikan satu, lumayan tebal. “Nanti kalo ada yang mau ditanyain, dibahas pas pulang, aku mau ngurus yang lain dulu.”
Aku mengangguk, menerima sebagai manusia polos, sedangkan Nando menatap sinis sosok Adit karena dia sudah berulang kali terpergok mendekatiku. Sering sekali melihatiku jika ada jadwal SKS, kata Nando. Sisanya dia sering memberikan banyak buku ketika tiba di perpustakaan dan pergi begitu saja.
“Dia itu malu-malu, padahal aslinya malu-maluin.”
“Kenapa kamu pikir begitu, Do?”
Aku tidak berniat membaca naskah, nanti ada jadwalnya sendiri. Aku memilih membuka buku teori Stephen Hawking yang diberikan Adit sembari mendengar Nando.
“Kamu tahu enggak, sih, Than? Cowok itu dekatin banyak perempuan.”
Aku menaikkan salah satu alisku dan memperhatikan bagaimana bibir Nando mangut-mangut tidak terima saat duduk di sebelahku. Ya, untung saja aku duduk agak belakang, tidak ada yang bisa mengataiku gila.
“Kamu cemburu?” Aku membalikkan halaman berikutnya. Jujur, sulit melakukan pembicaraan dan membaca dalam satu waktu. Hingga akhirnya aku memfokuskan pada Nando. “Aku enggak akan menyukai siapa pun, Do. Buang-buang waktu.”
Hingga ia mengacak-acak rambutku dengan bahagianya. “Itu adil buat aku, Than. Kalo aku enggak bisa punya kamu, orang lain juga enggak boleh memiliki kamu.”
Saat pelatihan vokal, aku berusaha yang terbaik, menuruti saran Nando sekali-kali.
“Ini nadanya patah-patah, kalo kamu main ngomong gitu aja, enggak ada kesan wahnya.”
Aku meremas kertas yang ada di depanku. Semua terasa mudah berkat Nando dengan sekali perbaiki.
“Maafkan aku, Raja,” ucapku kepada Adit yang demi apa menjadi lawan mainku. Nando masih terlihat tidak peduli, mungkin karena ia percaya aku tak akan menyukai siapa pun.
“Aku harap kau tidak perlu takut pada mereka, Ratu,” ucap Adit yang duduk di seberang.
Nando yang membalikkan kertas dan kututupi oleh tangan kananku agar tidak terlihat terbuka sendiri itu akhirnya berhenti di satu titik.
“Thania, baca ini, deh,” ucap Nando sembari menunjukkan beberapa adegan yang membuatku menutup mulut. Lembarannya masih lama untuk tiba, tetapi Nando membuatku lebih cepat menanggapi kejanggalan ini.
“Dia suka kamu, Than, dan itu sangat kurang berkelas untuk memperlakukan kamu dengan cara begini,” ucap Nando. Tangannya memegang kasar, matanya setajam elang sekarang. Aku hanya mampu menunduk ketakukan, tak berani melihat Adit.
Aku membacakan percakapan demi percakapan sembari menahan emosi, tidak mau menatap sosok Adit lagi. Dia sungguh menakutkan sekarang.
“Suaramu bagus, pertahankan seperti sebelumnya,” puji Bu Tari, membuat anak-anak lain berbisik, meragukan. Suasana hatiku selamat berkat Bu Tari, padahal bisa saja aku mengeraskan suara agar tidak diterima pada tokoh drama ini.
“Terima kasih, Bu.” Mendengarkan pengakuan ini, aku merasa seolah aku sudah mencapai suatu kesuksesan tersendiri.
Nando memberikanku dua jempol, meski ia tahu ada yang perlu diurus setelah ini. Tanganku berusaha bergerak, sembari tertawa ketika ada orang lain yang mencoba memujiku, membahas rambut dan gesturku.
Orang mulai menganggapku, untuk kali ini aku percaya bahwa hasil tidak mengkhianati usaha. Melupakan semua masalah, hingga semua senyum itu hancur begitu saja setelah jam pulang.
“Adit, aku enggak setuju sama ini.”
Adit yang merapikan beberapa kertas tersebar melihatiku dengan tatapan yang entah kenapa aku tak suka kali ini. Aku menunjukkan di bagian aku dipeluk oleh Adit, menyandarkan kepala, dan bahkan ciuman. Dia harusnya sadar bahwa sepersen pun aku tidak menyukainya.
“Kenapa? Ini sudah paling normal,” ucap Adit yang sekarang berdiri di depanku. Nando memperhatikan dengan saksama. Bisa saja ia merasukinya, tetapi itu justru malah memperparah.
“Aku enggak mau jadi peran ratu di sini. Lebih baik jadi tokoh lain.” Emosi sudah ada di ubun-ubunku. Jujur, aku tidak rela melepaskan tokoh utama, tetapi jika berhubungan dengan sosok yang aku saja tidak begitu mengenalnya, kecuali sebagai peminjam buku. Aku harus apa?
“Than.”
“Apa, Dit?” ucapku setengah berteriak.
“Aku bakal laporin kamu ke Bu Tari kalo kamu nolak. Dia menyetujui naskahnya.”
Aku tahu, ini tidak adil. Dia memaksaku hanya untuk terlihat benar sekarang. Bisa saja, yang diucapkannya adalah kebohongan.
“Kenapa harus aku, sedangkan ada yang lebih cantik buat jadi ratu?”
Aku melempar naskah itu ke bawah hingga ada kertas rusak. Sudah cukup aku ditekan.
“Karena kamu paling polos di sini.” Suaranya terdengar santai, seolah semua keinginan sudah tergenggam di tangannya, sangat terencana.
“Pokoknya aku enggak mau!” Aku mengambil tas selempangku yang ada di tempat Nando duduk sebelumnya dan dengan perasaan takut akan banyak hal, aku berjalan menuju ke pintu keluar.
Aku mampu melihat ruangan itu kosong dan semua mimpiku hancur hanya dengan kata berkatnya. Nando bersiap memberikan banyak nasihat saat aku sudah sampai apartemen, sebab aku tidak memedulikannya sama sekali.
“Karena kamu ansos, Than!”
Ketika lima langkah meninggalkannya itu, langkahku terhenti. Berbalik dan berjalan ke arahnya dengan air mata yang jatuh. Aku sakit, sungguh. Orang mendekatiku hanya karena ini.
“Aku enggak ansos, Adit!” ucapku disertai dengan tamparan kasar. Air mataku turun begitu saja, ketika semua terasa jelas. Baru saja kemarin sembuh berkat Nando, dia merusaknya dengan kepura-puraan yang demi semesta dan seisinya, aku benci.
Setelahnya, aku berlari sembari menahan sesak, berharap aku bisa menjadikan diriku yang tidak dilecehkan dengan perangai tipuan. Aku tidak semurah itu, aku lebih dari itu.
Ketahuilah, yang aku butuhkan adalah segera pergi dari gedung yang berhalaman bunga anggrek ini. Aku benci laki-laki, aku benci diriku sendiri, dan aku ingin tidur selamanya, tidak pernah bertemu dengan dunia yang kejam.
“Hei, dengerin dulu!” Adit berteriak, tetapi kali ini aku tak mau menghabiskan air mata hanya untuk berdebat yang membuatku makin tersiksa.
Aku menekan tombol kata kunci apartemenku tak sabaran, lalu masuk dengan perasaan ingin meluapkannya.
“Thania,” ucap Nando untuk kesekian kali karena aku tidak mendengarnya.
Aku sibuk menangis di atas bantal, meredam semua tangis yang keluar semudah ini.
Awalnya, aku tidak menghidupkan lampu utama, hanya lampu kecil. Aku hanya ingin melepaskan siksa dalam gelapnya ruangan. Tidak ada yang jujur perihal aku pantas bahagia.
“Jangan nangis,” ucap Nando yang kemudian menghampiriku dan duduk di sampingku sekarang.
“Diem, Do, aku mohon.” Suaraku bergetar. Ini pukul enam malam dan aku sama sekali tak ingin makan setelah siang tadi kehilangan nafsu makan karena fokus membaca buku.
“Thania,” ucap Nando yang kali ini persis, membiarkan kepalanya di samping kepalaku, tetapi aku masih menutupnya dengan guling, menyembunyikan semua hal memalukan.
“Aku enggak mau mereka dan kamu berbohong perihal aku pantas bahagia. Semua bohong, Do, bohong….”
Jika orang menanyai siapa manusia paling hancur di dunia ini, mungkin aku akan mengajukan diri. Aku memegang kepalaku, memukulinya, karena semua itu adalah hal gila, yang semakin dipikirkan, air mataku turun makin deras. Aku membekap mulutku sendiri, ketika isakanku kali ini makin keras.
“Semua menyakitkan, Do, biarin aku mati. Aku pengen hidup bahagia sama Tuhan.” Aku makin terisak.
Kuturunkan guling dan ada wajah Nando tepat persis di depanku, hanya berbatas satu jengkal tangan, tetapi entah kenapa, aku tidak mempermasalahkannya. Aku hanya ingin, Nando menyibak semua luka yang bisa ia lihat di mataku saat ini.
“Kalo kamu pikir cintaku bohong, kamu salah, Than. Aku enggak sebercanda itu.”
Untuk kesekian kali, air mataku turun dan ditangkap oleh tangan lembutnya. Ia memang tidak berubah. Bukan hanya tidak berubah karena bajunya tidak pernah diganti, tetapi sifatnya yang tak pernah sanggup diragukan.
“Nando,” desisku dengan air mata yang jatuh deras kembali setelah sempat mereda. Aku jahat, kuakui, setelah semua sikap tak acuhku kepadanya, dan dia dengan sabar masih menyempatkan untuk mengusap air mataku. “Aku mencintaimu, Do. Terima kasih.”
Nando menyingkirkan guling putih pembatasku dengannya dan mendekatkan wajahnya ke arahku, dan dalam satu tarikan tangan kanannya, dia menciumku, membiarkan aku merasakan bahwa semua lukaku terbagi menjadi tak terhitung kemudian lenyap.
“Tidurlah, aku tahu kamu lelah, Than. Ini harimu yang dua puluh lima, waktumu sudah enggak banyak.”
Aku meringis, merasakan bagian hatiku ada yang sakit. Mama, teman-temanku seperti Lili, dan banyak orang lain lagi akan merasakan sedih luar biasa.
“Masih ada cita-cita yang belum aku gapai, Do.”
“Aku tahu, Than, kamu ingin jadi guru.” Rahang Nando mengeras saat ia berusaha bangkit, tetapi tertahan. Ia pasti lelah, tidak tidur berhari-hari.
“Do, aku ingin hidup seperti ini bersamamu. Aku takut jika nanti kamu belum diterima, sedangkan aku sudah diterima dan kita berpisah.”
“Akan ada banyak lelaki tampan di sana, Than.” Dia mengulangi motivasi persis, seperti yang pernah kukatakan awal bertemu.
“Kenapa cinta itu harus ada ketika sebentar lagi aku harus kehilangannya?”
Air mataku kembali menggenang di pelupuk. Nando merasa bersalah karena salah mengucapkan sesuatu. Ia hanya mampu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Mengembuskan napas, seperti bebannya banyak sekali. Ia bahkan belum menggapai cita-citanya pula.
“Aku sendiri enggak mengerti, Than. Yang aku tahu, kamu masih punya kesempatan untuk melakukan beberapa hal yang seenggaknya bisa kamu lakukan.”
“Aku cuma ingin bahagia.”
Nando tersenyum pahit, mengelus pipiku dengan pelan, kemudian menunjukkan senyum terhangat lagi.
“Itu kata kuncinya, Than. Kamu harus mencari kebahagiaan, tidak peduli seberapa banyak kamu terluka, kamu harus tetap berusaha mencarinya, mau tidak mau.”
***
Hari ini, hari ketiga puluh dari empat puluh. Aku sudah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ratu yang menderita karena Adit. Setidaknya, aku bisa mendapatkan suatu peran yang lebih baik di kesempatan berikutnya.
“Ayo, Than, coba bicara. Ingat, kalo kamu mau dihargai, kamu harus mencoba lebih keras untuk mulai menghargai.”
Aku mengangguk. Tampilanku tidak seperti kemarin, yang terlihat awut-awutan dengan rambut dikuncir seadanya, tetapi lebih rapi, dan wangi. Aku harus berubah sebelum kesempatan itu tidak akan pernah kembali lagi.
“Hai, boleh gabung? Aku butuh riset bareng kalian, biar gampang,” ucapku sembari menyisihkan rambut ke belakang telinga dan membawa beberapa referensi yang dalam waktu tiga hari kukumpulkan sekuat tenaga, setidaknya aku bisa memberikan mereka alasan untuk menerimaku.
Awalnya, ada satu orang yang mengalihkan pandangan, menganggap aku tidak ada.
“Yakin, Than?” Ramon dan beberapa dari anak yang satu jurusan itu melihatiku kaget, termasuk Bella yang entah kenapa senyumnya tulus semenjak aku bisa berpengaruh di kesenian sebelumnya.
“Kamu yakin?” Bella bersuara. “Jujur, ada yang aneh semenjak beberapa hari yang lalu, kamu lebih sering berbicara, semacam ada yang berbeda dari kamu, tapi aku suka.”
Mungkin, tidak banyak yang bisa aku tarik untuk bersahabat dari kesenian karena pemutusan sepihak, tetapi setidaknya aku punya alasan untuk tidak sendiri lagi dengan teman sejurusanku sendiri. Memulai dari hal kecil tidak salah, ‘kan?
“Boleh, besok ada tempat yang mau kita kunjungin. Boleh minta nomor, Than?” tanya Ramon lagi, sembari membenarkan kacamatanya. Suaranya tidak sesinis wajahnya. Aku tahu, selama ini aku salah menilai karena pikiranku sendiri.
“Oh, boleh.” Aku mengetikkan nomor ponselku dan semua berjalan sangat mulus, meski aku tahu mungkin saja belasan hari kemudian setelah laporan selesai, nama yang tercantum di sana tidak ada gunanya lagi.
Aku memberi centang pada buku kecilku. Lalu, pilihan terakhirku jatuh pada Mama. Aku sangat bermasalah dengannya dan hatiku sempat mendidih.
“Do,” bisikku.
“Kamu bisa, Than.” Nando yang duduk bersebelahan denganku di taman kampus hanya memberikan aku semangat.
Berikutnya, aku mengetikkan pesan untuk mama.
Thania
Ma, Thania sayang Mama. Jangan capek kerja, ya.
Oh ya, semangat juga!
Saranghae!
Stiker terkirim.
Mama
Makasih, Than.
Besok tanggal 2 Juni mama serius ketemu kamu.
Maafin Mama ya, Than.
Pandanganku terhenti pada suatu titik, jantungku berdegup kencang. Itu adalah hari kematianku, bagaimana bisa aku menemui mama di hari itu. Meski senang dibalas cepat, rasanya aku tidak terima.
Bagaimana jika aku mati besok, Ma?
***
“Tulisan motivasi buat hidupku lengkap, Do.”
Dua hari sebelum mati itu, aku entah kenapa merasa siap-siap saja. Nando masih berdiri di balkon, menatap gedung-gedung pencakar langit, menikmati, seolah ia juga hidup, walau dalam bentuk berbeda.
“Jika dipikir-pikir, hidup kita sebenarnya sudah panjang, Than, dibanding bayi yang belum ngerasain pendidikan saja, sudah dicabut nyawanya.”
“Do, aku mau cerita, seminggu terakhir aku bisa lihat hantu. Mulai dari yang jongkok dengan tulang dan darah keluar, juga yang enggak kelihatan kakinya, adapula yang manjat di atap tanpa mata pas aku tidur.” Aku mengalihkan pembicaraan, ke sesuatu yang lebih penting.
“Kenapa kamu enggak takut? Apalagi sesekali teriak?”
Nando masih santai, menikmati senja petang itu.
“Aku pernah takut dan saat kamu bilang saat kita takut dan bisa dengan mudah dikalahin sama dia, aku enggak takut lagi, apalagi setiap hari juga ketemu kamu. Yang aku takutin, ketika ketemu malaikat maut. Aku takut jika mati besok. Aku takut kehilangan kasih sayang yang sebenarnya enggak aku sadari dari dulu.”
“Apa ada hubungannya sama aku?” tambahku.
“Enggak, iblis di dirimu cuma nakut-nakutin kamu kalo fisikmu nanti kayak mereka.”
Aku menghampiri Nando dan membacakan semua motivasi yang kukumpulkan dalam buku kecil sampul merah di sampingnya. “Nanti, kalo aku hidup seribu tahun lagi, aku bakal jadi kuat karena sudah punya kiat bertahan. Pertama, mendengarkan lagu yang membangkitkan semangat, ngedalami religius dan memahami maknanya,
lihat pemandangan dan bernapas biar lega, ngelihat perjuangan kita selama ini yang berat dan susah jadi seperti sekarang, memikirkan orang tua yang susah payah, dan terakhir mendedikasikan hidup hanya pada orang yang mencintai kita karena enggak ada gunanya memikirkan orang yang membenci kita. Seribu tahun itu aku akan bahagia.”
“Janji ya, Than, kamu bakal bahagia.”
“Pasti.”
***
“Mama,” ucapku ketika mampu melihat wajah mama yang sudah keriput nan lelah di kafe hari itu, membawa tas hitam.
“Thania,” ucap mama dan memelukku. Aku tahu, berat bagi mama menghidupiku karena ayah yang meninggal karena penyakit kronis.
Aku menitikkan air mata hari itu. Sebab, aku bisa meninggal dengan kondisi bahagia, meski belum genap cita-citaku teraih.
“Thania sayang mama.”
“Mama juga sayang Thania,” ucap mama dan duduk di depanku.
“Ma, bagaimana jika aku mati hari ini?” Aku menitikkan air mata lagi sembari tersenyum lega, mampu mengungkap perasaan yang terpendam selama ini.
“Enggak boleh bilang mati. Memang kamu beneran mau mati? Biasa saja kalo ada masalah, jangan dibawa berat begitu.”
Aku tertawa, mama memang suka menentang seperti itu, setidaknya aku tak akan menangis di hari kematianku dan bisa menikmati suasana lampion indah yang ramainya tak kubenci lagi.
“Aku bangga sama kamu, Than.” Nando berbisik di telingaku.
Dan malam itu, aku jadi insan yang cukup siap mati, setelah menikmati menonton bioskop bersama Nando dan mama, mempelajari beberapa perkataan bahasa inggris dari film yang kucocokkan dengan rumusku, serta resolusiku untuk tidak lagi berniat mati terkabul.
Aku bahagia.
Paginya, aku membuka mata dan melihat mama datang setelah mengetuk pintu dan membawakan makanan juga koper, katanya sebelum pulang ke kota asal, ingin menikmati waktu bersamaku.
“Ma?” tanyaku ketika aku masih melihat jelas mama saat itu. Yang kusayangkan pada esok adalah, Nando hilang dengan segala kenangan yang membuat hatiku ngilu. Namun, bagaimanapun, aku memang sudah bersiap untuk merelakannya.
“Iya, Sayang? Ayo, makan, mama beliin sesuatu buat kamu.”
Aku duduk di depan mama yang kerepotan.
“Tuhan, terima kasih aku bisa hidup lebih panjang.”
Mungkin, Tuhan memberikanku kehidupan lebih panjang dan mengirimkan Nando ke sini karena aku pantas bahagia dan sudah waktunya berhenti untuk merasa harus mati lagi. Aku akan selalu jadi orang positif mulai sekarang atau esok sesuai janjiku pada Nando. Sebab aku, siap menyambut masa depan.


 sherenal
sherenal