Selamat membaca 😊
۞۞۞
Kepada siapa diri ini bergantung? Pada Dia yang selalu bersama kita di mana pun diri ini berada.
Lantas mengapa diri ini harus risau ditinggalkan sesama ciptaannya? Bahkan bayangan diri ini saja meninggalkan ketika gelap.
Namun… Apakah diri ini tidak munafik jika lidah berkata bersyukur ditinggalkannya sedang hati tersungkur dibuatnya?
Mulut Moira jelas ingin berkata tidak dengan lantang, tetapi kemudian otaknya berpikir, siapa dirinya? Dirinya hanya seorang gadis yang diperistri karena perjodohan, yang bahkan kehadirannya saja tidak diinginkan.
Lalu diam adalah pilihan yang tepat sebab lidah tak semengerti hati. Moira memilih pergi meninggalkan Ibram dengan pertanyaannya. Dirinya tak bisa menjawab, memangnya ada di dunia ini orang yang bersyukur ditinggalkan suaminya? Kecuali suaminya itu dzalim kepadanya.
Lalu apa yang Ibram perbuat selama ini bukan dzalim pada Moira? Entahlah, Moira tidak tahu. Seolah rasa sakitnya tertutupi oleh sebuah perasaan yang lebih besar dibandingkan rasa sakitnya itu.
Apa… itu cinta?
Ah, cinta.
Kadang cinta semenyakitkan ini; datang ketika tak diharapkan dan pergi ketika diinginkan.
***
“Alhamdulillah, senangnya bisa kembali ke rumah.” Moira menghempaskan tubuhnya ke tempat tidur. Semenjak pergi dadakan malam itu, ia baru kali ini kembali lagi ke rumah. Hamdalah hari ini Bunda sudah bisa pulang dan akan control kembali seminggu kemudian.
Kedua tangannya ia rentangkan, menarik otot-ototnya yang sekarang terasa pegal. Aneh, padahal ketika di rumah sakit tak pernah sedikit pun merasa kelelahan ataupun pegal-pegal begini. Kini setelah tubuhnya menyentuh kasur empuk kok badannya malah terasa pegal-pegal.
Mungkin mandi air hangat akan kembali menyegarkan tubuhnya pikir Moira. Lalu gadis itu beranjak untuk ke kamar mandi.
Selepas mandi setelah sebelumnya mengeringkan rambutnya, Moira langsung menyusupkan tubuhnya ke dalam selimut. Keputusannya untuk mandi pada pukul setengah 10 begini adalah salah, walau dengan air hangat tetapi entah mengapa tubuhnya terasa menggigil setelahnya. Telapak kakinya begitu dingin, dan juga matanya terasa panas.
Moira mengerang pelan kala menggerakkan kepalanya untuk membetulkan posisi bantalnya, mengapa terasa sangat berat. Ada apa dengan tubuhnya?
“Moira, aku lapar,” ucap seseorang dibalik daun pintu yang setengah terbuka.
Moira melenguh dengan mata tertutup, dirinya lupa tadi suaminya belum makan malam. Tubuhnya tengah tak bersahabat kali ini, susah sekali rasanya untuk sekadar menyingkirkan selimut dari atas tubuhnya. Bahkan, matanya sangat tak kuasa untuk dibuka karena kepalanya begitu pening.
Terdengar derap kaki mendekat petiduran. “Kamu udah tidur?”
“Belum…,” jawab Moira parau. Apalagi ini? Suaranya mengapa berubah begini.
Tiba-tiba sebuah telapak tangan mendarat di dahi Moira yang sontak membuatnya terasa nyaman kala merasakan dingin dari tangan tersebut.
“Kamu panas,” pekik Ibram kemudian menarik telapak tangannya lalu pergi begitu saja.
Moira menempelkan punggung tangan pada lehernya, dan benar saja suhu tubuhnya sedang tinggi sekarang. Mengapa tubuhnya begini? Padahal beberapa jam yang lalu baik-baik saja walau rasanya kerudung yang dikenakan serasa sudah menyesakkan dan ingin segera ia lepas sesampainya di rumah.
Kalau sedang sakit begini ia jadi teringat Ayah, betapa Ayah akan setia menemaninya, mengompresnya, memijat keningnya.
Ah, Ayah. Moira butuh Ayah sekarang.
Tak terasa suara isakan lolos dari mulutnya. Kemudian sebuah kain basah menempel pada keningnya yang sontak membuatnya membuka mata susah-susah.
“Gak usah nangis, cuma demam,” ujar Ibram enteng. “Besok pagi juga bakal sembuh kok.” Ibram menenangkan sambil menghapus air mata Moira yang tak sengaja jatuh.
“Aamiin, makasih Mas,” ucap Moira pelan.
Hati Moira sedikit terharu sebab peran Ayah-nya dulu, kini diganti oleh suaminya. tak disangka pria dingin itu perhatian padanya. Tadi ia sudah berpikir bahwa pria itu akan lari dan tak mengurusinya. Kemudain Moira beristighfar sebab telah berprasangka buruk.
“Pasti ini gara-gara kamu kelelahan jagain Bunda.” Ibram menarik kain yang mengompres kening Moira. Mungkin karena suhu tubuh Moira yang tinggi membuat kain basah itu cepat mongering. “Maaf, ‘ya? Sudah membuatmu begini.”
Moira menggeleng pelan. “Memang sudah waktunya datang aja sakitnya.”
Detik berikutnya terdengar suara perut Ibram berteriak minta sang empunya tubuh untuk memberi makan. Lalu ia berniat pesan makanan saja menggunakan jasa ojek online.
“Ponselmu di mana?” Ibram malas untuk mengambil ponselnya yang di kamar, jadi ia putuskan saja untuk menggunakan ponsel Moira. “Aku mau pesan makanan.”
“Di meja rias kayaknya.” Moira tidak ingat pasti.
Ibram beranjak untuk menghampiri tempat yang ditunjukan Moira. Terlihat benda pipih berwarna rose gold tergeletak dekat sling bag warna maroon milik istrinya. Diraihnya ponsel tersebut lalu kembali duduk di petiduran Moira. Kala menghidupkan data selular, deretan notifikasi muncul silih bertumpuk dari berbagai social media yang dimiliki Moira, tetapi kebanyakan dari whatsapp.
Hati Ibram jadi tergelitik untuk membukanya. Eh, kemudian satu sisi hatinya berteriak kalau dirinya sudah melanggar privasi orang lain. Tetapi itu berlaku untuk orang lain ‘kan? Sedang Moira adalah istrinya.
Ibram mengetukan ibu jarinya pada aplikasi berwarna hijau itu. Matanya sedikit terbelalak kala melihat deretan pesan yang rata-rata bernamakan seorang laki-laki. Sebagain pesan berisikan salam dan menanyakan Moira sedang apa. Lalu sebagain lainnya menanyakan tugas walau sebenarnya itu hanya modus agar bisa chatting-an dengan Moira.
Hati Ibram yang tadi seperti digelitik kini malah seperti sedang diasah oleh amarah. Entah mengapa ia jadi kesal pada Moira. Kemudian jarinya mengetuk foto profil Moira yang kini tengah menampilkan foto Moira yang sedang menatap ke arah lain tidak pada kamera.
Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepala Ibram. Ibu jari Ibram menari-nari dalam galeri foto milik Moira, mencari foto pernikahan mereka. Moira pasti menyimpannya. Tak lama foto yang dicari akhirnya ditemukan. Tampak Ibram dan Moira sedang menunjukan buku nikah pada kamera, di sana Moira terlihat tersenyum manis sedang dirinya tanpa ekspresi. Ah, terserahlah yang penting dengan foto ini akan semakin membuat teman laki-laki Moira tersadar.
Sebuah senyuman tercetak di bibir Ibram.
“Udah ketemu, Mas?” Suara Moira tiba-tiba membuat Ibram gelagapan. “Udah pesan makanannya?”
“Eh, i-iya… ini… umm… anu… lagi cari,” ucap Ibram yang kemudian ia merutuk dirinya sendiri.
Jari Ibram langsung menekan tombol home dan beralih ke aplikasi lain untuk memesan makanan. Ia akan memesan bubur saja sekalian biar Moira bisa makan obat sebelum tidur.
Untung Moira gak curiga, batin Ibram seraya menghembuskan napas lega. Tetapi, kemudian pria itu kembali ke aplikasi semula mencari nama yang mengganjal hatinya. Mengapa tadi tak tampak di sana? Ataukah Moira menamainya lain?
Dengan saksama Ibram mencari hingga pesan terbawah namun tak di dapati nama yang ia cari. Akmal, mungkin kah laki-laki itu sudah tidak berhubungan lagi dengan istrinya?
Detik berikutnya Ibram melempar ponsel Moira ke kasur seraya mendengus. Untuk apa dirinya begitu penasaran dengan urusan Moira. Lalu ia menyesali perbuatannya yang telah mengganti foto profil Moira. Nanti apa kata Moira kalau tahu foto profilnya diganti olehnya. Mau jawab apa? Cemburu? Ah, tentu tidak. Ini bukan perasaan cemburu.
“Kok dilempar, Mas? Nge-hang, ya?” tanya Moira dengan suara paraunya, terheran atas tindakan suaminya barusan.
“Hah? I-iya… itu… tadi… iya nge-hang!”
“Emang suka gitu, Mas, maklum udah veteran.”
Ibram mengangguk cepat, hatinya bersyukur atas kepolosan Moira yang tidak mencurigainya sama sekali. Kemudian Ibram kembali menarik kain kompresan yang sudah mengering.
Bubur yang dipesannya datang 30 menit kemudian. Ibram dengan sabar menyuapi Moira, walau sebenarnya bisa saja Moira makan sendiri. Tetapi atas keinginan Ibram sendiri, Moira tidak menolak. Malah dengan senang hati Moira menerima suapan dari suaminya itu. Sesuap bubur yang diberikan Ibram rasanya sesuap energi yang perlahan membuat tubuhnya membaik.
Malam ini telah membuktikan bahwasanya Moira berselesa untuk mendapatkan Ibram. Malam ini membuktikan bahwa gunus es itu bisa runtuh dengan suhu tubuhnya yang tinggi. Malam ini membuktikan bahwa Ibram memang seorang suami yang bertanggung jawab.
Moira tersenyum dalam hati. Sungguh Allah Maha Baik, memberikannya rasa sakit dan memberikannya rasa bahagia pula.
***
Pukul setengah 6 Moira terbangun dari tidurnya. Di dahinya sudah tidak ada lagi kain basah yang menempel. Setelah seratus persen mendapatkan kesadarannya, Moira kemudian mengedarkan pandangannya mencari sosok jangkung yang semalam tidur di sebelahnya. Tetapi tak didapati pria itu.
Rasanya badan Moira sudah membaik, sakit kepalanya sudah tidak lagi ia rasakan. Suhu tubuhnya juga sudah kembali normal. Moira berniat untuk mengambil wudhu akan tetapi suara pintu yang ditutup dengan keras di luar sana membuatnya penasaran. Dengan gerakan cepatan Moira keluar kamarnya untuk memastikan dan dilihatnya Ibram yang hendak pergi.
Pria itu terlihat buru-buru dengan pakaian rapi. Kalau Moira tidak salah ini adalah hari sabtu yang mana seharusnya pria itu tidak pergi berangkat bekerja ‘kan?
Sebelum Moira memanggil suaminya itu, Ibram sudah terlebih dahulu menghentikan langkahnya. Berdiri tepat di depan Moira, lalu tangannya terulur untuk menyentuh dahi Moira.
“Alhamdulillah,” ucapnya terdengar lega.
“Mas Ibram mau ke mana?” Moira menengadahkan kepalanya untuk melihat wajah suaminya yang terhalang oleh lengan besarnya.
“A-aku….” Ibram terbata, dalam hati ia menimang haruskah dia berkata jujur? Apakah itu tidak akan menyakiti Moira? Tetapi untuk apa pula dirinya berbohong, toh Moira pun sudah tahu ‘kan?
“Mas,” panggil Moira menyadarkan Ibram.
Ibram berdehem, tangannya yang menempel di dahi Moira kini berpindah pada lengan gadis itu. Ibram mencengkeramnya pelan sambil menunduk menatap mata Moira dalam lalu berkata, “Moira, aku meminta izin kepadamu untuk ke rumah Anindira sekarang juga. Dia sedang membutuhkan aku.”
Seketika hati Moira dirobek dengan paksa kala mendengarnya. Apa katanya barusan? Anindira sedang membutuhkannya? Lalu apakah diri ini juga tidak membutuhkannya?
Moira sebisa mungkin menahan tangisnya agar tidak tumpah sambil menundukan kepalanya. “Kalau Moira tak izinkan, apa Mas Ibram tetap pergi?”
Angan Moira berharap kata ‘tidak’ yang akan keluar dari mulut Ibram. Tetapi, kembali lagi itu mungkin hanya angan-angan.
Ibram mengangguk pelan. Robekan hati Moira kian besar, malah rasanya kini hatinya dicabut dengan paksa dari rongganya. Harusnya Moira tidak merasakan sesakit ini, toh dirinya memang sudah terbiasa bukan? Tentu saja Ibram akan lebih memilih Anindira, kekasihnya.
Perlahan tangan Ibram terlepas dari lengan Moira. Mata Moira enggan melihat wajah Ibram, dirinya terus menunduk menyaksikan kaki suaminya yang perlahan mundur lalu menghilang. Terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru yang kian lama kian menghilang dari pendengaran Moira.
Ibram telah berhasil meruntuhkan harapannya semalam pagi ini.
Moira menyalahkan dirinya sendiri. Salahnya sudah berharap, lalu mengapa harus menangis? Sedang pengharapan itu dirinyalah yang menciptakan.
Oh Allah, benarkah Engkau sedang cemburu pada hambamu ini, hingga Engkau pupuskan harapanku pada ciptaanmu?
***
Ibram berlari selepas turun dari mobil, buru-buru ingin segera masuk ke dalam rumah bernuansa abu-abu itu. Tak perlu mengetuk pintu, seseorang sudah menyambutnya di sana dengan wajah yang diselimuti rasa panik.
“Ibram.” Wanita itu menarik lengan Ibram untuk cepat-cepat masuk. Langkah kakinya tergesa-gesa melewati ruang tamu dan masuk ke lorong rumah kian dalam dan masuk ke kamar yang berhadapan dengan kolam renang di luar sana.
Ibram terkesiap kala melihat wanita paruh baya tengah terengah-engah sambil berbaring di petiduran. Terlihat napasnya begitu berat seperti terhimpit benda berton-ton di atas dadanya. Peluh sebesar biji jagung deras keluar membasahi pelipisnya.
“Astaghfirullah!” Ibram sontak menghampiri wanita paruh baya itu dengan perasaan panik. “Ayo kita bawa ke rumah sakit,” pekiknya.
Anindira menggeleng sambil menangis. “Mama gak mau.”
“Tante, kita ke rumah sakit, ya?” Ibram berusaha mengajak Mama Anindira, tidak tega rasanya membiarkan seperti ini.
Tangan Mama Anindira terangkat dengan susah payah hendak menyentuh lengan Ibram. “Tidak… usah… sebentar… la… gi… juga… re-reda.”
Ibram berdesah. “Enggak bisa, Tante!” Pandangan Ibram kini beralih pada Anindira yang tetap pada posisinya. “Anindira! Kamu tega biarkan Mamamu begini?!”
Kali ini Anindira menghampiri petiduran dan duduk di seberang Ibram. “Ma, please… ke rumah sakit.”
Lagi, wanita paruh baya itu menggeleng. “Ini hanya kecapean.” Suaranya sudah mendingan, disusul dengan napasnya kian melambat.
“Memangnya tadi Tante habis ngapain?” Pertanyaan ini Ibram tunjukkan pada Anindira.
Anindira menelan ludahnya. “Ta-tadi… Mama mencuci karena pembantu yang absen hari ini.”
“Astaghfirullah!” Ibram menggelengkan kepalanya tak percaya, ditatapnya Anindira tajam. Terlihat wanita itu mengigit bibirnya merasa menyesal.
“Ibram,” panggil Mama Anindira. “Kamu lihat kondisi Tante sekarang bagaimana, ‘kan?”
Ibram tak menjawab, dirinya masih menunggu Mama Anindira untuk melanjutkan ucapannya.
“Tante takut tidak akan lama lagi.” Hati Ibram berdebar, ia tahu pasti ke mana arah pembiacaraan ini akan bermuara. “Tante ingin sekali melihat Anindira menikah. Jadi, kapan kamu akan menikahinya?”
Ibram menelan ludahnya susah payah seperti kerongkongannya terhalang sebuah batu.
Apa yang harus ia katakan? Tentu berkata jujur bukan solusi terbaik saat ini, yang ada ia akan mengantarkan wanita paruh baya ini keliang lahat sebelum waktunya.
Tetapi berkata bohong pun bukan solusi yang diinginkannya saat ini. Tentu ia tidak akan terus-terusan berbohong soal statusnya sekarang yang merupakan suami orang.
“Ibram,” lirih Mama Anindira. “Apa yang membuatmu ragu?”
Ibram menatap Anindira yang kini membuat pandangannya bertemu dengan kekasihnya itu. Anindira diam tanpa kata, sebab inilah yang ia inginkan juga.
“A-aku…,” ucap Ibram gelagapan. “Tante, tolong beri Ibram waktu.”
“Untuk apa?” Kening Mama Anindira berkerut dalam tanda terheran. “Kalian sudah 10 tahun lebih, untuk apa butuh waktu lagi?”
“I-itu… Ibram….” Ibram memejamkan matanya sejenak. Rasanya ingin sekali sebuah meteor tiba-tiba menghantamnya saat ini juga agar terbebas dari situasi yang menyudutkannya ini.
“Segera, Ma. Sehatlah dulu dan saksikan kami menikah.” Kali ini Anindira bersuara.
“Ibram, Tante butuh kepastian darimu.” Mama Anindira masih bersikukuh.
Ibram satu-satunya pria yang Mama Anindira percayai untuk anak semata wayangnya itu. Selama 10 tahun ini, dia begitu baik selalu hadir di sisi Anindira kala anaknya itu senang maupun susah. Selain menjadi kekasih, Ibram juga sudah berhasil menjadi sosok laki-laki yang menggantikan peran Ayah bagi Anindira.
Anaknya itu dulu begitu nakal dan frustasi merasa sudah dipecundangi oleh dunia, karena Ayahnya yang pergi memilih wanita lain. Tetapi, semenjak hadir Ibram di sisinya, Anindira kembali menjadi anak gadisnya yang penyayang lagi penurut.
“Segera, Tante,” lirih Ibram.
Rasanya Ibram sudah menjadi pria pecundang saat ini. Dia tidak bisa tegas untuk hidupnya sendiri. Bagaimana bisa dia berjanji sesuatu hal yang sangat mustahil untuk ia penuhi. Bagaimana nanti tanggapan keluarganya? Tanggapan Moira?
Apakah harus ada kursi ketiga di rumah tangganya?
***
Terima kasih sudah mampir dan meninggalkan jejak, jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza 😊
Jangan sungkan untuk memberi kritik dan saran ^^
Jika berkenan sila follow IG ku @ceritaarney *promosi ceritanya wkwk* nanti Insya Allah akan ku fullback :))
27 Juni 2019,
Arney


 itsarney
itsarney





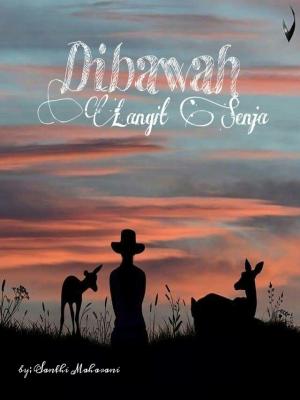


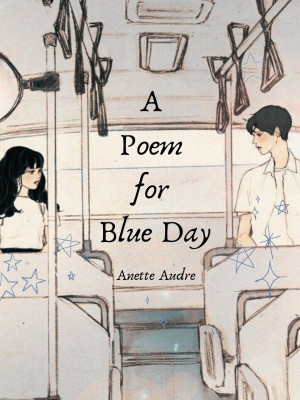

@itsarney akunku yurriansan. klo kmu mau mampir dluan boleh, aku bksln lmbat feedbacknya. krena klo wattpad bsanya buka pke lptop, aku gk dnload aplikasinya. dan lptopku lg d service
Comment on chapter BAB 1: Keputusasaan