Selamat membaca😊
۞۞۞
“Aku sudah capek berpura-pura di depan Mama.” Anindira menyimpan cangkir berisikan teh dengan keras ke atas meja.
Ibram yang tengah terpejam seraya memijat pelipisnya sontak membuka mata dan menatap wanita yang di hadapannya dengan nanar. Rasanya pendingin udara di ruang makan milik Anindira tidak berguna, sebab tubuh Ibram saat ini sangat kegerahan karena emosi yang sudah meluap. Marahnya ini tidak seratus persen karena Anindira, tetapi lebih kepada marah pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia tidak dapat mempunyai ketegasan untuk hidupnya sendiri. Dengan mudahnya ia berikrar janji sedang dirinya tak yakin bisa memenuhi.
Ibram menggeretakan giginya. Sungguh bukan keadaan seperti ini yang dia inginkan. Andaikan tak ada kehadiran Moira dalam hidupnya mungkin tak akan serumit ini, geramnya dalam hati.
“Ibram, aku butuh kejelasan tentang kita.” Rasanya kepala Ibram ingin pecah mendengarnya.
“Anindira… tidak bisakah kamu mengerti posisiku sekarang?” ucap Ibram menggeram ingin dimengerti.
Kepala Anindira menggeleng tak terima. Haruskah dirinya terus mengalah? Sedang selama ini rasa-rasanya ia cukup sabar dengan diamnya Ibram perihal hubungan mereka.
“Sampai kapan aku harus terus mengertikanmu?” tanya Anindira gusar. Detik berikutnya air meleleh dari kedua matanya. “Aku hanya minta kejelasan. Kamu lihat sendiri bagaimana kondisi Mama.”
Ibram mengusap wajahnya dengan kasar merasa frustrasi. Kejelasan seperti apa yang diinginkan Anindira? Soal janjinya yang akan menikahinya? Tidak bisakah wanita itu memberinya waktu barang sebentar saja untuk memikirkan semua ini.
“Apa karena kamu mencintai gadis itu? Sehingga kamu meragu untuk menikahiku?”
Bahkan pernikahannya saja dengan Moira belum genap satu bulan, haruskah dirinya menceraikan gadis itu? Hell, no! Ibram sudah janji kepada dirinya sendiri apabila dia harus berpisah dengan Moira maka itu harus atas permintaan Moira.
Soal perasaan pada Moira, Ibram sendiri merasa bukan cinta yang ia berikan kepada Moira selama ini akan tetapi lebih kepada rasa tanggung jawabnya saja. Toh, mereka juga tidak memiliki waktu perkenalan yang banyak, dan lagi selama ini rasa-rasanya jarang sekali mereka mengobrol karena sibuk dengan dunia masing-masing. Atau… dirinya yang sibuk sendiri?!
“Aku tidak mencintainya....”
Ibram menatap dalam Anindira yang sedang berurai air mata. Melihat Anindira seperti itu membuat Ibram melunak, bagaimanapun juga di sini yang tersakiti adalah Anindira gara-gara perjodohan, ah tidak, pembodohan ini. Wanitanya itu tak seharusnya juga berada dalam posisi seperti ini, harusnya Moira tidak hadir dalam hubungannya. Kedua kalinya Ibram menyesali kehadiran Moira.
“Lalu, kenapa kamu mau menikah dengannya? Kenapa kamu masih bertahan dengannya?”
“Aku menikahinya karena kamu yang tak kunjung menerima pinanganku… A-aku tidak bisa menceraikannya sebab pernikahanku dengannya seumur jagung pun belum.”
Anindira menghela napas dalam, air matanya yang berurai ia hapus dengan jari-jari tangannya. Hati kecilnya menyesal, andai ia bisa memutar waktu kembali ke saat-saat Ibram yang meminangnya maka dengan suara lantang ia akan mengatakan ‘iya’ dan kata ‘tidak’ hanya akan mejadi haram untuk diucapkannya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Tetapi, bukankah dirinya masih ada kesempatan?
“Ba-bagimana… kalau… kamu dan aku… kita….” Anindira berdehem membersihkan tenggorokannya yang terasa diganjal batu. “Aku rela jadi madumu.”
Ucapan Anindira barusan sukses membuat mata Ibram melotot. Apa yang dikatakan Anindira sama sekali tidak pernah terpikirkan olehnya. Tetapi… haruskah?
“Tidak akan semudah itu, An.”
Memikirkan gadis kecil seperti Moira dimadu membuat ngilu hati Ibram. Haruskah dia melakukannya? Tetapi Moira gadis yang baik, tidak mungkin ‘kan dirinya menolak?
Anindira menggigit bibirnya. Sejujurnya hal itu tak pernah menjadi cita-citanya, tetapi harus bagaimana lagi agar dirinya dapat memenuhi permintaan sang mama dan… memilki Ibram.
“Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya,” ucap Anindira. “Tentu kamu tidak mau ‘kan melukai kepercayaan Mama padamu?”
Ucapan Anindira barusan seperti sebuah ancaman bagi Ibram. Ah, Moira, haruskah jalan surgamu seperti ini?
Haruskah ada hati kedua dalam rumah tangganya yang harus ia muliakan? sedang hati pertama saja tak selalu ia abaikan.
***
Mata Fara tak kunjung lepas dari Moira yang sedang menyantap sepiring nasi goreng dengan perasaan enggan. Moira sedari tadi banyak melamun, bahkan beberapa kali sahabatnya itu tidak nyambung ketika diajak bicara. Sejujurnya Fara tergelitik untuk bertanya ada masalah apa sahabatnya tersebut, tetapi urung ia lakukan sebab Moira bukan tipe orang yang senang curhat kecuali memang betul-betul dirinya sudah tidak bisa menahannya lagi.
Suasana café pada saat jam makan siang begini memang terlihat ramai, tetapi suasana riuh tersebut tak mengganggu Moira yang terjebak dalam lamunannya. Rasanya seramai apapun dirinya tetap merasa kosong. Mengingat percakapannya tadi pagi dengan Ibram malah membuat perut sebelah kirinya menjadi sakit. Ah, nasi goreng yang membosankan di hadapannya itu kalau saja bukan permintaan perutnya yang terus berteriak minta diisi, tak akan Moira makan.
Perut dan napsu makannya sedang tak selaras sekarang.
Tiba-tiba mata Moira beralih pada Fara yang kini sedang gelagapan pura-pura menatap ke arah lain karena kedapatan tengah memperhatikannya.
“Ke-kenapa, Ra?” Moira terheran lalu mengikuti pandangan Fara dan tidak mendapatkan apa-apa.
Fara menggaruk hidungnya yang tak gatal. “I-itu… ta-tadi… bukan apa-apa.”
Moira mengerutkan dahinya seraya mencebik. “Aneh,” komentarnya pendek.
“Lo ada masalah apa sih?” Fara sudah tidak tahan, Moira harus dipancing.
Moira menatap Fara lama, bibirnya ia gigit tampak sedang menimang. Haruskah ia menceritakannya pada Fara? Tetapi selain di atas sajadah, Fara-lah satu-satunya tempat ia bercerita.
Sejurus kemudian kepala Moira menggeleng, dirinya merasa tidak perlu ia ceritakan urusan rumah tangganya selain kepada Allah. Moira tak mau memperkeruh keadaan dengan Fara yang ikut terlibat dalam cerita pilunya.
Cukup kebahagiaan yang dibagi, kesedihan jangan.
“Masalah Moira banyak, siapa sih yang enggak punya masalah?!” ucap Moira sambil tersenyum tipis. “Fara doakan saja biar masalah Moira cepet selesai.”
Fara mendengus, padahal dirinya sudah siap menjadi pendengar yang baik untuk sahabatnya itu. Jujur Fara bukan hanya ingin sekadar tahu mengenai masalah Moira, tetapi lebih kepada dirinya ingin membantu sahabatnya itu walau tidak menjamin dapat menyelesaikan masalahnya.
“Katakan pada masalah, sesungguhnya Allah Maha Besar dibandingkan dengannya.” Ucapan menyejukan Fara tersebut mampu membuat seulas senyum terbingkai dibibir kecil Moira.
Fara benar, ketika ada masalah jangan focus pada masalahnya tetapi fokuslah meminta pertolongan kepada-Nya.
***
Lamat-lamat telinga Moira mendengar suara langkah kaki seseorang yang kian lama kian mendekat ke tempatnya yang sedang berada di ruang tv. Benda persegi panjang di depannya itu sama sekali tak menarik minat Moira untuk menontonnya, ia menyalakan hanya untuk membunuh sepi.
“Assalamu’alaikum.”
Bersamaan dengan suara bariton itu yang mengucap salam, Moira membangunkan tubuhnya yang terbaring di sofa bed.
“Wa’alaikumsalam.” Moira menjawab seraya mengikat rambutnya yang lurus terurai menjadi seperti ekor kuda.
Ibram mematung di tempatnya sambil menatap Moira sehingga pandangan mereka bertemu. Semua perasaan berkecamuk dalam benaknya. Hati Ibram kian bersalah kala menatap mata Moira yang setenang danau itu. Mengapa gadis itu tidak berang melihatnya? Padahal sepanjang jalan Ibram sudah memikirkan bagaimana ia akan bicara dan menjelaskan semuanya pada Moira. Lihatlah sekarang apa yang ia dapati?
Tatapan Moira kian memperjelas bahwa Ibram adalah seorang pendosa yang tega meninggalkan istrinya dan memilih pergi ke tempat wanita lain. Ah, padahal kala di rumah Anindira dirinya begitu gencar menyalahkan kehadiran Moira. Tetapi mengapa setelah melihat mata Moira malah membuatnya merasa bersalah pada gadis itu?
Ah, persetan dengan semua ini! Kenapa perasaannya begitu mudah berubah-ubah?!
“Kita perlu bicara nanti, aku ke atas dulu.” Ibram tak perlu mendapatkan persetujuan Moira terlebih dahulu, dirinya langsung bergegas melangkahkan kakinya.
Moira menghembuskan napasnya kasar. Lalu tubuhnya ia gulingkan lagi ke sofa bed sampai suaminya muncul kembali. Moira kembali pada aktiviasnya yang menatap langit-langit rumah, sedang tv tak ia indahkan.
Apa yang akan mereka bicarakan nanti? Tentu Moira yakin bukan perihal sepele jika Ibram sudah berkata demikian. Moira harus menyiapkan hatinya barangkali suaminya akan mengabarkan hal buruk kepadanya. Siapa tahu? Sebab tadi pagi saja jelas-jelas suaminya memilih pergi walau tanpa izinnya.
Makin lama menjalani pernikahan ini makin terlihat jelas bahwa dirinya jauh dari Ibram. Mengingat fakta adik iparnya tak menyukainya makin membuatnya terlempar jauh dari Ibram. Belum lagi soal Anindira kekasihnya. Ah, tentu Moira tak akan menang melawan wanita itu.
Moira hanya memiliki Ibram di kartu keluarga saja, sedang raga dan hatinya milik orang lain.
Tak lama Ibram muncul dengan pakaian yang berbeda, kali ini pria itu mengenakan kaos berwarna merah dan celana chino selutut berwarna abu-abu tua.
Moira terbangun lagi, ia menghampiri suaminya itu yang masih berjalan. Ibram otomatis menghentikan langkahnya mendapati Moira menghampirinya. Tangan kiri Ibram diraih oleh Moira lalu gadis itu menuntunnya ke meja makan. Ibram menurut tanpa protes.
Moira membuka tudung saji yang memperlihatkan semur ayam yang menggugah selera. Menurut informasi dari Bunda, ini merupakan menu favorit Ibram.
Moira melepaskan genggaman tangannya pada Ibram lalu berkata, “Kita bicara setelah Mas Ibram makan.”
Ibram langsung menarik kursi untuk menyantap hidangan tersebut. Moira duduk di sebelah Ibram lalu mengalaskan nasi dan semur ayam ke atas piring.
“Kamu gak makan?” tanya Ibram terheran kala Moira mengalaskan nasi pada satu piring.
Moira menggeleng. “Sudah,” kilahnya.
Sejujurnya Moira tidak benar-benar berbohong sebab kata ‘sudah’ itu ia maksudkan pada makan siang tadi bersama Fara. Memang dirinya tidak sedang napsu makan.
Ibram kemudian menyantap makanannya dengan lahap sebab ingin segera menyelesaikannya karena ingin cepat-cepat berbicara dengan Moira.
Sedang Moira menatapnya dengan sendu. Otaknya berpikir perihal penting apa yang ingin dibicarakan suaminya sampai-sampai ia makan dengan terburu-buru.
“Moira,” panggil Ibram setelah menyelesaikan makan malamnya. “Kamu tidak bertanya alasan aku pergi tadi pagi?”
Moira menggeleng setelah beberapa detik terdiam. “Tidak perlu. Mas Ibram akan menjelaskannya.”
Moira paham betul pertanyaan Ibram tadi hanya sebuah basa-basi untuk membuka percakapan.
Ibram mengubah posisi duduknya yang semula menghadap meja kini menghadap Moira sehingga kini lutut mereka bersentuhan.
“Mama Anindira punya penyakit jantung,” kata Ibram.
“Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un….” Moira memegang dadanya seketika, merasa tahu betul bagaimana perasaan seorang anak yang mengetahui orangtua mengidap suatu penyakit.
“Tadi pagi kambuh, maka dari itu aku terburu-buru ke sana.”
Moira diam tak berkomentar, memilih menunggu suaminya melanjutkan cerita.
“Mama Anindira… beliau….” Ibram berdehem mencoba menghilangkan keraguannya. “Tidak tahu kalau aku sudah menikah.”
Tangan Moira yang sedari tadi memegang dadanya tak terasa tengah meremas baju tidurnya sekarang. Hatinya merasa pilu bak tertimpa beton kala mendengar penuturan suami. Harga dirinya sebagai seorang istri sudah terkoyak. Sampai hati Ibram menyembunyikan statusnya seperti ini. Moira melengos tak mau Ibram melihat wajahnya yang menyedihkan.
“Astaghfirullah…,” lirih Moira merasa pedih. Ibram sudah mencabik hatinya dengan sempurna. Mata Moira terpejam sambil mengigit bibirnya, menahan agar tangisnya tidak pecah.
Fakta bahwa Ibram masih memiliki wanita lain bisa ia terima sebab hakikatnya hati manusia tak dapat sepenuhnya dihuni oleh satu orang dan itu memberinya kesempatan untuk mendiaminya juga, menyingkirkan Anindira yang mengunggulinya. Tetapi, menerima fakta bahwa status pernikahannya disembunyikan sungguh segumpal daging dalam tubuhnya ini seperti ditikam belati bertubi-tubi tiada henti.
“Moira, dengarkan….” Ibram panik melihat Moira yang ringkih menangis di depannya. “Kamu tahu ‘kan betapa bahayanya penyakit jantung kalau mendengar berita yang mengejutkan?”
Moira tetap pada posisinya, enggan melihat Ibram walau pria itu berusaha menarik wajah Moira untuk menghadap wajahnya.
“Mama Anindira….” Ibram menjeda ucapannya sejenak. “Inginkan aku menikah dengan Anindira.”
Tangisan Moira kian terdengar pilu, bahunya terlihat naik turun. Tangis yang sedari tadi sunyi, kini bernyanyi meneriaki Ibram dengan rasa bersalah yang kian menggunung.
Tak lama terdengar suara Moira yang beristighfar berulang kali disusul dengan tangisnya yang mulai reda. Tangannya masih meremas bajunya seolah menahan sakit.
“Te-terus… Mas Ibram….” Moira menelan ludahnya coba menetralkan perasaannya yang sungguh mustahil. “Mau menikahi dia?” Moira enggan mengucapkan nama wanita itu saat ini.
“Aku berjanji demikian pada mamanya.”
Terdengar Moira mendengus pelan tak percaya bisa-bisanya Ibram berikrar pada wanita lain sedang dirinya masih dalam status pernikahan.
“Maksudnya Mas Ibram betulan mau menikahinya?” Moira mencengkeram lulut Ibram.
“Aku tidak tahu,” ucap Ibram seraya menggeretakan giginya. Kesal pada dirinya sendiri.
Moira membuka mulutnya tak percaya, ‘tidak tahu’ bukanlah kalimat yang ingin didengarnya. Kalimat tersebut bisa berarti bahwa Ibram tengah menimbangnya.
“Jadi….” Suara Moira bergetar tak sanggup rasanya mengucapkannya. “Mas Ibram mau ceraikan Moira?” lanjutnya pelan, tangan yang mencengkeram lutut Ibram ia tarik.
Ibram menggeleng lemah. “Bukan seperti itu… a-aku… memikirkan cara lain.”
Hati Moira rasanya terjatuh ke dalam perutnya.
“Apa… apakah….” Ibram berdehem, hati-hati sekali ia ia berkata, “Kamu mau dimadu?”
“Naudzubillahi min dzalik,” sahut Moira cepat. “Mas Ibram, istighfar!”
“Moira, bukankah itu sebuah sunnah yang dianjurkan?”
“Sunnah?” tanya Moira tak habis pikir. “Jangan dahulukan sunnah, ketika yang wajibnya saja belum Mas Ibram tunaikan. Kita belum genap sebagai suami-istri, tapi Mas Ibram sudah bertanya soal dimadu pada Moira.”
Ibram tertegun. Perkataan Moira begitu menamparnya kuat-kuat. Dirinya memang belum menggenapkan tugasnya sebagai seorang suami. Tak pernah sekalipun ia berpikir bahwa Moira akan menyinggungnya. Hal itu selama ini tak pernah menjadi kebutuhannya bersama Moira. Tetapi sebagai pria ia tak melakukannya jika tanpa dasar cinta. Anindira… masih mengusai hatinya.
“Tetapi, ini menyangkut nyawa seseorang, Moira.” Ibram berusaha melunakan hati Moira.
“Mas Ibram bisa jamin nyawa seseorang itu akan selamat dengan terjadinya pernikahan kalian?”
Ibram menatap Moira lekat. Gadis kecil ini tak dibayangkan olehnya mempunyai pemikiran yang diluar ekspektasinya.
“Kamu mau?” tanya Ibram hati-hati.
Mau? Coba tanyakan padaa ribuan istri di luar sana, maukah mereka? Tentu kata ‘iya’ menjadi haram untuk mereka ucapkan. Pun dengan Moira, ingin sekali rasanya meneriaki kata ‘tidak’. Tetapi, siapalah dirinya ini? Tak punya hak apapun soal Ibram.
Moira tampak memejamkan matanya. Ibram memperhatikannya dengan saksama. Tangan pria itu terulur untuk memegangi puncak kepala Moira. Jari telunjuknya mengelus pelan rambut Moira yang halus. Tatapan Ibram sendu melihat gadis ringkih di hadapannya ini. Sejujurnya ia tak ingin menyakiti siapapun, tetapi hidup bukannya seperti itu? Harus ada yang direlakan.
“Moira….”
Moira membuka matanya dan bertemu pandang dengan Ibram. Tak disangka pria rupawan di depannya ini begitu mengerikan, memberikan kesakitan bertubi-tubi kepadanya.
“Izinkan Moira jadi ibu dari anak Mas Ibram terlebih dahulu,” ucap Moira lemah seraya menunduk. “Jadikan Moira sebenar-benarnya istri untuk Mas Ibram.”
۞۞۞
Terima kasih sudah mampir dan meninggalkan jejak, jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza 😊
Jangan sungkan untuk memberi kritik dan saran ^^
29 Juni 2019,
Arney


 itsarney
itsarney









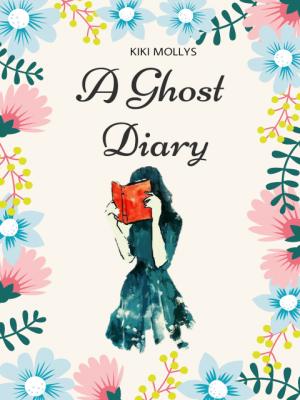
@itsarney akunku yurriansan. klo kmu mau mampir dluan boleh, aku bksln lmbat feedbacknya. krena klo wattpad bsanya buka pke lptop, aku gk dnload aplikasinya. dan lptopku lg d service
Comment on chapter BAB 1: Keputusasaan