Selamat membaca😊
۞۞۞
“Ibram!” pekik wanita parah bayu ketika melihat lebam di wajah pria itu. “Kamu kenapa?”
Ibram tak langsung menjawab, bingung harus mengatakan apa. Sebab jika ia katakan yang sejujurnya maka habislah dia. Begitu pun dengan Anindira yang terdiam membisu.
“Kenapa kalian diam saja?” tanyanya lagi gusar.
“Bukan apa-apa kok, Tante.” Akhirnya Ibram buka suara. “Lebih baik kita pulang sekarang,” sarannya yang disetujui dengan ragu oleh wanita paruh baya itu.
Hari ini Ibram diminta menemani Mama Anindira ke mal, dan tentunya Anindira ikut. Ibram tak bisa menolak permintaan wanita paruh baya itu. Mungkin kalian akan merasakan juga bagaimana rasanya jika sudah dekat dengan keluarga kekasih. Apalagi jika sudah 10 tahun.
Selain itu, Ibram tak bisa lepas begitu saja dari Anindira. Walau wanita itu dengan picik menjebaknya dengan bersandiwara bahwa dirinya akan segera melamar Anindira, dalam hati ia tak bisa menampik bahwa hatinya milik Anindira.
Namun belakangan ini, dirinya selalu dilanda perang batin. Di satu sisi ia ingin terus bersama Anindira, tetapi di sisi lain ada Moira yang kini surganya sudah berpindah ke telapak kakinya.
Mengingat nama Moira tak terasa tangan Ibram mengepal hingga membuat buku-buku jarinya memutih. Gadis itu sudah membuatnya berang hari ini, tepatnya Akmal. Hari ini menjadi pembuktian bahwa memang tidak ada yang namanya persahabatan antara wanita dan pria.
Sejurus kemudian Ibram mendengus, pikirannya itu membuat dirinya seperti pria yang tengah cemburu.
Tanpa disadari Ibram, Anindira ternyata sedari tadi memerhatikannya. Moira, geramnya dalam hati.
***
Sementara di tempat lain, seorang gadis tengah termenung sambil menatap langit oranye yang terhalang jendela kamarnya. Laptop yang berada di depannya ia abaikan.
Rencana untuk mengerjakan tugas kelompok ia batalkan dengan dalih ada urusan lain, dan meminta tugas bagiannya saja yang akan dikerjakannya di rumah. Namun, lihatlah dua jam sudah ia habiskan tanpa melakukan apa pun.
Moira mengeluh dalam hati. Begitu egoisnya waktu yang berjalan mendahului.
Pikirannya begitu kacau hingga tidak bersemangat untuk melakukan apa pun. Jangan tanya mengapa, tentu sudah jelas karena Ibram. Ah, ya dan juga Akmal. Tetapi Moira tak betul-betul menyalahkan Akmal sebab dirinya paham bahwa bukan tanpa alasan Akmal berbuat seperti itu. Namun tetap saja Moira tak membenarkan sikap Akmal yang lebih mengedepankan emosinya daripada logikanya.
Soal Ibram, Moira tidak tahu kecewanya ini oleh sebab apa. Anindira, kah? Tentu saja. Tetapi, ada perasaan lain yang tak Moira mengerti di sana. Moira bukan kecewa oleh sebab suaminya pergi dengan orang lain, lebih dari hanya karena status itu.
Mungkinkah ada perasaan lebih dari sekadar status sebagai suami istri yang selama ini tertanam di hatinya. Mungkinkah perasaannya ini condong pada kata perasaan seorang wanita pada pria? Entahlah Moira tidak tahu itu sebab ia belum pernah merasakan hal-hal seperti ini.
Derap langkah seseorang di luar kamar Moira memecah pikirannya. Sejenak Moira menimang tetap diam pada posisinya atau memulainya lebih dulu?
Sejurus kemudian kakinya menuntun untuk ke luar. Dirinya tak bisa terus seperti ini pikirnya.
Moira mengetuk pintu kamar Ibram dengan perasaan ragu seraya membawa wadah yang berisikan es batu dan selampai.
“Mas Ibram,” panggilnya memberanikan diri karena ketukannya tak kunjung dihiraukan.
Tak lama pintu terbuka hingga membuat Moira yang sebelumnya sudah gugup, kian gemetar sudah lututnya sekarang.
“Ada perlu apa?” tanya Ibram dingin.
“I-ini Moira bawakan es batu buat kompres lebam di wajah Mas Ibram,” jawabnya gugup seraya menunduk tak berani menatap Ibram.
“Tidak perlu,” terang Ibram sambil hendak menutup pintu kembali. Namun, sebelum itu terjadi Moira menahan pintu dengan kakiknya. “Apa lagi?!” ucap Ibram sedikit jengkel.
Aku harus bersabar hingga sabar tak dapat bersabar lagi denganku. Moira tengah membaca mantra agar dirinya tidak melampaui batas.
“Kita perlu bicara, Mas.” Hampir saja air mata Moira terjatuh kala berucap.
“Aku tidak sedang ingin bicara denganmu,” jawab Ibram ketus yang sejurus kemudian membuat tangis Moira terdengar. “Berhenti menangis. Jangan sampai karena tangismu itu setiap langkahku dikutuk oleh malaikat.”
Bukannya berhenti, air mata malah tambah deras mengalir di kedua pipi Moira. Bukankah itu seperti terdengar Moira yang bersalah di sini?
“Kalau begitu ijinkan Moira untuk bicara,” pinta Moira di sela tangisnya.
“Sudah kubilang, aku tidak ingin berbicara denganmu.” Ibram berucap penuh penekanan. Melihat Moira menangis di depannya tak sedikit pun rasa iba menerpa hatinya.
Perlahan kaki Moira yang menahan pintu ia tarik. Sepertinya percuma saja, toh pria di depannya itu enggan untuk berbicara dengannya.
Tak lama terdengar suara pintu yang dibanting dengan cukup keras membuat tubuh Moira tersentak kaget. Tangisnya kembali terdengar.
Bisakah matanya terpejam malam ini sedang suami tengah tak ridha kepadanya.
***
Dua hari sudah Ibram dan Moira saling diam. Bahkan di tahlilan ke-7 kemarin dulu mereka dengan gamblang menunjukan sikap tak akurnya membuat orangtua Ibram terdorong untuk bertanya.
“Kamu ada masalah dengan Moira?” tanya Bunda pada putranya waktu itu.
“Masalah bagi orang yang berumah tangga adalah hal biasa,” jawab Ibram enteng. “Bunda tidak perlu tahu. Biarkan kami selesaikan sendiri,” tambah Ibram sebelum ibundanya menyelisik lebih jauh.
Selama dua hari, Ibram dan Moira bagai dua orang asing yang tinggal dalam satu atap. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka, terkecuali ucapan salam. Walau begitu Moira tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, seperti mencuci baju Ibram, memasak, dan memberi ongkos pada Ibram.
Sebetulnya dalam hati ingin sekali Moira memulainya lebih dulu, tapi egonya lebih besar sehingga ia memberi pelajaran kepada Ibram dengan mendiaminya juga. Sepertinya stok sabar dalam dirinya mulai lenyap. Teringat perdebatannya dengan Fara siang tadi di kampus.
“Kalau lo berpikir sabar itu ada batasnya maka lo salah,” ceramah Fara. “Sabar itu tidak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti kita belum sabar.”
Mengingat itu Moira kembali dirundung rasa galau, perkataan sahabatnya itu benar. Tak seharusnya Moira berlaku sama seperti Ibram. Seharusnya dia terus mencoba untuk mengajak Ibram berbicara sehingga semua kesalahapahaman dapat disudahi, walau ditolak dirinya harus tetap berusaha dengan hati penuh sabar.
Soal Akmal, tadi siang Moira baru mau berbicara dengan laki-laki itu. Akmal meminta maaf kepadanya dan menyesali perbuatannya itu. Tetapi belum afdol rasanya jika Akmal tidak meminta maaf kepada Ibram langsung.
Tak lama suara adzan isya’ berkumandang membuat tubuh Moira tersentak. Kemudian gadis itu turun dari ranjangnya dan berlari kecil menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu.
Selepas shalat, Moira tak buru-buru untuk segera beranjak. Dibukanya mushaf Al-Qur’an untuk mencari ketenangan di dalamnya.
Gadis itu menyambung bacaannya yang dulu. Seketika ia tertegun sehabis membaca terjemahan ayat yang baru saja ia baca.
“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” (QS. An-Nahl: 126).
Tak terasa air mata Moira turun. Betapa angkuhnya dia telah merasa diri sudah sabar padahal belum, malah yang dia lakukan sama dengan yang apa Ibram lakukan. Sama-sama saling mendiami. Padahal sudah Allah terangkan bahwa sabar lebih baik timbang memberikan balasan yang serupa.
Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar diketuk. Moira diam sejenak, tak melanjutkan bacaannya untuk memastikan bahwa ia tak salah danger. Tak lama suara ketukan terdengar kembali.
“Mas Ibram,” ucap Moira tak percaya ketika membukakan pintunya. Air matanya yang tadi turun ia hapus terlebih dulu sebelumnya.
“Temani aku makan,” pinta Ibram dengan suara tenang bak tidak pernah terjadi apa-apa.
Moira sampai mengerjapkan matanya beberapa kali, takut-takut ini hanya halusinasinya. Dirinya merasa tidak percaya atas ajakan Ibram tersebut sebab hari-hari sebelumnya makan sendiri tak masalah.
“I-iya,” jawab Moira akhirnya dengan terbata.
Moira memenuhi permintaan suaminya dengan sebelumnya ia membuka mukenanya. Lalu, dilihatnya Ibram yang sudah berada di meja makan. Pandangan mereka bertemu dan tatapan Ibram membuat Moira salah tingkah sebab pria itu tak berkedip sama sekali.
Moira mengusap tengkuknya lalu tersadar kalau saat ini ia tak memakai kerudung. Pantas saja Ibram menatapnya begitu, mungkin suaminya itu pangling melihatnya begini. Kalau diingat-ingat selama pernikahan Moira belum pernah menampakan rambutnya yang tak berhijab pada Ibram.
Terdengar suara deheman Ibram memecah keheningan. “Maaf,” ujar Ibram sadar telah membuat Moira salah tingkah. “Aku pangling melihatmu seperti itu,” sambungnya.
Tak ada jawaban dari Moira sebab ia merasa bingung sendiri harus berkata apa. Lalu seperti inilah sekarang dia, hanya duduk memerhatikan Ibram makan hingga suapan terakhir.
“Banyak yang perlu kita bicarakan,” ucap Ibram setelah sebelumnya meneguk air putih.
“Mas Ibram mau menjelaskan semuanya?” tembak Moira langsung.
Ibram tak langsung mengamini pertanyaan Moira sebab ada beberapa hal yang tidak mungkin diceritakan. Soal lamaran itu misalnya. “Insya Allah,” jawab Ibram yang malah membuat Moira ragu.
“Jangan biarkan lidahmu itu digunakan untuk mengatakan sesuatu yang akan membinasakanmu kelak.” Moira langsung memperingati sebab tampak sekali keraguan pada air muka Ibram. “Biarkan Moira yang bicara,” pinta Moira.
Ibram menggigit bibirnya. “Baiklah, lepas itu biarkan aku yang bicara,” ucapnya mengalah.
“Moira akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Mas Ibram hanya boleh menjawab iya atau tidak,” ucap Moira tegas yang sontak membuat kening Ibram berkerut.
“Kita butuh komunikasi dua arah, Moira.” Ibram mengingatkan.
“Akan kita lakukan,” jawab Moira tenang. “Langsung aja, apa wanita itu pacar Mas Ibram?”
Ibram tentu tahu siapa yang dimaksud. “Begini, Mo−”
“Iya atau tidak?!” bentak Moira yang mengagetkan Ibram sebab baru kali ini ia mendengar gadis itu berbicara dengan nada tinggi.
“Iya,” jawab Ibram lemah. Hati Moira berkedut kala mendengarnya. Tapi dirinya harus kuat sebab itu adalah risikonya karena ingin tahu.
“Apa Mas Ibram masih mencintainya?”
“Iya.” Ibram tak mau menjadi seorang munafik.
Moira tampak memejamkan matanya sejenak. Ia mencoba untuk menetralkan emosinya. “Apa Mas Ibram berniat meninggalkannya?”
“Itu yang menjadi pertanyaanku juga,” terang Ibram seraya menatap Moira dalam. “Aku tidak tahu jawabannya.”
Sebetulnya Ibram tidak sepenuhnya tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebab jika ia mengikuti perasaaannya tentu tidak ingin yang akan menjadi jawabannya.
Terlihat Moira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ibram yang berada di seberang Moira menatap khawatir tatkala melihat kedua bahu Moira bergerak naik turun.
“Mas Ibram, maaf ‘kan Moira,” ucap Moira terdengar sambil terisak. “Maafkan Moira yang akan bersikap egois.” Moira menjeda ucapannya. “Moira akan tetap mempertahankan pernikahan ini bagaimana pun caranya. Moira tak akan biarkan siapa pun menggoyahkan perjanjian kukuh Mas Ibram kepada Allah dan orangtua kita.”
Ucapan Moira terdengar bak ancaman di telinga Ibram. Gadis itu telah sukses membuatnya diam tak bergeming. Padahal kehadirannya lah yang membuat janjinya pada Anindira sulit untuk ia penuhi.
Ibram bagai bertemu buah simalakama; dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu.
***
Terima kasih sudah mampir dan meninggalkan jejak, jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza 😊
Jangan sungkan untuk memberi kritik dan saran ^^
21 Juni 2019,
Arney


 itsarney
itsarney


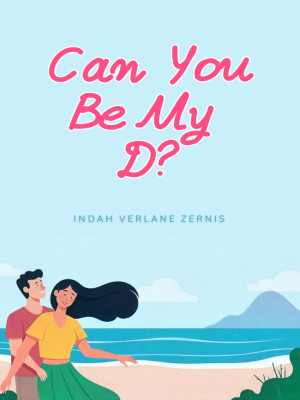







@itsarney akunku yurriansan. klo kmu mau mampir dluan boleh, aku bksln lmbat feedbacknya. krena klo wattpad bsanya buka pke lptop, aku gk dnload aplikasinya. dan lptopku lg d service
Comment on chapter BAB 1: Keputusasaan