Kemujuran yang tak terduga dari seorang pendeta muda meyakinkan Rei bahwa Dewa dan Dewi masih menyayanginya. Namun, kemujuran ini tidaklah lama. Ia memang lolos dari tagihan hampir empat ratus ribu itu, namun masih banyak penagih yang mengejar dirinya. Dengan sisa-sisa kekayaan, ia mulai memutar otak dan melatih lagi kemampuan bicaranya untuk menjual barang-barang yang ia miliki.
Suatu hari di tengah bulan Aktaver, ia bertolak ke Wellstrait dengan Neils. Hal ini memantik pesaing dan penagih hutang untuk berpikir bahwa kehancuran Rei makin dekat. Namun mereka salah, di awal bulan selanjutnya Arsiene dapat membayar lunas semua surat hutang yang disodorkan pada Rei. Dengan ini, mereka mengundur kehancuran Rei di bulan selanjutnya.
Rei mengorbankan segalanya: mulai dari perhiasan istrinya dan anaknya, koleksi-koleski vas bunga, bahkan jam klasik yang berada di ruang kerjanya. Tapi itu belum cukup, ia masih memutar otak bagaimana cara membayar tagihan empat ratus ribu itu.
Di lain hari, ia pergi ke kolega lamanya di Kota Trishti, meminta bantuan pada seorang sektretariat kota untuk meminjamkan uang sebesar itu. Sayang, dalam dunia bisnis tidak semudah itu; ia tidak bisa memberikan jaminan bahwa nominal uang yang sama akan kembali dalam kurun waktu satu tahun. Dengan itu, ia pulang tanpa membawa apa-apa, hanya rasa gelisah dan putus asa.
Satu bulan dari tenggat waktu yang dijanjikan. Selama tiga bulan sebelumnya, Rei bersyukur ia tak melihat mantan awak kapal dan kru karavannya; pertanda mereka mendapat pekerjaan lain yang mungkin lebih baik. Setiap hari, ia mencoba menghubungi kolega lain atau menjual barang-barang pribadinya di rumah.
Hingga di satu minggu terakhir, ia berhenti berusaha dan sering tersenyum dengan air muka tegar. Ia sering mengelus Nia juga istrinya yang tidak bisa bangun dari ranjang. Tak lupa, ia mengajak Niels dan Arseine untuk minum di malam hari, berbincang-bincang mengenai hal di masa hidup mereka.
Nia yang tak pernah mendapati perilaku ayahnya itu cepat-cepat mengirim sepucuk surat ke Albert, kakaknya. Ia berpesan agar Albert agar segera pulang dari asramanya di Kota Kesha dan mencoba untuk berbicara pada sang ayah. Lima hari kemudian—itu artinya satu hari sebelum jatuh tempo—Albert sudah sampai di Junier.
Malam itu, Albert langsung menerobos kerumunan dan berlari penuh tenaga menuju Mansion rumahnya. Nia yang tahu kepulangan kakaknya berlarian memeluknya dengan erat. Tak pernah Albert menemui Nia selemah itu dan sebuah firasat buruk tumbuh di hatinya, “di mana Ayah?”
Nia hanya menunjuk ke ruangan di ujung lorong atas. Albert langsung ke atas dengan berlari. Saat sampai, ia melihat dua sosok yang ia kenal: Arseine yang bijak dan Neils yang cerdas. Wajah mereka kisut, bahkan Arseine menitihkan air mata. Menyadari tuan muda mereka kembali, mereka lekas mengusap wajah mereka. “Tuan muda! Senang melihat Anda baik-baik saja,” papar keduanya.
“Baik-baik saja, Ser Arseine dan Neils. Dan kuharap Anda sekalian juga sama baiknya dengan saya.”
Keduanya tersenyum, “baik! Dan selalu baik, Tuan Muda,” jawab Neils. “Maaf, kami tak bisa menemani Tuan Muda; kami masih memiliki berbagai urusan di gudang.” Kedua insan itu pergi mendahului Albert dan hilang di tikungan koridor, meninggalkan Albert yang terpaku di depan pintu kayu ruang kerja ayahnya.
Tiga kali ia mengetuk pintu. Perlahan, ia mendorong pintu tak terkunci itu. Walaupun tak terkunci, namun rasanya berat untuk mendorong gagang pintu. Saat masuk, ia mendapati ayahnya sedang duduk di bangku seperti biasanya. Sejenak, sekelebat memori tersirat di pandangan Albert. Ia ingat betul bahwa di samping kanan-kiri ruangan itu terdapat dua rak buku-buku kesukaan ayahnya, juga vas antik di sudut ruangan, tak lupa pula batu lumos yang tergantung di tengah-tengah sudut ruangan sebagai penerang. Sekarang, tidak dari semuanya bersisa. Ruangan itu gelap, hanya tiga batang lilin dan sinar bulan sabit tua yang menyinari. Kosong dan sunyi, meninggalkan sosok ayahnya di bangku kerja, terduduk dengan pandangan mendongak menatap langit.
“Ayah....” sapa Albert memecah keheningan.
“Itu segitiga musim dingin, tanda bahwa salju akan turun beberapa hari ini, Albert,” ujar Rei, “itu hari yang sama ketika kau lahir di dunia ini. Bagaimana kabarmu, Albert?”
“Baik-baik saja Ayah. Beasiswa yang kuterima dari pemerintah membiayai penuh pendidikanku hingga selesai, bahkan aku sudah punya posisi untuk bekerja di pajak sebagai seorang akuntan.”
“Aku senang dengan kabarmu, Albert.... jadi kenapa kau pulang kemari? Bukankah akhir bulan ini kau ujian?”
Albert tak menggubris dan langsung menjawabnya, “Aku dengar kabar Ayah dari Nia. Dia memintaku untuk segera pulang dan bicara dengan Ayah atas keadaan ini,” Albert mengambil kursi dan duduk berseberangan dengan Ayahnya, “Ayah, kenapa Ayah tidak bilang? Kenapa Ayah menanggung beban ini sendiri? Jika Ayah bilang, pasti kubantu.”
Tangan hangat Rei memegang telapak tangan Albert, mengelusnya sembari menggeleng. “Tidak, Albert. Ini jalan Ayah; jalanmu masih ada dan mungkin tak sama. Simpan uang yang kau bawa di sakumu dan gunakanlah untuk kebaikanmu di masa depan.”
“Tapi Ayah, tidak ada masa depan bila kita hancur di sini!”
Rei mendesah halus, “kau benar anakku. Tapi kau salah di satu hal: tidak ada kata ‘kita’ di sini; hanya aku yang akan hancur. Sementara ibumu, kau, dan Nia akan tetap melanjutkan hidup.”
“Apa maksud Ayah?”
Suara ketukan pintu terdengar. Tanpa dipersilakan, dua orang masuk. Itu Arsiene dan Neils. “Seperti yang Anda perintahkan, Ser Rei, kami berhasil mendapatkan pembeli untuk Mansion ini.”
“Apa yang Ayah lakukan?” tanya Albert dengan berdiri lalu memegang pergelangan tangan ayahnya, “Ayah tak mungkin akan menjual rumah yang Ayah bangun dari awal ini, bukan? Ayah tidak akan menjual mimpi yang Ayah mulai dari nol di tempat ini, bukan? Jawab Aku, Ayah!”
“Albert anakku. Suatu hari kau akan mengerti bahwa impian di masa lalu tidak akan berlaku selamanya; kita suatu saat harus bangun dari mimpi dan melihat kenyataan. Dan sekarang, aku harus bangun dari mimpi, anakku,” Rei melongok ke Arseine, “terjual berapa, Arseine yang baik hati?”
“Lima ratus ribu. Kami beruntung sekali ada seorang pejabat muda yang tiba-tiba datang ke kantor pengurusan rumah. Baru saja kami akan menandatangani, orang itu berbicara dan tertarik dengan tawaran kami, pun membelinya dengan harga yang kami tentukan.”
“Kapan transaksi akan berlangsung?”
“Besok pagi.”
“Baiklah, kalian sekarang pergi beristirahat. Biarkan aku dan Albert berbicara di ruangan ini.” Dua orang itu balik kanan dan pergi dari ruangan, meninggalkan perbincangan keduanya.
“Albert anakku,” ujar Rei sembari mengambil sebuah pena bulu dan tinta. Tangannya mulai bergerak menggurat tinta hitam di atas kertas putih, “kau adalah pria terhormat; sama sepertiku. Kau mengemban nama keluarga ini kelak, tapi tak kusangka aku akan memberimu kewajiban semacam itu ketika kau berusia muda.”
Albert melirik secarik kertas itu, dari sana ia tahu apa yang ayahnya tulis: surat wasiat dan pesan terakhir. “Kau harus membahagiakan ibu dan adikmu, Albert,” lanjut Rei, “gunakan uang seratus ribu sisa penjualan mansion, tabunganmu, juga nanti gajimu itu untuk mengobati ibumu dan menyekolahkan Nia. Dan setelah kau berbahagia dan membahagiakan mereka, kelak kau akan berkata di depan makamku: ‘aku lebih bisa daripada ayahku dalam membahagiakan keluarganya.’ Alasanku memilih jalan ini ialah: jika aku masih hidup, kau dan Nia juga akan menanggung beban malu memanggul namaku, namun bila aku mati hanya tubuhku sajalah yang hancur namun tidak dengan kehormatan keluarga ini. Apa kau mengerti?”
Albert mengangguk lemah sebagai terhormat, bukan sebagai putra Rei. Sejenak, ia mengamati lamat-lamat. Dari air mukanya, Albert tahu bahwa orang tua itu penuh sungguh-sungguh dan telah bertekad bulat, ia tak bisa menghentikannya. “Oh, Ayah. Sebelum malam ini berganti esok, kumohon berkatilah aku dengan kasihmu untuk masa depanku.”
“Baiklah, anakku.” Kedua orang itu berpelukan di bawah siraman sabit tua. Hening selama lima menit, hingga Albert sendirilah yang melepas pelukan, merelakan sang ayah untuk pergi. “Jagalah ibu dan adikmu,” ujar Rei sembari menyodorkan sepucuk surat wasiat yang tersegel rapi itu. Dengan senyum sebagai pria, sosok Albert hilang di balik pintu kayu.
Ruangan itu lenggang, meninggalkan Rei yang berdiam diri menatap langit. Itu langit yang sama ketika ia masih seorang gipsi muda penuh semangat. Sebotol anggur pasti tersemat di tangan kanannya, juga api unggun yang menghangatkan tubuhnya di malam hari. Ah, masa lalu yang indah, namun jauh. Sekarang, ia hanya tertawa kecut mengingat kenangan itu; sudah bukan gilirannya. Sekarang waktu yang muda untuk bersinar dan yang orang tua sepertinya untuk meredup.
Rei tua tak bisa tidur bahkan sekedip. Malahan, ia menyibukkan dirinya dengan mengambil pistol lamanya, membersihkannya dengan kain basah dan memolesnya dengan halus. Itu pistol ketika ia masih seorang gipsi, dihadiahkan oleh seorang kawan. Ingin sekali ia mencoba berburu dengan pistol itu, namun tak pernah sekalipun ia mengisinya dengan mesiu dan peluru. Ironisnya, besok adalah kali pertama dan terakhir ia menggunakan pistol itu untuk mengakhiri hayatnya.
Dari balik Bukit Alliyun, sinar matahari mulai terlihat. Itu tanda tenggat waktu tinggal beberapa jam lagi. Suara ketukan mengembalikan Rei dari lamunannya, “masuklah Arseine!”
Arseine muncul dan menunduk, “Tuan, saya akan berangkat menuju kantor pengurusan tanah sekarang juga untuk menemui pembeli Mansion ini.”
“Berangkatlah Arsiene!” sebelum Arsiene benar-benar pergi, Rei bangkit dan mendekap pria tua itu. “Terima kasih Arseine, terima kasih kawan!”
Setelah dekapan itu, Arsiene undur diri dari hadapan Rei. Dengan langkah cepat, ia bertolak menuju Junier yang berjarak lima ratus depa dari Mansion itu.
Sesaat setelah Arsiene keluar dari Mansion, seseorang berbaju hijau masuk dari gerbang. Nia yang sedari tadi sudah bangun membuatkan sarapan untuk ibunya keluar dan menanyai orang itu, “ada yang bisa saya bantu?”
“Nona Nia?” tanya orang itu dengan suara yang Nia kenali.
“Betul, saya sendiri. Apakah Anda punya keperluan?”
Orang itu tak menggubris, malahan ia mengeluarkan sepucuk surat dari kantong di tas selempangnya. “Aku mohon Anda baca surat itu dan lakukan persis seperti yang surat itu perintahkan.”
Tanpa ragu, Nia membuka segel itu lalu cepat-cepat membacanya. Beginilah surat itu tertulis:
Segeralah pergi ke kuil terbengkalai di sisi utara bukit melalui jalan di berundak di sisi barat kota. Dari sana, Nona akan menemui kuil terbengkalai yang menghadap tepat ke lautan. Saat Nona masuk, lihatlah ke sisi timur dan Nona akan mendapati dua gundukan tanah lengkap dengan palang penanda pengganti nisan. Di salah satu dari keduanya, terdapat sebotol ramuan yang kubuat dan dompet lipat berwarna emas. Kumohon cepat sebelum lampu mercusuar di Junier padam, artinya sebelum jam kerja dimulai. Jika Anda lupa, kuuingatkan Anda dengan janji empat bulan lalu.
SI PENGEMBARA KESEPIAN
Tanpa pikir panjang gadis itu berlari menuju bukit demi memenuhi janji. Dengan gaun tidurnya, ia mulai menanjaki ribuan anak tangga dan akhirnya sampai di kuil yang dimaksud. Lekas ia menuju dua pusara berupa gundukan sederhana itu. Di sana tidak ada siapapun kecuali dirinya sendiri, membuatnya bertanya-tanya perihal siapa yang dikebumikan di tempat sepi semacam itu. Setelah ia berdoa untuk keduanya, ia mengambil dompet emas dan sebotol ramuan berwarna merah muda—semuanya tepat sesuai dengan apa yang dikatakan dalam surat.
Dengan berlarian kecil, ia menuruni undakan di bukit. Dari kejauhan, sinar matahari mulai menerang, mengalahkan sorot lampu mercusuar. Ia bergegas dan mempercepat derap langkahnya.
Saat sampai di rumah, ia langsung naik ke ruang ayahnya. Rei yang sedari tadi menunggu terkejut bukan kepalang dengan teriakan anaknya. Dengan cepat, ia membuka daun pintu demi menangkap sosok Nia. “Ada apa, Nak?”
“Papa! Lihat ini! Seseorang memberi ibu sebuah obat,” ucap gadis polos itu sembari menyodorkan dompet emas dan sebotol ramuan.
Samar-samar Rei pernah melihat dompet itu. Karena penasaran, ia perlahan membukanya. Di dalam sana tidak terdapat uang, namun sebuah kertas. Tangan Rei gemetaran karena tahu kertas itu. Saat lipatan kertas itu dibuka, Rei mendapati surat hutang atas nama dirinya kepada Keluarga Septim tercap “LUNAS”. Rei hampir jatuh menggelosor ke lantai, bertanya-tanya apa yang terjadi.
“Ayah!” sapa suatu suara dari lantai bawah. Albert datang dengan nada suara yang sama persis dengan adiknya, “ayah tak akan percaya ini sama diriku yang juga tak percaya; Paman Ariesh kembali, Ayah!”
“Apa maksudmu Albert?”
Albert tak menjawab dan menarik lengan ayahnya itu kuat-kuat. Rei tak punya kuasa untuk melawan dan menurut kemana putranya itu menuntun mereka hingga ke gudang belakang rumah. Di sana, Neils sudah lincah menurunkan kotak boks. Hidung Rei berkedut, mengenali bau dari boks itu. “Astaga itu rempah-rempah!”
Tidak hanya aroma rempah saja yang menyapanya, tapi juga kereta Karavan Palmite lengkap dengan Ariesh. “Demi Dewa dan Dewi, apa yang sedang terjadi?!” seru Rei dengan rasa tak percaya. “Pasti aku sedang tertidur dan bermimpi!” imbuhnya.
Belum usai keterkejutannya, Rei dikagetkan dengan suara lain yang ia kenal, itu suara Arsiene. Orang berumur empat puluhan itu berlari tergopoh-gopoh sambil memanggil Rei. “Ser Rei! Avem, Ser Rei! Avem bangkit dari lautan dan sekarang berlabuh di Junier!”
Rei yang terduduk di tanah langsung bangkit. Matanya membuncah. Ia sadar bahwa ini bukan mimpi. Dengan kedua langkah kakinya, ia berlarian menuju pelabuhan. Saat turun, beberapa orang bersorak: “Avem telah kembali!”
Rei tak mempercayai kedua bola matanya bahwa kapal itu sedang berlabuh. Warna layar, struktur kapal, tulisan “Avem” di lambung kapal, dan patung Dewi Fortunie di haluan tak membuatnya pangling. Itu sebuah kapal tiruan Avem yang paling sempurna bahkan dengan anggota kru dan barang bawaan yang sama: kain sutra.
“Ser Rei!” sapa Burdier yang berdiri di depan roda kemudi. Dalam langkah cepat, ia turun ke geladak lalu ke pelabuhan. Langkahnya pincang, namun kaki kayunya itu tidak mengurangi kelincahan sosoknya. Saat sudah dekat, Burdier menyalami majikannya itu dan dibalas dengan sebuah pelukan dari Rei sendiri.
Salju pertama turun ke Junier sewaktu Rei beserta keluarganya bersyukur di pelabuhan, seseorang dari ujung mercusuar melihati mereka dengan tersenyum. “Dalam dunia yang busuk ini, masih ada orang sebaik Anda....” itu si pendeta muda yang beberapa hari ini mengaku sebagai utusan Septim. Si pendeta itu ingin rasanya segera turun, namun ia berbalik lagi dan berkata, “terima kasih telah berbaik hati pada ibuku dan juga mati-matian membela ayahku, Ser Rei.” Si pendeta melongok ke arah Kuil Junier yang ketepatan di sana sedang berlangsung pesta pernikahan, “dan untuk Anda Ser Leris, terima kasih juga telah membela mayat kami dari amukan Junier saat itu. Anda mendapatkan hal yang pantas. Selamat tinggal kalian berdua, selamat tingal wahai rasa syukur! Semoga Dewa dan Dewi memberkahi apa yang telah anda perbuat dan apa yang akan anda perbuat nantinya!”
Sosok itu membaur dengan lautan manusia, namun mata seseorang yang jeli dapat melacaknya ketika ia berjalan menuju Grende, lalu benar-benar tak lenyap di balik tirai pepohonan Grende.


 KurniaRamdan39
KurniaRamdan39

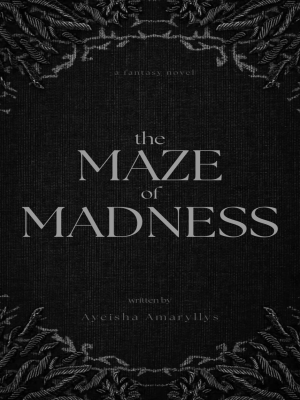









ntap
Comment on chapter Fiveteen: Persona