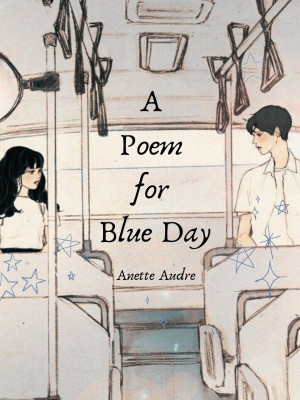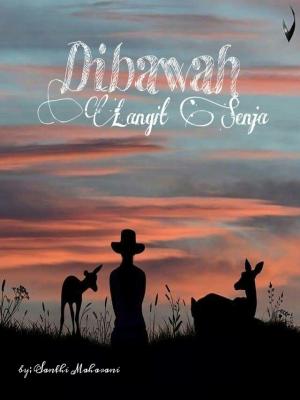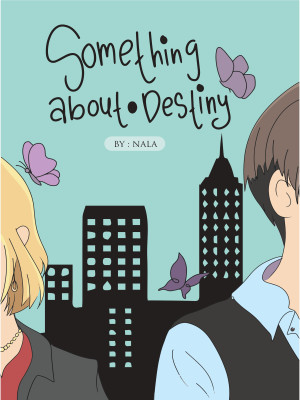“Kematian adalah takdir, tidak ada siapapun di dunia yang dapat mencegah maupun mengundurnya. Seperti halnya sebuah baterai, hidup manusia selalu tergantung pada keputusan Tuhan. Bagaimanapun, ruh mereka akan kembali kepada-Nya. Sebuah hukum kehidupan yang tidak pernah tertulis, namun selalu terjadi di sekitar kita.”
Pria itu manggut-manggut. Entah dia memang mengerti atau telah lelah mendengar ocehan manusia renta dihadapannya, yang setia pada posisi yang sama sejak pagi buta. Dan sekarang, petang tiba. Bayangkan, betapa kokohya kaki dengan sendi yang telah menopang tubuh puluhan lalu tersebut?
Tuk! Lengan yang kulitnya telah keriput terlihat menutup permukaan buku dengan spontan, lantas meletakkan di antara barisan koleksi filsafat lain pada rak di sisi ruangan. Ia melepaskan kacamata, kemudian menyeruput kopi yang telah dingin sejak berjam-jam yang lalu. Entah, sudah seperti apa rasanya. Tapi bagi dia yang telah lapuk dimakan usia, indra perasa sudah tidak lagi mempedulikan. Kenikmatan kopi pahit itupun tidak begitu nyata, mungkin sel-sel lidahnya juga lelah mengikuti tuannya. “Mengantuk?” katanya memecah keheningan. Tentu saja, selama seharian hanya dirinya yang bersuara di sana. Dengan niat awal berdiskusi, malah berakhir menceramahi. Sungguh, dia tidak tahan dengan situasi yang rumit seperti ini. Jika bukan karena rasa iba, ahh ... hatinya kelu jika berhadapan dengan anak itu.
“Hmm,” gumam pemuda dengan kulit seputih salju tersebut. Tatapannya sayu, ditambah badannya yang tegap bak binaragawan-yah, memang dia sebelumnya pernah mendaftar ABRI, namun mundur karena suatu hal-tampak rapuh. Ia tak ubahnya mayat hidup dengan kondisi begitu.
“Kau menghindari kontak mata denganku lagi,” keluh lelaki renta tersebut, setelah mendengar respon anaknya yang bahkan tidak mengeluarkan sepatah katapun. Dirinnya menepuk-nepuk punggung anaknya perlahan. “Harusnya kamu malu dengan umurmu. Haish, ayah seperti sedang berhadapan dengan kamu lima belas tahun yang lalu.”
Pemuda itu hanya terdiam, lantas menatap ayahnya dalam, “Maaf jika Ferd selalu menyusahkan Ayah, bahkan sampai sekarang.” Ferdian Nabastala, seorang pengusaha kuliner terkenal di era metropolitan, menangis sesenggukan. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia lakukan dihadapan kekasih hatinya, yang ia cintai seluas bentangan semesta. Hal ketiga setelah Tuhan dan orang tuanya. “Aku memang payah.”
“Sudahlah, sampai kapan kamu jatuh seperti ini, hah?” ujar ayahnya, dengan volume yang ditingkatkan. “Bukankah yang kulakukan seharian-mengucap semua kalimat penuh makna kehidupan-sudah seperti omong kosong bagimu? Janganlah seperti in, Ferd. Hidup harus tetap berlanjut, hingga tiba waktumu menyusul dia.”
“Hidupmu harus tetap berlanjut, meski aku akan pergi lebih dulu.”
Sesak kalbu Ferdian, merasakan hatinya tersayat seperti tergores belati yang tajam. Iris kelabu yang amat berbeda dengan dirinya, cukup kontras jika iris cokelat miliknya bersanding. Bibir semerah mawar, senyum seindah gugusan bintang di langit, juga ... pelukan sehangat mentari. Bagaimana caranya melupa, sedang kenangan hidup seperti sengaja memberinya efek jera, datang bertubi-tubi dan menghantui di kala fajar hinggap hingga senja tiba. Bahkan tak segan merayap di antara bunga tidur, mencipta perasaan kalut berkepanjangan seakan sosok gadisnya meminta agar namanya tetap di hari Ferdian, menyiksa lelaki itu dengan doktrin cinta yang masih bertebaran? Oh, shit. Mungkin kegilaan tak lama lagi akan mampir kepadanya.
“No, no, no,” seloroh sang ayah tiba-tiba. Ferdian menoleh, dia bahkan lupa bahwa pria tersebut memiliki kemampuan yang kini membuatnya merasa gerah. Dia tidak bisa leluasa bernostalgia dengan memoar siluet perempuan yang bersemayam tetap dalam pikirannya. Terlebih jika Rahmat Adiguna-ayahnya-tersebut mulai mengulik apa yang terbesit dalam benak yang berlabel privasi itu. Bodohnya, sudah tahu begitu Ferdian malah menatap bola mata yang menjadi perantara ayahnya untuk menguak segala rahasia batin yang ia rasa. Memang bodoh kau, Ferd! “Orang gila ingin menjadi normal dan hidup seperti kebanyakan makhluk di muka bumi. Dan kamu yang terlahir sehat bugar serta tinggi semampai, tampan, kuat, pintar, kaya-“
“Rajin menabung, badan bagus, punya ayah ganteng se-antero dunia. Terus, apa lagi?” sela ferdian meneruskan kalimat ajaib yang hampir setiap waktu selalu di agungkan ayahnya dengan bangga dan tidak tahu malu. C’mon, buat apa semua titel keduaniawian itu selalu dibanggakan? Toh, mati juga malaikat bahkan tidak akan memanggil dengan nama kita. “Leave me, Dad. Beri aku sedikit waktu untuk ...”
“Untuk apa? Untuk menyiksa dirimu sendiri, supaya malaikat pencabut nyawa berbaik hati memajukan hari kematianmu? Are you kidding me, Son. Kau pikir warisanmu nanti untuk siapa!”
Oh, Dad. Bahkan orang patah hati pun malah ngomongin warisan. “Thank you, Dad. Anda sangat menginspirasi saya untuk terus menyendiri.”
“Ho ho ho, semakin lama mirip Angry bird,” kelakar Rahmat lantas kembali ke tempat duduknya dan menghabiskan kopi yang tinggal seperempat gelas.
“Stop it!” gertak pemuda itu gusar, yang dibalas tawa renyah ayahnya dihadapan. Rahmat memang cukup tua, telah lewat setengah abad umurnya, tapi sifat dan kelakuan sungguh layaknya anak muda. Dan Ferdian benci tentang fakta itu pada saat seperti ini. Untung orang tua sendiri!
“Ah, iya,” ucap Rahmat kemudian, “Ibumu meminta kamu untuk pulang. Rumah ini kamu jual atau kontrakan saja.”
Mata Ferdian terbelalak. Seluruh kebahagiaan tercipta di tempat ini, yang awalnya hanya sepetak tanah ketika dirinya belum sesukses sekarang. Dengan kata lain, sebagian hidupnya adalah rumah ini! “You know that i can’t. Please, Dad. Ayah berkata seakan tempat ini aku beli baru beberapa hari saja ....”
“So,” balas Rahmat dengan wajah masam, “Kamu mau hidup tidak karuan di sisa usiamu? Kamu bahkan tidak memikirkan ayah atau ibumu, huh!” Rahmat berlagak merajuk. Dia paham betul bagaimana beban mental anaknya sekarang. Tapi sungguh tidak pantas jika hanya karena hal tersebut membuatnya menyia-nyiakan kehidupan. “Kau seperti tidak menghargai pengorbanan-“
“No, Dad. Maksudku ...” Ferdian terecekat. Kalimat yang hendak dikeluarkannya terasa menyangkut di tenggorokan.
“I want to say, you’re not alone ... I’m here. You’re have Mom and Dad. Yahh, itu juga kalau kamu masih mau melihat kami. Angry Bird.”
“Oh, Dad. Please ...,” keluh Ferdian dengan suara parau. Sebulan menyendiri mungkin mulai berpengaruh pada kesehatannya, dan Rahmat sudah memperkirakan hal itu sebelum memutuskan kembali membujuk sang anak untuk keluar dari keterpurukan. Dan entah sudah keberapa kali.
Rahmat menghela napas, kemudian bangkit dan melanjutkan, “Go home, Son. Hmm, mungkin besok atau lusa. Pokoknya kalau perasaanmu sudah baikan. I’ll show you about something.” Rahmat berlalu menuju pintu, kemudian berbalik sebentar, dan matanya bertemu dengan Ferdian yang masih bimbang. “Jangan lupa makan, Ferd. Ayah dan ibu menunggumu di rumah, Bye!”
Sepeninggal ayahnya, Ferdian semakin gusar. Ia mendesah dan bergumam lirih berkali-kali. Dilihatnya suasana bangunan yang memang sebulan ini tidak terurus, apalagi assisten rumah tangganya juga pulang kampung karena tidak kuat menanggung kesedihan mendalam. Pembantunya saja terguncang seperti itu, bagaimana dengan dirinya?
Dunia begitu luas, dan satu hal yang pergi telah mengubahnya menjadi seperti ini. Seakan semesta menelannya bulat-bulat. Seperti waktu bergerak lambat, dan memutar cuplikan dokumenter penyiksaan batin yang teramat merusak psikis. Yah, kondisinya lebih buruk dari itu. Sudah ia putuskan, dirinya akan datang ke rumah orang tuanya, paling tidak menemui sang ibu. Tentu saja, seperti kata ayah, mereka sama berharganya dengan belahan jiwa yang telah hilang. Mungkin datang kesana dapat memberinya sedikit ketenangan.


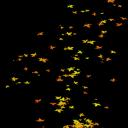 PenaLara
PenaLara