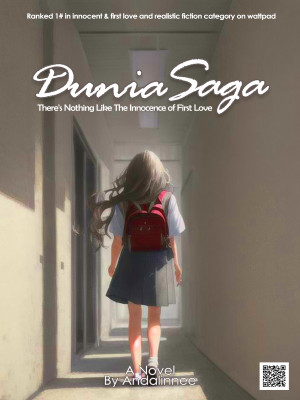Hal yang tak pernah aku lihat dari seorang Arza adalah hatinya. Selama ini aku hanya melihat dia seperti sebongkah es yang berjalan. Tiga tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mengenal seseorang namun yang aku ketahui tentangnya tidaklah sebanyak apa yang aku ketahui malam itu. Berbicara mungkin cara terbaik untuk mengetahui semua, hanya saja entah itu kebohongan atau kebenaran, aku tetap tak dapat membedakannya.
“Jika diperlakukan dengan buruk kenapa tak melawan?” tanya laki-laki itu memecah keheningan. Aku tengah berada di dalam mobilnya, duduk di bangku depan karena tak ada pilihan. Aku hanya menjadi boneka sejak kejadian di sekolah hingga mengetahui kebenaran tentang Jia. Semua kenyataan itu rasanya terlalu sulit untuk aku cerna, sementara tubuhku belum pernah menelannya. “Akan sulit bagi orang polos bertahan di dunia ini!”
“Aku bukan orang yang polos!” sahutku tak setuju. Arza tampak melirik sedikit dari kaca spion sebelum kembali fokus mengemudi. “Aku tidak seperti apa yang kau lihat!” lanjutku lagi.
“Kau benar! Matamu itu mungkin terlalu ambisius jika dikatakan sebagai seseorang yang polos.” Cibirnya membuatku sedikit tersinggung. Aku menggeser posisi dudukku sedikit mendekati jendela karena merasa tak nyaman. Mobil yang dikendarai Arza mungkin bukan Koenigsegg CCXR Trevita–nya yang mewah itu, melainkan sebuah audy yang lebih sederhana dari mobil mewah miliknya yang lain. Akan tetapi bagiku kedua mobil itu tetapsaja terlalu berlebihan untuk seorang anak SMA. Apalagi hanya sekedar pergi ke rumah sakit.
“Kau tidak tahu apapun tentangku! Kau juga pasti seperti yang lainnya bukan? Membenciku...”
Arza diam sejenak. Tak langsung menanggapi perkataanku. Barangkali dia mungkin sudah kehabisan kata-katanya untuk menyudutkanku. Aku tidak bisa membaca apapun eksepresi muka laki-laki itu karena pada kondisi apapun air mukanya tetap datar. Setelah mobil berbelok di sebuah tikungan, Arza kembali berdehem. Aku tidak terlalu tertarik lagi menunggu jawabannya.
“Awalnya mungkin kau benar! Aku memang membencimu…” ujarnya tanpa sedikitpun canggung. Aku merasa dadaku dihantam dengan keras. “Tatapan mata dan wajahmu terlalu mirip ibumu. Dan itu membuatku membencimu.” katanya lagi.
Aku menggenggam jari-jari tanganku dengan erat untuk menahan rasa nyeri akibat hantaman kata-katanya. Semua memang bermula dari ibu. “Tapi aku bukan ibuku… dan aku berbeda darinya!” sanggahanku untuk menolak semua perkataannya tentangku. “Aku juga tidak pernah meminta untuk dilahirkan sebagai putrinya, aku tidak bisa memilih itu. Lalu apa salahku sebagai putrinya?”
Bibir Arza kembali mengatup seperti semula. Matanya pun hanya terfokus pada jalanan malam yang tak terlalu ramai. Dia selalu mengambil jeda cukup lama disaat aku mulai meledak karena perkataannya tapi disaat aku sudah mulai tenang, dia kembali memancingku dengan kata-katanya. Aku pun merasa tak ingin berlama-lama lagi di dalam mobil itu.
“Kau tidak salah apa-apa!” katanya. Dia sangat penuh kejutan. Awalanya menyudutkanku lalu tiba-tiba membenarkan perkataanku, dia seperti orang yang tengah berada dalam sebuah gejolak untuk memihak siapa yang benar dan siapa yang salah.
“Kau berhak menuntut keadilan pada hidupmu dan jangan biarkan seseorang pun mengadilinya tanpa pembelaanmu.” Ucapan Arza malam itu. Aku tak sempat menyahuti kembali ucapannya karena mobil itu telah berhenti di pelataran rumah. Dia tidak mengantarku ke asrama, melainkan pulang ke rumahnya karena tahu bahwa gerbang asrama telah ditutup setelah tengah malam.
Dia benar-benar seperti orang yang begitu berbeda hari itu, karena esoknya semua terasa kembali seperti semula. Dia bongkahan es yang berjalan hanya melewatiku tanpa sepatah katapun. Aku tidak terlalu bingung karena pada dasarnya memang seperti itulah perlakuan Arza kepadaku. Hanya saja hari itu ada hal yang berbeda aku rasakan, aku tak melihat Jia. Entah dia sudah siuman atau belum, aku juga tak mengetahuinya. Arza mengatakan beberapa tentang Jia malam itu dan salah satunya adalah penyakit gadis itu.
“Dia menderita lupus sejak lama dan kata dokter itu dapat kembali kambuh sewaktu-waktu. Aku tak tahu apakah setelah ini dia masih ingin sekolah atau tidak, mengingat dia seharusnya menjalankan program home schooling yang telah diatur orang tuanya. Gadis itu keras kepala tapi juga lemah. Jadi apakah kau akan membencinya karena semua ini?”
“Aku juga sama sepertimu pada awalanya, aku ingin membalas ibumu melalui dirimu namun setelah aku pikir-pikir, itu sama sekali tidak masuk akal. Dan aku tidak berniat lagi untuk melakukannya.” Ucapan Arza padaku malam itu. Aku kembali memikirkannya. Dia memintaku melawan tapi dia secara halus berusaha mencegaku membalas Jia. Dia seperti Miko yang begitu mengkhawatirkan gadis itu, meskipun di luar dia seakan tidak peduli. Aku pun menjadi penasaran tentang hubungan Jia dengan Arza di masa lalu.
*****
“Aku tidak melihat Jia hari ini?” ujar gadis berambut pirang yang duduk di bangku paling depan. Dia berbisik-bisik ketika aku melewatinya. Dan aku sengaja mengecilkan suara musik di earphone-ku agar dapat mendengar perkataan mereka.
“Entahlah… aku juga tidak tahu! Lagipula siapa yang peduli dengan Jia. Aku hanya berteman dengannya karena kelurganya cukup terpandang. Dia kan anak pemilik sekolah ini…” sahut gadis di sebelahnya. Aku tidak terlalu menghafal nama-nama mereka meskipun hampir satu semester aku berada di kelas itu. Jika tak salah namanya Merisa, dia salah satu penggemar Arza yang paling fanatik. Sementara gadis pirang berwajah setengah bule disampingnya adalah temannya yang bernama Sarah. Mereka satu kelompok dengan Jia di beberapa kegiatan kelas sehingga cukup akrab dengan Jia.
“Itu juga aku tahu. Aku juga hanya terpaksa baik padanya. Dia itu menyebalkan! Kalau aku tidak menuruti kemauannya untuk satu kelompoknya, dia pasti mengancamku akan mengeluarkanku dari sekolah ini!”
“Seandainya dia tidak perlu ada di sekolah ini! Kita pasti juga tidak perlu mengikuti setiap perintahnya. Aku merasa hanya membuang-buang waktu saja mengerjai si anak pelakor itu! Arza… sepertinya membela anak itu.”
Aku menggebrak mejaku dengan keras hingga membuat beberapa anak di dalam kelas itu menatapku, termasuk Melisa dan Sarah. Dia tampak tak menyadari jika aku mendengarkan pembicaraan mereka dari awal. Ternyata kedua gadis tengil itu juga ikut ambil bagian saat mengerjaiku di gudang, ditambah mereka juga tak benar-benar tulus berteman dengan Jia. Aku paling tersinggung dengan seseorang yang tega mengkhianati temannya sendiri.
“Apa yang kau katakan tadi? Apa semua itu benar?” tanyaku begitu sampai di samping mejanya. Kedua gadis itu hanya melirikku datar tanpa berniat menjawab pertanyaanku.
“Aku tanya padamu! Apa kau yang mengunciku di gudang kemarin?” kali ini aku tak dapat menahan suaraku lagi. Melisa yang tak terima dengan ucapanku pun serentak berdiri. Dia melipat kedua tangannya di depan dada dan menatangku. “Memangnya kenapa jika semua itu benar? Apa kau marah? Sejak kapan anak seorang pelakor sepertimu mempunyai hak untuk marah?” katanya mencibirku.
Aku tidak terlalu tersinggung dengan perkataan itu. Namun gadis itu tampaknya memang sengaja ingin menguji kesabaranku. “Kau yang lahir dari rahim kotor! Apa kau tak malu menampakan wajahmu seperti ini? Kalau aku jadi kau, aku pasti akan memilih bunuh diri dari pada hidup dengan seorang ibu yang memalukan seperti itu.”
Mereka yang berada di kelas itu pun tampak tak keberatan dengan kata-kata pedas yang di ucapkan Melisa, bahkan tatapan mata mereka pun seolah lebih menyudutkanku. Aku tidak mampu lagi menahan amarahku. Mereka seperti para Haters yang memenuhi kolom media sosialku.
“Sayangnya aku bukan kau! Mana mungkin aku bunuh diri? Paling aku hanya akan membunuh orang-orang yang menghinaku.” Bukanya takut dengan ucapanku, Melisa dan Sarah justru tertawa renyah. Dia mengacungkan jari tengahnya di hadapanku.
“Ihh… takut! Apa kau takut Sarah?”
“Ih… aku takut!” cibir mereka.
“Sepertinya ibu dan anak akan sama saja! Sama-sama sampah masyarakat!”
Kedua gadis itu tak henti-hentinya mencercaku. Itu membuat lepas kedali hingga tanganku tanpa sadar telah menjabak rambutnya. Aku tidak bisa lagi menjadi seseorang yang pendiam seperti protagonist-protagonis di sinetron. Aku juga tidak peduli dengan posisiku di sekolah ini. Semua anak-anak itu seharusnya menyesal karena berurusan denganku.
“Sakit… sakit… lepaskan! Lepaskan!” rintihan manja Melisa yang berusaha melepaskan diri. SeluruH kelas pun tampak terkejut, bahkan beberapa anak yang berada di luar kelas ikut menyaksikannya. Sarah yang melihatnya juga tak tinggal diam. Dia berusaha menjambakku namun aku berhasil menghidar. Aku malah menendan dadanya hingga tersungkur.
“Lepaskan aku! Dasar sampah! Apa kau memang jalang ibumu?” racauan Melisa. Dia tidak tahu apa-apa soal ibuku, bahkan saat rumor tentang ibuku meledak di media dia juga masih seumuran denganku. Bagaimana mungkin gadis sepertinya bisa mengeluarkan kata-kata tak pantas seperti itu.
“Aku sudah memperingatkanmu! Kau pikir aku hanya bisa diam? Aku bahkan tidak melaporkan kalian karena mengunciku di gudang tetapi aku tidak bisa terima jika kau menghina orang yang tidak ada hubungannya denganmu!” peringatanku padanya. Seluruh kelas hanya memperhatikan kami berdua, bahkan tak ada satu pun yang sudi melerai pertengkaran itu. Mereka semua memang sampah. Hanya keluarga mereka saja yang terpandang, sementara mereka tidak mempunyai hati.
“Lepas!” teriak Melisa kembali merontah. Aku menarik rambutnya lebih kuat dan menghempaskannya hingga ke sudut kelas. Dia tampak kesakitan tapi aku sudah gelap mata hingga tak sedikitpun merasa kasihan. Peran kami dalam drama kelas itu pun berbalik dimana aku yang kini menjadi antagonis-nya.
“Kau… benar-benar liar! Apa semua anak rendahan sepertimu memang tidak tahu diri?” dia tampak tidak kapok dengan perlakuanku. Aku tak tinggal diam dan kembali menghampirinya. Melisa berdiri sesegera mungkin. Dia menamparku tetapi aku kemudian membalasnya lebih keras. Aku hendak meraih kembali rambutnya untuk memberi pelajaran pada gadis itu namun sayangnya wali kelas kami Bu Marini memergoki keributan itu dan melerai kami.
“Apa yang kalian lakukan di dalam kelas ini? Freya! Kau sudah cukup keterlaluan!”
Anak-anak di dalam kerumuanan itu pun membubarkan diri. Sementara aku dan Melisa berakhir di ruangan wali kelas kami. Aku tidak terlalu sadar dengan yang aku lakukan, bahkan aku merasa seperti bukan seperti diriku. Akan tetapi entah mengapa jiwaku terasa begitu bebas, terlepas dari belenggu yang selama ini membuatku sulit untuk menjalani hidup sebagai seorang anak pendosa.


 sylviayenny
sylviayenny