Papa benar, aku lebih hebat dari superhero manapun. Hanya saja, aku takut menghadapi kenyataan—Revandira Papinka.
***
Harzel terperangah melihat mobil hitam terparkir di depan rumahnya tepat pukul delapan pagi. Tak lama kemudian, Revan keluar dari sana sembari melepaskan kacamata hitamnya.
Harzel menyerngitkan dahi, “Itu mobil siapa?” tanya Harzel heran. Setaunya, Adrian tidak pernah memiliki mobil selama lelaki itu menjadi tetangganya.
“Gue pinjem mobil Bimo,” jawabnya, “Ayo!”
Harzel dan Revan melenggang masuk ke dalam mobil. Seketika, hembusan air conditioner membuat tubuhnya sejuk.
Revan pun melajukan mobilnya.
“Macet,” keluh Revan melihat sekeliling jalan yang mulai padat. Sesekali, ia melirik Harzel di sebelahnya.
Harzel tetap menampilkan tampilan khasnya. Bahkan Revan sepertinya tidak pernah melihat gadis itu mengenakan jeans. Kali ini, Harzel mengenakan knee length dress berwarna orange berlengan pendek. Rambut lurusnya tergerai rapi. Sangat natural.
Merasa kedinginan, Harzel mengeluarkan jaket coral peach dari ranselnya—lalu mengenakannya erat-erat—hingga kepalanya juga tertutup oleh topi jaket.
Revan tak mengerti. Berbagai macam kebetulan—yang mempertemukannya pada Harzel—menciptakan momen yang tak pernah ia duga sebelumnya. Jantungnya kembali berdebar mengingat bahwa Harzel adalah Tiara, gadis kecil yang ia selamatkan 10 tahun silam. Bahkan saat Revan tak menyadari bahwa Harzel adalah Tiara, tawanya tetap mengangkat beban yang menitikberatkan di kedua bahu lelaki itu.
***
Harzel membuka kedua matanya perlahan. Entah sudah berapa jam ia terlelap. Hembusan Air Conditioner dari mobil Bimo membuat sepasang mata gadis itu berat dan tak kuasa menahan kantuk.
Harzel menoleh ke kanan. Revan tidak ada. Gadis itu kemudian menyadari Revan yang telah menghentikan mobil.
Harzel bangkit, lalu membuka pintu mobil untuk melangkah keluar. Gadis itu mendelik bingung melirik sebuah taman yang tak ia kenal. Taman yang terletak di pinggiran kota dan terdapat berbagai macam arena bermain anak-anak. Sesekali, ia menguap dan mencoba memulihkan keadaannya agar kembali terlihat segar.
Sepasang mata milik Harzel langsung tertuju pada Revan yang tengah berdiri membelakanginya. Lelaki itu terdiam membisu sembari menatap kumpulan anak kecil yang tengah bermain di arena anak-anak.
Harzel menghampirinya.
“Padahal gue sama sekali nggak pengen lo bangun sebelum sampe rumah,” tutur Revan menyadari Harzel telah berdiri di belakangnya.
“Kita dimana?” tanya Harzel bingung.
“Di tempat bersejarah,” jawab Revan.
Harzel menepuk lengan Revan pelan, “Gue serius,” Lelaki itu menoleh sembari menampakkan wajah tanpa ekspressi, “Lo bilang kita mau ke rumah lo?”
Revan melirik jam tangannya, “30 menit lagi, ya?”
Revan kembali terdiam sembari menatap anak-anak yang tengah bermain sembari tertawa riang. Berkali-kali, ia harus menelan ludah menahan sesak saat datang ke tempat ini lagi.
“Gue suka tempat ini,” ujar Revan, “Saking sukanya, gue pernah jatuh dari pohon,” Revan tertawa kecil sembari menunjuk salah satu pohon besar yang rimbun. Menenangkan hatinya sendiri, “Rasanya sama sekali nggak sakit.”
Revan memejamkan mata. Dirinya mulai terhempas ke masa lalu saat Arnold—Papanya—masih ada disisinya. Lelaki itu selalu menjelaskan pada Revan agar dirinya menjadi jagoan. Revan kecil yang salah kapra, justru mengartikan jagoan dengan memanjat pohon yang menjulang tinggi di depannya, lalu terjatuh. Apalagi yang bisa dilakukan anak kecil saat terjatuh selain menangis dan merengek? Namun tangisannya terhenti ketika mendengar kalimat Arnold—yang bagaikan wejangan baginya.
“Menangis bukanlah pemecahan masalah. Daripada Revan nangis, mendingan Revan sediakan tenaga untuk di obati.”
Sejak saat itu, ia menahan tangisnya sebisa mungkin.
“Harzel, lo mau beli gula kapas?” tanya Revan, ketika melihat seorang lelaki penjual gula kapas yang berdiri tak jauh dari mereka.
Harzel tersenyum, “Terserah lo aja.”
Revan melangkah untuk membeli dua bungkus gula kapas. Kemudian kembali menghampiri Harzel sembari menyodorkan gula kapas yang berada di tangan kanannya. Harzel mengambil sedikit lalu melahapnya, kemudian mendelik heran pada Revan.
“Bukannya lo nggak suka yang manis-manis?”
Revan mengangguk sembari melahap gula kapas itu dengan raut wajah terpaksa, “Emang nggak,” ia mengeluarkan tawa yang dibuat-buat, “Tapi Papa gue suka.”
Mata Revan mulai berkaca-kaca. Membuat Harzel merasakan sesak yang sama.
Harzel merampas gula kapas yang tengah dilahap Revan, lalu menatap tajam lelaki itu, “Nggak perlu pura-pura bahagia depan gue!”
Revan mengangguk, ia mengerti bahwa Harzel memahami perasaannya. Tapi, ia hanya ingin bernostalgia. Apa salahnya? Lelaki itu kembali merampas gula kapas di tangan Harzel, lalu melahapnya seperti kesetanan.
“Sialan!” Revan menyeka dengan cepat sebulir air bening yang tiba-tiba menetes dari pelupuk matanya. Ia meremuk gula kapas itu dengan kasar, lalu melemparnya.
Revan menarik pergelangan tangan Harzel, menggiring gadis itu ke mobilnya, “Kita pulang aja!”
Revan merasa kalut. Melihat taman saja membuat hatinya tidak karuan, apalagi melihat rumahnya yang penuh sejarah menyakitkan.
Harzel menghentikan langkahnya, membuat Revan sontak menoleh.
“Gue mau ke rumah elo,” gadis itu melirik tajam.
Revan menggeleng. Ia takkan kuat. Lelaki itu hanya menyunggingkan senyum yang dipaksakan, “Kita ketempat lain aja. Ke bioskop atau ke Dufan? Kemanapun lo mau..”
Harzel menggeleng, “Revandira Louis Papinka yang gue kenal bukan seorang pengecut. Dia bahkan berani melawan siapa aja, termasuk penjahat. Jadi kali ini..” tutur Harzel disertai senyum yang menenangkan, “Gue yakin dia bisa menghadapi masalahnya sendiri.”
Mendengar penuturan Harzel, Revan kembali menemukan segenap keberaniannya. Ia tidak perlu takut. Ia tidak sendirian. Harzel bersamanya.
Tanpa ragu lagi, lelaki itu mengangguk mantap.
***
Harzel menatap sekeliling rumah Revan yang lebih pantas di juluki seperti museum berhantu. Rumah yang besar, didesain unik dengan dominasi warna kecoklatan, serta terdapat berbagai macam perabot barang antik. Rumah ini memang sudah lama tidak ditunggu lagi. Saat Revan memutuskan untuk pergi, Dewi pun memutuskan untuk menginap di apartement. Hanya ada beberapa pelayan yang senantiasa membersihkan dan menjaga rumah ini.
Revan menatap sekelilingnya sembari menahan sesak di dada. Rumah ini tak seperti dulu. Berbagai macam kehangatan terselimut di rumah ini ketika ia lahir di dunia hingga usianya menginjak tujuh tahun. Di rumah inilah, Revan kecil berlari-lari riang sembari bermain dengan ceria dan nakal—yang tak jarang menyusahkan pelayannya karena harus membereskan rumah setiap saat. Di rumah inilah ia menghabiskan masa kecil bersama adik sepupunya, Arieska Nowela Papinka dan ayahnya Arnold Louis Papinka.
“Piano??” Harzel melangkah masuk ke salah satu ruangan di rumah Revan sembari tersenyum senang, sudah lama ia tidak menyentuh benda ini.
Revan menelan ludahnya. Menghela nafas panjang. Arnold sangat ahli memainkan Piano. Lelaki itu pula yang mengajarkan istrinya bagaimana memainkan piano dengan indah—hingga istrinya menjadi mahir. Namun sayang, kemampuan Piano yang dimiliki Dewi membuat wanita itu lebih sering berkunjung kesini dibandingkan ke kamar putranya. Ia tidak menyempatkan diri meski hanya memastikan Revan baik-baik saja.
Revan duduk di sebelah Harzel yang tengah menekan tuts piano, “Mainkan satu lagu!”
Harzel mengangguk dan mulai menarikan jarinya di atas tuts piano. Tarian jari itu mulai membentuk alunan nada yang indah. Harzel mulai menyanyikan lagu favoritnya.
You and Me.
Revan mendengarkannya dengan seksama sembari bertopang dagu. Harzel mulai bernyanyi. Kemudian berganti dari satu lagu ke lagu yang lain. Gadis itu begitu menikmati alunan piano yang dimainkannya. Hingga ketika cukup lelah, ia berhenti lalu melirik Revan di sebelahnya.
“Gue dulu les piano. Tapi nggak ada piano. Jadi kalau mau main piano, gue nyusup ke ruang seni.” Ujar gadis itu kemudian tertawa kecil.
Revan manggut-manggut. Kemudian menatap jari-jari Harzel yang kembali menari di atas tuts piano, “Gue harap suatu saat gue bisa kasih lo piano paling bagus di dunia.”
Harzel menatap Revan. Kemudian mengerjapkan matanya berkali-kali. Cukup lama. Gadis itu hanya tersenyum tipis. Merasa gugup dan kikuk.
Setelah berhasil mengatur detak jantungnya sendiri, Harzel kembali tenggelam dalam alunan pianonya. Hingga Revan beranjak pergi. Membiarkan gadis itu bahagia bersama piano daripada memasuki zona masa lalu bersama dirinya.
***
Perlahan, Revan membuka pintu kamar lamanya—yang berbulan-bulan tidak ia lihat. Yang telah berbulan-bulan pula tidak ia sentuh. Kamar yang menjadi tempatnya berdiam diri untuk menangis. Karena sangat tak mungkin seorang Revandira Papinka menangis di depan orang banyak.
Terakhir kali ia tinggalkan, kamar ini sangat berantakkan.
Namun yang ia pandang sekarang, sebuah ruangan yang tertata rapi. Ruangan rapi itu mampu menghunus lubuk hatinya yang paling dalam. Ia melangkah pelan menuju tempat tidurnya yang berlapis seprai spiderman. Superhero yang pernah Papanya—Arnold—kenalkan padanya.
Lagi-lagi, ia terhempas ke masa lalu.
Kala itu, Dewi terlihat sibuk dengan berbagai macam berkas kemudian melirik jam dinding ruang kerjanya. Baginya, jam itu berputar dua kali lipat lebih cepat dibanding sebelumnya. Pekerjaan yang ditunggu deadline ini membuatnya kerepotan.
Putra kecilnya berumur 6 tahun melangkah mendekat sembari menyentuh baju piama yang Dewi kenakan.
“Mama..Mama..” Revan kecil berseru.
Dewi menjawab dengan lembut, “Ada apa, Revan?”
Revan menyodorkan sebuah undangan yang tadi siang ia dapatkan dari sekolah. Dewi mengambilnya, lalu membacanya sekilas.
Undangan rapat orang tua tentang kemajuan kegiatan belajar mengajar.
Dewi tersenyum, lalu mengembalikan undangan itu pada Revan, “Mama nggak bisa. Revan sama Papa aja, ya?”
Revan menggeleng, lalu merengek, “Temen aku semuanya datang sama Mama mereka bukan Papa!”
“Revan!” tukas Dewi, “Mama temen kamu itu nggak sibuk, nggak kayak Mama!”
Revan kecil mendelik kesal, “Kenapa aku harus punya Mama yang sibuk??!!” tanyanya dengan suara keras.
“Revan!” Bentak Dewi kesal. Revan kecil sama sekali tidak menangis seperti anak-anak lainnya ketika dibentak atau dimarahi, ia justru menatap Dewi dengan tatapan menantang.
“Ada apa ini?” tanya Arnold yang masuk ke ruang kerja Dewi ketika mendengar teriakan istrinya.
Revan mendongak, menatap Arnold, “Papa? Kenapa aku harus punya Mama yang sibuk?”
Dewi mengacak-acak rambutnya sendiri, “Anakku baru berumur enam tahun, tapi sudah berani kurang ajar!”
Arnold melirik Dewi dengan tatapan dingin, “Anakku tidak kurang ajar,” tukasnya dengan suara pelan, lalu menunduk untuk melirik Revan kecil yang tengah berdiri, “Jagoanku sama sekali nggak kurang ajar,” Lelaki itu kembali mlirik Dewi, “Dia punya kemampuan yang nggak dimiliki oleh anak laki-laki lainnya.”
Arnold menatap Dewi lekat-lekat, “Dia punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya tanpa rasa takut sedikitpun!”
Dewi mendelik sebal, “Jadi, aku yang salah??”
Arnold tak menggubrisnya. Ia langsung menggendong Revan kecil yang sedari tadi terdiam. Sebelum melangkah pergi, ia melirik Dewi, tatapannya tetap saja dingin, “Selesaikan pekerjaanmu!”
Arnold pun menggendong Revan menuju kamar bocah kecil itu, lalu merebahkan tubuh mungil Revan di atas ranjang dengan seprai baru bergambar spider-man.
Arnold tersenyum, “Papa sudah tepati janji, Papa.”
Revan bangkit duduk, lalu melirik seprainya, “Papa, ini kan cuma gambar!” Rengeknya, lalu menatap Arnold sebal, “Aku kan minta spider-man yang asli kesini.”
Arnold duduk di sebelah putranya, lalu menatapnya hangat, “Dia takut kesini.”
Revan mendelik heran, “Kenapa?”
“Karena ada superhero dirumah ini yang lebih hebat dari dia.”
“Siapa?”
Arnold tersenyum, “Revandira Louis Papinka.”
***
Revan mendengus sembari menatap foto dirinya bersama Papanya—Arnold. Kata-kata yang dilontarkan Arnold kembali terngiang di telinganya.
Jagoanku sama sekali tidak kurang ajar. Dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki anak laki-laki lainnya. Dia memiliki keberanian mengatakan kebenaran tanpa rasa takut sedikitpun.
Merasa tak berdaya. Revan terduduk sembari membenamkan wajah di samping tempat tidurnya. Air mata—yang selama ini ia bendung sekuat tenaga—mengalir begitu saja hingga membasahi seprai.
Kini kenangan itu mampu merenggut segala pertahanan dan kekuatannya.
Revan kembali mengangkat wajah. Menatap foto Arnold yang kini telah tiada.
“Papa benar. Aku lebih hebat dari superhero manapun,” ujarnya terisak. Ia terdiam sejenak, “Tapi aku takut menghadapi kenyataan.”
Revan memecahkan tangisnya. Kali ini lebih keras.
“Aku rela tinggal di kolong jembatan. Menjadi pengemis. Asalkan Papa kembali..”
Lelaki itu mengatur nafasnya. Sesak di dada—yang dilampiaskannya dengan air mata dan tangisan yang pecah—membuatnya sulit bernafas. Lelaki itu menoleh ke belakang. Entah apa yang mendorongnya untuk menoleh dan menyaksikan Harzel berdiri di depannya. Air muka Harzel menampakkan prihatin dan kesedihan yang sama. Revan langsung menyeka air matanya, bersamaan dengan Harzel yang langsung duduk di depannya.
Harzel meraih foto yang sedari tadi lelaki itu pegang, lalu melirik dua lelaki yang tengah berpose manis di depannya.
“Papa lo ganteng, ya? Lebih ganteng dari elo.” Komentarnya. Mencoba menghibur. Revan hanya tersenyum tipis sembari menghapus sisa-sisa air matanya.
Harzel tersenyum geli, lalu menatap lekat-lekat foto itu, “Ini elo, ya?” Harzel menunjuk anak laki-laki yang sedang digendong oleh Arnold, “Kayaknya gue pernah ketemu lo..” Harzel berfikir, “Muka lo waktu kecil nggak asing lagi.”
Harzel mengembalikan foto itu ke tangan Revan, “Apa lo suka main ke waterboom waktu kecil? Gue suka kesana, bahkan setiap tiga kali seminggu.”
Revan tersenyum senang. Artinya Harzel masih mengingat dirinya walau hanya sedikit, “Mungkin gue pernah kesana.”
Revan berdeham, “Jangan bilang ke siapa-siapa kalo gue nangis!”
Harzel tertawa renyah. Gadis itu tak pernah berfikir sebelumnya bahwa tangisan lelaki adalah aib. Namun tidak dengan Revan, lelaki itu malu setengah mati jika semua orang tahu bahwa ia bisa menangis.
Kini, Revam kembali termenung sembari memandang foto itu. Ia masih ingat betul ketika Arnold mati-matian menyuruh dirinya untuk latihan silat dan karate sekaligus. Lelaki itu sangat berambisi menjadikan putranya superhero sungguhan.
Dirinya, Adrian, dan Ari, adik sepupunya, berlatih bersama saat itu. Secarik kalimat dari Arnold membuat dirinya bersemangat.
“Kamu harus buat spider-man makin takut! Jadi, latihan sungguh-sungguh! Oke?”
Revan menyimpan foto itu di sakunya. Buat apa juga ia terikat dengan masa lalu. Tak akan ada yang berubah. Papanya sudah jauh. Sangat jauh. Dan Mamanya? Wanita itu juga jauh meski masih berada di bumi.
Revan belum berani memimpikan masa depan yang indah. Menjadi ini. Menjadi itu. Bahkan ia tak tahu apa yang akan dilakukannya selepas SMA. Kuliah? Menganggur? Entahlah. Hubungannya dengan Mamanya yang buruk membuatnya tak berani berandai-andai. Ia terlanjur berkomitmen untuk pergi dari Mamanya. Dan siapa yang akan membiayai kuliahnya setelah itu? Apakah ia masih sudi meminta biaya pada mamanya?
“Mending kita ke tempat yang lebih menyenangkan. Sea world, Dufan, Bioskop.. atau lo mau cari buku?” tanya Revan. Menghapus sisa-sisa rasa sesaknya. Kemudian berdiri. Dan diikuti Harzel.
Harzel mengangkat bahu, “Terserah lo aja.”


 gigikelinci21
gigikelinci21







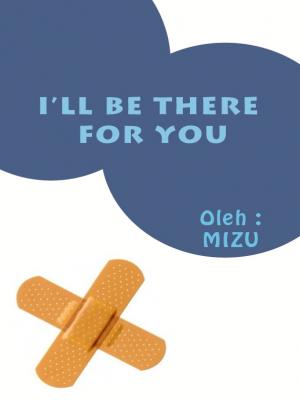

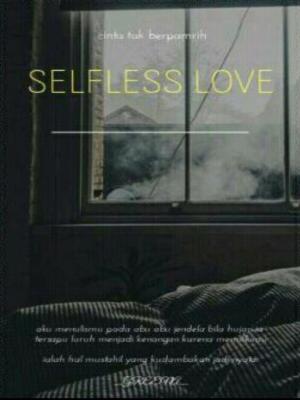
seperti lagi baca novel terjemahan. hehe. bahasanya enak dan mudah dipahami. udah kulike dan komen storymu. mampir dan like storyku juga ya. thankyouu
Comment on chapter PROLOG