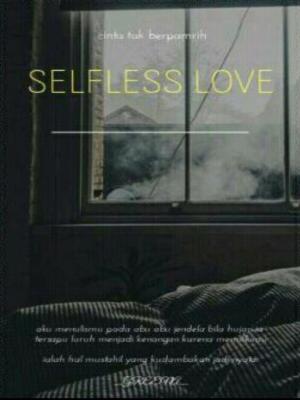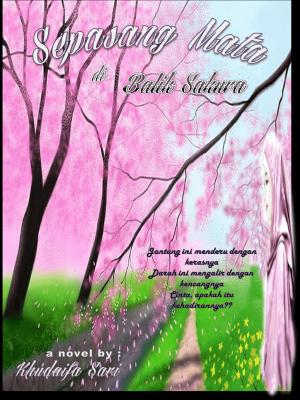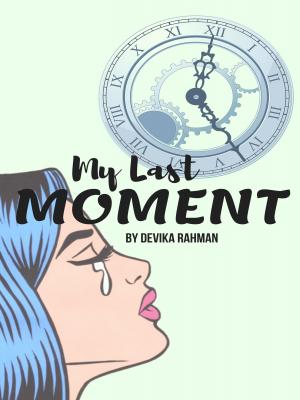Tak terasa gelap pun jatuh
Di ujung malam
Menuju pagi yang dingin
Mas Rey masih termenung di kamarnya. Ia merasa tidak enak badan. Kelelahan, mungkin. Ia harus mengurusi kafe, mengurusi stabilisasi koperasi para petani kopi di Cibeurem, dan sedikit-sedikit memenuhi panggilan Ayahnya untuk membantu urusan kantor yang bergerak di perdagangan rotan—yang kini menembus pasar luar negeri.
Tapi sebagai lelaki, semua pekerjaan itu bukanlah sesuatu yang berat. Tubuhnya masih cukup kuat untuk menangani itu semua. Hanya saja ia lemah dalam perihal asmara. Ketidakadaan kabar dari Nabil membuat pikirannya kacau. Sampai seringkali dokter ketika memeriksanya malah berpesan jangan terlalu banyak pikiran—ketimbang harus memberi resep obat-obatan yang bermacam atau mencegah makanan-makanan yang dirasa sensitif bagi organ tubuh.
Dan di saat-saat seperti ini, ingatan tentang perhatian Nabil muncul kembali. Andai saja ada Nabil. Nabil akan membuatkan bubur lengkap bersama sup ayamnya. Menyuapinya. Dengan raut muka yang begitu khawatir melihat Mas Rey yang terkapar. Setelah makan selesai, Mas Rey ingat betul bahwa setelah itu ia akan pura-pura tertidur demi mendapatkan elusan tangan Nabil yang mendarat di setiap helai rambutnya.
“Nabil, aku…”
Tuhan, aku ingin mati sehari. Hanya ingin sekadar mengintip sedikit bagaimana cara dia merindukanku. Jika mati terlalu seram, izinkan aku menjadi malaikat pencarat rindu.
“Nabil, aku,..”
Waktu takkan pernah bisa adil. Memang setahun akan tetap sama hitungannya, setahun. Tapi ia begitu sangat cepat bagi si bahagia. Dan seperti menunggu kereta telat bagi seorang yang sedang jenuh.
Dan yang Mas Rey rasakan memang benar-benar seperti sedang menunggu kereta telat.
Sebenarnya ia sedikit curiga dengan sikap Nabil saat itu. Hanya saja sebagai lelaki, Mas Rey harus bisa memposisikan diri sebagai seseorang yang memiliki pengertian yang lebih. Bayangkan saja, malam sebelum Nabil memutuskan kontak, mereka sempat Video Call-an. Saling menggoda. Di sana Nabil bertelepon sambil memasak sayur sop dengan isi sosis sapi. Ia menggoda-goda Mas Rey sambil memperagakan seseorang yang mencium aroma sop yang lezat; memejamkan mata bersama desir hmmm keluar dari mulutnya.
Dan… yah, besok malam ada pesan yang tak terduga. Bahwa Nabil memutuskan agar Mas Rey berkenan putus-kontak. Demi menjaga fokus dia dalam dunia perkuliahan di negeri orang.
Malam ini Mas Rey begitu butuh kehadiran Nabil. Atau memang sebenarnya Nabil hadir sebagai bayang-bayang yang lahir dari sketsa potonya yang kini sedang dipeluk erat dengan kedua tangan Mas Rey yang cukup panas. Lalu bayang-bayang itu merenkarnasikan dirinya sebagai angin malam. Sebagai dinding-dinding kamar. Sebagai lampu tidur. Wajahnya nampak bias. Berwarna abu-abu. Kemudian memudar putih terang. Lalu beranjak gelap.
“Nabil,.. aku”.
***
“Ul, ikut aku yuk”, ajak Anzza yang melihat Paul sedari magrib hanya fokus dengan TTS-nya itu, “Bosen kan?”
Paul segera mendekat dan berdiri tepat di di depan Anzza. Merasa aneh telapak tangannya ia daratkan di lapang kening Anzza, “Gak lagi sakit, kan?”
“Sial!”
“Oke bos, hayuuuu!”
Sesegera Paul mempersiapkan dirinya. Ia tidak peduli temannya itu akan membawanya kemana. Ia tak peduli jika pun hanya diajak ke warung di bawah fly over untuk sekadar menikmati segelas kopi dan hangatnya gorengan pisang. Yang terpenting, ia melihat Anzza bukan sosok yang begitu kaku lagi. Dan saat seperti inilah yang tidak boleh dilewatkan oleh Paul. Bayangkan saja selama ngekost bareng sekitar dua tahunan, baru kali ini ia merasa akrab sekali dengan Anzza. Bukan hanya sekedar menghabiskan waktu dengan cara; Anzza menggitar, Paul bernyanyi—setiap hari di bangku teras kosan.
Benar saja, atau mungkin saja gerutuan Paul dikabulkan Tuhan. Anzza memberhentikan motornya di depan warung yang berjejer di bawah fly over tepat di seberang Grage City Mall. Paul hanya mengekor pada langkah Anzza. Dihampirinya seorang bocah yang sedang menyandar di salah satu kaki jembatan, di atas sebuah tikar—lengkap dengan gitarnya.
“Udah lama Sa?”
“Baru kok om, hehe”
Paul masih belum mengerti kenaapa ia diajak kesini dan ada apa dengan bocah kecil ini, “Dek mata kamu kok agak kuning, pucet lagi,.. kamu sakit?”
Reksa masih diam saja.
“Tuh, Anzza mah dia lagi sakit juga”, ucap kecam pada Anzza.
“Enggak kok Om”, Reksa menimpali.
Anzza menarik Paul untuk sedikit menjauh dari keberadaan Reksa. Setelah sekiraanya tak mungkin Reksa mendengar, Anzza segera membisikan sesuatu, “Nanti aku jelasin di rumah”, Anzza menampakkan obrolan serius, “Sekarang jangan banyak tanya, kita gitar-gitaran malam ini, enak kok”.
“Siap bos!”
Tiba-tiba Paul cengengesan, sembari mengelus-elus perut buncitnya, “Demo nih bos”
Anzza paham geriknya. Dan merogoh dompet, “Sana beli makanan!”.
“Aku?”, tanya paul lalu diarahkannya matanya menuju ke kebaradaaan Reksa, “Kenapa gak dia aja bos? Lumayan atuh? Gimana?”
“Aku yang punya duit, aku yang bebas pengennya siapa? Kalo gak mau ya sini-sini”, Anzza mencoba merebut uang yang sudah berada digenggaman Paul.
Tapi Paul berusaha mempertahaankan uang itu.
“Iya iya bos”
“Bas-bos-bas-bos, lebai! Lagian tadi bilang kasihan sama Reksa, bilangnya sakit juga”
“Iya iya bos”
Mendengar kalimat bos lagi, Anzza memelototi Paul.
“Iya iya Zza”, tungka Paul menangkap maksud Anzza.
Paul pergi mencari makanan. Mungkin enak juga pikirnya, makan nasi goreng lengkap dengan teh manisnya, lalu menikmatinya di bawah jembatan, dan tentunya Cirebon malam punya. Ah. Di sela-sela bayangan indah tadi, terselip sebuah tanya, Anzza kenapa ya? Uh.
***
Mera mewanti-wanti adiknya agar mau tidur dengannya. Tapi Rina selalu saja enggan untuk menurutinya. Dua sosok ini padahal kakak beradik yang sama-sama perempuan. Hanya saja mereka memiliki perbedaan sikap. Utamanaya musabab Rina dalam sifatnya enggan dikatakan anak kecil lagi. Ia memberanikan diri menunjukan keberaniannya pada kakak satu-satunya itu. Itulah alasan mengapa adiknya terus menolak maksud baik kakaknya; ya maksud baik agar kejadian beberapa minggu yang lalu tidak terulang lagi.
Itulah sebenaranya yang menjadi dasar Mera ketika marah-marah pada Anzza, ketika dia mengajaknya ke rumah seorang bocah bernama Reksa itu; hanya untuk sekadar bermain gitar di tengah malam bolong. Aneh. Tidak mungkin bukan jika Mera lebih memilih menemani Anzza saat itu, ketimbang menjaga adiknya?. Mera tidak mau kejadian seminggu sebelumnya terulang kembali; Rina kambuh tengah malam, sialnya Mera dan Ibunya tidak mengetahuinya. Yang akhirnya dirawat berhari-hari, musabab kata dokter sudah sekitar lima jam lebih tidak ada yang menolong Rina saat kambuh waktu itu.
Baginaya, Rina seperti bunga. Seperti air. Seperti matahari. Sehingga ketiganya menyatu membuat sebuah harum mawar di hidupnya. Setelah Ayahnya tiada, ia tidak mau kehilangan orang yang ia sayangi lagi. Rina Dwi Kadarhariarto, sebuah nama untuk bunga yang mekar di dadaku, benak Mera.
***
Baru saja Mas Rey hendak terlelap, mengistirahatkan tubuhnya. Begitu cekatnya kini ia harus menaiki Kereta business yang terasa lamban dirasa. Beberapa saat pesan via WA itu mendarat, ia tak mengambil waktu untuk sekedar membiarkan nafasnya teratur sekalipun. Tak membiarkan pikirannya tenang dulu. Tak sedikitpun memikirkan keadaannya sendiri yang sedang lemah fisik.
“Kenapa kau tak bilang? Kenapa?”
Sebuah foto seorang gadis yang memiliki tahi lalat kecil tepat di atas mulutnya itu, dipegangnya erat-erat. Sesekali ia menengoknya. Lalu bergantian memejamkan matanya lagi. Ia mencoba menenangkan diri. Membayangkan ingatan-ingatan yang terkesan dalam kebersamaannya itu. Ingatan kebahagiaan mereka. Terus-menerus. Menggalinya sedalam mungkin. Ia ingin mencari sebuah senyuman yang dibuat di sebuah Kopinesia kala itu. Ia ingin mencari senyumannya yang begitu melengkung melebihi lengkungan pelangi yang pernah ia lihat dari atap rumahnya itu. Ia ingin. Dan akan selalu ingin.
Hanya ada sedikit bintang malam ini,
Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya.
Sepanjang jalan mata Mas Rey menembus kaca jendela kereta. Menjadikan langit sebagi satu-satunya yang ia tuju. Di sana, bayangan perempuan yang memiliki rambut sebahu itu, terpampang di hampar langit. Tidak ada satu bintang pun di sana. Ia hanya menyangka bahwa semua bintang nyatanya pengecut dan cemburuan. Gara-gara bayang perempuan itu semua bintang bersembunyi diri. Atau jangan-jangan perempuan itulah bintangnya. Ia menjadi bintang malam ini. Tidak ada yang lain. Hanya satu bintang malam ini. Hanya perempuan itu. Bersinar diantara wajah langit malam yang pekat.
“Nabil, semoga Tuhan melindungimu”.
***
Jam menunjukan pukul 12.30. Anak kecil itu; Reksa. Adalah anak malam. Dan orang tuanya sudah memakluminya. Reksa tidak suka siang, dia hanya suka malam. Utamanya malam-malam ala Cirebon. Seorang bocah yang ditemukan Anzza sekitar setahunan yang lalu terkapar di perempatan Jln. Perum.
Saat itu kebetulan Anzza baru saja pulang dari Kafe tepat di hari pertama ia bekerja, sekitar jam satu dini hari. Dengan setengah sadar anak itu meminta Anzza untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya. Untung saja rumahnya tidak jauh dari perempatan tersebut. Setelah ibunya menyambut kedatangannya, maka terbukalah sebuah cerita yang membuat Anzza akhirnya sering datang untuk menghiburnya.
Reksa. Seorang bocah yang putus sekolah sebab halangan penyakitnya. Kondisinya rentan dengan sesuatu yang membuatnya kelelahan. Kondisinya sangat lemah. Bahkan tiap hari mukanya semakin pucat saja. Dia mengidap penyakit turunan “thalassemia” lewat jalur ibunya. Sebuah penyakit kelainan dengan produksi darahnya, atau semacam anemia. (kekurangan darah). Hingga pada setiap bulannya harus rutin transfusi darah. Di tengah pelik itu, tinggalah ia hanya bersama ibunya seorang. Bu Surti, seorang buruh di tempat percetakan daerah Kranggaksan.
“Aku hanya ingin hidup dimulai dari malam Om. Siang mah panas,.. Cirebon teh”, jawab Reksa pada suatu ketika.
“Mamahmu gimana? Setuju?”
“Kata mamah yang penting aku senang,.. sebab kalo murung nanti nyerangnya darah”
“Bener?”
“Ya gak tau juga Om. Yang pasti kalo aku di kamer terus, malah lemes bawaannya”
“Kok malem banget kalo pulang?”, Anzza semakin mengintrogasinya.
“Aku suka sepi ditambah angin malam. Tinggal beli gitarnya aja, biar ada yang nemenin. Aku pengen kayak Aril”
“Kok Aril?”
“Ya Aril yang lengkap,.. ganteng udah, suara udah, ya sekalian megang gitar juga, hehe”
Percakapan itu lah yang membuat Anzza membelikannya sebuah gitar. Tidak sedikitpun Anzza rugi. Karena setelah ia belikan, ia melihat senyum yang begitu magic di wajahnya. Ia semakin yakin kenapa ia memilih Cirebon untuknya menetap. Ada Reksa. Ada senyumannya. Ada sedikit harapan juga untuknya mengingat masa-masa kecilnya—yang kala itu—ia berusaha belajar gitar sekalipun harus ngumpet-ngumpet dari Ayahnya yang galak itu. entah sampai sekarang Anzza masih belum tahu kenaapa Ayahnya sangat benci sekali dengan benda yang diberi nama Gitar.
Setelah panjang lebar ia menceritakan tentang Reksa kepada Paul. Seteleh sedikit tenang dengan matanya yang mengitari setiap sudut kamar. Ia ingin mencari-cari sesuatu; sebuah bayangan. Perlahan bayang itu muncul. Sebuah bayangan yang suatu saat ia bersama Reksa akan memainkan gitar di panggung yang sama. Bayang itu perlahan memudar. Dan tiba-tiba berganti dengan sebuah bayangan sosok perempuan. Ia tersenyum. Langit-langit menjadi langit. Sekadar langit kosong. Tanpa bintang. Mungkin hanya sedikit bintang yang membayang-bayang bergelantungan. Tapi, hanya sedikit. Dan semuanya kalah terang. Dengan sebuah bintang yang menyorot dari wajah sosok perempuan itu. Mungkin dia sedang cantik-cantiknya. Cantik sebagai bintang. Ya, sebagai bintang. Mera lagi.
Hanya ada sedikit bintang malam ini
Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya.
Perlahan kelopaknya menjadi gerai. Terlelaplah.
***
REYNALDI MUHAMMAD
Aku tak habis pikir jika sebuah prinsip dan perjanjian lebih penting dengan kecaman nyawa. Ketika janji bekerja, semua akan mundur untuk mengalah. Sampai-sampai kuyakin Nabil tidak menghubungiku sebab keberadaan sebuah janji. Apapun itu, kami tidak boleh berhubungan untuk sementara. Dia akan fokus kuliahnya, dan aku fokus dengan bisnisku.
Nabil masih belum sadar. Alat infus masih menutupi hidung mancungnya. Matanya terpejam, namun kulihat bola matanya begitu terang hingga menembus gerai kelopak itu—yang kurasa Nabil pun berbalik memandangiku.
“Kondisi jantungnya begitu lemah, lambatnya besok malam harus dioprasi.”
“Apapun Dok! Selamatkan Nabil”, jawabku panik.
Kata-kata dokter itu terus ngiang dipikiranku. Apapun caranya. Bagaimanapun caranya. Nabil harus sembuh. Ia harus kembali dengan senyumannya. Dengan harapannya. Denganku, pula.
Ibu Nana, pengasuh panti asuhan “Mekar Sari” dan dua anak panti yang menemaninya pamit pulang sementara, setelah kedatanganku. Ana Nabila, kekasihku, memang besar di panti asuhan di bilangan Kota Semarang. Aku berkenalan dengannya saat kami dapat tugas yang sama di kampus dulu, UNNES—dimana aku sebagai delegasi jurusan manejemen dan Nabil sebagai delegasi jurusan komunikasi pada suatu acara di Jakarta.
Entah sebab kenapa, pada saat itu, aku seoraang lelaki yang tak pernah mempunyai riwayat asmara sebelumnya, seketika percaya akan kehadiran cinta pada pandangan pertama. Unggah-ungguhnya, senyum manisnya, artikulasi dalam bicaranya. Aku menyukainya.
Waktu terus bergulir, kami semakin akrab setelah acara itu. Apalagi kopi telah mempermanis hubungan kita. Sebab di lain sisi, kami jadi sering ngopi berdua musabab aku dan dia sama-sama suka kopi. Hingga kami memiliki perasaan yang sama. Hingga aku beranikan untuk menyatakan perasaanku. Hingga alam mendukungku. Dan kami memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius.
Setelah lulus kuliah, aku memutuskan untuk langsung terjun ke dunia bisnis. Sekalipun bisnis kecil-kecilan. Sementara Nabil mendapat beasiswa ke London dan berniat untuk menerimanya. Tapi aku dan Bu Nana menyarankan untuk mengurungkan niatnya itu. Karena setelah lama kami hubungan aku tahu ia memiliki kelainan pada jantungnya. Tapi ia bersikeras untuk mengejar cita-citanya di jenjang akademika, dan bersikeras merayuku dan berusaha meminta restu pada Bu Nana agar mengizinkannya. Hingga akhirnya kesungguhannya membuatku dan Bu Nana hanya bisa mengiyakannya.
Namun mataku merasa malu
Semakin dalam, ia malu kali ini
Kadang juga ia takut
Tatkala harus berpapasan di tengah pelariannya
“Semoga engkau baik-baik saja Bil”
Aku masih disini. Dan akan tetap disini. Sebab Nabil disini. Dan malam ini, biarkan aku mengingat-ngingat kebersamaan kita, Bil. Sebuah ingatan yang sekilas monokrom.
Saat itu. Aku berjanji untuk menjemputnya sebelum jam 8 malam di rumah tante Nanik, yang sementara ia sedang di Cirebon untuk menghabiskan waktu sebelum beberapa bulan lagi ia harus pergi ke London.
Di perjalanan nanti aku masih ragu dengan niatanku. Tapi, hatiku berkata malam ini adalah saat yang paling tepat. Ada baiknya ia menyatakan niatnya sebelum Nabil pergi ke London. Untuk lebih meyakinkan pilihanku. Untuk meyakinkan Nabil tentang keseriusanku. Di kafe Goodhands. Di daerah Cipeujeh, Cirebon Timur. Aku akan merubah diri sebaagai petarung yang berani. Aku akan maju berperang dengan keraguanku. Aku akan menang!
Semua rencana sudah aku siapakan. Aku meminta bantuan ke pihak kafe untuk menyewa panggung dan alat musiknya. Lalu menghubungi Ipul dan Indra, dua teman SMA-ku dulu sekaligus sosok musisi local yang selalu tampil mengesankan dalam membawa lagu dengan iringan petikan gitar akustik. Aku ingin mereka menyanyikan lagu “Marry you” milik Brono Mars; kuyakin mereka sudah siap dengan versi akustik dengan tempo yang mendayu-dayu.
Ipul sudah mulai Menyanyikannya. Bukan hanya aku. Seluruh pengunjungpun menikmatinya. Sebuah lagu yang sedikit nge-beat kini begitu mendayu disulap mendayu oleh mereka berdu. Mengesankan.
I’ts a beautifull night…
Kurasa, Bruno Mars sedang berada disini. Menyanyikannya untuk kami. Di atas meja, sebelum pesanan datang, hanya ada sebuah bunga lavender dengan vas mungil dan kedua tanganku yang sedang memegang erat tangannya. Tanpa basa-basi apapun, tangan kananku mengambil sebuah cincin yang sengaja kusiapkan di saku yang mudah untuk kurogoh.
Nabil masih menatap penuh mataku. Tidak sedikitpun aku yakin ia akan mengangkat bicara. Lagu terus mengalir. Pelayan kopi yang ingin mengantarkan pesanan kami kulihat memberhentikan langkahnya, mungkin ia tahu aku dan Nabil sedang masuk dalam moment yang begitu melankolis. Dia mungkin tidak ingin menggagalkan momen seperti ini.
Nabil mengangguk. Dan aku tak sadar bahwa seluruh pengunjung memperhatikan kami. Karena kafe ini memang tidak terlalu luas juga. Tentunya moment seperti ini gampang ditangkap oleh mata mereka, dan sebagi manusia rasa penasaran itu bisa mengalahkan kondisi apapun. Ya, mereka semua melihat kami. Ipul bertepuk tangan, yang akhirnya diikuti seluruh pengunjung yang rata-rata masih muda –bertepuk tangan; Mengiringi saat aku memakaikan cincin itu di jemari lentik milik Nabil seorang.
Ah.
***
Waktu terasa begitu lama bagi Anzza. Seperti menunggu kereta telat datang. Seperti durasi seorang pengemis yang menunggu sereceh dari puluhan manusia yang melintas. Sedari pagi, ia hanya menghabiskan diri dengan gitarnya. Dan entah mengapa kali ini ia kembali membaca buku-bukunya kembali. Setelah lama ia tidak ingin membaca buku lagi. Setelah kecewa sebab semua alur yang ia baca selalu melewati bahkan berujung patah hati. Patah hati dengan apapun. Dengan wanita. Dengan nasib. Dengan jalan hidup. Dengan keluarga. Bahkan dengan kenyataan itu sendiri. Jadi mengapa ia harus membaca ketika semua itu telah ia rasakan sendiri. Tanpa ia membaca ia sudah mengetahui—tepatnya sudah merasakannya.
Tapi kini ia membaca lagi. Entah karena hari ini begitu terasa sangan panjang untuk menunggu sore. Entah karena hari ini begitu sangat panjang untuk menunggu rutinitasnya sebagi barista dimulai. Atau jangan-jangan sebab berharap cepat bertemu Mera? Ya, Mera.
Ketika warna langit sudah mulai memudar. Entah benar tidak bahwa warna biru yang beranjak menguning di sebut “memudar”, yang jelas ketiba-tibaan itu terjadi. Semacam kereta itu akan datang. Ia bersiap-siap untuk menaaikinya. Ya, sebentar lagi sore itu datang.
Setelah siap, pesan WA masuk. Dilihatnya pesan itu dari Mas Rey.
Za. Aku sedang di Semarang. Ada keperluan mendadak. Titip kafe sementara, untuk beberapa hari. Nanti kalo ada apa-apa hubungi saja Pak Wityo koperasi itu. Sekalian, Mera tadi izin tidak bisa datang hari ini, adiknya kembali masuk rumah sakit
Brakkk. Seperti hujan yang datang ketika panas menguasai langit, begitulah raut muka Anzza. Tak terduga jika tiba-tiba harus lesuh seketika. Ketimbang besarnya rasa senang ketika melihat langit sore, lebih besar lagi rasa gelisah mendengar kabar itu. Sudah barang tentu, Anzza akan gelisah jika orang yang ditunggunya tidak akan datang. Lebih kacaunya lagi seorang yang ditunggu tidak datang musabab sebuah musibah. Ia ingin segera menjenguk adik Mera dan tentunya menemani Mera. Tapi mana mungkin akan ninggalin rutinitasnya. Apalagi kini Mas Rey tidak bisa datang untuk beberapa hari kedepan. Mas Rey kenapa ya?
Pulang ini, aku akan berani datang ke rumah sakit...
***
REYNALDY MUHAMMAD
Nabil sudah masuk ke ruang operasi. Pagi tadi jantungnya semakin lemah. Ketika dokter menyarankan untuk melakukan kontemplasi jantung pada Nabil. Tanpa diam barang sejenak, aku mengabari Ayah tentang apa yang sudah terjadi. Tanpa banyak tanya, Ayah paham maksudku. Ia bersedia penuh dan mengabari semua relasinya untuk mencarikan sebuah jantung yang siap untuk dikontemplasikan. Sebab ayah selalu memahamiku, ia pun dapat langsung merasakannya. Dan bersegera membantuku.
Hanya hitungan jam, sekitar jam 4 sorean, sebuah jantung yang sudah siap untuk dikontemplasikan sudah mendarat di Rumah Sakit. Dan kini, Nabil sudah masuk ke ruang operasi. Sementara itu, Aku dan Bu Nana yang baru sore tadi datang kembali, menunggunya tepat di depan ruangan itu.
“Berdo’a ya Pak”, ucap seorang dokter yang kukira adalah dokter yang akan mengoperasi Nabil.
Aku dan Bu Nana, hanya bisa menahan air mata. Agar kami tenang. Agar kami bisa berdoa. Untuk Nabil. Ana Nabila.
“Nabil itu anak yang pintar,.. baik, dan semangatnya tinggi”, Bu Nana membuka bicara yang duduk di sebelahku.
Aku hanya terdiam. Dan tidak tahu harus nimbrung atau gimana. Yang jelas, aku tak bisa mungkir, usahaku untuk tenang rasanya gagal. Dan pikiranku semakin tidak tenangkan diri.
“Saking tingginya semangat itu, “ tambah Bu Nana dengan muka yang sebenarnya tidak dengan melihat wajahku, “demi belajar ke London, ibu tahu dia memalsukan riwayat kesehatannya. Ibu yakin dia bukannya curang, ataupun membohongimu Rey. Dia hanya semangat!”
Hatiku terenyuh mendengar hal itu. Nabil, Nabil, Nabil.
“Orang tuanya pasti bangga jika mereka tahu”, ujar Bu Nana mulai tenang.
Aku mencoba menyandarkan kepala nenek yang hendak mencapai usia 6o tahunan itu. Sambil sesekali menciumi kepalanya yang tertutup hijab berwarna merah maroon itu, “Nabil itu baik Bu, Tuhan pasti menjaganya”
Di malam hari, menuju pagi
Sedikit cemas, banyak rindunya
Nabil. Ada banyak cara semesta mengajarkan kebetapaannya akan kehadiran. Kamu memang ada di sekitarku. Ada di dekatku. Tapi, saat-saat seperti ini kecemasan bukan lagi sesuatu yang bisa kuusir secara mudah. Aku yakin Tuhan akan menjagamu. Tapi, aku hanya manusia yang masih kurang cukup nyali untuk duel dengan rasa cemas. Dan di balik itu semua, ada yang tak terhingga di dalam hatiku. Begitu banyak.. Kau tahu Rindu? Itu saja. Kuyakin kau pasti paham.
Di malam hari, menuju pagi
Sedikit cemas, banyak rindunya
***
KOPINESIA, Pukul 20.21 WIB
Bukan hanya Anzza yang merasa ada yang beda di kafe Kopinesia. Ketidakhadiraan Mas Rey dan Mera, nyatanya membuat Joan dan kawan-kawan juga merasa beda. Mungkin, mereka semua sudah menjadi keluarga. Suasana serasa hambar. Hanya ada beberapa pertanyaan bagi Joan dan kawan-kawan, “tumben banget Mas Rey pergi secara tiba-tiba dan begitu lama? praduga Anzza, Mas Rey pergi ke Semarang, kemungkinan ada kaitanya dengan Mbak Nabil.
“Mbak, Mas Rey ada?”, tanya seorang perempuan kepada Novi yang baru saja menyuguhkan pesanannya; segelas hot cappuchino.
“Oh, Mas Rey sedang ada urusan ke Semarang, Mbak”, jawab Novi santai. Hanya saja Novi memandanginya dengan sedikit terpengarah. Melihat perempuan tersebut sangat anggun memakai sebuah dress berwarna krim muda tanpa lengan, tanpa pernik, namun begitu sinkron dengan wajahnya yang oval dengan kulit langsatnya. Novi juga mengingat-ngingatnya lagi, Sepertinya perempuan ini sering datang ke Kopinesia. “Maaf, dengan mbak siapa? Barangkali mau nitip pesan?”
Segera perempuan itu tanpa ragu menyodorkan tangannya, “Oh iya kenalin mbak saya Alen”
Dengan senyum tipis, Novi menyambutnya. Namanya Alen. Setelah perkenalan singkat, Novi menebak-nebak sosok Alen. Seorang perempuan langganan di Kopinesia. Pasti dia sempat berkenalan dengan Mas Rey. Sebab sudah menjadi sebuah rahasia umum jika memang Mas Rey seorang yang mudah bersosialisasi dengan siapapun; apalagi dengan para langganannya. Ya, yang Novi heranin sebenarnya dengan penampilannya yang begitu anggun. Intuisi Novi berkata bahwa dia adalah salah satu perempuan yang ingin menarik perhatian Mas Rey. Mbak,..mbak, ada Nabil! Percuma, Novi berdecak dalam hatinya.
Waktu sudah larut. Anzza sudah siap untuk menuju Rumah Sakit. Setelah mendapatkan kiriman maps, ia bergegas menuju RSUD Gunung Jati, Jln Kesambi. Dan tak lupa mampir di tengah jalan demi membawakan martabak manis untuk Mera dan bingkisan buah untuk adiknya.
“O… ini pasti Om Rey”, sambut Rina melihat seorang lelaki yang baru saja dibukakan pintu sama Mera, “Ganteng ya?”.
Mera sedikit malu dengan tingkah adiknya, “Maaf ya Zza, he”.
Anzza meletakan bingkisan buah di meja kecil dekat Rina tiduran, “Ini buat kamu”, lalu menyodorkan martabak ke Mera, “Ini buat kakak”. Sambil tersenyum tipis.
“Gak mau ah Om Rey, aku juga pengen martabak”, tungkas Rina ngambek.
“Eh, Rina malu-maluin aja. Lagian ini bukan Om Rey, kenalin—”
Rina langsung menyambar tangan Anzza. Dari tadi ia ingin sekali bersalaman. Di mata Rina, Anzza itu kriterianya. Ganteng, putih, gaul gak monoton. Ditambah rambut panjangnya mengingatkannya pada sang idola, Adipati Dolken; ketika awal-awal baru nongol di televisi. Namun hal itu gagal, sebab selang infus masih tergulung—menghalangi maksudnya. Eh eh eh, auu, lirih Rina.
Mera langsung membenahinya, “ Lagian ganjen sih!”.
Bukan main. Gara-gara lirihan itu, Rina malah ketiban durian montong.Anzza mengelus kepala Rina. Mengelus-elus uraian rambut Rina, “Nama Kakak, Anzza, jangan panggil Om ya? Kakak masih muda, he”
“iya iya Om, eh, kak”
“Kamu gak pake suiter doraemon lagi?”
Rina mlongo. Dan Mera mencoba mengingat sesuatu yang menyerang otaknya. Ya, Meraa mengingat-ngingat tentang sebuah boneka doramon beberapa waktu yang lalu. Pasti Anzza!
Rina masih enggak nyambung, “Kok doraemon”. Mungkin dia lupa.
Mera menarik tangan Anzza mendekati pintu ruangan dan mulai membisikan sesuatu. “Kamu yang ngasih boneka waktu kemarin?”
Anzza bingung. Ia memberhentikan waktu untuk berfikir. Jika ia menjawab dengan sebenarnya, rasanya belum siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan berlanjut panjang; “Kenapa kamu gak bilang?”, “Kenapa kamu diam-diam ngasihnya?”, “Kenapa kamu ngasih?”, “Bukankah pada saat itu kamu masih cuek denganku?” dan bla-bla-bla-bla. Tapi kalo jawab enggak, Mera juga akan bertanya—
“Hei Zza?”
“Iya”, Anzza menjawab spontan.
“Benerkan dugaanku, kamu yang—“
Muka Anzza sedikit kaku, “Enggak, enggak. Maksudnya kamu tadi ngehai, ya aku jawab iyah”,
“Oh, gitu yah, jadi?”.
Tanpa melanjutkan percakapan intensifnya, Anzza menghampiri Rina. Sementara Mera masih diam di tempat dan berusaha untuk memadamkan kebingungannya. Segera Mera ngikut nimbrung. Anzza pamit pulang, dengan sebuah janji kepada Rina bahwa ia akan sering membawakannya martabak. Dan Rina menyambutnya dengan senyuman ala anak-anak SMA yang begitu memanja. Kata Rina, ia bukan suka martabak. Ia juga suka roti, kue, bahkan serabi sekalipun. Intinya makanan yang berserat akan membuatnya minum air putih yang banyak. Imbuhnya, hidup sehat itu dimulai dari minum air putih yang cukup. Anzza hanya terkekeh. Sedang Mera terpaksa ikut tertawa dengan terus berusaha membuang tanya ada apa dibalik sikap Anzza?
***
Jawaban dokter membuatnya tidak bisa tenang. Seolah pagi ini adalah pagi yang tidak memiliki matahari. Pagi ini adalah malam kelam yang berlanjut. Di luar sana, di atas sana, semua ilusi. Biru yang menembus kaca jendela rumah sakit sebenarnya gelap. Ia tidak sedang meminum kopi atau obat penahan kantuk. Tapi benar-benar tidak bisa tidur. Padahal ia pun tahu, keadaannya sediri sedang tidak baik. Seharusnya pun tahu, ia harus beristirahat yang cukup.
Bu Nana dan satu seorang laki-laki seumuran Mas Rey datang. Mas Rey sedang menunduk pasrah dan menyandarkan badannya pada sebidang dinding. Mas Rey mendengar suara pijakan kaki yang berhenti ketika berada tepat di depan di mana ia berdiam. “Bu,..” sontak Mas Rey mendengakkan kepalanya.
“Mari duduk, Rey”.
Suasana hening. Bu Nana melihat jelas bahwa rasa khawatir di mata Mas Rey begitu membuncah kemana-mana. Bu Nana memutuskan untuk berdiam. Membiarkan suasana hening. Pikirnya di saat hening seperti inilah, sebagai manusia akan bersadar diri, bahwa mereka perlu pertolongan Tuhan. Mereka perlu tangan kekuasaan-Nya. Jadi, biarkanlah hening menjadi tempat paling nyaman untuk berdoa kepada Tuhan.
Tapi ada satu hal lagi yang memungkinkan Bu Nana menjadi tegang. Ia melihat begitu jelas juga bahwa Mas Rey akan ikut jatuh sakit jika dia memaksakan diri bediam menunggu operasi selesai. Lingkaran mata Mas Rey semakin memekat hitam; tanda ia kurang tidur. Mukanya pucat; tanda tubuhnya semakin lemas. Dan membisu, tanda pikiraannya sedang kacau. Lengkap sudah untuk memastikan bahwa sebentar lagi Mas Rey drop. Tapi Bu Nana—sekaali lagi bingung—membiarkannya atau menyuruhnya untuk sekadar merehat di Panti Asuhan yang cukup dekat, hanya ditempuh beberapa menit dari keberaadaan rumah sakit.
Rey! Rey! Bangun Nak.. Dokter, doketeeeer!
Semuanya terlambat.
***
Mas Rey terkulai. Kebetulan sekali, teleponnya berdering—bahwa Bu Nana sepertinya menemukan satu tahap untuk menuntaskan masalah demi masalah—ibunda Mas Rey menelepon. Setelah mengabarkan apa yang terjadi, ibu dan ayahnya Mas Rey dipastikan untuk segera datang ke Semarang. Untung saja Mas Rey memiliki orang tua yang tidak seperti kebiasaan oraang kaya pada umumnya.
Mereka bersedia kapanpun untuk anaknya. Tidak memberatkan diri pada kerjaannya yang begitu padat. Untung bukan? Ya, Mas Rey memang beruntung. tapi tidak dengan hubungannya, simpul Bu Nana setelah beberapa saat ia menerima jawaban perihal keadaan Nabil dari seorang lelaki yang diutusnya untuk menunggu hasil kondisinya.
Tanpa kata, Bu Nana segera menghampiri ruang Nabil. Sebelumnya, ia ingin mengabari orang tua Mas Rey kembali. Pikirnya, orang tua Mas Rey pun harus tahu apa yang terjadi pada Nabil. Tapi niatnya harus diurungkan. Handphone Mas Rey terkunci dengan sebuah pola. Dan akhirnya Bu Nana memutuskan untuk berpesan kepada receptionis, jika Mas Rey sudah sadar bilang saja bahwa Bu Nana sedang mencari makanan.
Semua sudah siap. Sebuah lampu sirine dinyalakan. Menuju Panti Asuhan Mekar Sari. Suatu tempat di mana Nabil dibesarkan. Dan kini sebuah tempat teerakhir dimana ia akan dikebumikan.
***
KOPINESIA, 04.13 WIB
Sore ini kembali seperti semula. Menurut Joan dalam diri Anzza sore ini. Bahkan semenjak ada keberadaan Mera di kafe kopinesia, seperti ada yang hilang setengah dari dalam dirinya. Tapi kehilangan tersebut adalah hal yang Joan harapkan. Sudah lama dia berbenak diri andai saja suatu saat Anzza seperti manusia normal. Perlu senyum, tertawa, bersosialisasi. Dan mengenal cinta. Dan sekarang rasanya pengandaian itu sudah mulai mewujud.
Ya, paling penting Joan menangkap sebuah energi cinta pada mata Anzza.
Dilihatnya Anzza dan Mera memang tetap seperti biasanya. Tidak banyak bicara. Tapi di sela-sela waktu keduanya saling mencuri-curi pandang. Dan sebuah lemparan senyum terbentuk, ketika salah satu dari mereka ketahuan sedang mencuri pandang. Joan rasa bukan hanya ia yang menyadarinya, tapi juga teman-temannya. Bahkan Rara sempat bilang kepadanya, bahwa Mera terkadang curhat tentang Anzza kepadanya.
Novi menaruh kertas pesanan; single origin – Aceh Gayo – V60 – smooth di atas meja penyeduh kopi. Diserobaotnya catatan itu ketika Anzza ingin mengambilnya. Mera mencoba mencerna pesanan itu. Matanya jungkar-jungkir sambil melirih la..la..la.
“Serahin ke aku”, tegas Mera dengan tajam. Anzza tidak bisa berkutik, dan menyerahkan pesanan pada asistennya itu.
Beberapa saat sebuah kertas pesanan datang lagi; Vietnam drip tanpa susu. Bukannya mengerjakan pesanan itu, Anzza lebih memilh untuk tidak-menyanyiakan kesempatan melihat Mera utuk pertama kalinya dia menyeduh kopi. Tahap demi tahap ia melihat Mera menghayati proses manual-brewing-nya. Hingga pada tahap penuangan air panas mengitari bubuk kopi yang menggunung di atas kertas unblushed. Anzza yakin tempo waktu penuangannya sedikit terlalu buru-buru. Hingga menghasilkan aroma yang kurang maksimal. Tapi, Anzza diam saja. Malah mengumpat senyum.
Novi mengantarkan pesanan tersebut. Dan tak lain pemesannya adalah Alen. Seorang perempuan yang bagi Novi adalah korban yang terjebak di zona “Pengagum Mas Rey”. Biarlah-biar, hai mbak Alen yang terhormat. Sebenarnya kau senasib denganku. Oh, Mas Rey, kenapa harus ada Nabil di sebelahmu?, Novi membenak sesaat setelah menyuguhkan kopi di atas meja Alen.
Sebelum meminumnya, Alen mencoba menghirup kopi pesanannya itu. Dirasanya ada yang aneh—tak seperti biasanya. Rasa penasarannya membuat Alen sedikit lebih buru-buru untuk segera meminumnya. Srupppppp. “Mbak! Mbak! Mbak Novi!.....”
Ada apalagi nih orang, kesal Novi dengan lirih. Segera ia menghampiri Alen kembali dengan senyuman palsu.
“Pesan satu lagi ya, disamaain..”
“Mau ada temen mbak?”, tungkas Novi.
“Enggak, kayaknya saya butuh dua gelas deh”,
“O’ow!”
Novi yakin jawaban Alen hanya alibinya. Mungkin karena saking baiknya—atau jangan-jangan Alen sedang berusaha mendekati pelayan Kopinesia—agar bisa lebih mudah mendekati Mas Rey. Novi yakin andai saja yang mesan bukan Alen, pasti orang itu ingin minta ganti pesanan kopinya. Sebab dari awal Novi ragu dengan kopi bikinan Mera. Tapi toh pikirnya ada Anzza yang membimbing. Tapi pada akhirnya Zonk! Gerutu Novi.
“Zza, yang tadi pengen bikin satu lagi”
“Yang mana?”
“Yang tadi dibikinnya sama Mera”
Mendengar itu, Mera sangat kecewa. Ia terjerat bengong berdiri di tempat. Ia yakin kopi bikinannya tidak enak. Hambar. Tidak seperti bikinan Anzza. Pikirannya kemana-mana. Mera merasa telah merusak citra kafe Kopinesia. Mera merasa gagal!
“Hai”, Anzza mengagetkan Mera. “malah bengong”. “Bikinin kopi yang kayak tadi ya”, tambah Anzza bersenyum simpul.
“Tapi kan—“
“huusssssst”, potong Anzza sambil memalangkan jari tekunjuknya di bibir Mera, “Kamu asistenku kan?”
“Iyah”
“Ya sudah nurut aja yah”.
Apalagi Zza?”, lirih Mera dalam hati. Mera nurut saja membikin kopi yang sama seperti tadi. Bedanya kini semakin lebih hati-hati. Tahap demi tahap kini ia bukan hanya menyeduh kopi dengan modal ingatan ketika beberapa waktu lalu sempat belajar nyeduh kopi pada Anzza. Tapi ia pergunakan juga perasaannya. Hati-hati dan hati-hati. Nalurinya bekerja. Ia tak boleh gagal lagi.
Mera tidak tahu apa yang dipikiran Anzza. Seharusnya Anzzza kecewa mengetahui pelanggannya kurang puas dengan kopi bikinannya. Seharusnya jika manusia normal, Anzza tidak mungkin menyuruh Mera untuk membikin kopi lagi setelah kopi pertamanya gagal. Apalagi Zza?
Sementara dipikiran Anzza, ia memang harus demikian. Ia berpikir seseorang tidak boleh menyurutkan orang ketika dia sedang bersemangat. Seperti Mera yang sedang bersemangat menyeduh kopi. Mera harus terus diberikan kesempatan mencoba. Dia tidak boleh berhenti mencoba hanya gara-gara kopi pertamanya gagal. Setiap manusia berhak untuk terus mencoba. Perihal gagal itu suatu kewajaran. Ia selalu ingat sebuah quotes dari salah satu tokoh Muslim, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah untuk mencoba. Manusia harus terus mencoba. Dan semua quotes itu selalu dipegang erat oleh Anzza. Ia terus mencoba untuk bertahan hidup di sebuah kosan kecil, dengan sebuah gitar, dan upah yang pas-pasan.
Kecuali satu hal yang kemungkinan tanpa mencoba, Anzza akan menyerah. Hal itu tak lain perihal ayahnya. Anzza tidak akan mencoba menuruti kemauan ayahnya untuk menelantarkan gitarnya dan mencoba meneruskan bisnis ayahnya. Anzza anak tunggal. Anak seorang pengusaha bidang furniture dan perhotelan di Ibukota Jakarta. Sebenarnya siapa Anzza?
***
Sruuuuup…
Suara itu merebak dari bibir Alen, “good…”, pungkasnya pada Novi. Novi pun lega. Padahal sebelum mengantarkan kopi yang kedua kali kepada Alen, ia masih ragu. Novi tak habis pikir jika Anzza malah menyuruh Mera untuk membuat kopi yang kedua kalinya, padahal ia tahu dalam jangka yang sangat pendek, Mera gagal!
Mera sedikit tegang saat Novi kembali ke tempat penyeduhan kopi. Ia belum siap jika harus mendengar keluhan atas kopi buatannya lagi. Dengan siasat, Novi menundukan kepalanya. Menghampiri Mera. Berdiri tepat di hadapan perempuan berambut sebahu itu. Mera semakin tegang. Anzza pun ikut tegang. Sudah bisa ditebak bahwa ekspesi Novi membawakan kabar buruk untuk kedua kalinya.
Mera menunduk. Novi mendengakkan kepalanya. “kamu berhasil Mer, he”
“Apa?” sontak Mera.
Reflek Mera memeluk Novi beberapa saat. Kemudian beralih memeluk Anzza penuh erat. Ya, Mera memeluk Anzza. Menyiratkan rasa bahagianya. Keberhasilannya.
“ekhem ekhem”
“ekhem”
“ya yaya”
Mera dan Anzza tak sadar jika Joan, Sigit, Novi dan Rara sudah berada di sebelah mereka. Pelukan itu semakin meregang. Meregang. Regang. Terlepas dengan empat mata yang kini merasa malu.
“Anget, angeeeet”, celetuk Joan.
“ha ha ha”
Apakah benar Mera tak sadar telah memeluk Anzza?
***
Dering telepon Rara berbunyi kencang di sela ketawaan yang belum habis juga.
”Bentar, bentar. Mas Rey nelpon”, potong Rara.
Seketika tawa mereka pun ngerem mendadak.
“Iya Mas”, ucap Rara mengangkat telepon.
Rara begitu serius mendengarkan suara dari telponnya itu. Semua teman-teman lainnya sedikit curiga ada hal yang kiranya membawa kabar buruk, melihat ekspresi Rara yang menampakan wajah sedih kian menunduk.
“Gimana Ra?”, cekat Mera setelah telepon itu berhenti.
“Mbak Nabil….Na… Na—“
Mera semakin mendekati Rara, “Mbak Nabil kenapa Ra?”
Rara menangis memeluk Mera, “Mbak Nabil gak ada Mer, udah enggak ada”
HENING.
REYNALDI MUHAMMAD
Mungkin ada dua hal yang paling misteri di dunia ini; cinta dan kematian. Keduanya datang secara tiba-tiba, dan bisa pergi secara tiba-tiba. Keduanya bisa karena sebab-akibat; sebab sering bertemu akibatnya timbul rasa suka. Sebab sering begadang, liver, akibatnya meninggal.
Bisa juga tanpa sebab-akibat; tahu-tahu cinta tahu-tahu mati. Cinta pandang pertama, atau ada juga orang meninggal saat dia baru saja makan malam.
Tapi apalah istilahnya, yang jelas kini keduanya sedang menggenang di danau kesedihan jauh di dalam benak Mas Rey. Entah perantara sebab-akibat ataupun tidak, kini Mas Rey mencoba untuk menanggapinya dengan diam mengendalikan emosinya.
Ayah, Bunda, seorang supir, Bu Nana, menyaksikan betapa Mas Rey meringkuk di atas epitaf almarhumah Ana Nabila. Ia tak habis pikir jika di akhir perpisahan dengan kekasihnya itu tanpa ada cakap sedikitpun. Tanpa sepatah-kata pun. Ia hanya menyaksikan wajah pucat . wajah terakhir sebelum dia pergi untuk selamanya.
Bu Nana memberi kode pada Ayah dan Bunda, agar mereka berusaha menenangkan Mas Rey, “Sebaiknya bapak mengajaknya pulang secepatnya”. Ayah menepuk pundak Mas Rey. Sedangan Bunda mencoba duduk menyampingi Mas Rey. “Sudah Nak,… Nabil sudah tenang di Surga”
***
Malam semakin hening. Sedari pulang dari pemakanan, bahkan saaat mampir ke Panti Asuhan, Mas Rey menutup mulutnya. Saat di sana pun, ia hanya (terus) berdiri di depan pintu kamar Nabil. Menatap tajam daun pintu itu. Hatinya berkata bahwa semua kisah itu takan terjadi jika tidak ada kamar itu. Kamar tempat Nabil merebahkan dirinya. Sedari kecil hingga ia bertemu dengannya. Kamar yang melahirkan keabadian. Mungkin?
Ayah dan Bunda tidak mengizinkan anak semata wayangnya itu untuk pulang menaiki Kereta. Mereka masih khawatir. Dan memutuskan untuk mengajak Mas Rey bergabung naik mobil saja. Di dalam, Mas Rey memang masih terdiam. Menikmati setiap apa yang dilihatnya dari balik jendela mobil. Ia melihat kedai kopi Hugo tempat di mana mereka dulu ngopi santai.
Mas Rey berusaha tersenyum, mengingat-ngingat senyuman khas Nabil. “Kau sudah bahagia di sana Bil. Di surga. Aku yakin Tuhan selalu menyayangimu”.
Di malam hari, menuju pagi
Sedikit cemas, banyak rindunya.
Entah sebab Nabil. Sebab nyerah menerima kenyataan. Atau memang sebab capek badan. Kini Mas Rey memulas dalam tidurnya. Di malam hari, yang (beranjak) menuju pagi. Di rundung cemas, juga rindu. Mana yang lebih banyak? Entahlah. Lihat saja Mas Rey terjaga besok pagi. Atau bisa jadi saat nanti sekiranya ia terjebak dalam dunia igauan. Entahlah.
Di malam hari, menuju pagi…
Sedikit cemas banyak rindunya.


 Chairulanam22
Chairulanam22