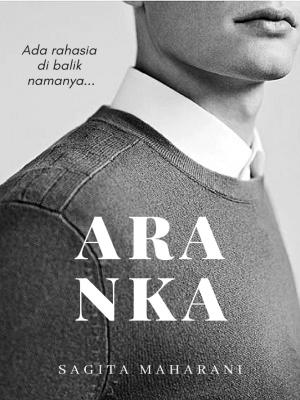Mentari mulai menyentuhku , menembus jendela kamar dan membangunkanku perlahan. Ayam berkokok dengan lantang menandai pagi sudah datang. Ku buka jendela yang menghalangi sinarnya, kupandang hamparan rumput hijau berembun. Aku tarik nafas dan menghembuskannya, betapa sejuk udara di desa ini. Hari pertamaku bersama nenek. Sejak semalam ibu menitipkanku disini. Semejak ayah pergi untuk selamanya meninggalkan dunia ini, ibu menjadi wanita pekerja keras. Semua ini gara – gara aku. Secepat kejadian 2 tahun yang lalu secepat itu ibu menjadi sibuk dengan dunianya. Aku tahu yang ibu lakukan untuk menghidupiku dan memberikan segala keinginanku.
Dipagi hari ini, kulihat dari jendela induk ayam dan anak – anaknya sudah sibuk mencari makan. Sekelompok wanita berpenutup kepala dengan selendang dibakulnya berjalan kearah utara. Mereka tidak mengeluh dengan beratnya bakul itu dan jauhnya jarak yang ditempuh untuk menuju pasar di pusat desa. Pagi di desa ini jauh lebih tenang daripada pagi di kota. Jarang kudengar suara bising kendaraan bermotor dan kepulan asapnya yang kelabu.
Setelah sarapan dengan surabi buatan nenek, nenek mengajakku berkeliling desa, sepertinya sudah banyak yang berubah di desa ini. Kulihat anak – anak yang sedang membantu ibunya memberi makan ternaknya, berlari – lari dan ada juga yang hanya sekedar duduk di saung – saung desa. Nenek juga menceritakanku tentang penduduk di desa ini. Semua orang di desa ini terlihat begitu pekerja keras dan anak – anak mereka pun tidak pernah putus asa. Jika mereka menginginkan sesuatu mereka harus bekerja dulu. Semua yang mereka inginkan tidak didapat dengan instan. Tidak sepertiku yang hanya bisa meminta dan mengeluh pada ibu, lalu dibelikan. Aku malu pada anak – anak desa ini yang sangat mandiri.
Setelah cukup berkeliling, aku mencoba membantu nenek merapikan meja makan dan membantunya memasak, walaupun ia selalu melarangku. Aku tidak ingin tampak tidak berguna. Hari pertamaku di desa, aku mulai mencintai desa ini. Menjelang senja kulihat dari serambi rumah, wanita – wanita berpenutup kepala pulang dengan bakul – bakul yang kosong. Aku teringat cerita nenek, mereka adalah pedagang – pedagang sayuran. Setiap pagi mereka pergi ke pasar untuk menjual sayurannya dan lalu pulang diwaktu senja. Tentu saja mereka berjalan kaki, mereka tidak pernah mengeluh, mereka adalah wanita – wanita yang kuat. Semua yang dilakukan untuk menghidupi dan menyekolahkan anaknya. Tiba – tiba saja aku teringat ibu. Aku rindu pada ibu.
Tidak terasa sudah 6 hari aku tinggal bersama nenek. Aku rindu pada ibu, apa kabarnya ibuku di kota? batinku. Aku segera mengambil handphone dari tas, lalu kutelepon ibu. Tidak ada jawaban. Ibu apa kau tidak rindu padaku, angkatlah bu! Dengan rasa kecewa aku mencoba berdiri dengan tongkat penyanggaku, keluar kamar menuju dapur nenek. Terlihat wanita lebih tinggi dari nenekku berambut lurus sepundak sedang membuat surabi. Ia adalah ibuku, Kudekati ia dengan begitu semangat hingga aku terjatuh. Ibu dan nenek segera menghampiriku, mencemaskanku seolah aku begitu lemah. Ia membangunkanku tapi aku menolaknya, aku ingin bangun sendiri. Ini hanya hal kecil, mengapa mereka melihat ini tampak besar.
“Hey cantik, pasti kamu rindu ya?” kata ibu menggodaku sambil menyembunyikan kecemasannya.
Aku hanya diam dan tersenyum padanya.
“Ini, makanlah surabi buatan ibu. Ibu buatkan spesial untukmu.” kata ibu melirikku sambil tersenyum.
Sudah lama aku tidak menikmati masakan ibu. Entah kapan terakhir ibu memasak untukku. Tapi hari ini aku senang tenyata ibu masih peduli denganku. Hari ini aku akan kembali kerumah. Kata ibu, urusannya sudah selesai. Sebenarnya aku sudah jatuh cinta pada desa ini tapi aku lebih mencintai ibuku. Ia adalah segalanya yang kupunya. Setelah menyiapkan barang – barang, aku pamit pada nenek. Aku duduk didepan, ibu yang menyetir mobilnya sendiri. Ia memang wanita yang hebat.
Matahari mulai terbenam, langit mulai tampak jingga kehitaman. Sore ini aku tiba di rumah. Ibu terlihat kelelahan, matanya sayu dan wajahnya tampak pucat. Ia langsung beristirahat dan aku menyiapkan untuk sekolah besok pagi.
.....................................................................................................................................
Suara kendaraan bermotor dengan segala hiruk pikuk kota ini membangunkanku dari tidur. Ya, seperti inilah pagi di kota. Ketika kulihat ibu sedang memasak, nasi goreng yang hampir matang.
“Marsya kamu sudah bangun? Baru saja ibu ingin membuat kejutan untukmu.”
“Ibu masak buat Marsya?” kataku terheran – heran karena biasanya ibu membeli masakan jadi.
Ibu membalasnya dengan tersenyum, Ia menyuruhku mandi dan setelah itu kami sarapan bersama. Lalu, tidak sengaja aku menjatuhkan gelas minumku, ibu segera mengambil kain pel dan “dug” aku terjatuh dari kursi saat aku ingin mengambil gelas yang jatuh itu. Kau tahu betapa sakitnya itu. tampaknya aku sering mengalami kejadian seperti ini. Ibu membangunkanku tapi aku mencoba untuk bangun sendiri. Berulang kali aku mencoba bangun. Namun, kaki kiriku tiba – tiba melemah tampaknya tidak kuat menopang badanku sendiri. Ibu memelukku dan menangis. Kutahan rasa sakitku sendiri, aku tidak ingin ibu tambah bersedih. Aku takut ibu belum bisa sekuat aku. Aku mencintai ibuku, Ia tidak pernah mengeluh dan malu punya anak cacat sepertiku. Seperti biasa ibu selalu mengantarku ke sekolah bahkan ia mengantarku sampai kekelas karena untuk naik tangga sekolah saja aku merepotkan.
“Bu, biarkan aku ke kelas sendiri ya dan nanti pulang sekolah jangan jemput aku, aku pulang bareng teman – temanku bu.” kataku mencoba kuat.
“Tidak, ibu harus pastikan kamu baik – baik saja.”
“Marsya 16 tahun bu, Marsya bisa sendiri.”
terlihat betul kecemasan dari wajahnya, matanya menahan air mata turun.
“Baiklah.” Ibu membiarkanku ke kelas sendiri.
“Yasudah, sekarang ibu pergi kerja nanti terlambat.”
Ibu tidak ingin pergi, sepertinya ia takut sesuatu terjadi padaku.
“Bu ayolah percaya sama Marsya.” kataku meyakinkan ibu sambil tersenyum.
Akhirnya Ibu pergi sambil tersenyum tapi matanya tidak bisa berbohong kalau ia menahan airmata. Ibu memang selalu memakai topeng didepanku.
Langkah pertama menaiki tangga, aku bisa. Weny sahabatku mencoba membantuku, tapi aku yakin aku masih bisa menaiki tangga ini sendiri seperti 2 tahun yang lalu. Sampai anak tangga terakhir, aku bisa.
“Kenapa mereka selalu menatapku seperti sedang menonton pertunjukkan sirkus? Apa karena aku berbeda? Aku payah!” kataku pada Weny.
“sudahlah jangan pedulikan mereka, mereka hanya iri padamu yang begitu kuat.” weny mencoba menghiburku, ia memang sahabatku yang paling setia.
Hari ini aku pulang sendiri, jalan kaki itu tidak buruk. Batinku. Sepanjang jalan, puluhan pasang mata melihatku dengan iba. Aku terbiasa menjadi tontonan. Aku berhenti di sebuah taman untuk sekedar beristirahat dan melamun. Ternyata cukup sakit berpura – pura menjadi kuat. Sebenarnya jauh lebih sakit melihat Ibu selalu menangis karenaku. Seorang laki – laki bertopi coklat usianya kira – kira 5 tahun lebih tua dariku, Ia menghampiri dan duduk disebelahku. Ternyata Ia adalah pelatih taekwondo-ku dulu, sebut saja kak Hilal.
“Marsya apa kabar?” tanyanya.
“Seperti yang kamu lihat”
“Baguslah kamu baik – baik saja.” katanya sambil tersenyum.
“Kamu ingin menontonku dari dekat? Ya aku terbiasa menjadi tontonan.”
“Sya, bukan maksudku seperti itu.”
“Maafkan aku kak, aku hanya terbawa suasana.” kataku menyesal. Kak hilal hanya mengangguk.
“Gara – gara ayah menolongku, nyawanya melayang. Aku selamat tetapi harus kehilangan kaki kananku. Kenapa tidak aku saja yang mati?” ucapku menyalahkan takdir.
“Hey Marsya, kamu tidak sayang dengan orang – orang yang selalu mendukungmu? Ayahmu sudah tenang disana, jangan kecewakan dia.”
Tanpa sadar airmata turun membasahi pipiku dan sapu tangannya.
“Tidak ada gunanya kamu terus meratapi hidup ini. Hidup ini untuk dijalani bukan diratapi. jangan halangi dirimu sendiri!” lanjutnya menyemangatiku.
“Untuk berjalan saja aku susah. Sekarang hidupku hanya merepotkan. Mungkin tongkat penopang ini pun bosan menyanggahku setiap hari.”
“Aku sedih melihat anak muda yang menyerah pada takdir hanya karena kehilangan salah satu fungsi kakinya. Untuk tersenyum pada hidupnya pun pelit” Kak Hilal menyindirku.
“Kamu fikir ini lucu? Kamu tidak pernah merasakan pahitnya kenyataan!” aku tersenyum miris padanya.
“Tersenyumlah selagi kamu masih bisa tersenyum.”
Lalu, kak Hilal pergi meninggalkanku. Sejak itu sepulang sekolah aku menjadi sering pergi ke taman. Sekedar melihat kak Hilal melatih anak – anak kecil itu taekwondo. Masih teringat jelas saat aku masih bisa berlatih bersamanya. Kak Hilal tersenyum melihatku. Setelah Ia melatih anak – anak kecil itu, Ia mengeluarkan biola dari tasnya.
“Untuk apa biola itu?” tanyaku.
“Untuk kamu mainkan, daripada hanya diam.”
“Tapi aku tidak bisa.”
“Aku akan mengajarkanmu.”
Kak Hilal selalu membuatku tersenyum, karenanya hidupku menjadi lebih berarti. Sesekali Ia ke rumah untuk melatihku bermain biola dan sesekali kami berlatih diluar rumah. Ibu juga sudah sangat dekat dengannya. Sekarang Ia telah menjadi sosok kakak untukku. Aku sangat dekat dengannya. Banyak hal menyenangkan yang selalu Ia buat untuk menghiburku. Sampai suatu hari pulang sekolah, aku tidak melihatnya di taman. Aku hanya melihat anak – anak kecil itu berlatih taekwondo dengan pelatih yang lain. Saat kutanya pelatih itu, Ia hanya memberiku selembar kertas bertuliskan nama rumah sakit dan ruang kamarnya. Secepatnya aku pergi ke rumah sakit itu. Aku takut sesuatu yang tidak kuinginkan terjadi. Tidak peduli puluhan pasang mata yang menontonku.
Sudah kutemui kamarnya, aku kaget melihat kepalanya yang hampir botak seluruhnya. Saat kulihat kakakku terbaring lemah di atas kasur dengan selang oksigen dihidung dan alat – alat canggih yang mengawasi tubuhnya. Aku mencoba untuk tidak meneteskan air mata didepannya. Aku mencoba menghiburnya seperti Ia menghiburku waktu lalu. Matanya menatapku seperti ingin mengatakan sesuatu namun Ia tidak bisa. bahkan untuk tersenyum pun dihalangi oleh penyakitnya.
“kak Hilal, apa kabarmu? Kak kenapa kamu tidak bilang tentang semua ini? Kak, aku tahu kamu hanya ingin selalu bisa membuat orang lain bahagia.”
Aku tahu kak hilal masih mendengar suaraku, walaupun ia tidak menjawabnya.
“kak, aku sudah bisa bermain biola lho! Kakak mau lihat? Iya baiklah”
Kumainkan biola yang kubawa didepannya. Kutatap wajahnya, setetes air mata turun dari matanya, secepat kanker otak yang merontokkan rambut dan merenggut hidupnya. Kuhapus air mata itu dan aku tersenyum padanya. Aku ingat kata – katanya yang menyuruhku tersenyum selagi aku masih bisa tersenyum.
Setiap hari sepulang sekolah, aku datang untuk menjenguknya. Menemaninya dan menyemangatinya seperti yang ia lakukan padaku.
“Lihatlah keluar, kamu tidak sendiri! Aku juga merasakan bahwa kenyataan memang pahit, tapi aku selalu berusaha melakukan apa yang aku masih bisa lakukan, membuat orang lain menghargai hidupnya dan tersenyum sebelum aku benar – benar pergi.” Kata kak Hilal kepadaku sambil terbata – bata.
Aku tidak bisa menahan air mata yang tiba – tiba turun sederas tangisanku. Sudah dua kali orang yang aku sayang pergi mendahuluiku. Kenapa harus mereka? Sekali lagi aku mencoba mengingat semua pesan kakakku. Kakak yang selalu membuat tawa disetiap hariku. Kakak yang mampu membuatku menghargai hidup ini dan tidak menyerah pada keadaan. Dengan sabar ia mengajariku bermain biola dan yang terpenting ia mengajariku arti hidup ini. Terima kasih guru sepanjang masaku. Akan selalu kuingat pesanmu “tersenyumlah selagi masih bisa tersenyum.”
with love,
Anita Lidia Putri


 anitalidyap
anitalidyap