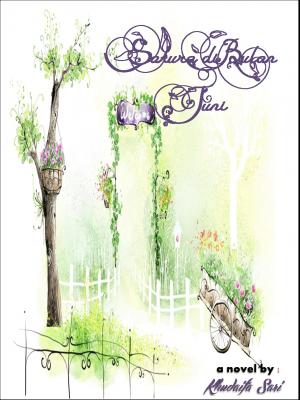Come
Let things come and go
The things that are meant to stay,
will stay
D e n n i s
“Kok gue baru tahu sih, No?” Tanya gue sambil memasang muka yang begitu penasaran—tapi sejujurnya, gue memang penasaran. Sementara itu Nino—teman mengobrol akrab gue sepulang dari masjid—itu mengangguk-angguk.
“Memang gak ada yang aneh, jadi gue gak pernah cerita sama lo, Den,” jawab Nino. Kasus yang beberapa hari kemarin terjadi—tentang Rajasa Lukas, anak teknik tersebut—masih menjadi perbincangan hangat di banyak kalangan, mulai dari anak-anak kos, ibu-ibu gosip, sampai bapak-bapak yang nongkrong di warung kopi. “Pokoknya hari itu tempat kos gue biasa aja, sebelum akhirnya Emak teriak-teriak histeris gitu.”
“Jadi yang huni lantai atas emang cuma Raja, ya?”
“Ngg—iya,” jawab Nino. “Kayaknya lo udah tahu juga kalau dia anak orang kaya? Tiga kamar di lantai atas dia embat jadi satu,” terang Nino sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. “Gue jadi ingin pindah tempat kos deh.”
“Nah, pindah ke tempat gue aja, No. Lagian masih ada kamar kosong di bawah satu!”
“Tapi kasian Emak Ratna, lagian tempat kos itu udah paling murah di antara tempat-tempat lainnya,” Nino mendengus. “Seandainya aja gue orang kaya.”
“Gak boleh gitu, No,” gue menepuk-nepuk pundaknya. “Bersyukur aja lo masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Ngomong-ngomong, kenapa polisi-polisi di sana langsung yakin kalau itu pembunuhan?”
Nino mengernyitkan dahinya, mencoba mengumpulkan informasi-informasi yang dia dapatkan. “Dia gantung diri, tapi gak ada kursi atau apa pun yang ditemuin. Kalau gak salah sih gitu. Kan aneh juga kalau dia benar-benar gantung diri, pasti ada benda buat bantu dia naik, kan?”
“Jadi di ruangan itu benar-benar gak ada kursi?”
“Ada. Tapi di sudut ruangan dia. Kalaupun iya itu yang dipakai, pasti ada orang yang mindahin,” ujar Nino. “Den, bisa gak, gak usah ngomongin ini lagi? Gue ngeri,” Nino bergidik, kemudian setelah sadar sudah sampai di depan tempat kosnya yang terasa semakin horor, dia berhenti. “Doakan hari ini gue bisa tidur tenang.”
Gue mengangguk-angguk. Kemudian, dengan kecepatan tinggi, Nino berlari ke arah kamar kosnya. Kasihan penghuni dan pemilik tempat kos ini, mereka jadi ketakutan dan gak bisa tidur.
Gue menghela napas dan segera melangkahkan kaki menuju tempat kos gue, pasti orang-orang sudah menunggu—karena tadi mereka titip nasi goreng di perempatan menuju masjid. Giliran diajak ke masjid aja gak ada yang mau ikut, eh pas gue berangkat, mereka malah titip nasi goreng, banyak pula, pake uang gue pula.
“IMAM KITA UDAH DATENG! GUYS, NASI GORENG, NASI GORENG!” Bang Julian yang sedang mengerjakan tugasnya di ruang tengah mendadak meloncat-loncat dan menaruh laptopnya sembarangan. Sementara itu, anak-anak lainnya yang tengah sibuk dengan urusannya masing-masing langsung muncul. “Asik-asik!”
Semenjak kejadian tiga hari lalu, anak-anak gak pernah pulang lebih dari jam delapan malam. Mereka akan sudah duduk manis di tempatnya masing-masing. Sena dengan senang hati mengerjakan tugasnya tanpa begadang, jam tidur Jhordan bertambah, Brian dan Bang Yoga memulai pergosipannya lebih awal, Bang Julian juga mulai menggarap skripsinya dengan tekad lulus-tiga-setengah-tahun, dan Cakka mengurung diri di kamarnya seperti biasa.
Kalau gue sendiri sih memang biasanya pulang jam segitu, kalau mereka…mungkin mereka takut. Agak geli juga membayangkan kalau mereka yang biasanya mengejek gue karena gak bisa pulang tengah malam, kini mereka sendiri yang sangat parno dengan hal-hal yang terjadi di sekitar.
“Guys,” Sena memecah kenikmatan makan, disusul dengan tatapan-tatapan yang beralih dari nasi goreng mereka menuju muka Sena. “Gue ngundurin diri aja apa, ya…”
“Ngundurin diri dari?” Tanya Jhordan cepat.
Sena menghela napas. “Jadi kompin FTG, habis gue jadi takut pulang malem.” Sena memonyongkan bibirnya sambil mengaduk-aduk nasi gorengnya, membuat selera makan gue menjadi turun. “Gimana kalau mobil gue tiba-tiba dibegal sebelum masuk ke sini?”
“BANGKEEE!” Jhordan menoyor Sena hingga ia hampir terjengkang. “Mana bisa lo ngundurin diri jadi kompin? Lagian mereka semua udah percaya sama lo, gak. Pokoknya gak boleh titik.”
“TERUS KALAU GUE MATI GIMANAAA?”
Bang Yoga menepuk-nepuk bahu Sena. “Tenang aja, Sen. Kita kan sampai sekarang gak tahu motif pembunuhnya apa. Kalau misal iya dia cari orang-orang kaya, kita gak mungkin kena. Kita kan kere semua, kecuali Dennis.” Bang Yoga mengerling kemudian nyengir.
“Bang…,” gue menyentakkan kepala. “Jadi maksud lo cuma gue yang berpotensi jadi korban?” Tanya gue.
“Hayoloh imam kita marah,” Bang Ijul terkekeh. “Ambil tuh ambil nasi goreng si Yoga. Sekalian dah suruh muntahin yang udah dia makan,” ujar Bang Ijul, kemudian tertawa garing karena tidak ada yang menyahut.
Gue mencoba berpikir, “Kalau dia memang pembunuh berantai ya bisa jadi kita dalam bahaya. Tapi kalau engga dan memiliki maksud tertentu sama Raja, kita sebenarnya gak apa-apa.” Gue menghela napas. “Bakal apa-apa kalau kita malah ikut campur.”
“Betul tuh,” Brian menyahut. “Kita gak bisa gini terus masalahnya. Kita semua kan punya urusan masing-masing, gak mungkin gara-gara kejadian itu doang, kita malah jadi berhenti sama tanggung jawab kita kayak gini. Gue yakin lambat laun gak akan apa-apa, kok. Mungkin lo semua masih pada shock, lagian korbannya juga seumuran kita, tanpa motif yang jelas.”
Bang Ijul menghela napas, “Gini deh gini. Lo semua tahu kan kalau tempat kos mereka itu emang terpisah gitu kamar sama pintunya, jadi gak bisa saling menjaga. Kalau kita kan, kayak gini, serasa dalam satu rumah. Apa pun yang terdengar atau terlihat mencurigakan, kita bisa saling bantu, saling jaga. Selama segala sesuatunya belum pasti, kalian boleh pulang malam, tapi jangan sendirian. Kita bagi tanggung jawab. Cakka dan Dennis sama Yoga, Sena sama Jhordan, dan Brian sama gue. Oke?”
Keenam orang di sini mengangguk-angguk. Beberapa saat keadaan hening, sebelum akhirnya Cakka angkat bicara, “Rasanya pasti bakal menyakitkan banget kalau kita kenal sama korbannya.”
“Iya, untung kita gak kenal…”
“Gue kenal,” jawab Cakka pelan. “Sama kembarannya…”
“Maksud lo?” Tanya Sena kencang. “Raja itu punya kembaran?”
“Dan belum ditemuin sampai sekarang,” sambung gue.
Bang Yoga terbelalak, “Lo—lo berdua kenapa bisa tahu, deh?” Tanya Bang Yoga dengan dramatis. “Kok gak bilang-bilang?”
“Gue baru denger kemarin,” ujar Cakka. “Kemungkinannya Raka juga sedang dikejar, makanya polisi lagi fokus cari Raka, takutnya dia kenapa-kenapa, dan siapa tahu bisa diselamatkan sebelum terlambat.”
“Oh, pantesan,” jawab Brian. “Rasanya kasus ini belum berkembang informasinya. Jadi namanya Raka?” Tanya Brian penasaran. Belum sempat dijawab, raut muka Brian tiba-tiba berubah. “HALAH BENCI GUE SAMA YANG NAMANYA RAKA!” Brian merenggut kemudian menyendokkan nasi goreng sebanyak-banyaknya.
“Heh, nape lu?” Bang Yoga menoyor Brian, kemudian tertawa terbahak-bahak.
“Biasaaa,” Bang Ijul menanggapi. “Bilangnya sih sahabat, tapi pas Chila jalan sama cowok lain, beuh sedihnya kayak patah hati. Sahabat apa sahabat? Makanya jangan mau terjebak friendzone dong!”
“Daripada terjebak mantan?” Sahut Brian.
“Sialan!” Mereka berdua berakhir bertengkar, membuat gue menggeleng-gelengkan kepala pusing. Ada-ada saja mereka ini. Belum juga nasi goreng yang mereka makan habis, semua orang sudah tidak bernafsu makan.
Cakka mengernyit, “Tapi kalau menurut gue sih, ya, kayaknya itu pembunuh emang nargetin keluarga mereka doang. Raka—kembarannya Raja—kan gak tinggal di sini, tapi tetap jadi incaran. Kalau memang dia pembunuh berantai dan korban pertamanya di sini, kemungkinan besar dia bakal muter-muter di daerah sini doang.”
“Iya juga, ya,” Sena manggut-manggut. “Ok, let’s start a new day! Tidak ada kata takut dalam hidup seorang Sena!”
“Takut sama Tuhan atuh,” Bang Ijul menanggapi.
“Iye Bang, iye,”
“Ngomong-ngomong ya, gebetan barunya Chila itu anak kedokteran!” Ujar Bang Ijul, kemudian terkekeh. “Ya lu mah pasti kalah, Yan. Otak lo itu mesti dicuci dulu tujuh kali, jangan lupa pakai tanah, terus masukin tuh buku-buku si Cakka yang setebel dosa lo!”
“ANJIR BANGSAT EMANG LO!”
Gue menggeleng-geleng pusing, tapi dalam hati juga sedikit lega. Walaupun semuanya belum terbukti, seenggaknya gak ada gelagat kalau orang-orang di komplek ini akan menjadi korban selanjutnya. Terus, kalau gue nanti sendirian di tempat kos pun, gue gak harus merasa takut dan gak bisa tidur sampai mereka semua balik.
“Gebetan Chila itu Rakasa Lukas namanya?” Tanya Cakka.
“Mana gue tahu,” jawab Brian asal-asalan, kemudian melipat bungkus nasi goreng dan membuangnya ke plastik bekas.
“Gak, Bang. Gue serius…,”
“Maksud lo kalau Rakasa Lukas, dia kembarannya Raja? Rajasa Lukas kan namanya?” Tanya gue lagi, disambut anggukan Cakka dan gerakan anak-anak yang terhenti beberapa saat. “Jadi dia anak kedokteran?”
“Kakak tingkat gue, makanya gue bilang gue kenal sama dia. Gak kenal dengan dekat, tapi seenggaknya gue hapal nama, muka, dan kebiasannya,” jawab Cakka pelan.
Bang Yoga menghela napas, “Kenapa dunia ini sempit banget ya,” kemudian ia menggeleng-gelengkan kepalanya. “Kalau gitu tanya aja ke Chila, kapan dia terakhir jalan bareng Raka?”
“Gak, males gue,” jawab Brian.
“Yan, kita butuh kejelasan untuk tetap di sini atau beraktivitas kayak biasanya,” jawab Sena memelas.
“Logikanya, kalau polisi masih cari, Chila gak mungkin ketemu sama Raka,” ujar Brian. “Satu-satunya pertemuan mereka baru Jum’at kemarin, dan malamnya Raja meninggal. How is it possible?”
“Kalau Chila adalah orang terakhir yang lihat dan bareng-bareng sama Raka gimana?” Tanya gue pelan.
Brian mengernyit, kemudian raut mukanya berubah. Tangannya segera mencari-cari handphone miliknya, lalu memukul keningnya. “Bego gue. Udah sejak saat itu gue gak chat dan ketemu sama Chila. Kalau dia ilang juga gimana?”
***
“Den! Gimana progresnya?” Sena nyengir sambil menepuk pundak gue. Gue yang sedang berjalan sambil memperhatikan handphone terlonjak dan terdiam sesaat. Sebagian kecil dalam hati gue berterima kasih pada Sena yang membuat gue tidak menabrak pagar di depan gue.
“Progres apaan?”
“Gebetan baru,” Sena terkekeh. “Katanya lo punya gebetan, kok belum ada kelanjutannya? Cerita-cerita, dong, sama gue. Masa lo kalah sama si Chila yang tahan bertahun-tahun sama Brian dan akhirnya punya gebetan baru?”
“Lo sendiri apa kabar, jomblo?” Tanya gue sambil memberi penekanan pada kata jomblo. “Gak usah bilang gue mengenaskan ketika lo sendiri belum punya gebetan.”
Sena mendengus. “Wah—wah, diajarin sama siapa lo buat membully gue? Sejak kapan kaliamat lo penuh dengan sarkastik seperti ini?” Sena memegang kedua bahu gue lalu menggoncang-goncangkannya. “Lo kesurupan atau sudah ternodai oleh Jhordan?”
“Sen…,”
“Jawablah Dennis!”
“SEN GUE MAU BELI COTTONBUD NANTI KEBURU KEMALEMAN!”
“Astagfirullah, sejak kapan kamu membentak yang lebih tua, Dennis?” Sena menggeleng-gelengkan kepalanya dramatis. “Ya sudah, sebagai permintaan maaf lo, gue titip pringles,” jawab Sena nyengir.
“Nitip apa nitip?” Tanya gue. “Lagian siapa juga yang mau minta maaf.”
“Iya nanti gue ganti uangnya elah,” Sena merenggut.
“Oke, gini, deh. Kalau lo mau gue beliin, lo harus anter gue. Kalau lo gak mau, gue beli tapi lo harus ganti uangnya!” Jawab gue, menaik-naikkan alis, merasa penawaran gue sangat bagus. Bukan berarti gue takut, tapi rasanya aneh kalau harus mengendarai motor malam-malam sendirian.
“Ya Allah, sejak kapan lo bisa main-main sama gue!!!! Kamu sudah berubah Dennis, aku kecewa!”
“Astagfirullah, Sen,” jawab gue, kemudian tertawa. “Jadi mau ikut gak?”
“Demi setabung pringles, gue ikut, deh!” Jawab Sena. “Pake helm gak?”
Gue menghela napas. “Sen, kita mau ke indomaret, bukan ke TSM.”
“Yeuuu, pake helm tuh bukan karena jauh, tapi karena peduli dengan keselamatan, gimana, sih,” Sena misuh-misuh, kemudian dia segera naik ke atas motor. Beberapa saat kemudian, gue sudah menyalakan motor dan menjalankannya keluar tempat kos.
Udara Bandung malam itu cukup dingin. Sebenarnya gue juga gak tahu kenapa suhunya bisa sangat jauh antara siang dan malam hari. Di siang hari suhunya bisa lebih dari tiga puluh derajat, tapi di malam hari bisa sampai lima belas derajat. Hal itu membuat gue kadang tidur dengan baju berlapis-lapis plus dengan selimut tebal. Lain lagi dengan Sena yang lebih sering tidur di atas meja dan gak peduli dengan udara sekitar dia.
“Dennis…,”
“Hm?”
“Ada indomaret baru, lebih deket dari tempat kos kita,” Sena menunjuk ke sebelah kanan, membuat gue memberhentikan motor mendadak hingga kepala kita saling berbenturan. “Buset! Kepala lo keras banget, untung gue gak mimisan.”
“Astagfirullah…”
“Kenapa, Den?”
Gue menggeleng-geleng. “Tempat indomaret ini bukannya tadinya mushola, ya?”
“Eh iya bener,” jawab Sena kaget. “Cepet banget ya, berubahnya? Sejak kapan? Laknat banget emang, masa mushola dijadiin indomaret? Tapi gak apa-apa, deh. Daripada kejauhan, iya, gak? Udah Den, buruan parkir.” Sena menepuk-nepuk punggung gue dan segera masuk ke dalam Indomaret dengan langkah ceria.
Selesai memarkirkan motor, punggung gue ditepuk keras. “Mas!” Sesaat kemudian gue menoleh dan melihat seorang perempuan mengasongkan dompet. “Itu dompet temennya jatuh. Apa buat saya aja?” Tanyanya dengan nada datar. Sorot matanya terlihat yakin dan tajam, gayanya agak selengean dengan rok di atas lutut. Gak dingin apa, ya?
Untuk beberapa saat gue terkejut. Itu Aleta. Kita bertemu lagi di sini, di tempat yang tidak terduga. “A…leta?” Tanya gue memastikan.
Gadis itu mengerutkan keningnya, sebelum akhirnya membuka mulutnya lebar-lebar. “Oww, masnya yang waktu itu lewat di depan Fakultas Psikologi, ya? Yang malem-malem itu?” Tanyanya sedikit terkejut. “Wah gue gak menyangka bisa ketemu lagi di sini. Mas waktu itu ngapain sih di kampus malem-malem?”
Agak sedikit kaget—tapi sebenarnya enggak, karena sejak awal pun gue sudah sangat kaget—gue menjawab. “Ya, mau jemput temen. Lo sendiri ngapain waktu itu gelap-gelapan? Oh iya, waktu itu gue pernah anterin lo ke tempat kos, lo…gak inget?” Tanya gue memastikan.
Tiba-tiba jantung gue rasanya ingin loncat menunggu jawaban cewek yang kelakuannya bisa berubah seratus delapan puluh derajat di saat gue bertemu di angka genap. Maksud gue, pertama kali ketemu, dia baik-baik aja, yang kedua kali kayak gini, yang ketiga dia baik-baik lagi, sekarang yang keempat…., “Hm, kayaknya…enggak? Gue emang sering diantar pulang sama cowok, tapi yang jelas bukan cowok seperti lo?”
“B—bukannya lo gak boleh keluar malem?”
“Ha? It’s ok, dunia malam adalah dunia gue hahaha,” jawabnya, lalu tertawa terbahak-bahak. “Mas-nya ini agak kudet ya sama dunia malam?”
Semakin dia menjawab, pikiran gue semakin berputar-putar. “Is this you, Aleta?”
“Ya? What’s wrong?” Aleta menyipitkan matanya.
“Lo…kuliah di fapsi?”
Aleta mengangguk lagi.
“Kelas B?”
“Mungkin?” Tanya dia pelan. “Lo kelas B ya, Aleta?” Terdapat jeda beberapa saat hingga ia kembali melanjutkan kalimatnya. “Yap, kelas B katanya.”
Tunggu, apa maksudnya dengan katanya? Orang ini…orang ini udah gila atau gimana, sih? Apa dia memang jadi gila kalau udah lewat Maghrib makanya orang tuanya melarang dia untuk keluar saat malam hari? Gue gak percaya soal kerasukan, tapi gue rasa….
“DOMPET GUEEE! Mbak, dompet saya ketinggalan. Saya minta uang dulu ya sama temen saya,” suara dari dalam minimarket itu terdengar sangat kencang hingga gue dengan cepat menoleh. Pasti Sena sudah memilih-milih banyak barang ketika gue masih bengong semacam orang linglung di sini.
Beberapa detik kemudian, Sena sudah berlari-lari menuju gue. Tampaknya ia akan berteriak keras sebelum akhirnya terpaku dengan sosok di hadapan gue. “Ge—gebetan lo?” Tanya Sena terbata-bata.
Secara otomatis gue mendelikkan mata. Gebetan dari mana? Gue aja masih aneh dengan asal-usul perempuan di hadapan gue ini. “Bukan sih, Sen.”
“Halah, boong. Lo gak bisa membohongi seorang Sena yang sudah bertahun-tahun hidup sama lo,” Ujarnya sambal nyengir. Lebay emang, baru juga dua tahun kita tinggal bareng. “Tuh, pipi lo merah gitu dan lo masih menyangkal?”
“Sen….,” rasanya gue ingin melempar orang yang biasanya diam tetapi tiba-tiba menjadi menyebalkan seperti ini.
“Halo, gue Aleta,” ujar Aleta sambal tersenyum lebar, memperlihatkan pipinya yang berwarna kemerahan. Gue gak bisa menyangkal kalau dia sangat cantik—seperti saat gue bertemu dengan dia pertama kali. “Lo?”
“Sena,” jawab Sena pelan. “Lo ini…”
“Temen satu fakultasnya mas ini!”
Sena menahan tawanya mendengar gue dipanggil dengan sebutan ‘Mas’, sementara itu gue langsung memberenggut kesal. “Yaudah mana duit lo, Den? Dompet gue ketinggalan hehehe, mohon maklumi,” ujar Sena.
“Gue juga mau masuk, kok. Dan ini dompet lo tadi jatuh, makanya jangan sembarangan,” ujar gue.
Sena mendengus, “Yah, padahal gue pengen minta duit lo aja,” Sena mengambil dompetnya dari tangan gue. Kemudian, ia menatap kita berdua bergantian sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk kembali ke dalam minimarket.
“Gue masuk dulu, ya,” ujar gue pada perempuan di hadapan gue.
“Oke, see you,” ujarnya. “Lo…lucu. Gue pengen kenal lo lebih dekat?”
Gue terdiam, tidak tahu menahu respon apa yang ingin gue keluarkan, karena di dalam hati gue, gue masih merasakan ketakutan itu. Sebenarnya gue ini mengenal dua Aleta atau bagaimana? Tapi kalau boleh jujur, gue lebih suka Aleta yang malu-malu, Aleta yang introvert, bukan Aleta yang ini. Tapi mereka berdua ini sebenarnya….siapa?
Gue memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaannya tadi, karena mungkin itu bukan pertanyaan. Namun baru beberapa langkah gue berjalan, suara itu terdengar kembali.
“See? Gak ada laki-laki yang membuang muka dan menolak gue begitu saja,” Aleta tertawa. “I like this type of boy. You’re different.”
Tanpa berbalik, gue menggeleng-gelengkan kepala. Gak, gue pasti udah gila. Gue pasti udah salah mengenali orang.
***
N o u s
Hujan yang cukup lebat membuat penghuni maison de rêve tidur kurang nyenyak. Beberapa dari mereka ada yang menggigil karena selimutnya yang tiba-tiba terlepas dari tubuh—terutama Julian yang tidurnya sering berpindah-pindah posisi. Beberapa lagi tetap merasa dingin walaupun sudah menggunakan berlapis-lapis pakaian. Tapi berbeda dengan Yoga yang walaupun kedinginan, dia masih terjaga sepanjang malam.
Yoga mencoba menutup matanya, membaca ayat kursi hingga surat an-Nas. Namun apa daya, matanya memang belum ingin terpejam. Pikirannya melayang-layang antara tugas lombanya, hingga Ditas—perempuan yang tidak pernah hilang dari pikirannya akhir-akhir ini. Masalahnya, Yoga tidak pernah bertemu dengan Ditas lagi—baik itu di gedung fakultasnya maupun di sekitaran kampus FISIP. Ditas seakan menghilang ditelan lautan tanpa kabar sedikit pun setelah putus dari Yoga. Ya, walaupun siapa Yoga yang berharap dikabari? Seharusnya, ia senang kalau Ditas tidak ada, karena ia bisa melupakan Ditas sedikit demi sedikit.
KRIEEEK!
Yoga terkejut dan segera mencari sumber suara. Pikirnya mungkin suara pintu salah satu kamar yang lupa ditutup, atau suara pagar yang mungkin lupa dikunci. Beberapa saat Yoga menggerutu, kenapa teman-temannya bisa seceroboh itu tidak mengunci pagar ketika baru-baru kemarin ada kejadian….. Ah gak, bikin takut diri sendiri aja, batinnya.
Tutup, gak, tutup, gak, tutup, gak.
Yoga menghela napas. Oke, sebagai seorang gentleman, Yoga tidak perlu takut untuk menutup pagar dan menyelamatkan dunia. Yee, lo pikir lo superman apa?!
Yoga bergegas turun dari kasurnya dan menuju ke pintu depan yang rupanya sudah dikunci. Dengan memutar kunci satu kali, pintu itu akhirnya terbuka, menampakkan halaman depan yang basah terkena air hujan dan pagar yang setengah terbuka. Menghela napas, Yoga melangkahkan kakinya menuju ke arah pagar, membiarkan dirinya tertetesi air hujan.
“You should wear an umbrella,”
Buset, siapa yang ngomong?
Yoga mengatur detak jantungnya pelan. Gak ada yang namanya hantu, Yoga yakin itu. Lagipula cowok mana sih yang takut hantu? Tapi suara cewek yang tadi, mungkin halusinasi Yoga soal Ditas.
“Or you will get sick, maybe?”
Yoga menoleh perlahan hanya untuk mendapati seorang perempuan tengah meremas-remas ujung bajunya, menyisakan air yang bertetesan di sana. Kulitnya pucat, sorot matanya dingin dan tajam. Yoga masih berpikir perempuan itu adalah hantu, tapi mana ada hantu yang basah kuyup seperti itu?
“Lo…siapa? Lo butuh tumpangan, ya? Lagian cewek kok malah keluar tengah malam, hujan pula.” Yoga memberanikan diri berbicara panjang lebar. “Tapi lo siapa? Lo bukan pembunuh yang lagi berkeliaran, kan?” Yoga adalah salah satu orang yang menjadi agak parno setelah kejadian itu.
“Memangnya lo pernah bertemu pembunuh dengan tampang seperti gue?”
Yoga mendengus kesal. “Emang ada pembunuh yang pakai tanda kalau dia itu pembunuh?”
“Just let me in, please,”
“Ya?”
“It’s cold outside,”
“Gue? Bawa cewek ke dalam tempat kos? Sorry, ya, Mbak. Bukannya gue gak kasihan lihat Mbak basah kuyup begini. Tapi di sebelah tempat kos ini ada kos putri, yang mungkin bisa Mbak tinggali,” Yoga menjelaskan.
Perempuan itu mendengus. “Gue memang mau ke sini.”
“Kesini apa sih?! Ampun deh, dari tadi gue gak bisa tidur, sekarang lo tambah bikin kepala gue pusing!!” Tanpa sadar Yoga berteriak, hingga membuat beberapa dari mereka terbangun. Seperti Jhordan—yang biasanya tidur paling nyenyak—dan Sena.
“Lo teriak-teriak begitu malah dikira apa-apain gue.”
Yoga menghela napas. “Ini tengah malam. Mau lo apa?”
“Masuk.”
Yoga mendengus. “I can’t let you in without their permission. Do you understand?”
“Temen-temen lo pasti kenal sama gue,” jawab perempuan itu santai. Kelakuannya tampak tidak peduli pada apa pun, termasuk rambut dan bajunya yang basah, padahal Yoga tahu kalau perempuan ini kedinginan. Tapi, bagaimana mungkin di bawa perempuan ke dalam? Bisa dikira kumpul kebo sama Babeh Rahmat. Nanti namanya yang sudah sangat baik harus tercoreng, Yoga sih mana mau.
Suara orang yang menuruni tangga terdengar. Dengan mata setengah mengantuk, Sena dan Jhordan terlihat berusaha menuruni tangga sambil saling dorong karena ingin duluan. Yoga menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan kedua temannya yang seperti anak kecil. Inget umur woy!
“Apa sih, Bang? Lo teriak-teriak bikin gue gak….” Jhordan membelalakkan matanya. “Buset! Lo siapa? Cewek baru Bang Yoga?” Pandangan Jhordan menelusuri perempuan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki.
“See? Temen-temen gue gak kenal sama lo.” Yoga terkekeh puas.
“Emang dasarnya pada bego, ingatannya gak pada panjang,” sahut perempuan itu datar. Membuat Jhordan mengernyitkan kening, “Lo—lo bilang apa tadi?” Tanya Jhordan pelan, harga dirinya serasa runtuh.
Sena manggut-manggut, “Gue tahu nih siapa,” ujar Sena sambil mencolek Jhordan dan setengah berbisik, “Lo inget gak, polisi yang waktu itu ngalangin kita deket TKP?”
Jhordan kembali menatap perempuan itu dengan tatapan tajam, kemudian membulatkan mulutnya ketika sebuah pikiran sudah sampai ke otaknya. “Oh! Polisi yang nyebelin itu? Ngapain lo kesini?”
Yoga mendengus. “Polisi? Kayak dia?”
Perempuan itu menghela napas. “Gue bakal tinggal di sini sampai kasus Raja terselesaikan.”
“WHAT?!”
“Jangan teriak-teriak, nanti lo dikira apa-apain gue,”
“Tinggal di sini lo bilang?” Jhordan mendengus. “Dari sekian banyak tempat kos yang ada di sini lo memilih tinggal di tempat kos laki-laki? Di gang tempat kos Raja masih banyak tempat kos yang bisa lo tinggali, dan lebih gampang juga buat lo mata-matain tuh tempat kos. Gak, gue gak sudi sama sekali, ya,” Jhordan mendelikkan matanya dengan tatapan mengusir.
“Kita gak bisa kalau gak bilang sama Babeh Rahmat….”
Perempuan itu memutar bola matanya, “Dari tempat-tempat kos yang ada di sekitar sini, cuma ini yang punya kamar kosong, dan Pak Rahmat udah setuju ketika atasan gue datang minta izin, katanya kalian cowok baik-baik, gak akan apa-apain gue.”
“Iya, kita emang cowok baik-baik. Tapi cowok baik-baik mana yang mau tinggal sama perempuan yang bukan mukhrim?” Tanya Sena.
Jhordan menggeleng-geleng, “Masya Allah, super sekali, Sen!” Kemudian tatapannya mengeras dan beralih ke arah perempuan yang seakan tidak peduli dengan apa yang dibicarakan. “Pagi nanti kita omongin sama Babeh Rahmat.”
“Gak akan ngaruh apa pun,” jawabnya cepat. “Dia udah setuju, dan ini demi kepentingan penyelidikan juga. Gue gak akan ganggu kalian, kalian bisa beraktivitas tanpa menganggap gue ada.”
“Gimana bisaaaa?” Jhordan mendesah. “Bang?” Tatapannya beralih kepada Yoga.
Yang ditatap itu malah terkaget-kaget, dia sendiri bingung harus bagaimana. Dia setuju kalau gak boleh ada perempuan yang tinggal di sini, terlebih, kamar yang disebut kosong itu adalah gudang, dan Yoga ogah banget kalau disuruh bantu-bantu membersihkan kamar itu—banyak kerjaan yang lebih penting buat Yoga. Tapi melihat perempuan itu sok kuat padahal mukanya sudah pucat, kasihan juga. “Oke-oke, gini, deh. Karena kamarnya belum diberesin…”
“BANG?!” Sena dan Jhordan kompak menginterupsi.
“Belum beres gue ngomongnya,” jawab Yoga tenang. “Lo boleh tidur dulu di ruang tengah. Lo boleh tinggal malam ini aja, inget, MALAM INI AJA, karena udah tengah malam dan gue gak suka lihat cewek berkeliaran malam-malam,” Yoga menghela napas, “Soal lo tinggal di sini seterusnya, kita bertujuh harus rapat dulu. Tapi maaf, kalau hasil rapat mengatakan ‘tidak’, lo gak bisa tinggal di sini. Deal?”
Perempuan itu menghela napas, mencoba menimbang-nimbang, sebelum akhirnya tersenyum—mungkin lebih tepatnya seperti seringai, “Deal.”
Yoga mengangguk-angguk, kemudian menyuruh mereka semua masuk ke dalam—karena udara di luar sangat dingin. Hujan masih saja turun, menimbulkan aroma yang menenangkan, sementara itu Yoga masih mengamati bagaimana perempuan itu menaruh tasnya di karpet.
Gimana bisa dia mau tinggal di sini tapi gak bawa apa-apa?
Perempuan itu meraba-raba kancing bajunya, membuat Yoga terbelalak. “Woy gue gak nyuruh lo buka baju di situ?!”
“Siapa yang mau buka baju, sih,” perempuan itu mendengus. “Let me use the bathroom.”
“Here is that,” Yoga menunjuk pintu kamar mandi.
Kemudian ia mendengus kesal ketika sebuah pikiran menghampiri. Tapi bagaimana pun, dia tetap melangkah menuju kamarnya, mengambil sweater yang tentu saja kebesaran untuk perempuan itu, celana kaus yang juga milik Yoga, serta sebuah handuk bersih. Sebagai orang yang paling diandalkan untuk urusan kebersihan, Yoga memang menyimpan banyak benda-benda cadangan yang mungkin saja dibutuhkan oleh teman-temannya.
“Pake dulu,” Yoga menyerahkannya ogah-ogahan.
Perempuan itu mendongak untuk memandang Yoga yang cukup tinggi, sorot matanya yang tajam dan dingin melunak, membuat Yoga tidak tega kalau harus membiarkan dia terusir dari tempat ini. Perempuan itu merasakan wangi khas seseorang di hadapannya, yang juga tertinggal pada barang-barang yang dipinjamkannya. Aroma yang jarang sekali mampir di hidungnya, mungkin aroma buah apel bercampur mint?
“Thanks,” perempuan itu segera berjalan menuju kamar mandi.
Yoga mengangguk-angguk, membiarkan pandangannya mengikuti ke mana perempuan itu pergi hingga menghilang di balik pintu kamar mandi. Sekarang ia sendiri bingung, apa yang harus ia lakukan. Pandangannya beralih ke arah pintu kamar teman-temannya.
Tok! Tok! “Brian, cek grup ya, urgent,” ujar Yoga yang dibalas dengan erangan malas dari dalam kamar. Yoga pun bergeser ke kamar sebelah, mengetuk pintu kamar Julian yang dibalas dengan respon yang sama.
To : Sena
Sen, ketokin kamar anak-anak, suruh cek grup. Kita rapat sekarang, besok kan kalian harus berangkat.
Beberapa saat setelah pesan terkirim, Sena langsung membalasnya, membuktikan bahwa ia belum tidur lagi.
[Sena]
Ok, Bang.
Sambil menunggu semua orang muncul di grup, Yoga melangkah menuju kamarnya, membiarkan dirinya berbaring di atas kasurnya. Sekarang sudah pukul satu pagi, tadi Yoga baru tidur sekitar tiga jam, sementara besok dia harus latihan untuk lomba debat—di mana ia menggantikan Ditas yang tiba-tiba mengundurkan diri dari perlombaan.
Babeh Rahmat 4 life (7)
Yoga Alfian : Anak-anakku, bangunlah
Read by 6
Yoga Alfian : Guys, urgent nih, gue tahu kalian pengin tidur lagi tapi please!!
Brian D. A. : Apa sih, Bang? W masih mau tidur:(
Julian : Tauk tuh
Bhismasena : Bangun dulu yok bentar, ini demi dunia yang lebih indah dan tentram
Julian : Loh ada member smash di grup ini?!!!!
Dennis Ardhi : ….
Jhordan Ali : Ada perempuan yang lagi tinggal di ruang tengah. Gimana, kalian setuju?
Dennis Ardhi : Hah? Maksudnya apa?
Cakka Alfian : Perempuan apa maksudnya? Ada apa sih gak ngerti
Jhordan Ali : Ya, habisnya dari pada banyak bacot mending langsung to the point
Jhordan Ali : Karena gue mau tiduuuuur, plissss
Julian : Perempuan apa maksudnya, Ga? Lo bawa cewek ke sini? Buset
Yoga Alfian : Bukan cewek gueeee elaaaah
Yoga Alfian sent a photo
Yoga Alfian : Gue gak tau kalian kenal apa enggak, tapi ada polisi yang mau tinggal
Yoga Alfian : Untuk beberapa waktu, sampai kasus Raja selesai
Bhismasena : yoi, polisinya perempuan
Yoga Alfian : Dan dia udah bilang ke Babeh Rahmat, katanya boleh
Jhordan Ali : TAPI GUE GAK SETUJU SANGAT
Jhordan Ali : Bayangkan dunia kita yang telah tentram ini terinvasi oleh cewek!
Jhordan Ali : Bisa gila gueeee
Dennis Ardhi : Sama. Gue juga gak setuju. Perempuan tinggal sama laki-laki bertujuh
Dennis Ardhi : kenapa gak di rumah Babeh Rahmat aja?
Brian D. A. : Yeuuu, Den, itu lebih zina dari pada ini
Julian : Mana adeee zina cewek sama kakek-kakek bongkotan kaya Babeh Rahmat
Brian D. A. : Abang gak pernah liat gossip apa di tipi? Kakek enam puluh tahun sama perempuan lima belas taun aja bisa punya anak! Gimana kalau Babeh Rahmat juga punya anak?
Bhismasena : Yan, gue tahu lo bego, tapi pikirannya gak usah sampe sana juga
Bhismasena sent a photo
Cakka Alfian : Jangan-jangan polisinya namanya Bunga?
Jhordan Ali : NAH IYA! YANG WAKTU ITU NGALANGIN KITA
Cakka Alfian : Gak apa-apa, lagian kita bantu penyelidikan. Dan kita gak akan ngapa-ngapain juga ke dia. Selesai, kan?
Yoga Alfian : Ka….. dia cewek loh cewek
Cakka Alfian : Iya memang cewek, kata siapa cowok
Cakka Alfian : tapi kalau memang ini satu2nya tempat kos yang bisa dia tinggalin, yaudah
Cakka Alfian : Biar kasusnya cepet beres juga, dan kita semua gak takut kayak gini
Bhismasena : Hm. Iya juga, lagian kalau ada cewek enak tuh. Gak usah bersih-bersih
Dennis Ardhi : Tapi ini salah loh, gak boleh
Yoga Alfian : apa gue bikin polling aja?
Jhordan Ali : Gue setuju deh, lagian lumayan cuci mata, gak liat kalian mulu
Jhordan Ali : Setiap melihat kalian, mata gue semakin ikut tua
Dennis Ardhi : …..
Julian : Setuju. Tapi gue gak mau beresin gudang, males. Lagian kasihan juga dia, pasti dia ke sini disuruh sama atasannya
Yoga Alfian : Jadi gak apa-apa, nih?
Dennis Ardhi : Tapi, Bang, gue gak setuju ada perempuan di sini.
Brian D. A. : Den…..gue mau tidur!!!
Cakka Alfian sent a photo
Dennis Ardhi : Oke deh, tapi gak boleh ada interaksi khusus sama dia
Yoga Alfian : Deal, ya?
Bhismasena left the group.
Jhordan Ali left the group.
Brian D. A. left the group.
Julian left the group.
Cakka Alfian left the group.
Yoga Alfian : Ini kenapa tinggal gue sendiri?! Woy elah!!
Yoga Alfian sent a photo
Dennis Ardhi : Sabar, Bang..
***
Hari masih pagi ketika Julian mencium aroma gosong dari arah dapur. Matanya celingak-celinguk mencari jam dinding di kamarnya—padahal letaknya tidak pernah pindah. Melihat jam yang sudah menunjukkan pukul lima kurang lima belas menit, Julian segera beranjak dari kasurnya untuk mengambil air wudhu.
Langkahnya terhenti ketika melihat ruang tengah sudah rapi dan bersih, di salah satu sudutnya terdapat satu tas kecil yang tidak familiar. Oh iya, Julian hampir lupa kalau ada perempuan yang menginap di sini semalaman. Julian mempercepat langkahnya menuju kamar mandi dan segera menunaikan shalat subuh. Awalnya Julian masih ingin tiduran dengan selimut di tubuhnya, tapi rupanya bau gosong itu sangat mengganggu penciumannya.
“Bang Yogaaa! Masak apa sih?” Dari atas terdengar teriakan, siapa lagi kalau bukan adik semata wayang Yoga, Cakka yang pasti baru melaksanakan shalat subuh juga.
Tapi tidak ada jawaban, mungkin Yoga masih tidur dan yang memasak di sana bukan Yoga? Mana pernah Yoga masak sampai gosong begini.
Julian melangkahkan kakinya menuju dapur hanya untuk mendapati seorang perempuan dengan susah payah berusaha membalikkan telur yang sedang ia goreng. Beberapa saat Julian hanya terdiam, tidak berniat menyapa—karena ia sama sekali tidak kenal dengan cewek itu. Matanya sibuk memperhatikan perempuan berkulit putih yang terus mendengus sejak tadi. Mungkin baginya, memasak telur adalah hal yang sulit.
“Lo masak buat siapa?” Julian memberanikan diri bertanya, membuat perempuan itu terburu-buru mematikan kompornya dan menoleh. Perempuan itu terkejut dan sempat berpikir, bagaimana bisa penghuni kos ini gak ada yang jelek? Oke, mungkin itu terdengar aneh, tapi bagi Bunga, penghuni kos ini sudah semacam boyband yang ganteng-ganteng, terutama cowok di hadapannya saat ini.
Tapi Bunga bukan tipe orang yang akan terbata-bata berbicara di depan seorang laki-laki. “Buat kalian, tapi maaf kalau gak enak.”
Julian mengangguk-angguk bingung, “It’s ok. Jadi lo di sini buat penyelidikan?” Tanya Julian, disambut dengan anggukan Bunga. “By the way, gue Julian, lo?”
“Bunga,”
Julian manggut-manggut. Nama Bunga mungkin kurang cocok dengan orang yang berada di depannya saat ini. Bunga sering disamakan dengan sesuatu yang indah, manis, dan anggun. Tapi perempuan di depannya ini walaupun cukup manis, agaknya memang seseorang yang dingin sekaligus kuat—jika dilihat dari sorot matanya. “Wow, such a good name.”
Bunga tertegun beberapa saat, “You too.”
“Jadi apa yang sudah lo dapat?” Tanya Julian to the point, bukan berarti dia terlalu ingin tahu dengan semuanya, tapi tampaknya tidak ada topik lain yang lebih cocok selain pertanyaan itu. Dan sepertinya Bunga mengerti, karena akhirnya dia berdeham dan duduk di salah satu kursi, “Rakasa Lukas kemungkinan bukan korban selanjutnya…”
“Ya?” Tanya Julian kaget. “Kembarannya itu bukan korban selanjutnya? Tapi dia kan hilang, mungkin dia lagi disembunyikan sama pembunuhnya?”
“Dia lagi bersembunyi, bukan disembunyikan…”
“Maksud lo?”
Bunga menghela napas, “Dia adalah pelakunya, entah pelaku tunggal atau salah satu dari pelakunya.” Kemudian ia memegang keningnya. “Itu menurut gue. Tapi gue harus mengumpulkan banyak bukti lagi.”
“Kenapa lo bisa bilang begitu?”
“Can you help me to solve this, please?”
“Ya?”
“Gue butuh bantuan kalian,” jawab Bunga pelan. “Gue akan mencobanya dulu sendiri, tapi nanti kalau gue butuh bantuan, gue harap kalian mau bantu. Nanti…gue akan ceritakan kenapa gue berpikiran seperti itu.”
Julian manggut-manggut. “Oke, good luck, Bunga.”
Bunga menghentikan aktivitasnya sesaat hanya untuk menatap mata lawan bicaranya yang begitu indah.
***


 adillazulfana
adillazulfana