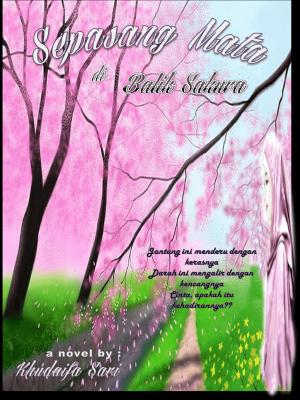Introvert vs. Extrovert
Introvert, Extrovert, Social-butterfly,
Kid who’s hiding in the corner sitting all alone.
All these titles all these labels
Do they truly represent who I am inside?
Every day I must be this happy-go-lucky girl smiling at the world
Something must be wrong if I don’t, or so they think it should.
Why can’t I have a day off to be tired, sick, or sleepy?
I have good days and bad days just like everyone else in this world does.
I’m not always this happy- go-lucky social butterfly,
I don’t need all these “friends” around me to be happy.
I’m perfectly fine on my own listening to my music
Playing soccer or taking a walk just me myself and I.
D e n n i s
“Buset, dah, mobil siapa itu di depan?” Jhordan yang sedang bercermin di jendela depan—padahal menurut Bang Yoga gak kelihatan sama sekali—menyipit-nyipitkan matanya seakan terjadi kesilauan yang menyakiti pupilnya untuk terus menerus bekerja. “Sen! Sini deh, sini. Buset, gue bisa menjadi mahasiswa terpopuler geo 2k18 kalau gue bawa mobil itu ke kampus!”
Sena yang sedang memakan masakan Bang Yoga mendengus, “Apa sih, Dan, heboh amat pagi-pagi.” Walaupun kesal pada Jhordan yang tiba-tiba berteriak, Sena tetap menghampiri Jhordan.
“WUAAA!” Sena menggeleng-gelengkan kepalanya, disusul dengan tabokan keras dari Jhordan, “Tuh kan, gak bohong kan gue? Tersepona kan lo?” Posisi mereka saat ini persis pencuri-pencuri yang sedang mengintip mangsanya; dengan gorden yang setengah di buka dan menampilkan sedikit bagian jendela yang tadi Jhordan pakai untuk bercermin.
Kehebohan mereka mengundang kehadiran Bang Ijul dan Brian yang sama-sama sedang makan, dan keduanya sontak ber-waw-ria. “Eh-eh, jangan-jangan itu mobil istrinya Babeh Rahmat?” Tanya Brian sambil mengedip-ngedipkan matanya.
“Heh, somplak lo! Istri Babeh Rahmat kan udah meninggal,” Bang Ijul menoyor kepala Brian. “Tapi kenapa berhenti di depan rumah Babeh Rahmat, ya? Lagian aneh juga mobil kayak gitu masuk perumahan yang isinya anak kos semua?”
Jhordan mengangguk-angguk. “Gue tau nih,” Jhordan kemudian tersenyum miring, “Jangan-jangan selingkuhan Babeh Rahmat?”
“Mau selingkuh dari siapa begeee,” Sena menoyor kepala Jhordan. “Mobil apa sih itu kayaknya gue pernah lihat, tapi di mana, ya? Apa di mimpi gue?”
“Anjir, bisa sih bisa kalau di mimpi lo,” Bang Yoga tiba-tiba berada di belakang mereka semua. “Oh itu mah Lamborghini Aventador kayak punyanya Raffi Ahmad. Ah, pada gak tahu, ya? Makanya update berita, dong.”
Sena mendengus. “Yeuu, gosip itu mah, bukan berita.”
Gue yang mendengar percakapan mereka semua—yang kini sudah bertumpuk di depan jendela hanya untuk melihat fenomena yang jarang sekali terjadi ini—mengernyitkan kening. Kok kayaknya kenal ya, sama mobilnya?
Gue gak mungkin meragukan kemampuan Bang Yoga untuk menganalisis berita-berita gosip. Setiap hari, Bang Yoga akan selalu update di instagramnya, selalu membaca line today dan bagian terfavoritnya adalah showbiz yang berisi berita-berita tentang artis gak penting. Contohnya, ‘Mau lihat mobil termewah punya selebriti Indonesia? Nomor lima bikin kaget!’ Ya, mungkin Bang Yoga habis baca itu.
[Mami]
Mami di depan, buka dong sayang
Tuh kan! Itu beneran mobil mama. Mama yang pengin banget gue panggil mami, padahal gue geli-geli gitu mendengarnya. Mama ngapain ke sini, ya? Padahal kan udah gue suruh kalau ke sini gak perlu bawa-bawa barang yang mencolok mata kayak gitu. Bikin orang-orang heboh aja.
Gue akhirnya melangkahkan kaki untuk membuka pintu kos, disambut dengan pandangan anak-anak lainnya yang mengikuti kemana kaki gue melangkah. Kemudian, ketika gue bersalaman dengan seseorang yang turun dari mobil tersebut dengan pakaian nyentrik, sebuah backsound terdengar, “Wuuuuu, ternyataaaa.”
Anak-anak maison de rêve memang belum pernah kedatangan mama dengan pose dan mobil yang seperti ini. Biasanya, gue suruh mama untuk memarkirkan mobilnya di masjid dekat komplek dan jangan berpakaian yang aneh-aneh. Tapi kenapa sekarang mama malah parkir di depan sini, sih? Sebentar lagi, pasti Babeh Rahmat keluar dan berteriak-teriak sama hebohnya dengan anak-anak maison de rêve.
“Ma, ada apa ke sini?”
“Loh? Mami mau jenguk anak sendiri gak boleh?” Tanya Mama sambil mengipas-ngipas mukanya. “Gak sih, sebenarnya Mami cuma mau kasih tahu kalau Mami dan Papi mau ke luar negeri selama sebulan. Siapa tahu kamu nyariin nantinya, jadi Mami mau pamit langsung, deh.”
Gue mengangguk-angguk. “Oh, ya udah, hati-hati ya, Ma.”
“Kamu kapan sih mau panggil Mama jadi Mami?” Tanya Mama sebal, membuat gue hanya terkekeh. “Kapan-kapan, Ma, hehehe. Ya udah Mama berangkat, deh, nanti ketinggalan pesawat.”
Tiba-tiba suara rusuh terdengar dari belakang gue. Anak-anak maison de rêve tengah berlarian dan berebut sandal jepit—padahal mereka punya sendiri-sendiri—untuk menghampiri Mama dan gue.
“Halo, Tante, apa kabar, tumben tiba-tiba banget ke sini?”
“Iya, Tante, masuk dulu, yuk,” Bang Yoga bersalaman. “Masih ada makanan di dalam, siapa tahu Tante belum sarapan.”
“Iya, Tante!”
“Iya, bener-bener!”
Mama sepertinya akan membuka mulut sebelum akhirnya gue memotongnya. “Eh, gak perlu, Mama gue mau berangkat sekarang, terus kalian kan mau kuliah juga. Ya udah, Ma. Hati-hati, ya, daaa!”
“Eh-eh,” Mama yang merasa terusir oleh gue akhirnya tersenyum. “Kapan-kapan ya, Tante mampirnya, Tante berangkat dulu, daaa!” Mama melambai-lambaikan tangannya heboh, membuat gue menggeleng-gelengkan kepala ngeri, disusul dengan suara. “Yaaaah,” dari anak-anak maison de rêve. Ya, mungkin sampai sekarang belum terpikir oleh gue, kenapa Papa yang kalem dan alim bisa menikahi Mama yang sangat heboh setengah mati seperti ini. Dan kenapa ada gue?
Bang Ijul menepuk-nepuk bahu gue sambil memperhatikan kepergian mobil Mama. “Den, kok gue baru tahu kalau lo….”
“Gak kok, Bang. Keluarga gue biasa aja,” jawab gue sambil terkekeh.
Dengan perginya mobil Mama, semua anak akhirnya kembali masuk ke dalam kos untuk mengambil tasnya masing-masing dan pergi kuliah. Kecuali Brian yang tidak ada jadwal kuliah pagi. Sena menaiki mobilnya, Jhordan menaiki motornya, Bang Yoga dan Cakka dengan mobil mereka, dan Bang Ijul yang memilih untuk jalan kaki biar sehat katanya.
Sementara itu, gue memilih menggunakan motor kesayangan gue untuk menuju ke kampus, karena kalau naik mobil nantinya harus cari jalan memutar dan cukup ribet. “Gue pergi, Yan!”
Gue sebenarnya bukan jenis orang yang picky. Bagi gue mau naik motor atau mobil sama saja sebenarnya, hanya saja ada kelebihan dan kekurangan tertentu. Naik motor di pagi hari seperti ini bisa membuat gue merasakan suhu dingin Bandung dengan sangat jelas. Walaupun setiap panas harus kepanasan dan setiap hujan harus kehujanan, itu lah sensasinya.
TIIIN!
Setelah masuk ke gerbang universitas, tiba-tiba motor di depan gue membunyikan klaksonnya cukup kencang dan melakukan rem mendadak hingga membuat telinga gue hampir pengang. Ditambah lagi dengan orang-orang di sekitar sana yang menoleh kaget—bahkan ada beberapa yang sampai loncat.
“Eh! Lo anak psikologi, kan? Gue nebeng, dong, sampai fakultas!” Sesosok cewek yang mukanya gak familiar buat gue ternyata yang menyetop motor orang di depan gue. Berniat mau menyusul motor itu agar tidak terlambat, cewek itu malah menghampiri gue juga. “Lo juga, kan? Temen gue mau nebeng, cepet, kalau gak kita telat!”
Gue mengernyitkan dahi. Kalau memang ini anak seangkatan gue di Fakultas Psikologi kenapa harus seheboh ini sih buat meminta tumpangan sampai orang-orang di sekitar sini kaget?
Untuk menghindari kerusuhan dan keributan yang akan terjadi, gue hanya mengangguk. “Iya, boleh, deh.” Berbeda dengan orang di depan gue—yang sepertinya itu temen gue, Dafa—yang masih misuh-misuh hingga si penyetop naik ke atas motornya.
Bersamaan dengan itu, sesosok cewek berambut panjang yang mungkin keturunan Arab menghampiri gue dengan tersenyum simpul. Setengah menunduk, ia berkata, “Maaf, ya, aku ikut, jadi ngerepotin.”
Gue melihatnya malah bengong sendiri. “Eh? I—iya gak apa-apa,” Jawab gue pelan sambil mengatur detak jantung gue agar masih berada pada ritme yang normal. Masya Allah, cantik banget. Kenapa rasa-rasanya gue gak pernah bertemu dia, ya, di kampus?
Selama perjalanan gue dan dia ke fakultas—yang sebenarnya cukup dekat, karena fakultas gue terletak di depan—tidak ada satu pun dari kita yang memulai pembicaraan. Mencoba melihat dari spion kiri motor gue, ternyata perempuan di belakang gue tengah melihat-lihat sekitar. “Lo…angkatan dua ribu tujuh belas?”
Bersamaan dengan berakhirnya pertanyaan gue, mata perempuan ini tertuju pada spion kiri yang membuat kita gak sengaja saling bertatapan. Hal itu membuat gue mengalihkan pandangan cepat ke arah jalanan. “Iya, kamu juga?” Tanyanya balik.
Gue mengangguk-angguk, gak berniat melanjutkan percakapan karena gerbang fakultas sudah terlihat. “Makasih, ya. Hati-hati,” ujarnya sebelum meninggalkan gue yang masih bengong di parkiran sambil memegang helm.
Seumur gue menjadi mahasiswa fakultas ini, gue belum pernah melihat dia—yang gue pun gak tahu namanya siapa. Ya, gue bukan orang yang cukup aktif di banyak organisasi, sih. Bagi gue, ikut futsal sudah cukup mengisi waktu luang gue. Mungkin karena ketidak aktifan gue itu gue jadi gak mengenal cewek tadi? Atau mungkin sebaliknya, dia yang jarang menampakkan diri hingga gue pun gak ingat wajah dia.
Baru berjalan beberapa langkah menuju kelas gue, gue melihat perempuan itu lagi, sedang berjalan sendirian dan setengah menunduk. Menurut yang sudah gue pelajari, cara berjalan yang seperti itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang introvert. Ya, sepertinya memang begitu, bukrtinya tadi pun dia gak menunjukkan tingkah-tingkah petakilan atau terlalu penasaran akan diri gue hingga banyak bertanya.
“Aleta! Lo udah ngerjain tugas?”
Seseorang di belakangnya membuat cewek itu menoleh. “Oh udah. Kamu udah?”
Oh, namanya Aleta, ya.
“Belum nih, gue nyontek punya lo, ya?” Tanya temannya itu yang kini merangkul Aleta dan berjalan menuju kelasnya melewati gue. Waduh, dasar mahasiswa-mahasiswa yang seenaknya menyontek tugas punya orang.
Oh, kelas B, ya, pantesan gak pernah ketemu.
“Den? Itu lo, kan?” Suara yang cukup familiar kini membuat gue menoleh. Sesosok manusia dengan kemeja berwarna biru langit dan lengan yang digulung hingga siku menghampiri gue sambil memamerkan gigi-giginya yang rapi. “Gue nyontek tugas, dong.” Kini tangannya sudah melingkar di bahu gue, membuat gue menghela napas panjang.
Ternyata spesies semacam itu memang sangat banyak di sini.
***
Kalau Cakka akan rela menunggu abangnya rapat dan belajar di perpustakaan fakultasnya hingga malam hari, berbeda dengan gue. Gue lebih senang kalau mata kuliah ditiadakan dan gue bisa pulang ke maison de rêve saat teman-teman gue yang sibuk berorganisasi itu belum pulang. Melihat maison de rêve sepi bagaikan melihat sebuah keajaiban. Karena, kalau salah satu dari teman-teman gue sudah pulang, mereka akan rusuh tiada tara, mulai dari bernyanyi hingga heboh menonton televisi walaupun acaranya gak menarik.
Hari ini bukan hari ketika mata kuliah di kelas gue ditiadakan, namun anehnya, saat gue kembali ke maison de rêve tepat pukul delapan malam, belum ada satu pun dari anak-anak yang pulang. Sena dan Jhordan yang super sibuk gak perlu ditanya lagi, mungkin mereka akan pulang hampir tengah malam.
Tapi anehnya, ketika gue bangun pukul tiga pagi untuk belajar—dan gue sudah tidur tepat pukul sepuluh malam, Sena adalah orang yang berbeda dan buat gue sangat-sangat menarik. Dia mungkin baru pulang rapat jam dua belas malam atau jam satu pagi, tetapi dia akan bangun di jam yang sama dengan gue untuk belajar.
Walaupun terkadang gue merasa ingin seperti itu juga, sayangnya gue orang yang berbeda, gue gak bisa seperti itu. Untuk bangun jam tiga pagi, gue gak bisa begadang. Dan apabila gue begadang, gue gak akan bisa bangun jam tiga pagi. Itu lah mengapa gue gak suka ikut organisasi yang kelar rapat terlalu malam.
Biasanya jam segini kalau Brian gak ada kegiatan apa pun, dia pasti udah di kosan. Tapi, batang hidungnya belum gue lihat. Kosan ini benar-benar sepi, sebagaimana keajaiban yang tadi gue bilang sebelumnya.
[Sena]
Dennnnn!!!
Gue menyipitkan mata memandang pesan yang mampir tiba-tiba, tepat ketika gue baru selesai mandi dan sedang tiduran di atas sofa. Tumben banget Sena chat gue dengan rusuh kayak gini.
Baru aja gue mau mengetik balasannya, pesan lain sudah mampir.
[Sena]
Den, di kosan ada siapa?
Jemput gue sama Jhordan, dong.
Masa parkirannya ditutup
Parah banget anjir pak satpam
Gue menggeleng-gelengkan kepala. Astagfirullah, gue kira ada apa. Mata gue menyisir tiap sudut kosan memastikan bahwa memang belum ada siapa-siapa yang datang. Mungkin masih pada rapat. Ya udah, mau gimana lagi? Gue jemput aja Sena sama Jhordan sekarang. Terlalu jahat untuk menolak permintaan tolong seorang Sena yang sangat baik kepada gue.
Segera gue mengambil kunci motor dan mengendarai motor gue kembali menuju kampus. Memang terkadang gue aneh juga dengan kampus gue ini. Penerangannya di malam hari gak begitu bagus, padahal ada fakultas yang letaknya sangat atas dan ujung—cukup menakutkan, terutama bagi perempuan yang mungkin selesai rapat pada malam hari. Penerangan hanya ada di titik tertentu, seperti masjid, kompleks UKM timur dan barat, selebihnya gelap gulita.
Menuju Fakultas Teknik Geologi, harus melewati fakultas-fakultas yang berada di depan, seperti kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, dan fakultas gue sendiri. Parahnya, dikarenakan cukup gelap, sering ada orang-orang nongkrong di sudut pohon yang sama sekali gak terlihat, tapi terdengar suaranya—mau itu gosip sampai cekikikan. Seperti yang gue alami saat ini.
Bagi orang yang gak tahu, mungkin cukup menyeramkan ketika lewat sini. Tapi, sebenarnya, ini memang ulah-ulah para mahasiswa yang entah mengapa lebih suka nongkrong di kegelapan seperti ini dibandingkan dengan kafe-kafe yang ada di luar sana.
Seperti suara cewek-cewek yang samar-samar terdengar dari radius seratus meter, entah karena gue yang mengendarai motor terlalu lambat, atau karena suara mereka yang memang cukup kencang untuk terbawa angin dan sampai ke telinga gue.
“Hahaha! Woy, lo harus tahu, ya. Gue itu gak suka banget yang namanya cewek-cewek kuper kayak gitu. Bikin gue pengen nindas aja tau gak?”
“Tapi lo tadi pagi kelihatan gitu masa? Apa karena lo nebeng cowok ganteng kelas sebelah jadi sok sok kayak gitu?”
“Gue? Emang gue nebeng cowok pagi ini? Dan seinget gue… gue gak masuk kelas?”
“Apaan sih lo suka bercanda, gue tadi nyontek PR lu anjir!”
“Hah? Hahaha, iya emang? Ah, pokoknya gue tuh gak mungkin kayak gitu!”
Mendengar suara-suara itu tepat di depan fakultas gue, di antara rerimbunan pohon yang gelap—hingga gue gak bisa memastikan siapa yang berada di sana—gue memelankan laju motor.
Bersamaan dengan itu, sebuah puntung rokok terlempar dengan sudut yang cukup besar hingga lemparannya itu hampir mengenai muka gue dan membuat gue melakukan rem mendadak.
“Eh sorry, gue gak lihat ada orang,” ujar cewek itu. Membuat mata gue terbelalak dan dahi gue mengernyit aneh. “Mas-nya mau ke mana, sih? Jalannya kepinggir banget, di sini kan emang banyak yang nongkrong.”
Gue gak menjawab dan malah mengalihkan pandangan ke arah cewek sebelahnya. Dua cewek ini adalah dua orang yang gak sengaja gue temui tadi pagi. Berbeda dengan cewek yang berbicara tadi, cewek yang di sebelahnya malah mendorong-dorong lengan temannya pelan. “Heh, itu kan cowok yang tadi pagi lo tebengin? Gak inget?”
Untuk beberapa saat cewek itu terlihat berpikir, “Gak.” Lalu mukanya mengamati muka gue. “Emang masnya namanya siapa?”
Gue masih gak bisa mengerti apa yang terjadi. Sebelum mulut gue akhirnya membuka, “Dennis, lo siapa?” Gue bertanya bukan karena gue ingin berkenalan, tapi… karena gue ingin memastikan bahwa gue gak salah lihat.
“Aleta,” jawabnya. “Sorry ya, Mas tadi ngeganggu. Dan kalau misalnya tadi pagi gue beneran nebeng seperti kata temen gue ini, makasih. Yuk, Cha!” Tangannya menggandeng temannya, lalu kembali masuk ke dalam kegelapan.
“Ih aneh deh lo!” Samar-samar gue masih bisa mendengar suaranya.
Diam-diam gue bergidik ngeri. Ini gue gak salah lihat, kan? Apa gue habis ketemu hantu? Ah, jelas-jelas dia manusia dan ngerokok. Jelas-jelas itu orang yang gue temui di depan kelas gue tadi pagi. Jelas-jelas dia adalah …. Aleta yang gak sengaja nebeng gue tadi pagi.
Tapi, kenapa mereka terlihat seperti dua orang yang berbeda? Pikiran gue berkelebat mengingat bagaimana Aleta mengucapkan, “Maaf ya, aku ikut, jadi ngerepotin” dan “Iya, kamu juga?” serta “Makasih, ya. Hati-hati.” dengan sangat lembut. Apa yang tadi pagi cuma khayalan gue?
Ah enggak, kok.
Tadi pagi Aleta terlihat sangat anggun, berbicara dengan aku-kamu, hingga cara berjalannya yang introvert. Bahkan, ketika temannya meminta melihat tugasnya, dia terlihat pasrah-pasrah saja. Tapi kenapa….kenapa yang gue temui malam ini justru sangat berbeda? Dandanannya yang seperti itu, rokok di tangannya, hingga cara bicaranya, semuanya terlihat berbeda.
Dan kok bisa dia gak inget gue sama sekali?
Gue ulangi lagi biar lebih dramatis.
Sama sekali?!
Astagfirullah. Gue ini mikir apa? Gue ini sebenarnya habis bertemu apa?
[Jhordan]
LO DIMANA SIH YA AMPUN?
Melihat pesan itu, gue memutuskan untuk mengendarai motor dengan cepat dan meninggalkan area fakultas gue. Walaupun memang terasa aneh dan ngeri, sebaiknya gue gak perlu memikirkan ini lagi. Cukup.
***
S e n a
Pernah gak sih lo merasa bahwa dua puluh empat jam dalam satu hari itu terasa sangat singkat? Atau bahkan lo merasa kalau dua puluh empat jam itu gak cukup untuk melaksanakan semua kegiatan lo dalam satu hari? Gue selalu merasa begitu. Entah karena kegiatan gue yang terlalu banyak, atau mungkin karena gue berharap semuanya berjalan dengan sempurna. Yang jelas, menemukan waktu tidur yang cukup adalah sebuah kemewahan untuk gue.
Sayangnya, gue gak bisa tinggal diam melihat kerja seseorang yang berantakan. Salah satunya ketika Nandhika Sahara—dia lagi—asyik tertidur di tengah kerjaannya yang menumpuk. Katanya sih, ‘katanya’ dia sedang menyelesaikan laporan untuk ospek yang sudah selesai dilaksanakan. Walaupun kelihatannya ospek di fakultas gue ini sebentar—hanya sebulan—sebenarnya perjalanan para maba baru dimulai di sini, karena setelah ini ada pendidikan dasar yang akan dilaksanakan rutin selama satu tahun. Pendidikan dasar itu akan dilaksanakan oleh divisi yang berbeda, maka dari itu sudah seharusnya Nandhika Sahara menyelesaikan tugasnya.
Tapi sekarang baru pukul empat sore dan dia sudah tertidur dengan enaknya di sudut sana. Gak ngerti lagi, gimana sih caranya orang-orang bisa istirahat sejenak di tengah tugas yang menumpuk?
Pintu ruang BEM terbuka tiba-tiba, menampilkan sesosok perempuan yang sebulan belakangan ini selalu berurusan dengan gue dan Jhordan akibat tingkahnya yang aneh-aneh dan gak masuk akal. Bagaimana bisa dia naik ke atas panggung saat sambutan ketua pelaksana ospek dilaksanakan dan berteriak, “Hara, ini beneran lo?”
Dan dia berakhir diseret oleh para komdis dengan puluhan poin yang ditambahkan pada kartu kuningnya. Lalu setelah itu? Gak ada kapoknya. Seorang Bening bahkan menerobos ruangan panitia ketika rapat hanya untuk mencari orang yang bernama Hara.
“Hara-Hara apaan sih lo?” Gue yang saat itu langsung berhadapan dengannya sudah sangat-sangat ingin mengusirnya pergi. “Nandhika Sahara maksud lo?”
Tapi bagaimana pun gue membalas perkataannya, dengan mukanya yang gak ada takut-takutnya itu, dia tetap menjawab, “Bukan! Gue mau ketemu Hara!” Ya, mana gue tahu Hara yang mana? Akhirnya, dia tetap terusir dari ruangan gue.
Yang sekarang sangat mengejutkan buat gue adalah sudah seminggu ini tiba-tiba dia bersikap sok-sok manis di hadapan gue. Hukuman push-up nya sudah dia bayar semua—kata Jhordan—dan gue gak mengerti maksud terselubung apa yang ia sembunyikan dengan melakukan semua ini.
“Eh, Kak Sena. Belum pulang?”
“Udah,” jawab gue.
“Ya ampun, gitu banget jawabnya,” ujarnya.
Gue meneliti mukanya yang sedang tersenyum. “Lo mau ngapain ke sini?”
Bening tertawa. “Ketemu lo lah, Kak.” Kemudian dia terkekeh. “Lo gak ada rapat lagi? Gue mau ngobrol sama lo boleh?” Tanya dia. Walaupun pertanyaan yang ia tujukan adalah untuk gue, tapi gue merasa kalau pandangannya sesekali tertuju pada Nandhi yang tertidur. Kalau dia mau deketin Nandhi, kenapa harus lewat gue, sih?
Cewek gak ada harga dirinya lagi apa gimana, sih, sekarang?
“Gue mau ke perpus,” jawab gue pelan. “Udah lo balik aja sana, gih. Terus kalau lo mau ketemu Nandhi bilang aja, gak usah sok-sok mau ketemu gue.” Jawab gue sebal. Setelah memasukkan barang-barang ke dalam tas, gue segera keluar dari ruang BEM dan melewati dia.
Sialnya Bening malah mengekori gue menuju perpustakaan hingga beberapa pasang mata sesekali melihat dan membicarakan gue. Gak kedengeran, sih. Lagi pula kalau ngobrol berbisik-bisik kayak gitu dengan mata yang jelalatan ngelihatin gue udah pasti ngomongin gue, kan?
“Lo ngapain sih ngikutin gue?” Tanya gue lagi, kali ini dengan nada yang lebih tinggi.
Gimana gue gak sebel? Udah seminggu ini dia selalu tiba-tiba muncul di depan kelas gue atau di depan ruang rapat, membawakan gue minuman—dari mulai es teh manis sampai es kepal milo—dan senyum-senyum sendiri. Dia sering bilang, “Gue pengen ngobrol.” Tapi gue gak tahu sebenarnya apa yang mau dia obrolkan sampai mengejar-ngejar gue seperti itu.
“Kak, gue tuh cuma pengin ngobrol….”
“Ya udah, gak usah ikutin gue bisa gak sih? Gue mau belajar!” Gue gak bisa menahan emosi gue sampai akhirnya raut muka dia berubah, dan tangannya yang tadinya menarik-narik kemeja gue kini melemah.
Dengan wajahnya yang berbeda dari tadi Bening berkata, “Ya udah, Kak. Maaf ganggu.” Kemudian dia berbalik dan berjalan dengan gontai.
“Eh?” Dan lebih menyebalkannya lagi, gue merasa bersalah sudah membentaknya seperti itu. “Ben? Ning? Duh gue harus manggil lo apa, dah. Bening gue gak maksud bentak lo. Ya udah iya, lo mau nanya apa buruan.” Ujar gue, menunggunya berbalik.
Satu.
Dua.
Tiga.
Dia benar-benar berbalik dan kini menghampiri gue lagi dengan mukanya yang ceria. “Yey, boleh, Kak?”
Hahaha, gue ingin menertawakan diri sendiri karena seharusnya gue gak usah memanggil dia lagi. Ya harusnya gue tahu kalau ternyata dia cuma akting agar dikasihani. Hah, salah gue. “Gue traktir bakso, ya nanti malemnya,” sambungnya.
Kalau seperti ini sih, bau-baunya dia akan meminta pertolongan yang bisa membuat jadwal gue berantakan.
Bening berakhir mengikuti gue ke perpustakaan dan duduk tepat di hadapan gue. Walaupun dia gak melakukan apa-apa yang menarik perhatian gue—selain membaca majalah fashion—gue tetap gak nyaman kalau ada seorang cewek berada di hadapan gue seperti ini.
“Kak…”
“Hm.”
“Lo seneng bikin lagu ya ternyata?” Tanya Bening sambil membuka-buka sebuah buku….woy itu kan buku gue, dia ambil dari mana?
Mata gue bertransmigrasi ke arah tas gue yang terbuka dan menampilkan beberapa buku yang ada di dalamnya. “Lo…,” baru saja gue akan marah ketika gue ingat ini perpustakaan dan gue gak mungkin bentak-bentak cewek. “Gak usah buka-buka buku gue.”
“Kenapa, Kak?” Tanyanya lagi. “Kenapa lo gak seneng karya lo dilihat orang?”
Karena gue belum yakin, karena gue gak tahu itu bagus atau enggak. Gue hanya berakhir menyanyikannya dengan Brian dan Bang Ijul tiap sore, karena mungkin itu masih kurang untuk diketahui oleh orang-orang. “Gak apa-apa.”
“Liriknya bagus banget, Kak. Gue suka,” ujar Bening sambil tersenyum. “Apalagi yang ini, I hope I’m just a guy, out of the many people who come and go in your life, I hope our memories are like the sunset; short and beautiful, your small back hasn’t left yet, I hope you can push me away happily,” nada bicaranya berubah menjadi sendu saat membacakan lirik yang gue buat. “Ini… apa judulnya?”
Gue menghela napas. “Apology.” Gue bertanya-tanya dan menunggu respon perempuan di hadapan gue ini; apakah beneran bagus atau enggak.
“Lo… pernah patah hati seberat apa sampai lo bisa nulis lirik kayak gini, Kak?” Tanyanya menatap gue dalam.
Gue yang ditatap seperti itu segera mengalihkan pandangan ke arah lain. “Gue gak pernah pacaran.”
“DEMI?” Tanyanya setengah berteriak, membuat hampir setengah populasi yang ada di perpustakaan ini menoleh ke arah gue dan dia sebelum akhirnya dia menunduk-nunduk meminta maaf. “Lo gak bohong, Kak, gak pernah pacaran? Gak pernah suka sama cewek juga?”
“Gak,” jawab gue sejujurnya.
Gue menjawab sejujurnya, karena gue benar-benar gak pernah merasakan hal semacam itu? Inspirasi lagu yang gue tulis seringkali dari teman-teman gue sendiri di maison de rêve, dari Bang Yoga yang sering galau, dari Bang Ijul yang sok-sok kuat, dan dari mana pun di antara mereka.
“Ya pantesan sih, lo aja memperlakukan gue seperti ini,” ujar Bening.
“Dih, gue gak ngapa-ngapain lo, ya?” Ujar gue sewot.
Bening kemudian tertawa. “Hahaha, iya, kok, Kak,” jawabnya. “By the way, Kak, gue punya tawaran yang sangat menarik.” Ujarnya, mendistraksi pikiran gue yang sedang melanglangbuana mencari-cari isi dari soal yang diberikan oleh dosen gue.
Tuh kan. Sudah gue duga, pasti bocah ini mau melakukan sesuatu yang gak masuk di akal dan melibatkan gue dalam masalah besar. Gue bersumpah pada diri gue sendiri kalau tawaran dia sangat gak masuk akal, gue gak mau berurusan lagi dengan dia.
“Apa?”
“Lo deket sama Hara?”
“Hara-Hara apaan sih, gue gak kenal sama yang namanya Hara kecuali Nandhika Sahara yang tadi tidur di sebelah gue,” jawab gue pelan. Gue masih sadar kok ini perpustakaan. Bahkan, pembicaraan kita tadi cenderung berbisik-bisik.
Bening menghela napas, “Gue….”
***
B e n i n g
Gue menghela napas berkali-kali, lalu menimbang-nimbang apakah gue harus menceritakannya kepada kakak tingkat super dingin dan menyebalkan ini tentang semuanya. Tapi, gue kembali pada visi dan misi gue untuk mendekati seorang Bhismasena—komandan terpimpin Teknik Geologi saat ini—yaitu untuk mengetahui sedikit banyak tentang Hara.
Selalu ada kalimat seseorang yang membekas di ingatan lo, bukan? Seperti, “Lo itu cantik banget, deh,” atau “Lo bego banget, kayaknya mesti belajar lagi,” atau mungkin nasihat-nasihat yang langsung menyentuh batin lo selain judgement seperti yang tadi gue bilang.
Gue juga punya kalimat yang seperti itu. Kalimatnya berbunyi…, “Lo itu beda.”
Maka dari itu, ketika gue mendengar seorang Bhismasena mengatakan kalimat sakral tersebut, yang gue ingat adalah seseorang. Seseorang yang selalu melontarkan kalimat itu saat gue terlalu ceroboh, cerewet, atau terlalu membuat banyak kesalahan.
Lo itu beda.
Lo itu beda.
Tapi, orang itu tiba-tiba menghilang dari hidup gue. Entah sudah berapa lama, mungkin sekitar delapan tahun? Karena dia menghilang saat usia gue masih sepuluh tahun—masih bocah ingusan yang gak tahu, apa alasan dia tiba-tiba pergi.
Namanya Haradhika Putra.
Iya, namanya Hara. Hara yang terus gue tanyakan pada kakak tingkat yang sekarang sedang memelototi gue karena gak sabar menunggu apa yang ingin gue katakan. Duh, serem amat, Kak.
Tapi tiba-tiba, saat gue menginjakkan kaki di kampus dan jurusan yang sangat gue inginkan, gue melihat seseorang yang sangat mirip dengan Hara di masa kecil gue. Gak, bukan mirip. Gue bahkan sangat yakin bahwa dia adalah orangnya.
Tapi dia gak mengenali gue sama sekali.
Hati gue terus-terusan mengatakan bahwa Nandhika Sahara—ketua pelaksana ospek kemarin—adalah orang itu, orang yang datang dan pergi di hidup gue begitu saja, karena menurut gue dia gak berubah sama sekali. Tapi otak gue berkata lain, dia mengatakan bahwa Nandhika Sahara bukanlah Hara di memori gue, karena dia gak mengenali gue sama sekali, dan itu gak mungkin.
Menurut lo, gue harus menuruti hati atau otak gue?
Gue sangat yakin, dia lah orang itu.
Gue sangat yakin.
Gue yakin.
Gak, sekarang gue gak yakin.
Tapi walau bagaimana pun, gue harus mencoba, kan?
“Gue punya temen kecil, namanya Hara. Gue mau memastikan dia Kak Nandhi atau bukan,” ujar gue pelan. Sementara itu, Kak Sena masih menatap gue bingung sambil memainkan pensilnya. “Lo mau gue ngapain?” Tanyanya.
“Gue mau lo kasih tahu gue tentang masa lalu Kak Nandhi,” jawab gue cepat.
Kak Sena mengernyit—dan gue entah kenapa suka banget ketika dia tampak berpikir seperti itu, karena… mungkin terlihat lebih ganteng?—kemudian dia menatap gue. “Memang sepenting itu teman masa kecil lo sampai lo minta tolong sama gue kayak gini?”
“Ya,” jawab gue singkat. Ya, memang sangat penting untuk gue, karena…dia lah yang membuat hidup gue berubah.
“Setahu gue dia tinggal di keluarga yang kaya raya,” ujar Kak Sena. “Dia itu anaknya Pak Dekan, Pak Nandhika Wiardhi,” lanjutnya.
Mendengarnya, jantung gue serasa melorot menuju perut gue. “Gak ada lagi, Kak?”
“Gue gak deket sama Nandhi, kebetulan aja lo sering lihat gue bareng dia,” jawab Kak Sena lagi. Dan tampaknya, dia tidak tertarik untuk berurusan dengan Kak Nandhi ini. “Kalau lo mau minta gue untuk deketin Nandhi dan cari tahu tentang masa lalunya, gue gak bisa, gue gak mau deket sama dia.”
“Tapi, Kak,” gue mencoba membuat Kak Sena yakin dengan permintaan gue.
Kalau Kak Nandhi itu anak dekan sini, apa mungkin….
Tapi kenapa dia gak pernah bilang dan ngabarin gue setelah itu? “Kalau Kakak berhasil nyari tahu masa lalu Kak Nandhi buat gue, gue bakal bikin lagu-lagu lo masuk dapur rekaman,” ujar gue setelah sekian lama berpikir. “Gue bisa negosiasikan itu sama Papa.”
Bersamaan dengan terhentinya kalimat gue, gerakan dari Kak Sena yang sedang menulis terhenti. Dahinya lagi-lagi terlihat berkerut dan menatap gue tajam. “Papa lo…”
“Iya, Papa gue punya agensi, kalau lo berhasil cari tahu tentang Kak Nandhi buat gue…”
Kak Sena terlihat berpikir lebih lanjut sampai akhirnya, “Oke,” jawabnya pelan, namun gue tahu, masih ada sedikit keraguan di dalamnya.
Mendengarnya, gue tersenyum.
***
S e n a
Apa yang lo akan lakukan ketika tiba-tiba ada seseorang yang datang ke kehidupan lo dan menawarkan sebuah cara yang bisa membuat mimpi lo terwujud? Pasti lo akan mengiyakan tawaran itu tanpa kecuali, bukan?
Sama dengan keadaan gue saat ini.
Sayangnya, imbalan yang harus gue berikan adalah sesuatu yang paling gue benci sefakultas ini; Nandhika Sahara. Mungkin orang-orang melihat gue dan Nandhi sebagai dua orang sejoli yang selalu bekerjasama di banyak event. Tapi bagi gue enggak.
Bagi gue, di setiap kali ada event, dia akan selalu panik dan gue yang akan mengerjakan. Dan itu membuat gue gak suka dengan seorang Nandhi, gue gak suka partner yang gak membantu apa pun.
Tapi, kalau benar lagu-lagu gue bisa go public, itu artinya… salah satu dari mimpi gue bisa terwujud, dan gue senang akan hal itu.
Terus, mau bagaimana lagi? Semua hal selalu memiliki konsekuensi, dan konsekuensi yang harus gue tanggung saat ini adalah dekat dengan seorang Nandhika Sahara. Oke, mungkin gue akan melakukannya secepatnya agar gue gak banyak-banyak berurusan dengan dia lagi.
“Sen! Sen! Kita gak bisa balik anjir! Parkirannya ditutup,” gue mendengar suara Jhordan yang berteriak-teriak dan menepuk bahu gue, tetapi gue gak fokus dengan kalimat yang dia lontarkan. “Sen! Lo denger gak, sih?”
“Eh?” Gue menoleh ke arah Jhordan yang panik. “Ada anak kosan yang mau balik gak?”
Jhordan menggeleng, “Gak, mereka masih rapat sampai tengah malam. Gue gak mau nunggu sampe tengah malam ketika ada kesempatan balik jam segini.”
“Di kosan ada…,” gue berpikir. “Pasti Dennis udah balik. Minta Dennis jemput aja apa, ya?”
Jhordan mencibir. “Ya udah lo yang line, kayaknya dia gak ridho ngejemput kalau gue yang line, terlalu banyak salah gue sama dia,” ujarnya.
Gue terkekeh. “Yeuu,” jari-jari gue mengetikkan pesan pada Dennis dan mengirimnya.
“Lo kenapa sih, Sen, dari tadi bengong mulu semenjak keluar dari perpus sama si Bening itu?” Tanya Jhordan, ia menempelkan punggungnya ke dinding dan menyilangkan kedua tangannya di depan dada. “Lo naksir dia?”
“Gak lah! Amit-amit!” Gue menggeleng-gelengkan kepala diikuti tawa Jhordan.
“Terus?”
“Lo mau rekaman bareng gue gak, Dan?”
“Ha?”
***


 adillazulfana
adillazulfana