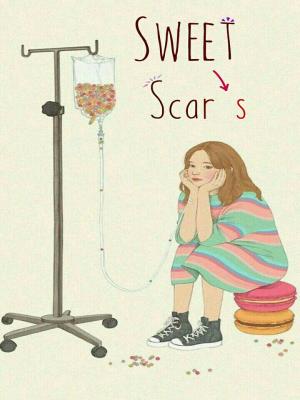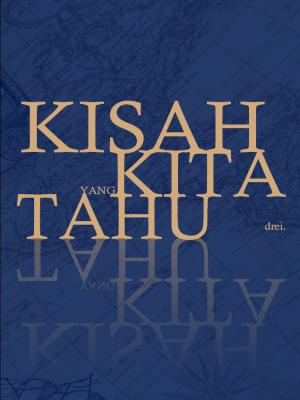Giant cell tumor--sebuah nama yang mengubah kehidupanku. Aku masih ingat betul, bagaimana caranya aku mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang terjadi setelah biopsi. Oke--ucap batinku, tertegun sesaat tanpa tedeng aling-aling dokter mengutarakan apa yang terjadi dengan rasa sakit yang mendera sebelah kakiku. Setelah itu, aku diam cukup lama, berjam-jam kuhabiskan waktu di kamar, hanya dengan tatapan kosong. Bayangan tentang rasa takutku mendadak bermunculan--mendesak kepalaku yang nyaris pecah.
Aku dan ayah tak kalah sama takutnya menghadapi hal semacam ini--yang belum pernah kami hadapi sebelumnya. Rasa takut, membuat kami tak mampu berpikir apa-apa lagi, selain patuh dan mengikuti perintah dokter. Bagai tengah mengoper bola, terbanglah aku ke Jakarta atas rekomendasi dokter yang menanganiku di Palembang.
Dalam waktu bersamaan, hari-hari terasa memanjang dan lebih singkat dari sebelumnya. Kehidupanku berubah total, tubuh ayah menyusut seibu jari selepas meminta cuti dari kantornya dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk kesembuhanku. Tak ada tes masuk perguruan tinggi, apalagi bermimpi bisa diterima di universitas ternama--segala hal yang menyangkut mimpiku itu telah terhenti, sejak aku tahu kisahku sudah berbeda.
Poliklinik jadi satu-satunya tempat aku berinteraksi, memenuhi kewajibanku selayaknya makhluk sosial, sesak dari kerumunan orang yang tengah mencari secercah harapan. Satu dari sekian banyak mata kutemukan dia di sana--yang selalu berada di titik yang sama : duduk di dekat rolling door. Entah apa yang membuatku agak memperhatikannya sejak kali pertama kami berjumpa, lebih tepatnya, kami hanya orang-orang asing yang kebetulan berada di tempat yang sama. Dia akan selalu datang lebih awal dariku, dengan tatapan yang tertuju di satu titik yang sama : ponsel, yang membuatnya tak banyak berinteraksi mata, kecuali di saat-saat tertentu--di mana kala itu, kursi rodaku menyenggol dengkul kakinya. Dalam sekian detik, mata kami saling bertumbukkan. Harus kuakui, dia pria tampan--mengenakan kaos putih yang serasi dengan kulitnya, dan yang membuatnya makin terlihat olehku, sebab hanya terhitung beberapa gelintir anak-anak usia muda seperti kami yang dipilih Tuhan untuk diberi anugerah seperti ini. Aku tak sempat berkata "maaf", lagipula ayah tak menyadari dorongannya terlalu kuat. Tatapan itu hanya berakhir begitu saja. Tak ada nama yang bisa kuteriakkan, apalagi nomor ponsel untuk berbagi cerita. Kami--tetaplah orang asing yang hanya sekedar kebetulan dipertemukan.
Di hari ke tiga belas, hujan turun begitu derasnya di bulan September. Aku tengah menunggu di deretan bangku antrian--tempat pengambilan obat di lantai dasar, di simpang pertigaan. Hujan mungkin membuat semua orang malas untuk keluar rumah, tak seperti biasa, sepanjang bangku nyaris kosong, hanya beberapa orang yang berlalu lalang, dan itu pun hanya lewat dalam lima belas menit sekali. Mendadak gedung rumah sakit Cipto ini seperti kehilangan riaknya. Seakan-akan di hari itu, Tuhan tengah memberi kesempatan kami untuk saling mengenal.
Tak tahu datangnya darimana, pria ini tiba-tiba telah duduk di sebelahku. Aku terperanjat kaget, tapi tak cukup membuatnya bertanya-tanya. Lagi-lagi, pria ini menawarkan senyuman padaku. Aku membalas senyum sekenanya. Lalu, diam--seperti baru saja ada orang ketiga hadir di antara kami.
"Mau ini," serunya tiba-tiba, menyodorkan permen dari tangannya yang entah diambilnya dari mana, di tubuhnya. Aku tertegun beberapa jenak, memandangi dirinya bergantian dengan permen di tangannya, "Permen jahe, lumayanlah buat menghangatkan tubuh di musim dingin." lanjutnya mencoba mencairkan kembali obrolan kami.
Kurambet pelan sembari tersenyum simpul, "Makasih!" seruku, tanpa berkeinginan menyambung kalimat lainnya.
"Sendirian?" tanyanya memecah sunyi, tanpa menoleh. Refleks aku menoleh ke arahnya, mendapati sudut terbaik memandangi hidungnya yang bangir.
"Nggak, bersama ayah," ujarku menunjuk pada ayah--yang menuntun matanya di ruang pengambilan obat.
"Sendirian?" kini, aku balik bertanya.
"Nggak bersama ayah," tunjuknya, yang menuntun mataku ke ujung sana--seorang pria paruh baya yang tengah berbincang dengan ayahku. Aku terkesiap, dalam waktu hampir bersamaan kami saling bersitatap, cukup lama, seolah lewat mata kami tengah saling bicara.
"Kebetulan," teriak kami kompak bersama-sama. Diam, lalu tawa lagi-lagi pecah serempak.
Dengan mulut yang masih memanas karena tawa, pria ini kembali memberi kejutan, diberinya aku sodoran tangannya ke udara. "Aku Arif dari Bekasi." katanya menghangat.
Aku tertegun beberapa jenak, membiarkan tangannya berjuang cukup lama di udara, hingga aku tersadar, "Aku Via, dari Palembang." sambutku tak kalah hangat.
"Waah... Jauh...." teriaknya perlahan memelan, seakan ada rasa kecewa dari kalimatnya itu.
Di sela kami tersenyum bersama, hujan masih turun dengan derasnya yang makin menambah suasana dingin, berbeda dengan tubuh kami yang perlahan-lahan menghangat tiba-tiba. Ada kehangatan yang muncul di sela jarak yang membatasi kami. Sejak di hari itu, aku merasa begitu dekat.
Suara ibu terdengar samar, memanggil-manggil namaku. Tubuhku serasa digoyang-goyang, ditepuk-tepuk sampai dibelai-belai, hingga mataku perlahan-lahan membuka. Bukan Arif, cuma ibu. Rasa-rasanya mimpi mengenainya seolah terasa nyata dan sudah tak terhitung ini kali berapa aku bermimpi tentangnya.
"Vi... Mau bangun jam berapa?" teriak ibu lagi. "Kamu terlambat!" Dari mata yang sayup-sayup, aku terperanjat menatap jam yang sudah pukul 6.30 WIB, tanpa aba-aba, aku bergegas menuju kamar mandi. Mimpi yang harus kupaksa lenyapkan dari realita, meski rasanya, rindu ini masih mencari hadirnya.
***
Tak ada pelajaran. Berita bagusnya, aku memiliki waktu tambahan menyelesaikan pola dress anak-anak untuk beberapa hari ke depan. Pelajaran berganti perlombaan. Perayaan 17 Agustusan menyulap kawasan ini mirip pasar malam--riuh dengan celoteh, diiringi suara musik membahana. Ada tiga lapangan yang digunakan untuk lomba. Dari atas langit, orang-orang seperti titik yang tersebar acak; beberapa panitia telah sibuk mengatur suasana lomba, pemain yang siap bertarung, dan sisanya suporter setia yang suaranya naik-turun sesuai arahan bola.
Lomba telah dimulai beberapa jam yang lalu, saat kami masih mengeram di dalam kelas. Jadi pemenang, itu penting, tapi tanpa dukungan yang seimbang akan mengurangi performa pemain di lapangan. Jadilah kami telah merencanakan sebelumnya; mengenakan kemeja putih, yang senada dengan warna jilbab bagi yang mengenakan, dua pompom wajib di kedua tangan, coretan merah putih di pipi yang dibuat dari lipstik dan eye liner putih. Satu per satu, kami dihiasi Mba Parsini yang dulunya berprofesi penata rias pengantin--sampai sekarang. Aku cukup tahu diri, tak mengajukan diri dalam lomba apa pun. Bagi mereka, doa-doa orang sepertiku sangat dibutuhkan, sebab keampuhannya menembus langit--mungkin mereka pikir aku tengah teraniaya.
Hanya empat orang tetap yang akan terus diikutsertakan dalam setiap tangkai perlombaan--Mba Parsini, Mba Tia, Reni dan Salma--mengingat bobot gajah dan tubuh atletis mereka berbanding lurus dengan varian lomba yang sepenuhnya membutuhkan tenaga. Voli, bola kaki, basket, juga tambang--yang juga butuh kekompakkan yang dinamis. Sisanya, sukarelawan yang memiliki jiwa nasionalisme kelas. Bukan aku tak tahu, dua alasan teman yang tak masuk hari ini--hanya karena tak ingin merusak kulit tangan dan kukunya yang baru saja mendapat perawatan gratis setelah sepuluh kali perawatan--strategi marketing yang bikin orang sulit ke lain hati. Lainnya, mulai melipir, menunduk-nunduk dengan mulut berkomat-kamit seperti merapal doa, berharap saat mata Mba Parsini mengitari kami, namanya tak tersebut. Dan akhirnya, tetap saja tak ada yang bisa menolak ketika sebuah nama terlontar dari mulut Mba Parsini--seolah sumpah yang dapat termakan bila tak terpenuhi. Mulut Mba Parsini mengingatkan aku pada Si Pahit Lidah.
Beramai-ramai kami berhamburan keluar macam ember tumpah, setelah terdengar pemanggilan kelas kami dari suara speaker. Kelas jahit dan kelas sekretaris, ibarat melawan emak-emak versus perawan ting-ting. Coba lihat bodi rata-rata kelas kami yang segede gajah, berbanding terbalik dengan bodi papan triplek kelas sekretaris. Tak hanya aku, semua orang pasti sama-sama tahu--siapa yang akan mengungguli siapa? Dari segi ukuran, kami sudah menang banyak. Bahkan sejarah pun tak menuliskan, emak-emak mampu dikalahkan anak-anak. Di antara tubuh-tubuh mereka yang tambun, hanya aku si itik buruk rupa yang tak tahu lahir dari rahim ibu yang mana. Sudah kecil, agak bantet.
Enam formasi di lapangan sudah lengkap, kami pun sudah siap mengambil tempat. Ada dua kubu yang terpecah di sisi suporter : kiri jahit, kanan sekretaris. Meski tahu, siapa yang akhirnya menang--mental kelas sekretaris patut di acungi jempol. Tak surut, teriakannya membelah langit, bahkan sebelum pertandingan dimulai, mereka sudah menyerukan yel-yel. "Sekretaris yeye... Sekretaris yeye...." dilengkapi dengan kuncir dua ke atas dan pompom di kedua tangan--yang mengingatkanku pada satu orang yang enggan aku sebutkan. Bisa jadi, aksi mereka dipicu karena sadar tak dapat mengungguli siapa-siapa, satu-satunya prestasi yang masih bisa mereka banggakan adalah menjadi suporter ceria. Meski tak terlihat, tim-tim penilai cukup aktif mengawasi. Ada sekotak hadiah yang dijanjikan untuk para suporter aktif. Janji-janji yang cukup menggiurkan.
Kami, kalah banyak dari sudut suporter. Jiwa nasionalisme terhalang mental tempe. Tanpa keterangan, sepuluh orang absen di kelas. Cuma aku dan Gia yang berdiri di sisi suporter, berharap yang lain hanya terlambat beberapa menit saja. Harapan itu segera disambut baik di jam-jam berikutnya setelah lomba tengah berlangsung, saat skor kami di babak pertama mengungguli jauh--17 : 8. Satu per satu, para suporter bermunculan dengan wajah wangi bedak bayi. Mereka, setidaknya 4 orang yang datang--terlahir sebagai pahlawan kesiangan, bukan pahlawan bertopeng. Amunisi kami bertambah, teriakan kami agak menggelegar mendapat personil tambahan, saat satu skor kembali pecah.
"Go jahit... Go jahit... Go...." diselipi lagi yel-yel mematikan, "Dedel... tindas... matikan...!" teriak kami membahana--kalimat aneh yang kami padupadankan dari istilah-istilah dalam menjahit.
Di tengah mata yang lagi serius-serusnya mengintai bola yang pindah ke sana kemari, tiba-tiba bahuku disenggol. Aku tersentak, tak cukup meloncat, cuma refleks menoleh. Seseorang dengan cepat menyambarku dengan senyuman. Manis, tapi tak ada bedanya dengan kue kering putri salju yang dipenuhi bubuk gula putih--pucat. Wajahnya pucat berseri-seri.
"Hei, Cit!" sapaku menepuk bahunya. "Kamu kemana aja? Belakangan nggak keliatan, apel juga, di masjid juga, kamu kemana sih Cit?" lanjutku agak memberi sinyal khawatir, dengan mata yang terus berloncatan mengawasi jalannya pertandingan. Bola masih disambut dengan baik, meski harus melewati aksi jatuh sebelumnya.
"Kamu sakit ya, Cit?" kataku sekali lagi.
"Kata siapa?" tanyanya, tak kusangka kalimatku memancing rasa penasarannya dengan cepat.
"Aldi!" Jawabku singkat, tapi tak sesingkat itu namanya lenyap di pikiranku; melayang-layang di kepala, menghentak-hentak di telinga, turun ke mata sampai ke dada dan tak bergerak-gerak lagi. Kemana dia? Bisik batinku.
"Iya Vi, pusing kepala."
Mulutku membentuk huruf "O" bulat, dengan wajah yang mengisyaratkan kata : aku cukup prihatin mendengarnya. "Kamu pucet deh Cit," kataku akhirnya yang tak bisa lagi menutupi rasa cemasku. "Kalo masih sakit sebaiknya kamu pulang aja, Cit, nggak papa, atau perlu aku temenin minta izin."
"Nggak usah Vi, aku juga mau pulang kok, sebentar lagi."
Kalimat Citra tersaru--tenggelam di antara teriakan yang kembali pecah, lagi-lagi satu skor kami kantongi. Kami, cukup beruntung memiliki Mba Parsini, Mba Tia, Reni dan Salma dengan kelebihan atletisnya yang mampu mengharumkan kelas dan nama Wali Kelas kami.
"Ya udah aku pulang ya, Vi." ujar Citra akhirnya, setelah dirasa telah senyap dari teriakan-teriakan histeris yang mampu menghalangi terdengarnya suara.
"Ayo, aku temenin," sahutku yang sudah menjejak satu langkah ke belakang. Selain jiwa nasionalisme, dibutuhkan jiwa ksatria meninggalkan pertandingan yang lagi seru-serunya atas nama pertemanan. Dan itu, tak jadi soal.
"Nggak usah, Vi. Aku bisa sendiri, kok," sergahnya sembari menebar senyum. "Semoga menang ya," lanjutnya, sebelum berbalik dan lenyap.
Lenyapnya satu orang di lapangan, tak mengurangi keseruan yang terus berlangsung awet, rintik yang datang tak surutkan api yang membara di dada. Sudah dua babak terlewati dengan kemenangan di kelas jahit, hebatnya kelas sekretaris tetap menggunakan performa terbaiknya di akhir pertandingan. Tinggal dua angka lagi yang harus dicapai untuk kemenangan sempurna--pada akhirnya teriakan suporter tak lagi ternilai karena euforia sudah terbentuk di dada. Langit saja seakan tengah mengadakan pesta besar-besaran untuk kami, hujan deras pun turun setelah kemenangan penuh tergenggam di tangan.
Titik-titik yang sibuk di tengah lapangan, kini memencar, berlari menuju tempat berteduh. Satu-satunya kelas terdekat yang dekat dengan lapangan : kelas motor, aku--satu di antara deretan orang-orang yang mengelilingi sisi luar kelas motor. Makin lama, hujan makin deras, kanopi yang memayungi tak cukup menghalau hujan yang menukik membuat kami makin mundur ke tembok. Sudah lebih-lebih mirip cicak. Penuh wajah-wajah memelas, mirip potongan anak-anak yang mengantri jatah makanan di masjid setiap ramadhan.
Ah, tiba-tiba saja bayangan Citra menari-nari di mataku. Hanya berselisih lima menit sebelum akhinya hujan turun, Citra undur diri. Anak itu mungkin pucat dan sakit, tapi untuk menemukan tempat berteduh tidaklah sulit dengan jalanan yang sudah padat dengan bangunan. Entah di belahan mana, kuharap dia sama sepertiku, tengah menatap hujan. Lamunanku belum jauh, saat tiba-tiba tanganku dirambet dan ditarik ke sisi, aku tak tahu itu siapa, tubuhnya tertutup oleh tubuh-tubuh lain--bertumpang tindih, bersama orang-orang yang berteduh. Di tempat yang sudah sempit itu, aku menembus mereka, berdesak-desak sembari pelan, berkata,"permisi," sepanjang jalan, sampai dibawanya aku, tepat, di ambang pintu kelas motor. Ingin rasanya marah, saat pria itu berbalik : Aldi--aku urung, cuma mampu bersungut-sungut kecil. Pandangan pun kulempar jauh ke tengah hujan.
"Kok cemberut?" tanya Aldi yang melihat perubahan ekspresiku. Aku tetap bergeming. "Seharusnya makasih lah sudah ditolongin biar nggak kehujanan." Dia pun sama, melempar muka ke tengah hujan.
Jujur, kalimatnya agak menyentil perasaanku. Meski berat, akhirnya, aku buka suara, "Tapi nggak begitu juga, kamu itu, lagi narik orang normal atau apa? Lupa sama kondisiku?" Air mata ini rasa-rasanya ingin keluar, tapi kutahan. Berbagi air mata dengan orang asing bukanlah pilihan yang tepat, meski berbagi cerita selalu menyenangkan pada orang-orang baru.
Kini, giliran Aldi yang bergeming, dari raut mukanya kelihatan betul, dia cukup terkejut pada apa yang terlontar dari mulutku. Mungkin, aku benar-benar merobek sisi sensitifnya. Bayangkan, ada seorang perempuan yang nyaris menangis di depan matanya, persis seperti reka adegan wanita yang tengah minta dinikahi sama pasangannya. Ah, masa bodoh, lebih sakitan mana dari pergelangan tanganku yang mulai memudar warna merahnya?
"Sori...." ujarnya lirih, dengan wajah bingung seakan tak tahu harus berbuat apa, disusul suara hujan yang makin menunjukkan keeksistensiannya ke permukaan bumi. Tak cuma aku, siapa pun wanita--selalu punya ruang yang luas untuk memaafkan. Raut wajahku yang tadinya dongkol, kini memelan merah muda. Suara-suara lainnya lenyap, bak tersumbat tutup botol. Hanya ada aku dan Aldi.
"Bukan maksudku nyakiti kamu. Ya udah deh, gimana sebagai permintaan maafku, aku traktir kamu makan?" Refleks, aku menoleh cepat. "Iya makan, aku rasa bentar lagi hujan berhenti," serunya sembari melihat jam di tangannya. Ekspresinya yang murung, memelan kembali ke titik normal.
Aku diam beberapa jenak, melempar pandanganku jauh ke tengah hujan, "Ketimbang menunggu hujan reda, mending kamu beri aku tempat duduk terlebih dulu?" ujarku seraya memelas.
Dilihatnya kakiku yang bergetar, sebelah kaki yang tak kuasa menopang tubuh. Nyeri menjalar dengan cepat, macam kain kering jatuh di tengah sungai. Bukannya aku tak tahu raut panik menyambar pula di wajah Aldi, segera dia mengajakku masuk ke dalam kelasnya. Beberapa orang yang tadinya tengah melakukan aksi unjuk gaya, mulai menyingkir, menepi ke sisi, kalau sudah begitu--mereka macam tengah melihat ibu negara yang bertandang ke rumah-rumah warga, dan berharap ada kompensasi untuk rumah-rumah mereka yang nyaris ambruk. Dilihatnya aku, keheranan oleh mereka dari ujung rambut sampai ke bawah kaki, tamu besar yang datang tanpa di undang. Setipe jelangkung. Rasanya aku ingin beringsut, membatalkan kembali langkah-langkah yang sudah terjejaki, tapi urung, memastikan Aldi berada di sisiku--sudah cukup menguatkan.
"Di sini aja," sergahku, menghentikan langkah di kursi paling belakang. Aldi turut, menarik bangku ke sisiku.
Memang, ini bukan kali pertamaku ngobrol dan dekat dengan Aldi seperti ini, tapi aneh saja, setiap kali itu terjadi, rasanya seperti kali pertama mengalaminya--yang bikin rasa canggung ini tak kunjung memudar. Bagai hadir orang ketiga, setelah itu diam menyelimuti kami beberapa jenak.
"Semoga dia baik-baik saja," bisikku samar membuang muka ke arah kaca nako yang buram. Meski di tengah rasa canggung, kecemasanku dari awal tak kunjung pindah.
"Apa?" tanya Aldi singkat.
Aku menggeleng cepat, "Tadi aku lihat citra pulang dengan wajah pucat. Aku cuma khawatir aja."
"Khawatiran mana, aku sama kamu, ngeliat kaki kamu gemetar begitu tadi?" Wajah Aldi mendadak menjelma ibu, dengan kerutan yang sama waktu lagi ngomel. "Kamu terlalu memikirkan orang lain, sementara dirimu tidak pernah kamu pikirin."
Kalau sudah ibu yang ngomel, aku kalah telak. Diamku akan jauh jadi lebih emas ketimbang menemukan alasan yang menimbulkan perdebatan baru. Untuk sementara, aku bakal jadi anak yang patuh sampai waktu tak ditentukan. Hujan masih turun dengan deras saat kalimat itu terhenti begitu saja. Tak ada kata-kata, pandangan kami ke satu arah--menatap kaca yang sama. Memandangi hujan yang menyamarkan segala yang ada.
***
Sebagai permintaan maafnya, Aldi benar-benar memenuhi janjinya membawaku ke meja hidangan. Tak kurang dari lima menit, kami telah sampai di area "jajanan dogan"--sebuah tempat nongkrong cukup bersejarah di Palembang. Mengapa disemat kata "dogan", sebab tak kurang sudah ribuan dogan yang terhidang memenuhi selera "wong kito galo" ini. Seiring perkembangan zaman, layaknya ruas kota yang terus bertumbuh, varian dogan pun tersentuh inovasi, dari dogan biasa, dicampur susu kental manis hingga menjelma jadi dogan bakar yang menggugah penasaran. Dunia, memang selalu mencari orang-orang yang terus berinovasi semacam ini, cepat atau lambat, segala yang tertinggal akan cepat tenggelam.
Nyaris sepanjang kawasan ini tersebar deretan penjual dogan menumpuk dogan-dogan macam gunung kerinci, dengan payung-payung dan bangku-bangku panjang yang dihiasi aneka sampul warna, seakan-akan mereka tengah adu kompetisi membuat tempat semenarik mungkin hingga menyedot banyak mata--yang membuat nama "simpang dogan" makin tenar sepanjang masa. Siapa yang tak tahu nama simpang dogan, sebut saja namanya kalau ingin janjian, tak sedikit orang yang menjadikan tempat ini semacam tempat ajang pertemuan atau alternatif reunian--menyesuaikan kantong yang belum terisi penuh di akhir bulan. Angin yang tiba-tiba menerpa wajah, tak kalah bikin kita betah berlama-lama di tempat ini. Tawa yang tersaru kendaraan, bikin kita seolah-olah tengah berada di kawasan terpadat di kota ini. Namun, pohon-pohon besar yang meneduhkan, seolah membuat kita berada pada kata "pulang."
Tak cuma dogan, dibuatnya pecinta dogan tak lari ke lain hati--minuman penyegar tenggorokan ini disajikan bersama penganan lainnya, macam tekwan, pempek, model, mie ayam, bakso, juga siomay--yang sudah tak asing dengan lidah orang Palembang--menyisakan ruang "ingatan" yang membuat orang selalu "kembali".
Selain bersama keluarga, sebetulnya aku belum pernah menikmati waktu di tempat ini. Jika hari ini Aldi mengajakku, itu akan menjadi kali pertama aku mengabiskan waktu bersama pria lain, selain ayah. Jantungku nyaris lepas dibuatnya. Setiap kali melangkah, kakiku rasanya maunya melongsor, sulit diajak kompromi untuk tidak menegang seperti ini. Ini bukan kencan--oke. Cuma jamuan makan sesama teman--tak lebih. Bersikaplah senormal mungkin, Vi.
Tak seperti biasanya, tempat ini sepi pengunjung, cuma ada aku dan Aldi--memudahkannya memilih tempat dengan bebas. Dipilihnya bangku yang tepat menghadap langsung dengan jalan raya, dengan wajah tersenyum dibukakannya lebih lebar jarak bangku--memudahkan aku masuk dan duduk. Sulit untuk tak merasa spesial kalau sudah begini, ingatanku mendadak melayang ke istana putih dengan sepatu kaca tersemat di kaki. Perlakuan Aldi membuatku makin doyong, macam orang mabuk, hanya sekenanya kubalas senyum, cenderung kaku. Belum juga aku dan Aldi mengatur napas dan tempat duduk, di waktu yang sama seorang pramusaji datang membawa daftar menu hidangan ringan dan menyodorkannya tanpa raut senyum. Kami--yang sudah hapal luar kepala tempat ini, tak butuh daftar, hanya tersingkir jadi formalitas dan memesan sesuai dengan apa yang terlontar dari mulut kami.
"Siomay," teriak kami serempak tanpa janjian. Entah berjodoh atau tidak, hari ini kami memiliki selera dan jalan pikiran yang serasi.
"Dogannya, dogan biasa atau dogan...." Pramusaji setengah bertanya, perempuan muda yang mengenakan rok abu-abu lipat--ciri khas rok SMA yang tak mudah disamakan dengan rok lainnya.
"Dogan bakar," lagi-lagi kami serempak. Refleks menoleh bersamaan. Dalam per sekian detik, mata kami saling bertubrukkan, lewat matanya, aku merenangi di kedalamannya. Ada isyarat yang tak terbaca dari matanya, entah apa yang dipikirkannya, namun semakin dalam berenang ke dalam, semakin aku takut untuk membacanya. Buru-buru kualihkan pandangan, nafasku sudah memburu dan takut terbaca olehnya.
"Kebetulan yang tak disengaja," sergahku mematahkan apa pun, sebelum ada pikiran macam-macam di kepala kami.
Lama bertatap, membuat pramusaji tadi kurang selera, dan melengos pergi tanpa permisi. Selagi hidangan kami belum tersaji dan demi membunuh waktu yang rasanya kian detik kian aneh saja rasanya, benda mungil ini--ponsel, cukup ampuh mengentaskan ruang "aneh" di antara kami. Obrolan itu kembali terbuka setelah dogan dan sepiring siomay tersaji masing-masing di depan kami. Tepatnya, disuapannya yang keempat dan untukku, disuapan yang pertama--suaranya kembali pecah.
"Kenapa kamu pilih kelas jahit, Vi?" tanyanya begitu tiba-tiba seakan petugas lapas yang tengah menginterogasi pelaku kriminal pencuri ayam.
"Terlalu banyak yang ada di kepalaku, kamu mau aku sebutkan satu per satu, atau...."
"Katakan semua yang ada dalam pikiranmu." potongnya cepat.
Seperti kain selubung yang baru saja tersingkap, tiba-tiba kecanggungan yang kurasa melebur pelan-pelan. Bisa jadi, pemilihan katanya membuat otakku tak sempat berpikir terlalu jauh, selain fokus pada pertanyaannya yang bikin semangatku maju satu langkah di depan. Apalagi ini berkaitan menyoal masa depan, mataku langsung berbinar-binar seperti mendapat kado beberapa batang cokelat di tangan.
"Oke. Di rumahku, aku memiliki mesin jahit yang entah bagaimana caranya berada di situ, karena tak satu pun yang kutahu mahir mengenakan mesin jahit. Aku pikir tak ada salahnya kalau suatu saat nanti aku yang bisa memanfaatkannya. Lagipula ini juga cukup sinkron dengan mimpi besarku." ujarku, sembari menuangkan kembali beberapa sendok sambal di piring.
"Memang mimpi besarmu apa, Vi?" tanyanya, yang sudah kuduga, apa yang kuutarakan akan memancing pertanyaan berikutnya lagi.
"Sama seperti apa yang kuutarakan dulu?"
Aldi tertegun, dengan alis yang kini mengangkat sebelah. Matanya menerawang jauh, memikirkan apa yang dulu pernah terlewatkan darinya mengenaiku.
"Apa kita pernah membicarakan ini sebelumnya?" Aku menggeleng mantap.
"Terus, kenapa kamu bisa berpikir kalo aku bisa tahu apa itu mimpi besarmu?" Wajah Aldi makin tak karuan, terlihat betul memendam kebingungan yang akut. Kepalanya seperti ingin pecah.
"Jadi, waktu itu kamu ada di mana, waktu acara pembukaan BLKI waktu itu, lho?" desakku.
Kalimatku membuatnya menghentikan penuh suapan ke mulutnya. Kini, dia makin tak berselera menyelesaikan makan, apalagi menyeruput dogan. Aldi benar-benar terlihat berpikir keras, tapi akhirnya menyerah, "Aku benar-benar bingung, Vi, sekarang apa hubungannya mimpimu dengan acara pembukaan waktu itu?" Aldi sejenak berpaling. "Kamu itu ribet banget sih, cepet bilang aja apa susahnya sih!" lanjutnya, agak membentak. Dari wajahnya yang bingung kini berganti kesal. Sungguh, aku melihat Aldi yang seratus persen berbeda. Aku tersentak. Bisa kau bayangkan apa yang kurasakan saat ini, dia--bukan seperti sebal pada pasangannya yang tengah mencari perhatian, yang cuma sebal-sebal manja, tapi ini betul-betul telihat tengah marah dengan nada yang sedikit naik. Selevel lebih rendah sedikit, layaknya saat marah pada pramusaji yang menjatuhkan secangkir kopi tak sengaja, di atas seragam putih tamunya. Dalam sekian detik, aku merasa dalam fase menegangkan. Reaksi Aldi, di luar dari yang kubayangkan. Jujur, aku tersinggung, tapi ini bukan saatnya aku terbawa perasaan. Tiba-tiba saja, hari yang kuharapkan menyenangkan bersama Aldi, harus pupus karena kebercandaanku yang justru membawa malapetaka.
Kuatur napas, mencoba untuk kembali ke suasana normal. Menciptakan pikiran positif atas sikapnya padaku tadi, yang mungkin aku yang kelewatan bercanda. "Dulu, dalam sesi sambutan," kataku pada akhirnya, melepas ego. "Pak Tugiman pernah bertanya pada salah satu peserta, 'kamu bercita-cita menjadi apa', aku lupa persisnya bagaimana, tapi ya intinya seperti itu...."
"Oh, jadi itu kamu." potong Aldi cepat. Raut wajah marah tadi, kini secepat kilat lenyap dari wajahnya, tergantikan dengan wajahnya yang kembali ceria. Mungkin mudah baginya mengalami perpindahan emosi dengan cepat, tapi tidak bagiku--menyisakan raut wajah 'tertekan' padaku yang tak sudah-sudah. Tanpa ekspresi, aku mengangguk.
Mendadak Aldi terkikih, seakan kupu-kupu mengepak di perutnya--geli. Belum lama aku mengenal pria ini, semakin aku tak habis pikir dengannya. Jalan pikirannya benar-benar membuatku nyaris kehilangan akal. Apa ini terlihat lucu baginya, setelah membentak seseorang tanpa merasa bersalah, lalu sekejap berpikir kalau semuanya baik-baik saja. Hei, yang benar saja!
"Sori ya, Vi," katanya tiba-tiba sembari mendekatkan wajahnya ke mukaku--hanya berjarak sekepalan tangan saja. Pada akhirnya, air mata yang sudah kutahan-tahan dalam kantung mata, kini memberondol. Sulit menggambarkan ekspresiku, sebal, menangis, bercampur tawa akan kebodohanku. "Aku sebenernya sudah dari tadi gak tega ngeliat kamu udah mau nangis gitu, tapi aku tahan deh, soalnya lucu liat wajah kamu kayak gitu." lanjut Aldi, berupaya betul untuk menahan tawa agak tak lagi menyinggung diriku.
"Jadi, tadi itu kamu lagi bercanda ya!" celetukku menyamakan persepsi yang ada di pikiranku. Aku sudah tak sudi terjebak lebih lama lagi dalam teka-teki ini.
Aldi mengangguk bersalah, tapi sedetik kemudian, lagi-lagi dia terkikih, seakan keberlangsungan adegan 'tersudutnya aku' terus memantul-mantul di kepalanya.
"Apanya yang lucu," teriakku sebal sembari menghapus sudut-sudut mata yang agak basah.
"Kamu juga sih pake acara bikin aku penasaran aja, Vi. Ya, aku juga coba becandain kamu balik. Hihihihi...." Lagi-lagi diakhiri tawanya, bikin perasaan sebalku makin memuncak. "Tapi beneran, ekspresi kamu lucu banget deh, Vi. Hihihi...." Matanya mengerling ke arahku.
"Aldiiii...," teriakku membahana, refleks melontarkan pukulan kecil di lengan Aldi. Pria ini benar-benar membuatku tak habis pikir dengannya. Bersamanya, aku seolah berada dalam wahana roller coaster, dibikinnya perasaanku berfluktuasi naik-turun dengan cepat. Efek shock therapy-nya masih terasa.
"Sori deh, Vi." Akhirnya, kali ini Aldi memperlihatkan wajah serius.
"Tapi janji ya Di, nggak bikin lelucon gini lagi." ujarku, dengan mulut maju menyaingi mulut bebek.
Aldi mengangguk, tanpa berkata. Sekian menit berikutnya, kami habiskan dengaan diam, hanya terdengar suara dentang piring dan kunyahan mulut masing-masing kami, sungguh lelucon apa pun tadi--meski singkat telah menghabiskan banyak energi yang kumiliki. Jika ini bukan pengalaman pertamaku, aku takkan pura-pura elegan di depannya untuk menambah porsi lagi. Terlalu cepat mengubah kesan "elegan" menjadi "enggan".
"Kamu hebat Vi," katanya, setelah kami menuntaskan hidangan di depan kami tanpa sisa. "Sudah punya mimpi besar di kepalamu, sementara aku belum berpikir apa-apa, selain ikutan pelatihan ini, aku cuma anak kuliahan yang baru masuk semester pertama."
"Kamu kuliah pun itu sudah berarti merencanakan masa depan, Di. Nggak seperti aku, syukur-syukur mampu menyelesaikan sekolah." kataku menghela napas. Seakan tengah berlomba mencari simpati, kami saling bersusulan menyodorkan kisah-kisah "ketidakberuntungan" di antara kami. Nasibku, bergulir tak kalah naas.
"Oh ya Vi, tau nggak," kata Aldi ceria, menutup cerita sebelumnya, "Di rumahku juga ada mesin jahit, lho Vi, ayahku mahir kalo soal jahit-menjahit, awalnya aku itu mau pilih jurusan jahit, ya tapi aku tahu, aku takkan bisa menolak apa pun keinginan ayah. Pokoknya, keputusan ayah seolah jadi harga mati yang tak bisa ditolerir. Dan akhirnya, ya aku di sini, di kelas motor, tak sesuai dengan apa yang kuinginkan, tapi sesuai apa yang ayah harapkan."
Entah mengapa, setiap pembicaraan orang lain selalu membuatku terkesima lebih cepat. Tak jarang, aku sering kehabisan kata-kata untuk menanggapi, membuat obrolan tak berlanjut kemana-mana. Mentok respon, dan kesan diawal-awal, makin ke sini--aku tak semenarik saat kali pertama mereka mengenalku. Kelenyapan mereka di hari-hari berikutnya menjadi makin beralasan cukup kuat. Aku ditinggalkan dengan alasan yang sama : aku membosankan. Tapi kuharap, tidak untuk kali ini.
Akhirnya, hanya huruf "O" bulat penuh mewarnai mulutku--menuntaskan respon. Setelah memantik kata "kenapa", pada kalimat sebelumnya.
"Entahlah," katanya sembari melempar pandangan ke depan. "Mungkin menjahit takkan membuatku terlihat macho, tak seperti saat aku belajar di kelas motor, mainan laki. Padahal kalo aku di kelas jahit, aku bakal gangguin kamu terus neh!"
Serentak kami terkikih bersama-sama. Tak terhitung, ini kali keberapa aku memukul pelan lengan Aldi dan setiap kali aku memukulnya, aku merasakan adanya denyar-denyar perasaan yang tak terbaca olehku apa itu. Tepatnya, aku masih tak mau memaknainya terlalu dalam. Aku percaya, akan ada pada saatnya tiba, hati ini yang menuntunnya dengan sendiri.
Tak ingin terjebak dalam drama ini lebih lama lagi, kuganti topik obrolan. "Aku jadi inget cerita dalam buku, apa ya aku lupa namanya, inti ceritanya dua orang yang dipertemukan di satu tempat, dan akhirnya semakin dekat."
"Maksudmu kisah itu, mirip kisah kita berdua, begitu?"
Aku mengangguk cepat. "Bedanya mereka belum pernah bertemu, cuma melalui surat yang mereka tulis di waktu-waktu berlainan; ganjil-genap, yang diselipkan di salah satu buku paling tua di perpustakaan--yang berpikir takkan ada yang bakal meminjamnya. Kecuali, mereka berdua. Dan ternyata, benar. Kisah yang benar-benar luar biasa, mereka bisa jatuh cinta tanpa bertemu."
"Menarik," celetuk Aldi singkat sembari menarik sebelah alisnya.
Kami lagi-lagi diam sejenak dan dimanfaatkan Aldi memberi isyarat pada pramusaji yang tengah bersantai di ujung sana, setelah menununjuk-nunjuk, mengangguk, lalu jari terlipat membentuk angka dua, lalu mengangguk sekali lagi sebelum batuk-batuk datang menderanya--hanya mereka berdua yang memahami bahasa penuh isyarat itu.
"Pesen teh botol, Vi. Mulutku gatel. Juga laper lagi sebetulnya, mungkin karena bersama kamu bikin aku jadi laper terus. Aku juga pesanin kamu satu."
"Kenapa gak pesen aja sekalian makanannya lagi?" tukasku.
"Nggak ah, menghargai kamu jauh lebih penting. Kamu pasti nggak mau kalo ditawari lagi, kan? Alasannya pasti sudah kenyang. Oh ya tadi kita sudah sampe mana neh?"
"Baca! Buku yang kubaca." jawabku singkat.
"Kamu suka baca ya, Vi?" Aku mengangguk.
"Kalo kamu suka baca, berarti kamu juga suka nulis dong," seru Aldi, setelah menunggu pramusaji meletakkan teh botol dan berlalu dari hadapan kami.
Kalimatnya segera memantik binar-binar di mataku. Aku tersenyum dan entah dalam sekian waktu yang tak ditentukan, aku mendadak melompat dari mimpi satu ke mimpi berikutnya. Salah satu topik yang membuatku kembali bergairah.
"Kok kamu tahu sih, Di?" tanyaku dengan wajah sumringah. Aldi hanya mengangkat bahu--sebagai pengganti kalimat, "entahlah". "Dari kecil, aku juga suka nulis. Nggak tahu, aku sering terkesima aja melihat tulisan-tulisan orang lain. Tau nggak Di, siapa itu Avianti Armand atau Dewi Dee Lestari--dari tulisan mereka, aku seperti menemukan dunia baru, tempat yang benar-benar aku kunjungi. Kalimat mereka selalu menyihirku yang bikin aku selalu terkagum-kagum pada mereka."
"Dan kamu suatu saat ingin menjadi seperti mereka, kan?"
Aku mengangguk, pelan-pelan mataku berkaca-kaca. "Tapi itu terlalu jauh."
"Kalau terlalu jauh, biar aku yang menarik tangganya. Aku akan membantumu meraihnya." ujar Aldi tersenyum simpul yang pelan-pelan sewaktu Aldi berkata--aku seolah melihat dua wajah bergantian di dalam dirinya, terus berselang-seling, antara wajah Aldi dan Arif--sesuatu yang tiba-tiba membuatku tertegun beberapa detik kemudian. Aku menemukan arif di mata Aldi. "Komposisi yang bagus neh, pengusaha sekaligus penulis. Hebat euuuy...." Aldi terkikih, membangunkan aku dari ketertegunan, menyisakan raut wajahku yang berkaca-kaca.


 silviaoktaresa
silviaoktaresa