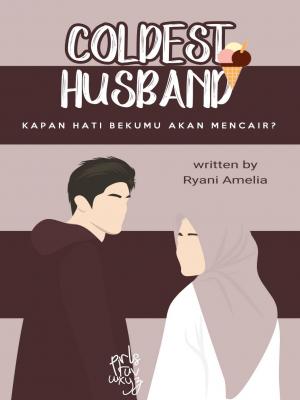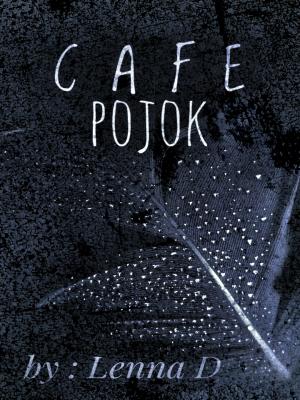Tanpa batasan usia, balai latihan kerja industri (BLKI) menyulap dirinya bak wanita aduhai yang menyedot semua lapisan. Konon katanya, tempat ini menjadi tempat paling produktif penghasil tenaga kerja berkompeten. Jangan terkecoh pada peserta yang disebut anak-anak, kadangkala garis muka menunjukkan tak lagi pantas disebut demikian. Tak pandang usia, satu kelas dicampur jadi satu. Ada 11 jurusan yang dibuka dan aku, memilih jatuh di tempat ini untuk memulai kehidupan baruku dari nol.
Ini bukan kemauanku, tapi usul ayah. Ingin kutolak, tapi toh, tak ada salahnya buat menerima.
Mati-matian aku berupaya menyiapkan segalanya lebih awal, entah sisipnya di mana, aku tetap saja si anak "telat". Baru saja aku ingin bergabung ke dalam barisan--layaknya minyak dan air, apel pagi denganku tak bisa bertemu--aku masuk, mereka bubar jalan. Buru-buru aku menyajari mereka yang berhimpit-himpit masuk pintu utama, bagai cabang, kami pun berpisah di tengah jalan. Menyingkir ke sisi kiri, melewati koridor yang remang-remang dan pengap tanpa ventilasi udara. Beberapa rombongan lain telah menemukan tempatnya dan kelas jahit berada di ujung, dihimpit di antara kelas sekretaris dan WC umum paling pojok.
Kami segera disambut dua pengajar yang telah berdiri di sisi pintu. Satu berseragam batik dan lainnya, tidak.
"Selamat datang anak-anak di kelas jahit!" seru perempuan paruh baya tampil ceria.
Satu bernama "Rosa Rosdiana"--tertera di tanda pengenal di dadanya, yang kemudian menggiring kami masuk setelah kenyang bermain dan mengunyah rumput di lapangan--saatnya gembala menuntun kami ke kandang. Kami berhambur, memencar, mendadak air muka kami berganti sumringah dan mata berbinar, tak kuasa menahan gejolak saat menatap meja-meja jahit listrik yang terhampar rapi di depan, persis mengingatkanku pada pria tampan bermata jeli.
Belum pernah aku se-excited seperti ini setelah masa-masa sulit yang kualami. Macam Adam yang kali pertama menginjak bumi, segala sesuatunya membuatku berminat. Semua hal yang kulihat tampak anyar di mata dan rasa keingintahuan yang menggebu-gebu, aku takjub pada hal baru setelah satu per satu rasa bosan menjejaliku dulu, terkukung pada kotak yang membatasiku dengan dunia luar, yang membuatku usang di tubuh yang belia.
Kutatap jendela di sisi, langit dan dinding beradu biru. Cahaya matahari menyelinap masuk dan tertinggal di atas meja, membentuk sudut cantik yang penuh artistik. Beberapa yang lain sudah memastikan tempat duduk mereka. Beberapa memilih duduk di depan dengan pertimbangan terbaik, yang lain tak suka cahaya dan duduk di sisi kanan bukanlah pilihan, sisanya lebih bebas duduk di belakang. Tak ada alasan yang jelas mengapa aku terdampar di kelas menjahit ini, hanya karena aku belakangan terpikir untuk berekspansi menjadi pengusaha garmen yang membuat alasannya sedikit lebih relevan.
Kelas ini dominan wanita, hanya dua pria yang sepertinya tertarik terjun ke sini dan membuat alasan kalau pria harus tampil serba bisa. Para ibu memasak di rumah, tapi pria selalu unggul menjadi koki. Tak semua ibu bisa menjahit, tapi selalu ada pria yang mahir menjahit. Jika ada emansipasi wanita, mungkin ini disebut emansipasi pria.
Dalam segi kecepatan, aku sadar tak bisa mengungguli siapa-siapa, tak ada yang lebih lambat dari berkaki tiga, kubiarkan mereka mengambil posisi dan jadilah aku duduk pasrah di belakang paling pojok. Segera, cahaya matahari membelah wajahku. Mata kecokelatanku makin bersinar tertimpa cahaya. Di depanku, bukanlah meja biasa, jadi satu menempel dengan mesin jahit listrik yang cukup besar, menyaingi mesin di bawahnya. Di sisi, ada tiang-tiang yang bila tak ada benang menancap di sana, aku bakal menyerah disuruh menebak fungsinya. Macam tulisan arab gundul, aku buta dengan segala yang ada.
Kalau hanya menyebut jarum mesin, benang, dinamo, pedal kaki--aku tak buta-buta amat, jangkauanku sebatas itu yang mudah kudapati di sudut rumah. Cuma mesin jahit biasa, sangat berbeda dengan mesin jahit di depanku ini. Selain sebagai hiasan rumah, kurasa tak ada alasan yang lebih kuat lagi mengapa ada mesin jahit di rumahku, mengingat tak satu pun yang piawai memainkannya.
Kelas ini berlangsung cukup lama dari yang kubayangkan. Sekalinya aku keluar rumah, menjadi waktu paling terlama aku mengembara. Hari pertama, dihabiskan dengan pengenalan basa-basi yang diteruskan dengan pengenalan alat-alat menjahit yang lumayan banyak. Mata nenek, penggaris ukur berbagai macam bentuk, rader, kapur, pendedel, pita ukur, skala, sekoci, spul dan lain sebagainya yang bikin aku sedikit migren untuk hapal satu per satu.
Seseorang muncul di depan pintu saat aku tengah menghabiskan nasi bungkus gratis di jam makan siang. Berperawakan semampai, tubuh proposional macam badan model, rambut terurai sebahu dan wajah khas orientalnya membuatku tak mungkin salah mengenalinya : Citra. Tangannya terangguk-angguk ke arahku setelah menemukan keberadaanku. Aku mengangguk, tinggal satu suap lagi kutuntaskan dengan garang makanan di depanku. Jujur, rasanya hambar untuk kategori sayur nangka yang seharusnya rasanya lebih pekat. Hanya karena lapar membuat segala makanan menjadi sangat nikmat. Lamat-lamat kujejaki langkah menujunya.
"Udah makan, Cit?" kalimat pertama yang terlontar dari bibirku, sembari bergeser cepat membuang bungkus nasi ke kotak sampah terdekat.
"Udah Vi. Aku bingung berada di kelas itu, nggak ada teman yang mampu kuajak bicara." Tak bisa tertutupi wajahnya yang tampak mengenaskan itu. Aku tertegun, tapi tak mampu berkata-kata.
"Kalau kamu mau, jam istirahat atau jam makan siang seperti ini dateng aja ke kelasku Cit." kataku pada akhirnya, berharap memberi ruang segar untuknya.
"Kau mau ke masjid kan, Vi?" kata Citra mengubah arah pembicaraan. "Barengan yuk!" lanjutnya mengubah cepat air mukanya.
Aku mengangguk. Meminta izin sebentar mengambil mukena di dalam tas, sebelum menjejaki langkah bersamanya.
"Oh ya Vi, kemarin kamu bilang ada anak kelas motor namanya Aldi ya? Aku tahu orangnya, duduk di belakangku. Anaknya jahil banget." ujar Citra di sela perjalanan menuju masjid yang letaknya di luar kawasan ini, tepatnya di seberang jalan, hingga memberi banyak waktu untuk kami menjejalinya dengan obrolan ringan.
"Jahil?" tanyaku selidik.
"Beberapa anak udah kena jahilannya, baru aja pas jam makan siang tadi, ada satu anak yang ketiduran sama dia ditutupi pake koran, terus dibacain surat Yasin. Sontaklah dia bangun!"
Aku terkikih. "Jahil juga tuh anak! Tapi dari gayanya aja emang agak tengil orangnya."
"Oh ya? Emang kamu juga kena jahilannya, Vi?" tanyanya terburu-buru sembari clingak-clinguk kiri-kanan mempersiapkan kami untuk menyeberang.
"Iya. Masak aku dibilang mau jadi desainer biar kayak Ivan Gunadi."
"Ivan Gunawan." sergah Citra membetulkan kalimatku sembari menahan perut.
"Iya tuh dia lagi meledek atau apaan itu." kataku dengan mulut menyerupai bebek. Aku berani bersumpah, waktu mengingat kata-katanya, mendadak rasa sebal ini kembali hadir.
"Kamu mau aku kenalkan atau nggak, Vi?" tanya Citra sesaat kami memasuki pelataran masjid.
"Sama siapa?" Mataku membelalak. "Aldi, maksudnya?" Kuberi tekanan pada kalimatku seolah tak abis pikir akan ide yang terpikirkan oleh Citra.
"Emang kenapa? Nggak ada yang salah kan berteman sama siapa aja?"
"Ya... bukan begitu, tapi...." Lama aku tergugu, berusaha menemukan alasan terbaik untuk menolak, tapi tak ada yang tersisa, selain semua alasan justru menuntunku untuk menerima. "Terserah!" kataku pada akhirnya, sebagai kata pamungkas--mengisyaratkan "menyerah" dengan ide gila itu, hanya untuk menutupi isyarat "menerima" malu-malu yang sebenarnya : oke, tak ada salahnya mencoba.
"Nah gitu dong!" seru Citra kegirangan seakan apa yang terlontar dariku akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidupnya di alam semesta.
Bak hadir orang ketiga, hening mendadak merajai kami sejenak. Hanya hitungan detik sampai disentilnya jemariku, tanpa menoleh ke arahku Citra berbisik pelan, "Aldi!" Matanya fokus menatap jauh ke depan sana, seorang pria duduk di lantai masjid tengah sibuk melepaskan sepatu. Mendadak, ada sesuatu yang entah membuncah di dada. Jantung ini berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Aneh tapi ajaib, rasa gugup segera menderaku.
Saat aku berharap dia tak dapat menemukan keberadaanku di sini, tapi matanya mendadak mendongak ke arahku. Refleks, aku terjengat bagai ribuan kilovolt tengah menyergapku. Aku nyaris megap-megap kalau saja dia tak menawarkan senyum simpulnya. Aku terpaku, tak mampu menghindar lagi selain membalas senyuman manisnya. Seakan hanya ingin menancapkan kesannya padaku, Aldi segera beringsut masuk, meninggalkanku yang masih mematung.
"Cie... Cie... Yang lagi kasmaran!" Goda Citra menghantam bahuku, melenyapkan lamunan.
"Apaan sih Cit, ya udah yuks!" seruku berusaha menyembunyikan rona merah di pipiku.
***
Jam 4 sore tepat, aku baru keluar dari kelas. Pelajaran yang cukup menguras otak, tak kusangka belajar menjahit persis mengurai pelajaran matematika. Membuat pakaian di badan tidaklah semudah mengenakannya, sebelum menjadikannya pola sesungguhnya, membuat pola di kertas dengan skala menjadi cukup penting. Kita akan dibawa ke dalam dunia ukur-mengukur, bentuk-membentuk, naik setengah atau turun setengah, mempelajari pola dasar sebelum naik ke pola turunan dan semua itu harus memiliki ukuran yang akurat, agar tercipta pakaian jadi.
Baru pertama saja, aku nyaris ketinggalan mengikuti pelajaran membikin pola dan terpaksa meminjam buku Gia--siswa paling menonjol di kelas sejak kali pertama. Memiliki ibu penjahit membuatnya lebih mahir memainkan tangan-tangan di bawah tusukan jarum-jarum, jauh mengungguli kami.
Aku melangkah gontai dengan wajah kusut masai menuju motor. Waktu berlalu begitu cepat, deretan motor yang terpakir pagi tadi sudah lenyap, tersisa beberapa gelintir orang-orang yang hendak pulang di atas motor. Aku tengah bersiap menghidupkan motor saat Citra melintas di arahku sebelum menuju motornya yang terpakir di sebelah. Kami terlalu malas dan lemah untuk sama-sama menyapa, jadilah sekedar melempar senyum lebih dari cukup. Citra masih saja berkutat dengan jaket saat aku mengklaksonnya di sela deru motor.
Jalanan berundak-undak segera menghantamku, ada akar pohon yang muncul ke permukaan tanah membikin sensasi mantul-mantul, kulempar senyum ke arah satpam sebelum--tepat di depan gerbang motorku mendadak mati seketika. Belum juga usai rasa heranku, lamat-lamat tercium aroma terbakar di sekitarku. Sontak aku meloncat dan turun dari motor. Tak tahu apa yang terjadi, yang terpenting bagiku keselamatan diri. Kuberanikan diri menghidupkan kembali starter saat kurasa aroma terbakar itu sudah lenyap. Benar-benar tak ada api atau hentakan yang memicu suara motor bergerak. Kutoleh kanan-kiri, tak seorang pun melintas, sampai mendapati Citra menghentikan motornya.
"Kenapa Vi?" tanyanya di atas motor.
Aku menggeleng bingung. "Entahlah Cit, motorku mati mendadak." Sama sepertiku, kali ini Citra mengedarkan pandangan ke sekeliling dan berharap ada orang lain yang cukup peduli masalah kami.
"Haruskah aku memanggil...." Belum usai kalimatnya, motorku mendadak menderu secara ajaib di detik berikutnya.
"Hidup lagi!" seruku girang di tengah suara deru mesin motor. Sebelum melaju, aku mengangguk ke arah Citra, isyarat undur diri. Di tengah aku memutar stang, tampak samar kulihat orang di seberang sana memperhatikan kami. Entah berapa lama. Aku tak sempat membalas ekspresi apa pun, motorku terlanjur melaju, dan hanya mampu melihat dari refleksi spion, dia--lagi-lagi Aldi.


 silviaoktaresa
silviaoktaresa