Bunga-bunga yang berada di halaman telah bermekaran, indah. Sebelum turun dari mobilnya, Linta meneliti belanjaannya. Dia mengajak Nokva untuk membuat kue ulang tahun yang besar. Rencana mereka yang dulu tak berhasil, maka Linta akan menagihnya sekarang. Sayangnya tadi seharian dia tak bertemu Nokva. Dia juga tak menjemput Linta. Maka dari itu, Linta langsung ke rumah Nokva siang ini.
Linta tepat di depan pintu saat pintu itu terbuka dari dalam. Linta agak terlonjak, namun tetap tersenyum. Nokva yang membuka pintu, dia tampak sama kagetnya. Dia sedang membetulkan kancing di lengan panjang kemejanya.
“Kenapa?”
“Gue mau minta maaf soal cupcake semalem,” kata Linta, masih tersenyum. Nokva hanya mengangkat alisnya. “Eh… soalnya kecil banget.”
“Nggak masalah.”
Kemudian mereka terdiam dan saling pandang. Linta merasa pipinya merona.
“Gue belum ketuk pintu,” kata Linta, menyamarkan tegangnya. “Nok… nok…”
Nokva tersenyum. Ini malah membuat Linta semakin tegang.
“Sebe…”
“Gue keren belum?” potong Nokva. Dia merapikan pakaiannya di depan Linta, minta pendapat. Baru sekarang Linta menyadari bahwa Nokva rapi sekali, seperti saat pesta kemarin dulu. Namun berbeda, saat pesta dulu Nokva mengenakan jas dan sepatu kulit, sekarang dia hanya berpakaian biasa. Namun benar-benar sama rapi, seakan akan menghadiri acara penting.
Perut Linta mencerna sesuatu yang membuatnya tak nyaman.
“I-iya,” jawab Linta lirih.
“Ini ulang tahun keberuntungan gue! Lo tahu kenapa?” Nokva melebarkan senyumnya. Linta hanya menggeleng lemah. “Melani ajak gue jalan!”
Sesuatu yang tak nyaman di perut Linta kini mengeliat. Apa yang ditakutkannya benar terjadi. Linta menunduk, berpura-pura mengecek bawaannya. Takut Nokva menyadari perubahan drastis pada wajahnya.
“Bawa apa?” tanya Nokva.
“Ini,” kata Linta menutup kreseknya keras-keras. “Nyokap elo nyuruh gue masak.”
“Elo?” tanya Nokva tak percaya. “Masak?”
“Emang kenapa?” hardik Linta, tak berani mendongak.
“Jangan racunin nyokap gue, ya!” Nokva tertawa keras, membuat Linta semakin ingin memukulnya.
“Orang yang pengin gue racuni cuma elo!”
Tawa Nokva kian keras, “Gue ogah makan masakan elo kali!”
Pipi Linta yang tadinya merona, kini telah panas karena marah. Namun, sepertinya Nokva tak memperhatikan ini.
“Kunci,” Nokva mengulurkan telapak tangannya. “Kunci mobil lo!”
Linta menaruh kunci mobilnya ke tangan Nokva penuh emosi. Kemudian dia melangkah masuk melewati Nokva, tanpa menatapnya. Tapi ketika dia akan menutup pintu, dilihatnya punggung Nokva yang berjalan ke arah mobilnya. Dia masih bertahan di depan pintu sampai Nokva memundurkan mobilnya. Linta menghela napas tak rela dan membanting pintu untuk menutupnya.
Rasanya Linta mengerti, mengapa dulu Vega marah kepada Linta, saat Vega akan merayakan ulang tahun Linta, Linta malah pergi dengan orang lain.
*
Terdengar suara pintu depan terbuka. Kemudian suara langkah-langkah kaki mendekat. Linta masih jongkok, menangis di atas tangannya yang melepuh. Dia tak bisa berhenti menangis. Ketika langkah-langkah itu telah terdengar jelas dan berhenti, Linta tahu bahwa orang yang datang telah sampai ke dapur.
Linta mendongak, masih dengan mata berlinang. Ternyata laki-laki itu lagi. Mereka selalu bertemu pada saat yang tidak tepat. Lelaki itu masih menatap Linta dengan tatapan yang sama, menilai. Kemudian matanya menyapu dapur. Menatap bagian dalam oven yang gosong. Loyang hitam yang jatuh ke lantai yang sangat berantakan, dan juga tempat cuci piring yang sangat kotor.
Lelaki itu menatap Linta lagi. Tatapannya terfokus pada tangan Linta yang melepuh. Linta rasa, dia sudah tahu apa yang telah terjadi.
Dia menghampiri Linta, “Ayo duduk di atas,” dia membimbing Linta untuk bangun dan mendudukkannya pada kursi makan. Kemudian pria itu menyibukkan diri membuat teh.
“Kita sudah sering bertemu, tapi kita belum saling kenal,” katanya.
Linta menatap punggung pria itu bingung.
“Saya Linta,” jawab Linta.
“Saya Ota,” dia menoleh dan tersenyum.
Ota telah selesai membuat teh.
“Hanya sekedar ingin tahu,” katanya seraya menaruh salah satu cangkir di depan Linta. “Kenapa kamu kesini?”
Sekarang Linta telah dapat menguasai diri dan berhenti menangis. Dia tersenyum kecil seraya berkata lirih, “masak kue.”
Ota tersenyum. Kemudian dia ikut duduk di salah satu kursi makan di lain sisi. Dia menatap loyang jelaga di lantai yang berantakan. Linta menghirup tehnya untuk menutupi kebodohannya. Linta menggunakan tangan kirinya yang tak terlalu parah untuk mengangkat cangkirnya. Sedangkan tangannya yang panas melepuh, dia sembunyikan di pangkuannya. Meskipun demikian, tangan kirinya juga sakit untuk mengangkat cangkir.
“Lalu Nokva siapa?” tanya Ota. “Pacarmu?”
Linta agak tersedak tehnya, “Bukan!”
“Lalu?”
“Kami…” Linta agak bingung harus bilang apa. “Kami… kami rumit.”
“Jelaskan kalau begitu,” kata Ota enteng, tersenyum.
Linta menatapnya. Dari matanya Linta tahu bahwa dia adalah orang yang baik. Linta membalas senyumnya, “Ceritanya panjang.”
“Ceritakan kalau begitu. Saya suka cerita,” kata Ota. “Sepertinya cerita kalian menarik.”
Ota tersenyum lagi dan Linta membalas yang ini juga.
“Saya memanfaatkan Nokva,” kata Linta.
“Memanfaatkan?” ulang Ota.
“Saya tertindas di rumah saya, karena saya cucu termuda kakek-nenek saya,” cerita Linta. “Saya pacaran dengan sepupu saya untuk merubah itu.”
“Sepupu?”
“Bukan benar-benar sepupu… ini juga rumit.”
“Jelaskan yang ini juga kalau begitu.”
Linta tersenyum tak sabar. “Sepupu saya ini… ah, panggil saja dia Vega. Nah, Vega ini punya ibu, yang ibunya adalah adik dari suami adik ayah saya.” Linta berhenti, karena melihat Ota agak melongo, tak mengerti.
Mereka terdiam agak lama. Ota sepertinya masih mencerna apa yang dijelaskan Linta.
“Rumit, kan?” Linta nyengir.
“Nggak sebenarnya, cuma kamunya saja yang terlalu berbelit-belit,” kata Ota. “Bilang saja kalau dia keponakan Oommu, mudah, kan?”
“Tapi itu nggak jelas! Masih kayak sepupu saya, kan?” bantah Linta.
“Kalau gitu, keponakan suami tantemu?”
Linta hanya tersenyum, mengalah.
“Nggak ada ikatan darah, tapi tetap sepupumu, ya?” gumam Ota, tampak bingung namun tertarik.
“Iya.”
“Lanjutkan cerita yang tadi.”
“Dan kami putus karena suatu masalah,” Linta memulai. “Waktu kami bertemu lagi, dia bawa pacarnya, dan saya ditindas lagi! Jadi, saya pura-pura punya pacar.”
“Nokva?” sambar Ota.
Linta menganguk, “Tapi kami nggak benar-benar pacaran.”
“Emang rumit, tapi ceritanya nggak panjang,” komentar Ota.
Mereka terdiam lagi, sibuk dengan teh masing-masing.
“Jadi, Anda oomnya Nokva?” tanya Linta, untuk memecah keheningan.
“Nggak tepat seperti itu juga.”
“Jadi?”
“Ini juga rumit,” Ota tertawa.
“Jelaskan,” sambar Linta ikut tertawa.
“Lebih rumit dari ceritamu.”
“Jadi harus lebih dijelaskan.”
Ota tertawa lagi. “Kakek Nokva punya satu anak. Saya.”
“Lalu…” Linta yang bingung sekarang. “Ayah Nokva?”
“Nah, di sini rumitnya,” kata Ota. “Kamu nggak bakal ngerti.”
“Saya bisa ngoreksi atau mengomentari,” timpal Linta, dan mereka tertawa lagi.
“Lanjutkan,” pinta Linta, menirukan gaya Ota.
“Ibu saya kanker rahim.”
Linta tercengang. Dia tak tahu harus bagaimana. Harus menghibur atau minta maaf, karena telah memaksa Ota untuk menceritakannya. Namun itu tak perlu, karena Ota sepertinya tak terganggu harus menceritakannya.
“Dia tak bisa punya anak,” kata Ota. “Ketika umurnya sudah semakin tua, dia mengangkat anak dari panti asuhan, ayah Nokva.”
“Lalu Anda?”
“Saya lahir disaat ibu saya hampir berumur empat puluh delapan. Sungguh keajaiban.”
Linta hanya menganguk mengerti.
“Jadi saya adalah Oomnya?” tanya Ota.
“Tak ada hubungan darah, namun anda tetap Oomnya.”
Ota tersenyum lunak. Linta menyukainya, dia pendengar yang baik. Dan bukan tipe pemarah seperti Nokva. Dan tak seperti kesan pertama Linta saat melihatnya.
“Saya nggak pernah seperti ini dengan Nokva,” kata Linta.
“Maksudnya?”
“Saya suka cerita apa saja sama dia, tapi dia nggak pernah mau cerita sama saya, seperti Anda,” Linta berhenti sebentar. “Bahkan dia suka bentak-bentak saya kalau saya cerewet dan sok akrab.”
“Jangan tersinggung, dia seperti itu sama semua orang.”
“Saya nggak tersinggung. Saya hanya heran saya bisa dekat dengan keluarganya. Dengan ayahnya, ibunya, dan Anda,” Linta memandang Ota, minta persetujuan. “Saya rasa.”
“Kamu boleh anggap saya teman,” kata Ota, tersenyum.
“Terimakasih,” kata Linta. “Anda mau mendengarkan saya. Padahal di rumah saya, tak ada yang mau mendengarkan saya, hanya pembantu saya yang mau mendengarkan.”
“Kamu benar-benar ditindas?” tanya Ota, agak geli.
“Nggak seperti itu, lebih tepatnya mereka agak nggak suka kalau saya berada dekat-dekat dengan mereka. Mereka sayang saya!” ujar Linta keras, saat Ota menatapnya dengan ekspresi aneh. “Tentu mereka sayang saya, hanya sebal.”
“Sebenarnya kamu menyenangkan,” kata Ota, membuat Linta tersenyum. “Kamu lucu, saya nggak tahu kenapa Nokva nggak tertarik sama kamu.”
Senyum Linta lenyap dan pipinya panas.
“Atau Nokva seperti keluargamu? Sebal, namun sayang?”
“Kami tak seperti itu!” bantah Linta.
“Saya tahu kamu ada rasa sama Nokva,” kata Ota, tenang namun yakin. “Kue ini buat dia, kan?”
“Iya, tapi tak seperti itu. Saya hanya…”
“Kamu nangis dari tadi,” potong Ota, “bukan karena kuenya gosong. Atau kuenya gosong karena kamu nangis?”
Linta tercengang, terkaan Ota sedari tadi tepat. Dia menghela napas. “Dia nyium saya semalam.”
Ota menatapnya. Linta merasa dia sedang menembus pikirannya, dan membacanya.
“Saya hanya terlalu terpengaruh dan bodoh. Itu buat saya berharap, dan… dan… dia pergi dengan Melani!” napas Linta terengah. “Saya hanya terlalu memikirkannya.”
“Memang sakit melihat orang yang disuka bersama orang lain,” kata Ota penuh arti.
Ota memandang loyang jelaga di lantai sekarang. Dia menunduk untuk mengambilnya, dan menaruhnya di meja. Linta merasa tersindir dan malu karena itu.
“Masih agak panas,” kata Ota. “Tadi kamu ngambil langsung dari oven tanpa sarung tangan?”
“Iya,” kata Linta, bodoh. “Tangan saya jadi begini,” dia mengangkat kedua tangannya yang melepuh.
“Saya nggak bisa berpura-pura menjadi dokter,” kata Ota.
Linta mendengus geli dan meratapi tangannya yang mengerikan. “Saya sudah kalah cantik dengan Melani. Ditambah tangan seperti ini, saya nggak ada apa-apanya.”
“Dia anak Pimpinan Redaksi majalah di tempat saya bekerja,” celetuk Ota.
“Eh?”
“Melani,” jelas Ota. “Tapi percaya saja, kecantikan itu bukan segala-galanya. Yang penting itu perhatian.”
Ota menyentuh bagian kue gosong Linta, keras. Kemudian dia mencoba mengirisnya dengan sendok tehnya.
“Kayaknya bisa dimakan bagian dalamnya,” gumam Ota.
Ketika Ota berhasil mencukil kue beracun itu, isinya hanyalah kulit telur. Linta hanya nyengir ketika Ota menatapnya bingung. Sejak dulu, Linta tak pernah bisa caranya memecah telur, dia hanya berhasil meremuknya di dalam mangkuk.
“Saya juga nggak bisa berpura-pura kalau ini enak,” kata Ota tertawa. Linta ikut tertawa.


 bektidh
bektidh



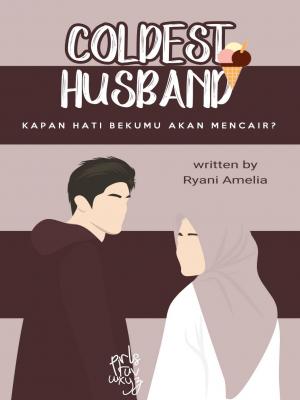








wew
Comment on chapter Pesta Kedua