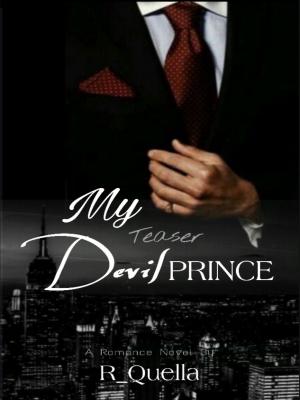[ EVAN ]
ENTAH KENAPA, SAAT ini aku merasa lebih dekat dengan Giana daripada dengan siapa pun di dunia ini. Ironis, memang, padahal aku sendiri harus naik kereta 12 jam kalau mau mengunjunginya di Bandung sana. Sebenarnya tanganku gatal banget ingin mengetikkan segala sesuatu—kayak percakapan di telepon antara Mama dan Maggie yang tadi nggak sengaja aku dengar—di ruang chat kami, namun aku teringat kalau kami terikat peraturan yang kami buat waktu itu.
Dan iya, saat aku memberitahu Giana kalau menurutku dia imut, itu karena menurutku sahabat penaku itu memang imut. Memang bukan tipe yang akan membuat cowok-cowok stalking akun media sosialnya berjam-jam, tapi begitu aku melihatnya di TV tadi, dia seakan memiliki magnetnya tersendiri.
Evan Alamsyair
btw gi
Evan Alamsyair
kapan-kapan mau ketemuan nggak?
Sekarang sudah hampir jam dua belas, namun Giana membalasku dengan cepat. Aku kira dia kecapekan setelah syuting tadi. Ternyata, sama sepertiku, Giana nggak bisa tidur.
giana
???
giana
akunya yang ke surabaya atau kamu yang ke sini?
Evan Alamsyair
aku aja yang ke bandung
Evan Alamsyair
ngapain kamu ke surabaya di sini nggak ada apa-apa
Nggak lama kemudian, aku merasa kebelet. Karena malas mengambil tongkat, aku pada akhirnya keluar kamar sambil berjalan pincang. Aku sempat ketemu Mama di ruang keluarga—"kamu nggak denger percakapan Mama sama Kak Maggie, kan?" tanyanya, dan aku menggeleng bohong.
Begitu kembali dari kamar mandi, aku melompat-lompat dengan satu kaki karena kaki kiriku terlalu sakit untuk diajak berjalan. Saat itulah, aku langsung ingat kalau Giana nggak boleh melihatku begini—untuk sekarang, cuma dia yang nggak tahu apa-apa dan memperlakukanku layaknya orang sehat biasa, dan lebih baik memang begitu.
Aku langsung buru-buru mengetik di laman chat-ku dengan Giana:
Evan Alamsyair
eh kayaknya kita nggak usah ketemuan-ketemuan deh
Evan Alamsyair
lagian kita kayak gini juga karena tugas satu semester ini doang, kan?
Entah kenapa, setelah mengetikkan hal itu, aku merasa sedikit nggak enak.
Untungnya, keesokan harinya Giana belum membalas pesan yang kukirim. Dibaca pun enggak. Aku menduga cewek itu pasti sedang sibuk merhatiin penjelasan guru tentang Pithecantropus erectus atau entah apa di kelasnya. Entah bagaimana dia bisa nggak tergoda untuk membuka HP saat pelajaran berlangsung—sesuatu yang di lingkungan teman-teman sekelasku mustahil terjadi.
Aku sendiri nggak masuk sekolah hari ini. Instead, aku diajak ketemuan lagi dengan Kak Wisnu, psikolog yang selama ini menanganiku. Dalam hati, aku bersyukur hari ini aku nggak sekolah. Sekarang hampir semua orang di sekolah tahu aku menderita kanker, dan setiap hari aku diingatkan kalau hidupku nggak akan lama lagi. Aku mendadak berubah dari agak diabaikan menjadi diperhatikan semua orang, meski bukan tipe perhatian yang kuinginkan. Teman-teman sekelasku—biasanya cewek—mulai mengerubutiku di jam istirahat dan menanyakan hal-hal kayak dikemo rasanya kayak gimana sih? atau kamu kok nggak botak? (Di titik ini, aku sendiri bertanya-tanya kenapa aku belum botak dan menenteng infus kemana-mana kayak stereotip anak-anak penderita kanker yang biasa kulihat di film-film.) Kadang-kadang, ada yang mentraktirku makan, meski sebelumnya mereka menanyakan boleh enggaknya aku makan ini dan itu seakan-akan aku nggak bisa makan apa-apa kecuali cairan dari selang. (Akiu belum separah itu. Penekanan pada kata belum.)
Hari ini, aku kembali bertemu dengan Kak Wisnu, psikologku yang sebenarnya sudah lama nggak kutemui. Aku menduga pertemuan ini direncanakan Mama gara-gara percakapannya tadi malam dengan Maggie. Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya kenapa Maggie yang kudengar lewat telepon tadi malam berbeda jauh dengan Maggie yang mengataiku nggak punya masa depan dua bulan yang lalu.
"Dari cerita yang mama kamu beberin tadi, kayaknya kamu ada gejala-gejala depresi, deh," ujar Kak Wisnu yakin, yang bikin aku mengerutkan dahi. Jangan-jangan Mama menelepon Kak Wisnu tadi malam setelah aku kembali dari kamar mandi, saat aku benar-benar sudah tidur dan nggak mendengarkan. AKu heran kenapa Kak Wisnu mau meladeninya di tengah malam. Buru-buru, dia menambahkan, "Itu hal normal, kok. Putus dari pacar memang sakit. Belajar dari pengalaman."
Mau nggak mau aku tertawa sedikit. Kadang-kadang, Kak Wisnu memang sering curhat tentang mantan-mantan pacarnya dan cewek-cewek yang tengah dia dekati, meskipun harusnya dia-lah yang menjadi "tempat sampah"-ku. "Kasih saran, dong, yang pacarannya awet," mintanya tempo hari. "Minta aja dia comblangin kamu sama temannya, Kak," jawabku.
Kalau mengingat bagaimana dulu aku lumayan sering cerita tentang Astrid ke dia, aku kembali merasa kosong.
"Eh, tapi seriusan. Kalau menurut pemantauanku, kayaknya kamu sekarang ini lagi merasa terisolasi, deh. Dan bukan karena putus sama si Astrid doang. Belakangan ini, kata mama kamu sekarang kamu lebih sering menutup diri, ya?"
Lamunanku terbuyar. "Itu karena mereka semua—teman-teman sekolahku—merlakuin aku kayak orang sakit." Aku menghela napas, pada akhirnya memberanikan diri untuk membuka segalanya. "Aku cuma pengen balik ke masa SMP, waktu aku masih bisa jadi anak normal yang berteman sama siapa saja tanpa dikasihani."
Kak Wisnu mengangguk. Dia terdiam sebentar, kemudian mengeluarkan selembar pamflet dari kolong meja kopi ruangannya. "Sabtu nanti bakal ada event buat anak-anak seperti kamu," ujarnya. "Mereka nggak bakal menilai kamu macam-macam, kok. Mereka juga nggak bakal nganggap kamu orang sakit."
Giana menulis tentang perasaannya selama masuk Goodnight Indonesia waktu itu, dan sesuai tebakanku, Giana waktu itu merasa nggak nyaman. Suratnya kali ini dipenuhi coretan koreksi dari gurunya, yang kadang-kadang membuatku sulit untuk membaca tulisannya yang besar kecil nggak beraturan itu. Selain itu, Giana juga memberitahuku kalau dia seorang Gryffindor—yang bikin aku sedikit iri, dia saut asrama dengan The Golden Trio!—dan patronusnya stoat, sejenis musang.
Seakan-akan beliau tahu kalau aku dan Giana diam-diam berhubungan lewat chat untuk saling mengajak kopi darat, Pak Bima kali ini menugaskan kami untuk menulis tentang Surabaya di surat balasan kami.
Salah satu sisi positif dari bersahabat pena adalah kamu bisa kenal sama tempat asal teman kamu," beliau menjelaskan di depan kelas. "Dan sebaliknya, kamu juga bisa ngenalin teman kamu sama kota asal kamu. Surabaya itu unik, lho. Setiap aspek kehidupan di sini—kayak rujak cingur, Patung Buaya, atau bahkan misuh-misuh kalian itu—bisa banget, lho, jadi bahan tulisan."
"Kalo dibandingin sama Bandung, Surabaya mah nggak ada apa-apanya padahal," komentar Raga, yang duduk di belakangku. "Palingan cuman panas, macet, sama bonek doang."
Mau nggak mau aku ikutan nimbrung. "Sama Gang Dolly."
"Gang Dolly udah ditutup, cuk." Raga menoyor kepalaku. "Yang tersisa sekarang cuma panas, macet, sama bonek."
"Sama banjir," aku menambahkan. Aku nggak pernah menduga aku bakal menjelek-jelekkan kota tempat tinggalku dengan teman sekelas yang jarang aku ajak bicara. Mungkin, inilah pertama kalinya aku mendekati normal selama setahun terakhir.


 sweatertowns
sweatertowns