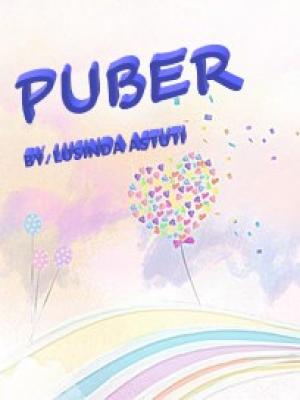[ EVAN ]
AKU NGGAK BICARA dengan Astrid selama seminggu lebih. Berkali-kali aku berusaha untuk berbaikan dengannya secara baik-baik kayak yang disarankan Giana tempo hari, namun sahabat penaku itu belum berhasil meyakinkanku kalau Astrid masih mau memaafkanku. Di kelas, meskipun Astrid masih duduk di depanku, kami nggak pernah lagi saling curi-curi pembicaraan saat kelas berlangsung. Aku seringkali ingin menepuk bahunya hanya untuk mengajaknya ngobrol, namun niat itu seringkali aku urungkan.
Jam istirahat lebih sering kuhabiskan dengan menonton teman-temanku—that is, jika orang-orang yang aku ajak bicara dua-tiga kali masih bisa disebut "teman"—main bola di lapangan, memperhatikan tiap gerakan mereka sambil dalam hati berharap aku dapat turun ke lapangan untuk bergabung. Seringkali malah aku nggak harus mengkhawatirkan bagaimana aku mau menghabiskan jam istirahat, karena aku harus pulang setengah hari untuk kemo atau fisioterapi atau sejenisnya. Oleh karena itu, ditambah fakta kalau kaki kiriku masih pincang, rumor kalau aku mengidap penyakit serius mulai santer terdengar. Dalam hati aku berdoa semoga kemo nggak membuatku botak dalam waktu cepat, atau segala sesuatu yang kusembunyikan akan langsung terkuak. Hal terakhir yang kuinginkan adalah semua orang—nggak cuma Astrid—memperlakukanku seakan-akan aku ini orang sakit, meskipun aku memang sakit.
"Evan, 'kan?" Aku menoleh ke arah suara dan mendapati diriku berhadapan dengan seseorang yang kukenal. Mas Chandra, mantan kapten tim sepakbola SMP Diponegoro yang dulu beberapa kali kutemui saat turnamen antarsekolah. Aku sama sekali nggak menyangka dia ternyata melanjutkan SMA di sini. Kayaknya dia sekarang sudah kelas sebelas. Mas Chandra duduk di sebelahku dan bertanya, "Ndak masuk tim bola? Padahal dulu aku lihat kamu mainnya bagus, lho. Bisa masuk Timnas U-17, malahan."
"Aku isih masa pemulihan, Mas." Aku menunjuk ke arah tongkat yang terletak di samping bangku tempat kami duduk. "Waktu itu sempat cedera berat sebelum masuk sini."
Mas Chandra mengangguk penuh pengertian. Dalam hati, aku berdoa semoga dia nggak menanyakan macam-macam yang nantinya akan memaksaku membeberkan segala sesuatu tentang penyakitku. Aku nggak butuh kejadian Astrid terulang lagi. "Lama juga, ya," komentar Mas Chandra. "Nanti kalo udah boleh main bola lagi Line aku, ya. Line aku masih ada di kamu, toh?"
Aku dan Mas Chandra memang sempat bertukar ID Line waktu kami pertama kali bertemu. "Belum tahu juga kapan sembuh," tambahku, agar Mas Chandra nggak bertanya macam-macam.
"Kira-kira berapa lama sembuhnya? Ada satu-dua bulan?"
Aku langsung menggigit bibirku sendiri. Jika aku berbohong dan menyebut asal berapa bulan, jelas bakal ketahuan. Mencurigakan kalau bulan November nanti aku malah semakin sakit, saat aku menjanjikan Mas Chandra kalau aku akan "sembuh" saat itu.
Oleh karena itu, bukannya memberinya jawaban, aku langsung bangkit dari bangku tempat kami duduk dan berkata, "Pamit dulu, Mas. Habis ini ada ulangan Biologi," meskipun secara teknis minggu ini adalah minggu tenang sebelum UTS sehingga nggak ada lagi ulangan. Aku memutuskan untuk balik ke kelas dan berpapasan dengan Astrid di koridor. Entah apa yang membuatku tahu-tahu menarik lengan cewek itu dan mengajaknya ke belakang tangga, di mana kami hanya berdua.
Aku menatap mata hitam Astrid lekat-lekat, dan aku langsung menyesal telah menyeretnya ke sini. Astrid masih melihatku dengan terheran-heran. Dia mungkin bertanya-tanya dalam hati kenapa pacarnya, yang omong-omong telah membuatnya kecewa, tahu-tahu menghampirinya lagi. Aku menghela napas sebelum akhirnya mengeluarkan semua yang selama ini kupendam dalam sekali teriakan napas, "Sekali-lagi-aku-minta-maaf-gara-gara-udah-bikin-kamu-kecewa-aku-cuma-nggak-mau-bikin-kamu-khawatir-gara-gara-aku-sakit." Kemudian, setelah aku mengambil jeda selama beberapa detik, aku melanjutkan, "I love you, Astrid."
Hening sebentar. Astrid menaikkan sebelah alisnya. Kalau di film-film, ini adalah saat-saat di mana aku akan menciumnya, tapi kami sedang ada di sekolah dan aku nggak berani buat melakukan hal itu bahkan saat kami berada di balik semak-semak sekalipun.
Kini Astrid menunduk, kepalanya menggeleng. "Udah sewajarnya aku khawatir, Van," ucapnya pelan, nada yang dia gunakan dingin. Dia kemudian kembali mendongak. "Cinta itu berarti kamu cuma mau orang yang kamu cintai itu bahagia. Kamu nggak mau mereka kenapa-kenapa. Dengan kamu nyembunyiin penderitaan kamu selama ini, kamu malah kesannya kayak nggak cukup yakin kalau aku sayang dan peduli sama kamu."
Aku membatu di hadapan Astrid, nggak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya aku ingin sekali mengelak dan bilang nggak, Astrid, aku yakin, kok, aku cuma nggak mau bikin kamu menderita dengan punya pacar penyakitan kayak aku, namun aku tahu itu malah akan membuatnya merasa lebih buruk.
"Aku jadi suka mikir," lanjut Astrid dengan cara bicara yang membuatku menduga dia sedang menahan tangis, "kamu itu sebenarnya memang sayang dan peduli juga, nggak, sih, sama aku?"
Setelah mengajukan pertanyaan yang entah retoris atau tidak itu, Astrid berjalan keluar dari belakang tangga tempat kami bersembunyi, meninggalkanku dengan perasaan yang lebih buruk dari sebelumnya.
"You don't look too good, hu zi[8]," komentar Mama begitu melihatku duduk murung di depan . Beliau meletakkan telapak tangannya yang dingin di pipiku. "Efek samping kemo?"
Aku menggeleng, meski efek samping kemoterapi memang mulai bermunculan belakangan ini. Badanku, contohnya, lama-lama bertambah kurus—Hana, yang sedang duduk di pangkuanku sambil memainkan sebuah game di tabletku yang sedang dia pinjam, terasa lebih berat dari biasanya karena di pahaku sudah nyaris nggak ada lagi lapisan lemak dan otot. Dalam hati aku bertanya-tanya apakah Hana mengenal permainan anak-anak yang normal kayak petak umpet atau saya minta anak.
Karena Papa masih kerja lembur, kami bertiga kini sedang berkumpul di depan TV sambil menikmati spaghetti sebagai makan malam. Kami sedang menonton sebuah talk show yang mengundang seorang pianis cilik berbakat yang umurnya ternyata nggak beda jauh dariku. Dalam hati, aku agak iri pada anak yang namanya kalau nggak salah Genta itu. Nggak kayak aku, dia nggak harus menyerah dalam mengejar cita-citanya gara-gara sebuah penyakit mematikan.
Aku sendiri nggak terlalu fokus pada apa yang ditayangkan di TV karena aku masih terlalu larut dalam rasa bersalahku terhadap Astrid. Tadi, setelah istirahat, dia meminta Arif, anak kutu buku yang duduk di bangku paling depan kelas kami, untuk tukaran bangku dengannya. Sepulang sekolah, aku mendapat notifikasi kalau Astrid sudah nggak mengikutiku lagi di Instagram. Aku nggak tahu apakah itu berarti aku dan Astrid sudah putus atau apa.
"Ada masalah di sekolah?" tanya Mama, yang kini mengusap-usap punggungku kayak yang sering beliau lakukan saat meninabobokanku waktu masih kecil.
"Ya, gitulah," jawabku dengan agak nggak niat. Mama sangat menyukai Astrid, dan beliau kadang-kadang bahkan memperlakukan dia seolah-olah dia sudah menjadi menantunya. Aku nggak tahu bagaimana menjelaskan ke beliau kalau aku dan Astrid mungkin baru saja putus. Bagian mungkin itu adalah yang paling susah dijelaskan.
"Kak Epan dibikin nangis cama temen Kakak?" Hana tahu-tahu mendongak dari tablet di pangkuannya.
Kakak yang bikin nangis temen Kakak, batinku, dan Kakak merasa bersalah banget gara-gara itu. Karena tentu saja aku nggak akan bilang itu ke Hana, aku membalasnya dengan berkata, "Hush. Ini urusan orang gede."
Mataku kembali terfokus ke layar TV. Kini, host dari talk show yang sedang kami tonton itu sedang berbincang-bincang dengan ibunya si Genta-Genta ini tentang bagaimana beliau memberi anak itu dukungan dalam karirnya sebagai pianis. Di sebelah ibunya Genta, duduk seorang gadis berambut sebahu yang terlihat nggak asing. Gadis itu, yang kayaknya masih SMP, kayaknya sedang berusaha untuk nggak terlihat bosan. Aku berusaha untuk mengingat di mana aku pernah melihat gadis itu.
"Nah, kalo menurut Giana sendiri, Bang Genta itu kayak gimana?" Host talk show itu kini beralih ke gadis berwajah datar itu, dan pada saat itulah aku tersadar akan sesuatu.
Di layar TV di depanku, aku sedang menyaksikan sahabat penaku sendiri.
Saat itulah aku mulai sadar akan kenapa Giana pernah berkata kalau dia nggak dekat dengan kakaknya. Kakaknya, si Genta-Genta itu, sudah dikenal banyak orang dan disanjung tinggi sebagai seorang jenius—dan saat dia memainkan lagu gubahannya sendiri di piano yang terletak di tengah studio, aku harus mengakui kalau permainannya mampu membuat siapa pun yang mendengarkannya menganga. Gampang sekali untuk merasakan adanya "jarak" di antara kamu dan seseorang saat dia telah melangkah jauh dan kamu masih diam di tempat.
Namun apa hubungannya dengan Giana yang diberi tahu oleh kakaknya kalau dia nggak mengerti apa-apa tentang cinta, aku nggak tahu.
Host di talk show yang sedang kami nonton tengah menanyakan Giana apakah dia tertarik untuk mengikuti jejak Genta menjadi pianis. Sambil memaksakan seulas senyum malu-malu, Giana menggeleng sambil menjawab, "Belum tahu."
Evan Alamsyair
gia
Evan Alamsyair
aku barusan lihat kamu di tv
Aku meletakkan ponselku di atas dadaku setelah mengetik kata-kata barusan. Sekarang sudah jam sepuluh malam, dan Mama sudah menyuruhku tidur ketika jam sembilan. Menurut beliau, aku perlu banyak istirahat. Meski demikian, aku nggak bisa tidur. Aku ingin curhat ke Giana mengenai segala sesuatu yang terjadi di antara aku dan Astrid, meski aku tahu Giana nggak akan bisa banyak membantu. Aku nggak peduli.
Setelah beberapa menit, belum ada balasan yang masuk, jadi aku berasumsi Giana sedang nggak memegang ponselnya. Aku bisa membayangkan cewek itu pulang dari studio dengan mata terkantuk-kantuk dan perasaan kesal karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan host itu barusan. Mungkin sekarang dia baru tiba di kamar hotelnya dan langsung menghempaskan dirinya di atas kasur tanpa mengganti baju atau menghapus make up, karena dia cuma ingin menyudahi hari yang bikin capek fisik dan mental ini. Pesanku kayaknya baru akan dia baca besok.
Oleh karena itu, aku menutupi seluruh tubuhku dengan selimut, memeluk boneka gajahku (Giana nggak boleh tahu kalau aku masih tidur dengan boneka), dan berusaha tidur. Aku sendiri sama lelahnya dengan Giana, baik secara fisik maupun mental, setelah seharian ini.
Saat itulah, aku mendengar suara kasak-kusuk dari luar kamarku. Yang kemudian disusul oleh suara seseorang berbicara.
"Jadi tahun depan kamu lulus ini, Mag?" Suara Mama. Kayaknya dia sedang menelepon Maggie di ruang duduk lantai dua. Menggunakan kaki kananku yang masih berguna, aku melompat-lompat menuju pintu kamarku untuk menyimak percakapan Mama dan Maggie lebih lanjut, meski aku tahu aku akan menyesal jika mengetahui segalanya. Aku teringat bagaimana tiga bulan yang lalu aku melakukan hal yang sama saat Mama dan Papa sedang berbincang-bincang dengan Dokter Arni di luar kamar rawat inapku, dan aku malah mendengar kabar kalau kankerku sudah menyebar kemana-mana.
"Semoga aja, Ma." Suara Maggie bisa terdengar agak jelas karena Mama kayaknya menyalakan speaker. Ini adalah kebiasaan Mama tiap kali menelepon seseorang sendirian—aku sendiri nggak tahu kenapa Mama melakukan hal itu. "Waktu itu sih, aku seneng banget waktu proposalku di-acc. But now, I don't know. Everything's just too hard. Aku bahkan baru nyampe bab satu tapi dosen udah nyuruh aku revisi berkali-kali." Ditilik dari nada bicaranya, Maggie terdengar lebih capek dari biasanya. Which is saying something, karena biasanya Maggie memang selalu terdengar serak kayak orang sakit tenggorokan. Aku menduga itu efek samping dari kebanyakan merokok.
"Kamu pasti bisa, kok."
"Evan mana?" Telingaku langsung tersentak begitu mendengar Maggie menyebut namaku. Then again, kayaknya aku cuma salah dengar.
"Oh, Evan? Udah tidur dia," jawab Mama. "Tumben kamu nyari-nyari Evan, Mag."
"Anu, Ma." Hening sebentar. "Aku... mau minta maaf soal yang waktu itu. I feel like I was too hard on him. Skripsi yang lagi aku kerjain ini tentang psikologi anak-anak penderita penyakit terminal. Waktu aku riset di lapangan, aku sempat ngobrol panjang lebar sama anak ini, umurnya baru delapan tahun tapi dia udah pakai kursi roda gara-gara atrofi otot[9]. Pas denger ceritanya aku langsung inget Evan, Ma. Di situ aku langsung sadar, betapa nggak pekanya aku sama penderitaan adikku sendiri." Kemudian, setelah Maggie berhenti berbicara selama beberapa menit, dia bertanya, "Omong-omong, Evan apa kabar?"
Mama menghela napas. "Mama sendiri lagi khawatir sama Evan, Mag," ucapnya pelan. "Dia... jadi lebih tertutup. Nggak pernah lagi cerita apa-apa sama Mama. Dia juga udah jarang main sama teman-temannya lagi." Dengan tangan kiri beliau masih memegang ponsel, Mama kembali berjalan menuju kamarnya. "Mama takut dia kenapa-kenapa. Tahu sendiri kan, dia itu lagi masa-masa labil, belum lagi dia sakit... ."
[8] Secara harfiah berarti tiger atau harimau dalam bahasa Mandarin, sering dipakai untuk memanggil anak laki-laki.
[9] Suatu keadaan di mana otot mengalami pengurangan massa.
a/n; sIGHS i know this chapter is super rushed and is of low quality sobs


 sweatertowns
sweatertowns