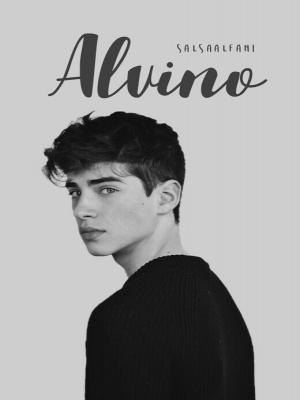Dari kecil, aku selalu diajarkan ikhlas. Mama selalu bilang kalau hidup ini apa adanya yang kamu bisa saja. Termasuk setiap aku melakukan sesuatu yang berakhir gagal, aku selalu dengan lapang dada menerimanya walau dengan rasa malu. Mama adalah orang yang paling berpengaruh di kehidupanku. Kata-katanya, meskipun jarang sekali kudengar dia menyampaikan kalimat dukungan untukku, tapi dia jadi orang pertama yang memintaku agar ikhlas setiap aku mendapat kegagalan. Belum waktumu, katanya.
Maka sekarang ini, rasanya aku ingin menangis jika menghadapkan muka ke bangku audiens barisan depan. Mama dan Kak Ratih menatapku dengan mata berkaca-kaca ketika waktunya aku menerima penghargaan dari panitia lomba.
Ketika kuberitahu wanita yang paling kusayang itu mengenai juara ini, Mama sempat syok, dia juga sempat menangis. Katanya dia malu ketika anaknya tengah berjuang tapi dia tidak tahu apa-apa. Ayah dan Kak Ratih juga bilang, kalau dia bangga, tidak menyangka jika Raras yang selama ini hanya menyimpan sendiri karya-karyanya bisa menjuarai lomba tingkat Nasional. Ini mungkin tidak seberapa untuk mereka yang terbiasa meraih kesuksesan, tapi untukku, melihat orang-orang yang kusayang itu bahagia karena sesuatu yang berhasil kucapai, tidak ada lagi yang lebih bahagia dari ini.
Tentunya, aku nggak akan melupakan orang penyebab aku bisa berdiri terharu sambil memegang piala penghargaan dengan tangan gemetar ini. Kak Arja. Andai aku mengambil keputusan lomba ini sejak dulu, apa kesuksesan juga akan datang di masa itu?
Setelah kejadian di Kopi Bar kemarin lusa, aku betulan memberi hadiah yang ditagih Kak Arja jika aku berhasil juara. Tentunya dia kuberi sesuatu yang juga masih membuatku bahagia hingga saat ini. Novel yang kuberi judul ‘Kupu-kupu’ itu yang jadi hadiahnya. Itu adalah novel yang kutulis sejak dulu dan baru dikabarkan terbit beberapa bulan lalu. Rencananya, lusa aku akan menghadiri public speaking untuk acara launching novel perdanaku itu. Ah Tuhan, semesta, terima kasih!
“Mama selalu bilang ke saya, kalau sukses itu punya waktunya sendiri sendiri,” ujarku ketika panitia meminta sepatah dua patah kata untukku mengungkapkan perasaan.
“Yang pernah gagal pasti tau rasanya. Apalagi yang lebih sakit, ketika kita merasa mampu menghadapi tapi masih tetep gagal. Dan di fase-fase itu, Mama selalu suruh saya buat ikhlas. Akhirnya saya nggak pernah berani cerita kalau lagi pengen meraih sesuatu. Takut gagal.” Aku tersenyum singkat sebelum melanjutkan. “Cuma satu orang yang tahu kalau saya ikut lomba lukis, bahkan satu orang itu yang maksa saya buat ikut.
“Dari dulu, saya belum pernah buat orang tua bangga. Tiap usaha, pasti gagal.” Aku menatap Mama yang duduk di barisan depan itu dengan mata berkaca-kaca, kulihat disana Mama juga menitikkan air matanya. “Maaf ya Ma, Ayah, Kak Ratih, Raras baru buat kalian bangga hari ini. Makasih juga udah selalu doain Raras.” Suaraku mulai bergetar ketika kusaksikan di bangku audiens sana bahu Mama kian terguncang karena tangisnya, Kak ratih juga tersenyum ke arahku dengan dua mata yang berembun. Maka dari itu, tak mau tangisku pecah di atas panggung, akhirnya aku mengakhiri pidato singkat itu dan diikuti gemuruh tepuk tangan setelahnya.
Apa kalian pernah berada di titik puncak kebahagiaan? Aku belum pernah melihat Mama menangis karena dia banggga padaku seperti yang terjadi hari ini. Dan sekarang, ketika hal itu nyata ada di depan mata kepalaku sendiri, to be honesty, aku masih belum percaya sepenuhnya. Semesta mungkin sudah lelah bermain-main denganku, terima kasih Tuhan.
Jadi, untuk kamu yang masih tetap gagal dengan sesuatu yang ingin kamu capai, kesuksesan itu sudah diberi nama masing-masing. Mereka seperti panah yang dilepaskan dari busur yang akan menghampirimu kapan saja jika itu memang sudah waktunya.
Dua hari kemudian, aku juga berhasil menyelesaikan public speaking kepada calon pembeli novel ku itu dengan baik, dua hari setelah penerimaan hadiah di Galeri Nasional itu, aku kembali bertemu lagi dengan Kak Arja. Laki-laki yang baru kutemui setelah terakhir kami bertemu di Kopi Bar tempo lalu. Dan tidak kusangka juga, novel yang awalnya kubuat hanya untuk iseng-iseng itu laku lebih dari 1000 ekslempar dalam masa pre-order. Meskipun bukan hal yang spektakuler lagi, tapi untukku itu sangat berarti.
“Kenapa judulnya Kupu-kupu?” tanya laki-laki itu ketika kami berdua sedang dalam perjalanan pulang ke rumahku. Public speaking untuk peluncuran novel kali ini aku di antar Kak Arja karena katanya dia punya waktu luang. Aku menoleh ke samping, menatap Kak Arja yang tengah fokus dengan kemudinya.
“Something special,” jawabku singkat sambil kembali memalingkan muka. Kulihat dari sudut mata Kak Arja gantian menoleh dan samar-samar kudapati dia menganggukkan kepala beberapa kali.
“Kenapa si tokoh utama mati?” tanyanya lagi, sepertinya dia sudah membaca novelku hingga tamat.
Aku diam demi kembali memikirkan cerita yang sudah kubuat. Tak perlu ditanya lagi siapa seseorang yang menginspirasiku untuk membuat si tokoh utama mati dalam keadaan gemilang, pelan kutolehkan kembali pandanganku ke kak Arja. “Karena aku sayang dia,” jawabku pelan. “Tuhan juga sayang dia,” lanjutku.
Laki-laki itu mengangkat sudut bibir. “Pas gue baca novel itu, nggak tau kenapa, dari cerita, suasana, semuanya familiar. Bahkan beberapa dialognya ada yang gue hafal,” ujarnya serius kemudian menatapku sangsi. “Buat gue, novel lo aneh Ras. Bukan cuma cerita biasa, tapi itu semacam catatan kematian seseorang. Dan nggak tahu kenapa gue serasa hidup di dalamnya.”
Setelah itu Kak Arja memelankan laju mobilnya, keadaan jalanan lengang hanya ada satu dua mobil yang melaju. Laki-laki itu kemudian menatapku serius.
“Apa yang lo ceritain itu, gue Ras?”
Tubuhku kaku, lidahku juga kelu untuk sekedar mengucap sepatah kata. Kak Arja masih menatapku dengan raut anehnya. Mendadak aku ingin menangis.
“Maaf Kak,” ucapku pelan.
Laki-laki itu tidak bereaksi apa-apa, satu hal yang kutahu, dia itu penyimpan emosi yang baik. “Jadi, apa yang terjadi sama kehidupan ini?” tanyanya kemudian dengan nada santai.
“Kak Arja tau Paradoks waktu?” tanyaku, kali ini pandanganku beralih jalanan depan dengan lamat. “Suatu kemungkinan yang kita pikirkan, nanti akan jadi kehidupan lain di dimensi yang lain juga. Kemungkinan kita, aku, Kak Aja juga punya dimensinya sendiri-sendiri. Tapi beda sama orang-orang yang nggak sadar ada dirinya di dunia lain atau bahkan nggak tau, ingatanku selalu hidup di semua dimensi. Aku udah kenal Kak Arja sejak dulu.”
Suasana hening sejenak, Kak Arja masih mendengarkan ucapanku dengan serius.
“Contohnya yang Kak Arja bilang pernah ngerasa liat Devina sebelumnya, atau rasa aneh pas baca novelku, itu semua bukan déjà vu. Semuanya pernah kita lewatin,” ujarku.
Laki-laki di sampingku itu tidak mengeluarkan ekspresi sama sekali, aku kira, setelah kusampaikan kata-kata yang mengatakan dengan tersirat bahwa dia pernah mati sebelumnya, reaksinya tidak akan sesantai ini.
“Siapa aja yang tau tentang dimensi ini?” tanya Kak Arja
Aku menggeleng singkat lalu mengangkat bahu sekilas.
“Kok bisa?” Kak Arja menolehkan kepalanya ke samping, tepatnya ke arahku. “Kok lo bisa ngedepin ini sendirian? Nggak takut?” tanyanya.
“Berkali-kali sih, dan sekarang kata itu udah basi. Aku nggak akan bisa raih apa yang aku pengen kalau terus takut. Adakalnya kita itu harus ngalah sama keadaan. Intinya ya hadepin aja,“ ujarku.
“Apa gue selalu mati di dimensi-dimensi itu?”
Aku mengangguk pelan. “Kak Arja nggak takut kan?”
Aku mendapati laki-laki itu tersenyum sekilas. “Enggaklah,” jawabnya singkat yang jujur membuatku lega. “Gue nggak suka sesuatu yang nggak pasti. Jadi kata-kata lo barusan ini perlu gue filter dulu, cari referensi yang sumbernya jelas.”
Rautku yang tadi sudah seperti orang galau dengan sifat melankolisnya itu tiba-tiba berubah cengo setelah laki-laki itu selesai mengatakan kalimatnya. “Jadi menurut Kak Arja daritadi aku cerita itu ngarang? Nggak jelas?” tanyaku mulai nyolot.
“Yah sedikit tabu,” jawabnya santai.
Di sampingnya aku sudah komat-kamit, kalau dia sedang tidak dalam keadaan menyetir seperti sekarang, niatku untuk memukul kepalanya mungkin akan jadi kenyataan.
“Biasa aja deh mukanya!” perintahnya dengan raut songong.
Gimana mau biasa aja, topik berat yang hampir membuatku ketakutan setiap waktu itu cuma dianggap nggak jelas.
“Tau gitu nggak usah cerita tadi, rugi nih mulut,” omelku. Laki-laki itu hanya terkekeh pelan, benar-benar bukan laki-laki yang romantis. Dibujuk kek!
Sampai mobil jeep itu sampai di depan rumahku, Kak Arja masih tidak mengeluarkan kata-katanya lagi. Aku membuka pintu mobil dengan gerakan grusak-grusuk dan berniat turun secepat-cepatnya.
“Eh, biasa aja dong bukanya!” laki-laki itu berkata dengan nada ngegas tapi lebih banyak songongnya.
“Makasih ya tumpangannya,” kataku cuek.
“Dih, bilang makasih tuh dari hati, kalupun nggak ikhlas minimal senyum kek, jangan pake muka asem.”
Kampret!
“Makasih ya Kak Arja, nggak mau mampir dulu?” kataku akhirnya dengan nada selembut kain beludru serta senyum secerah matahari siang ini.
“Lain kali ya, gue sibuk,” jawabnya dengan percaya diri. Padahal sih nggak mampir juga nggak masalah. Meskipun Mama akan menyambut kedatangan laki-laki itu dengan gembira loka, tapi sekarang perasaankku sedang kesal dengan dia. Pokoknya aku nggak terima ceritaku dianggap nggak jelas.
Aku yang sekarang sudah berdiri di pinggir jalan hanya membalas ucapan Kak Arja dengan senyum singkat.
Dan sebelum mobil itu benar-benar meninggalkan halaman rumah, laki-laki itu mengucapkan sesuatu yang membuatku bimbang.
“Ras, makasih ya buat good talk-nya.”
Setelah itu aku terdiam. Jadi kesel nggak ya?


 histooriaa
histooriaa