Beberapa hari sebelum masa orientasi di kampus barunya, Abriel menerima telepon dari Mbak Wilda, yang memberinya kabar baik kalau naskah komik yang ia antarkan lima minggu sebelumnya, mendapat respons positif dari pihak penerbit. Menepati janjinya, Abriel pun mengajak Irena dan Adit untuk merayakan momen penting tersebut.
Adit menyusul mereka setelah ia mengantar gebetan barunya pulang. Entah siapa nama gadis itu, karena Abriel tidak benar-benar menyimak saat terakhir kali Adit berceloteh padanya. Alasannya karena ia yakin Adit sudah pasti akan memberitahunya nama lain.
Tidak seperti dirinya, sepertinya Adit sudah melupakan Isabel... Atau barangkali, anak itu hanya berputar-putar layaknya bumi yang berotasi, tetapi terbelit matahari purba yang lama? Entahlah. Yang jelas, pernah satu waktu Adit menanyakan kabar Isabel, sekilas, sekelebat, jenis pertanyaan yang sebetulnya tidak butuh jawaban.
"Nggak nyangka lo bisa masuk fakultas ekonomi ya, Dit," cetus Irena seraya mengiris steak-nya. Malam itu mereka makan di salah satu kafe ternama di Jalan Riau. Abriel yang mentraktir.
Adit terkekeh. "Hoki doang... Nah, lo siap-siap deh, Dung. Tahun depan kan lo masuk kuliah. Belajar lo dari sekarang... jangan pacaran mulu."
"Huuu... Belagu ya sekarang mentang-mentang udah jadi anak kuliahan," cibir Irena.
"El," ujar Adit yang menyadari bahwa sedari tadi sahabatnya itu hanya memandangi makanannya tanpa memakannya. "Kok, lo nggak kayak happy, sih? Come on, Nyet, komik lo terbit bentaran lagi, lho!"
Abriel terenyak. "Biasa... Kurang tidur gue." Ia buru-buru melahap makanannya.
Irena menyeruput minumannya. "Gimana, udah ada kabar dari si Angsa?"
Abriel tertegun sejenak mendengar panggilan itu disebut. Ia menggeleng. "Belum."
"Wait, wait. Emang dia masih ngilang?" Adit tiba-tiba menyanggah.
Dengan murah hati Irena lalu menceritakan bagian yang diketahuinya pada Adit.
"Jadi, sejak terakhir kali lo bilang waktu itu, lo masih belum dapat kabar dari dia? Kenapa nggak cerita lo!"
Abriel kehilangan nafsu makanannya seutuhnya. Ia nyengir, mendorong piringnya seraya menghela napas. "Gue takut dibilang bego sama lo."
"Ya elah, El. Enggaklah... Masak gue tega ngatain lo bego. Yang ada gue bakal ngatain lo goblooook banget karena nggak melihat lebih jelas petunjuk di depan mata lo," seloroh Adit.
"Maksud lo?"
"Mulai telusuri dari usaha nyokapnya—jangan yang di Bandung doang, lo ke Jakarta, kek, lebih niat. Come on, jangan maunya petunjuk di antar ke depan muka lo. Lo cari coba. Katanya lo serius sama dia..."
"Udah gue pikirin, sih. Cuma kemarin belum ada waktu aja." Ucapan Adit barusan seolah menamparnya. Selama ini yang ia lakukan lebih banyak menunggu ketimbang mencari.
"Aneh sih, menurutku," tambah Irena. "Kalau dia sengaja menghindari kamu. Buat apa coba? Pasti ada sesuatu."
"Atau dia memang masih butuh waktu," sambung Abriel.
"Tapi sampai kapan kalian saling tunggu? Lo, Nyet, harus maju. Cari dia: kalau perlu lo berenang melintasi lautan artik, dah. Pokoknya cari dia. Titik."
Menjelang pukul tujuh malam, Abriel dan Adit berpisah kendaraan di parkiran. Sementara Irena memilih untuk tinggal lebih lama di kafe itu, menunggu jemputan Andre.
Dalam perjalanan menuju rumahnya, Abriel merenungkan ucapan kedua penasihatnya itu. Barangkali ia memang kurang berusaha; barangkali selama ini ia hanya lelah menunggu bukan lelah mencari.
* * *
Akhirnya Abriel memantapkan diri. Setelah pembicaraannya dengan Irena dan Adit kemarin, alih-alih mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa untuk masa orientasi di kampusnya, ia sudah setengah jalan menuju Jakarta: mengemudikan mobilnya melewati jalan tol, ditemani satu album AM milik Arctic Monkeys dan sekaleng kopi, serta berbekal alamat dari brosur katering yang ia dapatkan sebelumnya yang digeletakannya di dasbor.
Pukul dua siang, ia sudah sampai di tempat usaha katering dan dekorasi pernikahan milik ibu Isabel di bilangan Jakarta Selatan. Ada beberapa tamu yang sedang menunggu untuk dilayani, satu tamu sedang memilih menu untuk acara pernikahannya nanti, jadi Abriel mendahuluinya.
"Sore, Mbak. Gini, saya Abriel, kenalanannya Ibu Jane, um, boleh nggak saya minta alamatnya Ibu Jane yang di sini? Soalnya saya udah datang jauh-jauh dari Bandung buat ketemu sama Bu Jane," ujar Abriel kepada wanita berjilbab di depannya.
Wanita itu tampak mengingat-ingat, kemudian membisiki pegawai di sebelahnya yang sedang melayani tamu.
"Saya telepon Bu Jane dulu, ya. Udah dua bulan sebenarnya saya yang handle urusan di Jakarta, Bu Jane lebih sering di Bogor untuk sekarang ini," ujarnya. Wanita itu kemudian memungut telepon di sebelahnya. Setelah berbicara sebentar dengan suara tak kentara, ia kembali menghadap Abriel. "Bu Jane memang lagi di Jakarta, cuma... katanya nggak lagi ingin ketemu tamu. Maaf ya, saya nggak bisa bantu."
Abriel tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Kalau ngomong via telepon bisa nggak, Mbak?"
"Kalau itu saya kurang tahu. Tadi Bu Jane langsung bilang nggak bisa ditemui soalnya..."
Ia menyerahkan brosur kepada wanita itu. "Setiap saya telepon nomor itu, saya cuma disuruh ninggalin pesan tanpa ada kepastian. Makanya saya datang ke sini."
"Oh, gitu..." Wanita itu tampak tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Abriel tampak begitu putus asa. "Mungkin Bu Jane memang sedang sibuk. Coba Mas hubungi lagi asistennya, namanya Mbak Miftah." tambahnya membesarkan hati.
Abriel menghela napas. Ia kemudian merasa tidak ada gunanya mendesak wanita itu agar mau bersimpati padanya. Saat ia sedang di dalam mobil, ia mendapat sebuah SMS. Dari ibu Isabel.
El, besok kamu masih di Jakarta? Kalau iya, temui Tante di Chicken Town Kemang, ya. Jam 1 siang. Hari ini Tante sedang banyak urusan, jadi nggak bisa mampir-mampir.
Tanpa berpikir lagi, Abriel segera mengetikkan: Oke, Tante. Besok saya ke sana. Makasih, Tante udah kasih saya waktu. Gimana kabar Isabel Tante?
Namun hingga pukul setengah lima petang, saat Abriel sampai ke Tanjung Mas, tempat kediaman Kausar, teman SD-nya yang ketika dikontek langsung bersedia menampungnya bermalam, ia tidak juga mendapatkan balasan SMS dari ibu Isabel.
Malamnya, sesaat sebelum ia terlelap, ponselnya bergetar. Pesan itu akhirnya dibalas:
Besok kita bicarain tentang Abel ya, Abriel. Malam.
* * *
Baru sebentar Jane duduk di sofa di dalam kafe itu, saat ia melihat anak itu mendorong pintu kaca dan masuk. Wajahnya masih saja tampan, meskipun air mukanya penuh dengan kekhawatiran.
Abriel tersenyum muram ketika ia menemukan Jane di sana. Ia kemudian menjulurkan tangan untuk menyalami Jane, menanyakan kabar wanita itu sebelum duduk di depannya.
"Kamu sendiri ke Jakarta, El?" tanya Jane. "Udah makan? Kamu pesan dulu, ya. Tante udah pesan barusan."
"Nggak usah, Tante. Saya pesan minum aja. Barusan, saya dijejali makanan banyak sekali di rumah teman lama saya," Abriel menolak sopan. Jelas, ia masih berusaha tersenyum.
Jane menghela napas. "Maafin kalau tadinya Tante nggak mau temui kamu, itu karena Tante sebelumnya merasa kalau belum saatnya urusan Isabel diusik dulu," cetusnya. "El, kejadian di Bandung itu benar-benar ngejatuhin mental Abel lagi. Sudah susah payah dia berusaha bangkit, dia harus dibikin drop lagi. Abel ceritain semuanya sama Tante. Termasuk tentang hubungan kamu sama dia. Pertama-tama, Tante mau ucapin makasih sama kamu, berkat kamu, hatinya kembali hangat."
Abriel terdiam, termenung. Tidak ingin berkomentar. Ia hanya ingin mendengar kejelasan kabar Isabel saat ini.
Seorang pramusaji kemudian datang untuk mengantarkan pesanan Jane dan mencatatkan pesanan Abriel.
"Tante yakin, dia nggak pernah bermaksud untuk menyakiti siapapun, bikin khawatir kamu terutama, orang yang berarti buat dia," sambung Jane. "Tapi, dia masih butuh sendiri, untuk sementara waktu, nggak mau diganggu. Menurut Tante, biarlah dia tenang dulu. Yang Tante paham, Isabel selalu punya teori untuk semua hal. Kalau dia yakin inilah saatnya, Tante yakin dia akan muncul lagi di permukaan, menghirup oksigen yang sama dengan kita."
Abriel mendesah, membuang pandangannya ke luar jendela sebelum kembali memandang Jane. "Orang-orang yang ngelakuin itu, apa Tante laporin ke polisi? Mereka pantas dapat imbalan untuk apa yang mereka lakuin ke Isabel."
"Tante juga sependapat, tapi Abel nggak mau memperpanjang lagi. Makanya sudahlah, Tante ikutin aja," jawab Jane.
Mereka lalu sama-sama terdiam beberapa waktu.
"Abel itu ibaratnya ketam pertapa. Makhluk itu amat mencintai cangkangnya. Tapi, dia bisa saja hidup tanpa cangkangnya, berjalan menyusuri bulir pasir dan membenamkan diri. Meski begitu, pada akhirnya, ia tetap membutuhkan cangkangnya: yang lama—atau yang baru. Semua ada waktunya. Biarlah Abel bebas mengeksplor prasangkanya terhadap dunia dulu, biarlah dia merasa aman dengan semesta ini lagi. Ketika semuanya sudah stabil, ia akan sanggup memilih."
"Memilih kembali sama saya, atau melepas saya," Abriel menyimpulkan cepat. "Apa begitu, Tante?"
"Peluang kamu lebih besar daripada siapapun. Kamu sendiri juga tahu itu," ujar Jane, membesarkan hati Abriel.
"Jadi sekarang saya harus gimana, Tante?" Jane jelas membaca kefrustasian di wajah itu.
Jane tiba-tiba merasa inilah saatnya. Ia kemudian menyodorkan kantong kertas berwarna perak kepada Abriel. "Ini dari Abel buat kamu. Satu bulan yang lalu, dia nitip ini sama Tante supaya dikasihkan ke kamu kalau kamu betul-betul clueless. Tante awalnya nggak merasa sekarang saatnya, tapi melihat kesungguhan kamu mencari Abel, mungkin inilah waktunya yang dimaksud dia."
Lambat, Abriel menarik benda itu mendekat padanya. Ia memandangi kantong kertas itu, yang mana bagian atasnya direkatkan oleh selotip bening.
"Saran Tante, kamu bukanya di rumah aja, ya. Biar kamu bisa memaknai semuanya dengan tenang."
Saat itulah pramusaji kembali muncul untuk mengantarkan segelas minuman untuk Abriel.
* * *
Usai berpisah di depan kafe itu, Abriel menjinjing benda itu di tangannya hingga sampai ke mobilnya. Ia lalu menghidupkan mesinnya, menyalakan CD player yang otomatis memutar lagu Arctic Monkeys terakhir yang didengarnya tadi: Mad Sounds.
Ia membuka wadah itu, mengeluarkan isinya. Kotak DVD berjudul Breakfast at Tiffany's yang cover-nya menampilkan perempuan cantik bergaun hitam—Abriel mengenali perempuan ikonik itu. Ia pernah melihat sosoknya dijadikan poster di beberapa tempat. Ia juga ingat bahwa saat ia bertemu Isabel di pemakaman dulu, Isabel bergaya persis seperti penampilan wanita di cover itu. Audrey Hepburn. Audrey... Ternyata dari sana Isabel mendapatkan inspirasinya. Ada secarik notes di bagian belakang wadah DVD itu, tulisannya, "Tengkorak saja yang bentuknya seram, memberikan kesempatan kita untuk menjadi besar".
Sambil sedikit mengecilkanvolume stereo-nya, ia berusaha memaknai kata-kata itu. Tapi ia tetap tidak paham maksudnya.
Sore itu, Abriel pun memutuskan kembali ke Bandung membawa hatinya yang terbebat keputusasaan.


 Andrafedya
Andrafedya









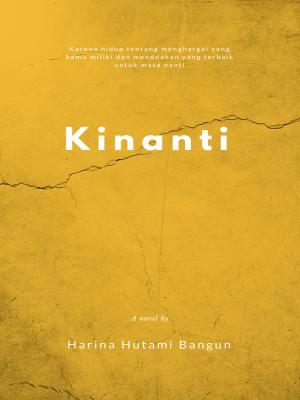






Teenlit namun lbh matang. Metropop namun tidak ngepop amat. Kadarnya pas, bakal lanjut membaca cerita cantik ini. Trims Author untuk cerita ini
Comment on chapter 1. Makhluk MalangKalau suda beres saya akan kasih review.