“YAN?” Aku berteriak sambil berlari untuk mengejar Lyana yang berjalan ngebut. Aku menyalipnya dan berhenti tepat di depannya untuk menahan langkahnya. Lyana mencoba menghindariku dengan menerobos sisi kananku. Aku mencekal tangannya.
“Yan? Please, dong! Jangan kayak anak kecil begini.”
Lyana menatapku tajam. “Gue? Kayak anak kecil?” Lyana tersenyum sinis. “Apa kabar lo? Yang tanpa merasa berdosa bawa Rafa ke depan Arda.”
“Makanya dengerin dulu penjelasan gue.” Aku berseru tertahan. “Pertama, lo nggak bilang kalo ada Arda juga. Kedua, gue terpaksa nebeng Rafa.” Aku memberi penekanan pada kalimat terakhir.
“Semalem itu gue berdiri di pinggir jalan raya depan kompleks rumah gue. Nggak tahu kebetulan atau apa, Rafa lewat dan tawarin gue tumpangan. Tadinya gue nolak. Tapi berhubung udah setengah jam nggak dapet taksi juga, makanya gue iyain. Dan lagi, gue udah larang dia ikut masuk ke starbucks. Tapi dia maksa. Gue bisa apa, coba?”
Ya Tuhan. Maafkan hambaMu yang berbohong ini. Demi keselamatan, maklumilah kebohonganku kali ini.
Lyana tidak menjawab. Dia menghembuskan napas berat. Aku menunggu dengan tegang apa yang akan dikatakan Lyana.
“Lo kan bisa tolak, Ra.” Kali ini nada suara Lyana terdengar desperate. “Gue ngerasa bersalah banget sama Arda. Tadinya gue mau bantu lo baikan sama dia. Tapi, ternyata?” Lyana menarik napas panjang. Aku bisa merasakan mataku berkaca-kaca. Terharu atas usaha Lyana sekaligus sedih karena membuatnya kecewa.
“Maaf.” Kataku lirih. Suaraku mulai bergetar menahan air mata.
“Arda marah. Dia udah nggak mau lagi peduli sama lo. Itu yang dia bilang tadi pagi ke gue. Kayaknya lo harus usaha sendiri buat baikan sama dia. Itu pun kalo lo serius sama dia. Kalo enggak, lupain.” Pelan Lyana mengatakan itu. Tapi rasanya nyaring di telingaku.
“Gue mau ke kantin. Dika udah nungguin buat sarapan.” Kata Lyana kemudian meninggalkanku.
Pandanganku buram. Aku mengusap air mataku yang membasahi pipi. Itu pun kalo lo serius sama dia. Kalo enggak, lupain. Kalimat Lyana itu kembali terngiang ditelingaku.
Aku sendiri juga bingung. Kenapa semalam aku mengiyakan ajakan keluar Rafa. Apalagi dengan bodohnya membiarkan dia ikut bertemu Lyana. Yang ternyata ada Arda juga disana.
Aku bingung. Jenis perasaan apa yang kupunya untuk Arda dan Rafa. Satu sisi hatiku mengharapkan Rafa kembali. Satu sisi lagi menginginkan Arda. Aku nyaman bersama Arda. Tapi, aku juga ingin merasakan kembali masa-masa bersama Rafa.
----
“TARAA. Fokus! Hadang Rena!”
Aku mendengarkan instruksi Pak Daren untuk menghadang pergerakan Rena yang sedang mendrible bola. Akulah orang terakhir dan harapan terakhir timku untuk menghadang pergerakan Rena yang seperti bola bekel itu. Kecil tapi gesit dan lincah.
Aku melihat Verin berlari menunju aku untuk membantu menghadang Rena. Fokusku sudah mencapai titik sempurna untuk merebut bola dari tangan Rena saat tiba-tiba aku melihat dua manusia yang berjalan beriringan. Arda dan Ralin.
Wait? Siapa? Arda sama Ralin? Ya Tuhan. Apa sih, dosaku dimasa lalu sampai Ralin berkali-kali membuatku emosi? Kenapa dia harus muncul dihidupku dan merusak alur cerita yang sudah kususun dengan susah payah.
“TARAA?”
Aku terkesiap mendengar teriakan Pak Daren. Aku tersadar dari keterpakuanku dan saat itu juga Rena berhasil memasukkan bola ke ring yang harusnya kujaga. Yang harusnya dengan mudah aku bisa menghentikan pergerakan Rena tadi.
Sepertinya Ralin kutukan buatku. Bawaannya sial terus kalau ada didekatnya. Bahkan radius lima puluh meter seperti ini pun masih berpengaruh. Dulu dia rebut Rafa dariku. Sekarang, dia berdua Arda. Dan sukses membuyarkan konsentrasiku yang hampir klimaks.
Aku menatap teman satu timku dengan rasa bersalah. Mereka terlihat kecewa padaku. Marah. Ada juga yang menatapku dengan tatapan sebal. Kesal. Jengkel. Marah.
“Kamu itu bukannya main lebih bagus, malah makin kacau seperti ini. Kalau begini terus, mana mungkin saya masukkan kamu ke tim inti?” Pak Daren berhenti sejenak untuk mengambil napas. Siapa juga yang suruh teriak-teriak seperti itu? Padahal berkata pelan saja aku juga dengar.
“Kamu keluar!” Pak Daren membentakku sampai aku mengkeret. Kemudian mengalihkan tatapannya ke segerombol temanku yang duduk di pinggir lapangan. “Shena, kamu masuk ganti posisi Tara.” Pak Daren menunjuk Shena.
Yaelaa. Siapa juga yang ingin masuk tim basket. Pak Daren juga kan, yang memaksaku. Padahal aku nggak berminat sama sekali. Dan kalian tahu apa alasan Pak Daren merekrutku untuk masuk pelatihan tim basket? Hanya karena tubuh tinggiku dan lariku yang lumayan kencang. Padahal untuk menjadi pemain basket kan, nggak cukup hanya dengan tinggi badan dan lari doang. Skill dan kemauan juga harus ada, kan?
Aku berjalan dengan lesu menuju Lyana yang duduk di pinggir lapangan. Menerima minuman isotonik yang dia sodorkan padaku. Dan dengan sedikit hempasan aku duduk di sampingnya.
“Lo kenapa, sih? Perasaan dari tadi mainnya bagus. Kenapa tiba-tiba jadi kacau gitu?”
Aku tidak langsung menjawab. Menenggak minuman isotonik sampai habis setengah botol. Mengusap bibirku kemudian menoleh untuk menatap Lyana.
“Lo nggak liat siapa yang barusan lewat?”
“Siapa emang? Christiano Ronaldo? Apa Robert Pattinson?”
“Taylor Lautner.” Jawabku pendek. Lyana mengernyitkan dahinya.
“Taylor Lautner?” Lyana bertanya dengan wajah innocent. Aku memutar mata dengan sebal. Aku tahu sebenarnya si Lyana ini tahu siapa yang kumaksud. Sepertinya dia sengaja sekali mempermainkanku.
“Plesae deh, Yan!?” Aku berkata dengan kesal. Lyana tertawa pelan.
“Arda maksud lo? Mana? Gue nggak lihat tuh.” Lyana menoleh kanan-kiri untuk mencari keberadaan Arda. Nggak bakal ketemu. Orang Ardanya sudah masuk perpustakaan berdua Ralin.
Astaga! Kenapa sepertinya sejak perselingkuhan Rafa, nama cewek itu seriiing banget aku sebut, ya? Padahal aku kan sudah melabelinya dengan kata haram.
“Masuk perpus. Sama Ralin.” Jawabku pelan.
“WHAAAT?” Seru Lyana kemudian membekap mulutnya sendiri. Sesaat membukanya kembali. “Siapa lo bilang? Ralin?”
“Yup. Si stranger yang entah muncul dari planet mana itu, yang datang tiba-tiba dan ngerebut Rafa dari gue. Dan sekarang?” Aku tersenyum sinis. Menyadari buruknya nasib percintaanku.
“Ya elo sih. Coba semalem itu nggak bikin masalah dengan ngajak Rafa ke starbucks. Pasti?” Lyana berhenti karena melihat tatapan tajamku.
“Please, Yan? Harus ya, lo ungkit-ungkit terus kesalahan gue itu?” Aku mengajukan pertanyaan retoris. Lyana hanya nyengir. Kemudian kami terdiam sampai Pak Daren membubarkan kami untuk istirahat. Plus review pertandingan yang ujung-ujungnya malah mengomeliku.
----
“Hai, Tara? Sendirian aja.”
Tanpa menatapnya pun aku tahu siapa pemilik suara cempreng yang dibuat-buat sok manja itu. Yeah, she is Ralin. Si stranger yang merebut Rafa dan sekarang lagi berusaha merebut Arda. Nggak merebut juga sih. Kenyataannya kan, aku baru memasuki tahap PDKT sama Arda. Tapi tetap saja kelakuan si Ralin itu menyebalkan. Kalau kata Bu Wiyarti guru Kewarganegaraan, ini sangat tidak terpuji.
Aku tidak menjawab. Sebelum aku benar-benar muak, lebih baik segera kuhabiskan setengah mangkuk soto Ayamku ini.
“Baru ditinggal Arda ya?”
Oke. Lumayan mancing pertanyaannya. Tapi, biarlah, nggak usah ditanggapi.
“Rafa buat lo deh. Gue udah nggak butuh. Tapi Arda, sekarang buat gue.” Lanjut Ralin tanpa mempedulikan perubahan warna mukaku yang memerah menahan emosi.
Aku meletakkan sendokku dengan sedikit sentakan. “Mau lo tu apa, sih?” Aku berseru dengan keras. Ralin sedikit berjengkit. Seketika itu seisi kantin menatap kami. “Elo bisa nggak, nggak usah ganggu gue? Belum cukup yang dulu itu?”
Ralin menyibakkan rambutnya dengan sombong. Kemudian tersenyum sinis. “Belum cukup! Sebelum lo memohon ke gue untuk lepas cowok lo itu.” Tajam Ralin mengatakan itu.
“Sayangnya Arda itu bukan cowok gue. Lo salah sasaran kalo tujuan lo buat rebut cowok gue LAGI.” Kataku kemudian berdiri dan meninggalkan Ralin.
Ya Tuhan. Apa Ralin itu benar-benar kutukan buatku? Kenapa dia suka sekali membuatku marah. Apa dimasa lalu aku jahat padanya, sampai dia menyusulku ke masa sekarang? Untuk balas dendam mungkin.
-----
Asap kendaraan. Suara bising dari motor-motor anak berandalan. Matahari yang terik. Lengkap sudah penderitaanku siang ini. Pukul tiga lebih. Satu jam dari jam sekolah dibubarkan, Pak Danang nggak juga muncul. Yang tadinya aku menunggu di dalam sekolah harus rela diusir satpam karena pintu gerbang mau dikunci.
Kok ya tumben-tumbenan hari ini nggak ada les, rapat guru, rapat OSIS, kegiatan ekstrakulikuler atau apa pun itulah yang mengharuskan gerbang nggak dikunci. Hasilnya sekarang aku harus menunggu Pak Danang di halte depan sekolah.
Kalau masalah bising ataupun terik matahari sih, nggak terlalu aku pusingkan. Yang membuatku enggan untuk duduk di halte adalah, Lega yang bisa muncul dengan tiba-tiba. Nggak lupa kan, sama kejadian kemarin itu? Dan asal tahu saja, Lega itu sekali ditolak, tindakan selanjutnya akan lebih ekstrim. Aku jadi menyesal kenapa tadi nggak menerima tawaran Lyana untuk pulang bareng.
Bukannya apa-apa, berhubung aku orangnya sangat pengertian dan nggak mau juga jadi obat nyamuk antara Lyana dan Dika, aku menolak tawaran pulang bareng dengan alasan Pak Danang sebentar lagi jemput. Apanya? Sudah sejam ini nggak muncul juga. Mana teleponnya nggak aktif lagi.
Dan… malapetaka akhirnya tiba. Aku melihat Lega keluar dari warung tempat dia biasa nongkrong dengan teman-temannya. Aku menoleh ke kanan. Berharap Corolla Altis silver metallic yang Papa belikan empat bulan lalu itu muncul dan berhenti tepat di depanku. Atau paling tidak bus lah. Berharap taksi muncul pada jam segini di daerah sekolahku itu sama saja dengan berharap Chace Crawford muncul dan menawarkan tebengan. MUSTAHIL.
Doaku adalah, semoga saja Lega nggak melihatku. Atau tiba-tiba perutnya mules dan membuatnya ingin cepat-cepat pulang. Atau kalau enggak, ada kabar saudaranya kecelakaan dan membutuhkan pertolongannya. Atau anjingnya mau melahirkan dan Mamanya nggak bisa mengantar ke dokter. Atau?
Oh, no! He saw me! Mati gue! Mati! Mati! Siapapun, datang dan tolong aku.
Seperti yang sudah kutebak dan yang terjadi sebelumnya. Lega menatapku dengan senyum sinisnya. Sinis campur senang. Emmm… gimana mendeskripsikannya ya? Ya begitulah. Dan sekarang dia masuk ke mobilnya. Fuuihhhh, leganya. Mungkin salah satu doaku yang mengharuskan dia pulang itu dikabulkan sama Tuhan.
Aku terus mengawasi sampai Everest hitam itu melaju menjauh dari warung. Tiga meter, enam meter, delapan meter……
Napasku serasa terhenti saat tiba-tiba Lega memutar kemudi sampai seratus delapan puluh derajat. Berbalik arah dan sekarang melaju cepat menuju ke arahku. Aku langsung memalingkan wajah. Melanjutkan napasku yang sempat terhenti tadi. Lega menghentikan laju mobilnya tepat di hadapanku dengan bunyi ban berdecit. Aku terbatuk-batuk. Mengibaskan tanganku untuk menghalau debu.
Lega melompat turun dari mobilnya kemudian menghampiriku. “Dentara Mahardika.” Lega menyebutkan nama lengkapku dengan lantang. Kemudian duduk di sampingku. Seketika itu juga tercium bau nikotin bercampur parfum dari tubuhnya. Membuatku mual. Aku memalingkan wajah ke samping kanan.
“Pengennya sih nawarin pulang, tapi pasti lo tolak. Jadi?” Lega mendekatkan wajahnya ke wajahku yang masih menoleh ke kiri. Refleks aku menarik kepalaku ke belakang. Lega tersenyum tipis kemudian kembali menarik wajahnya. “?gue temenin aja sampek supir lo jemput. Nggak masalah, kan?”
Tentu aja masalah. Karena elo, trouble maker. Dimana elo berada, disitu masalah akan muncul.
Tapi aku nggak berani mengatakan itu. Cari masalah namanya. Bukannya aku takut atau apa. Hanya malas meladeni Lega. Ah, jadi menyesal kenapa nggak menerima tawaran Lyana untuk pulang bareng. Lebih ikhlas jadi obat nyamuk ketimbang bertemu Lega seperti ini.
“Hei, Tara? Kok diem aja, sih?” Lega mengusap kepalaku pelan. Dengan kasar aku mengibaskan tangannya.
“Jangan lancang, ya?” Seruku dengan nada tinggi.
Wajah Lega mengeras. Aku tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Lega itu suka main fisik sekali pun dengan cewek. Jadi, sebelum terjadi sesuatu yang nggak diinginkan?yang pasti buruk untukku?lebih baik aku pergi. Memohon ke satpam untuk dibukakan gerbang sepertinya bukan ide yang buruk.
Maka, aku berdiri. Melangkah meninggalkan Lega dengan langkah cepat. Tapi sekali lagi, aku hanya bisa berencana. Baru tiga langkah aku merasakan sebuah tangan mencengkeram lenganku dengan kuat. Menarik dan mendorong tubuhku sampai turun dari trotoar dan menabrak mobil. Lega menatapku tajam.
“Lo sombong banget sih, jadi cewek? Oke, lo emang cantik gue akui. Tapi lo itu bodoh. Satu-satunya cewek bego yang nolak cowok keren, tajir, populer kayak gue.” Lega berkata dengan intonasi naik turun. Terlihat sekali menahan emosi.
Iya sih. Harus kuakui. Lega memang ganteng, charming, tajir (tapi duit orangtuanya yaa..). Mobil mewahnya itu kalau dibelikan mobilku mungkin bisa dapat dua. Tapi, sikapnya yang bossy, bad boys, angkuh, sombong, dan sok banget itu yang bikin cewek waras kayak aku nggak mau deket-deket dia.
Aku tersenyum sinis. “Tajir, memang. Tapi itu duit orangtua lo. Keren, menurut gue masih kerenan juga Julius. Populer? Ya, populer karena kebandelan lo sama kebodohan lo.”
Aku berhenti sejenak. Menantang tatapan nyalang Lega. Aku bisa melihat kemarahan dari kedua rahangnya yang mengatup rapat. Jujur, aku ngeri melihatnya. Tapi bukannya diam, aku malah semakin memancing emosi Lega dengan kalimat tajamku.
“Tanpa duit dari orangtua lo, elo itu nothing. Nggak ada artinya.” Lanjutku. Saat itu juga Lega semakin menekan kedua lenganku hingga punggungku benar-benar menyatu dengan pintu mobilnya. Kedua lenganku terasa nyeri. Aku hanya meringis tanpa bisa berontak.
“Sekali lagi lo ngomong gitu?”
“Kalo lo emang cowok, nggak bakal nyakitin cewek kayak gitu.” Sebuah suara memotong kalimat Lega.
Aku dan Lega menoleh serempak. Arda berdiri tiga meter dari tempatku dan Lega. Dan disampingnya berdiri Ralin yang memeluk lengannya dengan mesra. Rasanya perih. Bukan dikedua lenganku yang dicengkeram Lega dengan kuat. Melainkan dihatiku. Melihat Ralin yang saat ini tersenyum penuh kemenangan menatapku.
Lega melepaskan cekalannya dilenganku. Membalik tubuh untuk menghadap Arda dan Ralin. “Arda. Si kapten sepakbola sekolah yang membuang Tara. Udah dapet gandengan baru, nih?” Lega berkata dengan sinis. Matanya menatap tajam menghujam Arda. Arda, selalu dengan wajah tenangnya. Dan itu membuat dia terlihat semakin menarik. Astaga. Disaat seperti ini pun aku masih memikirkan hal seperti itu. Aku rasa aku benar-benar gila.
“Gue nggak pernah membuang siapa pun.” Arda menjawab dengan tenang.
“Gitu, ya? So?” Lega menoleh sesaat untuk menatapku. Kemudian melanjutkan, “?bisa dong Tara buat gue? Lo kan udah punya cewek tuh.” Lega menunjuk Ralin dengan dagunya. Arda hanya mengangkat sebelah alisnya.
“Nggak ada cewek waras yang bakal mau sama lo.” Sahutku dengan tajam. Lega menoleh untuk menatapku. Dengan gerakan cepat kembali mendorong tubuhku sampai membentur mobil. Aku menjerit refleks.
Kejadiannya sangat cepat. Arda menarik tubuh Lega untuk menjauh dariku. Dan beberapa kali melayangkan pukulan ke wajah Lega sampai dia tersungkur.
“Sekali lagi lo berani sentuh dia, gue pastiin lo nggak akan hidup tenang.” Arda meneriakkan kata-kata itu tepat di depan muka Lega.
Speechless. Aku menatap Arda dengan nggak percaya. Aku senang sekaligus terharu mendengar apa yang baru saja dia katakana dengan nada sarat kemarahan itu. Arda menegakkan tubuhnya dan menarik tangan kananku untuk mengikutinya. Aku sedikit kesulitan mengikuti langkah lebarnya.
“Arda. Gue gimana?” Ralin berteriak.
Aku menoleh sekilas ke arah Ralin yang masih berdiri di tempatnya dengan wajah kesal. Tanpa mempedulikan Ralin, Arda terus menarikku menuju mobilnya.
----
Déjà vu. Sekitar sebulan lalu, saat Arda memergokiku pelukan dengan Rafa. Saat Arda mengantarku pulang waktu itu. Hening selama di mobil. Saat ini pun juga begitu. Arda sama sekali tidak bicara. Tatapannya lurus ke depan. Aku baru hendak membuka mulut saat tiba-tiba Arda bicara.
“Jangan pancing kemarahan Lega kayak tadi kalo kamu nggak pengen kenapa-napa.” Arda berkata dengan nada yang seperti menyalahkanku. Entah kenapa, aku nggak suka mendengarnya.
“Terus, menurut kamu, aku harus diem aja gitu kalo dilecehin kayak tadi? Kamu nggak tau sih, apa yang dia bilang sebelum kamu dateng. Atau mungkin kamu malah seneng kali denger Lega lecehin aku begitu?” Aku berkata dengan nada menyolot.
“Kalo aku seneng nggak bakal aku tolongin kamu.” Arda menatapku tajam. Nada suaranya terdengar antara kesal dan kalau aku nggak salah tebak, putus asa. Ada juga nada lelah didalamnya. Entahlah!
Hening.
Aku menarik napas berkali-kali untuk menekan amarahku yang tiba-tiba menggelegak. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Hanya diam. Begitu pun dengan Arda. Aku merasa kebersamaan kami ini seperti kebersamaan dua orang bisu, tuli dan buta. Nggak ada interaksi apa pun.
Di kejauhan, pagar hitam rumahku sudah terlihat. Dalam hitungan detik saja kami akan tiba di depannya. Dan kebersamaan ini pun harus berakhir.
Arda menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang rumahku. Lagi-lagi hening. Terlebih saat mesin mobil dimatikan, kesunyian semakin terasa. Aku nggak juga turun dari mobil.
“Kenapa harus Ralin?” Pelan aku mengatakan itu. Tapi tenggorokanku terasa kering. Seakan-akan baru saja mengatakan kalimat panjang. Aku menoleh untuk menatap Arda. “Apa karena dia pernah sama Rafa? Kamu mau balas dendam ke aku?” Aku melanjutkan dengan suara sedikit bergetar. Arda masih tetap bergeming. Aku merasakan mataku memanas. Kalau aku melanjutkan kata-kata yang sudah ada di ujung lidahku, bisa kupastikan aku akan menangis di depan Arda. Dan aku nggak mau itu terjadi. Aku nggak mau terlihat lemah di depan Arda.
Aku menghembuskan napas, putus asa. Tanpa berkata lagi aku turun dari mobil. Arda tidak menahanku. Tidak juga menjawab pertanyaanku. Yang ada dia langsung melajukan mobilnya begitu aku benar-benar turun dari mobil. Membuat dadaku semakin sesak.
Aku menekan bel rumah berkali-kali dengan lengkingan panjang. Kulihat Pak Danang yang sedang mencuci Honda Jazz biru Mama, tergopoh-gopoh menghampiriku (salah satu hal yang aku banggakan dari Mama, nggak tergila-gila dengan barang mewah dan terbaru?seperti Ibu-Ibu sosialita lainnya yang hobi banget pamer kekayaan suami?asal tahu saja, Mama beli mobil itu dengan uangnya sendiri). Sebentar. Tumben-tumbenan Mama sudah pulang?
“Aduh, Non Tara. Sekali aja atuh pencet belnya. Bapak denger, kok.” Kata Pak Danang sambil membuka gembok.
“Bapak lagi! Kenapa nggak jemput saya? Saya hampir kering, tau, kejemur matahari gara-gara nungguin bapak yang nggak dateng-dateng.” Semburku begitu Pak Danang berhenti bicara. Ini salah satu sifat burukku yang nggak juga hilang. Kalau lagi kesal, sopan santunku bisa menguap begitu saja.
Aku menerobos masuk sebelum pintu gerbang benar-benar terbuka. Begitu mengunci gerbang, Pak Danang berlari menyusulku.
“Tadi kan Non Tara bilang nggak usah dijemput. Mau bareng Non Lyana katanya.”
Aku menghentikan langkahku. Pak Danang ikut berhenti. Aku menatapnya dengan mata menyipit dan dahi mengerut.
“Kapan saya ngomong begitu?”
“Tadi pas jam makan siang. Pas Non istirahat, telepon saya tadi.” Pak Danang mengingatkan. Aku memutar otak untuk mengingat kejadian empat jam yang lalu.
Ups! Aku ingat sekarang. Rencananya tadi aku mau nebeng mobil Lyana sekalian minta antar ke toko buku buat beli The Cuckoo’s Calling kemarin itu. Tapi batal karena supir Lyana nggak bisa jemput dan Lyana pulang bareng Dika. Karena sifat nggak enakku, aku menolak saat Lyana menawariku pulang bareng. Yaelaa, siapa juga yang mau jadi obat nyamuk?
“Iya sih…. Tapi kan…. Tadi saya teleponin Pak Danang berkali-kali buat minta jemput. Tapi HP Pak Danang malah nggak aktif.” Yeah, pertahanan terakhir. Membela diri disaat salah sekali pun.
“HP saya baterainya habis. Ini juga masih di isi.”
“Ya harusnya jangan sampek mati dong. Ini kan masih jam kerja. Nyusahin orang aja!” Kataku dengan kesal kemudian meninggalkan Pak Danang yang masih berdiri ditempatnya. Daripada semakin banyak kata-kata kasar yang keluar dari mulutku.
Aku bisa menebak Pak Danang menatapku dengan dahi berkerut-kerut. Aku rasa otaknya sekarang jadi gimbal karena bingung dengan rentetan kalimatku yang walau pun bersalah masih saja membela diri.
-----


 annis0222
annis0222



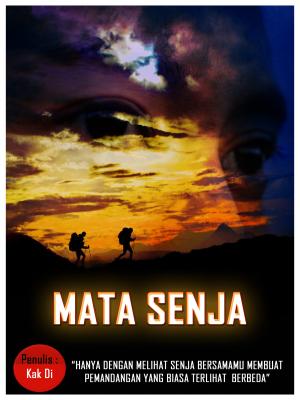

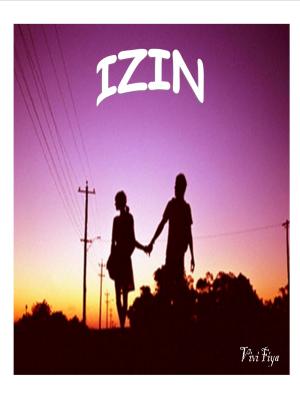
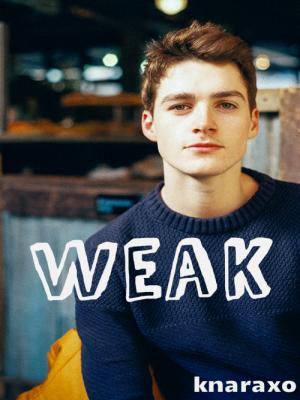



Thank you, kakak.... Cerita kakak lebih keren. Jadi minder... ????
Comment on chapter SATU