Aku keluar dari kediaman Ahn Tae Young dan kakeknya usai hujan reda. Jam di pergelangan tanganku telah menunjukkan angka empat lewat tujuh belas. Kakeknya Ahn Tae Young berterima kasih atas ayam goreng yang kubawakan untuknya, ia juga tak henti-hentinya memintaku untuk mendatanginya lagi bila aku punya waktu saat aku sedang berpamitan dengannya tadi. Aku pun tak lupa balik berterima kasih padanya karena telah membiarkanku menumpang sebentar di rumahnya.
Perasaan gembira memenuhi rongga dadaku sewaktu melangkahkan kaki bersama Ahn Tae Young menuju kereta bawah tanah—Ahn Tae Young bilang, ia ingin mengantarku ke sana. Sebab, selain karena keramah-tamahan kakeknya Ahn Tae Young padaku, pengetahuan tentang diri pemuda itu semakin bertambah-tambah di dalam ingatanku. Aku juga merasa karena adanya hari ini hubungan kami bertambah dekat.
Namun, ada satu hal yang mengganggu isi kepalaku.
“Tae Young-ssi, boleh aku tahu, mengapa kau lebih memilih mengambil kuliah di jurusan Politik ketimbang melanjutkan bakatmu itu?” tanyaku, “Padahal, kau bisa saja menjadi pianis sekarang, atau mungkin menjadi musisi.”
“Kau tahu, kau orang yang keempat puluh tujuh yang menanyakan hal itu kepadaku.” Sahutnya.
Aku menatapnya tak percaya. “Kau menghitungnya?”
Ia mengangguk. “Tanpa sadar aku menghitungnya.”
Aku pun terkekeh.
“Sedari kecil, aku selalu menganggap bermusik hanya sekadar hobi. Bukan suatu bakat yang kuasah setiap harinya sebagai bekal masa depanku.” Jelasnya, kemudian. “Berbeda dengan politik. Semasa sekolah dulu, aku hampir-hampir tak pernah tahu tentang politik. Namun, sewaktu akan melanjuti pendidikan ke perguruan tinggi, keinginan mengambil jurusan yang mana bukanlah keahlianku semakin menggebu-gebu. Begitu, politik adalah pilihanku. Kuanggap menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Politik adalah tantangan baruku dalam menjalani hidup.”
Ternyata, pemuda itu juga senang menantang diri. Akan kuingat itu.
“Kau pernah berpikiran sama sepertiku?” tanyanya. “Tentang bakat yang kusebut sebagai hobi, dan menantang hidup dengan menyelami sesuatu yang sama sekali tak kau tahu?”
Aku pun berpikir.
Selama aku hidup, tak pernah kuketahui bakat macam apa yang ada pada diriku. Apa menyanyi saat sedang membersihkan diri di kamar mandi juga termasuk bakatku? Sewaktu aku masih tinggal di Goyang, Ibu acap kali memujiku bila tak sengaja mendengarku bernyanyi dari dalam kamar mandi. Karena kamar mandi di rumah bukanlah ruangan kedap suara, terlebih kamar mandinya di dekat dapur, satu keluargaku pun pasti bisa mendengarnya meskipun mereka berada di ruang tengah. Di luar kamar mandi, biasanya Ibu akan berteriak seperti ini: Yuna-ya, bukankah sebaiknya kau mengikuti audisi pencarian bakat yang diselenggarai oleh sebuah agensi hiburan di Seoul? Suaramu itu bagus.
Namun, selain di dalam kamar mandi, aku hampir-hampir tak pernah bernyanyi, kecuali bila dipaksa Ibu. Pernah sekali aku menyanyi di depan keluargaku, lalu Ayah beserta adik-adikku turut memuji dan berkata bahwa aku memiliki bakat bernyanyi. Bak berlian yang tersembunyi di dalam tong sampah, begitu kata mereka. Tapi, aku tak pernah menganggap pujian itu dengan serius. Aku pun tak pernah menganggap bahwa bernyanyi adalah bakatku—semua orang kan bisa bernyanyi, tergantung bagaimana cara mereka mengeluarkan suara.
Jadi, bila aku mengaku bahwa aku tak punya bakat, itu berarti aku tak punya hobi. Tapi nyatanya, sampai sekarang memang aku tak tahu hobiku apa.
Bila menyangkut tentang menantang hidup dengan menyelami sesuatu yang sama sekali tak kutahu… Kupikir dengan keberanianku pergi ke Seoul.[]


 rizukiaaaa
rizukiaaaa

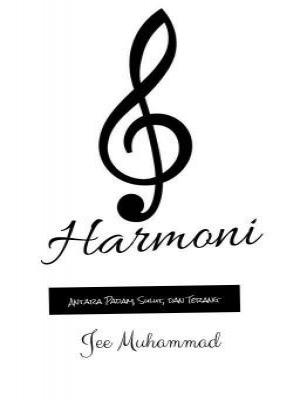








i love rain too
Comment on chapter [2]