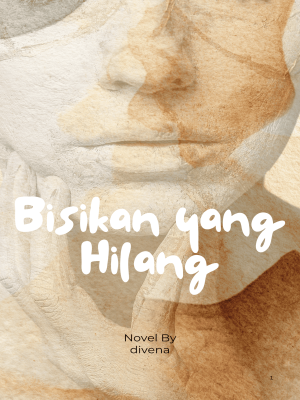Hari ini benar-benar melelahkan.
Sejak program full days ditetapkan, setiap orang di sekolah jadi sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tentu saja yang kusebut sebagai urusan adalah kegiatan belajar yang tiada habisnya seperti robot. Bangun pagi-pagi buta untuk belajar, sekolah dari pagi sampai sore untuk belajar, dan pulang sekolah mengikuti bimbel sampai malam untuk belajar. Monoton.
Lain halnya dengan diriku. Selain memang karena tidak terlalu suka dengan kegiatan monoton itu, hidup yang kumiliki memang benar-benar sebuah tuntutan. Menyedihkan, bukan? Aku hidup hanya untuk ditindas.
Tapi aku tidak pernah membiarkan diriku untuk terlalu tertindas. Untung saja setiap ada orang tertindas, di situ pula masih ada orang-orang yang peduli. Kalau semua orang melihatku seolah aku ini gembel miskin yang harus ditindas, mereka tentu tidak akan membiarkan rahang mereka jatuh mengetahui seberapa besar uang yang mendiang orang tuaku titipkan kepada sahabat karib mereka yang paling terpercaya.
Sampai waktunya belum tepat, aku masih harus menderita. Kira-kira seperti itu.
“Ra, ambil sapu!” teriakan Kak Betha membuyarkan lamunanku. Aku segera berlari kearahnya setelah sebelumnya mengambil sapu dari ruang belakang.
Inilah aku. Seorang freelance kedai makanan kecil. Mungkin memang ukurannya terlalu kecil untuk sebuah kedai biasa. Tapi jangan tanya setiap harinya kami selalu kewalahan dengan pelanggan di kedai, maupun di luar kedai yang memesan makanan secara online.
Om Anwar memang sangat baik. Memang perbuatan yang baik menghasilkan buah yang baik juga. Mungkin itu sebabnya ia sangat dihargai banyak orang dan kedainya laris manis. Ia bahkan mengizinkan anak SMA yang belum punya ijazah sepertiku untuk bekerja di kedainya. Ingatkan aku untuk membayar jasanya setelah aku sukses nanti.
Kedai INDAH mempekerjakan sebanyak sepuluh orang karyawan. Lima karyawan bekerja dari pagi sampai sore, dan sisanya bekerja dari sore sampai malam. Aku, Kak Betha, Bimo, Kak Galang, serta Kak Fudy kebagian jadwal kerja jam sore sampai malam. Mungkin karena hanya kami berlima pegawainya yang terlalu sibuk dengan urusan sekolah, makanya Om Anwar sengaja menempatkan kami di jam jam demikian.
Hari ini Om Anwar sedang ada kunjungan ke luar kota. Aku tidak tahu urusan apa—dan tidak mau tahu. Tapi yang jelas akhir-akhir ini beliau memang kelihatan lebih sibuk dari biasanya. Kata Kak Dilly sih urusan bisnis.
Oh iya, sekedar informasi, Kak Dilly itu anak sulung dari Om Anwar, alias, ahli waris kedai ini nantinya di masa depan.
Hari ini semua orang terlihat sibuk. Kak Dilly sedang sibuk dengan buku keuangan kedai di meja kasir. Kak Galang dan Bimo sibuk mencuci piring di dapur, beberapa kali terdengar suara gelas dan piring bergesekan dari sana. Aku dan Kak Betha sibuk membersihkan sisa-sisa kotoran di lantai kedai. Kak Fudy terpaksa absen hari ini karena ibunya sakit.
Kedai INDAH tutup pada pukul 23.00. Aku melirik jam tangan. Kurang lima menit lagi, tapi kami semua sudah bersiap berpisah di depan pintu kedai yang lampunya sudah dimatikan. Kak Dilly sudah pulang sepuluh menit yang lalu naik mobil pribadinya. Kak Betha dan Kak Galang pulang bersama karena arah rumah mereka sama. Aku dan Bimo melambai dan ikut berbalik ke arah yang berlawanan. Rumah kami memang searah, tapi Bimo hanya perlu menemaniku sekitar dua ratus langkah kaki kemudian berbelok untuk sampai di rumahnya.
Cowok gendut itu melambai dan berbelok ke arah kanan setelah menemaniku berbincang selama beberapa menit. Aku membalasnya sambil tersenyum. Melihat sosoknya sudah menghilang ditelan kegelapan, aku mendesah dan kembali menatap ke depan, ingin melangkah.
Baru saja hendak melangkah, mataku menangkap sesuatu. Aku menyipitkan mata untuk memperjelas pandangan. Semoga aku melihat hal-hal yang normal. Namun, sepertinya doaku tidak terkabul karena aku langsung terbelalak.
Aku benar-benar melihat sesuatu. Berdiri sekitar lima meter di depanku.
Haruskah kujelaskan detailnya? Baiklah. Kedua matanya putih, tanpa iris. Putihnya sepucat tembok di sekolah. Dan cara berjalannya sempoyongan.
Tahu mana yang lebih mengerikan lagi daripada itu? Bukan, bukan cara jalannya yang sempoyongan. Tapi saat dia melihatku.
Dia tahu aku bisa melihatnya.
Dia hantu.
Tiba-tiba saja ketakutan menggerayaiku. Tanganku mulai berkeringat dingin dan jantungku mulai berdebar dengan irama tak tentu. Apa aku sudah pernah bilang kalau aku tidak takut hantu? Bisa iya, bisa tidak.
Aku memang tidak takut hantu, selama mereka tidak mencari masalah denganku. Sekarang kutanya, jika kamu sedang berdiri sendirian dan dihadapkan pada dua orang, mana yang paling kamu takuti. Orang yang cuek, atau orang dengan muka mesum yang berniat menyerang dan menghabisimu?
Orang bodoh akan menjawab dengan jawaban pertama. Dan kuingatkan, kalian tidak bodoh.
Dan sudah kuputuskan, aku takut sekarang.
Karena dia tengah tersenyum menatapku.
***
Aku memutar pandangan ke sekeliling dengan hati-hati, berharap ada orang lewat. Setiap pergerakan yang kulakukan—bahkan hanya untuk memutar mata—aku melakukannya dengan sangat hati-hati. Aku gugup dan takut setengah mati.
Seketika nyaliku ciut dan dadaku serasa mencelos saat melihatnya mulai berjalan mendekatiku. Kalau aku tidak memaksa, mungkin aku sudah ambruk karena tidak kuat berdiri. Jika orang lain yang ada di posisiku saat ini, aku yakin dia sudah pingsan karena tidak tahan.
Dia terus mendekat. Dan aku malah membatu seperti patung monumen nasional. Sekitar tiga meter dari tempatku berdiri, aku bisa melihat sosoknya dengan jelas yang terkena sinar lampu jalanan. Dan seketika itu juga aku menangis.
Saat itu selain kabur, ada satu hal lain yang kupikirkan dalam otakku. Mungkin aku memang tidak waras ketika menghadapi kenyataan bahwa apa yang akan kulakukan nantinya hanyalah sia-sia. Tapi entah datang darimana, keyakinan akan dorongan ketakutan itu membuat tanganku terangkat dan mulai beraksi.
Aku menampari kedua pipiku secara bergantian.
Aku tahu ini tidak akan bekerja, aku tahu! Tapi otakku memang sudah tak bisa diajak berkompromi lagi. Mungkin karena batinku juga terlalu takut. Aku terus melakukannya. Berulang kali. Sampai terasa memanas. Idiot.
Bukannya menghilang seperti asap mengepul, tapi dia malah semakin mendekat. Seketika aku menyesal. Seharusnya aku berlari saja sejak tadi. Rupanya aku telah membuang-buang waktu. Tiba-tiba saja aku berharap petir datang menyambar mataku hingga aku buta. Sungguh ini semua terasa menyiksa.
Kalau aku tidak benar-benar bodoh, aku sudah membalikkan badan dan berlari sekencang yang aku bisa. Dear Pak Yanuar, guru olahragaku yang paling tampan dengan kumis menggelegar, maafkan aku yang selalu beralasan haid saat engkau menyuruh kami untuk praktek mengelilingi lapangan lima kali.
Aku membalikkan badan dan mulai berlari. Aku terus memacu kakiku secepat yang aku bisa. Seluruh tenaga kukerahkan untuk berlari ke arah jalan yang akan membawaku kembali ke kedai. Dalam lariku yang tak kenal lelah, aku menyempatkan diri untuk menengok ke belakang sekedar memeriksa.
Damn, dia mengejarku!
Oh Tuhan tolong aku. Aku tidak tahu harus pergi ke mana lagi. Seharusnya aku sudah sampai di rumah dan terlelap dengan nyenyak hari ini. Tapi gara-gara makhluk sialan yang menakutkan itu... argh, sudahlah berlari saja!
Aku kembali menengok dan seketika melotot. Sial, jaraknya semakin dekat.
Sedikit lagi sampai di kedai. Sebelum napasku habis. Aku terengah-engah.
Begitu sampai di depan pintu kedai, aku merogoh saku celana dalam-dalam, berharap menemukan kunci cadangan, sampai melupakan fakta bahwa sejak pertama masuk kerjapun Om Anwar sekalinya tidak pernah memberiku kunci cadangan.
Sedang paniknya merogoh saku, ponselku sampai ikut terjatuh ke tanah. Aku menunduk dengan secepat kilat untuk memungutnya. Dan tepat saat itu juga aku melihat penampakan kaki berbalutkan sepatu vans berdiri sekitar tiga kaki di hadapanku.
Ada orang!
Aku mendongak dan melihat seorang cowok memakai kaus putih polos dan jeans, menatapku dengan dahi berkerut, seakan menilaiku. Dia berdiri satu meter di hadapanku. Astaga, apakah sedari tadi aku panik, aku baru menyadarinya?
Ini saatnya meminta bantuan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini.
“Kak!”
Aku tak tahu bagaimana mendiskripsikannya, tapi dia terlihat terkejut luar biasa. Entah mendengar pekikanku yang terlalu nyaring atau apa. Cowok itu menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu menunjuk dirinya sendiri.
Aku mengangguk kelewat kencang, “Iya, kamu kak! Tolong!”
Dia mengedip tak percaya.
Aku mendekatinya dan meraih tangannya dengan paksa. Ia tersentak. “Kak, tolongin aku, pelase!”
“H-hah?”
“Tampar aku sekarang juga!” pintaku langsung.
“A-apa?”
“Ayo kak buruan!” aku mendesaknya.
“T-tampar?”
“Iya, tolong tampar aku sekarang juga.”
“T-tapi—“
“Cepetan kak!”
“K-kenapa kamu—“
“KAK!”
“Oke.”
PLAK!
Aw.
Pertama terasa panas, kemudian perih, lalu di ujung lidah terasa getir. Sepertinya bibirku berdarah. Aku mengusap ujungnya pelan. Nah kan benar berdarah.
Kelewatan.
Aku menghela napas, lalu melempar tatapan tajam pada cowok itu. “Makasih sebelumnya, tapi setidaknya kalau nampar yang lebih manusiawi dikit, kek.”
Tanpa perlu mendengar sepatah katapun darinya, aku memilih membalikkan badan lalu pergi.
Sambil berjalan terseret-seret karena kelelahan, aku mengelus pipiku yang sudah pasti semerah apel. Manalagi perih. Tahu begini mending pingsan saja. Tidak hantu tidak orang sama-sama menakutkan. Oh tambahan, kejam.
“Kamu bisa lihat aku?”
Aku terkejut mendengar suara itu. Ternyata cowok tadi mengikutiku. Kini berjalan di sampingku. Apa arah rumahnya dan rumahku sama? Lagipula buat apa dia berkeliaran di jam segini? Dari tampangnya yang—ehm ganteng terawat sepertinya mustahil dia anak freelance sepertiku.
“Makasih tamparannya, tapi jangan ngajak aku ngomong,” jawabku ketus. Aku tidak boleh terhipnotis kegantengannya. Sadar Ra. Fokus.
“Sakit ya? Maaf, kamu nyuruhnya tiba-tiba, sih.”
Meski kesal, tapi kutelan kekesalan itu bulat-bulat. “Kalau Kakak mikir aku gila nggak pa-pa, kok. Lagian cewek normal mana yang malem-malem maksa cowok buat nampar pipinya.”
Dia tersenyum geli. Dih, baru saja kenal sudah sok akrab. Kalau yang tersenyum Ando mungkin aku bisa maklum, tapi kalau Kakak ini... yah, untung ganteng, jadi juga dimaklumin.
“Aku kaget sih. Tiba-tiba kamu panggil terus suruh nampar,” katanya lagi kemudian tertawa kecil.
Aku mendengus menanggapinya.
“Tapi meski sakit seenggaknya kamu harus berterima kasih secara ikhlas. Gara-gara kutampar om-omnya hilang beneran, ‘kan?”
Jantungku mencelos. Mungkin sudah menggelinding ke aspal yang dingin. Langkahku terhenti. Aku menurunkan tangan dari pipi, kemudian menatap cowok di sampingku ini pelan-pelan. Slow motion. Tunggu... kenapa dia...
“Om-om?” aku memastikan.
Dia mengangguk tanpa ragu. “Om-om yang larinya sempoyongan di belakangmu tadi,” jawabnya, “Langsung menghilang setelah kamu kutampar. Wah, kayaknya aku jago bela diri juga.”
Tunggu. Kalau dia bisa melihat om-om tadi, itu artinya...
“Kakak bukan manusia?” aku membekap bibir, tak bisa menahan keterkejutanku. “Kakak hantu?!”
Dia tak kalah terkejut. “Aku kira kamu sudah tahu.”
Tahu tidak, seharian ini terasa melelahkan. Pulang sore langsung lanjut bekerja. Pulang larut malam dan bertemu hantu pemabuk yang menakutkan. Aku pikir kelelahanku akan terbayar setelah tamparan menyakitkan itu. Tapi ternyata, tidak semudah itu.
Kalau orang yang menamparku tadi adalah hantu, lalu siapa sekarang yang akan menamparku supaya cowok ini menghilang?


 brnike__
brnike__