BAB 8
MENINGGALKAN JAWA
Sukma Pujangga (J.E.Tatengkeng)
O, lepaskan daku dari kurungan
Biarkan daku terbang melayang
Melampaui gunung, nyebrang harungan
Mencari cinta, kasih dan sayang.
Aku tak ingin dipagari rupa
Ku suka terbang tinggi ke atas,
Meninjau hidup aneka puspa,
Dalam 'alam yang tak berbatas...
Matahari bersinar cerah hari ini, sebelum pukul 10.00 WIB aku harus sudah sampai di pelabuhan untuk berangkat ke Borneo. Tas yang hendak kubawa ke kapal sudah di tangan Warsonoe, jadi tak akan ada keluarga yang mencurigai aku akan pergi jauh. Berat rasanya memang memutuskan meninggalkan keluarga tercinta, namun saat ini aku tidak punya banyak pilihan. Aku akan pamit pergi ke pasar seperti biasa, bapak dan ibu sudah sibuk di pabrik tahu sejak pagi-pagi buta, jadi aku hanya cukup pamit pada Sinar dan Mulyati. Warsonoe sudah berjanji menungguku di depan kampung untuk mengantarku ke pelabuhan.
“Mba, aku pesan ongol-ongol ya.” Rengek Mulyati seperti biasa, setiap aku hendak ke pasar dia selalu menitip jajanan.
“Aku nitip rengginang saja deh, Mba.” Ujar Sinar. Aku hanya mengangguk pelan. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa aku akan pergi ke luar pulau, bukan pergi ke pasar.
“Tumben, Mba ke pasar dandan cantik banget.” Celetuk Mulyati sambil memperhatikanku lekat dari atas sampai bawah. Aku terdiam sejenak.
Dia menyadari pakaian yang kugunakan cukup rapi dibanding hari-hari biasa aku ke pasar. Kali ini aku memilih menggunakan baju terusan berwarna kuning muda dengan aksen renda di bagian bawahnya, aku juga sedikit memakai gincu merah dan bedak tabur milik ibu. Rambutku kubiarkan tergerai padahal pada hari biasa aku ke pasar hanya memakai baju terusan berwarna coklat yang kusam karena terus-terusan dipakai dan tidak pernah pakai gincu atau bedak tabur. Aku sedikit kaget dengan celetukan Mulyati.
“Iya, tumben banget Mba, kaya mau kemana aja. Mana pake sepatu rapi banget.” Tukas Sinar menambahkan. Jantungku berdegup kencang, celaka, mereka menyadari perubahanku tapi kalau aku berpakaian seperti biasa akan memakan waktu untuk ganti baju dengan pakaian rapi. Jadi kuputuskan langsung saja berpakaian seperti ini.
“Memangnya kalau ke pasar, Mba gak boleh dandan?” tanyaku sambil berpura-pura tertawa. Sial bibirku terasa kaku, ternyata begini ya rasanya berbohong. Bikin gila.
“Hehehehehehe...” Sinar dan Mulyati hanya tertawa mendengar responku. Untuk terakhir kalinya aku memandang wajah Sinar, wajah Mulyati dengan lekat. Aku tidak ingin melupakan wajah mereka jadi kupuasi memandang wajah mereka sebelum aku pergi. Ah, kulihat Sinar masih ada belek di matanya, sedangkan Mulyati rambutnya yang sedikit keriting menjadi megar seperti singa di pagi hari. Pemandangan biasa ini tidak akan kutemui lagi selepasnya aku pergi ke Borneo. Biasanya langsung kumarahi mereka berdua bila kudapati wajah mereka masih ada kotoran, namun untuk hari ini pengecualian bagi mereka, aku sedang berbaik hati lebih tepatnya tak sampai hati.
Aku mengedarkan pandangan kedua mataku untuk menelusuri semua sudut rumah, aku khawatir aku akan kangen rumahku, maka aku cermat mengingat segala sudut rumah saat ini, ruang keluarga yang hanya ada tikar tempat Sinar dan Mulyati selonjoran saat ini sambil cekikikan entah apa yang mereka gumamkan, kemudian di bagian paling pojok ada dapur kotor yang berantakan, deretan kamarku, kamar Sinar dan Mulyati, dan kamar ibu bapak paling depan, lalu mataku tertuju pada bale-bale depan rumah yang dihiasi dipan bambu. Aku yang selalu biasa menghabiskan waktu di bale-bale ini. selepas kupergi bale-bale ini akan kehilangan pemiliknya.
Sampai jumpa Sinar, sampai jumpa Mulyati, sampai jumpa bapak, ibu, sampai jumpa kamarku, sampai jumpa semuanya. Aku menyampaikan salam perpisahan pada mereka dalam hatiku. Aku segera melangkahkan kakiku ke luar dari rumah sebelum mereka berpikir yang lain. Kuakui langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya. Aku pun tak bisa berjalan dengan tegap dan sigap, aku hanya menundukkan wajahku. Rasanya berat.
“Sudah siap?” tanya Warsonoe saat aku sudah sampai di depan kampung. Dilihatnya wajahku muram. Dia tidak mencoba menghibur, mungkin dia juga bingung harus menghibur dengan cara apa. Aku membonceng di sepeda ontelnya menuju pelabuhan. Kami berdua tidak banyak bicara. Entah mengapa lidahku terasa kelu, aku enggan mengucapkan sepatah katapun.
Beberapa puluh menit kemudian kami sudah tiba di pelabuhan. Warsono membawaku masuk mencari kapal yang akan menuju ke Borneo. Lalu lalang manusia yang cukup banyak membuatku sedikit tak nyaman. Dari atas kapal laut yang besar Zus Sulastri melambaikan tangannya padaku. Kulihat dia sudah berada di atas kapal yang di dalamnya terdapat banyak manusia, ada tentara Jepang dan juga pribumi sepertiku. Aku datang setengah jam lebih awal ternyata sudah seramai ini kapal yang hendak mengangkutku.
“Belum terlambat.” Ujar Warsonoe sambil membantuku membawakan tasku yang entah dia titipkan di mana sebelumnya.
“Hah?” aku tersentak dari lamunanku.
“Belum terlambat untuk berubah pikiran.” Ucapnya.
“Kalau aku tidak ke Borneo, aku akan menjadi istri ketiga Sutedjo.” Jawabku.
“Kalau begitu, angkatlah dagumu. Perlihatkan pada dunia bahwa kau wanita yang kuat.” Dia menepuk bahuku lembut. Aku menarik nafasku panjang dan menghembuskannya perlahan. Bulir air mataku menetes di pipi. Berat rasanya. Warsonoe tanpa komando segera mendekapku erat dalam pelukannya. Aku menangis sesegukan, ini kali kedua aku menangis dalam pelukannya. Entah mengapa aku merasa kedamaian dari dirinya yang ditularkan padaku.
“Berat rasanya meninggalkan orang tua dan adikku diam-diam seperti ini.” ujarku sambil menangis. Seolah mengetahui apa yang kurasakan, Warsonoe memelukku lebih erat, tangannya membelai rambutku, lembut.
“Bergembiralah, bukankah kau akan bertemu Mas Hartowardojo kelak sesampainya di sana?” Warsonoe mencoba menghiburku. Sedikit membantuku melepaskan beban di pundak. Aku tak bergeming cukup lama untuk menenangkan gejolak di dadaku, hingga akhirnya aku mengucapkan perpisahan padanya,
“Terima kasih, Warsonoe. Sampai jumpa.” Aku melepas pelukannya tanpa ragu. Aku, Ningsih. Harus menjadi gadis kuat. Warsonoe tersenyum sambil melepas kepergianku ke tanah yang belum pernah kuinjak sebelumnya.
Zus Sulastri menyambutku dengan hangat sesampainya aku di atas kapal, ini pertama kalinya aku naik kapal laut. Ternyata sangat luas walaupun tidak seperti kapal laut besar seperti bayanganku namun kupikir ini cukup canggih pada zaman ini, kudengar kapal ini milik Jepang yang khusus digunakan mengangkut bala tentaranya dan juga pribumi yang hendak ke Borneo. Jepang berkali-kali jauh lebih maju dari bangsa kami bisa dilihat dari kapal laut yang terlihat kokoh ini. Aku mencari Warsonoe dari atas kapal, dia masih menunggu di bawah sambil melambaikan tangannya padaku. Aku tidak bisa melihatnya jelas dari atas sini, namun bisa kupastikan dia sedikit menyunggingkan senyum di bibirnya untuk memberiku kekuatan mungkin.
Dari jauh Warsonoe terlihat tetap tinggi menjulang dengan badannya yang tegap dan rambutnya yang hitam berkelebatan terkena tiupan angin laut. Dia melambaikan tangan padaku seolah mengatakan sampai jumpa. Kapal laut meninggalkan dermaga pelabuhan perlahan-lahan hingga akhirnya aku tidak lagi dapat melihat Warsonoe.
Aku memperhatikan sekeliling kapal ditemani Zus Sulastri, dia mendampingiku sebentar agar aku tidak begitu canggung di dalam kapal laut, sekitar ratusan pemuda dan pemudi pribumi, bisa kubilang mereka cantik dan rupawan, sedangkan laki-lakinya kebanyakan berbadan tegap. Mungkin untuk bekerja di grup sandiwara memiliki postur tubuh yang baik menjadi sebuah keharusan. Kurasa banyak juga orang yang direkrut Jepang untuk bekerja di Borneo. Kuperhatikan puluhan tentara Jepang berjalan mondar-mandir mengawasi keadaan. Aku merasa ini agak aneh, mereka seolah mengawasi kami semua yang berada di kapal tapi mungkin hanya perasaanku saja.
“Apa yang kau katakan ke orangtuamu agar bisa pergi ke Borneo?” tanya Zus Sulastri padaku sambil mulutnya mengunyah rempeyek kacang yang sepertinya sudah dia persiapkan dari rumah, tak lupa Zus Sulastri menawarkan rempeyek kacang itu padaku, aku menolaknya karena takut mual.
“Aku kabur.”
“Hah? Maksudmu?”
“Ya, aku tidak mengatakan kepergianku pada mereka.”
“Kau sinting!”
“Memang kurasa aku sudah sinting.”
“Yasudah, tidak memberitahu kepergianmu pada mereka justru lebih bagus kan.” Ujar Zus Sulastri.
“Nanti kau akan tidur di sini.” Zus Sulastri menunjuk kelas ekonomi padaku yang beberapa bagiannya sudah terisi orang lain yang sedang tertidur pulas atau sekedar leyeh-leyeh.
Suasana di atas kapal laut cukup ramai, Zus Sulastri menjelaskan padaku bahwa penumpang kapal ini sekitar lebih dari 500 orang yang dibagi menjadi 3 kelas di kapal laut ini, yaitu 1A, IIB, dan ekonomi. 80% dari penumpang kapal yang merupakan pribumi disediakan tempat tidur di kelas ekonomi. Kelas 1A dan IIB khusus untuk tentara Jepang dan beberapa pribumi pilihan, yang kudengar fasilitas di kelas 1A dan IIB lebih baik. Di kapal ini kami akan mendapat jatah makan sebanyak 2 kali, yaitu makan pagi dan makan malam. Kudengar darinya makanannya adalah singkong rebus, ubi rebus kalau beruntung bisa mendapat nasi dan telur ayam rebus. Tidak masalah bagiku, toh aku naik kapal ini pun gratis.
Menurutnya perjalanan ke Borneo memakan waktu berhari-hari sehingga jangan sampai jatuh sakit karena akan cukup merepotkan, Zus Sulastri membocorkan padaku bahwa di kapal kelas IIA dan IB terdiri dari kamar yang bisa ditempati 2 sampai 4 orang berbeda dengan kelas ekonomi yang semua tumpah ruah di dalamnya. Setelah mengajakku berkeliling, Zus Sulastri meminta izin untuk menemui rekan lainnya di kapal.
Aku memilih duduk di bangku kosong yang ada di dekat geladak kapal sambil menikmati sepoaian angin laut selepas kepergian Zus Sulastri. Tak terasa kapal sudah melaju cukup lama, matahari pun sudah berada di tengah ubun-ubun. Entah mengapa lama-kelamaan aku merasa mual dan tidak enak badan, kurasa ombak besar yang memberikan sedikit gerakan pada kapal mempengaruh kesehatanku.
“Mabuk laut?” tanya seorang gadis berambut bergelombang yang kutaksir sebaya denganku sambil duduk di bangku kosong sebelah aku duduk.
“Ya. Ini pertama kalinya aku naik kapal laut.” Jawabku sambil memijat keningku sedikit. Entah mengapa aku merasa sekujur tubuhku begitu dingin ditambah kepalaku pening dan perutku mual tak karuan. Jadi ini yang dinamakan mabuk laut, baru pertama kali aku merasakan mabuk laut sangat tidak enak. Lebih enak mabuk durian sebab aku pasti kenyang.
“Pakai ini.” ia menyodorkan minyak angin padaku.
“Wah, terima kasih.” Aku menerimanya tanpa basa-basi. Aku sungguh lupa membawa obat-obatan seperti ini. Untunglah ada orang yang berbaik hati padaku.
“Sama-sama, aku Mayang.”
“Aku Ningsih.” Aku meluburkan minyak angin ke keningku yang terasa sakit dan ke beberapa bagian tubuh lainnya.
“Bersama siapa ke sini?” tanyanya ramah.
“Aku sendirian, Mayang dengan siapa?”
“Hebat sekali, aku bersama adikku, Sekar. Itu dia sedang duduk di sebelah sana.” Ujarnya sambil menunjuk gadis yang tidak begitu jauh usianya dengannya. Gadis yang ditunjuk itu cukup manis dengan rambut yang dikepang dua. Gadis itu menoleh ketika ditunjuk, seketika dia menghampiri kami sambil berlari-lari kecil.
“Ada apa, Mba?”
“Kenalkan Ningsih ini adikku Sekar.”
“Sekar.”
“Ningsih.”
Tak terasa kami bertiga sudah menjadi cukup dekat dalam beberapa menit saja. Baru kutahu Mayang dan Sekar ke Borneo untuk bekerja karena kedua orang tuanya sedang kesulitan ekonomi, maka demi meringankan beban ekonomi mereka adik kakak ini memutuskan untuk merantau ke Borneo agar mendapat pekerjaan dengan gaji yang besar. Aku tidak menceritakan pada mereka betapa rumitnya hidupku saat ini, toh rumitnya hidupku ternyata tidak serumit perjalanan hidup mereka berdua.
Mayang menceritakan padaku bahwa dirinya dan Sekar tidak sempat lulus dari sekolah dasar di Taman Siswa karena keluarganya tidak memiliki uang maka mereka dari kecil membantu orangtuanya untuk berjualan di pasar. Meski begitu mereka berdua tetap terlihat sebagai gadis yang cerdik dan cekatan. Mayang terlihat sebagai sesosok kakak perempuan yang mandiri, tegar, kuat dan bisa diandalkan oleh adiknya Sekar.
Mayang berkulit sawo matang, dengan rambut ikal bergelombang sebahu, bibirnya tebal berwarna coklat, matanya hitam bulat penuh keingintahuan besar akan segala hal, tawanya renyah seperti rengginang yang biasa kumakan di rumah, kakinya panjang dan jenjang, dia gadis gesit dan cekatan. Sedangkan adiknya, Sekar terlihat lebih feminim dari Mayang, rambutnya dikepang dua, kulitnya agak sedikit lebih cerah dari milik Mayang, bibirnya tebal dan juga berwarna coklat. Melihat Sekar seolah teringat bunga matahari, berdiri dengan percaya diri, penuh semangat dan menggelora. Aku melihat keberanian, ketegaran di dua bola mata Sekar yang hitam tajam karena kehidupan banyak menerpanya sedari muda, matanya memancarkan keberanian.
Melihat sosok Sekar aku jadi teringat kedua adikku Sinar dan Mulyati. Kira-kira sekarang mereka sudah sadar belum ya kalau aku pergi dari rumah bukan untuk belanja ke pasar, melainkan pergi ke Borneo. Semoga Sinar dan Mulyati tidak menangis meraung-raung nantinya setelah mengetahui bahwa aku pergi ke Borneo.
Kurasa mabuk lautku sedikit terobati dengan baluran minyak angin yang diberikan Mayang tadi. Kami bertiga masih duduk di dekat geladak kapal, Sekar berteriak histeris saat dilihatnya sekawanan lumba-lumba melompat dengan lincah di samping geladak kapal tempat kami duduk. Aku dan Mayang menghampiri Sekar, benar saja yang dikatakan bocah itu, sekelompok lumba-lumba seolah-olah berkejaran dengan kapal yang sedang kami naiki, sungguh pemandangan yang pertama kali aku lihat. Ditambah buih-buih air laut yang terlihat di sekitaran kapal sangat menyenangkan untuk dilihat.
Langit biru yang indah, gumpalan awan putih bagaikan kapas, ditambah sejauh mata memandang hanya terlihat laut dan laut, seolah bumi tidak memiliki ujungnya. Angin laut yang membelai wajahku, benar-benar pengalaman menyenangkan sekali. Aku tidak pernah sebelumnya pergi naik kapal laut karena berkaitan dengan keadaan ekonomi keluargaku, juga berkaitan dengan mau pergi kemana? dan mengunjungi siapa naik kapal laut? Toh, seluruh keluargaku berada di Jawa. Demi Hartowardojo, lautan seluas ini aku lewati, demi bertemu Hartowardojo pulau Jawa kutinggali dan kini aku menuju pulau Borneo. Jika para penyair mengatakan cinta itu gila, memang benar gila, cinta itu buta, memang nyatanya cinta bisa membuat orang menjadi buta.
Langit biru membentang luas perlahan menjadi jingga senja dan akhirnya yang terlihat adalah gelap. Laut menjadi gelap, langit menjadi gelap. Kapal laut besar ini seolah menjadi setitik debu kecil yang melayang di sebuah tempat jauh entah berantah. Bahkan aku tidak bisa membedakan mana gelap langit dan mana gelap laut, hampir keduanya seolah menyatu dalam satu kata, hitam pekat. Aku sadar bahwa aku berada di laut karena suara deburan ombak yang terus menerus berdatangan. Angin dingin laut tak usah ditanya, membuatku membungkus diri menggunakan jaket hangat.
Sekar dan Mayang sedang mengantri mengambil makan malam, yaitu ubi dan singkong rebus. Aku segera menghampiri antrian makan malam yang cukup ramai namun tetap terkendali karena tentara Jepang berjaga di sekitar kami setiap saat. Aku mendapat antrian paling belakang saat ini karena aku terlalu lama duduk di geladak kapal memandang langit malam tak kusadari sudah masuk jam antrian makan malam, kulihat Sekar dan Mayang sudah sampai di tengah antrian. Sesekali keduanya menoleh padaku dan tersenyum simpul.
“BRUKKKK!!!” Tiba-tiba seorang gadis menubruk bahuku dengan keras dari arah belakang, agaknya dia terlalu cepat berjalan sehingga tidak memperhatikan langkahnya, dapat kurasakan bahuku sedikit sakit karenanya, beruntung aku tidak terdorong jatuh ke arah depan menubruk orang lain di depanku.
“Ma...maaf...” ujarnya lirih, gadis itu terlihat sedikit ketakutan.
“Tidak apa-apa. Apa kau baik-baik saja?” tanyaku cemas.
“Ya.” Jawabnya singkat sambil melirik ke arah kiri dan kanannya. Memastikan sesuatu.
“Aku Ningsih, kau siapa?” tanyaku penasaran siapa gerangan gadis yang menubruk diriku ini, mungkin kami bisa berteman seperti aku dan Mayang serta Sekar.
“Akuu... Kurnia.” Jawabnya.
“Kau sendirian?”
“Ya.” Dia mengangguk.
“Sama. Kita bisa menjadi teman.”
“Baiklah, aku setuju. Aku tidak punya teman sama sekali di sini dan aku juga tidak kenal siapa-siapa.” tukasnya, aku hanya membalasnya dengan senyuman.
“Mengapa kau tadi berjalan terburu-buru dan terlihat sedikit ketakutan?”
“Hmm... aku merasa ada yang aneh saja dengan kapal ini, terutama dengan mereka.” Jelas Kurnia sambil menunjuk gerombolan tentara Jepang. Suaranya pun dibuat sangat pelan hingga bisa dipastikan hanya aku saja yang dapat mendengarnya.
“Maksudmu?”
“Mata mereka, melihat perempuan kita, melihatku seperti mangsa.”
“Mangsa?” aku memincingkan mataku, entahlah apa yang sedang dipikirkan gadis ini, aku tidak begitu mengerti. Mengapa menurutnya tentara Jepang melihat kami seperti mangsa.
“Aku tidak yakin tentang hal ini. Namun... ini sulit dijelaskan mengingat kedatangan kita semua dalam kapal ini untuk bekerja di Borneo.”
“Yaa... Tentu saja.” Jawabku.
Kurnia seorang gadis yang lembut, dia sedikit lebih pendek dariku dan ternyata dia seumuran denganku. Kulitnya kuning langsat, matanya agak kecil, bibirnya tipis kemerahan, rambutnya hitam panjang dan lurus sepunggung, dia menguncir rambutnya dengan pita berwarna kuning. Bisa kutebak dalam sekali lihat, Kurnia adalah gadis yang selalu berhati-hati dalam berbagai macam hal, insting dan intuisinya kuat terhadap lingkungan.
Dia peka akan keadaan sekitar, jiwa sosialnya kubilang cukup tinggi. Kurnia bercerita padaku, ia sempat mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama di Taman Siswa, kemudian setelah lulus dia membantu orang tuanya membuat tahu di rumahnya. Sejenis pabrik tahu kecil dan keluarganya menjual ke rumah, pasar, atau ke pelanggan tetapnya. Kurnia memutuskan untuk ke Borneo untuk mengadu nasibnya, sama seperti kebanyakan alasan dari kami. Aku mengenalkan teman baruku pada Mayang dan Sekar setelah makan malam. Kami berempat tak lama menjadi begitu akrab di dalam kapal laut.
Malamnya kami berempat, yakni aku, Sekar, Mayang dan Kurnia memilih untuk tidur di dalam kapal di tempat yang sama. Kami berempat merasa semakin dekat dengan melakukan kegiatan di dalam kapal secara bersama-sama. Kurasa aku bisa menemukan keluarga baru di sini, yaitu bersama mereka. Sebenarnya tidak hanya mengenal Sekar, Mayang dan Kurnia aku pun sudah berkenalan dengan penghuni kapal yang lain, seperti Sri, Tyas, Tya, dan banyak lainnya. Namun kurasa aku paling cocok dengan ketiga rekanku tadi. Ada pepatah mengatakan, ketika kita sudah menemukan teman maka jangan sampai dilepas.
Beberapa hari di tengah lautan lepas aku mulai beradaptasi dengan baik dengan suasana kapal laut, ombaknya yang membuat mabuk, dan lainnya. Kapal beberapa kali mendarat di pelabuhan yang aku tidak tahu pelabuhan apa sebab tentara Jepang selalu melarang kami untuk turun setiap kapal laut singgah di pelabuhan untuk sekedar mengisi bahan bakar atau mengistirahatkan mesin kapal.
***


 dede_pratiwi
dede_pratiwi






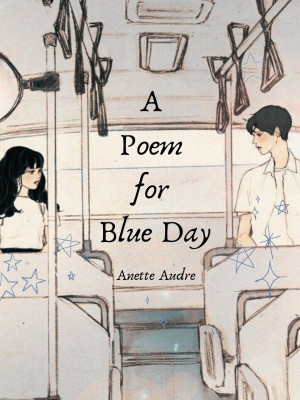



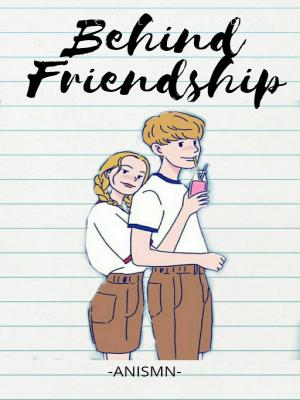

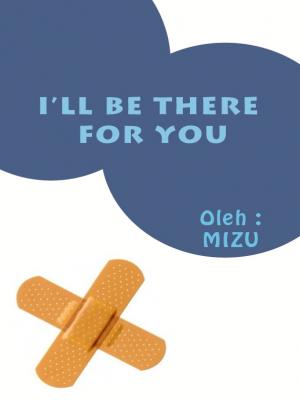
mapkhan saya bunda yg baru baca.. padahal cucok meong bgt
Comment on chapter BAB 2 Dirimu