BAB 6
AJAKAN
“Ningsih, bapak dan ibu akan segera tetapkan tanggal untuk kau menikah dengan Sutedjo! Dua atau tiga bulan lagi kira-kira.” ujar bapakku. Telingaku terasa panas. Bukan pertama kalinya bapak mengatakan demikian, namun yang terjadi kami selalu berdebat hebat setiap kali bapak berusaha menjadikan aku istri sah Sutedjo.
“Bahkan dia sudah mempunyai dua orang istri sah!!” jawabku dengan nada tinggi.
“Apa sulitnya menjadi istri ketiga? Dia bahkan menawarimu untuk menjadi satu-satunya jika kau bersedia, dia bisa menceraikan kedua istrinya.”
“Aku bukan jalang merebut suami orang!”
“Aku tahu anakku bukan jalang, maka jadilah istrinya! Entah itu kau menjadi satu-satunya atau yang ketiga tak menjadi persoalan.”
“Ningsih, Sutedjo orang baik.” Ibu mencoba menenangkan keadaan.
“Bu, kalau dia baik, lantas mengapa dia rela meninggalkan dua istrinya untuk perempuan lain?”
“CUKUUUUPPP!!! Setiap kali berbicara denganmu entah mengapa darahku terasa mendidih. Tidak cukupkah kami membesarkanmu dengan baik dari bayi merah? Sudah saatnya kau setidaknya menyenangkan kami dengan menuruti permintaan bapakmu ini!” aku tidak sanggup lagi berdebat dengan orang tuaku sendiri. Mereka benar-benar mengharapkan aku menikah dengan Sutedjo. Tidak ada yang buruk tentangnya, sudah kubilang berkali-kali dia bukan Datuk Maringgih dan tidak seburuk itu, hanya saja Sutedjo sudah memiliki dua orang istri sah dan jelas hatiku masih milik Hartowardojo.
Tak mau berdebat panjang lagi pagi itu aku beringsut menuju pasar raya membeli keperluan memasak hari ini, tidak banyak yang bisa kubeli namun singkong dan ubi menjadi incaranku hari ini untuk digodog sebagai makan siang dan makan malam. Di tengah perjalanan aku bertemu dengan Zus Sulastri, wanita paruh baya tetanggaku yang kuketahui menjadi pemain drama opera sandiwara dari kampung ke kampung. Zus Sulastri menyapaku dengan ramah seperti biasa saat kami berpapasan di jalan. Hubunganku dengan Hartowardojo sepertinya sudah menyeruak ke seluruh kampung, tak ayal Zus Sulastri sebagai ibu-ibu yang mengikuti perkembangan zaman mengetahui berita tentang itu juga.
Zus Sulastri mengatakan padaku bahwa Jepang saat ini sedang membuka lowongan kerja bagi gadis-gadis muda untuk bekerja sebagai pemain opera, penyanyi, pemain musik, penabuh gendang, seruling dan banyak lagi dengan gaji yang besar, mereka menyediakan pula pendidikan untuk orang yang berbakat secara gratis. Aku sangat tertarik mendengarnya. Terlebih saat kutahui lowongan kerja itu ada di Borneo. Jika aku bersedia ikut Zus Sulastri ke Borneo, katanya aku akan mendapatkan penginapan gratis di sana asal aku bekerja sebagai pemain opera sandiwara dengan baik. Menurutnya wajahku cantik dan oriental sangat cocok bermain peran.
“Ningsih, kalau kaubersedia, ayo ikut rombonganku ke Borneo dua minggu lagi, kau tahu tidak kalau gajinya besar sekali di sana. Kau hanya perlu menjadi anggota dari grup sandiwaraku. Biaya perjalanan ke sana pun sudah ditanggung.” Begitulah bujuk Zus Sulastri padaku. Aku menimbangnya begitu masak, itu artinya aku harus meninggalkan Jawa, meninggalkan bapak, ibu dan kedua adikku untuk pergi ke Borneo agar dapat upah yang besar dari hasil grup sandiwara. Kurasa ini adalah kesempatan emas, selain aku bisa lepas dari Sutedjo yang hendak menikahiku, aku bisa bekerja pula di sana dengan gaji yang besar mengingat saat ini di Djakarta mencari pekerjaan dengan gaji besar bukanlah suatu yang mudah, terlebih di Borneo aku bisa mencari Hartowardojo.
Aku memberanikan diri berpikir untuk menyusul Hartowardojo ke Borneo. Ekonomi keluargaku sudah lebih baik semenjak pabrik tahu selesai diperbaiki oleh Sutedjo. Aku berusaha menghindari Sutedjo baik terang-terangan maupun secara pasif namun agaknya Sutedjo tidak peduli akan penolakan bertubi-tubi dariku. Dia sangat yakin kelak aku akan menjadi istrinya. Sutedjo wajar sekali memiliki pemikiran seperti itu karena toh dia yang membantu ekonomi keluargaku menjadi lebih baik, jadi secara tidak langsung dan secara alam bawah sadar sangatlah alamiah jika dia merasa berhak memiliki diriku sebagai konsekuensinya.
Kedua orangtuaku pun ikut mengambil peran untuk segera meresmikan hubungan aku dan Sutedjo. Aku tidak ingin menjadi Siti Nurbaya karena kawin paksa. Aku hanya ingin menjadi gadis biasa yang dapat menikah dengan orang yang kucinta. Tapi masalahnya, orang yang kucintai itu tidak berada dekat denganku saat ini dan aku sudah kehilangan kabar selama satu tahun dengannya.
Aku ingin sekali berjumpa dengan Hartowardojo. Aku tidak dapat memberikan jawaban dengan cepat pada Zus Sulastri karena ada banyak aspek yang harus aku pertimbangkan masak-masak, aku tidak ingin kepergianku menjadi bencana. Sayangnya tidak ada berita yang jelas, orang pribumi yang pergi ke Borneo bagaimana kabarnya sekarang, aku tidak mendapatkan akses berita apapun mengenai Borneo dan pendudukan Jepang di sana. Itu artinya, satu-satunya orang yang dapat kupercaya hanyalah Zus Sulastri, sebab dia adalah pemberi informasi kepadaku dan lagi dia tetanggaku.
Tidak mungkinkan Zus Sulastri berbohong padaku, toh selama ini profesinya jelas, dia menjadi pemain sandiwara di sebuah grup sandiwara kecil. Dalam benakku, mungkin tentara Jepang merasa bosan di Borneo sana sehingga membutuhkan hiburan berupa grup sandiwara lengkap dengan alat musiknya, makanya mereka membuka lowongan kerja di Djakarta untuk dibawa ke Borneo. Sejujurnya aku merasa ini kesempatan yang sangat baik bagi diriku dan alangkah bodohnya jika aku harus melepaskan kesempatan besar ini begitu saja.
Yang menjadi persoalan bagiku adalah jika aku memberitahukan kepada kedua orang tuaku, besar kemungkinan mereka akan terang-terangan menolak dan menggunakan berbagai macam cara agar aku tidak dapat pergi ke Borneo. Mengingat mereka sangat bersikukuh menikahkan aku dengan Sutedjo. Sangat buruk sekali jika kedua orang tuaku tahu rencana kepergianku ke Borneo, jadi kurasa aku harus pergi ke Borneo sembunyi-sembunyi tanpa kedua orang tuaku tahu. Agak pahit memang di awal, namun kurasa aku harus melakukan hal ini. Aku tidak ingin kehidupanku di Djakarta menjadi runyam karena harus menikahi Sutedjo.
Berhari-hari aku menimbang dengan matang berbagai konsekuensi dari keputusan yang hendak aku ambil, plus dan minusnya aku tidak ingin melewatkan perhitungan sekecil apapun. Aku ingin pergi ke Borneo dengan matang tanpa kesalahan, banyak yang beranggapan bahwa aku sedikit perfeksionis dalam segala sesuatu dan itu memang benar. Aku harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencanaku, pun jika tidak sesuai aku masih memiliki rencana lain. Hatiku sedikit gamang sebetulnya, seorang anak gadis meninggalkan pulau seorang diri. Ketakutan seperti itu menghantuiku. Namun aku mencoba menghilangkan rasa takut tersebut.
Mencoba lebih baik daripada tidak sama sekali, begitu prinsipku. Baiklah, kukuatkan hatiku, aku mantap ingin ke Borneo namun pergi ke Borneo tanpa persiapan sama sekali adalah kebodohan terbesar, setidaknya aku harus memiliki uang pegangan untuk menyesuaikan kehidupan di sana sebab aku tidak memiliki bayangan sedikit pun bagaimana hidup di Borneo.
Aku memutuskan menjual giwang emas dan arloji milikku sebagai uang hidup di Borneo. Zus Sulastri mengatakan mereka memang menjanjikan memberikanku tempat tinggal gratis serta gaji yang cukup besar namun tidak ada salahnya aku menjual beberapa giwang emas dan arloji milikku untuk berjaga-jaga selama di Borneo nantinya sebab aku tidak pernah mengetahui apa yang terjadi ke depannya, ini hanya sekedar berjaga-jaga saja.
Siang itu aku beringsut menuju rumah Warsonoe, tidak ada yang mengetahui niatanku pergi ke Borneo, namun sebagai satu-satunya orang yang kupercayai, kurasa aku harus memberitahu Warsonoe akan niatku ini dan lagi aku ingin meminjam beberapa jumlah uang padanya untuk bekalku nanti di Borneo, aku tidak mungkin meminjam uang pada orang tuaku. Aku merasa, aku membutuhkan banyak uang untuk pergi ke sana beberapa lama, jadi selain menjual beberapa giwang serta arloji, aku juga butuh penambahan jumlah uang dari Warsonoe. Toh aku juga tidak tahu kapan aku kembali ke Djakarta.
Romlah menyambutku dengan hangat sesampainya aku di rumah Warsonoe, Romlah pun tak segan bercengrama denganku, sesekali ia menceritakan kisah kecil Hartowardojo padaku yang entah kapan sudah kudengar berulang-ulang setiap kali aku sempatkan diri berkunjung ke rumahnya. Semenjak Hartowardojo pergi, Romlah jauh lebih terbuka padaku, entah aku tidak tahu apakah Romlah mengetahui fakta bahwa keluargaku menyuruhku menikahi Sutedjo, kurasa dia belum mengetahuinya, mungkin jika Romlah tahu dia sedikit kecewa karena baik Romlah tidak pernah absen mengunjungi rumahku sekedar silaturahmi atau mengirimi makanan di saat ekonomi keluargaku jatuh maupun ketika ekonomi keluargaku cukup membaik seperti saat ini.
Agaknya Romlah tidak akan pernah bosan menceritakan setiap kenangan saat Hartowardojo kecil. Baginya tidak ada lagi yang bisa diajak mengenang Hartowardojo selain diriku. Memandangku seolah memandang Hartowardojo, memelukku seolah memeluk Hartowardojo, melihat senyumku seolah dia melihat Hartowardojo. Meski, baik aku maupun Romlah tidak akan pernah mengetahui kapan Hartowardojo kembali ke rumah namun kurasa aku bisa mengerti isi hatinya sebagai seorang ibu yang begitu merindukan anak lanangnya yang merantau jauh ke tanah Borneo dan hingga kini belum jua memberi kabar.
Romlah mengatakan padaku berulang-ulang bahwa Hartowardojo kecil adalah anak yang sangat periang, berani dan tidak bisa diam. Dari Romlah aku mengetahui yang tidak pernah kuketahui sebelumnya, bahwa Hartowardojo kecil pernah jatuh dari pohon jambu depan rumahnya hingga kepalanya bocor dan berdarah, namun begitu Hartowardojo kecil tidak menangis sedikit pun saking nakalnya dia malah kabur dari rumah karena ia mengira akan dimarahi oleh ibunya kalau ketahuan memanjat pohon jambu, cerita itu kurasa tidak begitu parah, dibandingkan cerita-cerita selanjutnya yang dilontarkan Romlah.
Untuk kesekian kalinya Romlah kembali bercerita padaku bahwa Hartowardojo kecil sangatlah nakal dan iseng, ketika bapaknya sedang tertidur pulas di dipan bambu dengan mulut terngangga sambil ngorok, Hartowardojo mengambil sesendok teh hangat wedang bapaknya yang biasa Romlah sediakan saat siang hari untuk suaminya. Dikucurkannya sendok berisi teh manis itu ke mulut bapaknya yang tertidur sambil mangap. Sontak bapak terbangun langsung berlari mengejar Hartowardojo sambil membawa sarung untuk menyabet anak itu, untungnya Hartowardojo sangat gesit sehingga ia bisa kabur dengan cepat. Entah mengapa, meskipun berulang kali aku mendegar cerita ini, aku selalu tertawa terkekeh-kekeh.
Kisah lain diceritakan Romlah, Hartowardojo kecil bersama Warsonoe bermain di kampung sebelah, mereka berdua tiba-tiba dikejar anjing kampung sehingga mereka berdua lari terbirit-birit dari kampung sebelah yang cukup jauh, nahasnya anjing kampung tidak berhenti mengejar mereka berdua, akhirnya karena panik Hartowardojo dan Warsonoe masuk ke salah satu rumah tetangga yang kebetulan pintunya sedang terbuka. Mereka berdua masuk diikuti anjing kampung yang ikut masuk. Sontak pemilik rumah yang saat itu sedang beristirahat sangat kaget dengan kehadiran dua bocah kecil berikut anjing kampung yang mengejarnya. Untungnya pemilik rumah tersebut bisa menjinakkan anjing kampung tersebut. Aku kembali terkekeh ketika mendengar cerita kekonyolan dan kenakalan Hartowardojo kecil.
Dari Romlah aku mengetahui kecintaan Hartowardojo begitu juga Warsonoe pada sastra menurun dari bapaknya. Bapaknya cukup sering membelikan majalah, roman, puisi semenjak mereka kecil. Sehingga ketika tumbuh dewasa baik Hartowardojo dan adiknya Warsonoe adalah para penyuka sastra. Berbeda dari Warsonoe, Hartowardojo lebih sedikit gila dalam meresapi esensi sastra dan seolah menjadikan sastra denyutan kehidupannya.
Kupandang figura hitam putih terpampang wajah Hartowardojo di sana. Aku tersenyum. Tak lama Warsonoe menghampiriku dari kamarnya. Dia menyapaku hangat. Rambutnya basah bekas air wudhu, nampaknya ia baru selesai shalat dzuhur dilanjutkan tilawah alquran karena aku sempat mendengar suaranya samar dari ruang tamu. Melihat Warsonoe sudah di ruang tamu, Romlah memutuskan untuk kembali ke dapur, ia bilang ingin merebus air untuk wedang suaminya yang sebentar lagi pulang istirahat.
“Ada apa Mbak?”
“Begini, ada yang ingin kusampaikan padamu. Tapi tidak sini.” Ujarku pelan. Warsonoe mengangguk, seolah ia paham bahwa aku ingin berbicara dengannya empat mata tanpa didengar siapapun termasuk Romlah ibunya. Tak lama Warsonoe mengeluarkan sepeda ontel miliknya dan mengajakku ke luar rumah. Sebelumnya tak lupa aku pamit undur diri pada Romlah.
Warsonoe mengajakku ke sebuah kebun jagung di kampung sebelah, siang-siang begini tak banyak petani di kebun jagung itu. Kulihat jagung-jagung gendut berserabut kuning sudah mulai matang dan siap dipetik. Warsonoe sengaja memilih tempat ini karena cukup sepi dan di pinggir jalannya terdapat sebuah pohon beringin besar yang rindang sangat enak duduk di bawah pohon beringin itu. Setelah memarkirkan sepeda ontelnya Warsonoe memastikan rumput yang hendak diduduki bersih dari kotoran, setelah itu dia mempersilakanku duduk. Aku duduk di tempat yang sudah dipersiapkan Warsonoe, kemudian Warsonoe ikut duduk di sebelahku.
Aku menarik nafas panjang menikmati pemandangan kebun jagung di bawah pohon beringin. Anginnya segar menggelitik pipiku, rambutku yang panjang dan hitam terkadang terkibas terkena buaian angin. Aku tak juga bersuara beberapa menit karena tak kukira sulit juga mengatakan sebuah rahasia pada seseorang, meskipun kita sudah mempercayai orang tersebut, namun rahasia ini cukup berat kuceritakan padanya. Warsonoe pun tidak bergeming, dia cukup menikmati pemandangan di depannya sambil memberikan waktu padaku untuk menceritakan sesuatu.
“Lusa aku akan ke Borneo...” Akhirnya kalimat itu muncul dari bibirku. Warsonoe tersentak kaget tapi Warsonoe tidak ingin melewatkan kalimat lain dariku jadi dia menahan dirinya untuk berkomentar. Aku kembali berbicara,
“Aku berencana ke Borneo untuk mencari Hartowardojo, Zus Sulastri yang menawariku bekerja sebagai pemain sandiwara di grup sandiwara miliknya. Kata Zus Sulastri Jepang butuh hiburan berupa grup sandiwara di Borneo, jadi mereka butuh orang. Mereka membayar mahal orang yang mau bekerja di Borneo, memberikan tempat tinggal dan juga memberikan pendidikan. Mereka memberikan itu semua beserta tumpangan gratis ke sana jika aku mau bekerja dengannya di Borneo.” Jelasku panjang. Warsonoe terlihat kaget.
“Bagaimana dengan keluargamu?”
“Aku akan pergi diam-diam, jika aku menceritakan niatku maka jelas mereka akan melarangku. Aku juga tidak ingin menikah dengan Sutedjo. Kurasa inilah jalan yang terbaik, aku bekerja di Borneo dengan begitu aku bisa mencari Hartowardojo dan menjauh dari Sutedjo.”
“Haruskah kau pergi ke Borneo, Mbak? Mas saja tidak ada kabar selama di sana. Tidakkah hal itu membuatmu takut? Tidak ada satu orang pun yang memberikan kabar selepas kepergian mereka ke tanah Borneo.”
“Jangan khawatir, Zus Sulastri yang mengajakku ke Borneo, dia tetanggaku. Kurasa aku bisa cukup mempercayainya, toh selama ini benar dia sebagai seorang pemain sandiwara dari kampung ke kampung.”
“Sejujurnya aku merasa cemas. Terlebih kau seorang wanita. Bagiku itu sangat berbahaya, pergi ke luar pulau tanpa didampingi keluarga dan pula bekerja untuk orang asing.”
“Percayalah, aku akan baik-baik saja. Aku akan menyusul kakakmu ke Borneo, namun aku memiliki sedikit kendala, bisakah kau meminjamiku beberapa uang? Aku sudah menjual giwang dan arloji milikku namun kurasa aku masih butuh uang untuk pegangan.”
“Berapa yang kau mau akan kuberikan. Jangan khawatir soal itu. Tapi bisakah kau memikirkan kembali keputusan ini? Saranku lebih baik kau tidak pergi ke Borneo. Toh di sini masih banyak pekerjaan untukmu.”
Warsonoe membujukku untuk tidak pergi ke Borneo, namun kali ini keputusanku sudah bulat dan sudah final, setelah melalui beberapa hari berpikir dan menimang konsekuensi, aku memutuskan untuk pergi bekerja ke Borneo. Hanya Warsonose satu-satunya orang yang kuberitahukan akan hal ini, tidak dengan keluargaku. Aku meminta Wasonoe menyembunyikan hal ini dari siapapun, termasuk Romlah.
“Lusa bantu aku pergi ke pelabuhan untuk segera ke Borneo tanpa keluargaku tahu ya.” Pintaku pada Warsonoe. Dia hanya mengangguk pelan. Kurasa dalam hatinya berkecamuk banyak hal mendengar keinginanku pergi ke Borneo.
“Baiklah, aku tahu tidak akan bisa menghentikanmu sama seperti aku tidak bisa menghentikan Masku pergi ke Borneo. Bukankah lusa kau ke Borneo, ada baiknya hari ini dihabiskan untuk menikmati Djakarta?”
“Hei... aku ke Borneo bukan untuk selamanya.”
“Ya, tidak ada salahnya menikmati hari di sini sepuasnya sebelum pergi ke sana. Mungkin saja kau akan rindu padaku.” Ungkapnya sambil terkekeh. Aku mencubit lengan Warsonoe. Sifat usilnya memang tidak hilang jua. Kemudian ia menyuruhku naik di sepedanya. Dia mengajakku berkeliling Djakarta dengan sepeda ontelnya. Adegan ini mengingatkanku pada kencan yang biasa aku lakukan dengan kakaknya.
“Mengapa tidak naik juga?” tanyanya mendapatiku masih termanggu belum juga duduk di boncengan belakang sepedanya. Aku tersenyum, bagaimana bisa aku mencampurkan antara kenangan dengan Hartowardojo dan Warsonoe? Keduanya adalah adik-kakak. Ini jelas bagiku namun mengapa aura kebersamaan dengan Warsonoe ini sangat biasa bagiku, sangat tidak asing dan anehnya aku nyaman.
“Kudengar kau juga menyukai sastra?” tanyaku sesaat setelah Warsonoe mengayuh pedal sepedanya dengan aku yang duduk manis di bangku belakang.
“Ya, tapi tidak segila Hartowardojo.” Jawabnya singkat.
“Aku menyukai sastra gara-gara dirinya.” Tukasku.
“Bukan karena sastranya?”
“Awalnya Hartowardojo mengenalkanku pada sastra sehingga lama-kelamaan rasa sukaku pada sastra berkembang dengan sendirinya.” Jawabku.
“Lantas siapa penyair yang paling kau suka?”
“Aku cukup menyukai Amir Hamzah.”
“Kalau begitu kau tahu sebuah sajak ini, coba tebak apa judulnya. Buktikan kalau kau memang penggemar Amir Hamzah.” Warsonoe menantangku.
“Memangnya kau hafal syairnya?” aku menantang balik.
“Tentu saja.”
“Kalian adik-kakak cukup gila ya.”
“Mengapa?”
“Tak banyak orang yang hafal syair dari sastrawan.”
“Berarti kau belum banyak bertemu orang di dunia, cukup banyak orang yang hafal namun hanya hidup dalam kedamaian. Jadi tak banyak yang tahu.”
“Kalau begitu aku harus banyak berkeliling dunia, maka cocoklah aku ke Borneo untuk membuktikan ucapanmu.”
“Ya.” Warsonoe dan aku membelah kebun jagung, angin yang lembut membelai wajahku, aku menggenggam erat kaos yang dikenakan Warsonoe supaya tidak terjatuh ketika roda sepeda melaju pada jalan yang terjal.
“Coba buktikan padaku kalau kau penggemar Amir Hamzah, tebak apa judul dari syair ini,” Warsonoe mulai mengucapkan kata demi kata membentuk syair Amir Hamzah.
Ombak memecah ditepi pantai
Angin berhembus lemah-lembut
Puncak kelapa melambai-lambai
Di ruang angkasa awan bergelut.
Burung terbang melayang-layang
Serunai berseru, “adikku sayang”
Perikan bernyanyi berimbang-imbang
Laut harungan hijau terbentang.
Dua syair sudah dibacakannya dengan baik, aku mencoba mengingat-ingat judul dari syair yang dia bacakan.
“Teluk Jayakatera ,tahun 1941.” Jawabku tegas tidak ada keraguan.
Warsonoe membunyikan suara “Kriiingg,,, Kriingg...” dari sepeda ontelnya menandakan bahwa jawabanku benar.
“Betuuuul sekali.” Ujarnya. Aku terkekeh. Seperti mengikuti sebuah lomba saja. Baiklah aku tidak mau kalah, kali ini giliranku membacakan sebuah syair yang kusukai, kira-kira apakah Warsonoe bisa menjawabnya.
“Bayu berpuput alun digulung
Banyu direbut buih dibubung.
Selat Melaka ombaknya memecah
Pukul-memukul belah-membelah.”
Aku membacakan syair puisi Amir Hamzah yang kuingat karena aku cukup menyukainya jadi tanpa sadar aku sudah hafal di luar kepala karena terus membacanya berulang-ulang. Warsonoe terdiam sejenak. Aku mengharapkan dia menjawab judul puisi yang baru saja aku bacakan tapi dia justru melanjutkan syair puisi tersebut.
“Bahtera ditepuk buritan dilanda
Penjajab dihantuk haluan ditunda
Camar terbang riuh suara
Alkamar hilang menyelam segera.
Judulnya Hang Tuah. Tahun 1932.” Jawab Warsonoe. Aku bertepuk tangan menandakan bahwa Warsonoe menjawab dengan benar. Tak kusangka, dia menyukai sastra sama seperti kakaknya. Sastra mengalir di darah kedua pemuda ini.
“Hartowardojo pernah sekali mengatakan padaku, di saat pemuda lain kecanduan minuman keras, kecanduan bermain wanita, tapi lebih baik baginya kecanduan sastra. Sastra tidak merugikan siapapun.” Jelas Warsonoe padaku.
“Ya, dia juga mengatakan orang yang menyukai sastra tidak akan pernah jadi bajingan. Tapi dia salah, dia menyukai sastra namun tetap bisa menjadi bajingan karena meninggalkanku dan pergi ke Borneo.”
“HAHAHAHAHA!!” Warsonoe tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia sangat senang mendengar aku berbicara jujur mengenai kakaknya.
“Aku tidak percaya kau bisa mengatakan hal semacam itu, emangnya dengan membaca sastra kau akan menjadi dewa yang tidak pernah berbuat kesalahan? Konyol sekali pemikiran itu. Tapi kurasa memang benar dia bajingan. Meninggalkanmu dan meninggalkan keluargaku.” Lanjutnya.
“Apa artinya aku juga bajingan? Aku akan meninggalkan keluargaku.”
“Tak masalah, menjadi bajingan cantik akan selalu dimaafkan orang-orang.” Ujarnya diikuti cubitan pada perutnya dariku. Dia hanya meringis sedikit.
“Aku ingin berjalan-jalan dengan Sinar dan Mulyati sebelum aku pergi ke Borneo. Aku khawatir sekali mereka akan merasa sedih jika aku pergi dengan tiba-tiba. Kurasa sebagai salam perpisahan aku ingin mengajak mereka berjalan-jalan.” Ujarku.
“Baiklah, kita jalan-jalan berempat. Kau membonceng Mulyati dan aku membonceng Sinar. Bagaimana?” ucap Warsonoe. Sebuah ide yang bagus terlontar darinya.
Saat aku dan Warsonoe pulang ke rumah dan mengajak Sinar dan Mulyati pergi jalan-jalan, mereka berdua senang bukan main. Keduanya segera berganti pakaian terbaik, padahal hanya diajak berkeliling saja naik sepeda. Seharusnya sebelumnya aku banyak menghabiskan waktu dengan Sinar dan Mulyati. Aku sedikit menyesal mengingat aku selalu sewot ketika Mulyati mengajakku main di saat suasana hatiku buruk. Seharusnya aku iyakan saja setiap ajakan main mereka kalau tahu aku akan pergi ke Borneo secara mendadak begini.
Mulyati mendekapku erat dengan jari-jarinya yang kecil dan ujungnya kemerahmudaaan saat kukayuh pedal sepedaku menelusuri padang ilalang jauh dari kampung kami, kulihat Sinar yang dibonceng oleh Warsonoe pun tampak menikmati perjalanan ini. Sebelumnya yang pernah mengajak kedua adikku jalan tentu saja Hartowardojo namun hari ini digantikan adiknya, Warsonoe. Hartowardojo juga kerap mengajakku serta kedua adikku berjalan-jalan menaiki sepeda, persis seperti saat ini. Lagi-lagi aku merasakan kehadiran Hartowardojo dalam diri Warsonoe, aku hanya berpikir karena mereka berdua adalah kakak-beradik. Sangat wajar jika ada hal yang sama dari mereka berdua karena di dalam tubuh mereka mengalir darah yang sama.
Aku termasuk kakak yang cuek kepada kedua adikku Sinar dan Mulyati, aku tidak banyak menunjukkan rasa cintaku pada mereka, sebab aku hanya ingin mereka tumbuh menjadi gadis yang kuat dan mandiri kelak, bukan gadis manja yang hanya bisa menangis. Pernah suatu ketika Sinar pulang dari Taman Siswa dalam keadaan menangis, ternyata dia habis berantam dengan teman sekelasnya, aku tidak mengelusnya, memeluknya atau membelainya untuk meredakan tangisannya. Aku justru memarahinya agar tidak berantam di sekolah dan mengatakan padanya bahwa perilaku itu buruk dan tidak pantas dilakukan, jika bisa dilakukan dengan damai mengapa harus ada kekerasan. Begitulah aku mendidik Sinar dengan sedikit keras.
Sama juga dengan perilakuku pada Mulyati, dia masih duduk di bangku sekolah dasar di Taman Siswa. Mulyati anak bungsu maka sikapnya sedikit manja, namun aku tetap berusaha mendidiknya dengan tegas. Mulyati sering sekali dijahili teman sekelasnya tak heran dia sering pulang dalam keadaan menangis. Lagi-lagi aku tidak memeluknya untuk meredakan tangisan adikku. Justru aku mengajarkannya agar tidak menangis lagi. Jadilah anak yang kuat, semenjak saat itu Mulyati tidak terlihat lagi menangis sesegukan. Dia sudah bisa mengontrol emosinya dan tidak lagi membiarkan teman yang lain menjahilinya. Kulihat banyak orang tua apabila mendapati anaknya menangis, mereka malah memukul anaknya agar tidak menangis lagi, tidak begitu bagiku. Kekerasan bukanlah cara menenangkan anak-anak. Pengalamanku mengasuh kedua adikku kurasa berguna bagiku kelak.
Aku hanya bertanya-tanya, bagaimana jika aku tidak ada di sisi mereka, bagaimana jika aku pergi mendadak ke Bornoe, apakah mereka bisa menerima keputusanku untuk pergi tiba-tiba? Bagaimana nanti Sinar dan Mulyati siapa yang akan menjaga mereka nantinya? Siapa yang mereka ajak bermain di rumah ketika bapak dan ibu sibuk di pabrik tahu? Siapa yang akan memasakkan mereka makanan di rumah? Siapa yang nanti akan mencucikan pakaian mereka? Siapa yang akan membantu mereka mengerjakan tugas matematika nanti? Karena biasanya semuanya aku yang melakukan. Pertanyaan-pertanyaan itu menari-nari di dalam pikiranku. Aku tidak habis pikir mengapa perasaanku jadi berat untuk meninggalkan adik-adikku? Aku menyeka air mataku yang tiba-tiba saja meleleh, Warsonoe yang sedang membonceng Sinar melihatku menyeka air mata, aku hanya tersenyum lembut ke arahnya. Aku hanya ingin memberitahu bahwa aku baik-baik saja.
Sepeda kami tiba di sebuah pantai di pinggir Djakarta. Pantainya bersih dan cukup sepi, tidak banyak pengunjung yang datang kemari. Aku dan Warsonoe memarkirkan sepeda ontel kami di dekat pohon kelapa. Tak menunggu waktu yang lama, Sinar dan Mulyati sudah berlari-lari bertelanjang kaki di bibir pantai. Keduanya asyik berlari-larian ke sana ke mari bagaikan anak ayam dilepas dari kandangnya.
Warsonoe membawa sebungkus besar kacang rebus dan beberapa bungkus wedang jahe yang dijual oleh mamang-mamang gerobak tak jauh dari tempat kami duduk. Warjonoe menghampiriku dan meletakkan sebungkus besar kacang rebus dan beberapa bungkus wedang jahe itu di pangkuanku. Matanya memperhatikan Sinar dan Mulyati berlari-larian di pantai, Warsonoe mengembangkan senyumnya.
Kulihat rambut Sinar berkelebat tertiup angin pantai, rok selutut yang digunakannya melambai-lambai terkena angin. Saat ini Sinar dan Mulyati hanyalah dua bocah kecil, namun suatu saat nanti mereka akan tumbuh menjadi dua gadis cantik. Sinar tertawa cekikikan, kulihat arah matanya tertuju pada Mulyati yang badannya sudah basah terkena deburan ombak, celakanya aku lupa membawakan mereka baju salin. Terlanjur basah, Mulyati segera memercikkan air pantai ke arah Sinar, tak ayal Sinar pun berlari kencang ke arahku yang sedang duduk bersama Warsonoe.
***


 dede_pratiwi
dede_pratiwi

















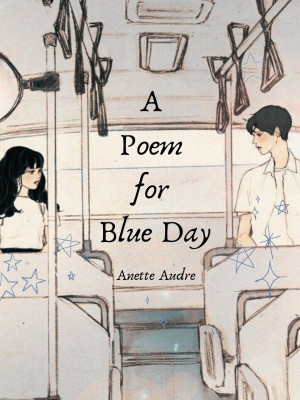

Waaawwww... Ceritanya beda. Latar yang berbalut sejarah. Bagus. Belum lagi tata bahasanya enak buat para pembaca. Sukses terus buat karyanya.
Comment on chapter BAB 3 1942