“Kalau nggak bisa itu bilang caranya, nggak usah sok percaya diri bawa semuanya. Biasa dimanja sih.”
Dhisti yang tengah merapikan isi kardus yang berceceran pun menghentikan kegiatannya. Ia mendongak dengan kekesalan yang kentara. Egonya terluka ketika mendengar perkataan menyebalkan itu. “Dari mana lo tahu kalau gue sok percaya diri? Lo punya mata apa nggak sih, gue kesandung, bukan nggak bisa.” Ia kembali memasukan barang-barang yang berceceran. Tubuhnya sedikit bergerak, meraih lakban yang cukup jauh dari tempatnya duduk. “Dan lagi, masih mending gue manja tapi mau bantu-bantu, daripada lo,” Dhisti mendongak lalu tersenyum remeh, “yang katanya mandiri tapi diem aja di tempat.” Ia mengangkat kardus dengan pelan dan berbalik, berjalan begitu penuh percaya diri.
Perlahan tapi pasti wajahnya kian mengeras, telinganya sudah jengah dengan ucapan seperti itu.
“Beh, songong banget.”
“Ya, maklumlah, kan anak Mama. Nanti juga kalau dia nangis tinggal lapor.”
Dhisti mempercepat langkahnya, bukan karena dia takut, namun dia tidak mau membuat gara-gara karena ucapan menyebalkan itu. Memangnya dia apa yang mau menjadi anak semata wayang? Nggak. Ingin sekali Dhisti membalas perkataan mereka semua dengan kalimat iya iyalah gue anak Mama, gue lahirnya dari perut Mama gue. Emangnya lo?!
“Nih, Ri.” Kerdus yang sejak tadi dipegang penuh kehati-hatian, ditaruh cukup keras hingga menimbulkan suara yang menarik perhatian orang-orang di kelas itu.
Adhisti sudah tidak tahan lagi, dia ingin mengeluarkan uneg-uneg yang ada dalam kepalanya saat ini. “Enak bener ya, bilang orang manja. Minta digaplak emang.”
“Kenapa lagi sih?” Asri melirik Dhisti sebentar sebelum fokus mengeluarkan barang-barang di kardus.
“Biasa. Lo kapan kelar? Gue mau beli es kelapa. Hati gue panas.”
“Ini juga udah kelar kok.”
Dhisti mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau bukan karena Asri, dia sudah pulang dari kampus. Helaan napas keluar dari bibir Dhisti. Gadis itu merasa kesal, dan putus asa ketika mengingat ucapan yang terlontar untuknya. Bukan kali ini saja dia mendengar perkataan itu, melainkan sudah berkali-kali mungkin puluhan atau ratusan kali. Dan tahu? Rasanya sangat menjengahkan. Memangnya dia apa yang mau menjadi anak semata wayang?
“Ayok pulang. Mau beli es kelapa di mana?”
“Mana-mana deh, gue haus banget.”
“Emang kenapa? Lo kayaknya kesel banget. Cerita.”
“Gue dibilang anak manja, lagi.” Dhisti menoleh dengan malas ke Asri. “Gue bosan dengernya, dari dulu sampai sekarang, kata-kata itu kayaknya melekat di gue. Emangnya gue apa yang mau jadi anak semata wayang? Emang gue apa yang mau dimanja. Heran gue.” Ia menyugar rambutnya, bibirnya masih mengeluarkan keluh kesah yang tadi mengganjal.
Asri menepuk pundak Dhisti berulang kali, menabahkan sahabatnya itu. “Ya, mau gimana lagi. Emang kata ‘manja’ udah melekat pada anak semata wayang, ‘kan?”
Dhisti menjetikan jemarinya di depan Asri. “Nah itu. Gue mau ubah. Kesel gue, muak. Pingin gue cakar tuh orang-orang yang bilang manja. Kayak ngeremehin banget.”
“Mau buktiin gimana?”
“Au.” Dhisti mengeluarkan kunci mobil dan langsung membuka pintu mobil dengan kasar. “Lo ikut gue minum ‘kan?”
****
“Udah deh, Dhisti. Lo nggak capek marah-marah mulu.”
Setengah jam mereka berada di kedai ice cream, Dhisti masih saja mengomel. Meski sekarang tingkat suaranya sudah menurun.
“Masih kesel gue.” Punggungnya ia sentakan cukup keras pada sandaran sofa. “Coba deh lo jadi gue, kalau setiap kali lo ngelakuin sesuatu terus pas lo lagi jatuh, tiba-tiba dibilang manja? Kesel nggak?”
Asri menggaruk kepalanya. “Ya kesel sih.”
“Kesel ‘kan? Mereka nggak tahu aja, kalau jadi anak semata wayang itu penuh aturan. Harus lapor segala macam, nggak boleh keluar malam, nggak boleh pergi terlalu jauh, nggak boleh bla bla.” Dhisti menghela napas. “Maaf ya, lo jadi sasaran kemarahan gue.”
“Santai. Lo habisin ice lo deh, biar agak tenangan.”
“Heeh.”
Sayup-sayup terdengar keributan, membuat keduanya menoleh untuk melihat. Dua orang laki-laki masuk ke dalam kedai dengan hebohnya. Percakapan mereka bahkan terdengar, yang langsung membuat emosi Dhisti naik kembali.
“Ya, mau gimana lagi. Dia kan anak Mama. Mana mau diajak keluar, gitu. Paling nih, orang tuanya udah beliin dia sesuatu biar dia nggak keluar rumah. Enak ya jadi anak sendiri.”
“Ah, pantes dia nggak bisa ngelakuin apa-apa sendiri. Gue curiga kalau dia juga nggak bisa mandi sendiri.”
Dhisti bangkit, ia menyambar tasnya dan langsung berjalan ke arah kedua orang laki-laki itu.”
“Heh, Mas. Nggak semuanya ya anak semata wayang itu manja!” hardiknya membuat kedua orang itu kaget.
“Maaf, Mbak. Mbak siapa ya?”
Mengabaikan ucapan itu, Dhisti kembali berkata.
“Denger ya. Lo boleh mikir apa pun, tapi nggak semua orang dan selamanya anak semata wayang itu manja, paham lo!” Dhisti menabrak keduanya dan langsung pergi dari kedai itu.
“Lo kenal, Sev?”
“Nggak.”
“Aneh banget, emang kata-kata kita ada yang salah ya?”
Sebagai jawaban laki-laki yang ditanya menaikkan bahunya. Ia terus menatap wanita yang masih terlihat marah.
“Permisi-permisi.” Keduanya menyingkir.
“Dhisti, lo mau kemana?!”
“Gue mau buktiin kalau anak semata wayang itu nggak selamanya manja!”


 D
D



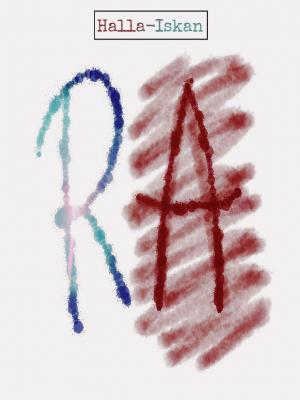

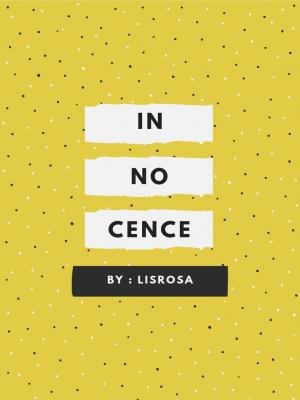




Saya anak semata wayang. Tapi saya jauh dari kata manja.
Comment on chapter Prolog