BAB 16. PUNCAK TANTANGAN
HARI KE-70, TIMIKA
Bagiku, waktu berlalu bagai lengkingan anak panah diloloskan angin, berlalu begitu saja hingga tak disadari kedatangannya. Tak terasa kami telah menempuh hari ke-70. Petualangan kami sudah mencapai puncaknya. Tampak wajah-wajah temanku kelelahan tapi juga puas telah mengarungi separuh negeri. Kini, tinggal daratan Papua yang belum kami taklukkan. Puncaknya adalah pegunungan Jayawijaya, tantangan terakhir sekaligus paling menegangkan yang layak dijadikan garis finish. Hari itu, akhirnya kami menjejakkan kaki jauh di ujung timur Indonesia. Jayawijaya, kami datang.
“Kita telah menempuh jarak yang luar biasa,” kata Harto.
“Ya, nggak nyangka kita bisa sampai sejauh ini,” kataku.
Papua merupakan provinsi terbesar dan paling timur di Indonesia, terletak di bagian barat pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sebagai kawasan konservasi terluas di Asia Tenggara, Papua memiliki bentangan alam yang menakjubkan seperti pantai indah yang membentang luas, padang rumput yang sejuk menghijau, dan sungai-sungai yang mengukir jurang menembus hutan tropis yang masih perawan. Hari beranjak sore ketika pesawat mendarat di Timika. Sesuai janjiku, petualangan ini harus selesai dan aku yang membiayai. Saat tiba di darat, Hana menghampiriku dengan langkah ringan dan memberiku surat.
“Apa ini?” tanyaku, bingung. Tak biasanya Hana menulis surat. “Kalau ada yang ingin kausampaikan, kenapa tidak katakan langsung saja?”
Hana hanya tersenyum dan melesat mendahuluiku. Aku mengangkat sebelah alis, terkejut atas sikapnya yang tak biasa. Akhirnya kumasukkan saja surat itu ke dalam tas. Kuputuskan akan kubaca kalau pulang nanti.
“Kira-kira isinya apa ya? Surat cinta?” bisik Harto.
“Mustahil, cewek selevel dia mana bakalan melirikku,” kataku.
“Hati-hati Lutfi, paling isinya surat tagihan hutang,” kata Nasuti. “Dulu dia bendahara kelas kita kan?”
Sementara itu, Igo menggandeng Inayah, berjalan bersisian.
“Kamu yakin sudah baikan, Ine?” Igo bertanya.
“Iya Kang, nggak apa-apa,” istrinya tersenyum. “Dulu juga aku sering kepeleset di kebun stroberi, sampai lecet-lecet dan kakiku keseleo, tapi besoknya bisa lari-lari lagi.”
Dua hari lalu mereka sempat bertengkar. Igo membujuk istrinya agar istirahat saja di resor, jangan memaksakan diri, tapi Inayah merajuk minta ikut mendaki karena penasaran ingin melihat salju. Dia tidak marah atau berteriak, tapi air matanya bercucuran saat dia meyakinkan Igo bahwa dirinya juga pandai memanjat pohon kelapa. Harto dan Nasuti saling pandang, tak percaya ceritanya, tapi aku ingat betapa gesitnya Inayah saat ikut memanjat tebing di Kabupaten Maros, jadi aku mendukungnya. Tak tega melihat istrinya menangis lagi, Igo terpaksa mengabulkan permintaannya, dengan syarat Inayah hanya boleh ikut sampai titik tertentu, mengingat lukanya belum pulih. Kalau terjadi apa-apa, Igo terpaksa mengajaknya pulang. Inayah berjingkrak senang.
“Kalau aku kenapa-napa, nanti pulangnya naik helikopter kan?” dia bertanya polos. Igo menggaruk kepalanya, mengiyakan saja.
Tiba di hotel, kami disambut kuliner khas Papua di antaranya sate rusa, aneka penganan ubi, dan papeda—makanan berbahan dasar sagu yang mirip lem kanji dan disandingkan dengan ikan kuah kuning, cara makannya diseruput langsung bersama kuahnya. Kami juga berkesempatan mencicipi sajian khusus yaitu udang selingkuh khas Wamena yang tak ada di tempat lain. Udang selingkuh merupakan hewan endemik sungai Baliem yang sifatnya musiman. Selepas makan malam, Muqodas mengajakku bicara serius.
“Nggak apa-apa nih kalau kau yang membayari? Biayanya mahal lho, butuh setidaknya dana 60 juta untuk mendaki Jayawiaya hingga puncak Carstenz, mulai dari biaya transportasi, hotel, hingga perbekalan. Apalagi jika memakai jasa biro perjalanan yang menawarkan helikopter sebagai transportasinya. Belum lagi biaya untuk membeli perlengkapan mendaki yang tentu saja tidak murah. Kau masih yakin ingin mendaki Carstenz? Kuperingatkan, Kawan, hanya pendaki yang punya cukup dana dan pengalaman yang sanggup menapakinya. Setiap tahun, tak terhitung jumlah pendaki papan atas lokal maupun mancanegara yang berlomba menaklukannya. Pendaki amatiran sebaiknya duduk tenang saja di rumah.”
Aku tahu dia mengejekku, tapi aku diam saja. Aku bukan amatir. Sudah lebih dari sepuluh gunung yang kudaki di Jawa bersama Harto, Nasuti dan Igo, ditambah lagi Kerinci di Sumatera yang kami daki di awal ekspedisi. Sebelum berangkat, kami juga berlatih memanjat tebing bersama Torik di Gor Satria. Bahkan Inayah si gadis desa jago memanjat tebing, sering naik turun bukit membawa bakul stroberi, dan masih segar di ingatanku saat dia dengan gesit memanjat tower di kampungnya. Kami semua sudah terbiasa dengan gunung.
“Nggak masalah, aku pasti bisa kok, lihat saja nanti,” kataku. “Soal biaya juga tak usah dipikirkan. Kau tahu kan, bukan keluarga Zhen saja yang punya bisnis travel. Pamanku juga punya. Beliau kemarin meneleponku, bilang agar aku mengambil alih proyek Shen Travel, melanjutkan pembuatan film dokumenter yang belum selesai ini. Aku juga sudah mengganti seluruh biaya perjalanan kemarin kepada Shen Travel. Yah, meskipun pemiliknya sekarang dipenjara, tapi hutang tetap harus dibayar. Nantinya film yang kita buat akan dipublikasikan sebagai sarana promosi dan masuk arsip perusahaan Paman. Kau tidak keberatan kan?”
Muqodas masih menatap sangsi, perlahan mengangguk.
*****
Esoknya, kami berbelanja logistik di pasar dan mencari toko khusus penjelajah untuk membeli alat-alat tambahan seperti tali pengaman dan pelindung sepatu. Adapun perlengkapan standar seperti carrier, sepatu, jaket, tenda, carabiner, gaiter dan lainnya kami sudah punya. Kami juga diwajibkan melapor ke Polres dan Pos TNI sebelum memulai pendakian. Sayangnya akses yang kami tempuh cukup sulit dan rumit, karena butuh waktu untuk memproses surat izin serta jaminan keselamatan untuk bisa meneruskan. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa situasi keamanan sedang gawat akibat terjadinya perang suku. Di perjalanan tadi, kami sempat melihat banyak polisi diterjunkan demi menangani masalah politik di wilayah sekitar. Untungnya proses negosiasi berlangsung mulus karena sebelumnya kami sudah memperoleh izin di Jakarta. Kami akhirnya meneruskan ke kaki gunung.
Pendakian kami di hari pertama lumayan ringan sama seperti gunung lainnya. Kami hanya harus melewati hutan lebat dan menyeberangi beberapa sungai. Sesekali kami juga melompati batang kayu lapuk yang sudah dimakan rayap.
“Aku tak sabar ingin melihat honai, rumah adat khas Papua yang berbentuk unik seperti jamur, tak berjendela, dan dibuat dari susunan jerami dan ilalang itu,” kata Harto. “Aku juga ingin menengok Suku Dani dan Suku Asmat yang gemar membuat ukiran kayu itu.”
Di perjalanan, kami sesekali mampir ke pemukiman sekitar. Suku Dani berkulit gelap dan berambut keriting, senang memakai hiasan kepala unik dan merias kulitnya dengan campuran tanah merah, serbuk kulit kerang, dan arang kayu. Suku yang gemar menindik hidung dengan tulang ini menganut kepercayaan kuno menyembah patung atau roh orang mati. Kami berkomunikasi dengan warga menggunakan bahasa isyarat karena kami tak mengerti sepatah pun ucapan mereka.
Beberapa keunikan kami jumpai di Bumi Cenderawasih yang masih belum terjamah peradaban modern ini. Salah satunya adalah saat Harto hendak memotret seorang suku pribumi di sana, si model ini malah minta dibayar. Meski begitu, mereka cukup ramah. Kami ditawari kuliner ekstrim berupa ulat sagu—larva kumbang sebesar jempol kaki yang hidup dalam pohon sagu busuk. Meskipun kandungan proteinnya tinggi, tak satupun dari kami bernyali menikmatinya. Torik adalah satu-satunya yang berani menyantap makanan itu. Aku sih menyentuhnya saja sudah segan.
“Nama latinnya sih keren, Rhynchophorus ferruginenus,” kata Igo, mengingat pelajaran mata kuliah Taksonomi Hewan. “Tapi larva berkepala merah ini menjijikan. Mendengar namanya saja membuatku geli.”
“Sesekali mencoba nggak ada salahnya kan?” kata Torik, melahap makhluk itu seperti mengemil kacang. “Toh makanan ini termasuk langka, cuma ada di beberapa tempat.”
Selain Torik, Hana adalah pemberani dari pihak wanita. Gadis itu berani memegang ular besar yang melintas di hutan dan melingkarkannya di leher tanpa takut dililit. Iseng-iseng dia menjulurkan ular itu ke dekat Inayah yang langsung lari sambil menjerit-jerit.
“Aku pernah dengar cerita Pak Edy, dosen ekologi yang pernah melakukan penelitian di sini,” kataku. “Katanya penduduk pribumi di sini senang makan daging rusa atau kanguru. Dulu aku bahkan pernah disuguhi gulainya saat bertamu ke rumah beliau. Katanya sih oleh-oleh dagingnya banyak sekali, sampai dibagi-bagikan ke tetangga juga.”
“Iya, aku ingat,” kata Harto. “Pak Edy juga memperlihatkan foto-foto penelitiannya padaku. Ada foto burung-burung langka, buaya besar, dan berbagai jenis ikan aneh yang belum pernah kulihat. Namun yang paling menarik adalah foto seorang pedagang ikan yang membuang begitu saja dagangannya yang tersisa, saat hendak pulang usai berjualan di pasar. Si pedagang ini tak merasa rugi sama sekali dengan mengembalikan ikan-ikannya ke sungai, karena besoknya pasti dia dapat tangkapan lagi. Menakjubkan, di tempat ini, bahkan mencari ikan pun mudah sekali.”
“Artinya kekayaan alam Papua memang sangat melimpah,” kata Nasuti, melangkahi akar pohon besar. “Oh ya, kabarnya beliau juga pernah diancam penduduk sekitar. Katanya, sebelum pulang beliau sempat menawar tombak milik kepala suku untuk dibeli sebagai oleh-oleh. Padahal, tongkat itu terbuat dari kayu biasa, tak ada istimewanya sama sekali. Tapi si kepala suku menolak menjualnya, berapapun harga yang ditawarkan. Ujung-ujungnya, Pak Edy dan tim ekspedisi mesti angkat kaki karena penduduk yang marah tiba-tiba membawa tombak, bahkan mereka sampai harus kejar-kejaran naik mobil jeep supaya bisa kabur dari perkampungan.”
“Hii serem, semoga nggak terjadi pada kita ya?” kata Hana, mengelus batang pohon berlumut. Kami semakin jauh memasuki hutan. Pohon-pohon besar mengepung kami, dengan kanopi yang tampak menjulang di atas, entah berapa puluh meter tingginya.
Aku sedang mengamati aneka tanaman liar hutan ketika Harto mencolek lenganku. Sambil nyengir, pemuda itu mengajakku menjauh dari yang lain, lalu memperlihatkan sebuah foto padaku. Aku sedikit terkejut. Ternyata itu foto Inayah yang sedang diikat di bunker. Aku mengangkat sebelah alis padanya. Aku heran sempat-sempatnya dia memotret dalam keadaan genting begitu. Dia bahkan merekam pertarungan dengan para buronan, dari awal hingga akhir. Hebat juga dia bisa mengambil gambar tanpa kami sadari. Aku bahkan tak tahu kapan dia melakukannya.
“Jangan sampai ketahuan Igo lho,” aku memperingatkan.
Kami terus melangkah di sela-sela pepohonan lebat. Pemandangan alam liar di sekitar kami cukup menghibur. Sambil menapaki hutan, aku menghitung hari. Tinggal sembilan hari lagi tersisa sebelum genap 80 hari. Kami meneruskan perjalanan hingga kaki pegunungan. Pohon-pohon mulai jarang, menampakkan pemandangan di baliknya.
“Akhirnya kita sampai, Teman-teman,” Torik berbalik menghadap kami, merentangkan lengan, wajahnya berbinar penuh semangat. “Welcome to Jayawijaya!”
Gunung tertinggi di Indonesia menjulang di hadapan kami, sosoknya berdiri gagah bagai raksasa. Kaki pegunungannya saja berkilo-kilometer lebarnya, dengan punggung tertutup salju dan puncak yang menjulang seolah hendak menggapai langit. Kami sampai menjulurkan leher mencari puncaknya yang tak terlihat karena bagian atasnya menembus awan. Jantungku berdebar penuh semangat. Ini akan jadi pendakian terberat yang kulakukan seumur hidupku. Gunung Ciremai ataupun Slamet tak seberapa besar jika dibanding gunung di hadapanku ini. Tentu saja Jayawijaya berada di level yang jauh berbeda dibanding gunung-gunung yang pernah kudaki sebelumnya. Tantangan sebenarnya baru akan dimulai.
“Gunung yang termasuk tujuh puncak dunia ini memiliki beberapa puncak,” Torik menjelaskan. “Di antaranya puncak Mandala, puncak Trikora, puncak Idenberg, puncak Yamin, dan puncak Carstenz yang akan kita daki. Sama halnya dengan puncak Kilimanjaro di Tanzania—karena tingginya mencapai 4800 meter di atas permukaan laut—tak mustahil jika pegunungan di daerah tropis ini diselimuti salju abadi.”
“Ya, mencapai puncaknya sudah jadi impian setiap pendaki, baik yang profesional maupun amatir, karena tempat ini menawarkan sejuta tantangan,” kata Muqodas.
Berikutnya, setelah lagi-lagi mengurus izin, kami menaiki kereta gantung ke kawasan Grassberg Hole di pertambangan Freeport. Inilah pengalaman pertamaku naik kereta gantung. Di bawah sana, dunia tampak begitu menakjubkan dilihat dari ketinggian. Tampak juga pemandangan lubang tambang emas dan alat-alat berat berlalu lalang. Kawan-kawanku tampak antusias, dan Harto tak hentinya memotret sana-sini.
Begitu kereta berhenti di High Camp, kami meneruskan naik bus menuju Zebra Wall, tebing setinggi ratusan meter dengan corak belang-belang. Dari situ kami berjalan kaki lagi menanjaki medan berbatu, menahan panas matahari yang menyengat. Sesekali kami bertemu pendaki lain yang sedang beristirahat, ditemani ibu-ibu porter pengangkut barang. Pukul empat sore, akhirnya kami tiba di Danau Biru yang letaknya 3.900 meter di atas permukaan laut. Inilah base camp pertama kami. Di depan sana terlihat tanjakan tajam yang melewati Pintu Angin, dikelilingi tebing-tebing batu raksasa.
“Kita bermalam di sini,” kata Muqodas. “Menurut panduan seniorku, setiap mendaki seratus meter kita harus melakukan aklimatisasi agar kondisi fisik terbiasa dengan ketinggian dan kadar oksigen yang tipis. Dari pengalaman mereka, proses pendakian ke Puncak Carstenz biasanya makan waktu sekitar sepuluh hari. Tapi kita bisa mencapainya dalam sembilan hari jika bergerak cepat.”
Segera saja kami sibuk mendirikan tenda dan memasak perbekalan. Kami melakukan pemanasan dengan berlari-lari kecil mengitari danau. Pemandangan indah di sekitar danau membuatku bersemangat. Kuperhatikan, Harto dan Nasuti yang biasanya ceria tampak lebih sering terdiam, barangkali gara-gara penyakit ketinggian menyerang mereka. Aku sendiri mulai merasa pusing. Kepalaku terasa terbebani seakan ada benda berat yang menggayut tak mau lepas. Aku khawatir terkena frostbite atau radang dingin yang terkenal ganas di kalangan para pendaki. Untuk mengurangi pegal, Torik bahkan mengolesi tubuhnya dengan daun gatal yang dibelinya di pasar setempat. Sepanjang hari ini, kami jarang sekali bicara dan hanya berkomunikasi lewat isyarat. Di tempat ini, yang jadi penjahatnya bukan lagi manusia, tapi kondisi alam yang liar dan sulit diprediksi.
“Mendaki gunung tak boleh terburu-buru,” kata Hana. “Saat mencapai ketinggian tertentu, kita harus melakukan pemanasan dulu sebelum naik lebih tinggi. Kamu masih kuat kan, Inayah? Luka-lukamu sudah baikan?”
“Nggak apa-apa Mbak, hehe. Dulu saya sering mendaki Gunung Tangkuban Perahu, kok. Saya sudah biasa dengan alam pegunungan. Sering kepeleset sampai lecet-lecet juga.”
“Gunung yang kita hadapi ini tingginya berkali-kali lipat lho,” Hana mengingatkan. “Siapapun yang berniat mendaki harus siap fisik dan mental. Selain itu medan pendakiannya juga cukup berbahaya. Sudah banyak pendaki yang hilang atau tewas saat mendekati puncak. Ini bukan main-main, lho, Inayah.”
Sementara itu, Igo yang memeriksa termometer melonjak terkejut. “Gila, siang hari aja suhunya sepuluh derajat celsius, gimana malamnya?”
“Cuacanya ngajak berantem nih, bibirku sampai pecah-pecah,” kata Nasuti.
Malam harinya kami meringkuk saling berdekatan di dalam tenda. Baju-baju ganti kami ditumpuk dan dijadikan selimut di sela-sela sleeping bag. Kami biarkan saja angin melolong-lolong di luar sana. Kami tertidur dalam pelukan udara beku yang meremukkan.
*****
Pagi-pagi sekali Igo sudah mengguncang tubuh kami. Selepas shalat Subuh, kami melakukan pemanasan sekali lagi di sekitar danau. Sekitar pukul tujuh kami baru berhenti setelah bermandi keringat. Aku berkeliling perkemahan dan memberi pengarahan.
“Inayah, tolong kaubantu Torik memasak sarapan sementara Hana menyeduh jahe. Muqodas, tugasmu menjemur barang bawaan agar tidak lembab sehingga takkan terlalu membebani. Sementara itu aku dan yang lain akan beres-beres tenda. Oke, semua bersiap!”
Setelah membenahi kemah dan briefing sejenak, kami pun merayap maju selangkah demi selangkah menuju camp berikutnya. Kami berjalan cepat-cepat, mengejar waktu.
“Ini baru hari ketiga pendakian, tapi tantangan sudah mulai terasa berat ya?” Hana terengah-engah. “Oksigen terasa menipis.”
“Iya, aku juga mulai sesak napas,” Inayah terbatuk.
Kami kelelahan dengan cepat ketika menghadapi lintasan menuju Pintu Angin. Baru beberapa meter kami harus sudah berhadapan dengan tanjakan terjal yang curam dan melelahkan, tampak begitu menantang. Kerikil dan bebatuan yang berguguran mempersulit langkahku. Beberapa kali Inayah hampir tergelincir, dan dengan sigap Igo berhasil menangkap tangannya. Gadis itu membungkuk penuh terima kasih. Di sebelahku, Torik mendaki dengan penuh semangat. Baginya, tanjakan ini seperti datar saja. Carrier yang berat seakan tak menghalangi tekadnya.
“Kalau kalian capek, bilang saja,” kata Torik seraya meneguk bekal air yang diisi ulang dari Danau Biru. “Nanti kita duduk sejenak untuk beristirahat dan mengatur napas.”
“Kalau jalan seperti ini terus, besok-besok kita super berotot,” kata Harto enteng saat kami menjajaki Tanjakan Aduh Mama, sebuah celah di antara dua tebing batu.
“Berotot? Yang ada malah bengkak,” kata Igo.
Setelah menempuh sekitar seratus meter, jalan menjadi datar dan tak lagi menanjak, hanya sedikit tanjakan ringan yang tidak terlalu terjal. Kami bernapas lega. Sambil melintasi dataran, Muqodas terus memeriksa peralatan GPS-nya dan memimpin jalan. Di atas kami, Puncak Jaya dan Puncak Carstenz sudah mulai terlihat. Kemegahannya tetap tak tampak semakin dekat meski sudah berkilo-kilometer kami tempuh.
Lembah batu membuka di depan kami, diselingi jalur berkerikil di tengah himpitannya yang tidak terlalu lebar. Kami berjalan cepat-cepat saat melalui jalan setapak yang dikepung dua tebing tinggi di kiri-kanannya. Di atasku, sinar matahari mulai tak tampak, terhalang gumpalan kabut. Berjam-jam setelah menyusuri dasar jurang, jalan semakin lebar dan memperlihatkan pemandangan menakjubkan di depan kami. Hamparan benda putih ajaib yang hanya pernah kulihat di foto, kini terpampang di depan mataku.
“Cihuuuy! Salju putih! Salju putih!” Harto melompat-lompat.
“Apa ini mimpi?” Nasuti mencubit pipinya sendiri, nyengir.
Kami serentak bersorak riang dan berlarian di lapangan salju. Harto memegang es dan mengaduk-aduknya dengan jari. Nasuti langsung meraupnya dengan dua tangan, tak sabar mencicipi rasa salju alami. Hana dan Inayah saling melempar bola salju, mengikik riang. Aku berbaring di atas hamparan es, menantang serbuan dingin. Tapi kami tak bisa berlama-lama merayakan pesta, karena pesta sesungguhnya belum dimulai.
Meninggalkan lapangan salju, kami meneruskan pendakian. Lima jam kemudian akhirnya kami tiba di camp induk Lembah Danau-Danau, 4300 meter di atas permukaan laut. Di sana tampak penuh sesak oleh para pendaki lain beserta tenda masing-masing. Bahkan kulihat ada juga pendaki bule di sana.
“Lihat, para pendaki hebat dari seluruh dunia berkumpul,” kata Nasuti, mengawasi para pendaki yang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sorot mata mereka penuh keyakinan, sikap mereka tenang, tampak berpengalaman. “Aku jadi merasa kecil jika melihat mereka. Rasanya, hanya orang-orang terpilih saja yang bisa sampai di puncak.”
“Kau salah, Nas,” kata Harto. “Semua orang bisa mencapai puncak, asal mau berusaha dan bekerja keras. Itulah yang terpenting. Selain itu, kau juga harus memiliki tekad baja dan sikap pantang menyerah. Apapun bisa kita lakukan jika memiliki beberapa hal tadi.”
“Lho, itu kan Kapten Jojo,” kataku, melihat sosok pria bertopi koboi dan berbadan tegap itu duduk di antara pendaki profesional. Aku mengucek mata, tak salah lagi, pasti dia. Kapten tentara itu melihatku, tersenyum dan melambai. Aku mengangguk saja. Mungkin dia ditugaskan mengawal para pendaki, atau mungkin punya agenda mendaki sendiri.
Tanpa mau kalah dengan pendaki lain, kami ikut mendirikan tenda dan menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Inayah langsung sibuk memasak dan menjerang air panas. Harto duduk di sebuah batu yang menghadap jurang, melihat-lihat hasil jepretan kameranya.
Sementara itu, aku dan Nasuti berkeliling melihat persiapan pendaki lain. Dari kilasan percakapan dan perlengkapan yang mereka bawa, aku menebak-nebak apa profesi mereka. Ada atlet panjat tebing, tentara, peneliti, wisatawan, kru stasiun televisi, ahli geologi, mahasiswa pecinta alam, hingga pendaki profesional yang berkali-kali meraih penghargaan. Hawa persaingan mulai terasa memanas ketika masing-masing mengeluarkan perlengkapan mendaki terbaik mereka. Ada yang membawa peralatan lengkap, namun ada juga yang hanya membawa tali dan carabiner saja. Nekat betul orang ini. Ketika kami lewat di antara tenda-tenda, beberapa pendaki menatap dengan tatapan heran, bahkan meremehkan. Kami menoleh ketika seorang pria berwajah lokal memanggil kami.
“Hei, anak SMA yang di sana! Kalian pernah mendaki Semeru? Raung?” pria itu tergelak. “Kami kaget sekali melihat pendaki semuda kalian muncul di camp ini. Kalian beruntung bisa sampai sini, tapi trek berikutnya lebih berbahaya, Nak. Aku ragu kalian bisa sampai di puncak hidup-hidup. Lihat, ini sertifikat kami, berbagai lencana dan medali penghargaan yang kami kumpulkan. Kami profesional, Nak. Kilimanjaro, Everest, Elbrus, sudah puluhan kali kami taklukkan. Lihat pria yang di sana itu? Yang tangannya diperban? Jari-jarinya dipotong dan dia juga hampir kehilangan sebelah kaki, akibat terjebak di longsor salju dan dagingnya membusuk. Meski begitu, dia mencoba ikut pendakian lagi tahun ini. Bagaimanapun dia pendaki profesional, beda dengan kalian. Jangan main-main dengan alam liar, Nak. Kalian masih terlalu muda. Sana, bikin istana pasir saja di rumah.”
Pria itu terbahak, melambaikan tangan menyuruh pergi. Rekannya menyikut, berkali-kali minta maaf pada kami. Aku dan Nasuti merapatkan jaket, meninggalkan mereka dengan hati panas. Aku lebih jengkel lagi karena disebut anak SMA. Apa-apaan orang itu? Huh, akan kami buktikan kalau kami juga bisa.
Kami duduk termenung di atas batu, mengamati matahari tersungkur di balik gigi-gigi perbukitan. Malam itu kami tidur meringkuk, kepalaku sakit. Angin sedingin es menggempur tenda kami, memaksa masuk untuk menggelitik kami yang terlanjur kedinginan.
*****
Udara beku begitu menyengat sewaktu kami terjaga keesokan harinya. Pagi-pagi sekali kami langsung berkeliling base camp dan melakukan pemanasan, lalu kembali ke tenda untuk berkemas. Anehnya suasana terasa sepi, tak seperti biasa. Aku sadar beberapa tempat tidur kosong tak berpenghuni.
“Muqodas mana?” tanyaku.
Igo angkat bahu, menatap tenda satunya. “Hana juga nggak ada.”
“Jangan-jangan, mereka pergi duluan ke puncak?” kata Nasuti.
“Masa sih? Paling-paling mereka masih di sekitar sini,” kata Harto.
Kami mencari mereka di sekitar perkemahan, memanggil kesana-kemari, bertanya pada pendaki lain, namun Hana dan Muqodas tak ditemukan. Tampaknya kedua orang itu memang iseng mendahului kami. Aku tak meragukan jika Muqodas berani pergi sendiri, dia akan baik-baik saja. Tapi yang gawat adalah dia membawa Hana.
“Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah tidak sebaiknya kita susul mereka?” Inayah menatap kami bergantian. “Kasihan mereka kalau ada apa-apa.”
“Eh, siapa yang semalam tidur di sini?” tanya Igo, membungkuk.
Aku melihat ke bawah. “Kayaknya Muqodas, kenapa?”
Igo berdiri, memperlihatkan sesuatu pada kami, sebuah kemasan plastik kecil. “Lihat, ada bungkus obat di bawah matras. Aku tak tahu obat apa ini, bentuknya aneh. Memangnya Muqodas sakit apa? Bukannya sejak kemarin dia sehat-sehat saja?”
“Sudah, jangan berpikir yang aneh-aneh,” kata Harto. “Mungkin obat sakit kepala. Lagian itu nggak penting sekarang. Kita harus mengejar mereka sebelum terlalu jauh.”
“Bagaimana menurutmu, Lutfi?” tanya Igo, mengantongi obat itu.
Semua memandangku, menunggu keputusanku. Sejak awal perjalanan, mereka selalu menanyakan pendapatku, seakan mereka sudah resmi mengangkatku sebagai kapten. Aku berpikir sejenak, menunduk, lalu mendongak penuh keyakinan, mengambil keputusan.
“Kita susul mereka!” kataku penuh tekad. Mereka berseru seraya mengangkat tinju, semua menyambut dengan antusias. Harto nyengir lebar.
"Aye, Kapten!”
Kami mengemas tenda diam-diam, lalu meninggalkan camp, bergerak memutari tenda pendaki lain. Hanya satu pendaki yang agaknya mengawasi kami. Kapten Jojo, si pria bertopi koboi itu! Ketika kami lewat, tatapannya seperti mengikuti. Kami buru-buru menjauh, melewati tanjakan, mencari jalur yang mungkin dilalui Muqodas dan Hana, melacak jejak-jejak di atas salju. Aku berharap semoga saja mereka belum terlalu jauh. Akhirnya kami berhasil menemukan mereka tengah duduk di sebuah batu, tak jauh dari camp.
“Sudah kuduga, kalian pasti menyusulku,” kata Muqodas, menunjuk wajah-wajah kami sambil menyeringai. “Kalian kira kami sungguhan meninggalkan kalian ya?”
“Dasar, isengmu itu kebangetan, tahu!” Harto terengah, ikut duduk.
“Aku sudah bilang jangan, tapi dia memaksaku ikut!” kata Hana kesal.
Aku menggeleng saja. Tanpa menunggu kami, Muqodas berbalik dan memimpin jalan, masih terbahak. Torik berjalan setelahnya. Akhirnya kami melanjutkan pendakian, mengikuti mereka menapaki batu-batu terjal, menuju camp terakhir di Lembah Kuning. Di belakang, Hana dan Inayah berjalan beriringan, entah membicarakan apa.
Aku berjalan paling depan, memimpin. Semangatku masih meluap-luap meski kakiku mulai terasa pegal. Beberapa jam kemudian, rasa capekku tak bisa lagi diajak kompromi. Ketika menoleh ke belakang, kulihat teman-temanku sama payahnya, dan Inayah tampaknya sudah kelelahan. Gadis itu berjalan gontai dan terseok-seok, jauh tertinggal di belakang. Igo bersedia menunggu dan memapahnya.
“Ayo, sedikit lagi, kamu pasti bisa,” Igo menyemangatinya.
Ketika Inayah tampaknya hampir pingsan, Igo menaikkan gadis itu ke punggungnya. Tas carrier mereka yang tak terlalu berat diserahkan padaku dan Harto. Semangat membara tampak di mata Igo yang berapi-api ketika dia merangsek maju. Di punggungnya, Inayah tersenyum lemah, tampak senang. Kami terus berjalan hingga segaris kabut menutupi kaki langit, dan akhirnya tanah menjadi datar, memaksa kami berhenti. Aku tersenyum lega. Kami telah tiba di Lembah Kuning, camp terakhir yang berhadapan dengan tebing menjulang, rintangan teberat kami.
“Kita bermalam di sini,” aku memutuskan.
Kami shalat maghrib dan isya bergiliran di dalam tenda. Karena tak ada air, kami ber-tayammum menggunakan debu. Untuk bersuci selepas buang air kecil pun terpaksa menggunakan batu. Kami meringkuk seperti batang korek api dalam sleeping bag. Dingin menjalar pelan merayapi leher dan pipiku. Termometer menunjukkan suhu nol derajat.
Baru beberapa jam terlelap, sesuatu yang gawat terjadi. Inayah menggigil kedinginan, mengigau dengan mata terpejam. Hana yang setenda dengannya berseru panik memanggil kami. Igo menyentuh dahi istrinya, menatapnya cemas. Ini sungguh gawat, agaknya dia terserang hipotermia. Kami semua kedinginan, tapi kondisi Inayah yang paling parah. Medan terjal atau tebing batu memang bukan masalah bagi gadis pemetik stroberi ini, tapi suhu dingin tak sebaik itu padanya. Bekas lukanya juga mengkhawatirkan.
“Tak ada cara lain, sepertinya aku harus mengantar Inayah turun,” kata Igo. “Besok, kalian teruskan saja pendakian tanpa kami.”
Saat Igo mengusulkan padaku untuk minta bantuan helikopter, Inayah tiba-tiba duduk dan memegang tangan suaminya. Tekadnya membara saat dia menatap kami, bersikeras ikut sampai puncak, tak mau jadi beban bagi kami. Untuk membuktikan diri, dia bahkan melepas jaketnya dan berjalan ke luar tenda, bilang kalau dirinya bukan gadis lemah. Igo menelan ludah, mengajaknya masuk dan menghiburnya, bilang tak apa-apa. Hana membuatkannya minuman jahe, Torik membagikan daun gatalnya untuk mengurangi kebekuan. Efeknya sangat manjur, setelah itu Inayah agak baikan, mulai terbiasa dengan suhu dingin.
“Dia akan melewati semua ini, tenang saja,” kataku, menepuk bahu Igo. “Dia wanita tangguh, tak pernah mengeluh selama mengikuti semua perjalanan kita, apapun yang terjadi, bukan? Inayah tahu apa yang dia lakukan, dia kan dokter. Percayalah pada istrimu.”
Igo mengangguk, memutuskan tak jadi turun, berpesan pada Hana agar menjaganya. Inayah menatapku penuh terima kasih, mengingat selama ini aku selalu mendukungnya.
*****
Syukurlah, ketika terbangun esok paginya, kondisi Inayah kembali bugar. Dia memohon agar diizinkan ikut meneruskan pendakian, bilang kalau memanjat tebing mudah saja baginya.
Setelah briefing singkat, kami meninggalkan tas carrier di tenda dan bersiap menjajal rintangan selanjutnya. Tebing curam yang tampak dingin menghadang kami seperti bayangan raksasa. Aku menatap lurus ke depan, mendongak sambil memicingkan mata, mengira-ngira berapa ketinggiannya. Mungkin sekitar 500 meter, dengan kemiringan mencapai 80 derajat. Satu-satunya cara melewatinya adalah dengan memanjat vertikal menggunakan teknik ascending, mengikuti tali pengaman yang sudah terpasang di dinding tebing.
Muqodas membagi-bagikan peralatan khusus yang kami beli di kota. Segera saja kami memakai sarung tangan wol, helm, buff, dan kacamata pelindung yang membuat kami terlihat seperti pembalap. Tak lupa kami juga membawa kapak es, harness, jumar penjepit, dan crampon paku yang dipasang di sepatu.
Muqodas yang sudah berpengalaman kutunjuk jadi pendaki pertama. Dia melangkah maju, menusukkan kapak es di dinding tebing yang keras, menguji kekokohan batuannya, lalu mulai memanjat. Agar tidak merosot, dia menjepitkan jumar di pinggangnya ke tali pengaman. Aku kagum dengan kecepatannya saat dia dengan mantap menapaki batuan licin itu tanpa takut. Sepatunya yang berduri menapaki dinding saat dia memanjat semakin tinggi, hingga tak lama kemudian dia tiba di teras bebatuan yang cukup datar. Menganggap lokasi sudah aman, dia memberi isyarat agar kami naik, utamakan wanita duluan.
Inayah tampak tertantang. Seperti saat di Maros dulu, dia menunjukkan keahliannya memanjat yang membuat kami tercengang. Gadis itu enteng saja memanjat, bahkan lebih cepat dibanding Hana yang empat tahun ikut grup Pecinta Alam. Harto dan Nasuti saling pandang, teringat aksi Inayah saat menaiki tower tempo hari. Di balik sikapnya yang lembut, ternyata dia tangguh juga. Meski lukanya belum pulih dan sempat kena hipotermia, kini dia membuktikan ucapannya. Igo menatap istrinya kagum, menyusul naik sambil menjaganya.
Dengan tegang aku mengawasi teman-teman naik satu persatu, hingga tiba giliranku. Aku memastikan harness terpasang dengan benar, mulai mencengkeram ceruk batu dan perlahan menambah ketinggian, berkonsentrasi saat mengikuti jalur tali tanpa melihat ke bawah. Dalam hati aku bersyukur saat itu tak ada badai. Di atas, Igo mengulurkan tangan dan menarikku. Akhirnya aku tiba dengan selamat di Teras Pertama, tempat kami beristirahat sejenak sambil tetap bergantung di tali. Tapi itu belum selesai, karena masih ada dinding yang lebih tinggi di atas kami.
Kami kembali beraksi, merangkak naik selama sekitar satu jam lebih menuju Teras Besar, area terbuka yang cukup lebar meski medannya masih miring. Dari situ kami masih harus merayap naik, menghadapi pertempuran fisik dan batin yang menguji kesabaran. Kebekuan menyergap sumsum ketika kami mendaki dinding batu satu demi satu. Setelah menaklukkan semua tebing, akhirnya kami tiba di medan gigir alias Carstenz Ridge, sebuah dataran yang cukup lapang di puncak tebing. Kami terduduk lega, bersorak setelah berjam-jam mendaki tebing yang menguras tenaga. Dari sini, Puncak Carstenz Pyramid sudah terlihat jelas, hanya perlu trekking selama 15 menit untuk menuju ke sana.
Salju abadi menyelimuti tempat ini. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya warna putih. Kami memakai kacamata pelindung dan masker untuk menghindari terpaan salju, berjalan hati-hati menginjak salju empuk, merangsek maju menyusuri puncak tebing. Sesekali aku menoleh ke belakang. Danau Biru tak lebih dari titik kecil di belakang kami. Jurang menganga di kiri-kanan kami, siap menelan siapa saja yang cukup ceroboh tergelincir di atasnya. Bebatuan beku licin berserakan di sepanjang jalur. Bila tidak hati-hati melangkah, kami bisa terpeleset dan pulang tinggal nama.
“Ayo, percepat langkah kalian!” teriakku.
Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Beberapa saat lagi kami akan tiba di puncak. Tinggal satu rintangan lagi yang harus kami lewati. Jembatan Tyrolean alias Kandang Babi yang terkenal itu. Di depan kami, jurang gelap tak berdasar menganga memisahkan kami dan daratan di sana, siap menelan siapapun yang lengah. Lebarnya sekitar 20 meter. Nasuti menjatuhkan batu untuk mengira kedalamannya. Lama kami menunggu, suaranya bahkan tak terdengar. Konon dalamnya mencapai 500 meter. Ada jembatan tali sederhana yang menghubungkan tanah tempat kami berpijak dengan tebing batu di seberang sana, terdiri dari dua garis tali yang posisinya paralel, dua tambang di atas yang berfungsi sebagai pegangan dan satu kabel besi di bawah untuk pijakan.
Kali ini giliran Torik yang unjuk gigi duluan. Dia mengeluarkan palu dan membungkuk di tepi jurang, mengetuk baut pada batu gamping, memeriksa kekokohan instalasi penopang jembatan yang dibuat Mapala UI itu. Setelah cukup yakin, kami bersiap melewati patahan di antara dua tebing itu. Torik si pemberani melintasi jembatan dengan mudah tanpa berpijak ke tali dan berhasil tiba di seberang. Aku menyusul, mengaitkan carabiner pada tali dan bergerak pelan, bergayut pada tali. Rasanya menegangkan, aku tak berani melihat ke bawah, seakan inilah jembatan shiratal mustaqim versi dunia.
Setelah aku tiba di seberang, giliran yang lain menyusul. Igo dengan cepat meniti jembatan, disusul Inayah yang mulai maju sambil berpegangan pada tambang. Gadis itu memejamkan mata, tampak ragu. Kami berteriak ketakutan saat dia gagal melompat di saat terakhir dan tubuhnya meluncur jatuh. Untung saja lajunya ditahan carabiner dan harness yang mengikat pinggangnya.
“Hampir saja,” dia tersendat, dengan cepat merangkak naik.
“Pegangan yang erat ya,” kata Igo pelan.
Dengan was-was, kami membantu Igo menariknya. Inayah mengelus dada, napasnya naik turun saat nyawanya berhasil kami selamatkan. Aku menatap ke depan. Puncak harusnya tak jauh lagi. Kami meneruskan berjalan di dataran yang tak terlalu curam, dengan es yang terasa keras di kaki kami. Dua kali lagi kami melewati jurang yang tak terlalu lebar.
Aku menguatkan tekad, anggap saja puncak tinggal satu meter lagi meski kenyataannya masih cukup jauh. Aku terus melangkah, bertumpu pada tongkat, meski energiku hampir habis. Napasku sesak, dan kakiku seperti digayuti beban berton-ton. Perjuangan kami begitu berat, namun aku takkan menyerah. Sejauh apapun pasti akan kutempuh. Aku pasti kuat, lihat saja nanti. Sedikit lagi... sedikit lagi...
Aku menegakkan diri, tak percaya melihat pemandangan di depanku.
Akhirnya, setelah berjam-jam bertempur habis-habisan, kami menginjakkan kaki di tempat datar, lapang, dan tak tampak ada dataran yang mengungguli ketinggian tempat ini. Inilah tempat tertinggi, puncak dari semua puncak. Di sekitar kami, dunia tampak begitu kecil dilihat dari ketinggian 4884 meter. Sebuah plat besi penanda puncak menyambut kami. Kelelahan yang kami rasakan beberapa saat lalu menguap sudah. Ekspedisi Khatulistiwa telah berhasil kami selesaikan.
“KITA SAMPAI!” Harto melompat tinggi-tinggi, mengacungkan tinju. “KITA TIBA DI PUNCAK!”
Aku berdiri bangga dan mengumandangkan takbir berkali-kali. Teman-teman bersorak penuh kemenangan, saling berangkulan dan melonjak-lonjak. Inayah sampai jatuh berlutut dan tersedu-sedu, terharu. Berbagai tantangan berat telah kami lewati. Perjuangan selama sembilan hari ini terbayar sudah. Misi telah selesai, kami berhasil tiba tepat waktu. Dengan kamera saku yang dipinjam dari Igo, Harto mengabadikan momen terbaik yang pernah kami alami sejak memulai ekspedisi tiga bulan lalu. Inilah final, inilah akhir perjalanan kami.
“Kurang ke kanan sedikit... yak, Lutfi, berdiri di tengah dan letakkan kakimu di atas batu. Nasuti, hadap sini, jangan meleng saja. Para wanita di depan, perlihatkan senyum termanis kalian. Torik dan Muqodas, karena kalian berbadan besar, berdirilah di pinggir. Igo, berhentilah cemberut atau ku-crop wajahmu dari foto nanti.”
Harto mengatur kami saat berpose di belakang sebuah batu dengan latar belakang awan-awan putih. Harto buru-buru berlari dan ikut berpose sebelum terdengar bunyi klik. Kami semua tersenyum lebar memamerkan gigi. Setelah berfoto, kami berlarian di sekitar area puncak seperti anak TK kegirangan mengejar balon. Aku mencium plat besi penanda puncak dan bersujud syukur. Nasuti dan Harto berjingkrak-jingkrak tak karuan, kulihat mereka juga menuliskan nama kami berdelapan di atas batu datar untuk kenang-kenangan. Muqodas memarahi mereka, melarang mengotori lingkungan. Torik menjelaskan bahwa membuang sampah sembarangan dan vandalisme adalah pantangan bagi pecinta alam sejati. Igo dan Inayah asyik berduaan di ujung sana. Hana berdiri menatapku.
“Kau sudah baca suratku kan?” dia tersenyum.
“Belum, memangnya kenapa?” tanyaku.
“Ah, nggak apa-apa,” katanya, terlihat agak kecewa.
“Lho, kamu kenapa? Hidungmu berdarah. Kamu baik-baik saja, kan?”
“Apa? Oh,” dia mengusap hidungnya, melihat cairan merah di jemarinya. “Ya, jujur saja aku kelelahan, tapi aku tak apa-apa kok, tenang saja.”
Gadis itu tersenyum menentramkan, coba meyakinkanku, lalu berbalik pergi. Akhir-akhir ini aku merasa sikapnya agak aneh.
Aku ingat sesuatu. Perlahan, kubuka tas kecilku dan kukeluarkan benda yang kubawa jauh-jauh dari Surabaya, bendera milik Pak Soetomo sang veteran. Sesuai janji, kami segera mengibarkannya di tempat ini. Aku lega bisa melunasi janjiku pada Bu Qoriah. Muqodas bertugas memegangi bendera sementara kami berbaris rapi dalam posisi siap. Tatapan kami mengikuti bendera yang berkibar tertiup angin. Serentak kami memberi hormat, menyanyikan lagu kebangsaan tercinta, Indonesia Raya, dengan Hana bertindak sebagai dirijen. Suaraku hilang timbul dalam desau angin, mendayu-dayu pelan, namun penuh khidmat. Air mataku berguguran. Setelah semua yang kulalui, aku baru menyadari betapa mahalnya negeri ini. Betapa berat perjuangan para pendahulu untuk merebutnya dari tangan penjajah.
“Pak Soetomo pasti bangga pada kita,” kata Harto, saat bendera itu berkibar bebas di titik tertinggi negeri ini. Dengan handycam, dia mengabadikan upacara kecil-kecilan kami.
“Ya, aku yakin beliau sedang tersenyum di alam sana,” kataku, memejamkan mata, merasakan bayangan Pak Soetomo mengambang di udara, menepuk-nepuk bahuku.
Rasanya pencapaian ini lebih menakjubkan daripada saat memenangkan kejuaraan tingkat provinsi beberapa waktu lalu. Aku merasa puas, merasa telah menaklukkan dunia, atau lebih tepatnya diriku sendiri, walaupun di sini tak ada teriakan suporter. Jika mengingat semua perjuangan yang telah kami lakukan untuk tiba di sini, dan rintangan-rintangan berat yang harus kami hadapi, kemenangan ini sungguh manis rasanya. Aku mengangkat tangan ke dekat telinga, menarik napas, lalu mengumandangkan azan. Kebetulan sudah masuk waktu maghrib. Teman-teman terdiam, mendengarkan dengan khusyuk. Entah sebelumnya ada pendaki yang pernah melakukan ini atau tidak.
“Perjalanan berat dan panjang telah kita tuntaskan,” kata Igo. “Kita bisa sejauh ini karena kita bertindak dan berjuang lebih keras dari yang lain. Lihat saja, dari sekian banyak pendaki profesional yang datang, hanya kita yang berhasil duluan sampai di sini. Awalnya aku sempat ragu kita akan berhasil, tapi seperti yang kita lihat sekarang, kita sampai.”
“Eh, kenapa cemberut saja?” aku menanyai Muqodas yang masih memegang bendera. “Datar-datar saja mukamu, ketawa kek.”
“Tahu nggak, apa yang kupikirkan waktu tiba di sini?” katanya. “Sudah jauh-jauh mendaki, berlelah-lelah... eh pas sampai puncak, masa pemandangannya begini doang? Masih bagusan puncak Rinjani kalau menurutku.”
“Kurang bersyukur kamu,” kata Harto. “Orang kayak kamu nih yang bikin perjalanan nggak asyik. Ke laut dibilang bosen, ke gua dibilang jelek, ke gunung dibilang biasa aja. Maunya yang kayak gimana sih?”
“Tahu tuh Muqodas, ciptaan Tuhan kok diledek,” kata Nasuti.
Sementara itu, Hana dan Inayah asyik mengikik riang.
“Kamu hebat lho, Inayah,” kata Hana. “Tadinya aku sempat khawatir sama kamu, takut lukamu kenapa-napa dan keteteran. Apalagi kamu nggak ada basic mendaki gunung es. Ternyata kamu... wah, pendaki cewek paling tangguh yang pernah kutemui.”
“Ah, Mbak Hana bisa aja,” Inayah tersenyum. “Tadinya saya juga mau nyerah kok, udah capek banget waktu mendaki tebing itu. Bekas luka saya juga masih agak sakit. Tapi saya udah bertekad, nggak mau kalah sama pendaki lain. Lagian kalau ada apa-apa kan tinggal panggil helikopter, hehe.”
“Ih, kamu lucu deh, ngegemesin,” Hana mencubit pipinya.
“Ehehe, gitu ya Mbak?” Inayah mengusap pipinya.
“Permisi Nona-nona, boleh kuminta foto kalian sekali lagi?” kata Harto. “Jarang-jarang lho ada pendaki wanita yang berhasil ke puncak Carstenz. Malah bisa jadi kalian pendaki berhijab pertama yang tiba di sini. Boleh kan?”
“Oh, boleh,” jawab kedua gadis itu, tersenyum.
Setelah puas bersenang-senang, Aku menatap bendera itu untuk terakhir kali. Teman-temanku tak ada yang bicara. Semua tampak masih diselimuti keharuan—kecuali Muqodas. Momen ini takkan pernah kami lupakan seumur hidup. Akhirnya kami harus pulang.
“Waktunya turun, Teman-teman,” kata Harto, menatap pemandangan di kejauhan. “Sedih ya, pulang. Kapan kira-kira kita bisa ke sini lagi?”
Seperti dugaanku, menuruni gunung memang lebih sulit. Kami harus berhati-hati saat menyusuri medan berbatu yang sangat rapuh. Sesekali aku melompat saat batu-batu yang kuinjak menggelincir menuruni tanah yang miring. Yang tersulit adalah saat menuruni tebing, kami harus ekstra hati-hati mengatur penjepit, dan Nasuti sempat menggelosor beberapa meter akibat kelelahan, hanya mencengkeram tali tanpa berpijak ke batu.
Saat langit berubah gelap, kami bergegas turun karena khawatir badai segera datang. Malam semakin pekat saat kami tiba di dasar tebing, dan anehnya kami tak bertemu pendaki lain. Tampaknya hanya kami pendaki yang pergi ke puncak, entah ke mana perginya orang-orang yang kami temui kemarin. Firasatku mulai tak enak. Aku masih menatap langit ketika awan hitam berarak menghalangi bulan, menjadikan dunia di bawahnya gelap gulita. Kabut mulai turun, angin bertiup kencang seakan mengundang badai.
“Ini gawat,” kataku. “Lihat, hujan es!”
Langit murka, angin meraung-raung kejam melibas sekujur tubuh. Dalam sekejap, pegunungan ini mendadak membenci kami, delapan penjelajah nekat yang kebingungan di punggungnya yang curam bersalju. Aku gemetar walau jaketku berjubel hingga lima lapis, lilitan syal tebal di leher tak membantuku sama sekali. Sialnya, sepatuku melesak ke dalam salju hingga kaus kakiku basah. Di sebelahku Harto menggigil hebat, wajahnya kebiruan menahan udara beku yang menggila. Keadaan Igo, Nasuti, Torik, Muqodas, Inayah, dan Hana tak kalah mengenaskan. Cuaca yang semula tenang berubah menjadi badai mematikan, tak lagi bersahabat. Di saat seperti ini, kami merindukan hangatnya cahaya mentari walau ia telah sirna berjam-jam lalu.
“Lebih baik kita cari tempat berlindung.”
Aku bergerak mendahului teman-temanku, memicingkan mata seraya melindunginya dari terpaan angin. Tetap saja aku tak bisa melihat apa-apa. Cahaya dari headlamp berpendar lemah, tak sanggup menembus kegelapan yang merajalela. Pemandangan di sekitar mengabur karena dahsyatnya badai. Seseorang berteriak di belakang, aku menoleh. Sorban Nasuti yang berwarna putih itu terbang tertiup angin. Ia mencoba menangkapnya, namun sorban itu terlepas begitu saja dari jari-jarinya. Ia berlari mengejar, meninggalkan jejak-jejak dalam di atas salju. Kami segera mengikuti. Berpisah dalam keadaan seperti ini adalah pilihan buruk.
“Hei Teman-teman, coba kemari! Ada gua di atas,” teriaknya.
Aku mendongak dan mengacungkan senter. Di atas sana memang ada cekungan batu yang cukup lebar. Akhirnya ada tempat berlindung. Namun medannya terlalu curam dan artinya kami harus berjuang untuk mencapai tempat itu. Sambil menguatkan tekad, kupaksa kaki ini melangkah. Angin menghantam bagai serbuan gajah, membuat sulit bernapas dan mempersulit langkah kami yang sudah terseok-seok, menambah kesengsaraan kami.
Hujan salju dengan kejam memerciki punggung bagai serangan peluru, perlahan melumpuhkan sel syaraf kami. Tangan dan kakiku mati rasa. Otot-ototku menjerit protes saat kupaksa kaki berjalan. Pandangan berkunang-kunang, pendengaran menjadi sayup-sayup. Desau angin bagai bisikan samar di telinga, seakan maut sendiri yang datang memberi kabar kematian. Namun aku bertekad bulat takkan membiarkan siapapun di antara kami mati, setidaknya jangan sekarang.
“Ayo Teman-teman, sedikit lagi,” kataku, melindungi wajah dari terpaan salju seraya membiarkan yang lain berjalan mendahului. Beberapa kali bongkahan es sebesar kelereng menghantam kepalaku, sakit sekali. Malah ada juga yang seukuran bola tenis. Kami hampir tiba di cekungan batu ketika aku menyadari ada anggota yang kurang.
“Hana? Di mana Hana?” teriakku.
Teman-teman menoleh, saling pandang. Mungkinkah Hana terjatuh? Aku langsung membalik arah, bersusah payah menerobos badai, mencari-cari di antara salju yang beterbangan. Kulihat Hana tergeletak pingsan di atas salju, tubuhnya setengah terkubur es.
“Masya Allah! Hana!” aku berteriak, menghambur dan membungkuk di atas gadis itu. Perlahan aku membalik tubuhnya, terkesiap melihat dahinya berdarah terhantam bongkahan es. Matanya yang setengah terpejam menatapku nanar. Suaranya terdengar lemah.
“Lutfi... aku tak kuat lagi... aku ingin pulang.”
“Tenanglah, aku akan membawamu,” kataku, melingkarkan lengannya di bahuku. Aku panik bukan main, tak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Kalimat zikir dan doa tak lepas dari lisanku, berharap kami bisa pulang dengan selamat. Hana mengerang pelan, menatapku lurus-lurus. Kemudian, perlahan matanya terpejam, tubuhnya melemas.
“Oh, tidak! Hana, bertahanlah!”
Kuguncang tubuhnya, namun gadis itu tak bergerak, lunglai. Air mataku mengalir. Segera kunaikkan dia ke punggungku, mencoba berjalan membelah salju. Sayangnya aku tak bisa melihat apa-apa di depanku, semua tampak kabur akibat dahsyatnya badai. Aku berteriak memanggil yang lain, tapi suaraku layu. Langkahku terasa berat dan terseok-seok. Hujan es yang terpercik membasahi kami, perlahan turun semakin deras, seakan langit pun berduka. Salju yang licin membuatku terpeleset dan jatuh. Aku berseru tertahan saat Hana terlepas dari punggungku dan ikut tersungkur, wajahnya semakin pucat dan bibirnya membiru. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku terasa kaku dan mati rasa. Siapa saja, tolonglah.
Aku menggertakkan gigi, mengerahkan sisa-sisa tenagaku dan kembali berdiri, berjalan menembus badai. Aku sudah berjanji, takkan membiarkan siapapun di antara kami mati. Aku sendiri sudah kepayahan, kakiku ngilu dan sekujur tubuhku kebas, tapi aku terus melangkah. Dahsyatnya terpaan angin membuat jalanku melenceng, tapi aku yakin sudah dekat ke mulut gua karena sayup-sayup terdengar teriakan Harto. Aku sedikit lega saat melihat teman-teman menghampiriku. Tubuhku ambruk untuk kedua kalinya, terlalu lelah untuk berjalan.
Aku merasa tangan-tangan memegang pundakku, mendengar seruan panik mereka, dan aku menurut saja ketika Harto menarikku berdiri dan menuntun ke gua. Torik menggendong Hana, membaringkannya di tempat yang lebih terlindung. Aku duduk menggigil, nanar mengawasi saat Inayah mengeluarkan kotak P3K, memeriksa luka di dahi Hana, memegang urat nadinya. Gadis itu menggeleng. Aku tahu ini pertanda buruk.
“Pendarahannya sudah dihentikan, tapi masalahnya bukan itu,” kata Inayah. “Dampak luka di dahinya harusnya tak separah ini, kecuali Mbak Hana punya riwayat penyakit sejak awal. Mungkinkah...” Wajahnya panik saat menatap Igo, yang sama pucatnya. Igo merogoh jaket, mengeluarkan bungkus obat yang ditemukannya kemarin di bawah matras Muqodas.
“Itu bukan punyaku,” kata Muqodas. “Obat itu ada di tas kecil yang dititipkan Hana padaku. Mungkin terjatuh saat aku packing kemarin. Aku juga tak tahu itu obat apa.”
“Ini obat penghilang rasa sakit, kemarin aku tak sempat memeriksanya dengan jelas,” kata Inayah panik. “Penyakitnya serius sekali, nyawa Mbak Hana dalam bahaya. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit.”
“Tapi, masih ada badai, kita tak bisa ke mana-mana,” kata Harto.
“Sial, apa tak ada yang bisa kita lakukan?” geram Nasuti.
Kami semua terpaku. Aku ingat saat Hana mimisan beberapa jam lalu, dan jika aku tidak salah, rasanya dia juga agak pucat beberapa hari terakhir. Torik juga bercerita bahwa sejak kami berpisah jalan, Hana beberapa kali minta izin ke rumah sakit. Mungkinkah selama ini Hana mengidap penyakit parah, berusaha menutupinya dan berpura-pura sehat di depan kami? Inayah membungkuk di atas tubuh Hana, tersedu tanpa suara. Badai masih mengamuk di luar sana, tak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu dan berdoa. Sepanjang malam, kami meringkuk di gua dalam kesunyian, tak ada yang bicara. Semua larut dalam kedukaan yang berbalut keputusasaan. Bisakah kami pulang dengan selamat?
*****
Keesokan harinya seorang pria bermantel tebal muncul di mulut gua dan menemukan kami. Ternyata Kapten Jojo, tentara bertopi koboi itu. Selama ini dia mengawasi kami. Dia curiga karena ada beberapa pendaki yang tak terlihat saat rombongan menuruni gunung. Kecurigaannya benar saat menemukan kami terjebak di sini.
“Maaf, aku baru memeriksa sekarang karena jalur pendakian terhalang badai,” katanya. “Para pendaki lain langsung turun setelah ada peringatan badai. Aku sungguh menyesal tidak segera menyusul dan memberitahu kalian. Kukira kalian sudah tahu akan ada badai.”
“Tolong selamatkan Hana,” kataku pelan, menggigil, menoleh ke arah teman-temanku. Kondisi kami mengenaskan, hanya berkemul jaket dan sleeping bag seadanya, bertahan pada suhu di bawah minus sepuluh derajat. Untunglah sekarang badai sudah mereda.
Kapten Jojo segera menghubungi anak buahnya, meminta pertolongan. Tak lama kemudian helikopter TNI datang bersama tim medis. Hana langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dia masih tak sadarkan diri meski tim dokter sudah memberikan perawatan terbaik. Kami patuh saat dokter menyarankan agar dia dipindahkan ke rumah sakit Ibukota. Wajah Hana yang pucat terus terbayang di pikiranku. Kini kami harus pulang dengan menanggung kekecewaan. Tak pernah kusangka ekspedisi kami akan berakhir tragis dan menyisakan beribu penyesalan seperti ini.
*****


 radenbumerang
radenbumerang





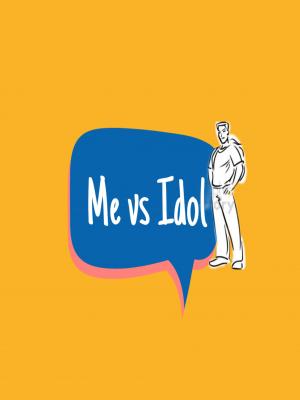
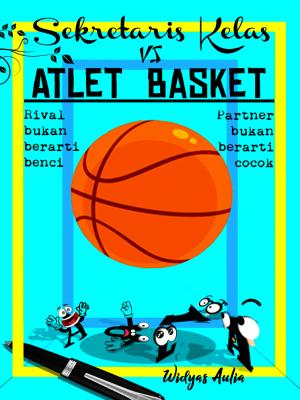



Iya juga yah, satu bab aja sepanjang ini... makasih masukannya Mas AlifAliss, mungkin ke depannya saya bagi per bab aja biar lebih pendek.