BAB 14. TRAGEDI EMPAT RAJA
HARI KE-65, SORONG
Sesuai janji, pukul lima sore kami menunggu empat teman kami dari regu pertama—Hana, Torik, Muqodas dan Zhen—di Bandara Jeffman, Sorong. Lama kami menunggu, mungkin sekitar dua jam yang membosankan. Kemudian, setelah bertukar pesan singkat lewat sms, kami melihat mereka muncul dengan senyum bahagia. Gelombang kegembiraan menyapuku ketika mereka menghampiri dan memeluk kami erat.
“Aku sangat merindukan kalian, meski hanya beberapa hari berpisah jalan,” kataku. Selain Zhen dan Muqodas, aku sadar banyak perubahan yang terjadi pada fisik mereka. Semuanya tampak makmur. Torik memangkas rambutnya dan kulitnya jadi hitam karena lama menyelam di laut. Yang paling membuatku kagum, Hana memakai jilbab! Sekarang aku tahu kenapa dia tak lagi memposting foto. Muslimah yang baik harusnya memang seperti itu.
“Senang bertemu lagi, Kawan,” kata Torik, mengguncang tanganku. “Gadis itu siapa?” Dia menunjuk Inayah. Zhen dan Muqodas juga memerhatikannya dengan tatapan tertarik.
“Istri tersayangnya Bang Igo,” celetuk Harto. Igo mendelik padanya.
“Oh, jadi ini orangnya, anggota baru yang ikut ekspedisi kita,” kata Zhen.
“Wah, hebat kamu, Igo, bisa dapetin cewek cakep kayak dia. Kenalin dong,” Muqodas nimbrung, mengedipkan sebelah mata. Inayah tersenyum dan mengangguk sopan saat para pria hendak menyalaminya. Semua ditolaknya dengan salam jarak jauh.
“Jangan pegang-pegang, bukan muhrim,” kata Igo, mengusir mereka. “Jangan samakan dia dengan gadis lain. Dia ini anak baik-baik, tahu.”
“Hai, senang bertemu denganmu,” kata Hana, menyalami Inayah dan memeluknya, bertukar sentuhan di pipi. Dalam sekejap, Hana langsung akrab dengannya karena merasa menemukan teman seperjalanan wanita. Aku juga sadar sikap Hana jadi lebih feminim dari biasanya, meski agaknya masih betah mengenakan celana jeans. Ia juga memakai kacamata sebagai tambahan penampilan barunya.
“Apa yang membuat Hana tertarik memakai jilbab?” Nasuti menyenggol Torik. “Apa kau yang menasehatinya?”
“Entahlah, aku juga tak tahu kenapa dia tiba-tiba insaf. Mungkin dia salah makan atau apa. Sejak beberapa hari lalu, dia terus menulis sesuatu di bukunya. Dia juga sering melamun, entah memikirkan apa. Sejak itulah dia mulai berhijab. Tapi itu bagus bukan?”
Sementara itu, aku menagih janji Muqodas.
“Gimana perjanjian awal kita, eh? Jangan bilang kau lupa. Kelompokku sampai lebih dulu di Papua, aku yang menang. Hadiahnya mana nih?”
“Iya, santai. Nanti kukasih uang satu juta deh. Nolnya aja tapi.”
“Ah, dasar, sudah kuduga pasti begitu,” aku tergelak, mendorong bahunya.
Meninggalkan pelabuhan, kami bergegas menyusuri jalan dan memesan hotel lewat online. Setelah makan malam berupa sup ikan, kami memilih sebuah hotel sederhana sebagai persinggahan malam ini, sekaligus membeli tiket masuk ke Raja Ampat.
“Eh Torik, kau sudah bosan dengan rambut gondrong ya?” tanyaku. “Kelihatan lebih rapi dan berbeda, seperti bukan kau yang biasanya. Dan kau juga lebih wangi sekarang.”
“Oh, itu ada alasannya,” Torik nyengir, wajahnya sumringah, tertawa sendiri. “Sini aku bisikin, jangan cerita ke yang lain dulu ya. Sebenarnya, aku habis melamar seseorang.”
“Eh, beneran? Siapa dia?”
“Ada deh,” katanya santai. “Yang jelas orangnya mungil, imut-imut, dan kalian kenal baik. Inisialnya R. Sudah bisa menebak kan?”
Aku manggut-manggut saja, nyengir. Ah, paling-paling si Ririn, cewek narsis bertubuh mungil tukang ngaca itu. Dari dulu sudah jelas kok siapa gadis yang naksir dia. Torik tidak menjelaskan lebih lanjut, melambai santai dan berjalan mendahuluiku sambil cengar-cengir.
Sambil menunggu mobil jemputan, kami bercerita tentang pengalaman masing-masing selama berpisah jalan. Aku mendengarkan dengan menggebu ketika Torik bercerita tentang petualangannya di Kebun Apel di Kota Batu, Malang.
“Tempat itu luar biasa, tak salah kalau dijuluki Swiss-nya Pulau Jawa. Ada beberapa pemilik perkebunan yang membuka wisata buah di kebunnya. Di sana kami bebas memetik apel sepuas kami, dengan syarat tak boleh dibawa pulang. Apel yang baru dipetik rasanya segar, beda banget sama yang biasa kita beli di pasar. Pokoknya lezat deh.”
Torik lalu menceritakan keseruannya berburu kuliner di kota-kota lainnya. Rasanya yang dia bicarakan sejak tadi hanya soal makanan. Sementara itu, Hana mencairkan suasana dengan berbagi pengalamannya menyelam di Kepulauan Seribu. Tutur katanya yang menarik berhasil mencuatkan senyum kami.
“Kami berangkat menggunakan perahu motor. Awalnya aku takut karena nggak bisa berenang. Untung saja ada pemandu tur yang menawarkan kursus berenang, membimbingku meski aku takut-takut. Saat menyelam, aku merasa menjadi putri duyung. Airnya jernih dan terumbu karangnya cantik sekali. Terutama di Pulau Tidung dan Pulau Bidadari, romantis banget tempatnya. Pantainya bersih, ada jembatan di mana kita bisa bersantai memandangi laut yang biru kehijauan. Selain itu, kami juga mengunjungi Pantai Kebumen, Karimunjawa, Alor, Derawan dan Wakatobi yang nggak kalah indahnya.”
Jika Hana berkisah tentang laut dan lokasi diving, Muqodas lebih tertarik dengan gunung. “Kami mendaki tiga gunung pemecah rekor di Jawa: Semeru yang merupakan gunung berapi tertinggi, Argopuro dengan trek terpanjang, dan Raung yang medannya paling ekstrem, dengan jurang di kiri-kanan sedalam ratusan meter. Pokoknya kalian belum lengkap disebut pendaki gunung kalau belum menjajal tiga gunung itu. Kami juga mendaki Seven Summit of Indonesia lainnya, seperti Rinjani di Lombok, Bukit Raya di Kalimantan, dan Rantemario di Sulawesi. Nih, aku juga dapat oleh-oleh ini di kakiku. Luka bekas digigit pacet di Bukit Raya, berminggu-minggu masih ada bekasnya. Tapi Pemandangan di sana bagus banget deh, kalian pasti nyesel nggak ikut.”
“Sepertinya perjalanan kalian menyenangkan, ya?” kataku, asyik menonton hasil rekaman mereka di handycam.
*****
HARI KE-66, RAJA AMPAT
Kapal mulai merapat di wilayah Raja Ampat, Papua. Suasana begitu hening, tak ada apapun yang mengganggu pendengaran kecuali debur ombak yang menghantam tepian kapal. Di atas kami, burung-burung beterbangan liar melintasi pulau terpencil ini. Kami turun dari kapal dan mengamati sekitar. Saat ini, kami telah menginjakkan kaki di surga tersembunyi, salah satu tempat menyelam terbaik di dunia. Di bawah tampak dasar laut indah berpasir putih yang menghubungkan pulau-pulau ini. Ikan-ikan tampak jelas melalui perairan yang sebening kaca. Raja Ampat atau “Empat Raja” adalah nama yang diberikan untuk empat pulau utamanya, yaitu Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Kami memilih tempat ini sebagai pemanasan menjelang destinasi terakhir di Jayawijaya.
Berbekal tiket masuk berupa pin seharga 250 ribu per orang, kami bertolak dari Waisai dan menentukan lokasi terdekat untuk dijelajahi. Seorang pemandu mendekati kami dan menawarkan tumpangan. Kami menyewa speedboat untuk melintasi pulau-pulau kecil tak berpenghuni di kepulauan karang Wayag, ikon Raja Ampat. Gugusan pulau-pulau atol yang mencuat seperti gunung tak terhitung jumlahnya, bertaburan bagai berlian. Kami berseru riang saat speedboat bermanuver memutari pilar-pilar batu, lalu menyusup ke celah sempit di bawah batu yang persis terowongan. Muqodas bahkan mengajak kami mendaki salah satu pulau karang, melewati batu-batu tajam dan pohon berduri, lalu berfoto ria di puncak bukit dengan latar belakang pulau-pulau kecil nan hijau.
Kami sejenak melakukan bird watching, mengamati burung-burung indah berkicau dan berterbangan kesana kemari. Ada beberapa hewan yang jarang kami lihat seperti kepiting, laba-laba dan arthoproda yang hidup tenang di wilayah ini. Daerah ini dihuni setidaknya 171 jenis burung termasuk cenderwasih merah, cenderawasih botak, kakatua putih jambul kuning, kakatua raja, nuri merah kepala hitam, mambruk victoria dan maleo.
Berikutnya, kami menuju salah satu spot diving terbaik, menyewa baju selam, kacamata kedap air, snorkel, kaki katak, dan menggendong tabung gas di punggung. Setelah siap, kami langsung terjun menjelajahi dinding bawah laut vertikal yang merupakan rumah bagi beragam jenis terumbu karang dan gudangnya spesies ikan. Inayah tak bisa berenang dan dibimbing seorang pemandu wanita. Dia dan Hana tampak gembira saat berenang bersama dugong dan diiringi ikan-ikan kecil. Meski memakai pelampung, keduanya tampak seperti putri duyung jelita. Kami juga berkesempatan melihat penyu laut langka yang bermigrasi menjelajahi dunia, juga ikan pari yang beberapa kali melintas.
“Rasanya seperti ilusi,” kata Harto, muncul di permukaan dan melepas snorkelnya. “Menegangkan juga saat aku terombang-ambing arus laut, ditemani hewan-hewan laut yang menyapa. Ada ikan badut dan kuda laut kerdil juga ternyata di sini. Makhluk-makhluk lucu itu menggigiti jariku, geli rasanya. Tadi aku sempat kaget melihat wobbegong berkulit belang bersembunyi di atas pasir, kukira makhluk apa.”
“Di sini memang surganya makhluk laut, To,” kataku, mengangkat kacamata selam. “Tak salah jika tempat ini disebut sebagai surga laut tropis terkaya di dunia. Tak terhitung pecinta wisata bawah laut dari seluruh dunia datang ke sini untuk menikmati pemandangan bawah laut yang mengagumkan ini.”
“Selain diving dan snorkeling, kita juga bisa hiking menyusuri bukit sambil mengamati pohon-pohon berumur ratusan tahun yang tumbuh di hutan-hutan sana lho,” kata Nasuti. “Kalian mau nggak? Atau kita naik perahu ke Pianemo aja, kayaknya asyik banget tuh.”
Puas menyelam, kami bermain di pantai sambil menyaksikan fenomena hantu laut, yaitu sinar yang memanjang dari arah laut dan menyebar di atas permukaan air yang berkelip seperti hamparan berlian, terjadi selama beberapa menit. Fenomena ini pada dasarnya merupakan pemandangan matahari terbenam yang hanya dapat dilihat setiap akhir tahun.
“Ayo Kang, kita foto bareng, sebentar saja,” Inayah menarik-narik tangan Igo ketika kami kembali ke pantai. Wajahnya sumringah, sebelah tangan menyembunyikan sesuatu di balik punggung, mungkin kejutan untuk Igo. “Ayo Kang, pemandangannya cantik banget.”
“Jangan pegang-pegang!” bentak Igo, mengibaskan tangan Inayah. Aku sampai kaget. Entah kenapa, dia tiba-tiba marah. “Kan ada Hana, kau pergilah dengannya.”
“Lho, Akang marah ya?” Inayah menatapnya kaget.
“You dont say?” Igo membelalak, suaranya meninggi. “Kita memang sudah menikah, tapi kita belum resmi secara hukum. Jadi jangan pernah kau menyentuhku.”
Inayah diam saja. Mungkin ia bingung apa yang membuat Igo semarah itu. Matanya yang bulat polos tampak berkaca-kaca. Perlahan pipinya basah. “Maaf Kang, tadi aku benar-benar tak sengaja. Tadi itu spontan saja, terbawa suasana.”
“Tak sengaja, katamu? Lebih baik aku memegang api daripada disentuh olehmu!”
Aku terbelalak mendengarnya. Igo sudah keterlaluan. Entah setan apa yang membuat sikapnya berubah bengis seperti itu. Inayah menunduk diam. Hanya air matanya yang bicara. Bibirnya bergetar. “Maafkan aku. Aku janji, tak akan lagi-lagi mengulanginya.”
“Sebenarnya aku mengizinkanmu ikut hanya untuk menuruti permintaan ayahmu,” Igo berkata dingin. “Aku belum percaya padamu. Selama ini aku berpura-pura dekat denganmu, ingin tahu bagaimana reaksimu ketika aku bersikap manis padamu. Aku membiarkanmu duduk di belakangku, kubonceng ke mana-mana... Sebenarnya aku tak ingin mengatakan ini, tapi aku terus penasaran sejak kita bertemu di Bandung. Kita belum lama kenal, tapi kau bersikap seolah sudah mengenalku sejak lama. Apa yang sebenarnya kauinginkan dariku? Mustahil ada gadis yang suka padaku dalam satu hari, kecuali ada maunya.”
Inayah terkejut dengan pertanyaan itu.
“A-apa maksud Kang Igo? Aku tak mengerti.”
“Kau belum tahu apa kesalahanmu?” suara Igo meninggi. “Coba jelaskan, siapa orang yang diam-diam kautelepon kemarin? Kaupikir aku tak tahu? Kau sampai mencuri waktu untuk menelepon, mencari tempat sepi, hampir berbisik, dan aku tahu itu bukan ayahmu. Aku mendengarmu berkali-kali menyebut kata ‘cinta’. Apa dia mantan pacarmu?”
“Maafkan aku Kang, maafkan aku,” Inayah memohon, kelihatan memelas sekali. “Aku... aku tak bisa bilang soal itu. Tapi percayalah, dia bukan pacarku atau apapun.”
“Sudahlah, jangan mengelak. Padahal aku sudah berkorban banyak untukmu. Tapi kau tega sekali berselingkuh di belakangku. Apa sih yang kurang dariku?”
“Aku tak pernah melakukan itu, sungguh. Apa yang harus kulakukan agar Kang Igo percaya?” Inayah memegang tangan Igo, tapi pemuda itu mengibaskannya lagi.
“Aku pikir kau wanita baik-baik,” Igo berbalik membelakangi Inayah. “Ternyata, aku salah menilaimu. Kau sama saja dengan wanita murahan. Aku kecewa.”
“Maaf maaf maaf,” Inayah sampai membungkuk-bungkuk. Air matanya menetes tiap kali membungkuk. Aku tak sampai hati melihatnya. Apa sih yang dipikirkan si Igo?
“Tolong dengarkan aku dulu,” Inayah memelas.
“Saat ini aku tak ingin diajak bicara. Biarkan aku sendiri.”
"Kumohon..."
"PERGI!"
Inayah tersentak, menatap Igo dengan tatapan tak percaya, kecewa, dan tersinggung, lalu menunduk dalam-dalam, sesenggukan. Pasti dia tak pernah dibentak sekeras itu oleh orang lain. Aku tak sanggup membayangkan, betapa hancurnya hati wanita itu mendengar ucapan yang meluncur dari mulut Igo, pria yang selama ini dikagumi dan disayanginya setengah mati. Sesuatu yang sejak tadi disembunyikannya di balik punggung terjatuh, rupanya seikat bunga hutan dengan warna-warni indah. Bunga itu terinjak saat dia melangkah mundur, tubuhnya berguncang, kemudian pergi meninggalkan Igo. Aku merasa melihat hamburan air mata di udara saat dia berlari melewatiku. Igo diam saja, sedikitpun tak peduli. Tampaknya dia bahkan tak sadar kami ada di situ.
“Apa-apaan kau?” Harto langsung memprotes dan menghampiri Igo dengan marah, menjitak kepalanya. “Kau memperlakukannya seperti pelayan. Pikirkan perasaannya dong. Kalau ada jus stroberi, pasti sudah kusiram mukamu. Nyebelin banget.”
“Kejar dia, Igo!” desak Nasuti, ikut menjitaknya. “Aku nggak tahu kalian ada masalah apa, tapi harusnya kau tak perlu semarah itu kan? Dia itu wanita, hatinya mudah terluka. Lagian ngapain coba tiba-tiba kamu ngambek begitu, nggak jelas banget deh.”
Namun kejengkelan Harto dan Nasuti tak seberapa jika dibanding kemarahanku. Aku menghampiri Igo, lalu mendorong bahunya keras-keras sampai dia terjengkang ke pasir. Igo menatapku kaget, berusaha duduk, bahkan Harto dan Nasuti tak menyangka aku akan berbuat begitu. Zhen, Muqodas, Torik dan Hana yang sejak tadi asyik bermain voli langsung mendekat mendengar kami ribut-ribut, bertanya ada apa.
“Minta maaf sana!” teriakku. “Kau membuatnya menangis! Dia gadis baik, cintanya tulus hanya untukmu. Tuduhanmu itu tak benar, tak mungkin dia berpaling ke pria lain. Kau mau tahu siapa yang dia telepon? Itu bukan pacar atau selingkuhannya, tapi Ruqoyah!”
Igo tampak kebingungan. Mungkin dia heran mendengar nama Ruqoyah disebut-sebut, menebak apa hubungannya. Tapi aku tak berniat menjelaskannya sekarang.
“Kau itu sangat beruntung, Igo, mendapat cinta tulus dari seorang gadis tanpa perlu berusaha. Sedangkan aku? Aku sudah berjuang mati-matian, mengorbankan banyak tenaga dan waktu demi mengumpulkan modal menikah, tapi malah tak dihargai dan dicampakkan oleh gadis yang kulamar. Akhwat itu bilang mau fokus kuliah dulu, membuatku menunggu satu tahun. Nyatanya sebelum wisuda dia malah menikah dengan pria yang sudah mapan!”
Entah kenapa aku jadi sangat emosional dan mengeluarkan unek-unek itu. Teman-teman menatapku prihatin. Mereka tahu kisah itu, tentu saja. Tanpa kusadari, ada sepasang mata yang menatapku sendu, tatapan penuh kerinduan.
“Dan kau malah menyia-nyiakan Inayah, gadis baik hati yang mencintaimu!” teriakku lagi. “Harusnya kau bersyukur tak perlu mengalami hal pahit sepertiku!”
Aku hendak memuntahkan semua kekesalanku, termasuk membalas tuduhannya saat di Ambon kemarin. Kebetulan aku masih kesal. Aku tak peduli meski Igo marah padaku, bahkan aku juga siap jika dia ingin memukulku. Namun reaksinya sungguh di luar dugaan.
“Eh, tunggu, tunggu!” Igo mengangkat tangan. “Tolong jangan menghujatku dulu, Lutfi. Kau salah paham. Tadi aku cuma pura-pura marah kok, tak serius melakukannya.”
“Apa maksudmu?” kataku, heran dengan perubahan sikapnya.
Igo berdiri, mengibaskan debu dari bajunya. “Maaf kalau membuat kalian kaget. Tadi aku hanya ingin menguji kesabaran Inayah. Sebenarnya aku juga sudah tahu kalau yang meneleponnya itu Ruqoyah. Sebelum berangkat ayahku berpesan: Jika ingin kenal seseorang, cari tahu hal apa yang membuatnya marah. Jujur, aku sendiri tak tega melakukan itu. Aku tak ingin menyakiti perasaannya, tapi aku terpaksa. Ternyata Inayah gadis yang baik dan lembut. Dia tak balas membentak saat kumarahi tadi, artinya hatinya memang seputih kapas.”
“Jiah, jadi barusan kau cuma akting?” kataku kesal. “Tega banget, sampai menuduh selingkuh segala. Inayah nangisnya beneran tuh, tanggung jawab sana!”
“Dasar aneh, kurang kerjaan banget sih!” Harto ikut-ikutan memaki.
“Iya, aku akan minta maaf padanya,” Igo membungkuk, memungut bunga berwarna-warni yang dijatuhkan Inayah, mengendusnya dengan mata terpejam. “Ini pasti untukku. Aku akan mencari Inayah dan menjelaskan semua itu padanya. Aku benar-benar menyesal.”
Igo bergegas pergi, meninggalkanku yang masih dongkol.
*****
Malam mulai turun bagai tirai hitam yang menutupi langit. Kami mencari rumah sewaan di kawasan Waigeo Selatan yang tidak terlalu ramai, memilih sebuah resor tradisional unik yang berupa pondok berdinding kayu, dibangun di atas air dan dihubungkan dengan jembatan. Kami menikmati makan malam di restoran dekat bibir pantai, merasakan udara asin dan dinginnya malam. Menunya cukup menggiurkan, yaitu hidangan laut tradisional yang dibuat langsung oleh masyarakat setempat. Hanya Muqodas dan Torik yang tidak ikut karena mereka memasak makan malam sendiri di penginapan. Zhen dan Hana entah pergi ke mana.
“Meski sepi, desa ini tampak rapi dan bersih, ya?” kata Igo ketika kami menyaksikan pertunjukan suling bambu yang biasa diadakan selama festival keagamaan atau untuk menyambut hari Kemerdekaan. “Penduduk sekitar juga ramah-ramah. Rasanya mereka tak henti-henti menyapa dengan senyum. Tampaknya nelayan di daerah sini terbiasa dengan turis asing. Yang paling unik, kelihatannya mereka gemar sekali mengunyah buah pinang.”
“Oleh-olehnya juga menarik,” kata Harto. “Lumayan sih, banyak kerajinan anyaman dan hasil budidaya mutiara yang membuatku tertarik, meski harganya cukup mahal karena letak pulau ini terpencil.”
“Yang paling membuatku tertarik, ternyata di hutan sana ada sisa-sisa bangunan bunker kuno juga lho,” kataku. “Kayaknya dibangun tentara Jepang pada masa Perang Dunia kedua. Tadi aku jalan-jalan sendiri dan melihat ada gua di Tomolol yang dindingnya dipenuhi lukisan telapak tangan manusia dan hewan-hewan besar, peninggalan orang-orang purba dari masa prasejarah. Sayang kalian nggak ikut.”
“Ha? Gua prasejarah?” Igo tertarik. “Kenapa tak mengajakku?”
“Gimana sih, tadi kau kan sibuk mengejar Inayah,” kataku, nyengir. Sebenarnya lucu juga membayangkan Igo dan Inayah berlarian di pantai, kejar-kejaran persis di film India.
“Ngomong-ngomong, sekarang Inayah ke mana ya?”
Aku menoleh ke sekeliling. “Bukannya dia bersamamu, Igo?”
“Tadi dia di sini kok. Apa pergi membeli makanan, ya?”
“Kita kan baru saja makan, masa dia mau makan lagi?” kata Nasuti. “Apa nafsu makan gadis remaja memang sebesar itu, ya?”
“Gawat nih, anak orang hilang di negeri orang,” kata Harto. “Zhen dan Hana juga nggak ada. Barangkali mereka main petak umpet. Sudah dicari di kolong meja? Di laci mungkin.”
“Coba telepon dia, atau sms,” saranku.
Igo mengambil ponselnya dan menelepon Inayah. Selama beberapa saat yang terdengar hanya bunyi tut tut tut, tak ada jawaban dari seberang sana. Kami saling pandang, kebingungan jika harus mencari Inayah ke sekeliling pulau yang luas ini. Akhirnya, telepon diangkat, namun kami tercengang karena bukan suara Inayah yang terdengar, melainkan suara serak dan kasar seorang pria.
“Gadis ini sekarang berada di tangan kami. Kalau mau dia selamat, datanglah ke bunker Jepang di tengah hutan. Jangan coba-coba panggil polisi, atau gadis ini akan kami bunuh!”
Kemudian terdengar suara jeritan Inayah, “Tolong... toloooong... lepaskan aku!”
Lalu telepon ditutup, menyisakan keheningan yang menyiksa. Kami tertegun. Awalnya kami mengira ini hanya sandiwara Zhen atau Muqodas yang iseng mengerjai kami. Tapi aku menyadari ada yang ganjil. Zhen bukan tipe orang yang suka bercanda, dan Muqodas juga tak mungkin keterlaluan begitu, meski dia agak slengean. Apalagi jeritan Inayah tadi terdengar memelas sekali. Wajah kami mendadak pucat. Jangan-jangan dia diculik sungguhan?
Kami langsung panik, tak kusangka akan terjadi hal seperti ini. Masalah ini serius sekali. Nasuti segera kutugaskan mencari Zhen, sementara aku, Harto dan Igo bergegas kembali ke penginapan untuk memastikan. Aku mengetok pintu, yang ternyata tak dikunci. Torik dan Muqodas mungkin masih memasak kaki kambing di dapur.
Namun betapa kagetnya kami karena ternyata ada seseorang yang menunggu kami di ruang depan. Tamu yang tak diundang. Pria itu duduk di sofa seenaknya, bertumpang kaki, dan tak ada satu pun dari kami yang mengenal pria ini. Pakaiannya serba hitam, wajahnya licik dan berjanggut putih, dan tangannya memegang pistol. Di sebelahnya Hana tergeletak pingsan dengan tangan terikat dan mata ditutup kain. Kami tercekat melihatnya. Di belakang kami muncul dua orang lagi yang berpakaian hitam. Satu orang memakai helm, dan satu lagi memakai topeng hantu berwajah putih panjang seperti di film Scream. Kami terkepung.
“Siapa kalian?” Harto mendesis. “Kalian bukan cleaning service kan?”
Pria berjanggut putih tertawa. “Namaku Hendrik, ini rekanku Kalong dan Togar.”
“Kami tidak tanya nama kalian,” kataku galak, melirik Hana yang tergeletak di sofa, lalu memandang sekeliling, mencari tanda-tanda bekas perkelahian. Namun ruangan itu tampak utuh, tak ada barang yang hancur atau rusak. Lalu, di mana Muqodas dan Torik? Apa mereka baik-baik saja? Atau pria ini menyekap mereka dengan obat bius sehingga keduanya tak sempat melawan?
“Oh baiklah. Kami adalah pasukan elit Jerangkong, tiga orang petarung ahli yang dipilih langsung oleh Bos. Tugas kami adalah membawa kalian ke hadapan Bos. Saat ini, dia menunggu kalian di markas. Bos sampai mengirim kami untuk memastikan kalian datang. Dia tak suka dibuat menunggu. Apa kalian tidak menerima teleponnya?”
Kami tak menjawab, masih berhitung dengan situasi.
“Di mana Inayah?” Igo berteriak.
“Sabar, sabar Kawan,” kata Hendrik. “Dia sudah dibawa ke markas kami. Tadinya aku hendak membawa gadis ini juga, tapi kalian keburu datang. Sudahlah, relakan saja kedua gadis cantik ini untuk kami. Aku yakin kalian akan jadi mayat setelah semua ini selesai. Bos kami kejam dan tak kenal ampun. Lagipula, dia tak ingin ada jejak.”
Dua orang di belakang kami bergerak maju, mengeluarkan senjata. Kami mengawasi mereka dengan waspada. Pria yang memakai helm mengeluarkan rantai dan pisau, sedangkan pria bertopeng scream mengacungkan celurit dan kapak. Dari cara mereka memainkan senjata, kami sadar mereka bukan penjahat sembarangan. Mereka pembunuh bayaran terlatih. Pria berhelm memutar-mutar pisaunya seperti pemain akrobat, begitu juga dengan rantai di tangan kirinya yang diayunkan ke arahku.
Harto kubiarkan menghadapi pria bertopeng scream, sedangkan Igo masih saling tatap dengan Hendrik. Aku dan Harto melompat maju, beradu serangan dengan lawan. Gerakan pria di depanku cepat sekali, seperti tak terlihat. Helmnya yang besar seakan tak menghambat geraknya. Aku meninju secepat kilat, mengarah perutnya, namun hanya mengenai angin. Terkejut, aku mendapati pria itu tak ada lagi di depanku. Tahu-tahu ada yang mendorong punggungku keras-keras, memitingku ke lantai. Kedua tangan tak bisa kugerakkan karena ditelikung ke belakang. Pria itu menekanku, merasa di atas angin. Harto mengalami hal yang sama. Apa-apaan mereka ini? Belum apa-apa, dalam sekejap kami dibuat tak berkutik.
“Kalian bukan tandingan kami,” kata Hendrik dingin, sekilas melirikku. “Dan sangat mustahil anak SMA seperti kau bisa mengalahkan kami.”
“Aku bukan anak SMA!” gerutuku.
“Kuperingatkan kalian, menyerah sajalah,” ancam Kalong, pria berhelm yang memitingku. “Kesempatan menang kalian hanya nol persen.”
“Benarkah?” aku terengah, melempar pandang ke arah Harto. Dia balas menatapku, nyengir, lalu kami berteriak bersamaan.
Aku memberontak sekuat tenaga. Kalong terkejut saat aku menghentak kepala ke belakang, menyundul dadanya keras-keras. Pria itu terhuyung dan melepasku, memulihkan diri dalam sekejap dan memasang kuda-kuda. Aku berdiri, kembali menyerang saat pria itu memainkan pisau dan mengayun rantai. Harto juga terbebas. Dia berteriak dan menerjang lawannya, Togar, sesekali menghindari ayunan kapak yang diarahkan ke leher. Kami terus menyerbu dengan ganas. Sialnya tak ada serangan kami yang kena. Mereka lawan yang kuat. Gerakan mereka gesit sekali, seperti ninja. Pukulan mereka mematikan. Tangkisan mereka tak kalah cepat. Namun bukan berarti kami tak punya kesempatan menang. Aku hampir mendaratkan pukulan di perut Kalong, ketika...
“Jangan bergerak!” Hendrik menodongkan pistol. “Sebaiknya kalian menyerah saja dan ikut kami dengan tenang. Jangan berani-berani melawan. Kalian tak punya pilihan. Ayo, ikutlah dengan kami, atau kami terpaksa harus menyeret kalian.”
“Kalau kami menolak?”
“Maka timah panas akan bersarang di tengkorakmu, dan teman kalian yang cantik ini akan mati. Begitu pula si cantik satunya yang ada di markas kami.” Hendrik mendekatiku dan menodongkan pistol ke kepalaku. “Aku dengar kalian mengalahkan Jeki, bawahan kami di Jakarta. Sayang sekali, posisinya hanya ‘Pion’, sedangkan kami ‘Menteri’. Jika melawan kami saja membuat kalian kewalahan, kalian takkan bertahan sedetikpun melawan ‘King’. Kalian bahkan tak akan melihat wajahnya, jika saja dia tidak mengundang kalian secara khusus. Ayo, menyerahlah.”
Aku mengepalkan tinju, hendak menyingkirkan pistol itu dan menghajarnya...
Tiba-tiba saja... Blep! Mendadak gelap. Mataku berkunang-kunang. Kenapa harus mati lampu di saat genting begini? Aku langsung merunduk untuk menghindari todongan pistol yang hanya berjarak beberapa senti dari kepalaku. Namun Hendrik tidak menembak. Aku tak bisa melihat apa-apa. Suasana gelap total. Tak ada cahaya yang lolos sedikitpun dari luar jendela. Perasaan khawatir menyergapku. Aku merasakan Harto dan Igo bergerak gelisah di dekatku, bunyi napas mereka tertahan. Terdengar langkah-langkah kaki. Ada seseorang yang mendekat. Kemudian... dor dor dor! Bunyi rentetan peluru membuatku terlonjak. Serentak aku tiarap ke lantai, memegangi kepala.
“Harto? Igo? kalian tak apa-apa?” panggilku, panik. Hening, kemudian terdengar suara gedebuk keras, seperti bunyi orang bergumul, lalu bunyi denting metal menghantam tulang, diiringi jerit kesakitan. Ada tubuh-tubuh yang ambruk ke lantai, aku tak tahu siapa. Semoga saja bukan di pihak kami. Lampu menyala lagi, membuatku silau. Aku langsung berdiri, menoleh mencari ketiga penjahat, namun mereka tak ada di depanku. Ketika menunduk, aku melihat ketiganya sudah bergeletakan di lantai. Seorang pemuda berdiri mengancam di atas mereka, mencengkeram pisau dapur di tangan kiri dan wajan berlapis teflon di tangan lain.
“Torik!” seruku lega. Sahabatku itu mengangguk puas, menunduk menatap lawan yang barusan dihajarnya menggunakan wajan.
“Bagus, kau hebat, Torik!” Harto memekik, seraya bangkit dan menghampiri Hana, memastikan dia baik-baik saja. “Dan siapa yang mematikan lampu?”
“Aku,” kata seseorang yang berdiri di pintu dapur. Rupanya Muqodas. “Sengaja untuk membingungkan mereka. Sekalian saja kumatikan sikringnya agar semua lampu padam.”
“Kau pantas dijuluki Raja Kegelapan, Muqodas,” kata Torik, memutar-mutar wajannya, mengawasi lawan yang pingsan. Aku segera melepas ikatan Hana dan menyandarkannya di sofa. Gadis itu masih dalam pengaruh obat bius.
“Padahal kami berdua sedang asyik memasak kambing guling, tahu-tahu ada yang ribut di depan,” kata Muqodas. “Begitu terdengar jeritan Hana, aku dan Torik mengintip dari pintu, mengawasi. Aku kaget sekali melihat begundal-begundal ini mengikat Hana dan duduk santai di sofa, mungkin mengira tak ada orang lain di penginapan. Tadinya kami berniat menolong Hana, lalu kalian datang dan beradu mulut dengan mereka.”
“Kami tak bisa sembarangan menyerang, jadi aku berencana menyergap mereka dalam gelap,” kata Torik. “Begitu Muqodas mematikan lampu, aku langsung berlari dan menerjang pria yang membawa pistol, memitingnya ke lantai. Dia sempat melawan dan melepas tembakan. Untung saja tak ada satupun peluru yang kena karena aku mencengkeram tangannya dan mengangkatnya paksa ke atas.” Dia menengadah menatap langit-langit yang berlubang-lubang, lalu menunduk menatap orang-orang yang terkapar, mengusap wajah, dan berkata, “Alhamdulillah.”
“Untuk apa?” tanya Muqodas.
“Puas aku menghajar orang-orang ini. Rasanya kenyang.”
“Seperti habis makan saja,” kata Harto. “Lalu, bagaimana caramu mengenali musuh dalam gelap?”
Torik mengetuk hidungnya. “Dari baunya. Aku sudah hafal bau kalian, jadi mudah sekali kubedakan dari mereka. Dan bau orang-orang ini sangat buruk. Seperti bau alkohol.”
Terdengar rintihan pelan. Hana mulai bergerak dan perlahan membuka mata, mengaduh memegangi kepala. Begitu menemukan wajahku, matanya langsung melebar.
“Lutfi... Inayah diculik...”
“Iya, kami tahu,” aku menunduk, menelan ludah.
Torik terperanjat mendengarnya, menjatuhkan wajan ke lantai. Muqodas berseru kaget, “Ya ampun, ini serius kan?”
“Tadi aku melihatnya, orang-orang itu membawanya ke mobil,” Hana sesenggukan. “Aku berusaha mengejar dan berteriak minta tolong. Tiba-tiba ada yang menyergapku dari belakang, dan... dan...”
Hana tak sanggup meneruskan, air matanya berlinangan.
“Ini salahku, aku tak bisa mencegahnya,” isaknya.
“Sudahlah, kita doakan saja semoga dia tak diapa-apakan,” aku menghiburnya. Harto memandang Igo dengan tatapan kosong, mengusap bahunya.
Kami semua menoleh saat Hendrik bergerak, lalu berdiri perlahan. Rupanya belum pingsan. Sebelum kami bertindak, pria itu berlari ke pintu dapur, mengacungkan pisau dan menyerang Muqodas yang tak bersenjata. Mungkin Hendrik mengira bisa melarikan diri dengan melewatinya, namun kami semua tahu dia berbuat kesalahan fatal. Bagaimanapun, Muqodas adalah mantan juara dua karate tingkat Nasional. Saat pria itu mendekat, Muqodas membuang napas, santai sekali, dan... BUK! BUK! BUK! Tak ada lima detik, penjahat itu terbanting di lantai, terkapar lemas.
“Siapa mereka sebenarnya?” Muqodas menepis debu dari pakaiannya.
“Pembunuh bayaran, begitu yang dikatakan mereka,” kataku.
Aku lalu menceritakan semuanya pada Muqodas dan Torik, tentang Inayah yang menghilang tiba-tiba, tentang pria misterius di ujung telepon, dan tentang teriakan minta tolong Inayah. Mendengar itu, wajah keduanya berubah keruh.
“Orang ini belum pingsan, dia pasti tahu sesuatu,” kata Muqodas.
Kami langsung menginterogasi Hendrik yang bergerak lemah, memegangi kepalanya. Torik mengacungkan garpunya dengan mengancam. “Katakan, siapa yang menyuruh kalian kemari? Ayo mengaku! Kalau tidak, kucongkel matamu dengan garpu. Siapa bos kalian itu? Dan apa yang kalian inginkan dari kami?”
Hendrik tertawa. “Kalian hanya beruntung mengalahkan kami. Kami adalah perwira Jerangkong dengan tiga nomor urutan terakhir, artinya kami terbilang paling lemah di antara tujuh orang perwira. Di atas kami ada empat orang lain yang peringkatnya lebih tinggi. Mereka sangat kuat, kalian bukan tandingan mereka, dan kalian akan langsung mati jika berhadapan dengan bos besar kami dan wakil barunya. Dua orang itu seperti monster!”
“Huh, aku tidak takut. Akan kulawan kalian semua!” seru Harto. “Kami tanya sekali lagi, siapa bos kalian?”
“Haha, kalian pikir dengan menangkapku akan membuatku buka mulut? Aku takkan mengaku semudah itu, dasar bod—”
“Ayo mengaku!” Torik berteriak, memukul kepala Hendrik dengan wajan keras-keras, menimbulkan bunyi denting mengerikan. Aku dan Harto sampai berjengit. Pria itu terkulai dan menggelosor ke lantai, tak sadarkan diri. Torik tampak menyesal sekaligus ngeri. “Yah, dia malah pingsan. Kita jadi tak tahu siapa dalangnya.”
“Tidak juga, aku sudah tahu siapa bosnya,” kataku. Teman-teman menoleh. Aku lalu menceritakan secara singkat tentang dua orang buronan yang kubuntuti tempo hari, juga percakapanku dengan Kapten Jojo tentang organisasi kriminal bernama Jerangkong.
“Lalu, orang-orang ini mau kita apakan?” tanya Muqodas.
“Kita goreng saja, sepertinya enak,” kata Torik, memutar-mutar wajannya. Aku menatapnya jengkel. “Ups, maaf. Maksudku kita serahkan saja ke polisi.” Perlahan, Torik melepas helm yang dipakai Kalong, memperlihatkan wajah pemuda di baliknya. “Dia masih seumuran kita. Ironis sekali, kecil-kecil sudah belajar jadi penjahat.”
“Helmnya bagus juga, di mana dia membelinya, ya?”
“Ya ampun, Muqodas. Bisa-bisanya kau memikirkan hal itu dalam keadaan seperti ini,” gerutu Torik. “Eh, kau kenapa, Lutfi?”
“Dia kan...,” kataku, terbelalak menatap wajah Kalong. Harto dan Igo juga sama terkejutnya. Aku mendekati Kalong, memastikan, dan semakin terkejut karena dugaanku benar. “Ini kan... Seno!”
“Kau kenal?” Muqodas mengernyit.
“Ya, dia pengamen yang pernah kami tolong di Jakarta. Tak kusangka dia melakukan ini.” Aku terenyak, menyesali keterlibatan Seno. Cerita ini semakin rumit. Kukira dia anak baik-baik. Kenapa dia memilih jalan ini? Aku tak tahu apakah dia dicuci otak lagi ataukah memilih profesi pembunuh bayaran dengan keputusan sendiri. Entah apa motivasinya. Balas dendam? Ingin membuktikan diri? Aku juga kenal wajah pria satunya yang bernama Togar—orang yang kulihat di bus dan menabrak Nasuti di kapal. Rupanya mereka satu komplotan.
"Seno... sulit dipercaya,” Harto menggeleng. “Padahal kami membelanya.”
“Profesi ini pasti sudah lama ditekuni Seno,” kata Igo. “Gerakan menyerangnya rumit, tak mungkin dia bisa menguasai itu dalam waktu singkat. Harus kuakui, bosnya itu pelatih yang luar biasa. Yang membuatku heran, dengan kemampuan seperti itu, kenapa Seno mau saja jadi bulan-bulanan preman Jakarta? Kenapa saat itu dia tidak melawan?”
“Mungkin dia disuruh bosnya untuk mengawasi mereka, berpura-pura lemah agar mudah memperoleh informasi tanpa dicurigai,” aku menghela napas. “Entah cerita tentang dirinya yang diculik waktu itu benar atau tidak, aku tak tahu. Tak ada gunanya berbelas kasihan, anak ini harus kita serahkan pada polisi, karena penjahat tetaplah penjahat.”
Aku menatap dingin wajah-wajah penjahat itu, enggan memberi kepercayaan untuk kedua kalinya. Harto dan Igo setuju. Kami mengikat para penjahat ini dengan rantai yang mereka bawa. Saat itu Nasuti masuk, terkejut melihat sosok-sosok hitam di lantai.
“Hei, siapa mereka?” Nasuti mendekat.
“Tamu tak diundang,” jawab Igo. “Mana Zhen?”
“Aku sudah mencarinya ke mana-mana,” kata Nasuti. “Aku heran, pergi ke mana dia di saat genting begini? Atau jangan-jangan dia diculik juga?”
“Sebenarnya, apa maunya orang-orang ini?” Igo menggeram dan menggebrak meja, kelihatan hampir menangis. “Apa salah Inayah sehingga mereka mengincarnya?”
Igo berdiri, mengacak rambut, lalu berjalan mondar-mandir. Masalah ini sangat mengguncang dirinya. Aku dan Nasuti menunduk mencari akal. Harto menampakkan wajah prihatin. Hana menggigiti jarinya. Entah mengapa liburan ini selalu tak berjalan mulus. Ada saja penjahat-penjahat yang berniat menyusahkan kami, menjebak kami dalam kemuraman dan jerat masalah. Entah orang-orang ini menculik Inayah karena ada kesempatan, atau sejak awal memang sudah direncanakan, aku tak tahu. Yang paling menyesal tentu saja Igo.
“Sekarang gimana? Apa kita ikuti saja kemauan mereka?” kata Harto.
“Kita tetap lapor polisi, jangan takut ancaman mereka,” kataku.
“Ya, tapi kita juga harus melakukan sesuatu,” kata Igo, menatapku. “Aku tak bisa diam saja di sini, Lutfi. Para penculik itu bisa saja menyiksanya. Nyawa istriku dalam bahaya!”
Igo memukul meja lagi, lalu bangkit dan berlari ke luar.
“Hei, kau mau ke mana?” aku dan Harto mengejarnya.
“Tak ada cara lain, aku akan pergi ke tempat perjanjian,” Igo menoleh. “Kalau kalian mau menghentikanku, silakan. Pokoknya aku tetap akan pergi menolong istriku.”
“Aku tidak akan mencegahmu,” kata Harto. “Justru kami ingin membantu. Lawan kita sindikat kriminal berbahaya. Kami tak bisa membiarkanmu pergi sendirian.”
“Ya, kami akan ikut denganmu,” kata Nasuti.
“Dengar, kalaupun kita akan lakukan misi penyelamatan, kita harus membuat siasat sebelum pergi, jangan gegabah,” saranku, khawatir akan adanya jebakan tersembunyi. “Lagipula ini sungguh aneh karena si penculik tak minta tebusan apa-apa, hanya minta agar kita datang.” Aku memejamkan mata, berpikir cepat dan menyusun strategi. Harus ada yang memimpin saat semua panik dan tertekan seperti ini. “Baik, begini saja, Hana tetap di sini bersama Muqodas, sementara aku, Harto, Igo dan Nasuti pergi mencari markas mereka untuk menyelamatkan Inayah. Lalu—”
“Aku akan mencari bantuan,” kata Torik. Aku menoleh menatapnya. “Tak apa-apa, aku punya rencana. Percayalah padaku, aku takkan berbuat ceroboh. Sementara itu Muqodas akan mengawasi orang-orang ini. Kalian pergilah dan selamatkan Inayah.”
Kami bertukar pandang suram, lalu mengangguk bersamaan. Kami berpencar sesuai tugas masing-masing. Aku, Harto, Igo dan Nasuti bersiap. Darahku berdesir jika memikirkan apa yang akan terjadi pada kami nantinya. Entah musuh seperti apa yang akan kami hadapi. Sebelum pergi, Hana mendekati kami, wajahnya cemas.
“Hati-hati, pulanglah dengan selamat,” katanya, meletakkan tangan di dada. “Aku... aku akan menunggu kalian pulang.”
“Jangan khawatir, Hana,” kataku. “Kami tidak pergi untuk mati. Kami pergi untuk menang. Hanya saja, kalau kami tidak kembali dalam tiga jam, segeralah lapor polisi.” Aku mengangguk padanya, menyerahkan kertas berisi nomor telepon yang diberikan Kapten Jojo tempo hari. Mungkin ada gunanya. Sebagai ketua rombongan, sudah jadi kewajibanku untuk memastikan semua anggota timku selamat. Aku menoleh menatap teman-temanku.
“Kalian sudah siap? Ayo berangkat!” kataku mantap.
"Aye, Kapten!"
Teman-temanku berdiri. Mereka menampakkan tekad kuat. Kami berangkat menjauhi perkampungan dengan hati kebas, mengingat misi ini sungguh menggentarkan, menantang maut dan mempertaruhkan nyawa sahabat kami. Saat menelusuri hutan, jantungku berdetak kencang, keringat menetes-netes. Aku meringis saat semak-semak berduri melecuti pipi dan menggores kulit lenganku. Suasana terasa makin mengerikan saat anjing-anjiing liar melolong di kedalaman hutan. Kelelawar beterbangan.
Tiba-tiba, Nasuti berhenti dan menarik kami ke semak-semak, meringkuk. Sejak kecil, temanku ini dianugerahi indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang sangat tajam. Tindakannya tepat waktu. Ada yang berjaga di sekitar hutan ini. Kami mengawasi saat dua orang lewat begitu dekat dengan persembunyian kami. Keduanya memakai tergos hitam yang menutupi wajah. Dilihat dari penampilan mereka, jelas mereka bukan penduduk lokal. Sepertinya dua orang ini satu komplotan dengan pria bernama Hendrik tadi.
Dua orang itu berhenti di depan semak tempat kami bersembunyi, menoleh ke sekeliling dan mengendus-endus udara. Tampaknya mereka menyadari kedatangan penyusup di teritori mereka. Salah seorang bahkan mengulurkan tangannya, hendak menyibak semak yang kami jadikan penghalang. Kami menahan napas, bersiap melakukan perlawanan, namun si pria hitam berhenti saat rekannya memegang bahunya, menggeleng, lalu mengajaknya pergi. Pria itu ragu, kemudian menurunkan tangannya dan mereka akhirnya berderap pergi.
“Mereka membawa anak buah,” bisikku, memerhatikan kedua orang itu menjauh. “Si penculik ini, anak buahnya pasti puluhan.”
Diam-diam kami membuntuti dua orang itu, yang kuduga hendak pulang ke markas. Tiba di pantai, kami tercengang saat melihat sebuah kapal besar tertambat di sana. Situasi ini menegangkan, tapi aku terkagum dengan kemegahan kapal itu. Panjangnya sekitar dua ratus meter, berwarna hitam metalik, dan agaknya penuh dengan muatan. Mungkin itu transportasi mereka. Tampak orang-orang bergerak sibuk mengangkuti barang ke kapal, dan bagiku terlihat mencurigakan karena mereka berlabuh di tempat sepi ini, bukannya di dermaga resmi.
“Bosnya pasti kaya sekali jika punya kapal sebesar itu,” kata Nasuti. “Mungkin hasil bisnis terlarang dan perdagangan barang haram kali ya.”
“Oh tidak, mereka banyak sekali!” Igo menunjuk segerombol pria yang bermunculan dari semak-semak, sibuk menggotong peti-peti kayu besar ke arah kapal, entah apa isinya. Sisanya membawa senjata tajam dan tampak waspada, mungkin bertugas mengawal. “Jumlah mereka sekitar empat atau lima puluh orang. Apa kita harus singkirkan badut-badut ini dulu?”
“Mereka bukan badut, mereka bebegig,” kata Harto.
“Apa itu bebegig?” tanya Igo.
“Ya ampun, masa sudah lupa,” Harto menepuk dahi.
“Ayo pergi, kita tak ada urusan di sini,” kataku. “Tempat perjanjiannya di bunker Jepang di tengah hutan, bukan di kapal itu.”
Kami menunggu sambil menahan napas. Begitu langkah mereka tak terdengar lagi, kami melesat keluar dan lari secepatnya. Kami menyeruak di antara semak, menajamkan mata dalam kegelapan, berhati-hati agar tak bertemu penjaga lain.
“Ayo, cepat,” bisikku. Jujur saja, aku tak begitu yakin misi ini akan berhasil. Bahkan jika memperhitungkan keahlian beladiri kami yang cuma berempat, dibandingkan daya tempur musuh yang berkali-kali lipat lebih kuat dan banyak, jelas kesempatan menang kami kecil sekali, mungkin kurang dari satu persen. Rasanya seperti mengantarkan nyawa ke sarang monster. Meski begitu aku tetap optimis, yakin sepenuh hati bahwa Allah bersama kami. Sehebat apapun organisasi musuh, sekuat apapun bosnya, jika Allah menghendaki mereka hancur, maka takkan ada yang bisa mencegahnya. Toh mereka juga cuma manusia biasa yang bisa berdarah dan mati. Aku berharap, di sela-sela krisis yang mencekik ini, kami akan menemukan keajaiban, setipis apapun harapan itu.
Kami terus mengendap-endap, semakin jauh ke jantung hutan.
Sialnya, meski sudah mengendap-endap, sebisa mungkin tak menimbulkan suara, tetap saja kami ketahuan. Tiba-tiba ada yang menangkap bahuku dari belakang, dari arah semak, berusaha menarikku mundur dan mencekikku. Aku memberontak, menyikut rusuknya beberapa kali, lalu membanting tubuhnya ke depanku hingga menembus semak-semak. Aku terengah mengamati sosok yang tergeletak itu. Wajahnya tak tampak karena tertutup topeng hitam, persis gerombolan tadi, dan ternyata pria itu tidak sendirian. Tahu-tahu kami sudah dikepung. Tak kurang dari dua puluh orang berpakaian hitam bermunculan dari balik semak, mengacungkan obor dan menyeringai galak. Jelas mereka bukan orang baik-baik.
“Wah wah, ada penyusup. Apa kita bunuh saja ya?”
“Bodoh, kau tidak tahu? Anak-anak ini target bos kita!” kata yang lain. “Bos pasti memberi imbalan besar kalau kita menangkap mereka.”
Tanpa aba-aba, orang-orang itu kompak menyerang kami, berteriak dan mengacungkan senjata masing-masing. Situasi memburuk. Meski kami pemegang sabuk hitam, kami hanya berempat dan lawan sebanyak itu cukup membuat kewalahan. Kami terus bertahan sambil sesekali menyerang, mengamati gaya bertarung lawan yang bervariasi. Senjata mereka juga aneh-aneh. Ada yang membawa badik, celurit, tombak, karimbit, mandau, hingga rencong. Agaknya mereka orang-orang buangan dari berbagai macam suku.
Aku menendang dagu lawan di depanku, membuatnya tersungkur. Dua orang lainnya menyerbu dari samping, berusaha menusuk dengan paku besar. Aku berkelit, menarik lengan pria di sebelah kanan dan memukul lehernya, secara bersamaan kutendang juga penyerang satunya. Beberapa dari mereka tangguh juga. Pria yang membawa rencong berkelit cepat menghindari tinjuku, memamerkan gerakan silat yang rumit dan berhasil membuat bahuku lebam. Tendangan dan sapuanku juga ditangkisnya dengan lihai. Pria itu tertawa mengejek. Butuh waktu agak lama menghadapinya, hingga aku berhasil mengecohnya dengan gerak tipu dan menonjok hidungnya hingga terpelanting.
Di sebelahku, Igo memukuli lawannya dengan trekking pole, sisanya ia lumpuhkan dengan tendangan cepat. Bahkan ia juga menghunus baton sword yang disembunyikan dalam trekking pole, menangkis sabetan celurit pendekar lawan dan menyapu kakinya. Harto menghadapi dua orang sekaligus, membungkuk menghindari tusukan golok dan membalas dengan uppercut telak di dagu lawan, membuatnya terjengkang dan menabrak pria lainnnya. Harto berkelit lagi, lalu menyundul dahi lawan satunya dan membantingnya ke tanah.
Sementara itu Nasuti merebut obor salah satu pria dan memakainya menghalau musuh. Ia merangsek maju dan berhasil melukai beberapa lawan dengan obor. Saat seorang pria menerjangnya, Nasuti sigap melompat ke pohon, menjejak batang dan memantul kembali, menendang dada lawan. Beberapa orang berhasil kami kalahkan, tapi mereka segera bangun lagi, berteriak garang dan kembali menyerang. Mereka banyak sekali. Kami tak sempat berpikir dalam situasi sericuh ini. Kami terus memukul dan menendang, tak peduli lawan kami pingsan atau hampir mati. Yang penting kami bisa meloloskan diri dan segera pergi.
Situasi kian rumit saat bala bantuan musuh datang. Puluhan orang yang mengangkut peti kemas itu menoleh melihat keributan, sejenak berpikir bahwa ada yang tak beres, lalu bergegas menurunkan bawaan mereka dan ikut mengeroyok kami. Beberapa pria yang bertubuh kecil berlarian kabur, mungkin mereka bukan petarung atau memang enggan berkelahi. Lawan yang merepotkan juga ada. Seorang pria bertubuh besar mengayunkan rantai dengan kait tajam di ujungnya, berbahaya sekali kalau sampai kena. Kami menghindar saat rantai itu meluncur, beberapa kali hampir mengenaiku. Aku dan Harto kompak meraih bambu yang mereka pakai menggotong barang, mengangkatnya bersama, lalu menyodok pria itu di dadanya. Tiga orang lainnya roboh sekaligus setelah terkena kibasan bambu gila kami.
Perkelahian ini berlangsung lama dan melelahkan. Untunglah kami hanya memperoleh beberapa memar yang tak begitu fatal. Setidaknya para bawahan ini tak sekuat Hendrik dan dua rekannya. Setelah banyak lawan tumbang dan hanya tersisa segelintir orang, kami ambil kesempatan dan kabur lewat celah yang terbuka, berlari sekuat tenaga. Tak ada gunanya meladeni mereka, karena tujuan utama kami adalah menyelamatkan Inayah.
DOR!!! Baru beberapa langkah berlari, sesuatu berdesing di udara dan menancap di tanah, menimbulkan asap. Kami berhenti bergerak, menahan napas. Bahkan para pria yang mengejar kami ikut berhenti. Dari suaranya saja kami tahu apa itu. Nasuti mengendus udara, mencari posisi si penembak. Tiba-tiba terdengar suara pria dari suatu tempat.
“Kalian, anak buahku, pergilah. Teruskan pekerjaan kalian, tinggalkan yang pingsan. Barang-barang itu harus segera dikirim. Telat sedikit saja, Bos akan marah. Anak-anak ini biar aku yang hadapi.”
Para pengejar kami langsung menurut, bergegas pergi.
DOR! DOR! DOR! Orang itu, yang entah berada di mana, kembali menembak. Tiga peluru sekaligus. Aku tahu dia sengaja tidak membidik kami, hanya membuat kami berhenti. Ini bukan main-main. Orang itu bisa melihat kami sedangkan dia tersembunyi di suatu tempat. Aku sadar ujung senapannya terarah ke kepala kami dan bisa meletus kapan saja. Jantungku berdegup kencang. Salah langkah sedikit saja, nyawa taruhannya.
“Kalian tidak akan lolos dariku,” terdengar suara pria itu lagi. “Aku Pansus, Si Nomor Empat, pria yang akan mengeksekusi kalian di tempat ini juga! Sebutkan nama-nama kalian, biar kuingat dan kutulis di batu nisan kalian!”
Aku pernah mendengar nama itu. Menurut Kapten Jojo, dia adalah teroris di balik insiden pengeboman di beberapa tempat di Indonesia dan mancanegara, seorang penembak jitu dan jenius perakit bom yang sudah lama dicari polisi. Hanya saja dia selalu bergerak dalam bayangan, berganti-ganti nama samaran, sehingga identitas aslinya sulit dilacak. Jumlah korbannya cukup fantastis, dan pria yang memiliki dua gelar master ini tak pernah gagal dalam setiap misinya. Ditambah lagi dia sangat lihai dalam pertempuran jarak jauh. Rekor menembaknya tak pernah meleset, sanggup menghabisi puluhan orang sekaligus dengan senapannya, bahkan meskipun targetnya berjarak lebih dari 500 meter dalam cuaca berangin. Pantas jika dia diberi peringkat empat. Lawan kami kali ini sangat berbahaya. Namun aku tak bisa memastikan dari mana suaranya berasal.
“Di sana!” teriak Nasuti, tiba-tiba mengacungkan senter ke atas dan menyalakannya, menampakkan seorang pria berjaket hitam yang memanggul senapan berburu. Pria itu mengerang dan menutupi wajahnya. Pasti silau sekali. Salahnya sendiri memakai nightscope, kacamata khusus sensitif cahaya. Aku mengagumi kecerdikan Nasuti yang memanfaatkan keunggulan lawan dan mengubahnya jadi titik lemah. Sebelum pria bernama Pansus itu pulih, Nasuti melompat ke pohon tempat dia bertengger, menggunakan sorban untuk mengait kaki si pria, menjatuhkannya hingga jatuh berguling-guling di tanah. Nasuti meluncur turun dan berdiri di atas si pria, memberinya bogem mentah. Pansus menangkis dengan mudah, meraih senapan yang jatuh di sebelahnya dan balas memukul dahi Nasuti dengan popor senapan.
“Kalian cepat pergi! Biar aku yang atasi dia!” teriak Nasuti.
Pansus berusaha menembak kami, tapi sasarannya meleset karena Nasuti menubruknya. Sniper itu membuang senapannya, lalu menarik senjata lain berupa dua buah pistol berbentuk aneh, membidik kepala Nasuti. Pemuda itu berguling menghindar saat buncahan api merah menyembur keluar dari moncong senjata itu.
“Kau takkan bisa menang,” Pansus menodongkan senjatanya lagi. “Ini penyembur api, pistol khusus yang kumodifikasi sendiri.”
Aku menelan ludah, orang ini tak sembarangan. Aku hendak membantu, tapi Nasuti memberi isyarat agar kami segera pergi. Raut wajahnya tampak yakin. Aku ragu sejenak, lalu mengangguk dan mengacungkan jempol, mengajak Harto dan Igo pergi. Aku memang khawatir dengan Nasuti, tapi aku percaya dia bisa menang. Terakhir kulihat, dia sedang bergumul dengan Pansus di tanah, berebut senjata aneh itu dan saling tendang.
Tanpa menoleh lagi, kami terus berlari. Jantungku berdetak tak karuan memikirkan betapa besar bahaya yang kami hadapi. Berhasil atau tidaknya misi penyelamatan ini bergantung pada kecakapan, kecerdasan, dan keberuntungan kami. Aroma kematian terasa semakin mengancam ketika kami mendekati persembunyian musuh. Setelah menempuh perbukitan, akhirnya kami tiba di tempat perjanjian.
Bangunan tua dan kusam berdiri di hadapan kami, sosoknya yang kokoh dan tak termakan zaman tampak mengerikan berlatar kegelapan. Di sebelah reruntuhan bunker itu terdapat gudang terbengkalai yang sudah lapuk, luasnya dua kali lapangan voli dan sebagian atapnya dilapis kayu. Kami mengendap-endap, melumpuhkan tiga penjaga yang ditempatkan di depan bunker, lalu mendekat ke pintu masuk yang tak ada daun pintunya. Sebagai gantinya, pintu itu ditutup papan kayu seadanya dan dipalang dari dalam.
Papan itu tak bisa didorong. Tak ada jalan masuk. Terpaksa kami mengintip dari celah pintu, berhati-hati dalam bergerak agar tidak membuat suara sekecil apapun. Aku tak bisa melihat apa-apa karena ruangan di dalam remang-remang. Hanya ada sebuah lampu redup menggantung dari langit-langit. Cahayanya yang sempit berbentuk lingkaran memperlihatkan sosok Inayah yang duduk lemas di kursi di bawahnya.
Wanita itu tampaknya tak sadarkan diri. Kedua tangannya terikat di belakang pinggang, kepalanya terkulai ke samping, dan matanya ditutupi kain hitam. Kerudungnya entah dibuang ke mana. Kami kesal sekaligus lega karena hanya sebatas kerudungnya yang dipreteli si penculik. Pakaiannya agak compang-camping, dan di beberapa bagian kulitnya tampak lecet dan mengeluarkan darah. Aku cemas sekaligus geram melihat luka-luka itu, tampaknya seperti bekas lecutan. Selebihnya, tampaknya dia tidak diapa-apakan.
Kami tidak langsung menolongnya, melainkan tetap menunggu dan mengawasi keadaan, khawatir disergap tiba-tiba. Aku yakin pasti ada jebakan di sini. Perlahan, Inayah bergerak lemah, tampaknya mulai sadar. Seseorang berbicara dari balik bayangan, dari tempat yang tak terkena cahaya. Aku sadar itu suara si penelepon gelap tadi.
“Sekarang sudah hampir tengah malam. Teman-temanmu tidak datang juga. Sudah terlalu lama aku menunggu. Apa kau tidak berarti bagi mereka?”
Aku menekap mulut. Tak salah lagi, itu suara Mandra, si buronan Nusakambangan! Dugaanku benar. Sekarang sudah jelas bagi kami siapa dalangnya.
“Mereka tidak akan datang, mereka tidak semudah itu termakan jebakan kalian!” Inayah berkata dengan suara lirih. “Tapi aku yakin Kang Igo dan teman-teman pasti menolongku dengan cara lain!”
Igo bergerak-gerak gelisah mendengar namanya yang pertama disebut. Aku masih memelototi ruangan, mencari-cari sosok Mandra yang tersembunyi dalam kegelapan. Harto sama gelisahnya denganku, atau mungkin dia geram menyadari siapa yang bicara. Pria itulah yang dulu membakar rumah Harto dan membuatnya jadi yatim piatu.
“Benarkah?” kata Mandra, suaranya terdengar mengecil dan berbahaya. “Kalau begitu, kau harus memanggil mereka. Ayo, panggil mereka!”
Sebuah tangan kurus panjang muncul dari kegelapan, menjulurkan HP milik Inayah ke depan bibir wanita itu. Di saat yang sama, Igo merasakan HP-nya bergetar, panggilan masuk. Walau matanya ditutup, Inayah bisa menebak benda apa yang disodorkan di dekatnya. Ia diam saja, lalu menggeleng.
“Aku tidak mau!”
PLAKK!
Inayah terhuyung ke samping saat Mandra menampar pipinya keras-keras. Bibirnya berdarah. Mandra menampakkan diri ke dalam lingkaran cahaya. Sosok kurus dan rambut panjangnya yang kusut membuat penampilannya tampak angker. Dia memelototi Inayah dengan tatapan kosong. Kecantikan wajah wanita itu yang akan membius pria manapun, tampaknya sama sekali tak berarti bagi penjahat berwajah dingin bernama Mandra ini.
“Siksa saja aku sepuas kalian!” teriak Inayah. “Aku takkan mau memanggil mereka kemari. Lebih baik aku menderita daripada harus membahayakan nyawa teman-temanku!”
Aku menggigit bibir, geram, saat melihat Mandra menjambak rambut Inayah, dengan kasar memaksanya berdiri menghadap dinding, tak memedulikan isakannya yang memelas.
“Tahu apa kau soal penderitaan?” Mandra menggeram. “Sejak kecil aku sudah kenyang dengan penderitaan. Nasib memusuhiku, dunia menolakku. Aku dibuang ibuku saat masih bayi. Rekanku, Brewok, nasibnya sama saja. Kudengar dia dipermalukan dan dipecat dari kesatuannya. Jalan hidup sebagai penjahat memang lebih cocok untuk kami.”
“Jangan, kumohon,” Inayah memelas. “Kalian bisa jadi orang baik-baik, aku yakin kalian bisa berubah!”
“Diam, aku tak butuh simpatimu!” Mandra mendesis.
Pria itu mengangkat cambuk, mendera punggung tak berdosa itu. Jeritan melengking memecah malam. Igo menggertakkan gigi, geram melihat kekejian Mandra. Aku berpaling, tak sampai hati melihat wanita lembut seperti Inayah disiksa seperti itu. Pria ini benar-benar sangat jahat.
“Sakit... aku tak tahan lagi... kumohon, bunuh saja aku!” Inayah terisak tak berdaya. Sekali lagi Mandra mengangkat cambuknya...
“Biadab!” Igo berkata tajam. “Kalian tunggu di sini, biar aku yang masuk!”
Igo tak tahan lagi. Dia menyuruh kami minggir dan menendang pintu. Pintu kayu yang dipalang dari dalam itu berdebam keras dan roboh ke lantai. Igo berdiri di sana, jaketnya berkibar seperti pahlawan. Sosoknya pasti terlihat mengesankan dilihat dari dalam ruangan, dengan latar belakang hutan gelap di belakangnya. Wajahnya murka menatap Mandra.
Bagaimana Igo bisa tampil sekeren itu? Tokoh utamanya kan aku! Pikirku muram. Melihat ada yang menerobos masuk, Mandra hanya menoleh pelan, tak tertarik. Dengan kasar, Inayah dijatuhkannya ke lantai. Pria itu mendengus, “Siapa kau?”
“Aku orang yang akan menghajarmu,” jawab Igo, dadanya naik turun. Sekilas dia melirik istrinya yang tergeletak di lantai dan menangis terisak-isak, kemudian kembali menatap pria di depannya. “Apa kau yang bernama Mandra?”
Mandra tak menjawab, mengukur kemampuan lawan di depannya, tak menganggapnya sebagai ancaman. “Oh, kau rupanya. Akhirnya datang juga. Mana temanmu yang lain? Tahu tidak, sudah lama aku menunggu kalian.”
Di lantai, Inayah memekik, “Kang Igo, kau datang!”
“Lepaskan dia!” Igo berteriak, ketenangannya mulai goyah. “Dan berani-beraninya kau melepas kerudungnya! Jika lebih dari itu, kubunuh kau!”
Mandra mendengus sebagai jawaban, lalu menginjak betis Inayah, membuat wanita itu menjerit kesakitan. Igo meraung marah, lalu melompat maju dan menendang perut Mandra, hingga pria itu terlempar ke belakang dan menimpa sesuatu yang tampaknya tumpukan kotak kayu lapuk. Setelah mataku terbiasa dengan keremangan, tampak banyak sekali tumpukan peti kemas memenuhi ruangan ini. Peti-peti inilah yang diangkut orang-orang berbaju hitam tadi ke kapal. Tampaknya bunker ini dialihfungsikan sebagai gudang penyimpanan atau semacamnya. Igo menurunkan kakinya, mengawasi tubuh Mandra yang lenyap di balik kepulan debu. Sesaat kelihatannya Igo menang, tapi kemudian Mandra bangkit lagi, tampak tak merasa kesakitan sedikitpun, berjalan santai mendekati Igo.
“Kau namakan itu tendangan? Terasa geli pun tidak,” katanya dingin. “Untung aku menahan diri. Kalau kucabut senjataku sekarang—” dia menyentuh saku celananya, “—kau akan mati dalam hitungan detik. Nah, kau mau mati sekarang atau nanti?”
“Wah, wah, kita kedatangan tamu,” terdengar suara kedua, suara kasar dan bergemuruh seperti guntur. Aku menyipitkan mata, silau, ketika lampu lain menyala dan menerangi seisi ruangan, hanya menyisakan sedikit kegelapan di balik pintu yang menuju ruang tengah. “Tak kusangka kau menuruti kemauan kami untuk datang ke tempat ini. Kau mudah sekali terpancing. Hebat juga kau bisa mengalahkan tiga petinggi Jerangkong.”
Aku menegang saat sosok kedua muncul dari balik kegelapan. Tubuhnya tinggi besar, mengenakan jaket kulit bermerk, wajahnya tampak mengerikan dengan berewok lebat dan rambut yang gimbal. Pria itu Marsekal Taher alias Brewok—buronan yang satu lagi. Seorang mantan marinir, bos besar narkoba, penjahat kelas kakap, dan mantan kolega ayahku. Dengan santai, Brewok melangkah ke sebelah Mandra, mengawasi Igo.
“Ah, ya, rekanku memang sedikit kasar, tapi sudah lama dia tak tertarik dengan wanita, beda denganku,” Kata Brewok. “Tapi tenang saja, cewekmu yang aduhai itu tidak kusentuh sedikitpun, setidaknya belum. Setelah selesai membereskan kalian, aku akan bermain-main dengannya.” Dia menjilat bibir, melirik Inayah yang terkulai di lantai.
“Kalian... bagaimana kalian bisa mengikuti kami?” geram Igo. “Apa kalian dendam karena kami menghajar anak buah kalian di Jakarta? Atau karena temanku mencuri-dengar rencana busuk kalian di Flores?”
Brewok terbahak mengerikan. “Mudah sekali bagi kami untuk melacak kalian. Aku bos dunia bawah yang punya ribuan kaki-tangan di berbagai pelosok. Tinggal suruh mereka, masalah beres. Anak buahku bisa siapa saja, tukang pos, petani, hingga kelasi kapal. Tapi memimpin sambil duduk-duduk di belakang meja bukan gayaku. Untuk menghindari risiko kegagalan, aku memutuskan turun tangan langsung, menyamar untuk menghindari polisi, dan akhirnya sampai di sini. Tempat ini sepi dan terpencil, sangat cocok untuk dijadikan ladang pembantaian. Lagipula aku punya markas di sini. Dan satu lagi yang perlu kauketahui, aku tidak membuntuti kalian karena ulah kalian yang menghajar anak buahku di Jakarta. Itu terlalu sepele, tak ada artinya bagi kami.”
“Lalu, apa alasan kalian?”
Brewok menggebrak tembok dengan sebelah tangannya. Aku ngeri melihat tembok tua kokoh buatan Jepang itu retak dan ambrol dengan sekali pukul. Tenaganya tak tanggung-tanggung. Sekuat apa sebenarnya orang ini?
“Sudah cukup bicaranya,” dia menggeram. “Bagaimana kalau kita undang dua tikus yang bersembunyi di luar itu? Ayo kemari, jangan malu-malu.”
Aku menelan ludah, kami ketahuan. Sadar Igo dalam bahaya, aku dan Harto keluar dari persembunyian, berjalan masuk dan berdiri di samping Igo, menghadapi dua penjahat itu.
“Nah, bagus juga kalian semua datang,” Brewok tertawa. “Tapi ini tidak adil bukan? Tiga melawan dua, benar-benar tidak seimbang. Betul kan, Mandra?”
Mandra tak menjawab, ekspresinya sedingin es. Matanya yang tajam masih mengawasi kami. Aku sadar dua orang ini benar-benar berbahaya, melihat sikap mereka yang terlalu tenang. Bisa saja mereka bukan tandingan kami. Tapi aku takkan gentar.
“Kau!” Harto menunjuk Mandra. “Kau yang membunuh orangtuaku. Apa kau ingat? Aku putra tunggal dari Wiranto Kusuma, orang yang kaubunuh dengan keji.”
Mandra menelengkan kepalanya, mengamati Harto dari ujung kaki hingga ujung kepala. Sesuatu berkilat di mata kirinya yang sehat. “Oh, kau anak kecil waktu itu. Ya, aku ingat. Walau aku sering melakukan pembunuhan, aku tak mungkin lupa yang satu itu. Gara-gara kau, aku kehilangan sebelah mataku. Malam itu, saat aku hendak merampok rumahmu, orangtuamu memergokiku dan berteriak minta tolong. Menyebalkan sekali, aku benci melihat mereka berteriak, jadi kubantai saja mereka. Kebetulan aku punya dendam pribadi pada ayahmu. Aku suka melihat darah mereka membanjiri lantai.”
Mandra menengadah menatap langit-langit yang kusam. “Sebetulnya dulu aku ingin membunuhmu juga, tapi ibumu membawamu lari dan melindungimu dengan punggungnya. Aku terkejut wanita itu masih sanggup bergerak setelah kutusuk berkali-kali. Kasih sayang seorang ibu, rupanya, benar-benar memuakkan. Aku, yang dibuang ibuku sejak kecil dan hidup di jalanan, tak pernah merasakan hal seperti itu. Sayang sekali, sebelum aku sempat membunuhmu, orang-orang berdatangan dan mengepung rumah. Aku terpaksa menyelinap lewat jendela belakang dan kabur. Tapi kesialan sedang menimpaku hingga harus dijebloskan ke penjara terkutuk itu. Seumur hidup, itu salah satu kegagalan paling memalukan yang pernah kulakukan. Tapi sekarang, aku menemukan kembali kesempatan itu.”
“Kurang ajar kau—” Harto hendak menerjang, tapi Igo menahannya.
“Nanti, ada waktunya untuk membalas,” katanya pada Harto, kemudian dia menatap kedua penjahat bergantian. “Kalian belum menjawab pertanyaanku. Sebenarnya apa tujuan kalian menculik Inayah dan membawa kami ke sini?”
“Aku senang kau bertanya,” kata Brewok, matanya teralih padaku. “Kau, namamu Lutfi kan? Kaulah sasaran utamaku. Aku sudah lama menunggu saat ini. Sudah banyak biaya yang kukeluarkan untuk membawamu ke tempat ini. Biar kuberi tahu, akulah pemilik perusahaan Shen Travel yang membiayai ekspedisi kalian.”
“Bohong!” teriakku. “Aku sudah tahu siapa kau. Dulu kau memang pemilik perusahaan itu, tapi setelah kau dipenjara, perusahaan itu milik keluarga Zhen, teman kami.”
“Tidak, tidak, sampai sekarang pun perusahaan itu masih milikku,” Brewok tertawa ganjil. “Memang benar aku sudah menyerahkan mandat perusahaan ke kolegaku sebelum aku dipenjara, tapi seluruh aset dan hak milik Shen Travel tetap ada di tanganku. Aku sengaja mengubah kepemilikan Shen Travel atas nama orang lain, agar semua hartaku di perusahaan itu—yang sebagian besar kuperoleh dari bisnis gelapku—tak terlacak polisi.”
“Ya, aku tahu orang macam apa kau,” kataku, teringat catatan di halaman terakhir jurnal Ayah. “Aku tahu kalau suatu saat kau pasti mengincarku. Dulu kau teman Ayahku. Setelah dipecat dari Angkatan Laut, kau membangun bisnis bersama Ayah, lalu dengan licik kau memanipulasi data dan membuat semua saham perusahaan beralih ke tanganmu. Itulah yang membuat Ayah murka dan memecatmu. Setelah itu kau semakin jatuh dalam keserakahan, terjun ke bisnis narkoba, penebangan liar, dan mendirikan perusahaan tandingan yang korup. Shen Travel salah satunya. Bahkan setelah dipenjara, kau masih menyimpan dendam pada Ayah yang kini entah ada di mana, lalu melampiaskannya padaku. Dari balik layar, kau terus memata-mataiku, lalu merencanakan program keliling Indonesia itu sebagai kamuflase untuk menjebakku. Kau memperalat Zhen dan kakaknya yang tak tahu apa-apa, untuk memberi kami tiket ekspedisi itu, iya kan?”
Harto menoleh padaku. “Benarkah itu, Lutfi? Jika dia yang punya perusahaan itu, aku tak sudi dibiayai orang seperti dia. Tadi dia bilang sendiri, harta miliknya tidak halal.”
“Kalian tenang saja,” kataku. “Kita tak berutang budi apapun padanya, karena aku akan mengembalikan semua dana yang diberikan perusahaannya. Paman Ilyasa sudah menduga ini akan terjadi. Seminggu sebelum berangkat, Paman memberiku sesuatu untuk jaga-jaga, sesuatu yang sangat berharga—kartu ATM perusahaan ayahku. Semua pengeluaran selama perjalanan kita kemarin, mulai dari biaya penginapan, tiket pesawat, ongkos mobil, hingga makan di restoran, semuanya akan kuganti.”
Aku memandang Brewok, membandingkan penampilannya sekarang dengan foto yang diperlihatkan Paman. Dulu wajahnya teduh, bersih dan rupawan, namun kini tampak bengis dan mengerikan, tak lagi ramah seperti di foto itu. Menurut cerita Paman, saat masih kecil dulu Brewok alias Li Shen adalah anak ceria bertubuh sehat, paling besar di kelasnya. Dia juga siswa berprestasi, IQ-nya di atas 150, nilai rapornya bagus dan sering jadi juara sekolah. Dia kemudian masuk militer setelah lulus akademi dengan nilai tertinggi, dan cepat naik pangkat berkat prestasinya yang melejit.
Namun nasibnya berubah setelah orangtuanya bercerai, rumah tangganya berantakan dan tak jarang dia jadi pelampiasan kemarahan sang ayah. Dia melarikan diri dari rumah, frustrasi dan terbuang, merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Tak cukup sampai di situ, dia dijebak dan dipermalukan atasannya sehingga dia dipecat secara tidak hormat. Semua penghargaan yang diraihnya selama ini dilucuti. Sejak itulah sifatnya berubah. Untuk bertahan hidup, dia bersedia melakukan apa saja, termasuk menipu ayahku, hingga akhirnya berkenalan dengan bisnis dunia hitam. Tampak luar, dia seperti pebisnis sukses yang terhormat, tapi di balik itu dia menyimpan iblis dalam dirinya.
“Sepertinya ada beberapa hal yang belum kauketahui, Anak Muda,” Brewok tertawa semakin keras. “Ada untungnya juga aku mengeluarkan banyak uang untuk kalian. Ekspedisi itu memang makan biaya besar, tapi program itu sejak awal memang dibuat untuk promosi perusahaanku. Aku tinggal menikmati hasilnya nanti. Lagipula, bukan hanya itu alasanku membawa kalian ke sini.”
Pintu belakang menjeblak terbuka, membawa hembusan angin masuk. Tampak seorang lagi melangkah masuk ke ruangan. Aku menatap sosoknya yang samar. Pria itu ternyata Zhen. Aku bernapas lega, gembira melihatnya datang. Akhirnya dia muncul untuk membantu kami. Kemampuannya dalam beladiri akan sangat membantu dalam perkelahian melawan dua pria berbahaya ini.
Namun aku kaget karena Zhen bergabung dengan dua penjahat, memelototiku. Brewok menepuk-nepuk bahunya. Kegembiraanku lenyap digantikan keheranan.
“Tujuan kami... adalah untuk menghabisi kalian, dan kau, Lutfi, ada sesuatu yang kami inginkan darimu,” kata Zhen, kesintingan membara di matanya. “Sekarang, tiga lawan tiga.”
*****


 radenbumerang
radenbumerang




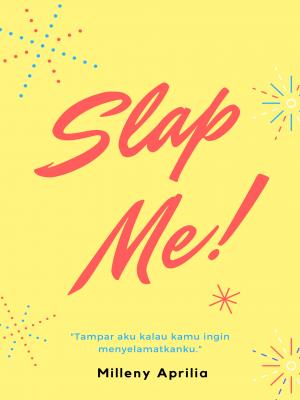



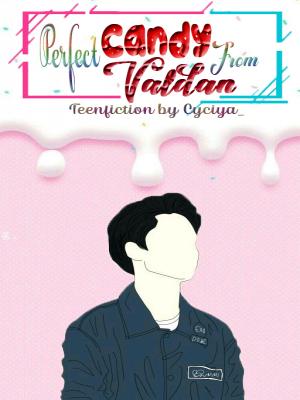

Iya juga yah, satu bab aja sepanjang ini... makasih masukannya Mas AlifAliss, mungkin ke depannya saya bagi per bab aja biar lebih pendek.