BAB 13. AKU TAK BISA MEMBENCI HUJAN
HARI KE-60, TERNATE
Aku tak bisa membenci hujan. Air berderai di sekitarku, menciprati wajah dan bajuku yang kepalang basah kuyup. Kami berteduh di halte, sesekali mundur menghindari cipratan lumpur yang dilontarkan roda mobil. Langit tak berhenti menangis sejak beberapa jam lalu. Aku sedikit kecewa karena hujan membuat perjalanan kami tertunda lagi. Sesekali sambaran kilat meluncur menuruni atmosfir diikuti gemuruh guntur memekakkan telinga. Beberapa wanita menjerit, seorang anak laki-laki penjual koran memeluk dagangannya.
Sejak dulu, hujan selalu menghalangi kegiatanku. Saat masih kuliah dulu, aku pernah terlambat dan dimarahi dosen, terjebak berjam-jam di tengah perjalanan, jemuranku tak kunjung kering sehingga aku harus memakai baju yang sama berhari-hari, dan laporanku telat kukumpulkan sehingga aku mendapat nilai jelek. Semuanya gara-gara hujan. Namun entah mengapa, aku tak pernah bisa membenci hujan. Bagaimanapun, hujan diturunkan Allah ke bumi untuk kesejahteraan makhluk hidup termasuk tumbuh-tumbuhan dan manusia. Ribuan malaikat diterjunkan menyertai tiap tetesan air, membawa rahmat dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Malah aku senang kalau hujan deras seperti ini, karena ketika hujan adalah salah satu waktu yang mustajab dikabulkannya doa.
“Koran Mas?” seorang anak laki-laki menawarkan dagangannya.
“Boleh,” kataku, merasa lebih baik membaca sesuatu daripada bosan menunggu hujan reda. “Siapa namamu?”
“Alan, Mas,” katanya, memberikan koran yang kupesan.
“Kamu masih sekolah?” tanya Harto.
“Masih, Mas, makanya saya jualan koran untuk membiayai sekolah.”
Aku merogoh dompet, lalu memberikan uang sepuluh ribuan padanya.
“Ambil saja semua, saya ikhlas,” kataku. Anak itu menerimanya dengan agak ragu, lalu berlari ke arah jalan. Aku memerhatikan dengan penasaran, heran ketika uang pemberianku diberikannya pada pengemis di tepi jalan. Setelah itu, Alan kembali ke halte untuk menawarkan koran pada orang yang baru datang. Aku penasaran ingin menanyainya lagi.
“Dek, uangnya kok malah dikasih ke pengemis?”
Alan menengadah, wajahnya kucel namun tampak ceria. “Hitung-hitung sedekah, Mas, hehe. Saya selalu diajari Ibu supaya hidup mandiri, tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Jadi, kalau ada orang yang memberi uang, saya berikan lagi uang itu ke orang yang lebih membutuhkan, gitu Mas, hehe. Meski kondisi saya begini, saya merasa tak pantas menerima sumbangan. Saya lebih suka jajan pakai uang hasil kerja sendiri, yang penting halal, gitu Mas.”
Aku mengangguk-angguk, salut pada prinsipnya yang layak ditiru. Meski sepertinya serba kekurangan, anak ini memiliki mental orang kaya yang tak pikir-pikir dulu sebelum memberi. Tangan di atas memang lebih baik daripada tangan di bawah.
Alan membungkuk padaku, kemudian berlari menerobos hujan untuk menjajakan koran di seberang jalan. Aku membuka-buka koran yang kubeli dan mencari info menarik. Hujan tampaknya akan melanda seisi Pulau Jawa pada bulan ini. Beberapa daerah di Jakarta malah sudah mulai direndam banjir bandang. Aneh juga, padahal sekarang waktunya musim panas.
Ketika membuka halaman berikutnya, aku terkejut.
“Lihat ini,” kusenggol Harto dan Nasuti, menunjukkan berita tentang aksi brutal Geng Motor Makassar yang memakan korban jiwa. Tak salah lagi, itu nama geng yang berkonflik dengan kami beberapa hari lalu. Gerombolan sadis itu melakukan konvoi dan merusak toko-toko di sepanjang jalan, bahkan tak segan menyerang warga yang lewat dengan senjata tajam. Dua nyawa melayang dan lima lainnya luka-luka akibat ulah mereka. Sayangnya para pelaku belum tertangkap dan saat ini masih diburu polisi. Ketika melihat nama lokasi naas itu, kami semua terkejut.
“Itu daerah yang kita lewati beberapa hari lalu kan? Lihat, nama jalannya sama,” Harto memekik. “Pasti para pelakunya sama dengan yang menyerang Nasuti.”
“Alhamdulillah aku bisa selamat dari tragedi itu,” kata Nasuti. “Kalau waktu itu tidak ada Zefry yang menolongku, entah apa yang akan terjadi padaku. Mereka banyak sekali dan membawa senjata, sedangkan aku cuma sendirian. Berkelahi pun percuma.”
Nasuti mengelus dada dan bernapas lega, bersyukur telah diselamatkan dari takdir buruk dengan cara tak terduga. Tuhan masih menjaga kami, berkat doa dari ibuku, Paman Ilyasa, Ruqoyah, Nelly, Dokter Isnain, Pak Asep, dan orang-orang yang kami tinggalkan.
Syukurlah, ketika penat mulai menggerayangi kakiku, hujan perlahan mulai menipis dan akhirnya reda. Gunung Gamalama yang sejak tadi terhalang kabut pun mulai tampak lagi kegagahannya. Para penduduk kota mulai sibuk beraktivitas kembali. Dengan semangat baru, kami melanjutkan perjalanan menelusuri jejak sejarah di Kota Ternate yang elok ini.
“Sejak ratusan tahun silam, kota yang terletak di pulau kecil ini terkenal sebagai penghasil rempah-rempah yang menarik perhatian bangsa Eropa, hingga berujung penjajahan selama beberapa abad,” kataku. “Dulu, kapal-kapal dari seluruh penjuru dunia berlalu-lalang di kota ini, menjadikannya tempat persinggahan dan pusat perdagangan yang tersohor hingga ke Arab dan Cina. Sayang memang, negara kita ini terkenal dengan hasil buminya yang melimpah, makanya jadi bahan rebutan para penjajah.”
“Dulu aku cuma tahu Kota ini dari buku-buku sejarah,” kata Harto. “Sekarang akhirnya aku bisa melihat sendiri suasananya, lingkungannya... ternyata menyenangkan.”
Kami berjalan-jalan di Pantai Sulamadaha, mengamati laut yang jernih dihiasi terumbu karang sambil menyantap seporsi kepiting kenari dan susu jahe khas Maluku. Kami juga mendokumentasikan bangunan-bangunan bersejarah seperti Benteng Tolukko peninggalan Portugis, Masjid Sultan Ternate dan Keraton Kesultanan Ternate yang masih menyisakan kemegahan masa lalu. Rencananya, kami juga akan singgah sejenak ke Pulau Halmahera untuk melacak keberadaan Suku Lingon—sekelompok orang yang tinggal di pedalaman hutan yang konon memiliki mata biru dan keberadaannya dianggap legenda. Aku juga penasaran dengan Pulau Dodola yang terkenal dengan pasir putihnya itu.
“Katanya cewek Suku Lingon cantik-cantik lho, kayak bule,” kata Nasuti. “Siapa tahu nanti ada satu yang kepincut denganmu, Lutfi. Biar kamu nggak jomblo lagi.”
Nasuti langsung lari saat aku melemparinya dengan pasir.
*****
HARI KE-62, PULAU SERAM
Sayangnya, niatanku untuk bertualang di Halmahera harus kandas karena waktu yang mendesak. Dari sms Torik, aku tahu kelompok Zhen sudah tiba di daerah Banggai, Sulawesi Tengah. Jadi aku harus menyingkat perjalanan jika tak ingin keduluan mereka di garis finish. Jangankan ke Pulau Dodola atau mencari Suku Lingon, kami hanya sempat mampir sebentar di Halmahera untuk dokumentasi, lalu langsung meluncur ke Pulau Seram dengan pesawat pribadi yang disediakan perusahaan Zhen. Meski buru-buru, aku tak bisa melewatkan pulau ini karena ada satu lokasi yang sangat kuidamkan sejak dulu.
Tiba di Bandara, yang pertama kulakukan adalah mencari penginapan. Ada satu peristiwa yang sulit kulupakan. Di perjalanan, kami berpapasan dengan seorang pria jangkung di tepi jalan. Mendadak, perasaanku bergejolak aneh. Aku mematung, membiarkan teman-teman berjalan mendahuluiku. Pria itu memakai topi koboi yang sama sepertiku, dan wajahnya terasa familiar, tak asing bagiku. Seakan ada kenangan tersembunyi yang bangkit kembali dalam jurang terdalam pikiranku. Entah mengapa lidahku tiba-tiba bergerak sendiri, tanpa sadar aku berkata, “Ayah?”
Ketika menoleh, pria itu sudah tak tampak ditelan kerumunan massa yang berlalu-lalang. Aku tertegun, masih menatap ke belakang ketika Harto mengamit lenganku dan mengajak pergi. Aku angkat bahu, sudahlah, mungkin itu cuma perasaanku. Kami segera mencari hotel karena malam turun dengan cepat.
Esoknya kami mencarter mobil dan memasuki kawasan Taman Nasional Manusela, melintasi hutan lebat dan memandangi Gunung Binaiya yang kokoh di kejauhan. Gunung setinggi tiga ribu meter itu adalah gunung tertinggi di Maluku, salah satu Seven Summits of Indonesia yang menjadi incaran para pendaki, termasuk aku. Sayangnya aku harus melawan godaan untuk mampir, karena lokasi yang kami tuju jauh lebih menakjubkan.
Beberapa jam kemudian kami tiba di salah satu surganya Maluku, wisata yang tak kalah elok dari Bunaken atau Derawan. Tiba di sana, teman-temanku ternganga kagum. Di depan kami terbentang salah satu pantai terindah di Indonesia, yakni Pantai Ora yang terletak di utara Pulau Seram. Pondok-pondok kayu berdiri elok di atas air, bersebelahan dengan pantai dan menghadap laut lepas. Tak jauh dari jajaran pondok itu ada sebuah jembatan yang menjorok ke laut, tempat kami duduk santai sambil memandangi perairan jernih yang penuh dengan terumbu karang. Warna-warni dan beragam bentuknya, bertebaran tak jauh dari kaki-kaki kami yang menjuntai. Bukit-bukit batu menjulang melatari pemandangan ini, semakin elok saat cahaya mentari menyirami rimbunan pohon di kaki bukit.
“Subhanallah, bagus banget sumpah,” Harto menyembulkan kepalanya setelah puas menyelam bersama Nasuti. “Koralnya deket banget, dari atas juga kelihatan jelas.”
“Baguslah kalau kalian puas,” kataku, berkeliling pantai dengan perahu sewaan. “Sejak kecil aku selalu ingin mengunjungi tempat ini. Biasanya cuma lihat fotonya di internet.”
“Kang, nanti kapan-kapan kita ke sini lagi ya,” Inayah tersenyum menatap suaminya. Mereka ikut mendayung bersamaku, seraya menikmati pedasnya rujak suli khas Ambon.
Setelah hampir seharian bermain di pantai, kami melanjutkan perjalanan meski rasanya enggan. Pengalamanku di Pantai Ora rasanya seperti mimpi, mau dilupakan pun tak bisa. Di tengah jalan, kami minta berhenti sebentar saat ada sekelompok warga yang melakukan tarian adat Si Bambu Gila. Beberapa pria tampak berkeringat saat memegang bambu panjang yang konon bisa meronta-ronta sendiri. Mereka tampak kesulitan, sekuat tenaga mengendalikan si bambu yang seolah menggila dan bertambah berat berkali-kali lipat. Bukan cuma menonton, kami juga ikut mencoba memegangi bambu tersebut, dan ternyata memang berat sekali.
“Seru ya pertunjukkannya,” kata Igo puas setelah tarian selesai, diakhiri tepuk tangan warga yang menonton. “Aku baru tahu kalau ada tarian adat seperti itu.”
“Menarik memang,” Harto tersenyum melihat rekamannya.
Setelah puas menonton, aku meminta supir melanjutkan perjalanan. Setelah lima jam yang terasa lambat, kami tiba di pelabuhan, menunggu kapal yang akan membawa kami ke Ambon. Teman-temanku beristirahat sementara aku pergi membeli karcis. Aku sendiri lelah bukan main, memutuskan hendak tidur sejenak di kapal nanti. Saat menunggu antrean, seorang pria duduk di sebelahku sambil membaca surat kabar. Kutatap sekilas pria itu, namun wajahnya tak terlihat karena terhalang bentangan koran.
“Lagi liburan ya, Dik?” dia menyapaku, menurunkan korannya.
Aku terbelalak. Itu pria yang berpapasan denganku kemarin! Tak salah lagi, wajah yang kulihat di hadapanku ini mirip sekali dengan foto Ayah, meski penampilannya sedikit berbeda. Tubuhnya tinggi tegap, mengenakan kemeja aloha dan celana loreng khas tentara. Mungkin dia anggota TNI yang sedang berlibur. Topi koboi cokelat masih bertengger di kepalanya seperti kemarin. Aku agak gentar saat dia mengamatiku.
"Kau dari Jawa kan?” tanyanya, dan aku mengangguk. “Menarik sekali, padahal masih usia SMA, tapi sudah berani melanglang buana ke tempat jauh.”
"Saya sudah lulus kuliah Om,” kataku, bosan harus menjelaskan ini hampir ke setiap orang. Pria itu terkekeh dan menepuk bahuku, minta maaf.
“Topi yang bagus Dik, sama seperti punyaku,” komentarnya, menunjuk topi koboiku. Pria itu melipat korannya, lalu membuka sebuah map dan memeriksa dokumen. Aku melirik sekilas lembaran kertas yang dia amati, kelihatannya seperti sketsa-sketsa wajah penjahat. Melihat salah satu wajah, aku berseru kaget. Pria itu mendongak.
“Maaf saya tak sengaja melihat dokumen Anda. Tapi saya pernah bertemu orang yang mirip dengan sketsa itu. Yang kumisnya baplang.”
“Sungguh?” dia tampak tertarik. “Di mana?”
“Di daerah dekat Samarinda, beberapa hari lalu. Saya satu mobil dengannya, sebelum saya dan teman-teman diturunkan di tengah jalan. Waktu itu si pria berkumis sedang tidur dan memeluk senapan, jadi kami enggan menyapanya. Apalagi dia sepertinya orang asing.”
“Ya, memang. Dia warga negara India yang masuk secara ilegal, sudah lama jadi buronan polisi. Namanya Akhsay Singh. Pekerjaan utamanya berdagang tanaman obat, tapi dia juga bekerja sambilan sebagai pemburu liar. Seminggu lalu ada laporan tentang ditemukannya bangkai rusa tanpa kepala di Gunung Leuser, Aceh. Itu pasti ulahnya. Sayangnya pria ini sangat licin dan sulit ditangkap. Biasanya dia bekerja sendirian, menangkap gajah, badak dan hewan yang dilindungi, tanpa memakai jebakan atau senjata apapun. Senapan yang dibawanya hanya hiasan. Kabarnya dia memburu mangsanya dengan cara aneh, yaitu dengan menjinakkannya. Selain itu ada saksi yang mengatakan bahwa pria ini membawa harimau peliharaannya ke mana-mana.”
Aku merenung, teringat pengalaman mengerikan saat diturunkan di tengah hutan beberapa hari lalu. Ini menjelaskan mengapa kami melihat harimau di hutan Kalimantan. Pasti itu peliharaan si pemburu. Apalagi saat itu dia satu mobil denganku. Mungkin dia hendak berburu rusa dan turun di lokasi tak jauh dari tempatku berkemah.
“Masih satu grup dengannya, ada juga enam orang lain yang sama merepotkannya. Salah satunya adalah orang ini.” Pria bertopi koboi itu membuka halaman berikutnya—gambar sketsa lainnya. Kali ini wajah tersenyum seorang pemuda dengan sorot mata lembut. “Jangan tertipu dengan wajahnya yang ramah, karena orang ini adalah pimpinan geng motor paling ditakuti di wilayah Indonesia Timur. Namanya Zefry, dan dia juga sulit ditangkap.”
Aku terkejut lagi mendengar nama itu. Mungkinkah dia pemuda berambut hitam yang menolong Nasuti beberapa hari lalu? Jika mendengar penuturan Nasuti, deskripsi fisiknya memang cocok dengan pemuda di sketsa itu. Pantas saja anggota geng motor itu takut saat dia muncul. Ternyata dia bosnya. Aku harus memberitahu Nasuti soal ini.
“Sebenarnya ini file rahasia, tapi tak ada salahnya kuberitahu padamu. Kuharap kau bisa membantu kami dengan menceritakan apa yang kau tahu. Apalagi keberadaan mereka sangat berbahaya bagi warga sipil. Ini daftar orang yang jadi target operasi kami, tujuh orang pentolan organisasi radikal berbahaya yang disebut Jerangkong.”
Mendengar nama itu, lagi-lagi aku tersentak. Itu organisasi kriminal yang merekrut Pak Suno sebelum banting stir jadi nelayan. Preman Jakarta yang kami kalahkan dulu juga pernah menyebutnya. Ternyata mereka saling berkaitan.
“Jumlah anggotanya ribuan, dipimpin tujuh orang ini dan satu orang lagi yang disebut bos besar. Sudah lama kami menyelidiki dan mencari markas mereka. Akhir-akhir ini anak buahku melihat adanya aktivitas mencurigakan di lokasi tertentu: pembunuhan tokoh penting, kecelakaan pesawat, hingga perampokan bank besar-besaran. Bagi orang biasa, deretan tindak kriminal itu seperti tak ada hubungannya, tapi menurut pengamat kami semuanya saling berkaitan dan didalangi organisasi yang sama. Tampaknya mereka mulai bergerak. Ada tujuan besar di balik semua peristiwa itu, dan kuduga otaknya adalah orang ini.”
Pria itu menyibak halaman berikutnya, memperlihatkan sketsa terakhir. Aku tak kaget lagi melihat wajah bercambang dengan rambut gimbal itu. Aku tahu siapa dia. Dialah orang yang kulihat bersembunyi di gubuk tepi pantai di daerah Ende, merencanakan sesuatu dengan rekannya sesama buronan.
“Dia bos besar dari organisasi Jerangkong. Dia punya banyak nama samaran dan sulit ditangkap, perlu lusinan anggota densus untuk meringkusnya. Dia dipenjara selama beberapa tahun, tapi berhasil meloloskan diri. Namanya Marsekal Taher alias Brewok, alias Li Shen.”
Li Shen? Mendengar nama itu aku terperanjat kaget, bahkan lebih mengejutkan dari nama-nama yang disebut sebelumnya. Saat mengintip gubuk waktu itu, pantas saja rasanya aku pernah melihatnya. Orang itu ada di foto yang diperlihatkan Paman, tengah berpose bersama Ayah di depan Menara Eiffel. Aku tak menyangka jika buronan itu orang yang sama. Penampilannya memang banyak berubah, termasuk raut keturunan Cina-nya yang tak kentara karena tertutup brewok. Tapi sorot matanya yang ambisius masih tetap sama. Dialah orang yang dulunya memimpin perusahaan Shen Travel yang membiayai ekspedisiku.
“Dia mantan perwira TNI Angkatan Laut, pernah satu divisi denganku, hingga dia dipecat dengan tidak hormat. Aku sangat mengenalnya. Dulu dia baik dan ramah, hingga ada kejadian tertentu yang membuat sifatnya berubah. Banyak sekali catatan kejahatan yang dia lakukan. Mulai dari pembunuhan berencana, terorisme, pembalakan hutan, pengedaran obat terlarang, hingga korupsi licik yang membuatnya didepak dari perusahaannya sendiri.”
Pria bertopi koboi itu memperlihatkan sketsa wajah pria lainnya yang diduga bekerja sama dengan Brewok, berikut catatan kejahatan mereka. Informasi ini cukup akurat, berkat mata-mata TNI yang menyusup ke sarang musuh. Selain Brewok, dari tujuh orang pentolan Jerangkong, baru empat orang yang diketahui identitasnya. Perlahan pria bertopi koboi itu mendongak saat ada yang memanggilnya. Tak jauh dari kami, seorang pria berseragam tentara melambai padanya, memberi hormat.
“Ah, rekanku sudah datang. Lama sekali aku menunggunya. Nah, aku harus segera pergi, Dik. Semoga sukses dengan perjalananmu. Jika kau melihat orang-orang di sketsa tadi, segera hubungi nomor ini.”
Pria itu memberiku secarik kertas, menepuk bahuku sebelum pergi. Aku membuka mulut untuk bertanya lebih jauh, tapi lidahku mendadak kaku. Aku menatap punggungnya ragu. Entah mengapa, aku masih merasa kalau dia ada hubungannya dengan ayahku.
Akhirnya suaraku terkumpul juga. “Tunggu, sebenarnya siapa Anda?”
Pria itu berbalik dan menatapku, tersenyum, perlahan mengulurkan tangannya. “Maaf lupa mengenalkan diri. Namaku Joe Jauhari, panggil saja Kapten Jojo.”
Aku mengangguk, mengamati pria itu berjalan pergi. Aku tertegun sejenak, hingga petugas loket memanggilku. Setelah mendapatkan tiket, aku dan teman-teman mengantri naik ke atas kapal. Aku masih penasaran siapa sebenarnya Li Shen dan apa hubungannya dengan Ayah. Jadi, sepanjang perjalanan menuju Ambon, aku membuka-buka jurnal Ayah, hingga menemukan sesuatu yang menarik. Selama ini aku hanya membaca bagian awal jurnal yang berisi info wisata dan foto-foto Ayah saat bertualang bersama Paman. Aku tak menyangka jika kunci dari semua kasus itu ada di halaman terakhir, di mana terdapat catatan kecil tentang teman lama Ayah yang bernama Li Shen.
*****
HARI KE-64, AMBON
Petualangan kami di Kota Ambon tak begitu menyenangkan. Mendung kelam menggayut menaungi seisi pulau, sehingga kami hanya sempat mengunjungi Patung Pattimura dan Tugu Trikora. Itu pun hanya sekedar lewat. Untunglah sebelum terjebak hujan deras, kami berhasil menemukan penginapan murah di pinggiran kota.
Jam dinding menunjukkan pukul dua siang. Perlahan aku melangkah ke jendela, menatap hujan deras yang masih mengamuk di luar sana. Padahal ini bulan Juli, waktunya kemarau merajalela, tapi masih ada saja hujan yang menyasar seolah tak kenal waktu. Jemariku terulur, mencoret-coret kabut tipis yang terbentuk di kaca. Tatapanku sendu memerhatikan pepohonan berguncang dipermainkan angin. Bunyi tetes hujan yang menerpa jendela masih seramai sebelumnya, seakan enggan berhenti, dan kabut di kaca semakin tebal.
Kami terjebak di penginapan hingga malam harinya, terpaksa menunda perjalanan lagi. Hujan membuat kami bosan, karena tak banyak yang bisa dilakukan. Mungkin hujan juga yang membuatku gampang emosi. Entah berapa kali aku menggeram dan membentak teman-temanku hanya karena masalah kecil. Semua itu kulakukan tanpa kusadari. Pikiranku benar-benar sedang kacau. Entah setan apa yang mengambil alih kesadaranku.
“Berhentilah mengeluh, Nasuti, omelanmu tak akan membuat hujan ini reda. Jangan duduk-duduk di sofa terus. Igo, jangan cemberut saja dan lakukan hal yang berguna. Dan kau, Harto, jangan menggangguku terus! Biarkan aku istirahat sebentar!”
Aku berteriak-teriak di luar kendali. Situasi semakin panas meski hujan di luar dingin membekukan sumsum. Rasanya ada yang salah dengan semua yang kulihat. Mereka hendak menjawab dengan pedas, membela diri. Untunglah pertikaian dicegah dengan munculnya ibu pemilik penginapan. Kami terdiam seketika, agak malu.
“Mas Lutfi, ini ada surat untuk kalian.”
“Lho, surat dari siapa Bu?” tanyaku, menerima amplop.
“Tidak tahu. Tadi ada tukang pos datang, katanya ini surat buat Mas Lutfi.”
Begitu pemilik penginapan pergi, kami langsung merubung untuk memeriksa surat itu. Pertengkaran tadi menguap begitu saja, terlupakan sama sekali.
“Siapa nama pengirimnya?” tanya Igo.
"Nggak ada,” kataku, memeriksa surat yang agak basah.
"Emang apa sih isinya? Coba dibuka!” saran Harto.
Aku agak ragu membukanya. Baru-baru ini aku sering sekali mendapat sms misterius bernada gombal, yang ternyata dari Nelly. Aku khawatir surat ini sejenis itu juga, atau mungkin dikirim orang yang sama. Entah mengapa, firasatku mengatakan surat ini jauh lebih buruk dari itu. Perlahan kurobek bagian tepi amplop, lalu kutarik isinya.
Apa yang kulihat nyaris membuat jantungku copot. Mataku terbelalak, dan teman-teman memekik kaget. Betapa tidak, isinya dua lembar foto mengerikan, menampakkan dua sosok tubuh wanita tergeletak di lantai, dengan kondisi tangan terikat dan mata ditutup kain. Satu memakai kerudung, satunya lagi tidak. Dipastikan kondisi mereka sudah tak bernyawa. Yang membuat ngeri, baju mereka dipenuhi bercak darah, dan luka-luka sayatan di sekujur kulit memberi kesan mereka adalah korban penganiayaan. Begitu melihat wajah mereka, aku lebih terkejut lagi.
“Masya Allah, ini kan Ruqoyah dan Nelly!”
"Ini... ini beneran mereka?” Harto terbelalak. “Oh, tidak, apa yang terjadi dengan mereka? Perbuatan siapa ini? Kejam sekali.”
"Nggak mungkin, ini pasti bohong!” Nasuti menggeleng. “Jangan percaya dulu, pasti ini foto hasil editan. Mereka pasti baik-baik saja. Cepat telepon mereka!”
Panik, aku menyambar HP dan menghubungi Ruqoyah terlebih dahulu. Lama sekali tidak diangkat. Dalam hati aku berpikir, siapa orang gila yang mengirim foto-foto ini. Mana mungkin Nelly tega mengedit fotonya sendiri separah ini, jadi jelas bukan dia. Aku juga tak ingat punya musuh bebuyutan yang seiseng itu. Meski ada beberapa kenalan yang tidak menyukaiku, aku ragu mereka sampai tega meneror dengan cara ini.
“Gagal, tak bisa dihubungi!” kataku, kecewa mendengar suara operator.
“Kalau begitu, coba lagi!” desak Igo, panik.
Aku menurut, menelepon sekali lagi. Tetap saja tak diangkat. Hanya bunyi tuut tuut yang terdengar. Kami semakin khawatir, jangan-jangan memang terjadi sesuatu dengan mereka. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Ayolah, angkat teleponnya, Ruqoyah.
“Halo? Kak Lutfi?” akhirnya, terdengar suara khasnya.
“Halo? Ruqoyah?” sambarku, senang mendengar suaranya. Tak salah lagi, ini pasti dia. Ruqoyah masih hidup! “Kau sedang apa?”
“Hah?” dia seperti kaget kutanya begitu. “Lagi baca buku di kamar. Sekarang kan libur, jadi aku main ke rumah teman. Kenapa tiba-tiba menelepon? Jangan-jangan Kak Lutfi kangen ya?” dia menahan tawa.
Aku hanya ingin memastikan. Kau baik-baik saja kan?”
“Ya, aku sehat kok. Ada apa memang?”
"Akhir-akhir ini, apa kau lihat ada orang mencurigakan di sekitarmu? Ah, gimana bilangnya ya? Ini cuma perasaanku, tapi kalau kau merasa dibuntuti seseorang, segera lapor polisi.” Sengaja tidak kuceritakan tentang foto-foto itu, khawatir membuatnya ketakutan. Mendengar itu, dia malah tertawa.
"Ah, Kak Lutfi ini ada-ada saja. Kalian tahu nggak, rumah temanku ini di mana? Nggak tahu kan? Lagian, memangnya siapa sih yang berani macam-macam denganku? Hmm, berarti benar kata-kataku dulu. Kak Lutfi kebanyakan nonton sinetron, makanya jadi paranoid gitu,” dia menahan tawa lagi. “Eh, udah dulu ya, hampir jam malam lho. Maaf nggak bisa lama-lama, udah ngantuk berat nih. Assalamualaikum.”
"Waalaikumsalam.”
Yang dia katakan ada benarnya juga. Entah perasaanku atau bukan, Ruqoyah sepertinya lebih ceria dibanding saat terakhir bicara denganku. Apa akhirnya dia menemukan penawar hati? Ah, itu nanti saja. Ada yang lebih mendesak sekarang. Setelah tahu Ruqoyah baik-baik saja, segera kutelepon Nelly.
Hasilnya sama saja, tetap tak ada jawaban, bahkan lebih lama dibanding tadi. Keringat dingin merayapi pipiku. Otakku membayangkan hal-hal buruk, kemudian menghalaunya saat itu juga. Mendadak aku ingat bahwa malam ini Nelly berangkat ke Jepang. Pasti dia berada dalam pesawat sekarang. Ketika kuberitahu teman-temanku, mereka justru semakin panik.
“Kita harus pulang!” kata Igo tegas.
"Buat apa? Bukankah kita sudah tahu mereka aman?” ujarku.
“Kita harus memastikan keselamatan mereka,” Igo berkeras.
“Jangan bodoh, ini cuma olok-olok. Lihat, foto ini hasil editan!”
“Bukan itu maksudku!” Igo berbalik menghadapiku. “Aku tahu foto ini palsu, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka! Mungkin saja ada orang-orang jahat yang berniat mengincar Ruqoyah dan Nelly, mengirim foto ini sebagai ancaman, lalu benar-benar menculik dan menyiksa mereka!”
“Dinginkan kepalamu, Igo!” kataku. “Aku tahu ini gawat, tapi coba tenang dulu. Tidakkah kau merasa ini aneh? Jika si pengirim benar-benar mengenalku, bukankah lebih praktis jika dia mengirim foto-foto ini lewat media sosialku? Kenapa harus lewat pos? Bisa jadi tujuannya bukan hanya meneror, tapi juga untuk membuat kita tercerai-berai.”
“Ya,” kata Harto. “Mungkin saja yang diincarnya bukan Ruqoyah dan Nelly, tapi justru kita. Coba pikir, bagaimana orang ini bisa tahu lokasi kita? Timing-nya tepat sekali. Padahal kita dalam perjalanan, pindah-pindah terus, dan baru tiba di penginapan ini siang tadi.”
“Mungkin selama ini ada orang yang membuntuti kita, lalu menyamar jadi tukang pos,” Nasuti angkat suara. “Tahu tidak, aku merasa akhir-akhir ini banyak orang mencurigakan yang mengawasi kita.”
Aku menoleh ke Nasuti, lalu kembali menatap Igo. “Benar, jika kita terus bergerak, kita akan aman. Menurutku, kita teruskan saja perjalanan. Jangan hiraukan foto-foto ini.”
“Kau tidak peduli pada temamu sendiri, Lutfi!” Igo melipat lengan.
“Tidak, bukannya aku tak peduli, tapi aku berpikir jernih dan melihat kenyataan!” kataku, heran sendiri bagaimana tensi pembicaraan naik dengan cepat.
“Ruqoyah dan Nelly dalam bahaya!” Igo sampai berteriak. “Ada yang mengincar nyawa mereka, dan kau malah santai-santai begitu? Aku tak peduli jika kau mau lanjut. Aku akan pulang!”
“Mereka baik-baik saja, Igo!” aku balas berteriak, hilang kesabaran. “Tadi kaudengar sendiri jawaban Ruqoyah, dan Nelly juga kemarin menelponku, mengabari keberangkatan ke Jepang. Lagipula, apa yang akan kaulakukan kalau kau pulang?”
“Setidaknya, memperingatkan mereka,” Igo menggeram.
Aku melirik ke dapur, tempat Inayah masih memasak sambil bersenandung, tanpa mendengar keributan kami. Headset menyumpal telinganya. Bagus, dia tak perlu terlibat. Tadi siang Inayah bercerita padaku bahwa Ruqoyah meneleponnya, mengajak bicara dari hati ke hati. Cukuplah masalah yang satu itu untuknya. Yang sekarang ini urusan kami.
“Baiklah, silakan kalau kau mau pulang!” desisku, melotot ke arah Igo, lalu menatap Harto dan Nasuti. “Kalian bagaimana?”
“Aku akan pulang,” kata Harto datar. “Besok, jika hujan reda. Perjalanan ini sudah tak aman lagi. Pertama buaya, lalu geng motor, dan sekarang foto-foto ini. Percuma saja aku ikut jika risikonya tinggi. Apanya yang wisata gratis.”
“Aku juga pulang,” kata Nasuti. “Igo benar Lutfi, kau terlalu egois.”
“Lalu, bagaimana dengan cita-cita kita?” kataku. “Bagaimana dengan rihlah bersama keliling Indonesia? Bukankah kita sudah merencanakan ini sejak lama? Kalian akan menelantarkan begitu saja?”
“Itu cita-citamu, Lutfi, bukan kami,” Igo tak peduli.
Harto diam saja, Nasuti berpaling. Semua memojokkanku rupanya. Aku menatap marah mereka. Napasku naik turun, kepalaku seperti mendidih. Karena frustrasi, aku langsung masuk kamar dan melempar diri ke kasur. Aku tak peduli pada apapun lagi selain mengharapkan hujan segera reda. Pertengkaran ini sia-sia. Berawal dari foto-foto misterius itu dan tekanan suasana yang suram diliputi hujan, membuat masalah terasa berat seakan menindihku. Jiwaku seperti terbakar, kepribadianku yang tenang habis menjadi abu. Sebagian diriku hilang dilahap emosi. Mungkin dengan cukup tidur pikiranku akan kembali normal.
Tengah malam, saat terbangun, kudengar Igo, Nasuti dan Harto berbisik pelan. Diam-diam kuraih HP dan kurekam percakapan mereka.
“Lutfi mulai menyebalkan,” kata Harto. “Memangnya salah kita apa? Sejak kemarin dia terus bersikap sok dan tak hentinya memerintah kita. Aku menyesal menjadikannya kapten. Dia merasa dirinya boss, bukan leader. Memerintah dan bukannya memimpin.”
“Aku tak suka caranya,” kata Igo. “Dia bahkan tak peduli pada nasib temannya sendiri. Tak kusangka dia tak punya hati. Kita unfriend saja kalau dia terus begitu.”
“Aku setuju denganmu,” kata Nasuti. “Tampaknya dia merasa seperti pemimpin dan berhak menyuruh kita seperti babu. Aku ragu perjalanan ini akan berhasil. Sejak awal sudah kuduga ini akan sia-sia. Kau benar, Igo. Sebaiknya kita berhenti di sini saja dan tinggalkan dia. Biarkan dia bertualang sendiri semaunya.”
Mereka terus membicarakanku, aku tak tahan...
Aku meringkuk di balik selimut. Telingaku panas mendengar semua itu, hatiku remuk, darahku mendidih. Mungkin aku memang sudah keterlaluan, tapi tak kusangka mereka tega berkata begitu saat aku tertidur. Temanku sendiri menikam dari belakang rupanya.
*****
Esok paginya aku bangun kesiangan, tak satupun ada yang membangunkanku. Baru kali ini aku shalat Subuh kesiangan. Aku menekap wajah, merasa berdosa dan menyesal luar biasa. Hatiku terasa suram. Hujan masih betah menerjuni tanah di luar sana. Aku beristigfar sebanyak-banyaknya, lalu segera mengambil wudhu dan melaksanakan shalat Subuh. Lebih baik terlambat daripada tidak shalat sama sekali. Saat berjalan ke kamar sebelah, kulihat Inayah sedang merapikan tempat tidurnya sambil bersenandung. Ketika melihatku, dia tersenyum riang dan menyapaku. Tampaknya dia tak ikut dengan diskusi rahasia semalam, mungkin sudah tidur. Aku lega karena punya alasan untuk tidak memarahinya.
Saat memasuki ruang depan, kulihat Igo, Nasuti dan Harto berkerumun sambil berbisik. Ketika melihatku, mereka langsung terdiam.
“Hai, Lutfi,” kata Harto dibuat-buat.
Aku bergerak mendekati mereka.
“Apa yang kalian bicarakan semalam?” kataku tenang, meski hatiku menggelegak. Kutatap satu persatu wajah-wajah itu. Mereka diam seribu bahasa, saling pandang. Mungkin mereka malu pembicaraan itu terdengar olehku.
“Ayo, katakan yang jujur, kalian sudah bosan berteman denganku, kan? Kalian ingin aku pergi?” kataku keras-keras. “Baiklah kalau itu keinginan kalian. Aku akan pergi.”
“Tunggu, dengarkan dulu penjelasanku,” kata Harto. “Kau salah dengar.”
“Apa? Kaubilang aku salah dengar? Maksudmu telingaku sudah tak beres, begitu? Kalau begitu, apa maksudnya ini?”
Aku mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman semalam. Harto, Igo dan Nasuti diam saja mendengar suara mereka bersahut-sahutan dalam rekaman.
“Dengar dulu Lutfi, bukan begitu maksud kami,” kata Nasuti.
“Aku tak mau dengar alasan kalian. Bukti rekaman ini sudah cukup jelas. Tak perlu kalian tutup-tutupi lagi. Kalian memang ingin menyingkirkanku, bukan?”
“Tidak, Lutfi, kau salah paham.”
“Sudahlah, Nasuti, biarkan dia pergi,” Igo mendengus, duduk di sofa. “Toh itu memang kemauannya. Dia takkan puas sebelum menyalahkan kita, jadi biarkan saja dia.”
“Apa maksudmu?”
“Sudah jelas kan, akar semua masalah ini?” Igo berdiri dan menatap tajam, menunjuk hidungku. “Kau iri padaku kan? Setiap kali aku berduaan dengan Inayah, kau selalu menatap dengan tatapan aneh. Kau pikir aku tidak tahu? Kau boleh saja mengelak, tapi aku tahu apa yang kaupikirkan. Kau iri, karena akulah yang selalu beruntung dalam perjalanan ini. Kau membandingkannya dengan masa lalumu yang gagal, saat cintamu ditolak tiga kali. Jadi kau benci melihat kedekatan kami, menunggu saat yang tepat untuk melampiaskannya. Kau bahkan menjauhi Inayah, bersikap dingin padanya, selalu menghindar dan jarang mengajak dia bicara. Benar kan?”
“Apa yang kaubicarakan? Tuduhan apa lagi ini?” seruku berang.
Harto dan Nasuti menatap Igo, tercengang atas penuturannya yang tak terduga. Sialnya, Inayah muncul setelah mendengar keributan yang kami buat. Wanita itu menekap mulut dan memandang kami bergantian.
“Ada apa? Kenapa kalian bertengkar seperti ini?” dia bertanya polos.
Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban tepat yang mencakup semua perasaanku tanpa melibatkannya dalam kekacauan. “Mereka memusuhiku.”
Harto bangkit dan mencengkeram bahuku. “Dengar, kami tidak serius dengan diskusi semalam. Kalaupun kami memang keceplosan berkata begitu, itu karena salahmu sendiri, Lutfi. Bukan berarti kami menyalahkanmu, tapi cobalah lihat ke dalam hatimu, rasakan apa yang membuat sikapmu berubah. Kau sama sekali tak seperti dirimu yang biasanya ketika marah-marah dan memusuhi kami. Kami hanya ingin kau kembali, Lutfi.”
Aku tahu dia berkata jujur. Akhirnya ada juga yang mengaku secara terang-terangan. Kemarin kami tertawa bersama, begitu ceria. Sekarang kami bertengkar hebat hanya karena masalah sepele. Kenapa harus seperti ini, kenapa?
“Perlu kalian ketahui, aku berbuat begitu untuk kebaikan kalian,” kataku. “Tak ada niatan lain dariku. Kalian harusnya sadar aku bersikap seperti itu bukan karena keinginanku. Hujan yang terus turun sejak kemarin membuat perasaanku tak nyaman dan mudah marah. Aku tak pernah bermaksud membentak kalian, maaf jika kalian tidak berkenan. Jujur saja, aku sungguh kecewa atas tindakan kalian. Selama ini, kalian anggap aku apa?”
Kesal atas sikap diam mereka, aku masuk ke kamar dan membanting pintu. Darahku mendidih, tergesa-gesa mengemasi barang dan menjejalkan baju-baju ke ransel. Aku tak percaya atas tindakan mereka, bahkan aku juga kecewa dengan Harto. Selama ini dia tak pernah marah, selalu mengiyakan pendapatku. Tak kusangka dia juga memusuhiku. Ketika aku kembali muncul di ruang depan, perasaanku tak enak membayangkan perpisahan macam apa yang akan terjadi. Mereka hanya diam, tak ada yang berusaha mencegahku, hanya saling tatap dan diam seperti patung.
“Kalau kalian berubah pikiran, temui aku di terminal. Kutunggu sampai pukul lima sore. Kuberi kalian waktu setengah hari untuk berpikir ulang. Kalau kalian tidak datang juga, aku akan pergi ke bandara. Perjalanan ini akan kuselesaikan sendirian, kalian boleh pulang. Tak ada lagi yang bisa kuucapkan. Kita berpisah di sini.”
Petir menyambar di luar sana, cahayanya yang tajam menerangi wajah marahku. Entah mengapa ada petir di momen yang tepat. Keheningan yang menyusul sungguh menyesakkan.
Sambil mencengkeram jaket, aku keluar menerobos hujan, tak peduli air menetes-netes dari rambut dan bajuku. Hanya Inayah yang berlari ke pintu dan memanggil-manggilku sampai suaranya serak, tapi aku terus berjalan. Perpisahan yang dingin membuat hatiku sakit, namun tekadku sudah bulat untuk meninggalkan mereka. Paman Ilyasa benar, perjalanan ini menyingkap sisi buruk mereka, wajah asli yang selama ini mereka sembunyikan. Tak kusangka persahabatan yang telah kami bangun bertahun-tahun luluh lantak hanya dalam semalam, dan itu semua gara-gara hujan. Melihatku pergi, hanya langit yang bersedia menangis untukku.
*****
Aku masih saja termenung sambil menatap jendela mobil, kecewa dan terguncang atas sikap teman-temanku. Perasaanku hancur lebur. Meski begitu, aku juga menyesali tindakanku yang di luar kendali. Apakah layak jika aku terus menyalahkan hujan?
Aku menatap sekitar, mengamati penumpang lain saat merasa ada yang aneh dengan mereka. Orang-orang itu menatapku sinis. Seorang pria bahkan sampai memerhatikanku dari kaki hingga kepala, tatapannya seperti mengejek. Perasaanku tak enak. Kenapa orang-orang ini bersikap seperti itu? Apakah karena aku telat shalat Subuh? Apakah dosaku sebesar itu sampai semua makhluk melaknatku? Aku beristighfar berkali-kali. Tatapan mereka masih saja seperti lampu sorot, mengikuti semua gerak-gerikku. Rasanya aku ingin pindah ke bus lain saja, namun tubuhku tak mau bergerak.
Aku terlonjak saat seseorang menepuk bahuku. Pria itu duduk di bangku sebelahku dengan seorang wanita yang tentu istrinya. Pria itu masih nyengir padaku, seolah menunggu reaksiku. Aku menatapnya curiga. Siapa lagi orang ini?
“Lutfi kan?” pria itu sok akrab.
“Ya,” jawabku datar, heran bagaimana dia bisa tahu namaku.
“Kau tidak ingat?” dia tampak kecewa. “Ini aku, teman SMA dulu!”
Aku mengamati pria itu, mataku melebar saat mendadak teringat.
“Yoga?” tebakku. Pria itu mengangguk bersemangat.
“Kau awet muda ya, tak banyak berubah, persis waktu masih SMA dulu,” katanya, lalu memperkenalkan wanita berkerudung yang duduk di sebelahnya, menggendong bayi mungil berumur satu tahun. “Ini istriku, dulu kau mengenalnya juga. Siapa coba, ingat tidak?”
“Ayu... Ayu Khumaida? Yang waktu itu kita tolong pas ada kerusuhan?” tanyaku. Wanita berdarah Jawa-Minang itu mengangguk, tersenyum. “Wah, sekarang kau sudah mau berjilbab ya. Bagus itu.”
Aku sedikit merileks. Tak kusangka akan bertemu teman lama di perantauan seperti ini. Meski dulu kami tak begitu akrab, aku menyambut kemunculan mereka dengan antusias. Yoga dan Ayu tampak sama senangnya. Kami mengobrol hilir mudik.
“Kau sedang jalan-jalan?” Yoga bertanya.
“Ya, begitulah,” jawabku. “Kau sendiri kenapa ada di sini?”
“Aku tinggal di sini sekarang. Kebetulan kakek istriku ini instruktur beladiri tradisional Madura. Perguruannya membuka beberapa cabang termasuk di sini. Aku kebagian tugas mengawasi para murid berlatih di pendoponya.”
Aku mengangguk, ingat bahwa di kampusku juga ada organisasi beladiri asal Madura yang namanya Persaudaraan Setia Hati Terate. Gerakan mereka terkenal dengan serangan yang khas dan memakai atribut berupa golok. Selain itu, seragam mereka berwarna hitam, tak seperti klub beladiri lain yang seragamnya putih.
“Masih suka berantem?” tanyaku.
“Ya nggak lah. Aku sudah berubah sekarang. Lagipula istriku ini orangnya penentram, selalu bisa menenangkan kalau aku marah. Jika ingat masa-masa jahiliah dulu, saat aku masih berandalan, malu sekali rasanya. Dulu aku emosian, beringas dan tak bisa mengendalikan diri. Ada yang menyenggol sedikit saja, pasti langsung kutonjok. Kau juga ingat kan?”
“Ya, dulu aku paling malas kalau berurusan denganmu,” aku terkekeh, lalu menatap bayi di pangkuan Ayu. “Itu... anak kalian?”
“Ya, namanya Billy,” kata wanita itu. “Lucu kan?”
“Iya, ngegemesin, jadi pengen nyubit,” kataku, tersenyum. “Eh, Yoga, teman-teman gengmu yang dulu itu gimana kabarnya sekarang?”
“Maksudmu si Edward, Yogi dan Asto? Wah, kau pasti kaget kalau kuberitahu soal mereka. Kudengar mereka pergi merantau juga, sama sepertiku. Edward yang paling pintar di antara kami, kini sudah tak badung lagi. Sejak ibunya meninggal, dia jadi rajin sekali belajar, berburu beasiswa sana-sini, sampai akhirnya diterima di universitas terkenal. Dia bahkan sering menang olimpiade, melakukan banyak riset di bidang kimia, dan katanya sih hasil penelitiannya diakui tim ilmuwan dunia, bahkan dapat penghargaan nobel segala. Hebat kan? Kalau si Asto, dulu kau juga ingat dia itu bebal sekali, nilai raportnya selalu merah, hingga akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Mungkin Pak Kepsek bosan melihat mukanya nampang terus di ruang BP. Meski tak punya bakat belajar, tapi semangatnya luar biasa. Tak mau kalah dengan yang lain, dia mulai rajin melatih fisiknya, dan kabarnya sekarang dia jadi atlet angkat besi lho. Kalau si Yogi, nah, rasanya aku tak tega menceritakan dia. Dulu kau juga ingat kami sering tertukar kalau dipanggil, karena nama kami mirip, cuma beda huruf akhirnya saja. Dia itu... aduh, dari dulu kerjanya main kartu saja, berjudi di warung-warung kopi. Kalau bukan main gaple, ya kartu remi. Kalau sudah pegang kartu, sikapnya jadi berubah, seolah lupa diri...”
“Eh, kalau jelek mending jangan diceritakan deh, dosa,” aku memotong.
“Oh, iya ya... sori,” Yoga menutup mulutnya, beristighfar. “Kebiasaan burukku kambuh lagi deh. Biasanya kalau cerita tentang sesuatu, bawaannya suka keterusan.”
Aku tersenyum, menoleh ke arah jendela.
Sambil menatap pemandangan di luar, ingatanku memutar adegan flashback saat aku dan Yoga pertama kali mengikrarkan diri sebagai teman, saat kami masih SMA. Saat itu kami naik di mobil yang sama dan duduk bersebelahan. Aku hendak ke toko buku di kota Cirebon sedangkan dia ke tempat bimbingan belajar. Sesekali kuperhatikan raut wajahnya yang keras dan sorot matanya yang tampak sangar. Selain semua ciri itu, wajahnya cukup rupawan. Aku tahu namanya dan dia juga tahu namaku, tapi kami tak pernah saling sapa. Alasan paling kuat mungkin karena aku anak jurusan IPA sedangkan dia IPS. Aku enggan bicara dengannya karena setahuku anak IPS kebanyakan bandel, pelanggar aturan, dan langganan dipanggil guru BP. Anggapan yang kurang tepat sebetulnya.
Persahabatan kami mulai tumbuh saat itu, ketika angkot yang kami tumpangi berhenti tiba-tiba. Sekelompok orang berteriak-teriak menghadang jalan. Tampaknya ada keributan di depan sana, mungkin pelajar tawuran atau mahasiswa yang berdemo minta harga BBM diturunkan. Mobil digedor-gedor dari luar, para penumpang disuruh turun. Aku ingat saat itu di Cirebon sedang rawan kerusuhan. Aku terpaksa turun sambil mengomel, menyesali siswa-siswa yang bertindak anarkis dan seringkali merusak properti umum seperti kotak telepon atau jendela-jendela kantor. Tak bisakah mereka melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat selain mencari keributan? Jalanan tampak ramai dipenuhi pemuda berpakaian kusut, memakai ikat kepala dan mengibarkan spanduk yang dicoret-coret dengan nama geng mereka. Mereka bergerak maju menguasai jalan raya seperti gelombang besar. Dari seragam mereka, aku tahu para pengacau ini adalah siswa sekolah anu yang acapkali merusuh di jalan.
Aku berdiri kebingungan bersama beberapa penumpang lain yang telantar. Beberapa siswi SMP mengeluh karena terlambat sekolah. Suasana semakin ricuh ketika polisi datang dan mengusir para perusuh dengan menyemprotkan gas air mata, namun sia-sia. Tak mau kalah, para siswa membalas dengan lemparan batu dan senjata tajam. Aku berlindung di sebuah gang agar tak terkena lemparan. Polisi dengan helm pelindung dan perisai membanjiri area terbuka, sementara para perusuh membalas dengan mengayunkan sabuk. Bagiku mereka seperti membuang-buang tenaga untuk hal yang tak berguna. Peperangan terjadi di depan mataku, begitu realistis dan memiriskan. Seperti inilah profil pelajar Indonesia kebanyakan.
Takut terlibat dan ditangkap pihak berwajib, aku melarikan diri ke sebuah gang sempit dan menunggu hingga situasi aman. Suara-suara pertempuran masih berlangsung seru di luar sana. Saat aku hendak mengintip, seorang gadis berseragam SMA dan berambut panjang muncul di mulut gang, terhuyung-huyung sambil memegangi bahunya, bajunya berdarah-darah. Begitu melihatku, gadis itu mengulurkan tangannya, kemudian ambruk tak jauh di depanku. Berteriak panik, aku langsung berlari menghampiri, mengguncang tubuhnya dan mencoba membangunkan, namun gadis itu masih tak membuka matanya. Tampaknya ia korban keributan di luar sana. Dahinya berdarah, mungkin akibat lemparan batu. Aku menoleh panik, namun tak kulihat seorangpun di tempat itu yang bisa kumintai tolong. Akhirnya aku memberanikan diri dan bergegas keluar.
Kericuhan masih berlanjut, dan mulai tampak korban jiwa bergeletakan di sana-sini. Aku berlari seraya melindungi kepala, bergegas mendekati seorang pemuda yang berdiri tak jauh di depanku. Pria itu ternyata Yoga. Tanpa pikir panjang, segera kutarik lengannya dan kuajak ke tempat si gadis. Yoga menepuk-nepuk pipi gadis itu, mencoba membuatnya sadar. Diam-diam kuperhatikan pemuda ini. Tampaknya dia tak sesangar penampilannya.
Akhirnya kami sepakat untuk membawa gadis ini ke rumah sakit terdekat. Kami harus menerobos kerusuhan, menghindari lemparan batu dan senjata tajam untuk mencapai tempat yang aman. Di situ kami menunggu angkot. Segera kurogoh tas selempang milik si gadis, mencari kartu identitas atau semacamnya. Aku menarik keluar selembar KTP dan memeriksa alamatnya. Nama gadis ini Ayu Khumaida, kelahiran Padang. Kami berdiri di trotoar selama beberapa menit yang menggelisahkan. Begitu angkot datang, aku langsung menyetopnya, menggendong si gadis masuk dan kuminta sopir bergegas ke rumah sakit. Kejadian itu sedikit membuka mataku. Sejak saat itulah aku jadi akrab dengan Yoga, dan pandangan negatifku tentang anak-anak IPS sudah tamat riwayatnya.
“Lagi ada masalah ya?” Yoga membuyarkan lamunanku.
“Eh, apa?” aku tergagap.
“Oh, ayolah, aku tahu kau sedang ada masalah dengan seseorang kan?” Yoga menatap dalam-dalam, seperti merontgen isi otakku. “Siapa dia? Pacar, atau temanmu?”
Aku tak tahu bagaimana dia bisa tahu sebanyak itu.
“Berbaikanlah dengan temanmu,” bujuk Yoga. “Cobalah memaafkan mereka, apapun kesalahan yang mereka perbuat. Kelak kau akan menyesal jika kehilangan mereka. Jangan marah hanya karena kesalahan kecil sehingga membuatmu lupa akan kebaikan mereka selama ini. Ingatlah bahwa mereka sering membantumu di saat-saat sulit, ikut gembira dan susah bersama. Memang, dikecewakan orang yang kita anggap sahabat lebih menyakitkan dibanding orang yang jadi musuh sejak awal. Tapi ingatlah satu hal, bukankah selama ini mereka mau mendampingi dan menerima kekuranganmu?”
Aku mengiyakan dalam hati, menyesal sudah meninggalkan teman-temanku. Aku heran sejak kapan Yoga jadi sebijak ini? Apa karena pengaruh mertuanya yang guru silat itu?
Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi akan ikut mendapat wanginya, sedangkan orang yang berkawan dengan tukang besi akan kecipratan baranya. Di balik orang hebat selalu ada ibu hebat, istri hebat...” dia mengelus istrinya, “dan satu lagi, dukungan teman hebat. Jadi selama temanmu baik, untuk apa membenci mereka? Tugas seorang teman adalah saling melengkapi, karena teman yang sempurna mustahil ditemukan. Mencari teman selalu lebih sulit dibanding mencari musuh. Camkan itu, Kawanku.”
Aku terdiam, terkenang masa lalu saat masih kuliah, saat aku sering menghabiskan waktu bersama teman-temanku. Aku sadar diriku tak ada apa-apanya jika tak ada mereka. Aku tak seperti Harto yang berbakat melucu dan menjahili orang. Tak pandai meruqyah dan berorasi seperti Igo. Tak setegar Nasuti yang hidup mandiri sejak kecil. Tak berpengetahuan luas dan kharismatik seperti Torik.
Aku tersentak kaget saat mobil berhenti tiba-tiba. Ada keacauan di depan. Jalanan yang kami lewati macet total. Berkali-kali sopir membunyikan klakson, menggerutu, namun iring-iringan kendaraan tak ada yang bergerak. Para penumpang berebut melongok jendela, bertanya-tanya ada apa. Rupanya, akibat hujan lebat dan angin kencang yang terus menerus, pohon-pohon besar di tepi jalan banyak yang tumbang, begitu juga dengan beberapa baliho dan papan iklan besar. Kabel-kabel listrik putus, daun dan ranting berserakan di mana-mana.
“Nah, kesempatan bagus. Perhatikan baik-baik, Lutfi,” kata Yoga.
Pria itu turun dari bus di tengah derasnya hujan, berlari kecil di jalan dan melewati kendaraan lain. Entah apa maunya. Para penumpang lain melongo keheranan, penasaran apa yang akan dilakukannya. Begitu juga aku, namun istrinya hanya tersenyum dan berkata, “Dia memang selalu begitu. Mulia sekali, aku bangga jadi istrinya.”
Aku terus mengawasi Yoga yang tengah berlari. Sesaat sosoknya hilang di balik mobil, lalu muncul lagi di ujung jalan depan sana, tempat sebatang pohon besar merintangi jalan. Rupanya itulah biang kemacetan ini. Sekuat tenaga, Yoga mendorong pohon tersebut, namun sia-sia. Pohon itu tak bergerak sedikit pun. Awalnya tak ada yang membantu, bahkan beberapa orang menertawakannya, meneriaki agar menunggu polisi saja. Tapi Yoga pantang menyerah. Dia terus mendorong dan mendorong, meski tahu usahanya tak berarti.
Wajahnya yang serius lama-kelamaan membuat kagum orang-orang, hingga tak ada lagi yang mencibir. Beberapa orang bahkan turun dari mobil dan membantunya. Satu orang... dua orang... hingga puluhan orang bergegas maju dan ikut mendorong pohon tersebut, yang bergeser sedikit demi sedikit. Adegan ini persis sebuah iklan India yang pernah kutonton di youtube. Awalnya sedikit, lalu lama-lama bantuan datang semakin banyak, hingga akhirnya polisi dan petugas PLN datang membawa gergaji mesin, memotong-motong pohon besar itu dan menyingkirkannya dari jalanan. Lalu lintas kembali lancar. Semua orang bersorak, terutama mereka yang ikut turun ke jalan. Para penumpang bus mendesah lega. Beberapa orang menepuk-nepuk bahu Yoga saat dia kembali naik ke bus, menganggapnya pahlawan.
“Kau hebat, suamiku,” kata Ayu, mengeluarkan handuk. “Tapi kau jadi basah kuyup.”
“Tak apa-apa, Sayang,” katanya enteng, lalu menoleh padaku. “Nah, Kawan, kau lihat sendiri kan? Selain kerjasama dan pantang menyerah, apa lagi yang kaudapat dari peristiwa tadi? Dalam segala hal, jika ingin melakukan sesuatu, kau harus mulai dari diri sendiri. Langsung bertindak, jangan tunggu orang lain. Begitu halnya dengan minta maaf. Ambil inisiatif, itu baru sikap ksatria. Jika kau ingin kembali, sekaranglah waktunya. Aku percaya teman-temanmu pasti sedang menunggu. Mereka membutuhkanmu, dan kau membutuhkan mereka. Orang baik bukanlah orang yang tak pernah berbuat salah, tapi orang yang langsung menyadari dan menyesali kesalahannya. Kita bukan tokoh film religi yang persis malaikat. Nah, kembalilah dan minta maaf pada mereka. Itu akan membuatmu merasa lebih baik.”
Aku mengangguk. Kata-katanya benar-benar mengena tepat di hatiku. Mobil melaju kencang, meski di beberapa daerah agak tersendat karena terhalang sisa-sisa pohon tumbang. Setelah waktu yang terasa singkat, Yoga meminta bus berhenti.
“Nah, kita berpisah di sini,” katanya. “Kami turun di depan. Yakin tidak mau mampir?”
“Wah, gimana ya? Sebenarnya aku ingin melihat rumah barumu, tapi aku harus segera ke terminal. Terima kasih atas saranmu.”
Yoga menepuk bahuku. Istrinya tersenyum, menggenggam tangan mungil Billy dan menyuruhnya melambai padaku. Aku memerhatikan mereka turun, membuka payung dan menerobos hujan, lalu masuk ke sebuah rumah pendopo. Mereka pasangan yang serasi. Saat bus melaju kembali, aku menatap ke depan, terkenang teman-temanku. Harto, Igo, Nasuti, sedang apa mereka sekarang, di tengah hujan seperti ini? Apakah mereka memikirkan hal yang sama denganku?
*****
Aku duduk sendirian di pintu masuk terminal yang sudah mulai sepi. Kakiku mengetuk-ngetuk lantai dengan tak sabar. Aku melirik jam dan menoleh berkali-kali begitu tampak seseorang mendekat, lalu melengos kecewa karena orang itu bukan yang kuharapkan. Aku menunggu, walau tahu mereka tidak akan datang. Hujan masih berderai dengan bebasnya, meramaikan udara dan membasahi tanah, menebar bau-bauan rumput ke lubang hidungku. Pukul lima sore telah lewat beberapa detik. Aku mulai bosan, kecewa. Sekarang sudah lewat lima belas menit, tapi mereka tak datang juga. Aku menghela napas, perlahan berdiri. Kusandang ransel sambil memantapkan hati. Sudah waktunya pergi ke bandara.
"Tunggu!"
Aku berhenti, menoleh, ketika ada empat bayangan mendekatiku. Harto, Nasuti, Igo dan Inayah muncul di belakangku, terengah setelah turun dari taksi. Mereka memandangku dengan mimik memohon.
“Maafkan kami,” kata Harto tulus. Memang kata itu yang ingin kudengar, tapi aku tetap merasa tak enak hati. Kutatap mereka satu persatu, mengamati wajah bersalah mereka, menebak kesungguhan hati mereka.
“Tidak, akulah yang harus minta maaf,” kataku tenang. “Memang aku yang salah. Kemarin aku terbawa emosi. Itu bukan diriku yang sebenarnya. Maafkan aku.”
“Tidak, tunggu, kami juga minta maaf,” kata Nasuti. “Kami juga bersalah padamu. Aku sudah memikirkan ini sejak pagi tadi. Kata-kata kami tadi malam memang sangat keterlaluan. Kau berhak marah jika kau mau. Kami sungguh minta maaf. Itu takkan terjadi lagi.”
“Dulu, kau membelaku,” kata Harto. “Tapi, apa yang kulakukan sebagai balasannya? Teman macam apa aku ini? Seharusnya kita saling melengkapi. Aku kan teman baikmu. Kita berangkat bersama, pulang pun harus bersama. Saat kau sampai di Papua, aku harus berada di sampingmu. Aku ingin setia seperti setianya Robin kepada Batman, seperti Watson kepada Sherlock Holmes, dan seperti... seperti Abu Bakar kepada Rasulullah.”
“Maaf, aku sudah keterlaluan menuduhmu yang tidak-tidak,” kata Igo. “Kupikir, kau pasti membutuhkan bantuan kami. Jangan pergi sendirian. Kami bersedia menemanimu sampai akhir. Kami berjanji tak akan melakukan itu lagi. Jadi tolong jangan perlihatkan wajah sedih itu lagi di depan kami.”
Aku mengusap mata dengan punggung tangan, menatap mereka.
“Kalian... kalian memang sahabat sejati.”
Aku menghambur ke arah mereka, merangkul semuanya. Kami saling berpelukan lama sekali. Pertengkaran tadi pagi rasanya sudah tak ada artinya lagi. Inayah tersedu-sedu melihat kami kembali akur, lalu menjauh sambil menutupi wajah. Aku menangis gembira sekaligus tertawa. Sungguh beruntung aku mengenal karib sehebat mereka.
"Jangan pernah putuskan silaturahmi, Kawan, dosanya berat,” kataku.
“Ini semua berkat dia,” kata Harto, menoleh ke arah Inayah yang masih berdiri agak jauh, menutupi wajah. “Dialah yang mendamaikan hati kami, membujuk agar berbaikan denganmu. Kita sudah berteman lama, empat tahun. Bodohnya aku hanya ingat kesalahanmu, sedangkan kebaikan-kebaikanmu kulupakan begitu saja.”
“Dia cewek yang hebat, bisa memahami karakter kita dengan baik,” kata Nasuti. “Kau harus berterima kasih padanya, Lutfi.”
Aku tersenyum, melangkah mendekati Inayah, berkata lembut, “Terima kasih banyak ya. Berkat kau, kami kembali akur. Untung kau ikut kami. Maaf, sikapku kadang agak dingin padamu karena kau satu-satunya wanita di kelompok ini.”
“Eh? Rasanya aku tidak melakukan apa-apa kok,” Inayah mendongak, berkata polos. “Aku hanya melakukan apa yang kubisa, memberikan beberapa saran, itu saja. Selebihnya teman-teman Kak Lutfi sendiri yang melakukannya. Kak Lutfi beruntung punya sahabat yang hebat seperti mereka.”
“Yah, emm… ada satu lagi yang ingin kutanyakan,” kataku.
"Ya?"
“Sebenarnya—maafkan aku—apakah selama ini kau berpura-pura bersikap polos, tak tahu apa-apa? Maaf kalau aku menyinggungmu.”
Inayah tertawa pelan, menutupi mulut. “Aku rasa Kak Lutfi sudah tahu jawabannya. Ketika bercanda, aku memang suka bersikap bodoh seperti anak kecil. Kebiasaanku memang seperti itu. Aku lucu kan?”
“Oh, begitu,” kataku. “Lalu, tulisan di buku harianmu itu, semua tentang perasaanmu pada Igo, apakah itu akting juga?”
Dia diam sejenak, rona wajahnya berubah. Pertanyaan yang sulit, aku tahu, namun Inayah tersenyum. “Itu, sayangnya bukan. Hatiku tak pernah berbohong, Kak Lutfi. Apa yang kulakukan itu memang keinginanku sendiri, bukan karena paksaan orangtua kami. Sejujurnya aku juga kagum dengan Kak Lutfi. Alangkah beruntungnya wanita yang memiliki suami baik hati, tulus, sabar, dan kalem seperti Kak Lutfi. Kharisma yang kaumiliki berbeda tipenya dengan Kang Igo, meski sama-sama hebat. Sejak pertama kali melihat Kak Lutfi, aku merasa aura Kak Lutfi beda dari yang lain. Seperti seorang panglima atau raja, kualitas pemimpin sejati. Bahkan dari cara berjalan dan sikap pun terlihat jelas. Emm, ayo Kak, sebentar lagi busnya berangkat.”
Inayah tersenyum, mendahului naik ke bus. Aku terpana mendengar kata-katanya. Bagaimanapun dia mahasiswi kedokteran, pasti sedikit paham mengenai psikologi. Mungkin ucapannya ada benarnya juga.
"Hei Kawan, jangan sedih lagi ya. Kita sahabat selamanya,” kata Harto, tiba-tiba merangkulku. “Jangan biarkan pertengkaran kecil seperti tadi malam merusak keharmonisan kita. Lagipula, apa jadinya tim Penakluk Khatulistiwa tanpa kehadiran Sang Kapten?”
Harto mengacak rambutku, dan aku tertawa seraya merangkul bahunya. Hujan mulai mereda. Matahari mulai menampakkan cahaya sesaat sebelum terbenam. Di langit timur mulai terbentuk pelangi, dengan warna-warna indah yang membentang seperti busur di cakrawala. Seperti kata pepatah, habis gelap terbitlah terang. Jika ingin melihat indahnya pelangi, maka kita harus siap menghadapi badai terlebih dahulu. Dalam Al-Qur’an juga disebutkan, Inna ma’al ‘usri yusran, setiap ada kesulitan, di situ ada kemudahan.
Masalah kami telah teratasi. Meski masih gerimis, kami melanjutkan perjalanan. Entah mengapa setiap melintasi satu kota, kami selalu berurai air mata. Aku yakin semakin ke timur makin unik petualangan kami. Yah, ternyata aku memang tak bisa membenci hujan.
*****
Saat itu, aku tak menyadari rencana mengerikan sedang mengintai kami. Aku memang tak melihat langsung kejadian ini, jadi agak sulit menceritakannya dari sudut pandangku. Cerita kelam yang menggentarkan ini baru kuketahui beberapa hari kemudian, langsung dari mulut para pelakunya. Ceritanya begini, malam itu, seorang pemuda berjaket hitam berjalan di hutan, menerobos hujan. Tudung diturunkan menutupi kepala, menoleh sekitar, memastikan tidak diikuti saat dia mendekat ke sebuah gedung tua. Bunyi letusan senapan membuatnya terkejut. Ada yang menembak ke tanah di dekat kakinya.
“Satu langkah saja mendekat, kupecahkan kepalamu!” terdengar suara dari atas pohon. “Sebutkan tujuanmu!”
“Tunggu!” si pemuda mengangkat tangan, mencari-cari posisi si sniper. “Turunkan senjatamu, Pansus, ini aku!” Pemuda itu menarik kerah jaketnya, memperlihatkan tato tengkorak dan angka satu di bahu kanannya. “Aku ingin bertemu Bos.”
“Oh, kau rupanya. Aku hampir tak mengenalimu dengan penampilan itu.”
Si pemuda tidak terkejut saat seorang pria mendarat di tanah, menyandang senapan-otomatis buatan luar negeri di bahunya. Sniper bernama samaran Pansus itu memberi isyarat agar si pemuda mengikuti. Keduanya berjalan cepat melintas hutan, menuju sebuah gedung besar yang katanya markas rahasia suatu sindikat berbahaya. Tanpa takut sedikit pun, si pemuda ikut saja saat si sniper menyuruh masuk. Banyak sekali penjaga disiagakan di pintu masuknya, namun itu bukan apa-apa.
Pemandangan yang dilihat si pemuda di dalam gedung lebih menakjubkan. Ratusan gelondong kayu berukuran besar bertumpuk rapi memenuhi ruangan. Beberapa pria tampak sibuk dengan kayu-kayu itu. Ada yang bertugas menggergaji, ada yang mencatat. Pasti ini barang gelap yang dimaksud, pikir si pemuda. Memasuki ruang berikutnya, pemandangannya lebih hebat lagi.
Si pemuda terpesona melihat puluhan pria berbadan tegap, berwajah sangar dengan pakaian beraneka ragam tengah menjalani latihan bertarung. Teriakan penuh semangat menulikan telinga. Ada yang berlatih pencak silat, memukuli samsak tinju, membelah bata dengan tangan. Ada yang melempar rantai dengan kait tajam di ujungnya dan memenggal boneka jerami sasaran. Ada yang melempar peledak berkekuatan kecil dengan percikan api. Ada yang melempar beberapa pisau sekaligus, sampai-sampai satu pisau melesat dekat sekali dengan pipi si pemuda, sehingga dia refleks menghindar, sebelum pisau-pisau itu menancap di papan sasaran. Seringai kagum menghiasi wajah pemuda itu begitu melihat ini semua.
"Orang-orang ini tangguh dan terlatih,” komentar si pemuda, matanya tertuju ke panji besar di dinding, dengan gambar tengkorak dan dua arit bersilangan—logo organisasi mereka yang juga ditatokan di bahu si pemuda.
“Ya, butuh persiapan luar biasa untuk rencana luar biasa,” kata si sniper. “Bagaimana misimu, Anggota Nomor Satu? Apa kau mengalami kesulitan?”
“Aku hampir selesai, dan aku tak butuh bantuan menyelesaikannya.”
“Oh begitu,” kata si sniper datar, “Kakakmu pasti senang.”
Pemuda yang dipanggil Si Nomor Satu itu dibawa ke sebuah ruangan khusus berpenerangan remang-remang. Ruang utama, di mana pertemuan akan dimulai. Beberapa orang duduk mengitari meja, sosok mereka tak terlihat jelas. Meski begitu, Si Nomor Satu kenal semuanya. Tampaknya ketujuh pentolan Jerangkong sudah hadir, termasuk dirinya dan Pansus si sniper. Ia menyapa Akhsay Singh Si Nomor Tiga—pemburu berpakaian eksentrik yang memakai hewan buas dan obat-obatan tradisional sebagai senjatanya. Seekor ular hidup melingkari lehernya, dan tas kulitnya penuh berisi kalajengking. Kabarnya pria itu juga mengoleksi ratusan gading gajah, cula badak, dan kulit harimau hasil buruannya sendiri. Di sebelahnya ada Zefry Si Nomor Dua, pria berwajah lembut yang identitas aslinya adalah bos geng motor yang terkenal sadis. Si Nomor Satu—pemuda yang baru datang itu juga menyapa tiga pria lainnya, Si Nomor Lima, Enam dan Tujuh. Di balik code name itu, nama-nama mereka sering terdengar di berita kriminal, para penjahat berbahaya.
“Adikku, sudah lama aku menunggumu.”
Suara itu berasal dari seorang pria besar yang duduk santai di sofa, seakan itu singgasana. Tangan kanan terkepal menopang pipinya. Tangan yang lain memainkan sebutir apel fuji. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Matanya licik dan cerdas, siapapun yang ditatap akan merasa seakan diancam, seperti ada pisau yang melintang di leher. Para pria yang berkumpul di ruangan itu adalah orang-orang mengerikan, tapi mereka tak ada apa-apanya dibanding pria ini—sang bos besar. Semua penjahat terkenal ini adalah anak buahnya.
“Kau boleh kembali ke posmu, Pansus. Kabari aku jika kapalnya datang, dan setelah itu kau boleh ikut rapat.” Pria besar itu melambaikan tangan, menyuruh si sniper pergi. “Selamat datang di sarang monster, Adikku, tempat orang-orang terpilih dari seluruh negeri berkumpul. Sini, duduklah di dekatku. Rapat kita mulai sekarang.”
Saat Si Nomor Satu mendekat, tampaklah ada pria lain yang berdiri di sebelah kanan sang bos. Pria itu bertubuh kurus, rambutnya panjang kusut, dan jelas bukan anggota Jerangkong. Suara geraman aneh terdengar di belakang pria itu, entah suaranya atau bukan.
“Siapa dia, Kak?” tanya Si Nomor Satu, menunjuk pria kurus.
“Sekutu baruku,” jawab sang bos. “Tadinya aku menawarkan posisi sebagai petinggi Jerangkong, tapi dia tak sudi jadi anak buahku. Dia bahkan tak mau kusuruh duduk.”
Tanpa diduga, si pria kurus melempar pisau tepat ke depan kaki Si Nomor Satu. Pemuda itu refleks mundur, menatap kaget pisau yang menancap di lantai kayu.
“Jaga sikapmu, Mandra! Dia adikku!” desis sang bos.
Si Nomor Satu masih menatap pisau itu, bertanya, “Kenapa Kakak memilih pulau terpencil ini sebagai markas sementara?”
“Ini salah satu gudang terbaik kami, Adikku. Aku khawatir polisi berhasil mengendus beberapa gudangku yang lain, jadi kupikir lebih baik sembunyi di sini, menyusun strategi bersama anak buahku. Mereka para pelarian, buronan tanpa harapan, pemberontak organisasi, aparat pembelot, mantan tentara sepertiku, orang-orang buangan, siapa saja yang tertarik dengan ideologiku dan bergabung dengan sukarela. Aku merangkul semuanya. Merekalah keluarga baruku, bukan orangtua bodoh yang membuang kita bahkan saat kau masih balita.”
Suara itu terdengar lagi, seperti geraman binatang buas.
“Bisa kausuruh dia diam?” sang bos menatap rekannya.
Pria bernama Mandra itu mengeluarkan cambuk. Akhsay si pemburu menyorotkan senter ke sumber suara geraman, memperlihatkan seekor harimau Jawa dirantai di sudut ruangan. Melihat hewan buas itu, Si Nomor Satu sampai mundur saking kagetnya. Dengan kejam, Mandra mencambuk harimau itu sampai diam, meringkuk.
“Jadi ini barang gelap yang Kakak maksud?”
“Ya, hasil tangkapan Akhsay, pemburu terbaik kita,” sang bos menunjuk pria India yang tampak sumringah, kumis baplangnya bergerak-gerak. “Memang agak merepotkan membawanya dari Jawa ke Kalimantan, menyelundupkannya ke kapal hingga ke tempat ini. Tapi itu mudah saja bagiku. Jika hewan itu sudah tak berguna, aku bisa menjual kulitnya. Kau lihat kayu-kayu di depan itu? Itu hasil ‘panen’ yang dilakukan anak buahku. Aku senang mereka bisa mandiri saat aku tak ada, dan gedung ini sangat cocok untuk menyembunyikan barang bukti. Semuanya demi uang. Dan harimau itu, bagaimana nenek itu menyebutnya, Wage? Konyol sekali. Aku ingat nenek itu pernah memojokkanku di pengadilan, sampai hakim sialan itu memutuskan menjebloskanku ke penjara. Membuat usahaku gulung tikar dan harus menarik mundur truk-truk besar kesayangaku dari hutan.”
Sang bos menyulut rokok, menawari rekannya, “Kau mau satu?”
"Tidak. Sudah kubilang, rokok membuatmu lemah!” jawab Mandra dingin.
Mendengar pria kurus itu bicara, Si Nomor Satu bergidik. Jika suara kakaknya berkuasa dan menciutkan nyali, maka suara Mandra terdengar dingin, kering, mistis, mengingatkan tentang sesuatu seperti hantu atau mayat hidup. Wajahnya pun datar-datar saja, hampa tanpa ekspresi. Dan matanya yang tinggal satu, seperti tak ada kehidupan di dalamnya.
“Kakak, ini foto mereka,” Si Nomor Satu mengulurkan selembar kertas, matanya terarah ke wajah Mandra, mengawasi dengan agak takut. “Target kita hanya lima orang. Yang satu lagi rekanku, jadi jangan bunuh dia. Begitu juga dengan yang wanita.”
“Kau mengejutkan, Adikku, tak kusangka kau berhasil menggiring mereka. Anak yang di tengah ini, dialah yang memergokiku beberapa hari lalu.” Sang bos mengamati foto, meremas apel fuji dalam genggamannya hingga remuk, lalu memperlihatkan foto itu ke koleganya. “Merekalah sasaran utama kita, Kawan-kawan. Ingatlah wajah kelima remaja ini.”
Zefry sang ketua geng motor mengangkat tangannnya. “Maaf menyela, Bos, tapi saya pernah bertemu salah seorang dari mereka beberapa hari lalu. Anak bersorban putih itu cukup kuat dan berhasil menghajar empat anak buahku sendirian. Anak yang menarik, menurutku. Jika Bos tidak keberatan, serahkan anak yang satu itu untukku. Aku tak sabar ingin bertemu dengannya lagi.”
“Baiklah, dia targetmu, kalau begitu,” sang bos mengiyakan. Si Nomor Satu bergidik saat melihat Zefry gemetar kesenangan, namun mau tak mau ia setuju dengan ucapannya.
"Hati-hati, meski masih remaja, mereka tidak lemah,” kata Si Nomor Satu. “Apalagi yang di tengah itu, yang pakai jaket merah dan topi koboi. Dia juara turnamen beladiri tingkat provinsi tahun ini.”
“Penjara tidak membuatku lemah, Adikku,” kata sang bos, “dan semua anak buahku terlatih dan profesional. Kau lihat sendiri seperti apa latihan mereka bukan?”
“Ya, latihan yang mengesankan, dan Kakak sendiri tak terkalahkan. Banyak rumor yang beredar tentangmu, si pemimpin Jerangkong. Pria yang sanggup menghadapi sepuluh orang polisi terlatih sekaligus, seorang diri. Mengalahkan semuanya hanya dalam satu menit dan melumpuhkan pria dewasa hanya dengan satu pukulan.”
“Benar, Adikku. Kini, setelah bebas, aku akan sekali lagi menguasai pasar, menyuap pejabat, dan memanipulasi negeri dengan barang haram. Kekuatanku segera kembali!”
Terdengar gumam setuju dari para petinggi Jerangkong yang mengikuti rapat. Saat itu, sniper yang tadi bertugas menjaga pekarangan gedung melangkah masuk. “Lapor Bos, persiapan sudah selesai. Kapal kita sudah tiba dan siap berangkat kapan saja.”
“Bagus,” kata sang bos, lalu memanggil, “Hendrik! Kalong! Togar!” Dari tujuh orang yang mengikuti rapat, tiga orang berdiri dan maju, membungkuk hormat. Mereka anggota baru, belum lama ini bergabung untuk menggantikan tiga petinggi Jerangkong yang terciduk polisi. Sang kakak bertitah, “Tugas kalian mudah, bawa anak-anak ini, padaku!”
Pria berjanggut putih yang berdiri paling depan memerhatikan foto yang disodorkan, tampak sangsi. “Tapi Bos, untuk meringkus mereka, tak perlu mengerahkan kami bertiga. Aku sendiri sudah cukup.”
Sang bos menggeram. Dalam sekejap, dia meraih sesuatu di sebelahnya, dan tiba-tiba sebuah senjata besar, tajam, berkilat, teracung ke wajah anak buahnya. Benda itu sekilas seperti pedang, tapi ukurannya lebih besar lagi. Yang ditodong terkejut, tapi tidak mundur.
“Kau menentangku?” ancam sang bos. Guntur menyambar menerangi wajahnya, memperlihatkan raut kejam bagai iblis. Si Nomor Satu terkejut mundur melihat wajah kakaknya sendiri, jauh lebih membuatnya ngeri dibanding harimau di belakang pria itu. Saat bicara, suara sang bos melengking tinggi, hampir hilang ditelan bunyi hujan di luar. “Aku senang kau mandiri saat aku tak ada, Hendrik, mengorganisir beberapa anak buahku. Tapi tak ada toleransi jika kucium ada pembangkangan. Aku belum mengakui kalian. Target kita, anak-anak ini kuat, cerdik, dan aku tak ingin ada kegagalan. Kau meragukan perintahku?”
“Tidak Bos,” jawab Hendrik, menelan ludah, merasa ujung senjata itu menyentuh lehernya. Perlahan benda itu diturunkan.
“Sekarang pergilah,” kata sang bos, menyuruh tiga orang itu keluar.
“Kakak masih menyimpan senjata aneh itu?” Si Nomor Satu bertanya. Tak mendapat jawaban, dia berkata, “Aku tak bisa berlama-lama di sini, yang lain akan mencariku.”
“Pergilah Adikku, jaga dirimu baik-baik. Ingat, tugasmu memisahkan target kita dari temannya, lalu menggiring mereka ke lokasi yang kita tentukan. Sisanya biar Hendrik dan dua rekannya yang bereskan. Aku akan membawa anak buah terbaikku, orang-orang terpilih, tangguh, berbakat alam. Malam itu, para petinggi Jerangkong akan berkumpul di sana—” pria itu tertawa jahat, kilat menyambar lagi, “—semuanya!”
“Semuanya?” Si Nomor Satu mendongak bergairah.
“Ya, semuanya akan ikut berpesta. Lima pemuda itu takkan punya kesempatan.”
*****


 radenbumerang
radenbumerang









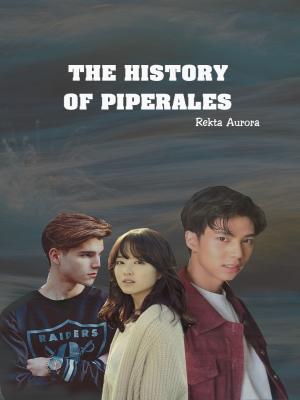
Iya juga yah, satu bab aja sepanjang ini... makasih masukannya Mas AlifAliss, mungkin ke depannya saya bagi per bab aja biar lebih pendek.