BAB 12. PEMUDA MISTERIUS, TANTANGAN EKSTREM DAN ADU MASAK
HARI KE-50, MAKASSAR
Teriknya matahari tak menghalangi antusiasme kami saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Aku berjalan di pelataran bandara, mendongak, memandangi arsitekturnya yang unik berbentuk kapal phinisi. Sebagaimana yang kubaca di buku-buku, tanah ini terkenal sebagai kampung halaman etnis Makassar dan Bugis, para pelaut tangguh yang melegenda hingga sekarang. Kapal tradisional mereka, phinisi, juga sama terkenalnya karena tercatat pernah beberapa kali berlayar mengelilingi dunia.
Kami bersantai dan selfie sejenak di Pantai Losari, wisata modern yang menjadi ikon Ibukota Sulawesi Selatan ini. Harto mengeluarkan handycam-nya dan meliput kegiatan penduduk setempat. Inayah yang menggantikanku menjadi host tampak bersemangat sekali saat mewawancarai seorang warga yang lewat. Ibu-ibu itu melambai ke kamera, berbicara cepat dalam bahasa daerah dan tertawa riang, mengira kami wartawan TV. Inayah bersikap profesional, tersenyum ramah dan menyalami narasumbernya, meski tak mengerti sepatah pun ucapannya. Aku sendiri sudah menahan tawa sejak tadi, lucu sekali melihat ekspresi Harto sang kameramen yang melongo seperti kesambet jin.
Setelah kenyang makan coto makassar dan sop konro, kami naik petepete—sejenis angkot—menuju destinasi berikutnya di Kabupaten Maros, tak jauh dari Makassar. Karena di dalam mobil sudah penuh, Nasuti berbaik hati mengalah dan memutuskan menyusul naik ojek. Kami melambai dari jendela angkot, bilang akan menunggunya di kota. Nasuti mengangguk, menghampiri tukang ojek yang mangkal di dekat situ. Kuperhatikan, Nasuti tampak lega dan ceria, tak tampak sisa-sisa kesedihan di wajahnya. Sejak mendengar kabar tentang kecelakaan yang menimpa ayahnya, tak pernah sedikitpun dia membahasnya. Dia juga tak ingin kami mengungkitnya. Tampaknya dia benar-benar sudah melupakan hal itu, bersikap biasa dan tertawa riang seolah tragedi itu tak pernah terjadi.
Satu jam kemudian, petepete yang kami tumpangi tiba di Kota Maros. Kami turun di depan sebuah warung dan memesan es teh, menungu Nasuti. Aneh, setelah lima belas menit dia tak muncul juga. Kucoba mengirim sms tapi tak ada balasan. Ditelepon pun tak diangkat. Satu jam lagi berlalu, gelas tehku sudah tandas kedua kalinya, tapi Nasuti masih belum tiba. Kami mulai khawatir, jangan-jangan dia tersesat atau terjadi sesuatu dengannya. Syukurlah, saat aku hendak kembali menjemputnya, tampak Nasuti melambai di kejauhan. Supir ojek yang memboncengnya tampak tertekan, wajahnya pucat seperti habis melihat hantu.
“Eh, kamu kenapa Nas?” tanyaku, ketika Nasuti ngos-ngosan mendekati kami, minta dibelikan es teh. Supir ojek yang mengantarnya langsung pulang setelah Nasuti membayar ongkos. Kami penasaran apa yang menyebabkan dia terlambat hampir dua jam.
Sambil terengah, Nasuti menceritakan pengalamannya.
*****
Dua jam lalu, saat meninggalkan terminal angkot, Nasuti sangat menikmati perjalanannya. Pertama, karena supir ojek yang memboncengnya pendiam, jadi Nasuti punya waktu untuk merenung. Meski dia terlihat tegar dan bersikap biasa di depan kami, kabar tentang kematian ayahnya masih menghantui pikirannya. Kedua, karena pemandangan yang terhampar di sepanjang jalan sangat indah, dan hal itu membuatnya terhibur, meski tak sepadan dengan kondisi jalan yang berlubang-lubang. Supir ojek mengambil jalur alternatif yang lebih sepi tapi lebih pendek. Mereka hampir sampai di Kota Maros saat supir ojek mengeluh, motornya mendadak oleng tak terkendali. Mereka pun berhenti dan memeriksa motor, mendapati ban depan kempes akibat melindas paku di jalan. Supir ojek mengeluh lagi. Padahal tinggal sedikit lagi mereka sampai.
Nasuti ikut kebingungan, karena jalan itu tampak lengang dan mustahil ada tukang tambal ban di daerah terpencil itu. Niatnya sih dia mau mendahului kami dengan mengambil jalan pintas, tapi malah dia yang tertinggal. Saat mereka kehabisan akal, memutuskan mendorong motor sampai bertemu tukang tambal ban, tiba-tiba muncul segerombol pengendara motor yang tampak mengerikan, mencegat dan menghadang jalan. Derum motor mereka memekakkan telinga, jumlahnya tujuh orang dan semua membawa parang.
“Aduh, gimana ini Mas?” gumam supir ojek ketakutan, “Harusnya tadi saya ambil jalan utama saja yang lebih ramai. Paku-paku di jalan tadi, pasti mereka yang sebar. Mereka pasti mau ngebegal motor saya. Kalau saya tak punya motor, saya mau kerja apa?”
“Bapak tenang saja, biar saya urus mereka.”
Nasuti maju di depan supir ojek, menghadapi para pembegal saat mereka turun dari motor dan berjalan mendekat, mengacungkan parang. Jalanan sepi sekali, kalaupun ada yang lewat langsung balik arah ketika melihat para pembegal itu, tak berani menolong. Nasuti menatap para pria itu, berhitung dengan situasi. Tinjunya terkepal saat seorang pria berjaket kulit memelototinya garang. Tampaknya dia pimpinan para begal.
“Serahkan motor kalian kalau mau selamat. Kalau tidak... grokk!” Pria itu melintangkan jarinya di leher. Rekan-rekannya terbahak.
“Enak saja! Kalau mau kaya, usaha dong! Kerja yang halal sana!” hardik Nasuti. Sejak dulu dia benci sekali dengan begal atau geng motor yang tak segan membunuh korbannya.
“Berani macam-macam kau ya!” pria itu berang. Dengan satu isyarat, anak buahnya maju menyerang, menusukkan parang.
Nasuti tak gentar sedikitpun, sigap melawan sebelum musuh siap, menendang salah satu begal hingga terjengkang, lalu menonjok dagu dua orang lainnya yang hendak menyerang supir ojek. Tak sia-sia Nasuti berlatih Shorinji Kempo selama empat tahun di dojo kampus. Sifatnya yang nekat dan tak takut apapun ada gunanya di saat seperti ini. Para begal terkejut melihat mangsanya bisa melawan, semakin beringas menyerang. Bahkan dua orang yang terjungkal segera bangkit lagi, berniat membalas Nasuti yang mulai kewalahan. Dari kejauhan, tampak pengendara motor besar lain mendekat. Nasuti menatap jerih. Agaknya pendatang baru itu satu komplotan dengan para begal, karena mereka tampak tak peduli dan terus mengeroyok Nasuti. Si pemimpin begal malah menarik lepas sorban di leher Nasuti.
“Hei, kembalikan!” teriak Nasuti.
Pria itu melambai-lambaikan sorban dengan mengejek, sementara empat orang lainnya menahan Nasuti yang merangsek maju. Empat orang itu langsung terkapar terkena tonjokan Nasuti yang mengamuk. Dia murka melihat sorban kesayangannya dipermainkan, mencoba merebut sorban dari pimpinan begal yang tertawa.
“Coba ambil kalau bisa, hahaha! Oi, oi... siapa kau?”
Si pimpinan begal berhenti tertawa saat ada yang mencengkeram tangannya, menoleh. Ternyata pengendara motor gede yang baru datang itu yang menahannya. Nasuti tertegun sejenak, menatap si pria berhelm misterius itu. Apakah orang ini berniat menolong?
“Kembalikan, itu bukan punyamu,” kata si pendatang baru, masih memegang tangan si perampas yang melotot. Begal itu memandanginya dari ujung kaki hingga kepala, mencibir.
“Siapa pula kau ini, berani memegang tanganku, hah?”
Pendatang baru itu melepas helmnya, membuat si begal terbelalak. Orang itu masih muda, seumuran Nasuti. Rambutnya hitam legam dan wajahnya teduh. Ada sesuatu pada sorot mata pemuda itu yang membuat si begal ragu, bahkan ketakutan.
“Tak mungkin, kau kan...”
Si begal tak menyelesaikan kalimatnya. Rekan-rekannya juga terdiam, terbelalak ngeri melihat pemuda itu. Akhirnya begal itu melepaskan sorban Nasuti, mengacungkan jari tengahnya dengan lagak mengancam, lalu mengajak kawanannya pergi. Satu-dua masih melirik ketakutan saat menyalakan motornya. Setelah mereka menjauh, Nasuti menghela napas lega, begitu pula supir ojek yang sejak tadi meringkuk ketakutan.
“Kalian tak apa-apa?” kata pemuda itu ramah. “Mereka Geng Motor Makassar, terkenal brutal dan tak pandang bulu menyerang korbannya. Tapi tenang saja, mereka takkan berani macam-macam denganku karena aku kenal bos mereka. Oh ya, kenalkan, namaku Zefry.”
Nasuti menyalami penyelamatnya.
“Terima kasih sudah menolong kami. Aku kaget sekali, tak kusangka ada begal siang bolong begini. Jantungku rasanya hampir copot. Untung kau datang.”
Nasuti memeriksa lengannya yang memar, menunduk utuk memungut sorbannya, lalu mendongak menatap Zefry, sadar pemuda itu terus memandanginya.
“Ah, maaf,” kata Zefry. “Kau mirip sekali dengan adikku. Dia sudah meninggal dua tahun lalu, aku jadi tertegun. Oya, tadi aku melihatmu berkelahi. Kau pemberani sekali, menghadapi lawan sebanyak itu. Jalan ini memang rawan perampokan, harusnya kalian lewat jalur lain yang lebih ramai. Kalian hendak ke Maros kan? Apa perlu kuantar?”
Demi keamanan, Nasuti menyambut baik tawaran itu. Zefry mengawal mereka hingga bertemu tukang tambal ban tak jauh dari situ, menunggu ban diperbaiki, lalu meneruskan perjalanan. Zefry hanya sedikit bicara, sorot matanya lembut, sikapnya tenang dan misterius, membuat Nasuti penasaran. Entah pemuda itu hanya remaja tanggung biasa, jawara beladiri kampung, atau anak pejabat hingga para pembegal itu amat segan padanya.
“Maaf, aku hanya bisa mengantar sampai sini,” kata Zefry, menghentikan motornya di persimpangan. “Hati-hati di jalan. Kuharap suatu saat kita bisa bertemu lagi.”
Zefry tersenyum, melambai, lalu mengambil jalur kiri. Motor besarnya menderum menjauh. Nasuti memandangi punggungnya, masih penasaran siapa dia sebenarnya.
*****
Nasuti meringis saat Inayah memeriksa memar di tangannya, yang baru terasa sakit sekarang. Saat bergumul tadi, dia tak terlalu peduli karena fokus menyerang lawan. Mendengar kisah Nasuti, aku mengingatkan yang lain agar selalu berhati-hati, karena apapun bisa terjadi di perantauan. Sebenarnya dulu sebelum berangkat ekspedisi, kami sudah siap dengan segala risiko di perjalanan, termasuk menghadapi tindak kejahatan, kehabisan ransum, cuaca buruk atau bencana alam yang tak bisa diprediksi. Tapi kejadian barusan cukup mengejutkan juga.
“Padahal hampir saja aku mengalahkan begal-begal itu,” gumam Nasuti.
“Udah, nggak usah sok-sokan, harusnya kamu bersyukur lho masih selamat,” kata Igo. “Mulai sekarang, sebaiknya kita jangan berpencar-pencar lagi. Kalau terjadi apa-apa, risikonya kita tanggung bersama.”
Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Berikutnya kami mengunjungi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, di mana terdapat ratusan jenis kupu-kupu yang terbang bebas di alam liar. Setiba di sana, kami disambut kolam air mancur bertuliskan Bantimurung The Kingdom of Butterflies, dengan tiga patung kupu-kupu raksasa di atasnya. Tak jauh dari situ ada sebuah sungai yang cukup indah, lengkap dengan air terjun yang tak terlalu tinggi. Kami langsung melepas sandal dan menggulung celana, berlarian di atas batuan sungai dan saling mencipratkan air. Inayah tertawa kecil melihat kami. Beberapa kupu-kupu tampak jinak beterbangan dan ada satu yang hinggap di kerudungnya.
Sebelum memasuki kawasan ini saja, kami sudah dibuat takjub dengan pemandangan alam yang luar biasa. Barisan pohon dan hamparan sawah terbentang bagai permadani, dibentengi tebing-tebing menjulang yang puncaknya dipenuhi gerumbul tumbuhan hijau. Kabupaten Maros memang terkenal dengan kontur alamnya yang dipenuhi gugusan tebing karst, yang katanya karst terpanjang kedua di dunia setelah di China. Melihat tebing-tebing itu, aku hampir tak percaya kalau sedang berada di Indonesia.
Setelah puas bermain air, aku tertarik untuk memanjat salah satu tebing. Kebetulan kami bertemu sekelompok warga yang hendak berburu sarang walet. Bapak-bapak itu ramah menyapa kami, dan kelihatannya mereka tak membawa peralatan khusus selain galah dan pisau. Karena penasaran, kami ikut mereka ke salah satu tebing yang katanya banyak terdapat sarang burung walet. Tanpa alat pengaman dan alas kaki, mereka memanjat batuan tebing dengan topografi nyaris tegak, sekitar 85 derajat. Aku terperangah kagum melihat kepiawaian mereka. Rasanya aku jadi sedikit tertantang.
Untunglah bapak-bapak ini berbaik hati mengulurkan tali untuk kami, mengikatkannya pada pasak-pasak yang jarang dipakai. Inilah saatnya mempraktikkan teknik memanjat yang kami pelajari sebelum memulai ekspedisi. Untuk memanjat tebing perlu perlengkapan khusus seperti harness atau sabuk pengaman, carabiner, dan helm. Biasanya pemanjat harus didampingi seorang belayer yang bertugas menarik-ulur tali dari bawah.
“Gimana kalau kita balapan?” Harto menyikutku.
“Oke, siapa takut,” sahutku.
Awalnya kukira Inayah tak mau ikut mendaki dan memilih menunggu di bawah. Namun di luar dugaan, ternyata dia mengajukan diri sebagai pendaki pertama. Harto sempat sangsi, mengira Inayah akan menyerah dan menangis di tengah jalan. Tapi itu tidak terbukti. Seakan sudah berlatih bertahun-tahun, Inayah menjajaki batuan tebing satu persatu dengan mudahnya. Gerakannya cepat sekali, dalam sekejap dia sudah berada di atas tebing, berseru riang. Harto sampai mengucek mata, tak percaya. Aku sendiri tak begitu kaget, teringat aksi si gadis desa saat memanjat tower di kampungnya.
“Jangan remehkan gadisku,” Igo tertawa, menepuk bahu Harto.
Berikutnya giliranku. Setelah memastikan harness terpasang dengan benar, aku mulai memanjat dan menambah ketinggian. Ini sih mudah saja, pikirku. Dari ketinggian ini, aku bisa melihat pemandangan sawah dan rumah-rumah penduduk, begitu juga hutan dan sungai di kejauhan. Setelah aku tiba di atas, giliran yang lain menyusul. Para pemburu sarang walet bergerak lagi. Dari sini, kami masih harus berjalan menyamping melewati tepian tebing dengan pijakan yang sempit, berpegangan ke dinding batu, lalu naik tangga bambu hingga tiba di sebuah gua kecil. Tampaklah puluhan sarang walet menempel di dinding gua yang gelap. Beberapa sarang tampak kosong, namun ada juga yang berisi telur dan anak walet.
Para pemburu ini hanya mengambil seperlunya, memilih sarang yang kosong untuk menjaga kelestarian walet. Katanya sarang walet bisa dijual hingga tiga ratus ribu rupiah per kilo, mengingat pekerjaan mereka yang sangat berisiko. Selain berburu sarang walet, mereka juga mengumpulkan kotoran kelelawar untuk dijadikan pupuk. Bau menyengat menyelusup ke hidung kami saat mereka meraup tumpukan kotoran di dalam gua, memasukkannya ke dalam karung, dan menurunkan karung-karung itu secara estafet menggunakan tali. Satu orang di bawah bertugas sebagai penerima, mengoper kepada rekannya yang ada di bawahnya lagi. Begitu seterusnya hingga karung-karung itu tiba di dasar tebing.
Setelah puas melihat perburuan sarang walet, aku jadi tertarik ingin menyusuri gua-gua di sekitar sini. Di gugusan karst ini banyak terdapat gua dengan keunikan masing-masing, namun yang paling terkenal adalah Gua Salukang Kallang. Dengan panjang 27 km, gua ini dinobatkan sebagai gua terpanjang di Indonesia. Untuk menghemat biaya, kami sepakat tak meminta bantuan guide atau menyewa petromaks, karena kami sudah membawa headlamp. Lagipula di depan kami ada rombongan pengunjung lain, jadi kami tinggal membuntuti saja sambil mencuri dengar saat guide memberi penjelasan. Sebelumnya kami harus berjalan kaki cukup jauh untuk sampai di mulut gua, melewati jalan setapak yang dipenuhi belukar.
“Nah, ayo kita siap-siap, Kawan,” kata Harto seraya mengenakan sepatu bot, helm, dan headlamp. Untuk melakukan caving, diperlukan latihan khusus dan kami wajib menggunakan peralatan pendukung yang sesuai standar kemanan. Untungnya kami cukup berpengalaman dan sudah berkali-kali melakukan penjelajahan gua ketika masih kuliah dulu.
Kami menatap mulut gua yang menganga sepuluh meter di bawah kami, bersiap melakukan caving atau susur gua, sebuah olahraga ekstrem untuk melatih fisik. Gua-gua ini terbentuk akibat pelarutan lapisan kapur atau limestone di bawah tanah yang terjadi ribuan tahun lalu. Bagian dalamnya menyimpan berjuta keunikan dan misteri. Petualangan menuju perut bumi pun dimulai. Bagian teras gua masih bisa ditapaki oleh kaki, setelah itu kami harus rapling menuruni tali sepanjang sepuluh meter untuk sampai di mulut gua. Nasuti mengecek harness yang melilit pinggangnya, lalu masuk ke lubang dan menuruni tali sebagai penjelajah pertama. Berikutnya aku mengikuti, mencengkeram tali dan melonggarkannya beberapa kali ketika meluncur turun.
“Aw panas,” aku berjengit. Tanganku terasa perih akibat bergesekan dengan tambang. Perasaan tegang yang menyenangkan merayapi kulitku ketika perlahan kami meluncur dari ketinggian, menuju kegelapan di bawah sana.
Akhirnya, aku mencelos lega saat menjejakkan kaki kembali di atas tanah. Meski mulut gua sempit, ruangan di dalam ternyata sangat luas dan gelap. Aku menyalakan headlamp, menatap sekeliling. Pemandangan yang ada di depan mataku mengundang decak kagum siapapun yang melihat. Di bagian perut gua terdapat stalagmit dan stalaktit yang tersusun membentuk corak-corak indah. Ada juga batu tetes yang mengeluarkan bunyi indah jika diketuk. Ratusan kelelawar menyerbu ketika kami masuk. Decit mereka terdengar lebih ramai di dalam sana, pasti ada banyak sekali yang bergantungan di langit-langit. Beberapa kecoa merayap di lantai gua yang lembap, membuat Inayah berjengit.
Ketegangan mulai terasa saat masuk lebih dalam ke perut bumi. Entah apa yang ada di dalam sana. Melangkah lebih jauh, kami menemukan sebuah lorong sepanjang 300 meter di depan kami. Berbagai benda unik menghiasi lorong ini, seperti batu sebening kristal, stalagmit yang mencuat dari permukaan gua, serta stalaktit yang menggantung dari langit-langit dan meneteskan air berlapis kapur. Harto menengadahkan kepala dan membuka mulutnya, menjulurkan lidah.
“Puah, air ini rasanya aneh,” kata Harto.
“Ngapain dijilat? Kurang kerjaan aja,” kata Nasuti.
Aku kagum mengingat bahwa selain gua ini, banyak sekali sistem gua berupa lubang bawah tanah yang belum dijelajahi dan tersebar luas di beberapa daerah di dalam bumi. Struktur tanah dan batuan di tempat ini berbeda dengan batuan di luar. Licin dan indah, seperti dari bulan. Selain itu bau kotoran kelelawar menyengat hidung kami. Aku menunduk dan merayap, sesekali harus menyeberangi sungai yang dalamnya sepinggang. Banyak sekali kejutan yang kami temui. Beberapa kali kepala dan punggungku menyundul langit-langit yang kasar, sakit sekali. Makin ke dalam, aku melihat banyak ornamen gua berbentuk aneh. Ada yang menyerupai gajah, otak, hingga tokoh pewayangan. Bahkan ada juga aliran air pada permukaan batu yang berbentuk riak, mirip kolam Pamukkale di Turki sana.
“Kalau gua ini tiba-tiba runtuh, gimana ya?” kata Igo, suaranya bergema. Inayah berjalan dekat-dekat dengannya, melirik deretan stalaktit di atas yang runcing seperti ratusan jarum. “Nggak kebayang kalau kita terjebak di antara batu-batu, nggak bisa keluar.”
“Ah, jangan ngomong gitu dong,” kataku.
“Tahu nih Igo, nakut-nakutin aja,” kata Harto.
Kami merayap maju, sesekali membungkuk rendah hingga merangkak ketika melewati celah-celah sempit, mendorong tubuh ke dalam lubang. Tantangan berikutnya adalah saat kami harus memanjat dinding gua yang curam, karena pintu masuk berikutnya berada di atas kami. Perlahan, kami tapaki dinding gua yang licin berlendir dan berbau kapur, lalu kembali merangkak karena jalurnya sangat sempit. Bajuku basah karena terus bergesekan dengan dinding yang lembab. Harto beberapa kali terpeleset saking licinnya. Tak lama kemudian kami berhenti ketika seberkas cahaya terang menembus udara di tengah kegelapan. Kami mempercepat langkah untuk melihat apa yang ada di depan.
“Masyaallah!” aku berseru kagum. “Allahuakbar!”
“Indahnya, bagai pancaran cahaya surga!” Inayah ikut bersuara.
Kami terpesona saat melihat pemandangan menakjubkan di depan kami. Air terjun bawah tanah mengalir deras, ujung bawahnya tak tampak ditelan kegelapan. Sinar matahari menerobos masuk dari celah sempit di atas, membentuk segaris tiang cahaya dengan ujung menyentuh lantai batu, menyinari kedalaman gua yang gelap gulita. Serbuan air yang menetes dari ketinggian ikut mempercantik panorama itu. Kebetulan saat itu matahari berada di atas kepala sehingga kami bisa menyaksikan cahaya dalam gua yang indah.
“Wah, keren ya,” kata Harto. “Keindahan yang tak terbantahkan. Aku senang bisa melihat mahakarya Sang Pencipta. Rasanya aku bisa semakin dekat dengan alam, dan semoga hal ini menambah keimanan kita.”
Kami mengambil jalur keluar melewati sungai bawah tanah, di mana ada beberapa pengunjung seperti kami yang baru saja menjelajahi gua. Kami menyusuri tepian sungai yang mengalir tenang, dikawal dinding gua yang gelap di kanan-kirinya. Perlahan jalur mulai melandai dan pintu keluar gua membuka di depan kami, memperlihatkan langit biru dan cahaya matahari yang membuat mataku silau. Pohon-pohon jati berdiri dalam barisan di sekitar mulut gua, daun-daunnya melambai seakan mengucapkan selamat tinggal pada kami.
*****
HARI KE-52, TANA TORAJA
Dengan mencarter mobil jeep, kami meluncur menuju Tana Toraja, melintasi jalanan berbatu dan berlumpur, sesekali malah mencoba off road menyeberangi sungai berbatu. Sopirnya orang Bugis asli, masih seumuran kami, rambutnya keriting dan wajahnya berjerawat. Nama aslinya Daeng Muzakki tapi lebih suka dipanggil Deki. Orangnya menyenangkan dan asyik diajak mengobrol. Sepanjang jalan dia terus bergumam dan bicara sendiri, menceritakan pengalamannya saat bergabung dengan tim SAR, sebelum jadi sopir.
“Sebenarnya menyenangkan menjadi anggota regu penyelamat, bisa menolong banyak orang dan ikhlas beramal. Waktu kecil aku memang bercita-cita menjadi superhero, jadi tak jauh-jauh amat lah. Aku pernah ikut mengevakuasi pesawat yang jatuh, mencari orang hilang di gunung, membuat tenda darurat untuk korban banjir, menghibur anak-anak yang desanya tertimpa longsor, hingga membagikan masker di pos pengungsian saat Gunung Merapi meletus. Waktu itu usiaku masih tujuh belas tahun, debut pertamaku sebagai anggota SAR.”
“Lantas kenapa sekarang kau jadi sopir?” tanya Harto.
“Yah, bukannya aku tak betah atau apa. Aku cuma keteteran dengan tugas kuliahku, nilai-nilaiku anjlok karena sering bolos, berhari-hari disiagakan di daerah rawan bencana. Makanya aku keluar dari SAR, dan setelah lulus aku banting stir jadi sopir travel.”
Deki terus bercerita, hingga tak terasa kami tiba di Tana Toraja pukul sebelas malam. Para penduduk berbaik hati menawari kami tinggal di Tongkonan, rumah tradisional Tana Toraja yang berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Tapi aku menolak halus karena sudah memesan penginapan. Rencananya besok kami akan menjajal olahraga ekstrem lainnya, yakni arung jeram. Kebetulan Deki tahu satu lokasi arung jeram yang cukup terkenal di daerah sini.
“Kalau Mas tertarik, besok kita bisa pergi ke Sungai Sa’dan, tak jauh dari sini. Sungai itu cukup populer di kalangan pecinta rafting, arusnya lumayan deras dan menantang dengan berbagai tingkat kesulitan. Gimana Mas?”
“Hmm, boleh deh,” kataku, seraya menghubungi biro penyedia jasa arung jeram terdekat, menyewa perlengkapan lengkap dan istruktur yang biayanya cukup mahal.
Esok harinya, kami melakukan pemanasan dengan berjogging santai keliling kampung, melihat-lihat keindahan rumah Tongkonan. Para penduduk menyapa kami ramah, mengajak berbincang dengan bahasa daerah. Deki dengan sukarela menjadi guide dan penerjemah, menjelaskan berbagai hal yang ia ketahui.
“Kalian tahu bagaimana uniknya ritual upacara pemakaman bangsawan Toraja? Wuih, cara pemakaman mereka cukup ekstrem. Pertama, jenazah dibungkus dengan beberapa helai kain dan disimpan di bawah tongkonan. Konon, arwah orang mati dipercaya tetap tinggal di desa sampai upacara pemakaman selesai. Peti mati mereka biasanya disimpan di dalam gua atau digantung di tebing. Di beberapa daerah, gua-gua batu digunakan untuk meyimpan jenazah seluruh anggota keluarga, lalu mayatnya dibiarkan hingga kering. Musik-musik seperti suling, nyanyian dan puisi, tangisan dan ratapan merupakan persembahan bagi yang sudah meninggal. Makanya upacara pemakaman biasanya makan biaya besar.”
Setelah agak siang, kami bertolak ke Sungai Sa’dan, bersiap melakukan arung jeram. Sungai ini panjangnya mencapai 182 km, membentang dari Pegunungan Latimojong hingga Selat Makassar. Lebarnya bervariasi mulai dari delapan meter hingga puluhan meter, dengan banyak bebatuan besar yang tersebar di sepanjang alirannya. Dua orang instruktur dan sebuah perahu karet sudah menunggu kami di tepi sungai.
Setelah berkenalan dan briefing singkat, kami pun mengenakan pelampung dan helm, bersiap memulai pelayaran. Untuk menggenapkan jumlah orang, aku memaksa Deki ikut ke perahu. Apalagi dia terlatih mendayung dan sudah beberapa kali menolong orang hanyut saat masih di SAR. Inayah juga ikut dan tampak tertantang, ingin mencoba hal-hal baru. Aku memegang dayung dengan bergairah. Rasanya menegangkan, mengingat inilah pertama kalinya kami melakukan arung jeram. Dari penjelasan instruktur, kami tahu bahwa di sungai ini terdapat beberapa jeram—bagian sungai yang deras alirannya—yang tergolong ke dalam Grade III, Grade IV dan Grade V. Namanya pun unik-unik, seperti Jeram Puru, Jeram Nusa, Jeram Lantak-lantak, Jeram Photo-Stop, dan Jeram Fitri.
“Belok kiri! Kiri! Dayung lebih kuat lagi!”
Kami berseru-seru panik saat perahu menuruni jeram yang cukup curam, terhempas ke sungai yang lebih landai. Masing-masing berusaha mendayung sesuai perintah instruktur, menjaga posisi perahu agar tak terbalik, beberapa kali menghindar agar tak menabrak batu. Kepalaku agak pusing saat perahu berputar-putar, meliuk terbawa arus dan terantuk-antuk menuruni bebatuan. Nasuti sejak tadi menekap mulut, mati-matian menahan mual. Dua kali ia tercebur ke sungai, berusaha naik ke perahu. Harto menarik tangannya dan membantu naik, menepuk-nepuk bahunya. Lagi-lagi dia hampir terjungkal di jeram berikutnya.
“Ampun deh, kapok aku naik beginian,” katanya.
Aku tertawa, menatap pemandangan di sekitar sungai yang cukup menghibur. Tampak tebing batu dan bukit-bukit hijau di kejauhan, belum lagi banyak hewan liar bergantungan di pepohonan, seakan mengikuti kami dari tepi sungai. Saat melewati perairan dangkal, kami bisa melihat ikan-ikan dan kepiting di dasar sungai yang jernih. Biasanya para pecinta rafting memerlukan waktu dua hari untuk menaklukkan semua tantangan di Sungai Sa’dan. Banyak juga yang berkemah atau bermalam di rumah panggung di tepi sungai. Tapi mengingat waktu yang terbatas, kami hanya menyusuri sungai selama tiga jam karena masih banyak destinasi berikutnya yang belum kucontreng.
*****
HARI KE-54, PALU & TOGEAN
Deki masih menemani kami hingga Sulawesi Tengah, lincah menyetir jeep menyalip kendaraan lain. Sopir muda itu bercerita sepanjang perjalanan, membuat kantuk kami lenyap. Semalaman kami menyusuri jalan lintas Sulawesi, melewati Danau Poso, melipir ke arah barat menuju Gintu, dan meneruskan ke utara menuju Kota Palu. Pagi itu aku menguap, melirik pemandangan kota yang mulai menggeliat dengan berbagai aktivitas warga.
Saat memasuki kota, perjalanan sempat terhambat saat ada iring-iringan mobil yang dikawal polisi melintas di perempatan, membuat jalanan macet dengan antrean panjang. Deki penasaran, melongok ingin tahu ke arah barisan mobil itu. Begitu tahu bahwa ada rombongan presiden yang sedang mengadakan kunjungan, dia melonjak girang dan bergegas keluar.
“Eh, kau mau ngapain?” seruku.
“Mau selfie, Mas, mumpung ada presiden lewat.”
Tanpa mendengarkan seruan kami, Deki nyelonong pergi ke arah iring-iringan dan bergabung dengan warga lain yang menonton, meninggalkan kami di dalam mobil. Lama sekali dia pergi, sosoknya bahkan tak kelihatan di antara kerumunan. Aku tak tertarik sama sekali, mulai kepanasan di dalam mobil. Iring-iringan presiden perlahan berlalu, tapi Deki belum kembali juga. Kendaraan di belakang kami ramai mengklakson, bahkan ada yang berteriak menyuruh kami maju. Apa boleh buat, pikirku. Karena Deki meninggalkan kunci mobilnya, aku terpaksa pindah ke kursi depan, menyalakan mesin, menginjak pedal gas dan membawa mobil melewati lampu merah, lalu menepikannya di depan sebuah toko.
“Eh, kau bisa nyetir mobil, Lutfi?” tanya Harto antusias. Teman-temanku yang lain tampak sama terkejutnya. Aku mengangguk saja, bilang sering belajar mengemudi bersama Paman Ilyasa. Daripada itu, aku lebih khawatir pada Deki, cemas jika sopir eksentrik itu mengejar iring-iringan presiden sampai jauh. Tak lama kemudian dia tergopoh menghampiri kami, agak kaget melihat mobilnya sudah di seberang lampu merah.
“Maaf ya Mas, maaf banget... Habisnya ini kesempatan langka. Presidennya nggak kelihatan, tapi yang penting saya sempat memotret mobilnya. Lumayan buat diposting di instagram, hehe.”
“Udah, ayo cepat berangkat,” kata Harto.
Deki minta maaf sekali lagi, memacu jeep menuju lokasi berikutnya, melintasi jalan berkelok-kelok yang cukup terjal. Tujuan kami adalah Matantimali yang merupakan salah satu tempat paralayang terbaik di dunia. Letaknya di lereng Gunung Gawalise, Kecamatan Morowali, Kabupaten Sigli, sekitar empat puluh menit dari Kota Palu. Tiba di sana, kami masih harus berjalan kaki lagi, menyusuri padang rumput nan luas, dan langsung terpesona dengan keindahan panorama Kota Palu di kejauhan. Jika malam tiba, pemandangannya pasti lebih indah lagi dengan kerlap-kerlip lampu kota yang memukau. Banyak yang berkemah juga di situ, menikmati keindahan Lembah Palu dari ketinggian 1500 mdpl. Lokasi ini pernah dipakai untuk kejuaraan dunia paralayang, dan kami juga bertemu beberapa atlet yang sedang berlatih. Menatap parasut warna-warni yang melayang di ketinggian, aku langsung tertarik.
“Serius nih, kita mau naik paralayang?” tanya Igo.
Aku mengangguk. “Nggak ada salahnya kan mencoba? Memang sih, perlu skill dan keterampilan khusus untuk menjajal olahraga menantang ini, tapi aku yakin kita pasti bisa. Kemarin kita sudah mencoba panjat tebing, susur gua, dan arung jeram. Sekarang saatnya kita terbang di langit, pasti seru banget.”
Seorang pemandu membimbing kami, menjelaskan tutorial singkat mengendalikan parasut. Kami memakai berbagai perlengkapan seperti flight suit, harness, helm, sarung tangan, dan parasut. Aku suit dengan yang lain, menentukan siapa yang terbang duluan. Untunglah masih ada tiga parasut tersedia, jadi kami tak perlu mengantre lama. Dibantu pemandu, kami mengecek peralatan dan menghamparkan parasut berbentuk oval panjang di tanah. Aku, Harto dan Nasuti bersiap dengan parasut masing-masing. Seorang pemandu berdiri di belakangku, memberi instruksi agar aku berlari menuruni lereng. Aku mengangguk, berlari sekuat tenaga, tak berhenti hingga menjejak ujung tebing. Aku berteriak kencang saat mendompak, merasakan kakiku tak menapak tanah lagi, membiarkan parasut terangkat dengan sendirinya oleh turbulensi udara.
“Subhanallah! Ini luar biasa!” teriakku.
Rasanya mendebarkan saat tubuhku melayang, ringan terbawa angin dan meliuk di udara. Harto dan Nasuti menyusul naik, sementara Igo, Inayah dan Deki tampak mengecil di bawah sana, bersorak-sorak. Aku memegangi tali parasut, mendengarkan instruksi pemandu di belakangku yang sesekali mengecek variometer, alat pengukur ketinggian. Aku melambai pada kamera gopro yang kuletakkan di tongsis, merasakan sensasi yang berbeda dengan naik pesawat karena berhadapan langsung dengan udara luar. Kami terbang di langit selama 30 menit, berputar-putar menembus awan, menyesuaikan parasut dengan kecepatan angin untuk terbang lebih tinggi lagi.
Pemandangan Kota Palu tampak semakin indah dari ketinggian ini, dengan rumah-rumah yang berupa titik kecil, aliran sungai, bukit-bukit hijau, serta lautan di sisi lain. Aku sedikit tegang saat pemandu menawariku memegang tali kemudi, mencoba sensasi menjadi pilot dadakan. Tak mudah mengendalikannya. Terpaan angin yang berhembus kencang ke lereng gunung menyebabkan turbulensi, dan kami memanfaatkan turbulensi itu untuk mengangkat parasut. Setelah puas berputar-putar, aku mengarahkan parasut turun, bersiap landing. Rasanya masih mau lagi, tapi aku harus bergantian dengan yang lain.
Aku bersiap saat mulai mendekati daratan, berlari kecil dan jatuh terduduk di rumput, tertawa. Kedua temanku ikut mendarat, tapi Harto malah meleset, bukannya mendarat di lapangan malah tersuruk ke luar pagar, lupa bagaimana cara landing. Teriakan pemandu tak terdengar olehnya akibat angin kencang. Nasuti terbahak-bahak melihatnya nyungsep di semak-semak. Kini giliran Inayah dan Igo yang mencoba paralayang, meninggalkan Deki yang hanya bisa menatap iri. Dia tak mengeluh, tapi raut wajahnya terlihat ingin sekali. Karena kasihan, aku menyuruhnya ikut terbang dan biayanya aku yang traktir. Sopir muda itu tak percaya mendengar ucapanku, bersorak girang dan menyalamiku berkali-kali, mendekati salah satu pemandu yang sedang merapikan parasut dan minta diajak terbang.
Sementara mereka bersenang-senang, aku mengobrol dengan tiga pengunjung lain yang ternyata wartawan acara TV. Begitu tahu kami membuat film dokumenter dan berkeliling Indonesia, wartawan itu berseru takjub dan menepuk pundakku, meminta nomor ponselku, bilang akan membantu mempromosikan film kami jika diperlukan. Aku senang berkenalan dengan mereka, apalagi si kameramen merekam dan mewawancaraiku.
Ketiga rekan kami segera mendarat saat gerimis turun, memaksa kami berteduh dan tak bisa berlama-lama menikmati pemandangan bukit. Setelah isi perut sejenak, mencicipi kaledo alias soto kaki lembu dan bawang goreng, kami pun berpamitan dengan tiga wartawan itu, bergegas menuju mobil dan melanjutkan perjalanan karena hari beranjak petang. Hujan turun semakin deras, dan lagi-lagi kami harus melewati jalanan rusak dan berlubang. Kami tak sempat turun saat melewati Poso, meskipun tadinya aku berniat melihat penangkaran burung maleo yang terancam punah. Kami sudah cukup puas mendengar cerita tentang burung itu dari penuturan Deki, yang tampaknya tahu banyak tentang berbagai hal. Selain burung maleo, Sulawesi yang berada di antara Garis Wallace dan Garis Weber juga dihuni hewan endemik lainnya seperti anoa, tarsius dan monyet hitam Sulawesi.
Saat melintasi hutan yang sepi, tiba-tiba Deki membahas hal mistis.
“Kalian pernah dengar cerita tentang kota gaib Uwentira? Lokasinya persis di hutan ini, dan konon hanya orang tertentu saja yang bisa melihat kerajaan jin itu. Katanya, kota itu sangat megah dan didominasi warna kuning. Para penghuninya adalah bangsa jin muslim, tapi ada juga yang jin jahat. Wujud mereka konon menyerupai manusia, hanya bedanya tidak punya garis di atas bibir. Bagi orang biasa, lokasi ini hanya terlihat seperti hutan biasa. Tak ada rumah penduduk, hanya pohon-pohon besar yang mengerikan. Sudah banyak orang yang meninggal di tempat ini karena tertimpa longsor. Konon kalau ada orang yang berbuat tidak sopan di daerah ini, dia akan hilang secara misterius alias diculik jin.”
“Ngeri juga ya,” kata Harto. “Aku jadi ingat tentang berita yang kubaca beberapa bulan lalu, tentang sebuah bus yang tiba-tiba nyasar ke tengah hutan. Kalian juga ingat kan?”
“Iya, itu kok bisa aneh banget ya?” kata Nasuti. “Padahal tadinya bus itu lagi ngebut di jalur Pantura, eh tahu-tahu ada di tengah hutan lebat. Padahal mustahil bus bisa masuk ke hutan serapat itu dalam kondisi normal, pasti bakal tersangkut dahan atau menabrak pohon. Anehnya, pas diperiksa, tak ada jejak ban atau semak yang terlindas. Itu gimana masuknya?”
“Itu sih belum seberapa, setidaknya busnya masih selamat,” kata Deki. “Kalian tahu tidak, di selatan Sulawesi ini ada wilayah laut berbahaya yang disebut Segitiga Masalembo. Letaknya di pertigaan antara selat Makassar, Laut Jawa dan Laut Flores, terkenal sebagai laut mematikan dan tak kalah misterius dari Segitiga Bermuda. Sudah banyak kejadian kapal dan pesawat tenggelam di perairan itu. Entah apa sebabnya. Kalau menurutku sih lebih karena faktor alam, karena arus laut yang labil atau cuaca ekstrem misalnya. Tapi tak sedikit juga yang percaya kalau di kawasan laut itu berdiri sebuah kerajaan jin.”
“Benar tidaknya wallahu a’lam, hanya Allah yang tahu,” kataku. “Yang jelas, sebagai orang beriman, kita harus percaya dan yakin dengan keberadaan makhluk gaib, seperti jin. Namun di sisi lain kita juga jangan mudah percaya pada desas-desus yang tak jelas. Mungkin saja kisah-kisah itu sudah dibumbui sana-sini biar terkesan seru, kan? Nah, mending sekarang kita tidur. Besok pagi-pagi kita harus ke pelabuhan. Oya, Deki, kalau kau mengantuk bilang saja ya, nanti gantian biar aku yang menyetir.”
Aku sukses menghentikan obrolan yang ngalor ngidul. Deki mengangguk, dan kami pun beranjak tidur. Terakhir kulihat ke jendela, mobil jeep yang kami tumpangi menerobos hutan yang semakin gelap. Sopir muda itu meski tampak mengantuk, nyatanya sukses mengantar kami hingga Pelabuhan Ampana, sama sekali tak minta digantikan. Menjelang subuh ia membangunkan kami. Kantung matanya menggayut akibat kurang tidur.
Udara asin menyergap hidungku begitu aku keluar dari mobil. Dari sini kami akan naik feri melintasi Teluk Tomini, menuju Kepulauan Togean. Deki ikut shalat subuh di mushala kecil, menemani kami sarapan dan mengantre tiket. Saat kapal hendak bertolak, ia menyalami kami dan kelihatan agak sedih. Sejujurnya aku juga merasa berat, karena di antara semua sopir yang mengantar kami, dialah yang paling akrab dan enak diajak mengobrol. Deki melambai saat kami menaiki feri, dan aku balas melambai, berseru menyuruhnya istirahat.
Perlahan, feri mulai berlayar menyeberangi Teluk Tomini.
Aku berdiri di buritan kapal, menatap laut. Mumpung masih ada sinyal, tak lupa aku menelepon Ibu dan Paman Ilyasa, saling bertanya kabar dan bercerita tentang pengalaman beberapa hari lalu. Harto tiduran di dek, menutupi wajah dengan jaket menghalau panasnya mentari. Igo dan Inayah berdiri agak jauh dariku, berseru riang melihat kawanan lumba-lumba berlompatan mengikuti kapal. Nasuti tak ada di sini. Mungkin di dek penumpang, mati-matian menahan mual.
Empat jam berlalu, akhirnya kapal merapat di Kepulauan Togean. Kawasan seluas 70 ribu hektar ini terletak di tengah-tengah Teluk Tomini, terdiri dari enam pulau besar yaitu Pulau Malenge, Una-Una, Batudaka, Talatakoh, Waleakodi, dan Waleadahi. Aku bersorak riang saat menuruni kapal, tak bisa berhenti tersenyum. Tempat ini sudah lama kuidam-idamkan dan kumasukkan dalam daftar sepuluh lokasi diving yang harus dikunjungi. Meskipun akses ke tempat ini agak sulit karena letaknya terpencil, namun Togean tak kalah indah dengan lokasi menyelam populer lainnya seperti Raja Ampat atau Wakatobi. Pokoknya tempat ini sudah seperti surga bagi para pecinta laut sepertiku.
Kami memutuskan untuk bersantai lebih lama di Togean, sekitar satu-dua hari. Uniknya di tempat ini kami tak perlu memesan penginapan, karena para penduduk berbaik hati mengajak kami menginap di rumah mereka, tanpa dipungut biaya alias gratis. Rencananya kami akan mengunjungi Danau Mariona, di mana banyak terdapat spesies ubur-ubur yang tidak menyengat. Aku juga tertarik menyambangi Pulau Papan yang dihuni Suku Bajo, para pelaut tangguh yang membuat perkampungan di atas laut. Di pulau itu kami bisa melihat pantai berpasir putih dan deretan rumah papan yang bertengger di atas laut.
Menjelang sore, kami melakukan snorkeling di sekitar Pulau Kadidiri, melihat bangkai pesawat tempur sisa-sisa Perang Dunia II yang ditumbuhi koral dan anemon. Harto memakai kamera bawah air untuk merekam kondisi kokpit dan baling-baling yang sudah rusak, kadang ditempeli aneka siput dan cacing laut yang bergerak-gerak lucu. Di dekat pesawat itu kami juga menemukan kerang raksasa, kawanan schooling fish yang melesat cepat, barakuda, gurita belang, hingga puluhan bulubabi yang bertebaran di dasar perairan. Kami bergerak hati-hati agar tak menginjak bola-bola hitam berduri tajam itu.
Kami juga mengunjungi Pulau Malenge dengan perahu sewaan, bermain sejenak di pantainya yang berpasir putih. Ditemani anak-anak setempat yang periang, kami berlarian di jembatan sepanjang 1,8 Km dan menceburkan diri ke laut, tertawa ke arah kamera. Nasuti menggantikan tugas Harto, menerbangkan drone untuk mengambil gambar dengan view terbaik. Sedangkan Harto si kameramen malah sempat-sempatnya memancing ikan dan gurita dari atas perahu, untuk kemudian dilepaskan lagi. Rupanya dia masih terobsesi dengan teknik memancing yang dipelajarinya dari Gun, anak nelayan yang kami temui di Sumbawa.
Aku duduk santai di atas hammock—kain semacam ayunan yang diikatkan pada dua batang pohon, merasa tenang dan damai dibuai angin laut. Aku membuka-buka facebook dan melihat postingan teman-temanku dari tim Zhen, memantau lokasi mana saja yang mereka kunjungi. Aku tersenyum melihat foto-foto dan video yang diposting Torik. Rupanya mereka sudah menjajal body rafting di Green Canyon Pangandaran, naik gondola di Pantai Timang Jogja yang curam dan terjal, hingga bersemedi di bawah derasnya Air Terjun Madakaripura.
Saat ini kabarnya mereka sedang bersantai di Wakatobi, dan foto terbaru yang diposting Torik memperlihatkan sosok dirinya, Zhen dan Muqodas tengah berpose di tepi pantai dengan latar belakang barisan pohon kelapa. Aku kenal betul barisan pohon kelapa itu, karena aku sering melihat gambarnya di internet. Caption yang ditulis Torik di bawah foto itu juga lucu: Liburan di Salah Satu Surga Wkwkwkland (Indonesia). Aku agak iri pada mereka, karena Wakatobi juga termasuk salah satu tujuan wisata impianku. Sayangnya aku tak sempat ke sana karena repot harus memutar jauh ke tenggara dari Kota Palu.
Anehnya aku tak melihat Hana memposting foto satu pun, padahal biasanya dia paling suka selfie. Bahkan di foto-foto yang diposting Muqodas dan Zhen pun Hana tak ikut berfoto. Entah ke mana dia, apakah terjadi sesuatu pada wajahnya sehingga dia malu berfoto? Atau jangan-jangan dia ketahuan mamanya pergi tanpa izin, lalu memutuskan pulang lebih cepat? Ketika aku bertanya pada Torik lewat sms, dia hanya membalas singkat, “Hana ada kok, dia baik-baik saja. Beberapa hari lalu dia memang terlihat pucat dan minta izin sebentar untuk periksa ke rumah sakit, tapi setelah itu dia sehat-sehat saja. Soal dia yang tak mau difoto, itu ada alasannya sendiri. Kau juga akan tahu nanti. Sampai jumpa di Papua ya. Bye-bye.”
*****
HARI KE-57, MANADO
Dari Togean, kami naik kapal feri selama 12 jam menuju Gorontalo, dan dari sana langsung meneruskan perjalanan darat menuju Sulawesi Utara. Tiba di perbatasan provinsi, sopir travel mengingatkan kami agar waspada karena di daerah ini sering terjadi perampokan. Katanya hampir setiap hari ada pengguna jalan yang dihadang orang-orang bersenjata, dipaksa menyerahkan kendaraannya. Kami langsung deg-degan, dan Nasuti komat-kamit merapal doa, berharap tak berurusan lagi dengan begal seperti tempo hari. Untunglah peristiwa yang kami takutkan itu tidak terjadi. Kami tiba dengan selamat di Kota Manado pukul lima pagi, dalam kondisi lapar dan mengantuk. Agak sulit mencari masjid di Ibukota Sulawesi Utara ini. Untunglah kami menemukan sebuah mushala kecil di pinggiran kota. Setelah shalat subuh, kami tiduran sejenak di teras, baru terbangun sekitar pukul delapan.
“Lapar nih, cari sarapan yuk,” ajak Harto.
“Aku tahu tempat makan yang enak,” kataku, teringat seorang kenalan yang tinggal di sini. Kami mencuci wajah sebelum berangkat, dan Inayah malah sempat-sempatnya mandi di kamar kecil mushala, lantas sibuk merapikan jilbab. Dengan menumpang angkot berwarna biru, aku mengajak mereka ke suatu pasar yang ramai didatangi orang. Teman-temanku tampak antusias melihat keramaian ini, apalagi pasar ini menjual aneka bahan makanan.
“Kalian tahu Pasar Beriman di Tomohon nggak?” Harto menyeletuk. “Kalau kalian ke sana, para pedagang akan menawari sate dan dendeng yang kelihatan lezat sekali. Tahu nggak, itu daging hewan apa? Yang dijual di pasar itu adalah daging anjing, biawak, monyet, ulat, laba-laba, lipan, dan hewan menjijikkan lainnya. Namanya juga pasar kuliner ekstrem.”
Teman-temanku langsung pias mendengar cerita Harto. Inayah menjerit ngeri, Nasuti menahan muntah, dan Igo mengelus dada, beristighfar.
“Tenang, kita tidak akan makan di tempat seperti itu kok,” kataku. “Lagipula pasar itu kan adanya di Tomohon, sudah terlewat kemarin. Beberapa blok dari sini kebetulan sedang ada festival kuliner, dan ada kenalanku yang kuliah di kota ini membuka stand di sana. Dia koki hebat lho, masakannya dijamin halal.”
“Tapi selera makanku kayaknya sudah hilang deh,” kata Igo mual. Harto mengelus bahunya, minta maaf sudah bercerita soal pasar tadi.
“Eh, Lutfi, koki yang kaumaksud itu si Sanjaya kan, kakaknya Ruqoyah?” tanya Harto. Aku mengangguk, lega tak perlu menjelaskan lebih jauh. Harto tampak senang. “Wah, kalau dia yang masak sih, aku oke-oke saja.”
Tak lama kemudian kami tiba di festival kuliner tersebut. Banyak tenda-tenda dan stand didirikan, dengan para koki dan pemilik restoran yang tampak sibuk memasak di setiap stand. Kesannya lebih bersih dan menggugah selera dibanding pasar yang diceritakan Harto. Pengunjungnya pun banyak sekali. Aroma lezat langsung tercium begitu kami memasuki area itu, membuat kami ingin mencoba beragam kuliner khas Nusantara yang dijajakan. Aku menghampiri salah satu stand, tersenyum lebar saat melihat sepupuku, Sanjaya, yang sedang membolak-balik telur di wajan. Pemuda itu melihatku, tersenyum dan melambai. Tadi malam aku sudah menghubunginya, bilang akan berkunjung.
“Wah, kalian juga datang rupanya,” Sanjaya melepas celemek dan menyalami teman-temanku, memeluk mereka akrab. Mereka sudah saling kenal, tentu saja, karena dulunya Sanjaya juga kuliah di Unsoed, kakak kelas kami. Hanya saja, menginjak semester lima, dia memutuskan pindah kuliah dan merantau ke Manado.
“Bagimana standmu? Pengunjungnya ramai?” tanyaku.
“Begitulah, setidaknya lebih laris dari stand lain sejak hari pertama festival. Tapi aku bukannya tak punya saingan. Kalian lihat stand di seberang sana itu? Masih pagi begini saja sudah ramai. Wajar sih, pemiliknya teman kuliahku yang juga hobi memasak dan punya kreasi baru setiap harinya. Namanya Chef Shomad, anak pemilik restoran terkenal dan pegawainya banyak. Sedangkan aku, kerja dari pagi hingga sore cuma dibantu dua orang pegawai, dan sekarang mereka belum datang.”
Jika diperhatikan, Sanjaya sedikit mirip dengan adiknya, Ruqoyah. Wajahnya cukup rupawan, dengan janggut tipis dan poni belah samping. Sejak kecil ia hobi memasak, jago sekali membuat masakan Barat, China dan Nusantara yang dipelajarinya manual dari buku resep. Sekarang ia sibuk mengurus restoran miliknya dekat Bandara Sam Ratulangi, Manado. Hanya satu kekurangannya yang menonjol, yaitu suka jelalatan melihat perempuan.
“Eh, gadis itu siapa?” dia membisikiku, menunjuk Inayah yang duduk di meja makan bersama yang lain. Sambil memasak, Sanjaya sesekali meliriknya. Begitu kuberitahu kalau Inayah istrinya Igo, Sanjaya tertawa. “Baguslah kalau Igo sudah menikah. Sejak dulu aku tak pernah setuju kalau adikku suka padanya. Mereka tak cocok. Kau juga sependapat kan?”
Aku mengangguk, meski yakin sekali Sanjaya mengalihkan topik karena tahu Inayah sudah menikah. Kalau masih gadis, Inayah pasti diembatnya. Sepupuku itu tampak kecewa, berpura-pura sibuk, lincah memainkan wajan di atas api kompor yang menjilat-jilat. Sesekali dia memutar-mutar pisau, memotong sayuran dengan cepat, memasukkannya ke dalam panci, lalu menaburkan bumbu-bumbu, harum sekali. Entah apa yang dimasaknya. Tak lama kemudian, lima mangkuk sup terhidang di meja di depan stand.
“Sup asparagus khas Madura, gratis untuk kalian, Teman-teman. Silakan dicicipi, bon appetite,” Sanjaya membungkuk.
Aku mulai menyendok, mencicipinya. Hmm, memang lezat. Sejak dulu aku selalu suka masakannya. Kalau aku mengajak Torik, kawanku yang pecinta kuliner itu pasti tak mau pulang saking lezatnya sup asparagus ini. Sambil makan, kami juga dihibur sekelompok penari yang membawakan Tari Cakalele dan Tari Maengket khas Minahasa di atas panggung. Rupanya selain menjajakan kuliner, festival ini juga mengadakan pertunjukan seni budaya untuk menarik pengunjung. Kami menikmati sup dengan lahap, dan Harto bahkan minta tambah. Hanya Igo yang mengernyit, mendorong mangkuknya menjauh. Entah dia masih mual teringat pasar ekstrem tadi atau karena menyadari Sanjaya melirik istrinya.
“Hei, habiskan makananmu, Igo, mubazir,” tegur Sanjaya.
“Kalau nggak mau, buat aku saja ya?” kata Harto, mengambil mangkuk Igo yang masih tersisa setengah porsi dan menyeruputnya. “Padahal enak banget lho.”
“Ya, masakan ini lumayan,” kata Igo, menatap Sanjaya. “Tapi menurutku masakan istriku masih lebih baik. Benar kan Ine?”
“Eh?” Inayah menoleh, mengelap mulut dengan tisu.
“Untuk membuktikannya, bagaimana kalau kita adakan demo masak?” kata Igo. “Di sini, sekarang juga. Kita lihat siapa yang lebih jago masak, kau atau istriku.”
“Boleh, siapa takut,” kata Sanjaya, tapi Inayah menggeleng.
“Aduh, aku malu Kang, takut masakanku nggak enak,” katanya gugup. “Lagipula ini mendadak sekali. Aku cuma tahu beberapa resep.”
“Tak usah malu, masakanmu enak kok,” kata Igo. “Waktu aku melamarmu dulu, makan malamnya kamu yang masak kan? Itu enak lho, serius.”
Aku mengangguk setuju. Hidangan malam itu memang Inayah yang memasak, dan masakannya lezat sekali. Dalam ekspedisi ini pun Inayah berperan ganda sebagai dokter dan juru masak, menggantikan Torik si jago masak yang ikut regu Zhen. Hanya saja selama ini kami makan di hotel atau restoran, jadi Inayah tak pernah berkesempatan menunjukkan keahliannya memasak. Karena Igo terus mendesak, Inayah akhirnya menurut. Apalagi Igo terus-terusan memuji masakannya, membuat wajahnya merona merah.
“Kalau hanya dua orang yang bertanding, rasanya kurang seru,” kata Sanjaya. “Aku akan memanggil Chef Shomad, kebetulan aku juga ingin menantangnya adu masak. Nanti kalau aku menang, kalian harus mengajakku ke Bunaken.”
“Hah, Bunaken?” kataku.
“Ya, aku sudah lima kali ke sana, tapi tak bosan-bosan,” kata Sanjaya “Tujuan utama kalian datang ke sini memang Bunaken kan? Ayolah, siapa yang sanggup menolak pesona tempat itu. Kebetulan ini hari terakhir festival, jadi besok aku bisa libur barang satu-dua hari.” Dia pun bergegas ke stand di seberang, memanggil koki saingannya.
Chef Shomad seumuran Sanjaya, wajahnya penuh semangat dan matanya berbinar saat menyalami kami. Pembawaannya ramah dan menyenangkan, dalam sekejap dia langsung akrab dengan kami. Harto dan Nasuti yang sama-sama periang seperti cocok dengannya. Uniknya dia tak mengenakan pakaian putih ala koki seperti Sanjaya, hanya memakai kaus lusuh dan celemek biasa. Padahal dia koki restoran bintang tiga.
“Wah asyik nih, aku paling suka lomba masak,” katanya. “Kalian tenang saja, akan kubuatkan masakan spesial yang membuat kalian tak bisa berhenti mengunyah.”
Dia menunjuk Nasuti, Harto dan aku sebagai jurinya, lalu menyuruh pegawainya menggotong meja, kompor, dan alat masak tambahan. Aneka bahan dan bumbu juga sudah disiapkan. Ketiga peserta bebas membuat masakan apa saja, dengan tema masakan Indonesia.
“Bikin steak boleh nggak?” tanya Inayah.
Sanjaya dan Shomad saling pandang. Akhirnya Sanjaya yang menjawab sambil tersenyum, “Boleh, asal disesuaikan dengan tema kita, masakan Indonesia.”
Ketiga peserta bersiap. Sanjaya menggulung lengan baju dan memakai topi putih panjang ala koki, Shomad cuma memakai ikat kepala, dan Inayah memakai celemek, tak mau kalah. Sama seperti saat memanjat tebing beberapa hari lalu, Inayah tampak tertantang. Sifatnya yang malu-malu dan selalu merendah itu lenyap saat menghadapi peralatan masak, digantikan semangat membara dan sorot mata yakin, seakan hendak menerkam siapapun yang menantangnya. Igo tersenyum pada istrinya, melihat jam tangan dan memberi aba-aba memulai pertandingan.
Ketiga peserta langsung bergerak menyiapkan bahan, lalu mengolahnya seperti tanpa berpikir. Dengan cekatan, Inayah memotong sayuran, mengaduk isi panci, lalu pindah ke wajan di sebelahnya. Sanjaya dan Shomad juga bersaing tak kalah sengit.
“Cuma segitu kemampuanmu? Lihat nih, aku bisa begini,” Sanjaya memanasi Shomad, membesarkan api kompor, melempar-lempar isi wajan ke udara dan menangkapnya lagi tanpa ada yang tumpah. Dia juga melempar tiga butir tomat ke udara, lalu memotongnya dengan sekali tebasan pisau tanpa perlu talenan. Gerakannya lihai sekali persis ahli kung fu.
“Itu sih tak ada apa-apanya, aku juga bisa. Lihat nih, kau pasti kewalahan melakukan ini.” Shomad memotong-motong cepat, membuat irisan daging ayam yang sama besar, tak berbeda semili pun. Dia juga mengeluarkan tepung adonan yang dipadatkan, meremasnya, lalu dibentangkan dengan dua tangan, ditarik ulur dengan jari hingga membentuk tali-tali panjang. Rupanya dia hendak membuat mie.
Kami yang menonton hampir tak berkedip melihat sengitnya persaingan mereka. Kadang mereka saling lirik mengawasi peserta lain, bergerak sibuk dari satu panci ke panci lain sambil menyiapkan bumbu. Hanya Inayah yang fokus dengan pekerjaannya. Saking semangatnya, dia sampai menjatuhkan pisaunya.
“Ups, pisaumu jatuh, My Lady,” Sanjaya tersenyum, memungutkan pisaunya. Inayah menggumamkan terima kasih, sementara Igo berdehem memperingatkan. Aku, Harto dan Nasuti menonton dari meja makan, tak sabar mencicipi masakan trio koki ini. Igo memeriksa jam tangannya, beberapa saat lagi waktunya habis. Kira-kira siapa ya yang akan menang?
Akhirnya Igo meniup peluit, waktunya habis. Kebetulan ketiga peserta juga sudah selesai. Dengan elegan, Shomad meletakkan enam piring ke meja makan, membungkuk sopan. Rupanya dia membuat mie cakalang dan bubur manado, makanan khas setempat. Melihat tampilannya saja membuat liur kami menetes. Sanjaya tak mau kalah, menyodorkan tiga porsi bebek sinjay khas Bangkalan dan halua kenari. Aromanya langsung merebak menggelitik hidungku. Adapun Inayah menyajikan serabi manis, steak tempe dan mie kocok bandung. Sikapnya yang berapi-api saat memasak tadi lenyap sudah, digantikan sikapnya yang biasa. Dia tampak gugup, tersenyum sambil menunduk dan ikut duduk bersama kami.
Aku menelan ludah, tergiur, mulai menyendok menu di depanku satu persatu. Semua tampak apik dan ditata dengan menarik. Aku menyeruput mie kocok, membiarkannya di mulutku, lalu kutelan perlahan. Ini enak sekali, tak terasa air mataku keluar. Berikutnya aku menggigit bebek sinjay dan mengunyah seratnya yang liat, kemudian menyecap steak tempe buatan Inayah, membandingkan rasanya. Aneka masakan ini seakan berpesta pora di lidahku, membuatku merasa terbang ke alam mimpi.
“Wah, semuanya enak,” kata Nasuti. “Kalau Torik ikut nyicipin, dia pasti jadi lebay, sampai nangis-nangis saking lezatnya masakan kalian.”
“Iya, aku juga bingung menentukan siapa pemenangnya,” kata Harto.
“Jadi juri yang serius dong,” kata Igo.
Akhirnya aku buka suara, “Baiklah... kalau dari sisi kreatif dan tampilan menu, Shomad yang menang. Tapi kalau menilai rasa agaknya Sanjaya lebih unggul. Rasa bebeknya pas, tak terlalu asin atau pedas, dan bumbunya meresap sempurna. Inayah juga tak kalah hebat, karena kulihat dia selalu fokus dan memberi perhatian lebih pada masakannya.”
“Jadi, pemenangnya?” tanya Igo.
Aku, Harto dan Nasuti saling berbisik, mengangguk, lalu sepakat menunjuk Sanjaya sebagai juaranya. Sepupuku tampak senang, tersenyum sumringah dan menepuk-nepuk bahu Shomad, saingan abadinya yang tampak kecewa.
“Sepertinya aku masih harus banyak belajar,” Inayah menunduk. “Maaf Kang Igo, aku kalah. Padahal aku sudah berusaha semampuku.”
“Jangan berkecil hati, masakanmu udah top banget kok,” hiburku. “Wajar sih, lawanmu kan koki restoran bintang tiga. Kamu harusnya bangga lho bisa bertanding dengan mereka.”
Igo mengelus bahu Inayah, membesarkan hatinya. Sanjaya berbaik hati mengantar kami jalan-jalan keliling Manado setelah kedua pegawainya datang, menggantikan menjaga stand. Kami diajak mengunjungi Citraland, Kelenteng Ban Hin Kiong yang berumur ratusan tahun, dan Universitas Sam Ratulangi tempat Sanjaya kuliah. Kami juga berbelanja oleh-oleh khas Manado seperti salak lahendong, gula semut tondanagow, dan pia pinaras. Malamnya Sanjaya mengajak kami menginap di rumah kontrakannya yang cukup luas. Lega rasanya beristirahat setelah seharian berkeliling kota.
*****
HARI KE-58, BUNAKEN
Sesuai janji, setelah festival kuliner berakhir, esoknya Sanjaya kuajak ke Taman Laut Bunaken yang berada di Teluk Manado, tak jauh dari sini. Bahkan Shomad juga ikut berlibur, membawa tas besar berisi pakaian. Kedua koki itu tampak senang terbebas dari rutinitas. Kami menumpang feri dari Pelabuhan Manado, hanya butuh empat puluh menit untuk sampai di tujuan. Aku bersorak riang setiba di sana, tak sabar ingin menjelajahi Pulau Bunaken, Siladen, Manado Tua, dan Mantehage yang terkenal beken di kalangan penyelam.
Di tempat ini terdapat sekitar 20 titik penyelaman scuba diving, di mana para penyelam akan mendapat kesempatan berenang di dasar laut dengan beragam biota laut yang menakjubkan dan penuh warna. Ada sekitar tiga belas jenis terumbu karang di taman laut ini yang didominasi oleh bebatuan laut. Ditambah lagi ada dinding karang laut yang mirip rak buku, di mana setiap kotaknya dihuni ribuan biota unik seperti beragam jenis ikan, kimah raksasa, ikan kepala kambing, goropa, koi putih, dan gurita bercangkang alias nautilus.
Kami juga berkesempatan menyelami keindahan dasar laut Bunaken lebih jauh dengan menumpang kapal selam berdinding kaca, mengamati gunung berapi bawah laut dan palung laut sedalam 1200 meter. Menurut keterangan pemandu, waktu terbaik untuk mengunjungi Bunaken yaitu antara bulan Mei hingga Agustus. Wah, beruntung sekali kami datang di waktu yang tepat. Setelah puas menyelam, kami mencicipi makanan andalan tempat ini, seperti bubur manado dan nasi kuning seroja yang rasanya tak terlupakan dan bersemayam di lidahku. Chef Shomad dan Sanjaya berbaik hati memasak untuk kami.
Lelah setelah seharian bermain air, aku kembali ke homestay dan memutuskan tidur lebih awal. Teman-temanku masih mengobrol di beranda, tapi aku sudah mengantuk. Besok kami harus ke bandara dan melanjutkan perjalanan ke Ternate. Saat aku hendak tidur, suara dering HP mengejutkaku. Aku meraih HP dan menyalakannya.
Ternyata sms gombal itu lagi.
Hai Sayang, udah bobo belum? Sebentar lagi aku berangkat, jadi agak sedih juga. Aku tak bisa melupakanmu, kenangan indah sejak aku mengenalmu, terutama aksimu ketika ikut turnamen itu, keren banget! Tapi nggak apa-apa, suatu saat kau akan kuajak ke kampus baruku. Banyak salju lho di sana!
Emosiku langsung berubah dalam sekejap. Aku tak tahu harus bagaimana menanggapi orang semacam ini. Dia pengagum rahasia yang meresahkan, dan sms itu semakin hari semakin parah. Tapi tunggu dulu... banyak salju katanya? Hm, pasti suatu tempat di luar negeri, dan dia bilang baru akan berangkat ke sana. Jangan-jangan orang ini adalah...
Aku harus memastikannya. Kucoba mengirim sms: Kau nonton pertandinganku ya? Aku setengah berharap sms itu tidak dibalas, karena biasanya juga tidak. Tapi aku berseru girang saat ada balasan masuk: Ya, kan kau sendiri yang mengundangku.
Aha, dia membocorkan rahasanya sendiri! Aku kan hanya mengundang temanku saja di turnamen itu. Aku berjingkrak senang, penyelidikanku selangkah lebih maju. Mendadak aku dapat ide bagus. Dengan gesit, kubongkar hp-ku dan kuganti kartunya dengan kartu cadangan yang sudah kusiapkan. Aku akan coba menelepon dengan nomor tak dikenal, menangkap basah pelakunya. Misteri ini akan segera terungkap. Hatiku berdebar, gelisah, mondar-mandir sambil menunggu teleponku diangkat. Si biang kerok ini takkan bisa berkutik.
“Halo, dengan siapa ini?” terdengar jawaban. Itu kan suara Nelly!
“Ini aku,” kujawab pelan.
“Maaf, siapa ya?”
“Tidak ingat suaraku?” kataku tenang.
Terdengar pekikan kaget di seberang telepon. Agaknya Nelly menjatuhkan HP-nya. “Eh, L-Lutfi? B-bagaimana kau bisa tahu nomorku?”
“Itu tidak penting,” kataku. “Jadi, yang selama ini mengirimi sms itu kamu ya?”
"Itu... itu... eh, bagaimana ya?” dia tergagap. “Aduh, aku jadi malu. Itu... itu bukan aku. Eh, maksudku itu memang aku, tapi bukan ideku. Maafkan aku, sms itu mengganggu ya? Aku tidak serius kok, iseng saja mengirim sms itu.”
Aku menghela napas. Jadi semua kata-kata manis itu baginya hanya iseng? “Jangan begitu dong, nggak baik. Kita bukan muhrim, tak sepantasnya kau mengeluarkan kata-kata mesra seperti itu. Lagipula bukannya kamu naksir Igo?”
Kata-kata lembut itu baginya sangat menusuk.
Maafkan aku” katanya. “Sebenarnya, selama ini aku mendekati Igo karena ingin tahu banyak tentangmu. Aku takkan melakukan itu lagi, kumohon jangan beri tahu siapa-siapa. Kupikir dengan mengirimimu sms akan membuatku puas.”
Sekarang giliranku terdiam. Apa yang dikatakannya tadi?
“Aku tak mau seperti Ruqoyah,” katanya. “Kau tahu apa yang dialaminya, kan? Ya, dia juga menceritakannya padaku. Sejak tahu Igo melamar gadis lain, dia sangat kecewa. Tak pernah aku melihatnya semurung itu. Tak ada keceriaan tersisa di wajahnya. Gadis yang malang. Tapi tenang saja, dia sudah bahagia sekarang. Dia bilang, akhirnya menemukan tambatan hati yang baru. Siapa orang itu, aku juga tak tahu.”
Nelly menghela napas, berkata lagi, “Kau pasti menganggapku wanita rendahan, tak punya malu... Terserah kau menganggapku apa setelah ini, tapi karena sudah kepalang basah, biar kukatakan satu hal. Aku… aku merindukanmu. Lebih tepatnya aku rindu kalian semua.”
Aku diam sejenak.
“Jadi, intinya kau suka padaku?” tanyaku penuh harap.
Nelly terdiam lama, kemudian menjawab, “Tidak.”
“Hah?” aku terbelalak mendengar jawabannya. “Lalu kenapa kau mengirimiku sms itu? Apa maksudmu sebenarnya?”
“Sudah kubilang, itu cuma iseng saja,” katanya.
“Keterlaluan sekali kau. Apa untungnya coba, melakukan itu?” kataku kesal. Betapa tidak, ucapannya persis seperti salah satu gadis yang pernah kulamar dulu. Awalnya kupikir si gadis suka padaku, karena sering melirik dan mukanya memerah setiap kali aku lewat di depannya. Dia bahkan pernah keceplosan memujiku ganteng. Begitu aku menanyakan hal ini, berniat melamarnya, nyatanya dia menyangkal dan tak mau mengaku. Entah apa sebabnya. Salah seorang teman wanitanya bahkan memusuhiku, mengancamku agar aku tak berani mendekati si gadis lagi. Usut punya usut, ternyata si gadis sudah punya pacar. Dia tak mau pacarnya tahu kalau dia tertarik padaku. Sungguh, aku tak pernah mengerti isi hati wanita.
“Sekali lagi kau mengirim sms seperti itu, kau... kau...”
"Iya, aku mengerti,” Nelly tergagap, sadar suaraku meninggi. “Setelah ini aku takkan berbuat bodoh lagi, aku berjanji. Oya, nanti sore aku berangkat ke Jepang. Tolong sampaikan salam perpisahanku ke teman-teman yang lain. Maaf sudah mengganggumu.”
Nelly menutup telepon, meninggalkan aku termenung dengan perasaan campur aduk. Aku mengusap wajah, meremas tangan dengan gelisah. Kupikir setelah semua sms itu, Nelly memendam perasaan padaku. Jadi itu hanya akal-akalannya saja? Ah, tentu saja. Mana mungkin ada gadis yang suka padaku. Buktinya sudah tiga orang akhwat kulamar, tapi semuanya menolakku dengan alasan yang tak jelas. Padahal aku mengajak mereka menikah, bukan pacaran seperti kebanyakan muda-mudi lain. Mereka seperti ragu menilaiku.
Terakhir kali aku melamar akhwat, aku ditanyai berapa juz Al-Qur’an yang kuhafal. Aku merendah, bilang baru hafal dua juz meskipun sebenarnya sudah lima belas juz. Aku menjawab begitu karena niat awalku menghafal Al-Qur’an adalah murni Lillahi ta’ala, bukan untuk melamar gadis. Mendengar itu si akhwat langsung diam, tak mengatakan apa-apa lagi. Akhirnya dia memutuskan akan fokus kuliah dulu, baru mempertimbangkan lamaranku. Aku pun menunggu dengan sabar, bekerja keras mengumpulkan uang dan berniat melamarnya lagi setelah wisuda. Kabar buruknya, aku tak perlu menunggu sampai wisuda. Sungguh terlalu. Beberapa bulan kemudian, aku terkejut mendengar kabar bahwa dia menikah dengan pria lain, dan aku tak diundang atau diberitahu sama sekali.
Aku frustrasi dan kecewa sekali, merasa semua kerja kerasku tak dihargai. Harto yang datang ke pernikahan itu menghiburku, bilang bahwa mempelai prianya tak seganteng diriku, hanya menang di isi dompet. Menurut Nasuti, lelaki itu bahkan tak rajin shalat di masjid dan bacaan Al-Qur’annya masih terbata. Entah apa yang dipikirkan si akhwat. Aku beristighfar dan menegur mereka, tak baik membicarakan orang. Mungkin lelaki beruntung itu punya kelebihan yang tak kumiliki. Lagipula aku sudah mengikhlaskannya, sadar bahwa gadis itu memang bukan jodohku. Sejak itu aku tak pernah memikirkan soal jodoh lagi, yakin bahwa “si tulang rusuk” sudah disiapkan oleh Allah dan kelak akan datang dengan sendirinya. Bahkan boleh jadi jodohku itu seratus kali lebih baik dari gadis-gadis yang meninggalkanku.
Lamunanku terhenti saat ada yang mengetuk pintu.
“Kak Lutfi lagi sibuk?” terdengar suara Inayah. Aku meletakkan HP dan bergegas membuka pintu, melihat wanita itu berdiri gugup sambil mematut-matut jari.
“Ah, nggak sibuk kok. Ada perlu apa ya?” kataku ramah.
Punten... boleh tanya sesuatu?”
“Silakan,” kataku.
Inayah tampak gelisah. Dia menoleh ke kiri-kanan seakan takut dicuri dengar. Saat Inayah bertanya, waktu seakan berjalan lambat. Aku melihat bibirnya bergerak-gerak pelan, meluncurkan pertanyaan horor yang membuatku hanya bisa bungkam.
Mbak Ruqoyah itu... siapanya Kang Igo?”
*****


 radenbumerang
radenbumerang





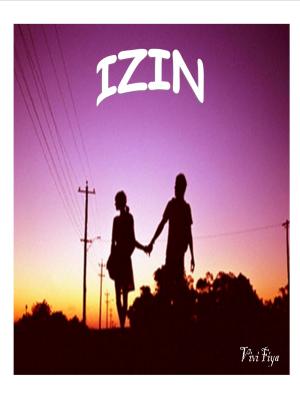




Iya juga yah, satu bab aja sepanjang ini... makasih masukannya Mas AlifAliss, mungkin ke depannya saya bagi per bab aja biar lebih pendek.