BAB 3. SHEN TRAVEL
Aku berdiri di depan bangunan berlantai dua, berpelataran luas, dipagari bambu tinggi dan dikelilingi pot-pot berisi tanaman hias. Inilah bangunan terindah di dunia yang selalu kurindukan, baiti jannati, rumahku surgaku. Kuturunkan ransel ke tanah. Letih akibat lima jam perjalanan naik bus Purwokerto-Cirebon tak lagi terasa ketika aku melihat sosok itu mendekat. Aku berlari dan menghambur memeluk ibuku, seorang wanita paruh baya berwajah ramah dan berkerudung lebar. Empat bulan lebih kami berpisah, namun serasa empat tahun bagiku. Dengan tangan merangkul, Ibu mengajak masuk. Ia telah membuatkan bakso sapi favoritku. Perut yang kosong sejak pagi terasa makin melilit saat aku duduk di meja makan. Sambil mengunyah, diam-diam kuperhatikan wajah Ibu. Kerut-kerut penuaan tampak jelas di dahi dan pipinya. Aku sadar ia sudah tak muda lagi, dan aku berpaling seakan tak ingin menerima hal ini.
“Maaf, Ibu tak bisa hadir ke acara wisudamu.”
Aku tertegun. Itu permintaan maaf yang kesekian kali.
“Tak apa-apa Bu, aku mengerti. Kehadiran Paman dan Bibi kemarin sudah membuatku sangat senang. Lagipula Ibu kan sedang sakit, jangan memaksakan diri bepergian jauh. Sudah, jangan pikirkan itu lagi ya. Doa dari Ibu saja sudah cukup bagiku.”
Ibu perlahan mengangguk, dan aku tersenyum.
Kami bahagia walau hanya hidup berdua. Selama ini kami hidup berkecukupan berkat paman-pamanku yang berbaik hati membiayai kami. Terutama Paman Ilyasa, adik ayahku yang punya banyak perusahaan di kota dan rumahnya bersebelahan dengan kami. Aku sangat berhutang budi padanya. Sejak dulu, ialah yang menanggung biaya hidup kami, termasuk biaya sekolahku. Selain itu, kami juga sesekali menerima kiriman dari Paman Jali di Madura. Dalam hati aku bersyukur karena masih memiliki keluarga yang baik dan peduli.
Malam itu kuhampiri Ibu yang tengah menjahit sarung di ruang tengah, kupijat bahunya dan kusampaikan niatku dengan hati-hati, bahwa aku akan mengadakan perjalanan bersama teman-teman. Kusodorkan formulir yang sudah kuisi, berharap Ibu mau menandatanganinya. Aku berdebar menanti jawabnya, namun ia hanya menatap lama, ekspresinya tak bisa ditebak. Kemudian, perlahan ia menggeleng. Artinya tidak mengizinkan. Aku kaget. Sudah jauh hari kuberitahu Ibu tentang rencana itu. Dulu ia mengizinkan bahkan mendukungku. Kenapa sekarang ia berubah pikiran?
“Tapi itu cita-citaku sejak kecil Bu,” aku memohon.
“Dengarkan kata-kata Ibu, Nak, kamu belum siap. Nanti kalau kamu sudah cukup pengalaman, baru Ibu izinkan.”
“Tapi, Ayah bilang...”
“Jangan bawa-bawa ayahmu!” teriaknya. Aku sampai terlonjak. Kemudian, dengan lebih lembut ia berkata, “Jangan sekarang, Nak. Saat ini, lebih baik kaulakukan apa saja yang penting untuk masa depanmu.” Aku menunduk lesu mendengarnya.
“Baiklah kalau Ibu bilang begitu,” aku menurut. Percuma saja mendebat. Sambil menunduk lesu kuarahkan langkah ke kamar, lalu menutup pintu pelan-pelan. Sejak dulu aku memang anak penurut. Aku tak mau jadi anak durhaka. Aku bukan Malin Kundang.
Aku termenung di kamar yang gelap. Rencana selama bertahun-tahun itu kini luruh seperti menara tinggi yang roboh terkena gempa. Aku teringat janji pada teman-teman. Aku harus bilang apa pada mereka? Bisa kubayangkan semua pasti kecewa. Impian yang tinggi ini harus kurelakan dengan berat hati, meski sudah di depan mata. Aku mengerti alasan Ibu melarangku. Tentu ia masih trauma setelah kepergian Ayah.
Aku teringat sesuatu. Dalam gelap, aku bergerak malas ke arah tembok, meraba saklar dan menyalakan lampu, lalu membungkuk di atas sebuah kotak kayu tua di sudut kamar—kotak rahasiaku, tempat aku menyimpan berbagai benda berharga seperti mainan atau catatan rahasia. Kuputar kuncinya, lalu kubuka tutupnya perlahan. Segera saja serbuan debu memenuhi hidung, membuatku bersin-bersin. Kuulurkan tangan untuk meraba benda antik di dalamnya: topi koboi cokelat tua warisan ayahku. Kuangkat tinggi-tinggi, dan begitu kupakai, aku tercengang mendapatinya pas di kepalaku. Dulu topi itu terlalu besar hingga menutupi wajahku. Mengingat masa itu, aku juga teringat Ayah, sosok yang selalu kurindukan dalam mimpi-mimpiku.
Aku ingat Ayah sering menggendongku, mengajari bermain layang-layang, mengajak berkeliling kota, meski aku hanya samar-samar ingat sosoknya. Ia seorang pria yang senang merantau dan hampir tiap bulan bertugas ke luar negeri. Profesinya sebagai ahli zoologi mengharuskannya sering menjelajah alam liar, baik itu menyelam di laut, menelusuri gua, atau keluar-masuk hutan untuk keperluan penelitian. Saat itu, aku baru berumur sepuluh tahun ketika Ayah meninggalkan kami. Katanya ia punya proyek penting dengan rekannya di Jerman, untuk menyelesaikan jurnal ilmiahnya. Saat hendak berangkat, ia pegang bahuku, membenamkan topi Indiana Jones-nya di kepalaku, lalu berkata pelan menembus kalbu.
“Ingatlah nasehat Ayah, Nak. Jelajahilah dunia karena Al-Qur’an juga memerintahkan demikian. Berjalanlah di muka bumi dan pelajarilah apa yang terjadi pada sejarah manusia di masa lalu. Lihatlah bahwa betapa Mahabesar Allah yang telah menciptakan bumi dan isinya, tempat-tempat menakjubkan yang belum terjamah dan flora-fauna liar yang mengagumkan. Dunia itu luas, tak sebatas negeri ini saja. Carilah pengalaman, temukan kebesaran Tuhan di manapun kakimu berpijak, karena Dia tak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Ah, sebenarnya Ayah ingin sekali mengajakmu, tapi kau punya cerita yang harus kaurangkai sendiri. Petualangan besar menantimu di luar sana. Taklukkanlah garis khatulistiwa. Ingat pesan Ayah dan simpan selalu dalam hatimu. Jaga ibumu baik-baik.”
Kata-katanya membekas di hatiku. Dalam pelukan ibuku, aku melihat punggung Ayah menjauh, perlahan naik ke kapal Paman Jali. Itulah terakhir kali aku melihat sosoknya. Sejak itu ia tak pernah kembali. Selama ini, Ibu tak pernah memberitahu ke mana ia pergi. Jika kutanya, Ibu pasti pura-pura tidak mendengar atau buru-buru mengalihkan pembicaraan. Tampaknya ada yang disembunyikan. Aku tak mengerti mengapa Ibu merahasiakan hal itu dariku. Tanpa sadar air mataku mengalir teringat kenangan bersama Ayah.
Aku terlonjak saat terdengar suara ketukan. Segera kuusap mata yang basah. Ketika membuka pintu, kulihat wajah Ibu berubah cerah.
“Ibu sudah pikir baik-baik,” katanya. “Kamu... boleh pergi.”
“Yang benar, Bu?” aku melonjak girang. “Tapi, bagaimana dengan Ibu?”
“Ibu akan baik-baik saja. Ada Paman Ilyasa dan Bibi Alia yang menemani.” Perlahan, suaranya menghilang ditelan pilu. ”Hanya saja, Ibu tak ingin kehilanganmu, Nak. Kamu masih terlalu muda untuk perjalanan seberat itu.”
Air matanya merebak. Sekarang aku tahu alasannya melarangku pergi. Ia tak ingin aku bernasib seperti Ayah. Segera kupeluk ibuku erat-erat.
“Jangan khawatir, Ibu,” kataku. “Aku sudah bernazar melakukan perjalanan ini, jadi tak bisa mundur. Aku janji tidak akan berbuat yang aneh-aneh, pasti langsung pulang. Nanti kubelikan oleh-oleh yang bagus untuk Ibu.”
Dengan jemariku, kuusap air mata di pipinya.
*****
Langit tampak jernih dan dipenuhi bintang ketika aku duduk di taman belakang rumah, menyepi di tempat yang adem sekaligus mencari sinyal internet. Aku menatap layar laptop, meneliti daftar email yang masuk ke inbox. Mengetik dengan cepat untuk menyelesaikan novel yang akan kulombakan. Sejak kecil, menulis cerita adalah hobiku.
“Sendirian aja nih?” terdengar suara ramah, membuyarkan lamunanku.
Aku menoleh, melihat dua orang menghampiri dari arah rumah. Ternyata Paman Ilyasa dan Bibi Alia. Keduanya duduk di bangku di sebelahku.
“Lagi cari angin, Paman,” jawabku. “Kapan Paman datang?”
“Baru saja,” Paman tersenyum, mengacak rambutku.
Nama pamanku Ilyasa Haythami, seorang penulis novel sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Mahira, jabatan yang diwarisinya dari Kakek. Selain itu, ia juga seorang CEO beberapa perusahaan terkenal meski usianya masih terbilang muda, 36 tahun. Sebagian besar perusahaan itu didirikannya bersama Ayah, yang artinya kelak akan jadi milikku juga. Tapi aku tak begitu tertarik dengan warisan ini karena masih harus melanjutkan kuliah. Agaknya pamanku yang lulus S2 di Al-Azhar Cairo ini juga berprinsip sama denganku, karena meski kekayaannya setara atau melebihi keluarga Zhen, ia selalu tampil bersahaja dan menjauhi barang bermerk. Istrinya, Bibi Alia Zulfiana Syifa adalah wanita muda berjilbab panjang, berwajah elok dan murah senyum.
“Bagaimana rencana keliling Indonesianya? Sudah menentukan mau ke kota mana saja?” tanya Paman tenang. “Kalau boleh, Paman akan memberimu tips. Nah, coba kamu baca ini,” ia mengulurkan sebuah buku padaku. Judulnya unik: Kepingan Surga Itu Ada di Indonesia. “Sebelum memutuskan tujuan, sebaiknya kamu pelajari dulu jurnal ini. Ayahmu sendiri yang menulisnya. Isinya catatan mengenai tempat-tempat yang pernah kami berdua kunjungi di Indonesia. Siapa tahu berguna dan bisa kaujadikan pedoman.”
Aku menerima jurnal itu, membaca isinya sekilas. “Kenapa harus Indonesia?” tanyaku. “Dan apa yang dimaksud ‘kepingan surga’ di sini?”
“Hmm kedengarannya kamu seperti meremahkan negara kita,” Paman nyengir. “Jangan salah lho, banyak wisata unggulan di Indonesia yang tak kalah menakjubkan dibanding negara lain. Ingat fakta ini: Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 km², mencakup daratan dan lautan. Indonesia disebut juga sebagai Nusantara karena terdiri atas pulau-pulau yang berjumlah 17.508 pulau. Dan yang dimaksud kepingan surga di buku ini adalah daerah-daerah yang Paman anggap sebagai bagian dari surga dunia yang tercecer, saking indahnya tempat itu.”
“Nggak perlu uang banyak buat keliling Indonesia,” kata Bibi. “Yang penting punya modal nekat dan tekad baja. Saat masih kuliah dulu, pamanmu ini pernah berjalan kaki puluhan kilometer, dari satu kota ke kota lain, berdua dengan ayahmu. Waktu kehabisan uang, sebetulnya bisa saja mereka mengambil uang di mesin ATM, tapi mereka lebih suka berhemat dan menggunakan sedikit bekal yang tersisa. Kadang juga harus makan umbi-umbian hutan, atau apa saja yang bisa dimakan, sebagai pengganti nasi. Katanya sih survival. Meski begitu, mereka nggak pernah kapok bertualang di alam liar. Pamanmu ini memang senang sekali bertualang di tempat-tempat aneh seperti rawa atau hutan.”
“Ya, begitulah,” kata Paman, meluruskan kacamata perseginya. “Yang penting kan cari pengalaman. Soal biaya itu tidak penting, karena mudah dicari. Oh ya, tantemu juga suka bertualang lho. Bedanya tantemu ini sukanya bertualang di mall alias shopping.”
“Ah Mas ini,” Bibi mencubit lengannya.
Paman tergelak, lalu menepuk bahuku, berkata serius, “Paman kasih tahu nih, Lutfi, biasanya perjalanan panjang akan membuka kedok teman-temanmu. Dalam beberapa hari saja kamu akan tahu seberapa jauh kesetiaan mereka sebagai teman, apakah mereka akan terus bersamamu sampai akhir atau meninggalkanmu. Karena di perjalanan nanti pasti kalian akan menghadapi berbagai kesulitan yang menguji kesabaran dan kesetiaan.”
"Kok kedengarannya mengkhawatirkan ya?” kataku.
Paman mengangguk. “Dulu juga Paman sering membuktikan sendiri. Biasanya kalau travelling bareng, sifat asli dan kebiasaan buruk seseorang bakal keluar semua. Yang rajin bantu-bantu, yang pendiam, yang tukang marah, yang kerjanya menyuruh saja, yang suka mengeluh, semua akan ketahuan.”
Aku mengangguk, sejenak memandangi langit. Malam itu cerah tak berawan, sehingga bintang-bintang tampak jelas bertaburan bagai permata. Sesekali tampak pesawat yang lewat berkelip-kelip. Pemandangan itu bagaikan lukisan dunia lain yang dibentangkan di atas kepala, begitu memesona, membuatku betah berlama-lama menikmatinya. Sejak dulu, aku memang suka sekali memandangi langit.
“Dinda, tolong buatkan teh panas ya.” Paman menatap istrinya.
“Pakai gula nggak, Mas?” Bibi Alia berdiri.
“Hmm boleh, tapi sedikit saja ya. Lihat Dinda aja udah manis kok.”
Bibi mengikik, beranjak, menjawil bahu Paman sebelum pergi. Paman mengawasinya masuk ke rumah. Setelah pintu ditutup, Paman berbisik padaku, pelan sekali, “Eh, Lutfi, apa benar ekspedisimu disponsori Shen Travel?”
Aku mendongak menatap Paman, menyadari ada yang aneh dari nada suaranya. Raut wajahnya, entah kenapa tampak mendung.
“Iya, Paman. Itu perusahaan keluarga temanku. Memangnya kenapa?”
“Begini, Lutfi, Paman ragu untuk menyampaikan ini, tapi rasanya kamu perlu tahu,” Paman memelankan suaranya, wajahnya masam. “Paman kenal CEO perusahaan ini. Dulu dia pernah menjalin kerjasama dengan ayahmu, mengembangkan bisnis bersama. Paman masih menyimpan fotonya, sebentar... nah, ini dia.”
Aku menatap layar tablet Paman, memandang foto dua orang yang saling berangkulan di depan Menara Eiffel. Yang satu kukenali betul, itu pasti Ayah. Satunya lagi seorang pria tinggi besar, berwajah rupawan dan tampaknya keturunan Tionghoa. Di balik pembawaannya yang ramah, aku juga menangkap kilatan ambisi di matanya yang tajam.
“Namanya Shen, mantan TNI yang banting stir jadi pebisnis. Setiap perusahaan yang dirintisnya berkembang pesat berkat otaknya yang brilian. Meski begitu, dia punya reputasi buruk sehingga ayahmu terpaksa menghentikan kontrak kerja dengannya. Ah, sekarang belum waktunya menceritakan itu padamu. Nanti Paman janji akan menceritakannya. Yang jelas, dua tahun kemudian Shen mendirikan beberapa perusahaan sendiri, dan salah satunya adalah Shen Travel. Dalam waktu singkat, perusahaan ini melejit dan membuat pemiliknya jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Tapi kejayaannya tak berlangsung lama. Karena insiden tertentu, dia hengkang dari perusahaannya sendiri. Yah, nanti juga kamu tahu soal itu. Sekarang Shen Travel diambil alih koleganya, salah seorang anggota keluarga temanmu yang bernama Zhen itu.”
Aku diam saja, belum mengerti ke mana arah pembicaraan ini.
“Syukurlah perusahaan itu sudah dikelola orang lain, karena jika Shen yang masih memegang kendali, Paman pasti akan menyarankanmu menolak tawaran ekspedisi gratis itu,” kalimat tegas Paman membuatku kaget. “Ah, sudahlah, tak baik membicarakan itu sekarang. Belum waktunya kamu memikul tanggung jawab perusahaan, jadi cerita ini sampai di sini saja.” Paman merogoh tasnya, lalu mengulurkan sesuatu ke tanganku. “Hanya firasat, tapi Paman rasa ada baiknya kamu membawa ini di perjalanan nanti.”
Aku terbelalak melihatnya. “Lho, ini kan...”
“Bawalah, siapa tahu perlu. Jika terjadi sesuatu, jangan ragu untuk menggunakannya sebaik mungkin. Ingat, jangan bilang ke siapa-siapa ya. Pembicaraan ini hanya di antara kita, jangan sampai... ups, bibimu datang!”
“Hayo habis ngobrol apa? Ngomongin Bibi ya?” Bibi Alia menghampiri kami, membawa tiga cangkir teh. Paman menyeruput tehnya, bersikap cool. Sejak dulu, aku selalu mengagumi Paman Ilyasa. Bagaimanapun, ia paman yang unik dan eksentrik. Ia seorang ustad tapi sikapnya tak terlalu formal, pokoknya enak diajak berdiskusi.
“Kau pasti sangat merindukan ayahmu,” kata Paman. “Ayahmu orang hebat, meski agak menjengkelkan sih. Dulu Paman sering bertengkar dengannya, memperebutkan saluran televisi. Ayahmu bersikeras ingin menonton bola, sedangkan Paman merengek minta nonton kartun. Saat itu usia kami masih sangat belia. Paman sangat menyayangkan kenapa dia pergi meninggalkan kalian. Ayahmu memang keras kepala dan tak bisa ditebak.”
“Apapun pekerjaan Ayah di luar sana, itu pastilah penelitian yang sangat menarik,” kataku. “Kelak, aku pasti akan mencarinya di manapun ia berada.”
“Wah, kamu selalu bangga dengan ayahmu, ya?” Bibi Alia tersenyum.
Suasana hening sejenak. Sambil menyeruput teh, aku memikirkan banyak hal, terutama kata-kata Paman tadi. Aku jadi penasaran siapa sebenarnya Shen, bagaimana hubungannya dengan Ayah, dan apakah ini semua ada hubungannya dengan ekspedisi nanti.
“Sudah malam Mas, dingin, ayo masuk,” kata Bibi, berdiri. “Kamu juga sebaiknya tidur, Lutfi. Jangan begadang lho, nggak baik buat kesehatanmu.”
Aku mengangguk pelan. Paman dan Bibi beranjak. “Jangan lupa baca bukunya ya,” Paman mengusap kepalaku lagi, lalu meninggalkanku berdua dengan laptop. Aku tersenyum lega, tiba-tiba mendapat ide. Berpedoman buku Kepingan Surga Itu Ada di Indonesia, aku merombak ulang rute yang sudah kubuat, menentukan kota mana saja yang akan kukunjungi. Setelah puas, aku mendongak menatap langit, tak sabar menunggu keberangkatan. Kami sepakat untuk berkumpul di Bandara Soekarno Hatta, seminggu dari sekarang.
*****
Akhirnya saat yang kunantikan selama bertahun-tahun itu tiba: hari keberangkatan. Tepat tengah hari, aku menginjakkan kaki di bandara bersama Paman dan Ibu yang bersikeras mengantar ke Tangerang. Mereka mengantar masuk hingga pelataran bandara. Kulebarkan pandangan mencari teman-teman. Kulihat Igo diantar ayahnya, Dokter Isnain. Igo tampak malu ketika dipeluk ayahnya erat-erat. Dasar manja, pikirku. Tak jauh darinya, Harto dan Nasuti datang bersama tanpa diantar. Torik, Hana, Muqodas dan Zhen berdiri bergerombol dengan bawaan masing-masing.
Kelompok Muqodas akan memulai start di lokasi yang sama dengan kelompokku, di Banda Aceh. Rencananya kami akan ekspedisi bersama selama di Sumatera, sebelum nantinya berpisah di Lampung dan mengambil rute berbeda, menunaikan misi utama masing-masing yaitu membuat film dokumenter. Zhen membawa dua handycam dan drone untuk keperluan dokumentasi, satu dibawanya sendiri dan satu lagi dipinjamkan ke Harto. Dengan penuh kebanggaan, mereka memakai jaket almamater Unsoed. Mereka melihatku, dan aku melambai tinggi-tinggi.
“Ananda pamit dulu, Bu,” kataku, mencium tangan Ibu yang keriput.
Kami saling pandang penuh arti. Kemudian, tanpa disangka-sangka, Ibu merengkuhku dalam dekapan erat, sekan tak ingin melepas pergi. Kasihan Ibu. Aku tak tega meninggalkan Ibu sendiri di rumah. Aku memejamkan mata, hati sedih meskipun tak ada air mata yang mengalir. Hampir semenit kami bertahan, hingga Ibu melepas pelukan, namun tangannya masih memegang bahuku.
“Maaf Ibu tak bisa memberi apa-apa,” katanya pilu.
“Tak perlu Bu, aku hanya butuh doa dari Ibu,” kataku pelan. Dalam hati aku merasa malu. Harusnya akulah yang memberi, bukan meminta. Aku juga ingin mengajaknya, tapi ibuku harus cukup istirahat. “Jaga Ibu ya, Paman.”
Paman mengangguk. “Jaga diri baik-baik, ingat nasehat Paman ya.”
Ibuku berpesan lagi, “Hati-hati di jalan. Jangan berhenti berdzikir.”
Aku mengangguk, lalu berbalik dan melangkah ke loket. Teman-temanku menyambut, dan Harto yang bawaannya enteng membantu mengangkat ranselku.
“Topimu bagus,” komentar Nasuti. Aku tersenyum, balas memuji sorban putih yang melilit lehernya, warisan sang ayah.
“Nah, karena sudah berkumpul, gimana kalau kita putuskan nama kelompok ekspedisi kita?” kata Torik. “Muqodas, Zhen dan Hana juga bikin nama kelompok, ‘Langlang Buana’, masa kita kalah sama mereka?”
"Gimana kalau ‘Penakluk Khatulistiwa’?” kataku, mengutip judul puisi yang kubaca di jurnal ayahku. “Tapi kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa.”
“Hmm, boleh juga,” kata Nasuti, manggut-manggut.
“Kedengarannya keren,” Harto sepakat.
“Nah, satu masalah beres,” kata Torik. “Sekarang tinggal putuskan siapa ketuanya. Jika beberapa orang melakukan perjalanan, salah seorang harus dijadikan pemimpin. Nah, siapa di antara kita yang cocok?”
“Sudah pasti kan,” Harto langsung menjawab. “Kaptennya Lutfi, aku wakil kapten, lalu Igo orang ketiga, Nasuti orang keempat dan Torik orang kelima, hahaha!”
“Woooi!” Nasuti protes. “Apaan tuh, pakai peringkat segala. Siapa yang sudi jadi orang keempat?”
“Gubrak berjamaah!” Igo menepuk dahi.
Kami menoleh saat ada yang berteriak di belakang. Seorang gadis berkerudung ungu berlari melintasi pelataran, tak salah lagi menuju kami. Ternyata Renata, gadis yang diam-diam sering menguntit Harto di kampus. Dengan malu-malu, gadis berwajah lembut itu mendekati Harto, mengulurkan sepucuk surat dengan amplop merah jambu. Harto tampak terkejut dengan kelakuan adik kelasnya. Ranselku yang berat dijatuhkannya.
“Apa ini?”
“Anu, t-tolong dibacanya nanti saja,” Renata menunduk, memilin ujung kerudungnya dengan malu-malu. “A-aku sudah lama memikirkan ini. Se-semalaman aku sampai nggak bisa tidur. Begitu tahu Kak Harto akan berangkat, aku langsung menulis surat ini. Jangan marah ya Kak.”
“Nggak apa-apa, aku malah senang kok,” Harto menerima suratnya.
“Hati-hati di jalan, semoga perjalanannya menyenangkan,” Renata tersenyum.
“Cie cie,” Nasuti dan Igo menggodanya. Torik bersuit-suit.
“Ruqoyah sama Nelly ke mana? Nggak kelihatan,” Nasuti menyikut Igo. “Aneh sekali mereka nggak ikut melepas keberangkatan Igo tersayang.”
“Berisik ah!” Igo cemberut. “Jangan meledekku terus dong.”
“Oke oke, aku nggak tahu soal Nelly. Tapi kalau Ruqoyah sih memang sudah pasti tak kelihatan. Untuk bisa melihatnya kan perlu bantuan mikroskop. Dia kan berukuran mini.”
Nasuti langsung kabur karena aku dan Igo kompak menimpukinya.
Aku tahu alasan Ruqoyah tidak ikut mengantar kami. Itu urusan antara aku dengannya. Top secret, masalah keluarga. Tak kusangka persoalan ini jadi rumit sejak kami ditawari tiket keliling Indonesia. Sebenarnya, tadi malam Ruqoyah mengirimiku sms:
Kak Lutfi, boleh minta tolong? Titip Kak Igo ya. Awasi dia, jangan sampai dia melakukan hal bodoh.
Itu saja pesannya, menggantung, tapi aku tahu pasti maksudnya. Sebenarnya, sudah lama adik sepupuku itu memendam perasaan ke Igo. Dia sering curhat lewat sms. Awalnya, kupikir itu tidak mungkin. Ruqoyah muslimah yang taat. Jarang sekali dia mau bicara dengan lawan jenis kecuali jika ada urusan yang superpenting. Rasanya mustahil dia terkena virus merah jambu. Tapi aku sadar bahwa dia juga wanita normal yang punya kecenderungan untuk itu. Begitu tahu bahwa pria idamannya adalah salah satu sahabatku, aku langsung menolak mentah-mentah. Bukan karena akhlak Igo jelek—aku tahu betul bagaimana tabiat teman karibku, tentu saja—tapi karena menurutku sifat mereka tidak cocok. Keduanya sama-sama cuek dan keras kepala, dan aku tak bisa membayangkan apa jadinya bila mereka tinggal satu rumah. Bakal banyak piring pecah, mungkin.
Ruqoyah, yang awalnya memintaku menjadi perantara, tentu saja kecewa. Dia jadi jutek dan dua hari tak mau bicara denganku. Dia bahkan mengadukan ini ke ayahnya, Paman Jali, yang sayangnya mendukung keinginan putrinya untuk segera menikah. Aku jadi serba salah, tergagap menjelaskan saat Paman mencoba membujukku. Aku tetap pada pendirianku, tak mau membantu. Gagal denganku, Paman pun menyerah. Tapi putrinya tidak selunak itu. Ia mencari perantara lain, bahkan ia coba meminta bantuan Ustad Faizar, pembimbing ruqyah kami. Tahu Ustad Faizar turun tangan, aku pun angkat tangan. Terserah gadis itu saja. Susah dibilangin, pikirku. Setelah itu, aku tak tahu lagi lanjutan ceritanya. Tapi melihat sikap Igo biasa-biasa saja, aku tahu Ustad Faizar belum mengajaknya bicara.
“Kau baik-baik saja, Kapten? Nggak ada yang ketinggalan?” Harto berseru. “Ayo, sebentar lagi pesawat lepas landas, kita berangkat, yoo!”
Kami bergerak maju. Di belakang, Renata mengikuti kami. Bahkan saat berbaris di pintu, kami masih melihat gadis itu berlari-lari di balik pembatas ruangan. Setelah menemukan kami, Renata meniup napasnya ke kaca, lalu mencoretkan jari di atas lapisan kabut yang dibuatnya, menulis: Cepat dibalas, ya. Kata-kata itu dibingkainya dengan coretan berbentuk hati. Harto mengangguk dan tersenyum padanya, mengabaikan ledekan kami.
Kami naik ke pesawat. Aku terus menatap Ibu dan Paman yang tampak kecil dari jendela pesawat. Mereka masih melambai. Di sebelah mereka, Dokter Isnain melambai pada Igo. Aku terus memandang jendela. Tak tega aku meninggalkan mereka. Kubalas lambaian mereka dengan mengangkat telapak tangan di kaca. Aku akan merindukan mereka.
Mesin menderu, pesawat mulai mengudara meninggalkan daratan. Tanah tampak semakin menjauh di bawah sana. Bandara Soekarno-Hatta tampak mengecil.
Aku meluruskan topi koboi warisan ayahku dan memakainya dengan gagah. Jaket almamater Unsoed aku ganti dengan jaket Rohis UKMI berwarna merah, dengan tulisan The Gate of Heaven, Freedom for Palestine di punggung. Jaket itu kusampirkan di bahu. Aku tersenyum, lalu berdiri dan berpaling menatap teman-temanku, sekelompok penjelajah nekat yang berambisi besar mengelilingi negeri. Para penjelajah muda, tim Penakluk Khatulistiwa dan tim Langlang Buana. Kuamati wajah-wajah yang berbinar ceria itu.
“Kalian siap untuk petualangan?” seruku.
“Siap, Kapteen!” sahut Harto. Yang lain mengangguk bersemangat.
“Ayo kita taklukkan khatulistiwa!” kataku lantang, dan mereka mengacungkan tinju seraya berseru, “Hidup Indonesia!”
Petualangan kami baru saja dimulai.
*****


 radenbumerang
radenbumerang







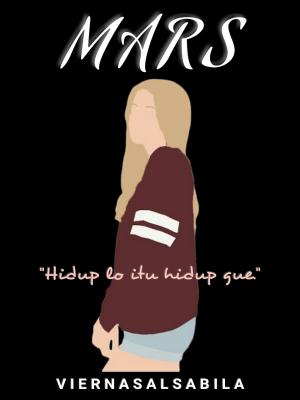

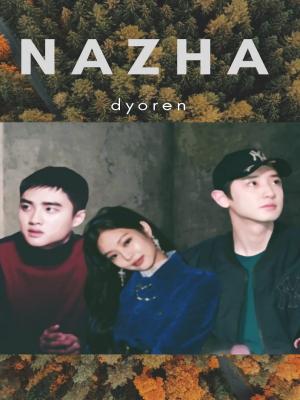
Iya juga yah, satu bab aja sepanjang ini... makasih masukannya Mas AlifAliss, mungkin ke depannya saya bagi per bab aja biar lebih pendek.