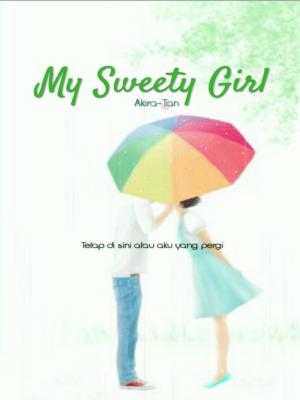Aku bertemu Mama yang sedang duduk diam di luar kamar rawat. Matanya menatap kosong. Wanita yang melahirkanku itu terlihat begitu tua. Rambut Mama nyaris putih seluruhnya, sangat berbeda dari terakhir kali bertemu.
"Assalamualaikum, Ma," sapaku pelan.
Mama mengangkat kepalanya, menatapku seolah tak percaya. Segera saja beliau berdiri dan menghambur memelukku. Aku balas memeluk tubuhnya yang ringkih. Mama menangis di dadaku.
"Adam, kemarin Papa pingsan di rumah," tangisnya.
Mama terus menangis sambil terbata-bata bercerita, kuusap punggung Mama, berharap bisa mengurangi kesedihan. Mataku mengabur, tak lama akupun menangis.
---
Papa sadar tak lama setelah itu, kondisinya sangat lemah. Saat melihatku, Papa mengulurkan tangan memintaku mendekat.
"Apa kabarmu, Dam?" Suara Papa begitu lemah.
Aku menjawab dengan anggukan, sambil menggenggam tangan kokohnya.
"Kamu sudah pulang, kan? Tidak pergi lagi?" Tanya Papa lagi.
Kepalaku mengangguk. Walau hatiku berontak, tapi tak mungkin aku berkata tidak untuk saat ini.
---
Setelah 3 hari dirawat, Papa dinyatakan sehat dan boleh pulang. Dokter mengingatkan agar Papa mengelola stres dengan baik. Jantung Papa bermasalah, tidak boleh terlalu lelah, jangan berpikir yang berat-berat.
Nisa bahagia sekali melihatku. Sang Kakak sudah kembali.
Namun kebahagiaaan kami tak berlangsung lama. Papa mulai mempertanyakan tentang rencana hidupku. Menikah salah satu topik utama pembicaraan di rumah ini.
Sekali dua kali, aku bisa menghindar. Lama-lama aku bosan. Hatiku tak tenang. Luka lama kenangan dengan Reina masih berdenyut perih setiap Papa menyinggung tentang kapan aku akan menikah.
Aku tahu, usiaku sudah 33 tahun. Usia yang sangat matang. Papa berkali-laki mengingatkan tentang usiaku. Tentang keinginannya menimang cucu. Tentang warisan.
Tutup kuping. Aku tak mau mendengarnya. Kembali ke Jakarta bukan pilihanku, hanya semata-mata karena aku menyayangi kedua orang tuaku.
Sampai suatu hari, Papa berkata dengan nada merendahkan, "Kau masih cinta pada janda itu, makanya susah untukmu membuka hati."
Sore itu juga, kutinggalkan rumah untuk kedua kalinya. Ternyata kembali ke Jakarta bukan ide yang baik.
---
Aku kembali ke Yogyakarta, menjalani hari dan rutinitasku lagi. Hari-hari yang damai, hidup semauku sendiri.
Pelanggan studio fotoku semakin banyak. Bahkan saat ini usahaku melebar, aku sering menjadi teman seperjalanan, semacam personal tour guide bagi para turis penggila fotografi. Para traveller berjiwa bebas. Lelah tapi mengasyikkan.
Beberapa dari traveller cewek mengakui terang-terangan jatuh hati padaku. Tua dan muda. Kadang ada yang tanpa malu menyentuhku, dengan cara yang membuat risih. Mungkin mereka pikir, aku ini lelaki kesepian. Saat itu terjadi, aku memilih tersenyum, lalu pergi.
Entah bagaimana, aku sama sekali tidak pernah merasa tertarik dengan wanita manapun. Terngiang kalimat Papa, "Kau masih cinta pada janda itu, makanya susah untukmu membuka hati." Mungkin hati kecilku mengakuinya.
Bagaimanapun, tak mungkin waktu kuputar kembali. Reina sudah bahagia dengan belahan jiwanya.
---
Sore yang cerah di Yogyakarta. Aku sedang hunting foto sambil menikmati keramahan Yogyakarta.
Hari ini ulang tahunku yang ke 34. Aku merayakannya sendirian dengan nongkrong di salah satu kafe kecil di sekitar Kampus UGM. Kafe Marcie. Croissant coklat dan milkshake stroberi di sini enak sekali.
Kukunyah croissant sambil menatap manusia lalu lalang di luar sana melalui jendela kafe. Mataku menangkap sosok yang sepertinya tidak asing. Mataku menyipit, berusaha melihat lebih jelas.
Tubuh mungil, mata bulat berbinar-binar, wajah putih bersemu merah, dan cara berjalan yang khas, cepat dan seolah melompat-lompat. Langkahnya seringan peri. Dia membawa ransel besar dan sebuah buku setebal kira-kira 5-6 cm di pelukannya.
Walau gaya pakaiannya lebih formal, dan model rambutnya berbeda, aku bisa langsung mengenalinya.
Dia Anaya.
Buru-buru kusembunyikan tubuhku di balik jendela, berusaha tidak terlihat. Aku sedang ingin menikmati waktu sendirian.
Tuhan rupanya sedang senang menggodaku.
Gadis itu berjalan memasuki kafe dengan bergegas, memilih meja di dekat pintu. Lalu dia duduk membelakangiku. Sekitar dua meter saja dari tempatku.
Kupandangi punggungnya, sambil berharap dia tidak menoleh. Kuambil kertas menu, lalu kuangkat menutupi wajah, pura-pura sibuk membaca menu. Tapi sesekali masih mengintip. Memastikan dia tidak mendadak berdiri dan datang padaku.
Anaya memesan secangkir teh hangat.
Terdengar suara berat seorang lelaki menyapanya, "Naya, sudah lama menunggu?"
Kunaikkan sedikit kepalaku, mengintip lewat kertas menu. Ingin tahu Anaya janjian dengan siapa di sini. Aku melihatnya, di depan Anaya, menghadap ke arahku.
Lelaki itu berusia kurang dari 30-an, tubuh tinggi, berkulit terang. Sosoknya mengingatkanku pada aktor sinetron di TV, dengan lekuk tubuh padat dan wajah yang sempurna. Dia tersenyum manis sambil mengucek rambut Anaya.
Matanya sekilas melirikku, sialnya aku terlambat menutupi wajah dengan kertas menu. Dia melihatku sekilas, lalu tatapannya kembali ke Anaya.
"Hei," sapa Anaya pendek. Tidak terdengar antusias.
"Bagaimana kuliahmu hari ini, Nay?" Tanya lelaki itu.
"Baik. Apa maumu?" Terdengar ketus suara Anaya. Seperti bukan dia. Aku jadi tertarik untuk menguping.
"Aku rindu," jawab lelaki itu dengan suara disyahdu-syahdukan.
"Apaan sih?" Ujar Anaya setengah membentak.
Lalu gadis mungil itu melanjutkan dengan nada kesal, "Tadi kamu bilang ada yang penting. Cepetan ngomong. Aku mau masuk kelas lagi!"
"Aku hanya rindu, Nay," jawab lelaki itu. Sungguh tidak kreatif.
"Kalau begitu, tidak ada yang penting. Aku pergi saja. Jangan ganggu aku lagi!" Katanya sambil berdiri.
Lelaki itu berdiri juga lalu tangannya memegangi lengan Anaya.
"Jangan pergi, Nay, maafkan aku. Gadis itu hanya teman biasa, hanya kamu yang kucinta," kata lelaki itu seolah mengiba. Tapi aku menangkap nada tidak tulus di sana.
"Teman biasa katamu? Teman biasa apa yang berciuman malam-malam di dalam kamar, ha? Teman biasa apa yang mengirimkan pesan sayang-sayang, ha?!" Anaya terdengar begitu marah.
Lelaki itu tersenyum. Nekat sekali. Aku ngeri membayangkan kepalanya digebuk dengan buku setebal itu.
"Naya, itu biasa di duniaku. Aku ini entertainer. Tapi aku tidak mencintainya. Aku hanya cinta padamu," rayu lelaki itu lagi.
"Dasar buaya! Brengsek! Pergi sana! Aku sudah bilang, kita putus!" Anaya benar-benar berteriak sekarang. Berpasang mata mulai menatap mereka.
"Putus katamu? Kamu berani mutusin aku?" Bentak lelaki itu.
"Ya! Putus!" balas Anaya tak kalah keras.
Lelaki itu tertawa mengejek, lalu dia menyentakkan tangan Anaya yang tadi dipegangnya.
"Cewek jelek macam kamu, mutusin aku?" teriaknya. Tak sopan.
Tangan Anaya cepat sekali bergerak. Dalam hitungan detik, sebagian wajah lelaki itu sudah basah terkena siraman teh hangat yang belum sempat diminum Anaya.
Dia terkesiap, matanya membesar. Ditatapnya sekeliling, mengusap wajahnya, lalu membentak Anaya dengan keras, "Dasar bego!" Setelah itu dia melangkah pergi dengan bersungut-sungut kasar.
Anaya masih berdiri, kulihat tangannya bergetar karena marah. Mungkin juga malu. Banyak mata memandangnya iba.
Aku bengong. Tak sadar tanganku menyenggol gelas milkshake yang terbuat dari kaca, jatuh ke lantai lalu pecah. Suaranya membuat Anaya refleks menoleh. Matanya memandangku dengan galak. Ada jejak air mata di sana. Segera dihapusnya dengan punggung tangan, lalu dia berderap menghampiriku.
"Apa liat-liat? Ada yang lucu?" bentaknya.
Aku belum sempat menjawab, dia sudah melangkah cepat keluar dari kafe. Lalu menghilang di sudut jalan.
Tinggallah aku duduk termangu di kursiku, dengan ceceran milkshake berwarna pink di lantai dekat kakiku. Beberapa pasang mata menatapku penuh tanya.
Apa salahku? Tak ada. Aku hanya sedang berada di tempat yang salah. Aku sedang sial.
Sambil menghela napas panjang, aku berdiri dan melangkah keluar dari sana. Me time yang kurencanakan buyar sudah.
Dalam perjalanan kembali ke studio, aku mengambil kesimpulan. Anaya adalah mahasiswa di Universitas Gajah Mada dan dia baru saja berantem lalu putus dengan pacarnya. Drama. Banyak drama. Macam kisah sinetron saja.
---
Keesokan harinya, aku sudah nyaris melupakan adegan itu. Tiba-tiba gadis itu muncul lagi di hadapanku.
"Hei!" Panggilnya dengan suara lantang.
Aku yang sedang memilah foto di layar komputer, sontak menoleh.
Anaya dengan balutan jins belel dan kaos abu-abu yang juga sama belelnya. Rambutnya yang sudah mulai panjang dikuncir satu di atas tengkuk. Tas kamera terselempang melintang di tubuhnya.
"Sedang apa kau di sana kemarin?" Tanyanya tanpa tedeng aling-aling.
"Di Kafe Marcie?" Tanyaku.
"Iya!" Jawabnya cepat.
"Makan," ujarku ringan.
"Jauh-jauh makan di dekat kampusku?" Cecarnya lagi.
"Aku tidak tahu itu kampusmu."
Mulutnya mengerucut. Mata bulatnya menatapku tajam.
Lalu mimik wajahnya berubah agak lunak. Dia ngeloyor lalu duduk seenaknya di kursi sebelahku.
"Aku benci laki-laki macam dia," ucapnya tiba-tiba. Matanya memelototi layar komputerku.
Kuteruskan pekerjaanku memilah foto. Sama sekali tidak tertarik dengan kisah cintanya.
"Dia dulu baik. Saat sudah jadi artis, kelakuannya jadi brengsek," katanya lagi. Matanya sekarang jelalatan melihat sekeliling.
Aku masih memilih diam. Pekerjaanku lebih penting.
"Bisa-bisanya dia bawa cewek ke apartemen lalu hehah-heheh di sana. Dasar bodoh! Aku kan juga punya kunci apartemen itu!" Nadanya semakin berapi-api.
Dan aku semakin tidak ingin mendengarnya. Aku benci drama.
"Pake ngatain aku jelek, lagi!" Katanya sambil mendengus kesal.
Aku tak bisa menahan senyum. Dia menyadarinya.
"Kenapa kamu senyum?" tanyanya galak.
Aku menggeleng, buru-buru kukulum senyum itu. Ngeri melihat tatapannya yang menusuk.
"Mana kamera Canon yang waktu itu? Aku mau pinjam!" Ujarnya tiba-tiba.
Aku buru-buru berkata, "Tidak boleh."
"Pelit," celetuknya. Lalu gadis itu bergegas pergi. Rambut ekor kudanya melambai mengikuti kecepatan langkahnya.
Aku menggelengkan kepala. Gadis yang sangat aneh
---
Hari-hari berikutnya, Anaya sering muncul di studioku. Ternyata dia tinggal di sekitar situ juga, menumpang di rumah tantenya.
Sepulang kuliah, biasanya dia mampir ke tempatku. Kami sering mengobrol, topiknya sangat random. Mulai dari tempat makan yang enak, kamera, tempat hunting foto yang asik, hingga masalah kuliahnya.
Suatu hari, setelah percakapan yang entah sudah keberapa kali, aku baru tahu kalau Anaya sudah berusia 25 tahun. Dan dia saat ini sedang kuliah S2 di jurusan Manajemen.
"25 tahun?" Ulangku.
"Iya, kenapa?" Tanyanya dengan nada menantang.
"Kupikir usiamu belum 20," jawabku.
Dia tertawa, gigi kelincinya nampak jelas, "Wajahku inosen ya?" Tanyanya masih sambil tertawa.
"Iya, polos. Padahal hobinya nyiram muka orang pake teh panas," sindirku.
Dia tertawa tergelak-gelak.
Aku tersenyum tipis.
-----
Sore itu, sepulang kuliah Anaya datang lagi, di tangannya ada jinjingan plastik kresek berisi entah apa.
"Nih," katanya sekonyong-konyong sambil menyodorkan plastik kresek.
"Apaan ini?" Tanyaku. Aku menerima pemberiannya dengan waspada.
Gadis ini usil, isi plastik kresek itu bisa apa saja.
Kau tahu, dia pernah memberiku seekor anak kucing yang masih merah. Dia memungut kucing itu dari jalanan, lalu menaruhnya di dalam kotak kardus bergambar makanan. Saat itu aku masih lugu, kupikir dia berbaik hati membawakan makanan betulan. Jantungku nyaris copot, saat kubuka kotak itu dan isinya bisa mengeong!
Sejak saat itu aku sangat berhati-hati pada setiap pemberian Anaya.
Dia menyeringai, "Nasi goreng spesial kesukaanmu, dari Marcie." Tatapannya menggoda.
Aku tersipu. Ah, Marcie. Gadis blasteran Jawa - Perancis pemilik kafe di dekat UGM itu akhir-akhir ini sedang sering mengirimkan makanan untukku.
"Jah! Malu-malu. Nggak pantes!" ujar Anaya sambil tertawa ngakak.
Aku membuka bungkusan titipan Marcie, lalu mulai menikmatinya. Sementara Anaya ngeloyor melewatiku, dan langsung duduk di depan komputer.
"Dam, menurutmu Marcie gimana?" katanya memulai percakapan, yang aku tahu akan kemana arahnya. Akhir-akhir ini Anaya sering mengomporiku untuk mendekati Marcie. Katanya dia bosan melihatku jomblo terus.
Sambil mengangkat bahu, aku terus menyendokkan nasi goreng ke mulutku. Aku menunggu gadis itu meneruskan usahanya.
Dia melanjutkan, "Setiap kali aku mampir makan di sana, Marcie selalu bertanya 'How's Adam?'. Biasanya kujawab 'Adam is still alive'. Gitu."
Aku menjawab, "Betul itu. I'm alive."
"Lalu Marcie ketawa, dan menitipkan makanan lagi untukmu. Tapi makananku tetap kena charge," gerutunya.
Aku senyum-senyum geli.
"Dia titip salam, lalu minta aku mengingatkanmu agar kesana lagi," ujar Anaya lagi. Matanya mengamati reaksiku.
"Iya, nanti," jawabku, sambil membersihkan sisa makanan yang sudah ludes.
"Kalau kamu ketemu dia, bilang aku nagih ongkos kirim salam. Paling tidak, free lunch buatku. Ya? Ya?" cerocosnya serius.
Aku nyaris tak mampu menahan tawa. Anaya kocak!
Seekor anak kucing berwarna hitam mengggesek-gesekkan badannya ke kakiku. Si Cumi, kucing yang dulu dipungut Anaya saat masih merah dan diterlantarkan induknya, sekarang sudah besar dan sehat. Makhluk itu menjadi peliharaanku, semacam penjaga ruangan di malam hari.
Anaya mengangkatnya dari lantai, langsung didudukkan di pangkuan sambil mengacak-ngacak muka kucing malang itu. Cumi diam saja, dia sudah tahu tabiat Anaya.
"Jadi, kapan ke Marcie lagi?" tagihnya. Gadis yang pantang menyerah.
Aku meliriknya, lalu berkata, "Ayo, sekarang. Mumpung udah sepi."
Anaya melonjak girang, lalu diangkatnya si Cumi mendekati wajah.
"Ha! Cumi, bentar lagi kamu punya ibu baru, and free food forever!" katanya sambil menyeringai lebar.
Aku melengos. Lebay!
---
Tiba di Kafe Marcie, Anaya langsung turun dari boncengan motorku. Sambil berlari kecil, dia membuka pintu kaca kafe, lalu berkata keras, "Marcie, aku bawa Adam!"
Bawa-Adam. Seolah aku ini kucing kecil yang dipungutnya di jalanan. Kulepas helm dan merapikan rambut sekenanya. Menatap bayanganku sekilas di kaca mobil sebelah. Rambutku sudah mulai gondrong. Rambut halus juga memenuhi atas bibir dan daguku. Sudah berapa lama aku tidak bercukur? Ah, peduli amat.
Lalu aku melangkah pelan memasuki kafe. Marcie sudah menungguku di sana. Meja paling ujung yang menempel ke jendela. Spot favoritku setiap kesitu. Entah kenapa, meja itu selalu kosong setiap aku datang.
Marcie hari itu cantik seperti biasanya. Tubuh langsingnya berbalut gaun simpel dan feminin berbelahan dada rendah, warna biru muda. Mata abu-abu gelap itu menatapku senang.
"Hai, Adam," sapanya lembut. Suara Marcie manis mendayu.
Lalu dia menghampiri dan langsung mengecup pipi kiriku. Wajahku memanas, dan aku berusaha tersenyum seganteng mungkin.
Sepertinya usahaku terlihat ganteng, kurang berhasil. Kulirik Anaya yang berdiri di samping Marcie. Mulut gadis itu tertutup rapat tapi pipinya menggembung, menahan tawa di dalam sana. Mata bulatnya bersinar seolah berkata, "Hoi, jelek hoi, jangan senyum!"
Aku berhenti senyum, lalu duduk di kursi yang disediakan Marcie. Anaya juga langsung duduk di hadapanku tanpa meminta ijin. Tak sopan.
Marcie masih tersenyum menatapku, sorot matanya mendamba. Dia duduk di sampingku, sebelah tangannya diletakkan di atas pahaku.
"Kamu mau pesan apa, Adam?" Suaranya rendah, menggoda.
"Minum saja," jawabku.
Anaya menyambar, "Dia sudah makan nasi goreng titipanmu tadi. Aku yang belum makan. Boleh pesan mie jawa?"
Aku mendengus. Sungguh, gadis yang tak tahu malu.
Marcie melirik Anaya sebentar, lalu kembali mata kelabunya menatapku.
"Are you sure? Hanya minum?" Dia tersenyum menggoda. Tubuhnya mendekat padaku.
Tenggorokanku mendadak kering, tubuh terasa hangat. Darah seolah naik ke atas, membuat wajahku memanas.
"Iya," jawabku lalu menggeser tubuh menjauh darinya.
Anaya terlihat menikmati pemandangan di depannya dengan mata bulat yang bersinar jahil. Senyumnya melebar.
"Tidak, Adam ingin makan croissant coklat. Dua croissant coklat yang besar," ujar Anaya dengan mata berkilat-kilat.
Marcie tersenyum manis, lalu beranjak dari sampingku.
"Oui," katanya sambil mengerlingku.
Aku memandang Marcie sampai dia menghilang di balik pintu. Terdengar perintah kepada asistennya agar menyiapkan makanan dan minuman sesuai permintaan Anaya.
"Hoi, awas lehermu terkilir," celetuk Anaya.
Aku meliriknya dengan tatapan "kau-sungguh-tidak-sopan". Gadis itu nampaknya tidak peduli.
Dia malah melanjutkan, "Cantik ya, Marcie itu? Seksiiiiiihh ..." Kedua alisnya turun naik menggodaku. Kedua mata bulatnya berbinar, senyum gigi kelinci muncul menghiasi wajahnya.
Aku menjawab pendek, "Yap." Lalu membuang pandangan keluar jendela.
Sejak menjadi saksi putusnya hubungan Anaya dan lelaki entah siapa namanya itu, aku memang jadi sering ke kafe ini. Kadang memang ingin makan, seringnya hanya membutuhkan suasana tenang diiringi musik lembut.
Rupanya Marcie memperhatikanku, seringkali dia mengantar sendiri makanan dan minuman pesananku. Padahal dia owner kafe. Normalnya waiter yang bertugas mengantarkan makanan.
Aku bukannya tidak bisa membaca ketertarikannya padaku. Aku paham, tapi tidak pernah berniat memberi kesempatan Marcie lebih dekat lagi. Aku hanya menyukai suasana kafenya, Marcie itu bonus.
Lelaki mana yang tidak suka didekati wanita secantik dan seseksi itu? Aku ini lelaki normal. Aku senang dengan pemandangan indah. Tapi hanya itu. Tidak lebih. Maka saat Anaya mulai ribut mengomporiku agar mendekati Marcie, aku tidak tertarik sama sekali.
Kedua alis Anaya masih turun naik, wajahnya mendekatiku.
"Ngelamun jorok, pasti," celetuknya.
Kertas menu yang cukup tebal kugetokkan pelan ke kepalanya.
Gadis itu tertawa tergelak-gelak.
---
Anaya punya pacar baru. Kali ini teman sekelasnya.
Lelaki itu bernama Tara. Beberapa kali Anaya mengajaknya ke studio fotoku. Dari gayanya, Tara itu anak baik-baik yang kutu buku. Aku menyukainya. Dia cocok dengan Anaya yang pecicilan.
Suatu hari, Tara ke studioku, tanpa Anaya.
"Mas Adam, berminat motret model majalah, ngga?" tanyanya dengan logat Jawa yang kental.
Aku mengerenyitkan dahi.
"Aku sudah sering, kok, motoin model," jawabku.
"Bukan model seperti itu, Mas," katanya dengan mata berkilat aneh.
Aku menunggu.
"Model majalah dewasa. Nude," bisiknya.
"Aku punya banyak stok teman model begituan. Ada beberapa yang minta khusus difoto sama Mas Adam. Katanya hasil foto Mas Adam keren, kalo ngirim ke biro modelling atau majalah dewasa, mereka yakin akan keterima," jelasnya panjang lebar.
"Dan, biasanya mereka bisa dipake juga, Mas," katanya lagi, masih pelan. Seringainya membuatku jijik.
Bocah setan, gerutuku dalam hati.
Aku menggeleng, lalu mengusirnya secara halus.
Esoknya, aku bilang pada Anaya tentang ide gila pacarnya. Mata gadis itu membeliak lebar mendengarnya. Lalu dengan langkah cepat, dia keluar dari studioku.
Dia kembali lagi malam hari, dengan ekspresi siap membunuh.
"Dasar lelaki mesum!" ujarnya.
Aku menoleh, memperhatikan. Tak ada jejak air mata di wajahnya. Hanya kemarahan.
"Kamu apain si Tara?" tanyaku.
Gadis itu menunjukkan foto di layar HPnya. Foto sebuah mobil sedan hitam, tulisan "MESUM" dengan cat berwarna merah terang memenuhi seluruh body mobil itu.
Baru kali ini aku tertawa sekeras itu.
Anaya menatapku dengan kening berkerut, lalu dia ikut tertawa keras.
---
Kuakui, hidup menjadi lebih seru sejak ada Anaya. Dia mewarnai hari-hariku seperti cat piloks merah yang menghiasi mobil hitam Tara. Terang benderang.
Berikutnya dia menjadi asistenku di studio. Pekerjaannya serabutan. Mulai dari memback-up orderan foto, editing, hingga menyiapkan makanan untukku dan si Cumi. Dia gadis yang sangat bersemangat. Aku beruntung karena bayarannya cukup murah.
Anaya menyenangkan sebagai teman diskusi. Kami punya banyak kesamaan, mulai dari hobi, makanan kesukaan, penilaian atas bagus tidaknya sebuah foto, nilai-nilai yang dianut, hingga rasa cinta pada si Cumi.
Kami pernah bertengkar gara-gara memperebutkan hak asuh si Cumi saat masing-masing dari kami menikah nanti.
Saat itu dia berkata, "Siapapun yang menikah duluan, berhak mengasuh kucing ini."
Aku setuju.
Lalu dia melanjutkan, "Kalau begitu, sudah pasti aku yang menang."
"Kok bisa?" protesku.
"Karena kamu ngga suka perempuan. Jangan-jangan kamu homo!" katanya sambil tertawa berderai-derai.
Sebuah bantal kursi melayang lalu mendarat tepat di wajahnya. Aku yang melempar.
Dia tertawa semakin keras.
---
Pagi menjelang siang, aku sedang mengerjakan project foto prewedding salah satu pelanggan.
HP berdering. Nama Nata muncul di sana.
"Halo, pa kabar, Ta?" tanyaku riang.
Hening sejenak. Lalu terdengar suara Nata berkata pelan namun sangat jelas di telingaku.
"Bro, Reina semalam dilamar Fahri. Dan dia bilang mau."
Napasku tercekat. Tubuhku terasa limbung. "Reina," bisikku.
"Keluarga Reina lagi mau nentuin tanggal dulu," lanjut Nata.
Aku masih diam, gemuruh di dadaku bertambah keras.
"Dam," kata Nata memecah keheningan.
"Ya, gue dengerin," jawabku.
"Segitu dulu infonya, nanti gue kabarin lagi," ucapnya, lalu memutuskan pembicaraan.
Kuremas rambut kuat-kuat, berharap sakit kepala yang mendadak muncul bisa sedikit berkurang.
Ada luka yang terbuka kembali, walau tidak seperih dulu.
----
"Adaaaaammmm...!" Suara cempreng itu membangunkanku pagi ini.
Kubuka mata, Anaya sudah berdiri di samping tempat tidurku. Aku sontak bergerak duduk.
"Jam berapa ini?" tanyaku, disorientasi.
"Jam 8 pagi," jawabnya.
Lalu dia melanjutkan, "Aku mampir sebelum berangkat kuliah, soalnya semalaman WA kamu dan tidak dijawab."
"Nyampe sini, studio belum buka. Lampu teras masih nyala, si Cumi ngeong-ngeong di depan pintu. Aku pikir kamu mati," katanya.
Mata bulatnya menatapku lekat, menganalisa.
Aku mengusap wajah, lalu menunduk.
"Ngga kok, aku belum mati," jawabku sekenanya.
Tangan mungilnya ditempelkan ke dahiku, terasa dingin. Sejuk. Entah mengapa, menenangkan.
Dia menarik tangannya, lalu membungkuk hingga matanya sejajar dengan mataku.
"Are you okay?" tanyanya.
Aku menggeleng. Kepalaku masih terasa berat.
Anaya meletakkan tas ransel besarnya, lalu bergegas keluar. Tak lama dia kembali dengan secangkir teh hangat dan dua potong roti di tangannya.
"Sarapan dulu," perintahnya.
Kuraih cangkir dari tangannya, dan menyesap teh hijau buatan Anaya. Hangat menjalari tubuhku. Saat aku mengunyah roti isi selai kacang pemberiannya, Anaya mengamatiku terus. Mata bulatnya menatap penuh kekhawatiran.
Selesai makan, aku beranjak keluar kamar. Berharap udara pagi Yogyakarta bisa menolong. Anaya mengikuti dari belakang.
Kami berdua tidak membuka studio hari itu. Anaya juga memutuskan tidak masuk kuliah.
Aku duduk di teras depan, menikmati pemandangan manusia lalu lalang. Anaya duduk di kursi sebelahku sambil menggendong si kucing hitam.
"Cerita," ujarnya bernada perintah.
Aku menoleh sekilas ke arahnya, mata bulat itu memandangku. Dia menunggu.
Kuputuskan, Anaya bisa dipercaya. Dia sahabatku sekarang.
Sudah saatnya menceritakan kisah tentang Reina, wanita biasa bermata indah yang telah membuat hatiku tercabik.
Cerita tentang aku dan Reina mengalir begitu saja dari bibirku, seolah bosan karena sudah begitu lama terpendam, dan kini kisah itu memaksa untuk diceritakan.
Anaya menyimak dengan diam. Sesekali mengangguk, terperangah, lalu mengangguk lagi. Sementara jemarinya terus mengusap kepala si Cumi. Kucing hitam itu tertidur di pangkuannya.
Setelah semuanya sudah kuceritakan, hatiku terasa lebih ringan. Seolah ada beban berat yang terangkat dari sana.
Anaya menatapku dengan mata bulatnya yang semakin membulat.
"Wow," desahnya pelan.
"Wow," ulangku. Aku berusaha tersenyum.
"Pantas kamu selalu terlihat murung. Sejak awal mengenalmu, hampir 3 tahun ini, hanya 2 kali aku melihatmu tertawa," ujarnya.
Aku tersenyum tipis, lalu membuang pandangan jauh ke depan.
"Kenapa tidak diperjuangkan?" tanya Anaya seperti berbicara pada dirinya sendiri.
"Karena kadang kita harus tau batas, Nay. Tidak semua hal yang diinginkan, harus diperjuangkan."
"Saat sudah berusaha keras, namun tetap tidak mendapatkan yang kita inginkan, harus mulai berpikir, mungkin itu cara Tuhan mengajari kita tentang pasrah."
"Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan," kataku lagi.
"Aku menginginkan Reina, tapi kusadari, aku tidak membutuhkan dia, lebih dari Fahri. Lelaki itu jauh lebih mencintai dan membutuhkan Reina. Begitupun dengan Reina." Aku tersenyum saat mengatakannya.
Lagi-lagi terasa sebuah beban terangkat dari dadaku.
"Karena cinta bukan hanya sekedar rasa," ujar Anaya pelan.
"Ya, karena cinta bukan hanya sekedar rasa," ulangku.
Kami berdua bertatapan sekilas, lalu senyum gigi kelincinya mengembang.
Gadis itu berdiri, lalu meraih tanganku dan menariknya.
"Ayo kita pergi. Kau perlu dihibur," ujarnya ceria. Aku tersenyum, lalu bangkit mengikutinya.
---
Aku memilih ke pantai.
Sejak dulu aku menyukai laut dan pantai. Udara asin, hembusan angin, debur ombak, dan keheningan pantai di waktu malam.
Kami berdua menyusuri seluruh pantai di sepanjang daerah Gunung Kidul. Mulai dari Pantai Sundak, Sanglen, Watu Kodok, Kukup, Baron, hingga Pantai Indrayanti yang menawarkan pemandangan indah dan pasir putih kecoklatan yang terhampar di sepanjang pesisir pantai.
Anaya dan aku memotret banyak sekali pemandangan dan kegiatan manusia di lokasi-lokasi itu. Pantai sepi pada hari-hari biasa.
Kami berhenti di Pantai Indrayanti. Pantai dengan pasir putih dan karang-karang menghampar, begitu memanjakan mata. Aku duduk di pasir pantai sambil menatap jauh ke cakrawala. Menikmati hembusan angin laut meniup rambutku. Debur ombak yang berkejaran selalu membuatku merasa tenang.
Anaya menyusul duduk di sebelahku. Wajah putihnya bersemu merah karena panas matahari. Rambutnya dikuncir satu di atas tengkuk.
Kami duduk bersisian dalam diam.
"Aku juga punya cerita tentang hidup," katanya tiba-tiba.
Aku menoleh ke arahnya sekilas, lalu menunggu dia bercerita.
"Aku anak tunggal. Papa meninggal sejak usiaku 8 tahun. Dua tahun kemudian, Mamaku menikah lagi dengan teman sekerjanya," Anaya memulai kisahnya.
"Dulu kami juga tinggal di Jakarta, Casagoya di daerah Slipi. Saat Mama menikah lagi, dia membawaku pindah ke rumah suaminya di Depok."
Aku mengangguk. Aku ingat Casagoya, waktu itu aku menumpang taksi bersama Anaya di pagi buta.
Dia melanjutkan, "Rumah Casagoya dibiarkan kosong, dijualpun belum ada yang membeli. Kata Mama, rumah itu diwariskan Papa untukku."
"Suami Mama duda beranak 1. Anaknya perempuan juga, usianya dua tahun di atasku. Namanya Kak Iffa. Aku menyayanginya seperti kakak kandungku sendiri."
Anaya menarik napas panjang, lalu melanjutkan.
"Papa tiriku baik. Terlalu baik. Dia sering menyentuh tubuhku di tempat-tempat tertentu," katanya sambil tersenyum pahit.
"Saat itu aku belum mengerti apa-apa. Hingga suatu malam, Papa masuk ke kamarku dan memaksa membuka seluruh pakaianku. Saat itu usiaku baru 13 tahun"
"Aku menolak, lalu memberontak. Aku berhasil lari keluar kamar dan bersembunyi di kamar Kak Iffa. Saat itu Mama tidak di rumah, sedang ada tugas keluar kota."
"Syukurlah saat itu Papa tidak mengejarku ke dalam kamar Kak Iffa. Malam itu kuceritakan semuanya pada Kak Iffa, dia memelukku erat," suara Anaya terdengar pecah.
"Keesokan harinya aku kabur dari rumah, menginap di rumah salah satu guruku. Kuceritakan semua kepada bu guru, yang lalu melaporkan kasus itu ke polisi."
"Papa dijebloskan ke penjara. Mamaku menceraikannya. Tak lama setelahnya, Kak Iffa bunuh diri. Dia menulis surat permohonan maaf padaku, katanya tak sanggup menanggung malu."
Anaya mengusap bulir bening di sudut matanya. Aku masih belum mampu berkata apa-apa.
"Setelah kejadian itu, aku kembali tinggal bersama Mama di rumah Casagoya. Mama berubah. Mama lebih pendiam dan menjadi mudah marah. Setiap aku dianggap melakukan kesalahan, Mama akan memukul dan menjambak rambutku. Katanya aku pembawa sial."
"Hingga suatu hari, Mama mengamuk lagi. Tetangga berdatangan dan menemukanku duduk terpojok di sudut ruangan, Mama berdiri di depanku dengan pisau terhunus. Mama nyaris membunuhku saat itu. Untung saja para tetangga datang menyelamatkanku. Saat dipegangi oleh para tetangga, Mama masih berteriak-teriak."
Anaya mengusap air matanya lagi, menarik napas lalu melanjutkan bercerita.
"Mama didiagnosa depresi, dan dirawat di rumah sakit jiwa. Aku menengoknya sebulan sekali."
"Waktu kita ketemu di kereta, pas pulang ke Jakarta, kamu ingat? Itu pas jadwal nengok Mama," lanjutnya sambil menoleh padaku.
Aku menatapnya, tak mampu berkata-kata. Gadis ini, yang setiap saat terlihat ceria seolah tanpa beban, yang selalu berusaha menghiburku, ternyata hidupnya begitu tragis.
Ada rasa geram membayangkan dulu ada orang dewasa menyentuh tubuhnya dengan tidak senonoh. Dia menjalani hidup apa adanya, seolah tanpa beban. Sementara orang tua satu-satunya dirawat di RSJ. Gadis ini sungguh kuat di balik sosoknya yang mungil.
"Lalu bagaimana ceritanya, kamu bisa sampai di Yogya?" tanyaku. Suaraku tertahan, rasanya ada yang mengganjal di tenggorokan.
"Saat lulus S1, aku mendapatkan beasiswa untuk lanjut ke S2 di UGM. Keluarga almarhum Papa mendesakku agar mengambil kesempatan itu. Adik Papa kebetulan ada yang tinggal di sini."
"Mama terpaksa kutinggalkan di Jakarta, Dam," katanya pelan, nyaris berbisik.
Aku mengangguk, lalu tanpa bisa kutahan, tanganku mengelus punggungnya. Berharap itu bisa mengurangi kesedihan.
Anaya menarik napas panjang, lalu memaksakan senyum. Gigi kelincinya muncul, dan langsung mengubah wajah sedihnya menjadi ceria kembali.
"Tapi sekarang, aku sudah baik-baik saja! Hidupku tenang dan bahagia!" katanya keras-keras. Berteriak ke arah ombak, seolah ingin menantangnya.
Aku tersenyum lagi.
Kau tahu, ada manusia yang bisa begitu hebat menyembunyikan masalahnya. Dia memilih menerima jalan nasib, tidak berkeluh kesah atau terpuruk dalam kesedihan. Malah bersikap bahagia, dan menularkan kebahagiaan kepada orang sekitarnya.
Anaya adalah manusia jenis itu.
---
Sudah malam saat kami tiba kembali di Kota Yogyakarta. Aku mengantarkan Anaya pulang, berkenalan dengan om-tantenya, lalu pamit kembali ke studioku.
Hatiku sungguh terasa lebih ringan. Mungkin benar bahwa saat bersedih, jangan menutup diri. Justru kau harus lebih banyak berteman, mendengarkan kisah hidup orang lain. Saat itulah akan terasa betapa hidupmu tidak seberat yang kau bayangkan. Masih banyak orang lain yang mengalami hal lebih buruk dalam hidup, dan mereka baik-baik saja.
Anaya telah membuka pikiran dan hatiku, bahkan tanpa dia sadari.


 Dewind
Dewind