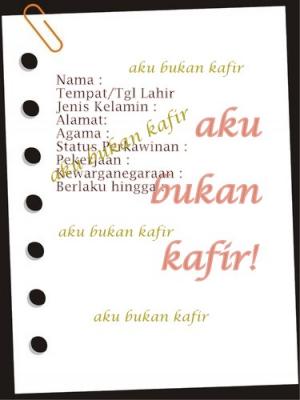Ular dan Kulitnya
Guru BK mengangguk, lalu berkata: silahkan. Dia tidak bertanya: Yana yang mana? Yana siapa? Hal ini kuartikan bahwa hanya ada satu Yana di sekolah ini. Polyana.
Terlebih lagi, dia tidak bertanya lebih jauh tentangku. Setelah mendengar nama Yana, dia seakan tidak mau tahu dengan diriku. Kecurigaannya telah menguap entah ke mana. Kini, yang ada di wajahnya adalah paras yang menuntut diriku untuk segera masuk ke dalam inti kedatanganku ke sana.
“Mungkin saya harus memperkenalkan diri lagi? Jika ibu tidak yakin, ibu juga bisa memeriksa buku alumni. Nama saya ada di sana.”
Tidak sedikit pun ia tergerak. Matanya tidak menertawaiku, tidak memicing sinis. Tidak ada rona malas mendengar cerita dari seseorang yang sekonyong-konyong datang mengetuk pintu tanpa membuat janji lebih dahulu. Aku bukan lagi murid di sekolah ini. Apa yang kulakukan saat ini pun tidak melalui izin siapa pun. Aku mengaku pada satpam bahwa sudah membuat janji dan sudah ditunggu, padahal tidak. Begitu masuk, aku tidak langsung menuju ruang ini, melainkan bertengger di pinggir lapangan, terhuyung tak jelas. Aku beruntung satpam itu tidak menaruh kecurigaan apa pun.
“Saya tahu ini terdengar aneh, tapi saya ingin mengaku,” kataku. Maka berkatalah Guru BK itu, dengan suara yang menggetarkan dinding yang melingkupi ruangan. “Cukup,” katanya. “Aku sama sekali tidak mau tahu tentang dirimu.”
“Tapi apakah ibu tidak menaruh curiga pada saya?”
Haruskah kukatakan pula bahwa untuk masuk ke sini pun aku telah menipu satpam sekolah.
“Apakah semua itu penting?” Ia bertanya.
Yang mana? Pikirku. Bagian mana yang ia pertanyakan: ceritaku tentang Yana, atau diriku. Segera kuasumsikan saja pertanyaan itu merujuk pada diriku.
“Saya bukan siswa yang mudah bergaul ketika sekolah di sini,” ungkapku.
“Saya tidak perlu tahu,” pungkasnya.
Separuh wajahnya tertutup bayang-bayang, aku segera menundukkan kepala. Yang kurasakan saat ini adalah rasa takut luar biasa. Takut pada Guru BK ini? mungkin tidak. Dia hanyalah perempuan tua yang sedang menunggu giliran untuk pensiun. Setiap kerut di sudut matanya telah menunjukkan bahwa dia sudah cukup lelah dengan remeh temeh kenakalan para siswa yang harus ia hadapi bertahun-tahun. Setiap helai ubannya berkata bahwa waktunya akan semakin dekat, dan ia sudah tidak sabar untuk duduk santai menikmati matahari pagi tanpa perlu berurusan dengan aduan ini itu. Begitulah kesan yang kubuat-buat untuk setiap guru tua. Satu petunjuk umum yang mempersatukan mereka: keletihan, keengganan untuk menyikapi segala permasalah dengan serius, dan anggapan bahwa semua masalah yang dimiliki para murid tak lebih dari kekonyolan masa muda mereka, yang lambat laun akan mereka sadari sendiri. Dengan wujud yang lemah seperti itu, tentu aku sama sekali tidak merasa takut padanya. Ketakutanku bersumber dan tearah pada diriku sendiri.
“Kalau begitu, jika saya katakan bahwa saat ini saya sedang dilanda ketakutan yang tak bisa lagi saya bendung, apakah ibu juga sama sekali tidak peduli?”
Dia diam, lalu aku melanjutkan. “Cerita yang akan saya beri bukan cerita yang bisa dimengerti oleh orang selain selain ibu. Setelah semua saya beberkan, saya sudah siap dituduh bahwa saya tidak lain hanya seseorang yang dihantui rasa bersalah atas hilangnya Yana. Silahkan. Saya sudah siap. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan, Bu. Saya ingin ibu tidak sedikit pun mengabaikan saya. Karena jika ingin tahu tentang Yana, ibu juga harus tahu tentang saya. Sebab saya dan Yana, pada waktu itu, seperti ular dan kulitnya.”
Perumpaan seperti ular dan kulitnya, tentang Yana dan diriku, datang begitu saja. sebelumnya, aku tidak pernah menggambarkan bahwa kedekatan kami seperti itu. Setelah menyelesaikan kalimatku pun, Guru BK itu masih mematung.
Aku memulai cerita.
*
Yana dan aku bertemu di satu sore yang sepi, di pinggir lapangan voli. Saat itu aku sedang bertengkar dengan ibuku, jadi kuputuskan untuk tinggal lebih lama di sekolah, menunda pulang ke rumah. Yana sedang menunggu ayahnya menjemput.
Tidak ada kata-kata dan tatap yang kami pertukarkan. Tidak ada firasat apa pun sebelumnya, bahwa dua orang akan bertemu di satu sore di pinggir lapangan hanya untuk berpisah dengan cara yang sangat tidak wajar.
Begitu mobil ayahnya tiba di seberang pagar, dia bangkit dari duduknya dan berlari.
Keesokan harinya, kutemukan satu sobekan kertas di laci. Tidak ada kata-kata yang tertulis, hanya tiga baris yang terdiri dari rangkaian titik dan garis. Kubaca dengan teliti.
Prpus
Istrht
Yana
Sejak hari itu, komunikasiku dengan Yana adalah melalui sandi morse. Aku sama sekali tidak mengetahui, bahwa ketika dia berada di sampingku sore itu, dia tidak hanya sekadar berdiri dan menunggu. Dia mempelajariku. Dan setelah jauh berkenalan dengannya kelak, aku akan tahu bahwa dalam diamnya, Yana mempelajari semuanya.
Kuturuti instruksi yang ia berikan. Saat istirahat tiba, aku pergi ke perpustakaan, dan melihat Polyana telah lebih dulu hadir, sendirian. Dalam ruang yang kental dengan aroma buku-buku tua, aku merasa sedikit sesak. Udara di dalam perpustakaan sama sekali berbeda dengan di luarnya. Sampai saat ini aku masih ingat bagaimana aku harus menahan batuk sejak memasuki ruangan hingga duduk bersebelahan dengan Yana.
Yana tidak memperkenalkan diri lebih lanjut, pun ia tidak menanyakan namaku. Saat itu aku hendak bertanya dari mana ia tahu kelasku, tapi pertanyaan itu terus kusimpan di dalam dada, seperti kelak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain yang kubiarkan teronggok begitu saja.


 chaeru
chaeru