Hari datang silih berganti,
Tapi luka seakan tiada henti.
Meratapi hari seorang diri,
Rasa hati ditikam belati.
Kemana harus berlari?
Mencari tempat tuk menghibur diri.
Langit sudah merona,
Tapi hati masih merana.
Bertahan karena satu asa,
Meski nyaris membunuh raga.
Kemana harus meminta?
Senyum dan tawa,
Yang seakan sudah ku lupa.
Manatap langit malam seorang diri di depan rumah mungilnya. Bintang-bintang di langit sana berkelip indah seakan seperti mata seseorang yang berkedip-kedip. Dia abaikan angin malam yang memeluk dirinya sangat erat. Deru suaranya terdengar ketika bergesekan dengan ranting dan daun-daun.
Reina meletakan buku hariannya di sampingnya dengan pena berada di atas buku tersebut. Kembali membayangkan senyuman Aresh yang selalu mengembang sempurna, mengajarkannya untuk tetap kuat.
“Tersenyum saat terluka atau tersakiti itu bukan artinya fake smile. Menurut kakak itu adalah senyuman sebagai bentuk betapa kuatnya orang itu. Dia tersenyum untuk dirinya sendiri, untuk menguatkanya. Jika bukan kita sendiri yang menguatkan diri, siapa lagi?”
Kalimat itu terus terngiang-ngiang ditelinga Reina. Kalimat yang akhirnya menjadi penguat untuk dirinya sendiri. Benar kata Aresh bahwasanya mereka yang terluka lalu tersenyum bukan berarti mereka sadang menipu semua orang lewat senyuman, tapi lebih kepada sedang menguatkan dirinya sendiri.
Hal yang sudah Reina lakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Tersenyum untuk selalu menguatkan dirinya sendiri, bukan untuk menipu siapapun. Dia sendiri bahkan tak percaya bahwa bisa sekuat ini, bisa bertahan sampai detik ini. Ucapan Aresh benar-benar berhasil menguatkannya di saat hatinya terhimpit oleh luka yang saling tumpang tindih di hatinya.
Ah, Aresh, Reina merindukan sosok laki-laki bermata indah itu.
“Mau gue temenin gak ngelamunnya?” tanya Abdi tiba-tiba.
“Abdi! Ya ampun sepupu gue,” Reina berdiri memeluk Abdi erat. “Gue kangen banget sama lo, kapan pulang?”
“Lebay,” Abdi mengurai pelukan itu. “Tadi sore. Udah makan belum?”
“Belum?”
“Keluar yuk cari makan.”
“Lo yang bayar ya, duit gue menipis nih, hehehe.”
“Siaaap!!”
“Asyik! Gue ambil tas dulu ya.” Reina masuk ke dalam thiny house-nya. Lalu kembali dengan membawa sling bag warna kuning dan dia kaitkan pada pundaknya. Cewek itu mengikutil langkah Abdi.
Jika biasanya Reina akan lewat dapur untuk menuju pintu depan rumahnya, kali ini tidak. Setiap ada Abdi, dia selalu mengambil jalan samping memutari sisi rumahnya untuk sampai di gerbang utama. Sejak kejadian itu Abdi tak pernah lagi mau masuk ke dalam rumah itu. Reina tahu kalau Abdi masih trauma.
“Lo pacaran sama Riga?” tanya Abdi begitu mereka berdiri di dekat mobil Abdi.
“Iya, kenapa gitu?”
“Bagus sih, Riga itu temen gue di box.”
“Maksud lo?”
“Boxing.”
“Riga suka tinju, kayak lo? Kok dia gak pernah cerita ya.”
“Sedikit banyak gue tahu tentang Riga,” Abdi membuka pintu mobilnya, lalu Reina menyusul. Cewek itu sudah duduk di samping Abdi. “Dia gak banyak omong. Punya pendirian yang kuat. Cocok sih, sama lo yang bego.”
“Kejam, masa ngatain gue bego.”
“Kenyataan.” Abdi terkekeh geli melihat Reina yang memberengut. Perlahan jeep kuning itu bergerak meninggalkan rumah Reina.
Abdi mengendarai mobilnya dengan tenang. Cowok satu itu tak suka terburu-buru, apalagi menyalip kendaraan di depannya. Bisa dikatakan emosi Abdi cukup stabil untuk ukuran remaja seusianya. Bahkan orang tua harus malu jika melihat bagaimana cara Abdi menyikapi masalah yang ada.
“Sate pinggir jalan, mau gak?”
“Satenya pak Min?”
“Iya,”
“Boleh deh, sekalian sotonya juga ya.”
“Bunda gak ngasih makan lo, lagi?”
“Bukan gak ngasih, tapi bunda gak suka kalau gue makan satu meja bareng sama bunda.”
“Sabar ya,”
“Pasti!” seru Reina mengacungkan kedua jempolnya. Tersenyum dan tersenyum itulah cara paling ampun untuk Reina tetap bertahan menghadapi dinginnya sikap sang ibu dan saudara perempuannya, Sheila.
***
Mereka sudah sampai di kedai penjual sate langganan Abdi. Cowok itu lebih suka kuliner pinggir jalan dibandingkan resto dan kafe yang mempunyai fasilitas mewah. Abdi bahkan mempunyai kriteria untuk calon pacaranya yaitu, tidak boleh menolak ajakannya untuk makan di pinggir jalan.
Kalau kata Reina itu adalah kriteria terkejam yang pernah ada. Bagaiman mungkin Abdi akan tega membiarkan kekasihnya makan di pinggir jalan saat cowok itu mempunyai banyak uang yang bahkan bisa mem-booking satu hotel mewah. Sayang sekali dengan uangnya yang banyak itu bukan?
“Satenya dua porsi sama soto satu.” ucap Abdi pada penjual sate yang sudah tak asing lagi baginya itu. Namanya pak Min, laki-laki paruh baya yang sudah berjualan di tempat itu selama dua puluh lima tahun.
“Oke!”
Mereka duduk bersebelahan. Di meja lainnya ada beberapa pengunjung perempuan, seakan menjadi sebuah kebiasaan di mana pun Abdi berada pasti selalu berhasil menarik perhatian. Mata kebiru-biruannya yang tajam, alis tebal yang terbentuk sempurna, bibi yang tidak tebal dan tidak tipis itu selalu melengkungkan senyuman yang mampu membuat perempuan merasa meleleh ketika memandangnya.
“Jadi sejak kapan lo pacaran sama Riga?” tanya Abdi memulai pembicaraan sambil menunggu pesanannya datang.
“Beberapa hari yang lalu. Lo kenal Riga udah lama?”
“Lumayan, dia juara Olimpiade Fisika tahun lalu. Dia cukup terkenal di sekolah, tapi lebih terkenalan gue.”
“Dih, narsis.”
“Lo cinta sama Riga?”
“Biasa aja.”
“Terus kenapa pacaran sama dia? bego apa gimana, sih lo?”
“Dia yang minta ya gue turutin aja, katanya soal cinta itu urusan belakangan. Lagian nih, orang tuanya baik banget sama gue. Kemarin aja gue di ajak liburan bareng, terus gue bisa dapet tumpangan gratis ke sekolah.”
“Oh, jadi udah gak butuh gue lagi, nih?”
“Kan lo kadang bisa, kadang enggak.”
“Sebahagia lo aja deh.”
Pesanan mereka datang, dua porsi sate ayam dan satu porsi soto ayam. Sambil makan Reina sesekali merilik ke arah sekelompok perempuan di meja sebelahnya yang masih memandangi Abdi, tapi yang dipandangi tak peduli.
“Mbak, pada suka sama sepupu saya ya?” tanya Reina pada para perempuan itu.
“Iya, ganteng banget. Udah punya pacar belum?” perempuan berpakian casual dengan rambut tergerai itu akhirnya memberanikan diri untuk bertanya.
“Jomblo mbak, udah dua tahun.”
Seperti mendapatkan door price mereka semua kompak langsung tersenyum senang. Senyuman genit lengkap dengan rona malu-malu di pipi. Dalam hati Reina terkekeh geli melihat mereka semua. Terlalu menilai seseorang dari fisiknya.
“Boleh dong kita daftar.” ucap yang lainnya sambil berjalan lalu duduk satu meja dengan Reina dan Abdi.
“Boleh aja sih, tapi...” Reina menggantungkan kalimatnya.
“Tapi apa?”
“Mbak harus ganti kelamin dulu biar sepupu aku suka.”
Kalimat yang meluncur begitu saja dari mulut Reina membuat Abdi nyaris tersedak cowok itu melotot menatap sepupunya yang tersenyum tanpa merasa berdosa.
“Homo, maksudnya?”
“Iya.”
“Ih! Enggak deh, makasih. Kita-kita masih suka cowok normal.”
Para perempuan itu segera beranjak setelah membayar makanan mereka. Reina tertawa geli melihat ekspresi kaget mereka, namun tawa itu langsung terhenti ketika melihat Abdi yang menatapnya tajam.
“Hehehe... maaf,” lirih Reina yang menciut mendapati tatapan tajam dari sepupunya itu. “Tapi, cara gue ampuhkan ngusir mereka? Kalau mereka di sini gue yakin lo pasti masih ngeras risih, iya kan?”
“Iya, tapi gak ngatain gue homo juga.” Abdi mengabil satenya lalu meletakan daging-daging kecil itu diantara giginya, dengan kasar Abdi menari tusuk sate itu sampai kayu kecil itu bersih.
Keduanya kini kembali menikmati makanan mereka sampai sebuah suara yang sudah akrab di telinga Reina membuatnya mendongak. “Pak sotonya dua, di bungkus ya.”
“Riga!” seru Reina riang.
Sedangkan cowok itu menatap Reina dengan kening berkerut lalu tatapannya tertuju pada Abdi. “Lo kok sama Abdi?”
“Duduk sini,” Reina menepuk kursi plastik kosong di sebelahnya. “Abdi sepupu gue. Dia bilang kalian saling kenal.”
“Hmmm,”
“Wah, bahagianya hidup gue punya dua cowok ganteng,” celoteh Reina riang. “Tuhan emang maha baik. Di setiap kesakitan dan luka, pasti selalu ada senyuman yang mengiringi.”
“Sok bijak lo,” Abdi menoyor kepala Reina pelan. “Sejarah masih dapet lima aja belagu.”
“Itu karena Pak Anton kalau ngejelasin mendayu-dayu, kayak naik sampan di sungai yang tenang. Bikin ngantuk.”
“Nyalahin Pak Anton, lo-nya yang males baca, males belajar.”
Reina bersingut membuang mukanya dari Abdi. Cewek itu menopang kepalanya dengan kedua tangannya memilih untuk memandangi Riga saja. Meski tak ada debaran aneh di dadanya, Reina cukup menikmati kedekatannya dengan Riga.
Ketiganya kini larut dalam obrolan yang tak tentu arah. Riga bahkan melupakan soto pesanan mamanya karena terlalu asyik mengobrol, apalagi obrolan seputar tinju yang digelutinya bersama Abdi. Reina yang tak mengerti memilih diam mendengarkan percakapan mereka di temani satu porsi sate yang baru di pesan lagi.


 yellowfliesonly
yellowfliesonly




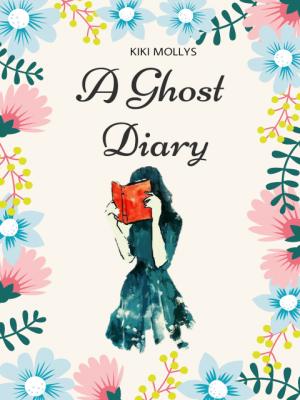









Ceritamu menarik dari awal, apalgi pggmbran tokohmu. manusiawi bget, (ada kelamahnnya) suka. tapi aku baca masih bnyak yg typo. bnyk hruf yng kurang juga.
Comment on chapter Pertemuan Yang Burukdan ini kan chapternya sudah ada judul, jdi di body text kya'nya gk perlu ditulis lgi judul chpternya. kalau mau di tulis enternya kurang kebawah. semangat yaaa