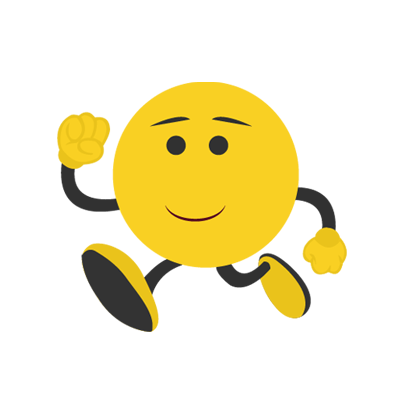
Part 6. Telor Balado dan Sambal Goreng Kentang
Lima hari sebelum kepulanganku ke Jakarta.
“I didn't love him!" Teriaku di depan wajah Bule itu.
"BULLSHIT!!" Dia berdiri tepat di hadapanku, dan baru saja memalingkan wajahnya ketika ia menamatkan makiannya itu. Baru sekarang aku melihat si laki-laki berkulit pucat itu marah. Tidak, Charlie tidak marah, ia kecewa. Kecewa padaku. Aku tahu dia membentaku karena tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Rasa kehilangan disebelum waktunya.
"So, I'm just a friend, HAH!" Bentaknya kembali dengan jarak satu meter denganku. Sesungguhnya, aku sangat ingin mengakhiri adegan ini. Sudah lama aku tidak bertengkar. Tidak adu mulut hanya untuk meyakinkan orang lain tentang apa yang kurasa. Yang aku mau saat ini, adalah, memeluk pria bertato di hadapanku tanpa kata. Mentransfer energi permintaan maafku dan rasa kehilanganku juga.
"NO! Of course you more than just-"
"A sleeping friend, right??" Sumpah ini ngeselin banget!0 Kata-kata Charlie yang memotongku tadi benar-benar membuatku tersinggung. Ternyata aku masih bisa merasakan ini, sakit. Aku langsung maju mendekati tubuhnya.
PLAK!!
"HOW DARE YOU!" kutampar Charlie. Pipinya merah, tapi tubuhnya tidak bergeming.
"Kenapa kamu nggak berani bilang tentang kita ke dia?!” Beda tinggi diantara kita yang sampai dua puluh sentimeter membuat dirinya sangat dominan di depanku dalam jarak sedekat ini.
"Yaa... Karena, aku nggak mau dia berpikir kalau aku..." Aku melemparkan pandangan ke sekeliling rumahnya, menghindari tatapan matanya.
"What? Because you don't want him to know, that you've being with someone else? Supaya masih ada kesempatan dia buat balik sama kamu lagi, kan!"
Honestly, tuduhan Chalie sembilan puluh persen benar. Sedangkan sepuluh persennya lagi yang salah, adalah bukan untuk memberikan kesempatan Nino kembali padaku. Tapi aku tidak ingin Nino menganggapku sebagai cewek yang tukang selingkuh. Nino tidak posesif. Malah aku yang posesif. Tapi negatif thinking-nya Nino itu kronis. Mungkin karena dia bekerja di bidang hukum, makes him such a judging person.
"Charlie, listen... I said, I'm sorry..." Nadaku melemah. Aku tidak mau lagi memperjuangkan egoku.
Sesaat kami berdia terdiam. Ia kembali duduk di sofanya. Membuatku tampak lebih tinggi dengan masih berdiri berdiri di hadapannya. Malam ini aku sengaja mampir ke rumah Charlie, karena sedari kemarin siang kita berpisah di Beachwalk, ia tidak mengabariku lagi. teleponku juga tidak diangkat.
"Just go with him, Luna." Nadanya ikut merendah.
"Beg a pardon??" Aku memiringkan kepalaku, memastikan melihat ekspresinya lebih dekat.
Ada jeda diantara kita berdua.
"What do you expect about us?" Dia kembali berdiri, memegang bahuku, membuatku harus menengadah untuk melihat wajahnya yang hanya berjarak sepuluh senti dari wajahku. Tapi, aku sama sekali tidak bisa menebak arti ekspresinya. Mukanya seperti datar namun matanya membesar dan alisnya naik. Seperti menantang, sekaligus memohon. Pertanyaanya menohok. Aku tidak tahu harus menjawab apa.
"I wish.... We could... Be together, or... Some kind of-" Hanya itu kata dapat kuolah di otak.
"You know I love you, but you're leaving..." Dia memotong ucapanku lagi. Ucapanku yang... memang terdengar berputar-putar. Dia menangkup pipiku dengan jemarinya. Semburat rasa yang selalu aku ingat, hangat. Kenapa malam ini aku selalu tidak tahan meliihat tatapannya. Rasanya mirip seperti maling yang tertangkap basah oleh si pemilik rumah.
Aku diam. Ah sudahlah, sepertinya ini bukan pertengkaran yang dapat diselesaikan dalam satu malam.
"You scared." Tuduhnya kemudian. Tidak kurasakan lagi hangat di pipiku. Dia sekarang berbalik badan. Walaupun yang diucapkannya adalah menuduhku takut, tapi bagiku, itu lebih terdengar seperti ungkapan menyerah. He giving up on me.
Aku diam. Perasaanku campur aduk.
"And that's why, you never say you love me." Lanjutnya.
Sumpah ya, situasi ini semakin ngeselin. Si Bule itu pikir bisa mendesaku. Memojokkanku. Membuatku merasa bersalah. But he couldn't! Walau apa yang dituduhkannya benar sekalipun.
"You better listen carefully Charlie, Whatever you said to me, that will-never could-simplifying-me!" Kutegaskan kalimat akhirku. Bahwa dia tidak bisa mengubahku. Tidak hanya dengan waktu tiga bulan ini.
"Yes, I'm scared. So, what?! Kamu tidak tahu rasanya mencintai orang bertahun-tahun, berusaha menjadi apa yang dia mau, tapi kemudian ditinggalkan." Lanjutku.
Pria berkulit pucat itu menyembulkan senyum sinis, "Keep remembering it. You hurt yourself, Luna. You, complicating yourself!"
"BULSHIT!" Aku sontak membalikan badan, berjalan menuju pintu lalu membantingnya.
Aku berlalu darinya. Tujuanku tentu saja pulang. Tapi sembari mencari taksi yang lewat, aku berjalan kaki ratusan meter sambil menyeka air mataku. Sendirian. Nino. Dia selalu mempersulitku. Sekelibat aku mempersalahkannya. Karena sebelum dia datang ke Bali, semuanya baik-baik saja.
***
"Luna, kamu kapan pulangnya?"
"Tanggal 25."
"Oh, sudah beres nulisnya? Sudah siap terbit, nih?"
"Ya nanti di Jakarta baru ke penerbitnya, Yah."
"Oke. Kalau sudah beres pokoknya langsung pulang, ya."
"Iya."
Kututup telepon dari ayahku. Bawel banget sih! Kenapa dia tidak pernah bisa memberi bantuan kepada anaknya.
***
Tiga hari sebelum kepulanganku ke Jakarta.
Charlie sama sekali tidak menghubungiku. Aku juga gengsi dong mau menghubungi dia. Walau, ada benarnya juga apa yg Bule itu katakan. Aku tidak bisa terus mengingat semua luka di masa lalu. Apakah aku masih mencintai Nino? Ah, entahlah. He was my everything. He was my every love songs. Tapi, ada tembok besar yang membuat aku dan dia benar-benar tidak bisa bersama. Walau harus mengemis pun, tetap tidak akan mungkin bisa bersama. Kita sama-sama tidak mau mengalah untuk merubah sifat buruk kita masing-masing.
Aku sekarang sedang berada di pinggir pantai Kuta, sendirian. Sore-sore seperti ini, kalau lagi di Kuta, biasanya ada si Bule bertubuh besar itu di sebelahku. Oh, sepertinya aku benar-benar merindukannya. Tapi, aku tidak berani mengambil risiko untuk kembali menyerahkan semua perasaanku, jika suatu saat harus kembali berpisah.
All my back are packed, I'm ready to go. Tinggal tiga hari lagi, aku sudah membeli tiket pesawat jam delapan pagi via agen travel online dari seminggu yang lalu. Jujur, sekarang otakku lebih dipenuhi Charlie ketimbang Nino. Karena gini-gini aku orang yang rasional juga. Tidak ada yang bisa Nino janjikan untuku. Tapi Charlie, ah, aku harus benar-benar harus pindah ke Bali jika ingin bersamanya. Benar-benar meninggalkan Jakarta.
Kaos biru gombrang yang kukenakan berkibar macam bendera yang tertiup angin. Rambut kucepol seadanya ke atas. Aku sedang sangat ingin, tiba-tiba si Bule itu nongol sekarang di sini, merangkulku seperti biasanya. Aku harus ke tempat Charlie sekarang. Aku harus meruntuhkan dinding egoku. Aku tidak bisa pergi dengan meninggalkan konflik.
Aku beranjak dari dudukku. Membersihkan pasir-pasir yang menempel di kaki dan belakang celanaku. Seketika ide memasak muncul di kepala. Selama ini kan dia yang selalu menjejaliku dengan kue-kue buatanya. Sekarang, gantian dong, biar dia tahu rasa masakan rumahan Indonesia. Mmh, tapi, masak apa ya. Haha... Selama serumah dengan Nino dulu, aku cuma bisa tumis-tumis dan goreng-goreng doang. Yaa... Whateverlah ya... apapun yang kumasak, Charlie pasti suka kali ya.
Aku berencana ke salah satu pasar tradisional di dekat Kuta. Berharap itu pasar masih buka di sore hari. Keluar dari area berpasir, aku menapaki trotoar di samping kawasan pantai. Lalu handphone-ku berdering. Sebuah nama yang sangat kuhafal muncul di layar.
"Kamu dimana?"
"Kenapa emangnya?"
"Kamu lagi di deket Kuta ya?"
"Kok tau?"
"Nengok ke sini deh. Arah jam lima."
Aku celingukan, berpikir ke manakah arah jam lima itu. Satu putaran kepala, aku tidak melihat siapa-siapa.
"Salah, bukan ke situ. Ke kanan, ya kanan."
Seketika aku melihat sesosok laki-laki sedang dadah-dadah ke arahku. Kok bisa sih malah ketemunya sama Nino!
"Sini deh sebentar." Sambil tangannya melambai-lambai memanggil. Aku pun kemudian menyebrang jalan, menyambanginya yang terlihat sedang duduk di sebuah meja makan
"Kok kamu ada di sini sih?" Tanyaku, agak kesel juga ya. Kenapa ini cowok suka tiba-tiba muncul seenak jidatnya. Kalau dulu Nino tiba-tiba muncul sih, aku senang. Kalau Sekarang, agak males juga ya. Mengingat kita sedang proses bercerai dan, kayaknya nggak ada gunanya juga dia ada di dekatku.
"Ya aku lagi makan, lah. Ini kan kafe." Oiya, lupa. Yang sedang di pantai tadi itu aku. Sedangkan Nino, sedari pertama dia dadah-dadah, aku sudah melihat seporsi spageti di atas mejanya.
"Oh." Aku kemudian duduk di kursi yang ada di hadapannya.
"Oiya, kamu jadi pulang tanggal 25, kan?” Aku mengangguk. Lalu laki-laki bermata bulat itu mengambil handphone-nya, men-scroll-scroll layarnya.
"Kamu pulang bareng aku aja ya. Flight jam sepuluhan. Udah aku beliin tiketnya. Nih.”
Nino menyodorkan layar handphone-nya ke depan mukaku, membuatku membaca email di handphone-nya. Garuda, kelas bisnis, atas nama aku dan dia.
"Tapi aku udah beli duluan, pake Lion jam delapan, No. Makasih, tapi nggak bisa kayaknya."
"Kamu beli tiketnya pake apa?"
"Travelika."
"Cancel aja. Bisa direfund, kan?"
"Mmh... Yaa... Bisa sih..."
"Yaudah, nanti aku jemput jam delapanan ya."
Kenapa sih si Nino ini selalu membuat sebuat statement. Jarang banget dia buat kalimat tanya. Bisa kan nanya dulu, "Mau pulang bareng apa nggak?" atau, "Kamu udah beli tiket belom?" HAH! Aku terganggu dengannya. Aku memantapkan sebuah kalimat.
"No, kita ini udah lagi proses cerai. Tapi kenapa sih, kamu masih selalu mendominasi aku?"
Nino mengernyitkan dahinya. "Dominasi?"
Aku diam. Please deh, nggak perlu dijelasin kali ya.
"Ooh... Beliin tiket kamu pulang itu, kamu anggap sebagai dominasi?"
Aku memanyunkan bibir ke kiri-ke kanan.
"Kita kan sama-sama bukan orang asing, Lun. Salah, kalau aku ngajak satu pesawat orang yang aku kenal?"
Pertanyaan yang nggak perlu aku jawab sepertinya.
"Atau, kamu sudah nggak mau kenal sama aku lagi?"
Gantian aku yang mengernyitkan dahi, "AU AH!"
"Aku duluan ya kalau gitu." Lanjutku, karena sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan Nino. Aku bangun dari dudukku. Membuat Laki-laki bertubuh 170-an sentimeter yang duduk di hadapanku tampak lebih pendek. Sempat aku mengintip dari ekor mataku, sesaat sebelum aku kembali menyebrang jalan. Nino terlihat memandangi kepergianku, menyandarkan duduknya, mengehentikan suapannya yang sebelumnya lahap.
***
TARA!!
Dari pagi-pagi buta tadi aku sudah ke pasar tradisional, membeli bahan-bahan, lalu memasak. Di jam sembilan pagi, dua menu kesukaanku sudah jadi, sambal goreng kentang dan telor balado. Keduanya berbau pedas. Tidak apa-apa. Aku memang sedang ingin mengerjai Bule itu agar kepadasan. Aku rindu suara renyah tawanya.
Duh, udah lama banget kayaknya aku nggak ngupas kentang, ngupas bawang, ngiris-ngiris bawang, cabai dan merebus telor. Cari mudahnya saja, bawang merah, bawang putih dan cabai kublender selagi ketang kugoreng dan telor kurebus. Setelah matang, lalu keduanya tinggal di tumis. tidak lupa pakai gula garam secukupnya.
Jam sepuluh aku sudah sampai di depan toko kue Charlie. Terlihat beberapa pegawai yang sedang sibuk siap-siap membuka toko. Tapi aku sendiri belum melihat Charlie. Menjinjing rantang tingkat tiga, aku langsung saja masuk. Charlie pasti sedang ada di dapur, seperti biasa, dugaanku. Tapi ternyata dugaanku itu salah, setelah satu langkah kakiku menapak masuk, kulihat Charlie berada di balik meja kasir. Dia masih menunduk, belum melihat kedatanganku.
TOK TOK!
“Excusme..." Kuketok meja kasir dan kulebarkan senyum semanis mungkin. Semoga dia membalasnya.
"Luna?" jawabnya kaku. Mukanya merah, seketika meletakan uang-uang yang sedang dihitungnya.
"Still remind me?" ledekku.
Dia akhirnya tersenyum juga.
"Aku bawain kamu sarapan. Nih."Kutunjukan rantang tingkat tiga itu ke depan mukanya. Tapi dia tidak mengubris rantang di hadapannya. Matanya tertuju padaku.
"Let's talk!" Ajaknya kemudian sambil berjalan berlalu menuju arah belakang tokonya.
Di dalam rumahnya aku langsung menuju sebuah meja, membuka rantangku. Charlie duduk di depanku. Melihatku yang lalu dengan sigap langsung mengambil piring di dapur.
"Masak apa?" Duh, itu nadanya, kayak, nantang atau, ngeledek ya.
"Masakan Indonesia, dooong..."
Mukanya kaget sesaat setelah kusiapkan nasi di piring dan kedua lauk tadi. "Is it spicy?"
“It is Hot! Not only spicy..." Dengan nada setengah bebisik. Macam si pengantar Pizza waktu dibukain pintu, di salah satu iklan jaman dulu.
"HAHAHAHA..." Aku kembali mendengar tawa renyahnya. Targetku tercapai. Sesuatu yang aku rindu, telah kulihat dan kudengar kembali. Padahal, kayaknya sih, nggak ada yang lucu ya dari kalimatku tadi.
Aku lalu menyuapinya. Dia pun menurut, cuma tinggal mangap saja. Satu suap, mukanya biasa saja. Dua suap, mukanya mulai mengernyit. Suapan ketiga, "Shit!" Dia berlalu ke dapur mengambil segelas air putih.
"Kamu sengaja ya?" Dia lalu duduk di sebelahku sambil menyuguhiku segelas air putih.
"HAHAHA..." Gantian aku yang ngakak. Aku pun menyuap. Satu suap, dua suap, tiga suap, empat suap. Laper apa nyoba ya. Charlie cuma bengong memandangiku yang lebih seperti sarapan ketimbang nyicip.
"Mau lagi?" tanyaku. Dia menggeleng sambil tersenyum.
"See? Nggak pedas, tau..."
Dia cuma garuk-garuk kepala saja.
"You're not mad at me anymore?" Pertanyaannya mengagetkanku yang sedang minum. Untung nggak keselek.
Aku menghentikan peringai laparku. Kutatap balik Charlie. "No. Aku nggak mau pergi dengan ninggalin konflik."
"But, If you ask me about us again? I guess-" lanjutku.
"I know." Dia memotong tegas. Suasana canggung itu tetiba muncul kembali. Aku kembali merapihkan rantang tingkat tiga tadi. Dia pun ikut merapihkan gelas-gelas dan bekas piring. Membawanya ke arah dapur.
“Charlie." Panggilku menyetop langkahnya ke dapur. Dia menoleh.
"Can you just stop, being awkward! Kataku setengah kesal. Dia cuma diam mematung.
"You don't know how I missed you!" kataku kemudian. Tapi dia malah berlalu, melanjutkan menaruh piring-piring dan gelas tadi ke dapur. Gila, gue dicuekin!
Aku menyusulnya ke dapur. Mungkin, sebetulnya, dia yang masih marah padaku.
"Aku kangen kamu, tau!" Kupeluk dia dari belakang. Dia lalu membalikan badan. Membuat pelukanku terlepas. Kemudian memegang kedua lenganku, membuatku tertahan untuk kembali memeluknya. Oh, should I begging for a peace? pikirku.
Dia memandangi wajahku sambil menarik nafas panjang. Beberapa detik matanya melihat ke segala arah. Bibirnya seperti ingin mengucap sesuatu, tapi tidak ada kata yang kudengar.
Seketika, "I missed you too, Luna." Kudengar kalimat itu keluar dari mulutnya, setelah ia menarik kedua lenganku ke arah dekapannya.
***


 Eno_wid
Eno_wid








