Zen, Vino, dan Haya di usia 10:
Mengucap sumpah sambil menatap langit malam penuh bintang. Satu diantara mereka menunggu pesawat lewat, satu lagi sedang memperhatikan bulan, dan yang lain memejamkan mata.
“Astronot!” lucu memang, walau tiap hari kerjanya hanya menunggu pesawat lewat, Vino bercita-cita jadi astronot, bukannya pilot.
“Astronot itu naik roket, Vin, bukan pesawat!” mungkin sudah seribu kali Zen mengucapkan kalimat itu. Sepertinya Vino tak peduli.
“Denger, tuh, Cil!” dan Haya selalu membela Zen. Sejak umur lima, Haya memanggil Vino dengan sebutan Nocil, artinya Vino Kecil. Dibandingkan dengan Zen badan Vino memang lebih kecil, tingginya hanya sepundak Zen. Tapi yang memberi julukan malah lebih kecil lagi, Tinggi Haya tak lebih dari telinga Vino.
Awalnya, walaupun bertetangga, Haya tidak berminat untuk menyapa Zen atau Vino. Sapaan pertamanya adalah saat Zen marah-marah di depan rumahnya, meminta Vino untuk pulang karena hari akan hujan.
Haya keluar dengan bonekanya dan berteriak, “Hari ini pesawat nggak lewat, lewatnya besok!”
Waktu itu ia hanya gemas melihat tingkah dua anak laki-laki itu. Siapa sangka, teriakan pertama itu akhirnya membuat mereka berteman. Haya dan dua orang aneh yang biasa ia perhatikan dari jendela kamarnya.
Selain Vino yang selalu menunggu pesawat lewat dan Zen yang selalu marah, Haya tidak mengetahui apapun. Sampai waktu yang memberitahunya, Zen adalah seorang jenius. Selalu peringkat satu di sekolah dasarnya, bahkan hampir masuk kelas akselerasi. Hampir, karena waktu itu Zen malah sakit selama sebulan hingga harus melewatkan ujian masuk kelas percepatan itu. Sedangkan Vino adalah seorang yang lebih bebas dari Zen. Ia selalu menunggu pesawat, berlarian di tengah panas dan hujan. Vino juga yang paling sering berteriak, memanggil Haya untuk keluar rumah.
Hal yang sama berlaku bagi Vino dan Zen. Dulu, Haya terlihat seperti anak perempuan pendiam. Ia lebih banyak diam dan hanya bicara saat ditanya. Namun, seiring dengan bertambah usia, Haya malah jadi yang paling banyak bicara. Bukan hanya itu, Haya juga mengambil alih pimpinan yang semula dipegang oleh si jenius, Zen. Saat mereka beranjak remaja, apapun yang akan mereka lakukan, harus atas izin Haya.
Apapun, kecuali menunggu pesawat lewat.
“Kalau ada pesawat jatuh, disini, kalian mau kabur atau nyelamatin aku?” Haya masih memperhatikan bulan.
“Kabur,” Zen tidak perlu berpikir. Tentu saja ia akan menyelamatkan dirinya sendiri.
“Sama,” kata Vino datar, menurutnya ada pesawat yang jatuh adalah sesuatu yang mustahil. Lagipula malam itu tidak ada tanda-tanda pesawat akan lewat.
“Jahat ya emang, aku ini perempuan, harusnya kalian sebagai laki-laki melindungi aku lah,” jawaban Zen dan Vino sebenarnya sudah diprediksi, tapi tetap saja menyebalkan. Seharusnya mereka bohong sedikit untuk membahagiakan hati Haya.
“Pertanyaan kamu nggak masuk akal, kalau pesawat jatuh nggak perlu aku nyelamatin kamu. Kita bertiga pasti lari pontang-panting,”
Zen benar, sih.
Haya menelan ludah mendengar tanggapan Zen dan tak mengharapkan Vino menimpalinya. Vino masih menunggu pesawat.
Hari semakin larut, ditandai dengan teriakan kakak Haya, menyuruhnya segera masuk ke rumah.
“Kalau kalian dalam bahaya, aku bersumpah, sekuat tenaga bakal aku selamatkan kalian,” kalimat itu meluncur mulus dari mulut Zen tepat saat Haya berdiri.
“Aku juga, tenang aja Hay, siapa yang berani sama kamu sih, kamu punya dua pengawal,” sahut Vino, ia kemudian melirik Haya sambil mengacungkan ibu jari.
“Janji ya?” Haya mengulurkan jari kelingking pada Vino dan Zen.
Kedua temannya itu menyambut, mengaitkan kelingking mereka. Sumpah itu terjadi di malam dengan bintang, tanpa pesawat lewat, dibawah terang bulan. Sumpah itu mungkin hanya sebatas kalimat yang tak disertai pertanggung jawaban. Tapi bagi Zen dan Vino, dengan mengucapnya, mereka telah berjanji saling menjaga.
-
Zen, Vino, dan Haya di usia 17:
Kamarnya masih gelap lengkap dengan suara dengkuran teman sekamarnya yang terdengar semakin keras. Zen terbangun dan mendapati dirinya bercucuran keringat. Gossip yang menyebar beberapa minggu terakhir membuatnya tak bisa tidur dengan tenang. Ada sekelompok orang yang memburu para peringkat atas, begitu katanya.
Sialnya, Zen adalah peringkat satu sejak kelas sepuluh.
Zen mengatur nafas sambil mengusap wajah. Gosip murahan itu seharusnya tak perlu ia hiraukan. Tapi, di Akademi Menengah Atas, tidak ada gosip tanpa dasar. Setiap orang hanya membicarakan hal yang penting. Jika desas-desus menyebar lebih dari seminggu, kemungkinan besar itu bukan sekedar kabar burung. Kemungkinan kabar itu memang benar adanya. Zen sedang diincar seseorang.
Nggak.
Zen menggeleng. Ia menarik nafas panjang lalu mencoba untuk kembali tidur.
Pikirannya tiba-tiba melayang pada Haya dan Vino. Dua tahun lalu, susah payah Zen mengajari dua temannya agar lulus tes masuk ke Akademi Menengah Atas, salah satu sekolah unggulan terbaik saat ini. Sekolah yang berada di pinggiran Kota Bandung, berupa kompleks luas lengkap dengan asrama, gedung olahraga, rumasakit, dan minimarket.
Demi masuk sekolah luar biasa itu, setiap sabtu dan minggu, mereka bertiga belajar di rumah Haya. Waktu itu Haya malah sempat menangis, karena ia yang paling tidak mengusai materi. Haya sudah pasrah jika harus berpisah dengan kedua temannya. Terbayang di benaknya, Vino dan Zen akan tinggal di asrama Akademi sedangkan Haya masuk sekolah biasa.
“Hay, jangan nyerah dong.”
Zen ingat bagaimana Vino berulang kali meminta Haya untuk tidak menyerah. Padahal, Zen tahu kemampuan Vino juga tak seberapa. Zen tahu, Vino lelah belajar. Tapi, temannya tak pernah menunjukkan itu. Berbekal tekad untuk bersama di sekolah terbaik, Vino memaksa dirinya sendiri sekaligus Haya, melewati batas kemampuan, menjadi lebih baik.
Saat hari pengumuman kelulusan, Haya tidak membuka suratnya. Ia malah mendaftar ke salah satu SMA Negeri di kota tempat mereka tinggal, Bandung. Hari itu, Haya mengetuk pintu rumah Zen sambil menangis.
“Zen, aku belum buka suratnya, aku takut,” tangan Haya bergetar memegang sepucuk surat yang sudah tak terlihat bentuknya.
Kedua alis Zen terangkat, “Terus, aku yang buka?”
Haya menunduk sambil mengangguk pelan. Ia memberikan surat yang sudah kusut pada Zen.
Saat terdengar bunyi gemerisik tanda amplop sudah disobek, Haya menutup wajah. Tangisnya semakin kencang.
Zen mematung tanpa tahu harus berbuat apa, “Hay, aku baca hasilnya ya?” Zen membuka surat perlahan, gara-gara reaksi berlebihan Haya, ia jadi ikut gugup.
“Zen, aku udah daftar sekolah negeri, kok. Sekolah biasa. Jadi, nggak apa-apa. Selamat ya, kamu sama Vino bakal asrama. Aku nggak—”
“Kamu lulus, kok,” Zen membuka surat itu lebar, menunjukannya pada Haya.
“Hah?”
“Nih, lulus, Hay,” Zen menunjuk-nujuk kata lulus.
Zen tersenyum sendiri, masih teringat jelas ekspresi Haya saat itu. Ia tersenyum sedikit, kemudian semakin lama semakin lebar. Dengan air mata yang masih becucuran ditambah hidung mengeluarkan ingus, Haya menghambur keluar. Ia berlari ke rumah Vino, jaraknya empat rumah dari rumah Zen.
Entah apa yang terjadi di rumah Vino, mereka tiba-tiba kembali mengetuk pintu rumah Zen. Berteriak-teriak, mengucapkan terimakasih dan beberapa kata lain yang tak terdengar jelas.
Zen hanya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, ia merasakan kebahagiaan.
Waktu itu, Vino dan Haya menghadiahkannya pelukan.
Zen menarik nafas dalam, seharusnya mereka masih dekat sampai sekarang. Andai perdebatannya dengan Vino tak pernah terjadi.


 MulierViridi
MulierViridi







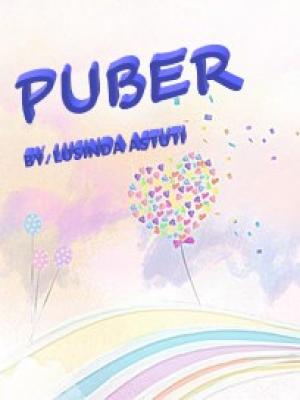


great story :)
Comment on chapter Batas ke 1