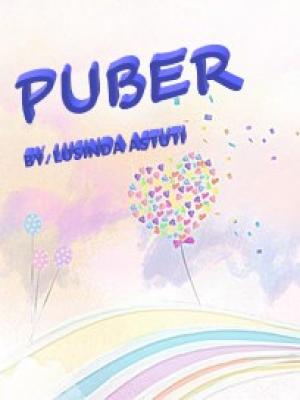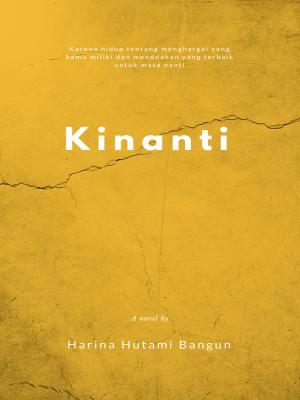Pagi belum terlalu beranjak, tetapi aku sudah berkeliyaran di hutan. Seorang diri menyusuri hamparan tanah berlumpur, basah, dan penuh genangan. Helaian kabut tipis bahkan masih menggantung di reranting pohon yang ada di kanan-kiri jalan.
Bukanlah keinginanku berkeluyuran di tengah rimba sedini ini. Terlalu merepotkan, menguras tenaga, dan melelahkan. Aku lebih suka membaca buku setebal lima ratus lembar di perpustakaan sekolah daripada harus mengarungi belantara.
Terlebih, ini adalah hari Minggu. Hari libur. Waktu untuk beristirahat, melepas penat, tidur, dan merileksasikan otak yang nyaris meledak gara-gara dijejali terus dengan materi pelajaran yang sangat banyak.
Namun, aku terpaksa melakukannya. Ada perkara lain yang jauh lebih aku takutkan daripada ledakan otak: amarah ibuku. Yap, itulah yang membuatku sudi berkeluyuran di hutan saat liburan.
Meskipun awalnya merasa kesal bukan main, tetapi aku tidak repot-repot membantah. Mengajak berdebat seorang wanita, terlebih ibuku sendiri yang hampir berkepala empat adalah hal konyol terakhir yang ingin kulakukan. Peluangku untuk menang darinya sangatlah kecil. Aku pasti langsung kalah telak di ronde pertama.
Ibuku seorang yang tegas, keras kepala, dan cerewet. Sukar mengalahkan perempuan semacam itu dalam perdebatan. Jangankan adu argumen, saat mengobrol biasa saja, orang-orang pasti menelan ludah karena sikapnya. Ia seakan tidak pernah kehausan, kendati telah berbicara panjang lebar.
Memang, sih, paras ibuku cukup cantik. Ia mempunyai sepasang mata sipit bercahaya yang terbilang tajam. Wajahnya oval, dengan bibir mungil dan tahi lalat kecil di sudutnya. Rambut hitam legamnya yang kini lebih sering digelung, kuyakini dahulu mampu membuat para lelaki bersiul menggoda.
Namun, tetap saja aku tak mengira ada pria yang mau mendekati ibuku. Kecerewetan wanita itu jelas menjadi alasan utama. Kaum lelaki yang tertarik pada dirinya, mesti ekstra bersabar juga berjuang untuk menghadapi cerocosan dan sikap keras kepalanya. Hanya lelaki yang tegar dan pantang menyerah yang mampu memenangkan hati ibuku.
Dan, kurasa pria bercaping yang tengah memetik bayam di sana berhasil memenuhi syarat tersebut. Ya, dialah ayahku. Orang yang sukses menaklukkan perempuan tercerewet yang pernah ada.
"Ayah kira kau tidak jadi ke sini, Micko, " ujar pria berkulit cokelat terbakar itu saat aku datang. Seulas senyuman tersungging di bibirnya.
Aku mendesah. "Mau bagaimana lagi, Yah? Ibu mengancam akan mengamuk dan mengobrak-abrik rumah kalau aku tidak pergi."
Ayahku tertawa. Membuat penutup kepala dari bambu yang dipakainya merosot hingga sebatas mata. Kerutan-kerutan di wajahnya terbiaskan oleh raut sumringah untuk sejenak. Dia membenarkan posisi capingnya, kemudian memandangiku.
"Ibumu memang tidak pernah berubah dari dulu," simpul ayah.
"Tepat sekali."
"Sama sepertimu, Micko," lanjutnya, "kau juga tidak berubah. Tujuanmu ke sini agar kau bisa membaca novel tanpa dimarahi ibu, tha?"
Pandanganku dan ayah lantas sama-sama tertuju pada buku tebal yang kujinjing di tangan kanan. Aku tersenyum lalu berujar, "Boleh, kan?"
Ayah menghela napas. "Terserahmulah, Le. Ayah larang pun, percuma. Kau pasti tetap tidak mau menurut. Wekel. Tapi, setidaknya bantulah ayahmu ini sebentar. Banyak bayam yang harus dipanen."
Aku mengernyit. "Bukankah kita baru akan panen minggu depan, Yah?"
"Rencana awal memang begitu. Tetapi, kalau tidak kita petik sekarang, ayah khawatir panen kali ini akan gagal."
"Kenapa begitu?"
"Lihatlah sekelilingmu, Micko! Bayam di lahan ini banyak yang rusak. Tidak ada jaminan kalau minggu depan masih ada bayam segar di sini."
Aku menengok ke kiri dan kanan. Benar kata ayah. Sebagian besar pohon bayam di lahan ini rusak. Dedaunan hijau yang ada di sebelah kiriku telah habis terkoyak, menyisakan semacam bekas gigitan hewan di pangkal daunnya. Selain itu, tanaman bayam di balik tubuh Ayah juga terlihat membiru, dengan batang membengkak dan agak berair.
"Bagaimana ini bisa terjadi?" desisku.
Ayah melepas capingnya. Gurat kesedihan bercampur rasa tidak percaya menaungi parasnya bak awan badai. Dia pasti sangat terpukul. Panen kali ini yang seharusnya menjadi panen terbaik sepanjang sepuluh tahun seperti harapannya, justru membuat ayah kecewa berat.
"Entahlah, Micko. Ayah juga tidak tahu. Sejak kemarin sudah begini," jawabnya sendu.
"Mungkinkah ulah hewan liar, Yah? Babi hutan, misalnya?"
Ayah menggeleng. "Apa pun itu, lebih baik kita segera memanen bayam-bayam yang masih bagus. Ayah takut mereka akan datang lagi."
Lelaki itu memakai kembali capingnya dan berbalik. Dia bergegas mendekati rumpun bayam di bagian belakang.
Biasanya, aku akan berkata enggan dan segera memosisikan diri di bawah pohon untuk membaca novel. Tidak peduli sekeras apa ayah membujuk.
Namun, kali ini aku sangsi melakukannya. Selama ini ayah telah bersusah payah mengurus kebun demi menghidupiku dan ibu. Terlalu kurang ajar rasanya jika sekarang aku hanya menonton ayah bermandikan keringat.
Kuputuskan untuk menaruh novel yang kubawa di atas batu besar tak jauh dariku. Kemudian, langkahku beranjak menghampiri tetumbuhan segar yang ada di sektor kiri.
Baru saja aku ingin memotek batang bayam pertama, bekas gigitan pada tumbuhan sebelah berhasil menarik perhatianku. Membuat rasa ingin tahuku terpatik.
Aku pun takluk di hadapan rasa penasaran. Niatku untuk memanen bayam-bayam segar runtuh. Lantas, kualihkan fokusku kepada bayam-bayam cacat itu. Mengamatinya dari jarak dekat.
Sebagian dari diriku ingin meyakini bahwa ini hanyalah ulah hewan biasa, seperti dugaan awalku. Mungkin kemarin ada segerombolan celeng lapar yang mampir bersantap atau bisa saja ternak-ternak tetangga yang kelaparan mengungsi kemari.
Namun, sisi lain diriku menolaknya dengan serta-merta. Ada yang aneh di sini. Kurasa, kerusakan ini lebih dari sekadar ulah kerakusan satwa. Andai kata penyebabnya memang kawanan hewan, maka dapat dipastikan mereka bukanlah hewan sembarangan.
Aku tidak sedang membual. Lihatlah bekas gigitan ini! Pada tepian alur geligi yang tertoreh di daun, tampak seberkas warna biru gelap. Saking tipisnya, rona tersebut hampir-hampir kuabaikan. Tak hanya itu, di sana aku juga mendapati bulir-bulir air agak kental yang menguarkan bau tidak sedap.
Baiklah, aku mungkin bisa memahami jika cairan tersebut adalah liur. Setidaknya itulah asumsi paling logis. Akan tetapi, bercak kebiruan yang tertinggal di pinggir koyakan bayam mengusik benakku. Hewan apa kiranya yang mampu menimbulkan noda demikian dari bekas kunyahannya?
Deg!
Tubuhku tiba-tiba menegang di tengah sibuknya berpikir. Aku tertegun. Ada semacam getaran ganjil yang merambatiku. Halus namun memiliki daya kejut yang lumayan. Kepalaku sontak menoleh.
Sepasang manik ini segera mengedarkan pandangan. Nihil. Hanya ada sehamparan luas bayam, semak, dan pepohonan. Embusan angin yang tenang mengakibatkan belukar-belukar bergemerisik. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan.
Aku bergeming. Bingung. Apa yang baru saja kurasakan? Getaran apa tadi?
"Jangan diam saja, Le!" seru ayah dari kejauhan. "Bayam-bayam itu tidak akan bisa memetik dirinya sendiri!"
"Iya, iya, Yah! Ini juga mau mulai!" balasku seraya menengok ke arah ayah.
Aku pun bergeser ke bagian bayam segar. Satu per satu tetumbuhan yang ada di sana kupotek. Lantaran tidak membawa wadah, aku mengumpulkan hasil panen dalam genggaman tangan kiri. Begitu seterusnya hingga matahari meninggi dan semakin terik.
Jujur, pikiranku belum bisa melupakan getaran aneh tadi. Rasa penasaranku masih mengepul. Sayangnya, kali ini aku tidak cukup berani untuk mencari tahu. Aku lebih memilih menuntaskan pekerjaan yang diberikan ayah. Sudah cukup masalah hari ini yang membuat ayah pusing. Aku tidak ingin membuatnya bertambah kesal dengan menelusuri hal yang tidak berguna.
Ya, ketika itu aku menganggap getaran ganjil yang kurasakan sebagai hal bodoh. Aku sama sekali tidak tahu bahwa beberapa jam lagi, perkara tersebut akan menentukan hidup dan matiku. Tidak. Bukan hanya nyawaku, melainkan nyawa seluruh rakyat Indonesia.
Sungguh, aku tidak bercanda.


 Dama_Elfaren
Dama_Elfaren