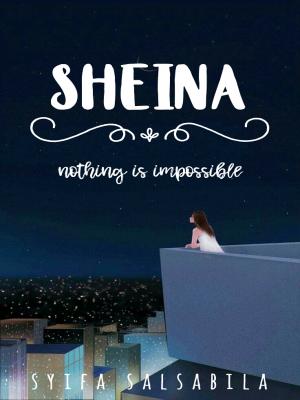Malam sudah berlalu. Pagi menamparku untuk cepat-cepat bangun dari tempat tidurku. Aku yang sudah rapih ini siap berkunjung ke Toko Dedi, selain aku ingin meminjam pakaian untuk melamar pekerjaan sekalian untuk bersilahturahmi. Sedangkan Rudi dan teman-temannya masih tertidur pulas. Aku yang hendak pamit pun ragu karena takut ganggu tidurnya. Aku berangkat.
Udara pagi di Yogyakarta masih alami sekali. Dinginnya masih berteman dengan tubuh, warga-warga di sini pun sudah terlihat berlalu-lalang mencari rezeki. Ada tukang becak yang sedang berhenti di pangkalan, delman yang sedang asyik menunggu penumpang, polisi yang sudah sibuk mengatur lalu lintas bahkan wisatawan yang sedang memotret suasana Yogyakarta di pagi hari. Aku bahagia kembali di sini.
Setengah jam berjalan, rupanya toko Dedi belum berani membukakan dirinya sendiri. Aku pun memutuskan untuk menuju ke stasiun Tugu untuk melihat kepergian ataupun kepulangan seseorang di sana. Sebab, aku menyadari bahwa kepergian seseorang adalah sebuah kenyakinan untuk melupakan masa lalu ke masa depan dan kepulangan seseorang adalah sebuah kerinduan untuk mengingat kembali masa-masa indah yang pernah ada. Aku memperhatikan orang yang di sekelilingku.
“Selamat pagi kekasih. Tetaplah menjadi Matahari di siang hari untuk menyinari kehidupanku dan tetaplah menjadi Bulan di malam hari untuk memancarkan cahayamu di dalam kegelapanku. Percayalah, aku adalah langit yang selama ini butuh kehadiranmu.”
Pesan itu aku kirimkan untuk mengucapkan pagi ke Desi. Karena pesan yang kemarin belum sempat kubalas, aku tidak ingin Ia khawatir tentang keberadaanku dan aku tidak ingin menahan rindu sendiri karena tidak ada kabar darinya. Karena bagiku, jarak bukan sebuah halangan bagi cinta seseorang, tetapi jarak mengajarkan kita untuk saling memahami dan saling percaya satu sama lain.
Setelah aku mengirimkan pesan untuknya. Ada seorang wanita yang menabrak tubuhku hingga ponselku terlepas dari genggamanku sendiri.
“Yah.. hpku jatuh.”
“Maaf, maaf, aku benaran nggak sengaja,” balasnya dengan mengambil ponselku lalu mengembalikannya. Saat itu aku menatap wajahmu, sepertinya ada rasa yang tiba-tiba muncul begitu saja. Aku melongo.
“Hey.. Hey.. Kamu nggak apa-apa?” tanyanya dengan melambaikan tangan ke wajahku.
“Eh iya, iya, maaf aku terlalu fokus lihat bidadari di pagi hari,” jawabku. Aku tidak tersadar dengan apa yang kuucapkan tadi, sebab wajahnya memalingkan duniaku sendiri. Aku terpaku padanya.
“Oh yaudah, aku lagi buru-buru. Kalau hpnya tiba-tiba rusak, tinggal hubungi aku aja. Nanti aku ganti perawatannya,” ujarnya dengan memberikan kartu nama yang diambilnya dari dompet. Lalu dirinya pergi dengan tergesa-gesa dan berbicara dengan sosok di balik panggilan telephonenya. Aku hanya menatap jejak langkahnya pergi. Saat aku asyik memperhatikannya, aku disadarkan oleh balasan pesan singkat kekasihku sendiri.
“Pagi juga sayang, kamu jangan lupa makannya. Aku mau kasih tahu.”
“Apa yang?”
“Aku di PHK,” pungkasnya di dalam pesan. Saat itu pula, aku ikut turut berduka cita lalu menghubunginya untuk mendengar suara yang lucu darinya.
“Kamu benaran di PHK?”
“Iyah, aku di PHK.”
“Sabar ya sayang. Sekarang aku mau coba lamar pekerjaan. Tetapi kamu nggak malu kan kalau misalnya punya cowok jadi tukang sedot wc?”
“Kenapa harus malu? Tetapi malu lah kalau kamu nggak bisa menepati janjimu sendiri. Aku percaya, apa yang kamu lakukan hanya untukku dan aku akan selalu ada untukmu. Doakan aku, dengan sisa uang yang kuterima dari PHK ini dapat kukembangkan jadi usaha.”
“Pasti aku akan doakan dirimu yang baik dan terbaik untukmu, kuyakin Tuhan akan selalu ada untuk kita,” ucapku dengan penuh kenyakinan. Kita saling menukar pikiran lewat ponsel. Waktu begitu cepat berjalan, kaki ini juga tidak lelah untuk tetap berdiri di ruang tunggu stasiun. Pukul 10.09 WIB menghentikan pembicaraan kita.
Aku pun meninggalkan stasiun dengan memasukan kartu nama sosok yang kutemui tadi ke dalam saku celana. Aku berjalan menuju Malioboro. Selama perjalanan, orang-orang yang kutemui saling bahu-membahu untuk menonjolkan kesibukannya, seperti halnya tukang balon yang sedang sibuk untuk menarik perhatian anak kecil hingga menangis agar orangtuanya membelikan balon untuk anaknya ataupun tukang becak yang saling berebut penumpang dengan tawaran menarik. Aku tahu bahwa yang mereka lakukan hanya untuk orang-orang yang disayang, entah berada di rumah, rumah sakit ataupun tempat-tempat singgah yang lainnya.
Pada akhirnya aku berhenti di toko Dedi yang memiliki daya tarik sendiri. Toko yang dihiasi oleh lampu kerlap-kerlip, penjaga toko yang berpenampilan menarik, pakaian yang dipajang pun masa kini bahkan promo-promo yang diberikan pun sungguh menggiurkan sekali. Aku tidak heran, kalau toko Dedi ini banyak dikunjungi oleh pembeli. Aku menghampiri salah satu karyawannya.
“Pak Dedi ada di ruangan nggak?”
“Lagi di luar, kayanya lagi beli makanan.”
“Kira-kira beli makanan di mana?”
“Itu di seberang. Kelihatan kok dari sini,” tuntasnya dengan menunjukkan keberadaan Dedi. Mataku mengikuti arah petunjuknya. Aku memperhatikannya, namun tidak melihatnya. Hingga aku teliti kembali, cowok kekar dengan rambut sedikit gondrong pun sedang membeli bubur itu adalah Dedi. Aku tidak menyangka, soalnya saat kecil dirinya paling kecil bahkan pendiam dari teman-teman lainnya. Aku menunggunya lalu karyawannya pun meninggalkanku karena harus kembali melayani pembeli. Aku yang sibuk memainkan ponsel saat menunggu, tak menyadari bahwa Dedi telah masuk ke dalam toko.
“Dedi.. Tunggu,” teriakku.
Dedi berhenti, “Hemm siapa yah?”
“Ini aku Randy, temen kecilmu dulu.”
“Randy siapa?”
“Teman satu panti.”
Randy pun mengingat-ingat kembali ucapanku. Namun, ia mengajakku untuk masuk ke dalam ruangannya.
“Ya ampun Randy, apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu? Kapan balik ke sini ya? Sudah sukseskah kamu merantau ke Tangerang? Bagaimana dengan Lilis yang dulu ngejar-ngejar kamu? Ihh, kamu tidak pernah berubah ya? Mukanya masih manis aja, pantes aja banyak yang suka sama kamu,”
“Deddd.. deddd.. nanyanya bisa satu-satu nggak?”
“Ya ampun Randy, aku kangen kamu. Udah makan belum? Pasti belum yah? Ini aku baru saja beli makanan. Makan yah!” lanjutnya sambil membukakan makanan yang dibelinya.
“Ini loh usaha aku sekarang. Kamu sekarang kerja di mana?” pungkasnya. Aku yang tidak sempat menjawab semua pertanyaannya malah ditinggal olehnya, ia menuju pintu keluar. Dedi tidak pernah berubah, dirinya masih sosok yang terheboh. Sekarang aku paham, dia mengajakku untuk ke dalam ruangan agar wibawanya tidak jatuh di hadapan pegawainya.
Saat Dedi keluar, aku melihat ruangannya yang begitu tertata rapih. Ada mobil-mobilan yang berjajar, foto-foto masa kecil kita yang semakin pudar, tumpukan dompet yang membentuk mobil sport dan ruangan yang difasilitasi pengontrol cctv, pendingin ruangan sampai laptop, ini adalah ruangan yang selama ini kuinginkan. Namun saat aku asyik melihat keseluruhan ruangan, perut ini mulai kesakitan. Aku berusaha untuk menahannya tetapi tidak mampu hingga akhirnya aku memakan bubur yang tergeletak di mejanya.
Buburnya telah habis, namun Dedi belum kunjung datang. Aku duduk di kursinya hingga tertidur, sebab kursinya bisa maju ke depan dan ke belakang. Nyaman. Di kursi ini, aku bermimpi sangatlah indah, bahkan baru pertama kali aku bermimpi seindah ini. Aku bermimpi bertemu dengan wanita yang sangat cantik bahkan melebihi semua wanita cantik yang kutemui. Selain itu, semua kebutuhanku terpenuhi tanpa harus mengalami penderitaan sama sekali, banyak pelayan yang melayaniku, orang-orang tunduk kepadaku. Aku seperti seorang raja.
Setelah aku asyik menikmati mimpi, Dedi merebut mimpiku karena membangunkanku dengan menepuk pundakku sangat kencang. Sakit.
“Sakit Ded,” ucapku dengan memegang tangan kiriku yang sedang menahan rasa sakit.
“Emang sakit Ran?” tanya Dedi dengan menepuk pundakku sekali lagi. Aku pun bangun dari singgasananya, “Ded, kamu punya kemeja putih sama celana hitam nggak? Pinjam dong, aku mau ngelamar kerja,” Dedi hanya terdiam, melihat bubur yang dia beli itu habis tak tersisa.
“Kamu makan bubur ini Ran?”
“Iyah Ded, habis lapar. Hehe,” jawabku dengan menyengir seperti kuda yang sedang bahagia.
“Oh yauda Ran. Lagipula buburnya mau aku kasih bebek di rumah.”
“Pantesan aja rasanya hambar. Nggak ditambahin apa-apa lagi. Terus gimana, kamu punya kemeja putih sama celana hitam nggak?”
“Ada kok. Ambil aja di toko”
“Tapi aku cuma pinjam aja kok. Masa ngambil yang baru.”
“Santai aja Ran,” pungkas Dedi dengan mendorongku untuk keluar lalu memilih pakaian yang cocok untukku, “Kamu pilih aja Ran,” lanjut Dedi dengan tersenyum melihatku memilih pakaian untuk ngelamar kerja.
Aku sudah menemukan pakaian yang sesuai dengan tubuhku. Lalu pakaian tersebut dibungkus plastik oleh pegawainya. Aku telah memegangnya.
“Ini beneran buat aku Ded?” tanyaku serius.
“Iyah beneran. Kamu tinggal di mana sekarang?”
“Wah makasih Ded. Aku sekarang tinggal di markas kita dulu.”
“Sama Rudi?”
“Iyah Ded,” tutupku dengan menepuk pundaknya sebagai ucapan rasa terima kasihku. Aku pun pergi dari toko Dedi, sedangkan dirinya memperhatikan jejak langkahku pergi yang semakin menjauh. Aku bahagia. Kini aku sadar bahwa kebahagiaan itu dapat kita ciptakan sendiri, bukan untuk dicari-cari. Aku belajar banyak hal dari Dedi.
Langit sore telah menyelimuti hari ini. Warga sekitar masih asyik dengan pekerjaannya, semuanya tampak bahagia dari kasat mata, tetapi aku tidak pernah tahu apa yang mereka rasakan sebenarnya. Mungkinkah senyuman yang lebar dari mereka adalah umpatan untuk tetap bahagia? Aku tidak pernah tahu.
Langkah ini menuntunku ke markas Albest. Sebelum tiba, aku sudah menyiapkan diri untuk beristirahat agar esok hari tidak telat untuk melamar pekerjaan.


 otakusut
otakusut