‘Oh, dua minggu lagi.’
‘Yuk ke Jakarta! Sekalian jalan-jalan.’
‘Woy! Tapi kan kita ada kelas.’
‘Yelah La, kan bisa Jumat sore berangkatnya. Acaranya kan hari Sabtu. Yuk! Sekalian kamu pulang kampung, Beb.’
‘Iya. Kita bisa main ke Ancol.’
‘Acaranya Sabtu siang jam 1, Minggunya kita bisa main ke Ancol. Senin pulang, Ta.’
Aku masih menimbang-nimbang ajakan mereka yang sejak tadi memenuhi grup chat kami. Sebentar lagi film yang dibintangi Rangga akan tayang, kami diundang Rangga untuk ikut acaranya di Jakarta. Sebenarnya aku cukup malas untuk pergi ke Jakarta lalu kembali ke Bandung sementara kami sudah masuk kuliah, takutnya capek. Akan tetapi mereka seperti sales yang semangat mempromosikan barang jualannya.
‘Ya udah deh. Aku ikut, tapi Senin kita harus pulang pagi ya. Ada kuliah jam 2, aku gak mau bolos.’
Iya. Jangan sampai bolos kuliah, apalagi masih di semester awal seperti sekarang. Lalu kemudian ballon bertuliskan oke dan gambar jempol yang terangkat muncul di bawah ballon chat-ku.
****
Libur kuliah tinggal sehari lagi, dan aku menggunakan waktu itu untuk merapikan kosanku yang sudah seperti kapal pecah. Tumpukan kertas-kertas tugas sudah mulai menghalangi estetika ruangan ini. Memang sudah saatnya untuk beres-beres ruangan.
Buku-buku yang sempat kupinjam dari Kang Ikal pun tersebar di mana-mana. Salah satu buku itu aku buka, di halaman pertama tertulis nama Haikal Anugrah, nomor pokok mahasiswanya, dan juga tanda tangan. Andai saja aku seorang ahli Grafologi, mungkin sifat Kang Ikal bisa kuprediksi melalui tulisan tangan dan tanda tangannya, mungkin aku akan menyebut ia laki-laki brengsek, kurang ajar, dan semua kosa kata terburuk di dunia ini sebagai definisi untuk menggambarkan dirinya. Terkadang manusia selalu melekatkan topeng dan enggan melepaskannya.
Aku menyimpan buku-buku Kang Ikal ke dalam sebuah kantong untuk nanti aku kembalikan padanya. Aku tak butuh, lebih tepatnya aku tak ingin ada unsur Kang Ikal dalam kamarku, bahkan dalam hidupku. Sudah cukuplah aku patah hati oleh Rangga dan Kang Ikal, jangan terlalu banyak, nanti hatiku tak bisa kembali utuh.
Lalu, aku menyimpan kantong berisi buku-buku Kang Ikal di sudut ruang dapur, tempat di mana kardus dan hal-hal kurang terpakai kusimpan. Indra pendengaranku menangkap sebuah suara di balik tumpukan kardus tersebut. Kondisinya memang berdebu, dan hal itu membuatku curiga akan sesuatu di balik kardus-kardus itu.
Kemudian….
“KODOK!!!”
Aku menjerit dan refleks menaiki meja yang ada di dapur. Seekor kodok sebesar kepalan tanganku meloncat kegirangan seolah-olah senang dengan reaksiku. Sialan!
Aku merogoh saku celanaku, berniat menghubungi siapa saja yang bisa mengusir binatang sialan itu dari kamarku. Dan satu-satunya yang ada di benakku adalah Rangga!
Aku menunggu Rangga mengangkat panggilanku dengan perasaan cemas dan takut. Sementara mataku masih terfokus pada kodok yang kini diam tak bergerak seperti menunggu reaksiku selanjutnya.
‘Ta.’
“Ga! Kamu dimana?!” tanyaku tidak sabar.
‘Aku masih di tol Pasteur, ada apa?’ tanyanya.
“Cepet ke kosanku!”
‘Ada apa?’
“Kodok, Ga. Cepet ke sini!” kataku merengek.
‘Ya udah sebentar ya, aku tutup teleponnya, sebentar lagi aku ke sana. Kamu diem aja di atas meja, jangan gerak kemana-mana.’
Setelahnya aku menutup panggilan dari Rangga, lalu ada sebersit hal yang baru kusadari, Rangga bisa tahu dimana aku berada kini. Aneh.
Jarak Pasteur dan kosanku ini lumayan jauh, sekitar 30 sampai 40 menit jika jalanannya lancar, bahkan bisa sampai dua jam jika akhir pekan karena macet.
“Sekarang kan akhir pekan!!!”
Aku mengusap wajahku frustasi, kesal dengan semua hal yang menimpaku hari ini. Memang, Kang Ikal membawa bencana di kehidupanku.
****
“Ta!!!”
Rangga masuk ke dalam kosanku lima belas menit kemudian. Membuatku terkejut karena kehadirannya. Ia berjalan menghampiriku yang masih duduk di atas meja dapur. Wajahnya penuh keringat dan nafas yang tersengal akibat berlari.
“Mana kodoknya?” tanyanya.
Aku menunjuk sudut dapur dekat toilet. Kodok itu masih diam tak bergeming setelah beberapa kali melompat ke sana ke mari seperti menghadangku untuk turun dari atas meja.
Rangga kemudian mengambil sapu dan pengki untuk menyapu kodok itu kemudian membuangnya jauh-jauh dari kosanku. Lega rasanya.
Tak berapa lama kemudian, ia kembali ke dalam kosanku, membuka sepatunya yang tak sempat ia lepas saat menangkap kodok tadi. Menyimpan sapu dan pengki ke tempatnya semula.
“Kodoknya tadi muncul dari mana?” tanya Rangga.
“Tuh,” kataku menunjuk ke arah tumpukan kardus.
Rangga melihat ke sekeliling kosanku. Berantakan. Karena aktivitas bersih-bersihku terganggu oleh kehadiran makhluk tadi.
“Aku bantuin kamu beres-beres. Biar dapur aku yang beresin.”
“Kamu gak mau minum dulu?” tanyaku tidak enak.
“Gak apa-apa, aku belum capek.”
Tapi yang kulihat Rangga seperti kelelahan. Gara-gara aku ya?
Selanjutnya, aktivitas beres-beres kosanku lebih ringan dan cepat berkat bantuan Rangga. Laki-laki penuh misteri yang selalu ada di saat aku butuh.
Aku menghampiri Rangga yang bersandar tak jauh dari kasurku, jaket yang ia pakai sudah ia lepaskan. Kini ia sedang menyalakan TV.
“Kamu bukannya lagi di Jakarta?” tanyaku memberikan segelas air padanya lalu duduk di hadapannya.
“Tadi pagi aku pulang,” jawab Rangga meneguk gelas yang kuberikan hingga isinya kandas.
“Oh. Bukannya di Pasteur macet ya jam segitu, ini kan hari Sabtu,” kataku lagi.
“Nggak kok. Gak semacet itu.”
“Kamu pasti ngebut.”
“Gak juga.”
Aku masih tidak percaya dengan ucapannya, tapi sudahlah, daripada semakin panjang dan tidak jelas.
“Kamu mandi gih, udah sore, kita keluar yuk cari makan,” ajakku.
“Kamu ngajak aku malam mingguan?” tanya Rangga.
Aku memandangnya malas, “Kamu pasti belum makan dari siang kan? Mau makan atau kelaparan di sini? Aku belum sempet masak atau belanja apapun. Udah mandi gih.”
Rangga lalu berdiri. “Kok kosanmu tumben sepi, yang lain kemana?”
“Masih pulang kampung, besok juga udah pulang.”
“Selama seminggu kamu sendirian di sini?” tanyanya heboh.
“Iya, biasa aja kali, Ga.”
“Kalau ada maling gimana, Ta? Harusnya kamu bilang aku dong.”
“Udah sana mandi ah! Cuma gitu doang kamu ributin, jangan protektif Rangga,” kataku mendorongnya.
****
Pada malam hari, tak jauh dari kampus, ada pedagang nasi goreng yang hanya berjualan di malam hari. Setiap ingin makan malam dengan nasi goreng, aku pasti akan membeli dari tempat itu. Rasanya enak, banyak, murah, dan aku sudah saling mengenal dengan pedagangnya.
“Mang!” kataku saat tiba di samping gerobak penjual nasi goreng.
“Kayak biasa Neng Nila?” tanyanya.
“Iya, makan di sini ya. Kamu mau apa?” tanyaku pada Rangga.
Rangga melihat-lihat menu yang menempel pada kaca gerobak.
“Aku mie goreng aja,” katanya.
“Mie gorengnya satu, Mang,” kataku.
“Pedes gak neng?”
“Sesendok aja Mang pedesnya.”
“Siap!”
Lalu aku dan Rangga duduk di kursi plastik yang berjejer di belakang gerobak penjual nasi goreng. Seperti kebiasaanku ketika menunggu nasi goreng itu jadi, aku dan penjual nasi goreng saling berbincang perihal kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kampus.
Penjual nasi goreng ini selalu peka akan hal-hal yang terjadi disekitarnya. Mulai dari motor yang hilang, maling yang hampir membobol sebuah mobil yang terparkir, hingga pertengkaran antar pedagang.
“Tau gak neng, tadi ada yang keserempet motor,” kata penjual nasi goreng itu di sela-sela kegiatannya.
“Oh iya, Mang? Siapa yang keserempet?” tanyaku.
“Katanya mah yang ngekos di sini, perempuan lagi. Karunya.”
Sedikit banyak aku mulai hafal kosa kata Bahasa Sunda berkat penjual nasi goreng ini.
“Itu siapalah yang nyerempet? Kan banyak polisi tidur di sini tuh.”
“Atuh Neng, yang bawa motornya juga anak geng motor gak jelas. Bawa parang sagala, untung sama Emang si anaknya teh dibawa biar gak di pukulin warga.”
Memang belakangan mulai marak kembali berita soal anak geng motor yang hobinya bikin kerusuhan bahkan melakukan tindakan anarki di sekitar kampusku.
“Si perempuannya trus gimana Mang?” tanyaku.
“Gak apa-apa sih Neng, cuma lecet-lecet aja, kakinya berdarah sedikit.”
Penjual nasi goreng itu pun memberikan sepiring nasi goreng dan mie goreng pada kami berdua. Selain enak, banyak, dan murah, aku tak perlu menunggu lama makanan itu jadi. Pernah aku bertanya sudah berapa lama penjual nasi goreng itu berjualan. Katanya hampir 15 tahun. Sudah terjamin profesionalitasnya.
“Neng tumben malam mingguan,” kata penjual nasi goreng itu.
“Iya Mang,” kataku malu-malu.
“Pacarnya ya Neng? Mang kayak pernah liat.”
“Hahaha….”
Aku hanya bisa tertawa renyah, pastilah penjual nasi goreng ini seperti pernah melihat Rangga, mungkin ia melihatnya di TV.
Rangga yang sejak tadi kuabaikan itu sudah menyantap mie gorengnya, dengan menyisihkan beberapa sayuran di dalamnya.
“Rangga, makan sayurnya,” kataku.
“Males.”
“Rangga, ih. Di makan!”
“Sama kayak Pak Maman penjual Ketoprak Pak Haji. Pedagang nasi goreng deket kampus pun akrab sama kamu,” kata Rangga mengalihkan pembicataan.
Ia lalu memandangiku sehingga membuatku kebingungan. Memangnya kenapa sih dia bertanya seperti itu?
“Kamu bener, harusnya aku gak perlu cemas waktu kamu tinggal sendirian di kosan.”
Untuk kesekian kalinya, tatapan dan kehadiran Rangga membuat hatiku berdebar. Dinding-dinding tebal di hatiku mulai runtuh dan menampakkan setiap sisi-sisi di dalam hatiku yang masih dalam perbaikan untuk mencintainya dan mempercayainya kembali.
Apa aku terlalu jauh berharap ya?


 cintikus
cintikus

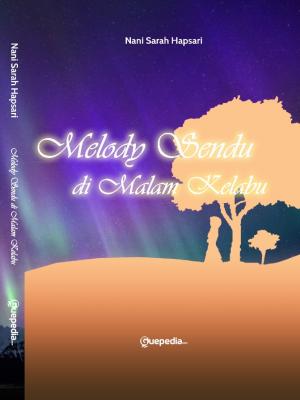








Mantan oh mantan... Kenapa kau jadi lebih menawan setelah jadi mantan?
Comment on chapter Bertemu Dengan Masa Lalu