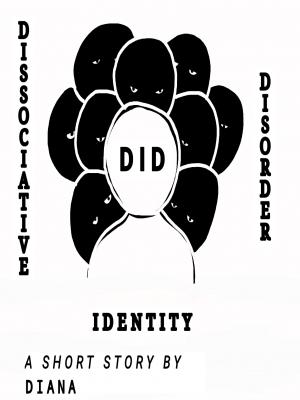“Beberapa luka tak terlihat, tapi menetap di tubuh kita seperti bayangan yang enggan pergi.” ~~Yuana
Sudah bertahun-tahun sejak hari itu.
Tapi pagi-pagi tertentu masih terasa seperti perpisahan yang belum selesai.
Yuana menyeduh kopinya seperti biasa—hitam, pahit, tanpa gula. Tapi bukan karena ia menyukai rasa itu, melainkan karena ia percaya: hidup kadang perlu diterima tanpa manis-manisannya.
Ia tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil, di kota yang tak pernah benar-benar ia pilih. Dinding putih, tirai abu-abu, dan rak buku yang lebih sering menyimpan kenangan ketimbang cerita baru. Tidak ada foto di ruang tamunya. Tidak ada suara selain detak jam dan kadang, suara hujan yang menggantikan segalanya.
Yuana menjalani hidupnya seperti seseorang yang hafal setiap luka—bukan karena ingin, tapi karena tak ada yang benar-benar sembuh. Ia bekerja, berbicara secukupnya, tertawa seperlunya. Tapi malam selalu datang sebagai pengingat: bahwa ada bagian dari dirinya yang tertinggal di waktu yang tak bisa ia datangi lagi.
Dan nama itu…
Masih hidup di antara halaman-halaman buku yang tak pernah ia pinjamkan pada siapa pun.
Masih terucap diam-diam ketika ia menatap hujan, ketika angin meniupkan bau tanah basah yang terlalu mirip dengan sore terakhir itu.
Namanya...
Masih ada.
Tidak disebut, tidak dicari, tapi juga tidak pernah benar-benar hilang.
Seperti bayangan yang tidak bisa dihapus cahaya, hanya bisa diajak hidup berdampingan.
Yuana tidak pernah menikah.
Bukan karena tidak ada yang datang, tapi karena tidak ada yang benar-benar membuatnya ingin bertahan.
Ia bukan menutup diri. Ia hanya pernah membuka pintu terlalu lebar, lalu kehilangan segalanya saat ia menutupnya kembali.
Dan sejak itu, ia belajar hidup dengan perasaan yang tidak diberi izin untuk tumbuh.
Ia tidak memberinya ruang. Tapi anehnya, rasa itu tetap bertahan.
Hidup dalam diam.
Bernapas dalam diam.


 rionhana
rionhana