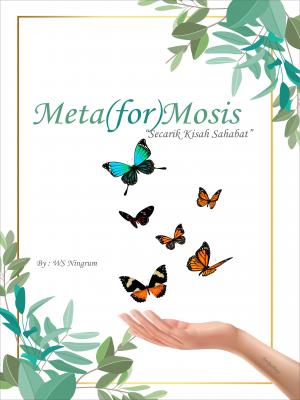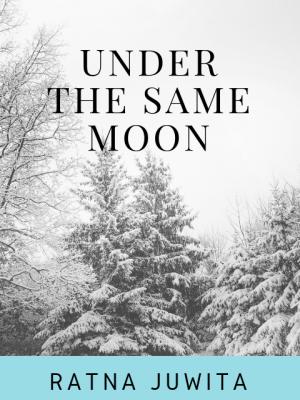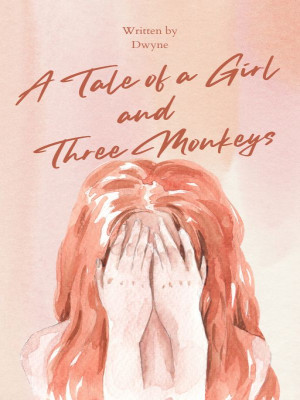Di atas lemari kecil dekat kamar Ibu, ada sebuah kotak kayu yang sudah mulai berdebu. Warnanya cokelat tua, dengan ukiran sederhana di sisi-sisinya. Kotak itu tidak terkunci, tapi seolah-olah tidak ada yang pernah benar-benar membuka kembali isinya.
Hari itu, entah kenapa, tangan ini otomatis membuka kotak itu.
Di dalamnya, ada beberapa mainan kayu yang sudah lama tidak kusentuh: sebuah mobil-mobilan kecil dengan roda yang sudah copot satu, balok huruf-huruf yang dulu jadi alat belajar membaca, dan seekor kuda-kudaan mini dengan ekor yang terbuat dari tali rafia. Semuanya berbau kayu tua yang lembap dan wangi masa lalu.
Tapi benda yang membuatku berhenti adalah satu boneka kayu mungil—berbentuk seperti manusia, dengan cat wajah yang sudah pudar dan satu tangan yang hilang.
Aku ingat betul siapa yang membuatnya.
Ayah.
Dulu, saat kami masih kecil, Ayah tidak bisa membelikan kami mainan seperti anak-anak tetangga. Tapi beliau bisa membuat sesuatu dari kayu bekas, potongan triplek, atau sisa-sisa papan reklame. Yang penting, kami bisa bermain.
“Ayah bukan orang kaya,” katanya suatu malam sambil mengamplas mainan di teras, “tapi Ayah bisa bikin kamu tertawa.”
Dan memang, tawa itu nyata. Mainan buatan Ayah tidak bersuara, tidak pakai baterai, tidak punya lampu. Tapi kami membuatnya hidup dengan imajinasi. Mobil-mobilan kayu bisa balapan keliling ruang tamu. Boneka kayu bisa berdialog seperti pemeran utama dalam pertunjukan drama.
Kami tidak kekurangan.
Kami hanya belajar bahagia dengan cara yang lebih sederhana.
Boneka kayu yang sekarang kugenggam ini adalah salah satu favoritku. Aku bahkan sempat menamainya: Pak Kecil. Dulu, setiap kali bermain sendirian, aku selalu bawa dia. Bahkan sampai pernah aku mandikan karena kukira dia bau. Setelahnya, catnya luntur. Dan Ayah hanya tertawa kecil sambil memperbaikinya lagi.
Tapi kemudian, aku mulai tumbuh besar. Dan perlahan, mainan-mainan itu hanya jadi penghuni kotak kayu yang diam. Tertutup waktu, tertutup kesibukan, tertutup ego remaja yang merasa terlalu tua untuk bermain.
Dan saat Ayah meninggal—beberapa tahun lalu—aku bahkan tidak pernah ingat lagi pada Pak Kecil.
Sampai hari ini.
Kehilangan memang tidak pernah datang dengan cara yang sopan.
Kadang ia menyerbu tanpa mengetuk pintu, membuat kita terpaksa menerima ruang kosong di dalam dada yang sebelumnya penuh suara orang yang kita cintai.
Aku mengelus permukaan boneka kayu itu pelan. Gurat-gurat kecil di tubuhnya terasa seperti jalur waktu yang tak bisa dihapus. Tangannya yang hilang mengingatkanku pada semua hal yang sempat hilang, yang tak bisa dikembalikan.
Dan dari situ, aku mulai belajar ulang tentang arti kehilangan.
Bukan kehilangan karena lupa, tapi kehilangan karena kita terlalu lama tidak melihat. Padahal benda itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk disentuh kembali.
“Masih ada boneka itu?” tanya Dira dari ambang pintu.
Aku mengangguk. “Kamu ingat namanya?”
“Pak Kecil,” jawabnya cepat sambil tersenyum. “Kamu dulu bahkan minta diajak tidur bareng.”
Aku tertawa kecil. “Kayaknya aku dulu lebih sayang sama dia daripada ke kamu.”
Dira cemberut pura-pura marah. Tapi kami sama-sama tahu, masa itu terlalu indah untuk diributkan. Kami duduk berdampingan, membuka isi kotak satu per satu. Setiap benda punya cerita. Setiap cerita membawa rasa.
“Ayah sayang banget ya sama kita,” gumamku pelan.
“Banget,” jawab Dira. “Dan kayaknya, Ayah juga tahu… cinta itu bisa disimpan di potongan kayu kecil, asal tangannya tulus waktu bikin.”
Aku mengangguk. Karena aku percaya, tidak semua cinta harus besar dan megah. Kadang, cinta cukup diwujudkan dalam bentuk mobil kayu yang bisa jalan miring, atau kuda mainan yang dibuat malam-malam sambil menahan ngantuk.
Kami menemukan satu balok huruf yang bagian sisinya sudah gosong.
“Ini bekas kamu bakar, kan?” tanya Dira geli.
Aku mengangguk malu. “Eksperimen waktu SD. Mau tahu apa kayu bisa meleleh.”
Kami tertawa sampai perut sakit. Tapi kemudian diam sejenak. Karena di balik tawa, ada satu rasa yang menyusup pelan: rindu.
Kami merindukan seseorang yang tidak bisa lagi duduk di tengah-tengah kami. Seseorang yang dulu selalu ada di setiap tawa dan tangis, tapi kini hanya tinggal di ingatan.
Dan mainan kayu ini—tanpa kami duga—menjadi penghubung diam-diam antara masa kini dan masa lalu. Antara kehilangan dan penerimaan.
Aku memeluk Pak Kecil sebentar. Mungkin konyol. Tapi aku merasa, Ayah sedang menatap dari jauh. Bukan dengan wajah sedih, tapi dengan senyum tenang.
Karena akhirnya, kami kembali membuka kotak kenangan itu. Kami tidak membiarkan waktu menguburnya sepenuhnya.
“Kalau kita punya anak nanti,” ucap Dira tiba-tiba, “kita ajarin mereka main kayak gini ya.”
Aku menoleh. “Maksudmu, kasih mainan kayu?”
“Bukan. Kasih mainan yang dibuat dari cinta. Supaya mereka tahu, bahwa bahagia nggak harus dibeli mahal. Kadang, cukup dari tangan yang sabar dan hati yang tulus.”
Aku terdiam. Lalu mengangguk pelan.
Karena kehilangan memang menyakitkan.
Tapi dari kehilangan, kita belajar menghargai yang pernah ada.
Dan dari kenangan, kita belajar mencintai sekali lagi—dengan cara yang lebih utuh.
Sebelum menutup kotak itu, aku menuliskan satu catatan kecil dan menaruhnya di dalam:
“Terima kasih, Ayah. Untuk semua mainan yang tak bersuara,
tapi penuh tawa. Untuk semua kayu yang jadi jembatan ke masa kecil kami.
Kau mungkin sudah pergi, tapi cintamu masih bermain di sini—bersama kami.”
Lalu kami menutup kotak itu perlahan. Bukan untuk melupakannya, tapi untuk menyimpannya dengan lebih layak.
Karena beberapa hal memang tidak perlu dibuka terus-menerus.
Cukup tahu bahwa mereka masih ada.
Dan bahwa mereka pernah menjadi bagian terindah dari hidup kita.
Refleksi: Kehilangan bukan akhir dari kenangan. Justru dari kehilangan, kita belajar menemukan bahwa cinta bisa hidup dalam benda-benda kecil, dalam mainan kayu tanpa suara, dalam tangan yang tak sempurna, tapi sepenuh hati. Dan saat kita menyentuh kembali benda-benda itu, kita tidak hanya menemukan masa lalu, tapi juga menemukan diri kita sendiri yang pernah benar-benar dicintai.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_