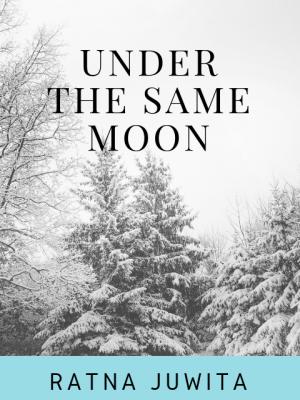Setiap rumah punya suara-suara rahasia. Ada yang berupa derit tangga tua, ketukan pelan di kaca jendela, atau suara gorden yang tersapu angin sore. Tapi suara yang paling keras dan membekas di rumah lama kami... adalah suara pintu kamar yang pernah aku banting keras-keras sepuluh tahun lalu. Pintu itu masih berdiri kokoh sampai hari ini, meski warnanya sudah pudar dan sudutnya mulai mengelupas. Engselnya berdecit setiap kali dibuka, seperti menertawakan seseorang yang dulu terlalu keras menutupnya. Aku berdiri di depan pintu itu pagi ini, menatapnya lama. Dan entah kenapa, hatiku ikut terdiam. Seolah aku sedang berdiri di hadapan versi remajaku yang dulu keras kepala, sok tahu, dan sangat mudah marah.
Kala itu, aku masih SMA. Umur 17. Umur di mana segalanya terasa salah. Dunia terasa sempit, orang tua terasa menjengkelkan, dan semua larangan terdengar seperti bentuk pengekangan, padahal hanya bentuk sayang yang salah diterjemahkan oleh ego remaja.
Hari itu, aku pulang dengan wajah kesal. Nilai ujian anjlok, sepatu kotor, dan dompet ketinggalan di kantin. Lalu di rumah, Ibu menegurku karena lupa menjemur handuk basah.
Hanya itu. Tapi aku merasa seluruh dunia menyalahkanku.
“Aku capek, Bu! Kenapa semua harus aku?” bentakku.
Ibu terdiam, berdiri sambil membawa cucian. Tak marah, tak membentak balik. Tapi justru diamnya itu yang membuat aku semakin merasa bersalah. Lalu dengan tenaga penuh, aku masuk kamar dan BRAKK!—pintu itu kututup keras-keras.
Tidak hanya tertutup. Aku membantingnya. Dengan semua amarah yang bahkan aku sendiri tidak tahu dari mana asalnya.
Di balik pintu, aku menangis diam-diam. Tapi tetap tidak keluar untuk minta maaf. Harga diri seorang remaja terlalu tinggi untuk sekadar meminta maaf duluan.
Pagi ini, aku menyentuh gagang pintu itu. Hangat. Seolah masih menyimpan amarah masa lalu yang belum sempat selesai. Kupeluk permukaannya dengan telapak tanganku yang kini lebih dewasa. Dan di dalam hati, aku berkata:
“Maaf ya… pintu. Tapi lebih dari itu, maaf juga untuk Ibu yang mendengarnya.”
Waktu sarapan, aku iseng membahas kejadian itu.
“Bu, Ibu ingat nggak waktu aku banting pintu kamar sepuluh tahun lalu?”
Ibu tertawa kecil sambil membalik tempe di wajan. “Yang mana? Kamu sering, lho.”
Aku tertawa malu. “Tapi yang paling keras.”
“Oh, yang waktu kamu lupa menjemur handuk, terus marah karena aku tegur? Aku ingat.”
“Waktu itu Ibu nggak marah?”
Ibu mengangguk pelan. “Marah. Tapi juga sedih. Karena kamu nggak tahu, pagi itu aku bangun jam empat, nyuci semua seragam kamu biar kering sebelum sekolah.”
Aku terdiam.
Kadang kita terlalu sibuk dengan emosi sendiri, sampai lupa melihat betapa banyak cinta yang tersembunyi di balik teguran.
“Aku minta maaf ya, Bu,” kataku.
Ibu hanya tersenyum. “Sudah lama aku maafkan. Pintu itu juga sudah dimaafkan kok. Cuma, tiap kali dia berderit, aku ingat kamu dulu pernah ngamuk.”
Kami tertawa bersama. Dan pagi itu terasa ringan.
Sore harinya, aku masuk ke kamar itu lagi. Duduk di ranjang lama, memandang ke sekeliling. Di balik pintu, masih ada bekas goresan kecil akibat bantingan dulu. Lucu ya, luka kecil itu lebih abadi daripada marahnya sendiri. Aku jadi ingat Dira, yang juga pernah membanting pintu itu. Bedanya, dia banting pintu sambil menangis karena Ayah tidak mengizinkannya pergi ke acara perpisahan malam.
“Cuma karena ada cowoknya,” kata Ayah waktu itu. Padahal menurut Dira, justru cowoknya batal datang karena takut sama Ayah.
Dulu kami menganggap pintu itu sebagai pelampiasan. Tapi kini aku melihatnya sebagai saksi. Saksi bisu pertengkaran yang tak pernah tuntas. Tapi juga saksi diam dari pertumbuhan kami dari remaja penuh ledakan, menjadi anak-anak yang akhirnya belajar minta maaf.
Aku membuka pintu perlahan. Deritannya masih sama. Bunyi khas yang entah mengapa sekarang terdengar seperti sapaan hangat.
“Selamat datang kembali,” seakan ia berkata.
Aku tidak membantingnya. Kali ini, kututup dengan hati-hati. Dengan tangan yang lebih dewasa. Dengan emosi yang lebih tenang. Karena kini aku tahu: pintu tidak hanya dibuat untuk dibuka dan ditutup. Tapi juga untuk menjadi batas antara emosi dan keheningan, antara konflik dan ketenangan.
Malam harinya, aku dan Dira berbincang di kamar.
“Eh, kamu inget nggak, kita berdua pernah adu banting pintu?” tanyaku.
Dira tertawa, “Iya. Tapi aku paling keras deh. Sampai Ayah bilang, ‘Kalau pintu rusak, kamu yang ganti’.”
“Terus kamu bilang, ‘Oke, aku tabung dari uang jajan.’ Tapi akhirnya minta tambahan juga, kan?”
Kami tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada rasa haru. Karena kini, kami tahu... semua drama remaja itu bukanlah akhir dari dunia. Tapi bagian dari proses menjadi manusia. Besoknya, sebelum kembali ke kota, aku berdiri sekali lagi di depan pintu itu. Kali ini, aku letakkan sebuah kertas kecil di sisi dalamnya. Tertempel dengan selotip bening. Isinya:
Untuk pintu yang pernah dibanting:
Terima kasih sudah bertahan.
Terima kasih sudah tidak patah.
Terima kasih sudah menjadi batas yang akhirnya membuatku tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara.
Salam,
Anak yang kini belajar membuka pintu dengan tenang.
Lalu kututup pintu itu pelan, dan melangkah keluar kamar. Tidak dengan amarah. Tapi dengan hati yang telah belajar memaafkan baik pada orang lain, maupun diri sendiri.
Refleksi: Kita pernah membanting pintu karena merasa tak dimengerti. Tapi seiring waktu, kita sadar: yang paling perlu dimengerti adalah hati kita sendiri. Dan pintu yang dulu jadi pelampiasan kini jadi saksi dari proses tumbuh dan pulih.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_